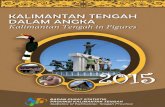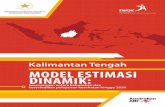Peningkatan PAD Kalimantan Tengah
description
Transcript of Peningkatan PAD Kalimantan Tengah

PENINGKATAN PAD KALIMANTAN TENGAH
MELALUI DAYAK LAND
Disusun oleh :
Ezza Mentariningrum..........NIS. 020844/XI IPS-1
Fauzia Rachmawati..............NIS. 020974/XI IPS-1
Gifari Widi Kurniawan........NIS. 020751/XI IPS-1
M.Yusuf Jaelani....................NIS. 020857/XI IPS-1
Sinta Rega Fitriyana Putri...NIS. 020960/XI IPS-1
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2013/2014

PENINGKATAN PAD KALIMANTAN TENGAH
MELALUI DAYAK LAND
MAKALAH SOSIOLOGI
Disusun Oleh :
Ezza Mentariningrum..............NIS.020844
Fauzia Rachmawati..................NIS.020974
Gifari Widi Kurniawan............NIS.020751
M.Yusuf Jaelani........................NIS.020857
Sinta Rega Fitriyana Putri.......NIS.020960
Telah dipertanggungjawabkan dan disetujui
pada tanggal 8 Mei 2014
Surakarta, 8 Mei 2014
Pembimbing,
Dra. M. Th. Sri Martanti
NIP.195810251981032005

KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pertolonganNya makalah sosiologi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
Dengan mengangkat judul “Peningkatan PAD Melalui Dayak Land”, dijabarkan mengenai pentingnya pelestarian budaya Indonesia sebagaimana bagian dari jati diri dan identitas bangsa. Pelestarian budaya dapat dilakukan secara kreatif dan produktif yakn dengan memanfaatkan potensi wisata alam yang ada dengan mendirikan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, yakni Perusahaan Resort Dayak Land. Dengan adanya perusahaan jasa perhotelan dayak Land, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kekayaan budaya Dayak yang saat ini semakin tergeser oleh kebudayaan asing sudah selayaknya dilestarikan sebagaimana kewajiban setiap insan nusantara dengan memperhatikan nilai luhur budaya, religi dan pancasila. Dalam pembuatan makalah ini, terdapat bantuan, arahan, inspirasi dan partisipasi dari beberapa pihak, oleh karenanya, diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Sri Martanti, Guru Sosiologi
3. Teman-teman kelas XI IPS-1
4. Segenap pihak yang terlibat dan telah berpartisipasi.
Dengan bantuan segenap pihak tersebut makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Disadari bahwasanya terdapat beberapa kekurangan di dalam makalah meskipun penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam pembuatan makalah. Dengan penuh harap, seoga makalah ini dapat berguna bagi umum dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia sebagaimana kebudayaan merupakan identitas insan nusantara.
Surakarta, 8 Mei 2014
i

IBU PERTIWI
Ibu Pertiwi...
Jika angin tak lagi berhembus
Jika api tak lagi membara
Jika air tak lagi mengalir
Jika tanah tak lagi membongkah
Apa kita masih tak dapat berkata?
Tentang hasrat dan milik
Tentang jiwa dan rasa
Tentang dunia yang dipijak nestapa
Tentang duka menyelimuti langkah
Ibu Pertiwi…
Masih adakah celah?
Untuk menyimpan gelisah
Untuk menyembunyikan langkah
Tidak, Bu!
Meskipun celah berongngga
Dada kita tetap ternganga
Meskipun jari tersembunyi
Mata dan telinga tetap ada
Ingatlah…
Wahai Ibu Pertiwi
Kami…
Putra putri bangsa akan melangkah
Dalam langkah satu dan satu
Bukan melompat setelah itu kami terjerat!
ii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………….i
PUISI………………………………………………...……………………………ii
DAFTAR ISI……………………………………………….……………………iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR……………………………………………v
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………….……....v
BAB I. PENDAHULUAN…...…………………………………………………...1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………….1
B. Tujuan Penulisan………………………………………………………2
C. Metode Penulisan……………………………………………………...3
D. Rumusan Masalah……………………………………………………..4
E. Sistematika Penulisan………………………………………………….4
BAB II. KALIMANTAN ……………...…………….…………………….……7
A. Topografi……………………………………………………………....7
B. Iklim…………………………...………………………………………8
C. Kondisi Tanah………………………………………………………..11
D. Flora………………………………………………………………….15
E. Fauna…………………………………………………………………17
F. Ekonomi……………………………………………………………...18
G. Demografi……………………………………………………………18
BAB III. DAYAK …………...………………...……………………….……….20
A. Sejarah………………………………………………………….…….20
B. Sub-Suku Bangsa Dayak……………………………………….…….22
iii

C. Sistem Kekerabatan……………………………………………….….22
D. Sistem Religi………………………………………………………....23
E. Upacara Adat………………………………………………………...24
F. Sistem Pengetahuan………………………………………………….28
G. Sistem Peralatan Dan Perlengkapan Hidup………………………….28
H. Sistem Bahasa………………………………………………………..29
I. Sistem Kesenian…………………………………………...................31
J. Sistem Ekonomi……………………………………………………...35
K. Mata Pencarian…………………………………………………...….36
BAB IV. PENINGKATAN PAD……………………………………………..38
A. Potensi Wisata……………………………………………………….38
B. Pembangunan Wisata………………………………………………..38
C. Realisasi Dan Pengelolaan…………………………………………...41
BAB V. PENUTUP………………………………………………...……….….44
A. Keterkaitan Makalah Dengan Materi Ajar Sosiologi…………….….44
B. Saran……………………………………………………….…….…..45
C. Kesimpulan……………………………………………….……….…45
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….………....47
LAMPIRAN………………………………………………………….…………48
iv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar 1.1. Peta Kalimantan Tengah …………………………………...……...48
Gambar 1.2. Pantai Sungai Bakau ...……………………………….…………….48
Gambar 1.3. Jalan di Kalimantan Tengah………………………………….…….48
Gambar 1.4. Kondisi Hutan di Kalimantan ...………………………………...…48
Gambar 2.1. Seragam Pegawai Dayak Land…………………………………….49
Gambar 2.2. Baju Adat untuk Disewaka ……………………………………..…49
Gambar 3.1. Rumah Panjang (Bangunan Hotel)………………………………....49
Tabel 1.1. Rincian Makan………………………………………………………..49
Tabel 1.2. Jadwal Kegiatan (Paket)……………………………………………...50
Tabel 2.1. Pembagian Kerja……………………………………………………...50
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 – Maket Rencana……………………………………………………53
Lampiran 2.1 – Tiket Dayak Land………………………………………………54
Tampak Luar…………………………………….……………...54
Tampak Dalam………………………………………………….55
v

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki
beraneka ragam budaya. Dengan total luas wilayah 1,904,569 km2 yang
terdiri dari 17.508 pulau, Kalimantan adalah pulau terbesar yang ada di
Indonesia dengan populasi penduduk 13,77 juta jiwa yang mayoritas adalah
suku Dayak.
Berkenaan dengan Suku Dayak, Kalimantan Tengah merupakan salah
satu daripada kebudayaan suku Dayak ditinjau dari asal suku dan kebudayaan
Dayak. Dayak merupakan suatu suku yang terdiri dari beberapa sub-suku.
Diantaranya adalah : Ngaju, Kayan, Otdanum, Iban, Banjar, Punan, Maanyan,
Bahau, Kenyah, Murut, Lawangan dan Melayu.
Dengan banyaknya kebudayaan yang ada di Kalimantan, khususnya
pada suku Dayak, diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan dan
pelestarian kebudayaan Dayak secara intensif. Baik melalui sektor edukasi
maupun ekonomi. Terlebih lagi saat ini banyak unsur – unsur asing yang
masuk ke Indonesia, baik berupa suatu bentuk kebudayaan, teknologi yang
berupa alat maupun ideologi atau cara berfikir yang telah beredar luas dan
dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya kaum muda.
Terdapat banyak cara untuk melestarikan kebudayaan Dayak. Salah
satunya melalui sektor ekonomi yang dapat ditopang oleh wisata, industri
maupun perusahaan jasa. Di bidang ekonomi, perekonomian Kalimantan
ditopang oleh perkebunan kelapa sawit, yang mana menjadi komoditi bagi
Kalimantan. Namun, dalam rangka usaha pelestarian budaya dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, diperlukan adanya bentuk variasi usaha yang lain
untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, seperti sektor wisata dan jasa.
Pemerintah Kalimantan sendiri telah melakukan promosi wisata yang ada di
1

Kalimantan untuk menarik minat wisatawan dan dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan disamping untuk
melestarikan kebudayaan Dayak, diperlukan adanya usaha nyata yang harus
dilakukan oleh seluruh pihak, baik masyarakat Kalimantan sendiri maupun
pemerintah. Selain itu, usaha pelestarian dan perlindungan budaya dilakukan
atas dasar kesadaran setiap individu sebagaimana bagian daripada budaya itu
sendiri.
Sebagaimana uraian tersebut, karya tulis dan penelitian ini
dimaksudkan untuk memberikan suatu bentuk pelestarian kebudayaan dengan
tujuan profit maupun non-profit. Dalam konteks Profit, diharapkan PAD
Kalimantan bertambah serta dapat menyerap tenaga kerja yang ada dengan
adanya usaha kreatif di sektor jasa dan wisata. Sedangkan dalam konteks Non-
Profit, dengan adanya usaha Resort yang mengusung tema kebudayaan Dayak,
diharapkan dapat menarik dan menambah minat pengunjung akan kebudayaan
Indonesia, khususnya kebudayaan Dayak melalui serangkaian kegiatan dan
pertunjukan yang diadakan oleh Resort yang memperkenalkan serta mengajak
serta pengunjung untuk belajar mengenai kebudayaan Dayak.
B. Tujuan Penulisan
Dengan mengangkat judul “Peningkatan Potensi Wisata Melalui
Dayak Land”, penulis ingin menjabarkan mengenai Kalimantan, Dayak dan
pemanfaatan potensi alam bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Kalimantan
dengan usaha kreatif, inovatif dan ramah masyarakat dengan cara mendirikan
usaha Resort yang mengusung tema kebudayaan Dayak dengan tempat
penginapan dan fasilitas yang dirancang sesuai dengan kebudayaan Dayak
serta Jasa Tour yang menyediakan perjalanan wisata menuju objek-objek
wisata yang ada di Kalimantan.
2

C. Metode Penulisan
Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis menggunakkan beberapa
metode untuk dapat menyaikan penjelasan serta mendapatkan hasil yang baik
dan relevan dengan realitas yang ada serta penyelesaian yang ada bersifat
nyata, sehingga dapat dipraktikkan dan diimplementasikan secara nyata.
Sehingga tujuan penulisan karya tulis ini dapat dicapai. Metode-metode yang
digunakkan oleh penulis yakni :
1. Kajian Pustaka
Penulis mengkaji teori-teori yang ada pada buku tertentu
sebagai landasan teori pembuatan karya tulis.
2. Browsing
Penulis melakukan pencarian sumber dan teori yang relevan
berkenaan dengan pembahasan yang pada di karya tulis ini melalui
internet,dengan cara mengkaji,mencatat hal penting yang diperoleh
dari sumber (website atau situs) terpercaya,seperti situs resmi dari
pemerintah (go.id),instansi (co.id),organisasi(org.id),universitas(ac.id)
maupun situs pribadi yang memberikan penjelasan lengkap,sistematis
dan dapat dipercaya.
3. Observasi
Penulis melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada
dan terjadi di lingkungan siswa dan guru berkaitan dengan penggunaan
teknologidi dalam kegiatan belajar dan mengajar,sehingga penulis
dapat mengetahui realita atas pembahasan yang dilakukan.
4. Interpretasi
Penulis memberikan pendapat dan pandangan secara teoritis
dan logis terhadap suatu masalah atau teori yang bersangkutan melalui
suatu usaha penerjemahan dan pemahaman secara kritis atas suatu
3

permasalahan dan teori yang terdapat pada fenomena di lingkungan
siswa dan yang terdapat di dalam pembahasan masalah pada karya
tulis ini.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penulisan yang
disebutkan penulis, penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagaimana
akan dijelaskan satu persatu secara terperinci, kritis dan logis pada Bab
selanjutnya. Berikut adalah rumusan masalah yang disajikan oleh penulis :
1. Bagaimanakah potensi alam yang dimiliki oleh Kalimantan ?
2. Bagaimanakah kondisi sosial budaya yang ada di Kalimantan ?
3. Bagaimanakah kondisi perekonomian Kalimantan ?
4. Bagaimanakah pemanfaatan potensi ekonomi Kalimantan ?
E. Sistematika Penulisan
Karya tulis ini dibuat menggunakkan susunan khusus yang
dirancang sesuai kaidah-kaidah yang baik dan benar agar isi daripada karya
tulis ini dapat teratur,sehingga mudah dipahami dan tidak ada kerancuan
dalam penulisan karya tulis ini. Berikut adalah sistematika penulisan karya
tulis yang dibuat oleh penulis :
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar belakang masalah
Keberadaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar
B.Tujuan Penulisan
1.Mengetahui peranan teknologi bagi pelajar
4

2.Mengetahui peranan teknologi dalam kegiatan Belajar Mengajar
3.Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan
Teknologi dalam kegiatan belajar bagi Pelajar
4.Mengetahui manfaat penggunaan teknologi sebagai belajar bagi
Pelajar
C.Metode Penulisan
1.Kajian pustaka
2.Browsing
3.Observasi
4.Interpretasi
D.Rumusan Masalah
E.Sistematika Penulisan
BAB II KALIMANTAN
A.Topografi
B.Iklim
C.Kondisi Tanah
D.Flora
E.Fauna
F.Ekonomi
G.Demografi
BAB III Dayak
A.Sejarah
B.Sub-Suku
C.Sistim Kekerabatan
D.Sistim Religi
E.Upacara Adat
F.Sistim Pengetahuan
5

G.Alat dan Perlengkaan Hidup
H.Sistim Bahasa
I .Kesenian
J. Sistim Ekonomi
K.MataPencarian
BAB IV Peningkatan PAD
A.Potensi Wisata
B.Pembangunan Wisata
C.Realisasi dan Pengelolaan
BAB V Penutup
A. Keterkaitan Makalah Dengan Materi Ajar Sosiologi
B. Saran
C.Kesimpulan
6

BAB II
KALIMANTAN
A. TOPOGRAFI
Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di
sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau
Kalimantan dibagi menjadi wilayah Brunei, Indonesia (dua per tiga) dan
Malaysia (sepertiga). Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan "Pulau Seribu
Sungai" karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Pada zaman
dahulu, Borneo -- yang berasal dari nama kesultanan Brunei -- adalah nama
yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini
secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh
penduduk kawasan timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia.
Wilayah utara pulau ini (Sabah, Brunei, Sarawak) untuk Malaysia dan Brunei
Darussalam. Sementara untuk Indonesia wilayah Kalimantan Utara, adalah
provinsi Kalimantan Utara. Dalam arti luas "Kalimantan" meliputi seluruh
pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit
Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia.
Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara pulau Jawa, sebelah timur
Selat Melaka, sebelah barat pulau Sulawesi dan sebelah selatan Filipina. Luas
pulau Kalimantan adalah 743.330 km². Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut
Cina Selatan di bagian barat dan utara-barat, Laut Sulu di utara-timur, Laut
Sulawesi dan Selat Makassar di timur serta Laut Jawa dan Selat Karimata di
bagian selatan. Gunung Kinabalu (4095 m) yang terletak di Sabah, Malaysia
ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu terdapat pula Gunung Palung,
Gunung Lumut, dan Gunung Liangpran. Sungai-sungai terpanjang di
Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1143 km) di Kalimantan Barat, Indonesia,
Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah, Indonesia, Sungai Mahakam
(980 km) di Kalimantan Timur, Indonesia, Sungai Rajang (562,5 km) di
7

Serawak, Malaysia. Jalan Nasional RI di Kalimantan sepanjang 6.075,97 km
yang secara umum dengan kondisi mantap baru mencapai 77%. Kondisi
Hutan di Pulau Kalimantan tidak dapat diketahui secara pasti seberapa luas
tutupan hutan pada jaman dulu. Namun berdasarkan estimasi potensi vegetasi
(yaitu luas kawasan yang kemungkinan tertutup berbagai tipe hutan dan
dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan lingkungan serta intervensi
manusia) dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia pada
awalnya tertutup hutan (MacKinnon, 1997).
Pada tahun 1950, Dinas Kehutanan Indonesia menerbitkan peta
vegetasi untuk negara ini. Dari peta ini disimpulkan bahwa hampir 84 persen
luas daratan Indonesia pada masa itu tertutup hutan primer dan sekunder serta
tanaman perkebunan seperti teh, kopi dan karet. Alasan utama pembukaan
hutan yang terjadi sampai tahun 1950 adalah untuk kepentingan pertanian,
terutama untuk budidaya padi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa luas
hutan tanaman dan perkebunan tidak lebih dari 4 juta ha pada tahun 1950, dan
sisanya berupa hutan primer dan hutan sekunder dan hutan pantai yang
dipengaruhi pasang surut. Dibawah ini tabel kondisi hutan berdasarkan data
pemerintah pada tahun 1950.
B. IKLIM
Borneo terletak di katulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu
yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 -350 C di dataran
rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan
juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang
garis katulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan
dapat mendukung hutan yang selalu hijau (Holdridge 1967). Semua bagian
Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun.
Pola curah hujan di Indonesia ditentukan oleh dua angin musim –
angin musim tenggara atau “musim kering” (mei – oktober) dan angin musim 8

barat laut atau “musim basah” (Nopember – April). Dari Mei sampai
Oktober matahari melintas Indocina dan Cina bagian selatan, dan suatu sabuk
dengan tekanan rendah berkembang di atas daratan Asia yang panas. Angin
yang membawa hujan bertiup ke arah utara dari daerah yang bertekanan tinggi
di atas Australia dan Samudera India. Angin ini menyerap kelembaban sambil
melintasi lautan yang luas.Ketika mencapai pulau-pulau di Kawasan Sunda
Besar dan daratan Asia, angin naik ke atas karena harus melintasi jajaran bukit
dan gunung. Sambil naik udara menjadi lebih dingin dan kelembabannya
turun menjadi titik hujan. Hujan musim yang sangat lebat jatuh di atas India
dan Cina bagian selatan dan curah hujan yang lebih rendah jatuh di pulau-
pulau Dangkalan Sunda termasuk Borneo.
Dari Oktober sampai maret matahari melintasi bagian selatan garis
katulistiwa. Asia tengah sangat dingin dan daerah yang panas bertekanan
rendah sekarangberada di bagian selatan Benua Australia. Angin musim yang
bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi di atas samudera India. Di tempat
udara panas danudara dingin ini bertemu, hujan yang lebat terjadi di atas
seluruh Dangkalan Sunda dan Sulawesi, Nusa Tenggara dan P. Irian.
Kalimantan terletak di garis Equator dan memiliki iklim tropis dengan
suhu yang relative konstan sepanjang tahun antara 250– 350 C di dataran
rendah. Dataran rendah di sepanjang equator yang mendapat curah hujan
minimum 60 mm setiap bulannya dapat mendukung hutan yang selalu hijau.
Kalimantan terletak di daerah basah sepanjang tahun. Memiliki sedikitnya
bulan basah dengan curah hujan kurang dari 200 mm. Angin musim barat laut
(Nopember-April) pada umumnya lebih basah dari pada angin musim
tenggara, tetapi beberapa daerah pesisir menunjukkan pola curah
hujan bimodal. Kalimantan dapat dibagi menjadi lima
zona agroklimat. Sebagian besar daerah perbukitanyang tinggi menerima
curah hujan 2.000 – 4.000 mm setiap tahun. Sebagian besar
wilayah Kalimantan masuk ke dalam kawasan yang paling basah (Oldeman
dkk. 1980). Tidak seperti Sumatera, di Kalimantan tidak ada gunung-gunung
9

di daerah pesisir yang mempengaruhi curah hujan, walaupun beberapa gunung
yang pendek mempengaruhi curah hujan lokal, terutama di Borneo bagian
timur. Borneo tengah dan barat adalah kawasan yang paling basah, sementara
bagian-bagian di pesisir timur jauh lebih kering. Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang paling basah. Angin musim
Barat laut di Kalimantan Barat pada bulan Agustus-September dan musim
hujan berlangsung sampai bulan Mei. Curah hujan sangat tinggi terutama pada
bulan Nopember dan yang kedua pada bulan April. Pada bulan Juni-Agustus
iklim relatif lebih kering, akan tetapi tidak ada bulan yang curah hujannya
kurang dari 100 mm. Curah hujan tahunan di Putussibau (Kapuas Hulu)
mencapai lebih dari 4000 mm dan tidak ada bulan yang curah hujannya
kurang dari 200 mm. Dengan wilayah panas sepanjang tahun dan daerah
lembab.
Angin musim barat laut mencapai Kalimantan Barat pada bulan
Agustus-September dan musim hujan berlangsung sampai bulan Mei; curah
hujan sangat tinggi terutama pada bulan Nopember dan yang kedua pada bulan
April. Dari bulan Juni sampai Agustus, iklim relatif lebih kering tetapi tidak
ada bulan yang curah hujannya kurang dari 100 mm. Curah hujan di Putusibau
lebih dari 4.000 mm dan tidak ada bulan yang curah hujannya kurang dari 200
mm. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, curah hujan umumnya bertambah
tinggi ke arah utara dari daerah pesisir. Pengaruh angin musim tenggara jauh
lebih besar daripada di Kalimantan Barat. Bulan kering terjadi dari bulan Juli
sampai September terutama di daerah-daerah bayang-bayang hujan di bagian
barat Pegunungan Meratus, misalnya di Martapura. Namun musim kemarau
disini masih tidak sekering di jawa dan Nusa Tenggara. Pesisir di bagian
tenggara dan P. Laut umumnya lebih basah daripada pesisir bagian
selatan.Karena pengaruh Pegunungan Meratus (Oldeman dkk 1980).
Daerah-daerah pesisir di Kalimantan Timur dan bagian timur Sanah
jauh lebih kering daripada bagian-bagian lainnya diBorneo. Pengaruh angin
musim barat laut jauh lebih lemah karena hampir semua hujan jatuh di
10

pegunungan tengah. Bahkan selama musim penghujan, curah hujan relatif
rendah dan seringkurang dari 200 mm/bulan, terutama di daerah Semenanjung
Sankulirang. Tidak ada musim kemarau yang khusus karena angin musim
tenggara melintasi laut terbuka sehingga juga membawa hujan ke daerah lain.
Walaupun pola iklim Borneo secara umum bercirikan curah hujan
yang tinggi, periode kemarau yang pendek sepanjang tahun berperan penting
dalam kehidupan tumbuhan dan mempengaruhi pola pembungaan dan
pembuahan pada tumbuhan. Hanya kadang-kadang saja musim kemarau
berlangsung agak lama. Pada tahun 1982-1983 di Borneo terjadi musim
kemarau yang berkepanjangan, yang terjadi lagi pada tahun 1987, 1990 dan
1997. Musim kemarau yang panjang ini terjadi secara berkala dalam
sejarah Borneo, dan mungkin berkaitan dengan osilasi El Nino di bagian
selatan (Leighton dan Wirawan 1986).
C. KONDISI TANAH
Kondisi tanah merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi
penyebaran vegetasi. Ada lima faktor utama dalam formasi tanah : litologi,
iklim, topografi, mahluk hidup dalam waktu.Secara umum pengetahuan
tentang penyebaran tanah di kalimantan masih terbatas ; 90% laporan survey
tanah yang dibuat oleh Pusat Penelitian Tanah terbatas untuk proyek-proyek
khusus seperti transmigrasi, perkebunan atau jaringan irigasi (sudjadi 1988).
Sebagian besar tanah telah di Kalimantan berkembang pada dataran
bergelombang dan pegunungan yang tertoreh diatas batuan sedimen dan
batuan beku tua. Tanah-tanah ini berkisar dari ultisol masam yang sangat lauk
dan inceptisol muda. Di bagian selatan dataran aluvial dan tanah gambut yang
sangat luas, terus meluas sampai ke Laut Jawa. Perluasan ini masih terus
terjadi di dangkalan Kalimantan bagian selatan, dengan endapan aluvial yang
terbentuk di belakang hutan bakau pesisir.
11

Di daerah tropis yang lembab pelapukan berlangsung sangat cepat,
disebabkan oleh panas dan kelembaban. Karena curah hujan yang tinggi, tanah
selalu basah dan unsur-unsur pokoknya yang dapat larut hilang ; proses ini
disebut pelindian. Tingkat pelapukan, pelindian dan kegiatan biologi
(kerusakan bahan-bahan organik) yang tinggi merupakan ciri berbagai tanah
di Borneo (Burnham, 1984). Batuan pulau ini miskin kandungan logam dan
tanah Borneo umumnya kurang subur dibandingkan dengan tanah vulkanik
yang subur di Jawa. Pelapukan sempurna yang dalam disertai dengan
pelindian menghasilkan tanah yang kesuburannya rendah di berbagai dataran
rendah. Lereng yang lebih curam mungkin lebih subur karena erosi dan tanah
longsor terus membuk batuan induk yang baru.
Tanah di atas bagian utama Borneo tengah dan Borneo timur laut
adalah ultasol (acrisol). Tanah yang mengalami pelapukan sangat berat ini
membentuk jenis tanah podsolik merah-kuning di sebagian besar daratan
Kalimantan yang bergelombang.Sebagian besar ultisol di Kalimantan
adalah tropodult. Jenisudult sukar untuk digunakan secara intensif karena
kandungan hara di bawah lapisan permukaan rendah dan komposisi antara
kandungan aluminium yang tinggi dan keasaman yang kuat (RePPProT
1990). Secara tradisional penduduk setempat telah menggunakan tanah ini
untuk perladangan ”berpindah” dengan tanaman berumur pendek dan masa
bera yang lebih panjang supaya kesuburan tanah pulih kembali. Cara ini
memberikan kesempatan bagi lapisan permukaan tanah untuk mengumpulkan
humus dan bahan organik lagi yang penting bagi cadangan hara dan untuk
mengatur kelembaban dan suhu tanah.
Kelompok tanah yang paling umum di Kalimantan
adalahInceptisol. Tanah ini pelapukannya sedang dengan profil yang jelas
merupakan tanah Borneo yang relatif lebih subur. Di Kalimantan juga terdapat
kelompok tanah aquept dan tropept(RePPProT 1990). Jenis
tanah tropoquept yang tersalir buruk terbentuk pada endapan sungai yang
tererosi dari batu pasir silika periode Tersier. Sabak merupakan
12

kelompok aquept yang paling tidak subur. Tanah tropept yang lebih subur
tersebar luas, terutama di pegunungan yang terpotong tajam dan daerah
pegunungan di tempat-tempat dengan kelerengan terjal dan erosi
aktif. Beberapa tropept tua berkaitan dengan bentang lahan yang
datar. Kelompok dystropept yang berwarna coklat tua kemerahan terbentuk di
atas batuan masam dan bersilika, seperti batuan konglomerat, batuan pasir,
dan batuan lanau mudah ditemukan di Kalimantan.
Tanah histosol, nonmineral atau tanah yang terutama tersusun atas
bahan organik disebut gambut, mencakup daerah yang luas di dataran rendah
Kalimantan (RePPProT 1990). Tanah ini semula berupa dataran aluvial
berbatu di rawa. Di sini serasah dan sampah organik terkumpul secara cepat,
lebih dari 4.5 mm/tahun (Anderson, 1964), karena kondisinya yang tetap
jenuh dan anaerob. Pada tanah tropohemist bahan organik hanya terurai
sebagian. Histosol juga terdapat di Borneo sebagai lapisan bahan organik yang
relatif tipis (50-150 cm) yang terkumpul di dataran tinggi dan perbukitan,
dimana terdapat banyak awan dan kelembabanya tinggi. Tanah ini berupa
gambut ombrogen (gambut asam) yang terkait erat dengan hutan
lumut. Hampir seluruh tanah histosol sangat masam dengan kandungan hara
utama dan hara tambahan rendah, sehingga sulit diolah dan memerlukan biaya
tinggi untuk mengolahnya (RePPProT 1990).
Tanah alfisol terbentuk bila batuan menghasilkan sejumlah besar
bahan dasar ketika mengalami pelapukan, seperti marl berkapur dan batuan
kapur di bagian timur Kalimantan. Di Kalimantan, malisol dibatasi oleh
bentang lahan yang kaya akan kapur. Tanah ini berwarna gelap, karena
kandungan humusnya tinggi dan kaya bahan dasar terutama kalsium. Secara
umum jenis tanah ini miskin kalium yang merupakan hara utama.Kapur yang
menyebabkan kekurangan hara tambahan merupakan masalah bagi
kebanyakan tanaman di tanah yang keasaman dan kebasaan
rendah. Rendol yang tersalir dengan baik dapat dengan mudah ditemukan
dibagian timur Kalimantan, terutama di Semenanjung Sankulirang.
13

Tanah yang paling lapuk adalah exisol, didominasi oleh liat yang
mempunyai sedikit mineral yang terdapat lapuk dan menghasilkan sedikit hara
tanaman. Jenis tanah ini terdapat diatas batuan ulta basa di Ranau dan Tawau,
Sabah dan pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Walaupun tanah ini
mengandung Mg/Ca dengan kadar tinggi dan nikel, krom dan kobalt yang
berkadar tinggi, vegetasinya tidak berbeda dengan hutan
disekitarnya. Sebaliknya tanah-tanah yang kaya akan bahan organik di daerah
yang tinggi dengan gambut di atas batuan ultrabasa, seperti g. Kinibalu pada
ketinggian 2.000-2.800 m, mendukung kehidupan vegetasi tertentu (Burnham
1984).
Jenis tanah entisols berasal dari batuan yang lebih muda dan kurang
berkembang. Fluvent dan aquents (tanah aluvial) terdapat di dataran-dataran
banjir pada lembah-lembah sungai dan di dataran pantai, yang menerima
endapan baru dari lembah-lembah sungai dan di dataran pantai, yang
menerima endapan baru dari tanah aluvial secara berkala. Tanah equentsjenuh
air dalam suatu periode yang panjang dalam satu tahun dengan ciri khas
dalam, berwarna abu-abu dan warna lainnya; tingkat kesuburannya bergantung
pada kandungan mineral dan bahan organik endapan aluvial
asalnya. Tanah hydraquentsterdapat di rawa pasang surut Kalimantan; tanah
ini muda, lunak, berlumpur dan belum
berkembang. Tanah sulfaquentsumumnya terdapat bersama-sama
dengan hydraquents. Tanah-tanah yang tersalir buruk ini sangat terbatas untuk
tanah pertanian, karena mengandung pirit, yang jika dikeringkan akan
menimbulkan kondisi yang sangat masam dengan kadar besi dan aluminium
sulfat yang cukup tinggi, sehingga bersifat beracun. Tanah asam sulfat ini
terdapat di daerah P. Petak, Kalimantan Selatan.
Jenis tanah fluvents penting di dataran banjir di tepi sungai atau danau
di Kalimantan. Tanah-tanah ini umumnya terdapat di sungai-sungai yang
mengangkut endapan yang rawan terhadap banjir dan perubahan aliran
sungai. Kandungan mineral dan kesuburan tanah tropofluvents di kalimantan
14

tergantung pada formasi geologi di daerah aliran sungai bagian hulu dan
topografi daerah sekitarnya. Dua lingkungan utama yang bertanah aluvial
adalah muara sungai dan rawa-rawa belakangnya. Tanah-tanah aluvial baru
yang berasosiasi dengan air tawar di Borneo sebagian besar mendukung
hutan-hutan rawa air tawar. Tanah aluvial yang lebih baru ini umumnya lebih
subur dari pada lereng-lereng sekitarnya, tetapi tidak sesubur tanah aluvial laut
atau abu vulkanik (Burnham 1984). Tanah-tanah aluvial di dataran tepi sungai
di Kalimantan adalah tanah-tanah yang paling subur dan merupakan habitat
yang mudah dikelola. Kebalikan dari tanah yang subur ini adalah
tanahpsamments, merupakan tanah muda yang mencolok, umumnya terdapat
pada pantai-pantai muda maupun pantai tua. Tingkat kesuburan jenis tanah ini
sangat rendah. Jenis tanahpsmaments yang luas terdapat di bagian tengah
kalimantan.
Kapasitas umum menyimpan zat-zat hara pada tanah-tanah Borneo
sebagian besar bergantung pada kandungan humus. Oleh karena itu
kandungan zat hara yang sangat rendah bila lapisan humusnya rendah,
misalnya pada tanah-tanah pasir kerangas.Di dalam tanah yang dalamnya satu
meter, hampir setengahnya dari basa yang diserap hanya terdapat dalam
lapisan atas sedalam 25 cm (Nye dan Greeland 1960). Hal ini menjelaskan
tingkat kesuburan yang sangat rendah pada ladang-ladang, karena pembakaran
vegetasi penutup dan erosi lapisan tanah atas menyebabkan lapisan yang
paling subur hilang. Untuk penggunaan tanah lahan pertanian yang
berkelanjutan, banyak tanah-tanah di Borneo memerlukan tindakan-tindakan
konservasi terutama untuk lapisan tanah atas dan pengendalian erosi,
penggunaan pupuk yang seimbang serta pengelolaan yang baik.
D. FLORA
Definisi atau Pengertian, flora berasal dari bahasa Latin yaitu Flora,
dewi yang bunga Flora dapat merujuk kepada sekelompok tanaman, sebuah
15

penyelidikan dari kelompok tanaman, serta bakteri. Flora adalah akar kata
bunga, yang berarti menyangkut bunga. Pulau kalimantan memiliki berbagai
jenis flora yang hidup di daratan kalimantan, maupun pesisir pantai dan
sekitarnya. Tercatat 817 jenis tumbuhan yang termasuk dalam 139 famili
seperti Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae
dan Ericadeae. Disamping terdapat tumbuhan untuk obat-obatan, kerajinan
tangan, perkakas/bangunan, konsumsi dan berbagai jenis anggrek hutan, juga
terdapat bunga Rafflesia (Rafllesia sp.) yang merupakan bunga parasit raksasa
serta diduga memiliki persamaan dengan jenis yang ditemukan di Gunung
Kinibalu Malaysia. Di daerah-daerah pesisir, dimana sungai bermuara
lebarnya 1 sampai 2 km, terdapat rawa-rawa yang pada waktu air pasang
tergenang air dan ditimbuni endapan yang terbawa oleh sungai-sungai. Jika
endapan mencapai tebal 1 meter dan tercampur dengan gambut, tanah itu
ditanami dengan tanaman-tanaman yang berakar, yang suka zat asam yaitu
famili nyrtaceae seperti jenis galam, palmae, rumbia, kemudian keladi air,
jenis pisang, kancur-kancur, kesisap sayur, semangka, ubi jalar dan labu
(waluh).
Kemudian juga famili compositae, jenis langsat, petah kemudi, galah
motawauk, famili papiliomacena, jenis sup-supan, kangkung, genjer, bingkai
dan balaran dali, dan famili nyphacacene. Di pantai dimana tidak ada sungai-
sungai bermuara, selain berbatu karang terdapat tanah kering dan bentuknya
bergelombang. Tumbuh-tumbuhan di tanah kering pesisir ini: famili graminae,
jenis alang-alang, gelagah, telor belalang, telor jarum, paku payung,
kangkung, hutan krokot, wedasan, karmalaha, masisin, keramunting, sukma,
hutan, tambaran-tambaran. Sementara tanah daratan di belakang pantai dan
bergelombang termasuk bukit yang tingginya sampai 120 m, dimana terdapat
kebun buah-buahan, tegalan dan sawah musim hujan (sawah tadahan). Di
daerah ini terdapat (dapat tumbuh) pohon-pohon nangka, durian, rambutan,
duku/langsat, kasturi, keminting, pisang, pepaya, dan terutama karet.
Dalam pembagian vegetasi menurut Dr. Schimper, hutan di
Kalimantan masuk ke dalam golongan hutan hujan tropis, yang dibagi-bagi
16

lagi dalam beberapa formasi: hutan payau, hutan nipah, hutan rawa, hutan
bukitbukit/ belukar/primer, dan hutan gunung. Wilayah Kalimantan di
dominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu keras dan
besar. Terdapat juga liana (tumbuhan pemanjat) yang menjadi komoditi
unggulan yaitu : rotan.
1. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas daerah dataran rendah pantai,
daerah
rawa, daerah perbukitan dan pegunungan
2. Di bagian tengah, terdapat pegunungan Meratus yang membujur dari
utara ke
selatan yang membelah wilayah menjadi dua bagian yang berbeda
3. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan
primer, hutan
sekunder, semak belukar dan padang ilalang. `
4. Di bagian barat, terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa
monoton, rawa
banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada bagian ini
ditumbuhi oleh hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai
jenis rawa.
E. FAUNA
Pengertian fauna adalah Fauna atau faunæ adalah semua kehidupan
hewan dari setiap wilayah tertentu atau waktu. Ahli zoologi dan paleontologi
menggunakan fauna untuk merujuk ke koleksi khas hewan yang ditemukan
dalam waktu atau tempat tertentu. Satwa mamalia yang dapat dijumpai antara
lain macan dahan(Neofelisnebulosa), orang utan (Pongopygmaeus) beruang
madu (Helarctos malayanus).Dari jenis aves antara lain enggang gading
(Rhinoplax vigil), rangkok badak (Buceros rhinoceros), enggang hitam
(Anthracoceros malayanus), kuau kerdil kalimantan (Polyplevtron
17

schleiermacher), dan ruai (Argusianus argus). Terdapat dua jenis burung yang
termasuk dalam “New Record” di Indonesia yaitu punai imbuk (Chalcohap
indica) dan uncal merah (Macropygia phaseanella). Terdapat dua jenis burung
yang termasuk dalam “New Record” di Indonesia yaitu punai imbuk
(Chalcohap indica) dan uncal merah (Macropygia phaseanella). Untuk jenis
amphibia dan reptilia yang merupakan jenis unik dan langka seperti katak
bertanduk (Megophyrs nasuta), biawak hijau (Varanus prasinus), dan
bengkarung (Mabuya sp.). Dari jenis insekta antara lain dari famili Lamprydae
(keluing pil raksasa, dan keluing biasa), capung (sibar-sibar cincin emas, dan
sibar-sibar merah), kupukupu sayap burung (Trogonoptera brookiana), kupu-
kupu jeruk sayap panjang (Papilio xunthos), kupu-kupu sayap burung paris
(Papilio paris) dan kupu-kupu jesebel (Delias sp.).
F. EKONOMI
Perekonomian Kalimantan Tengah memiliki total Nilai PDRB sebesar
20,o7 Trilyun , sektor pertanian memberikan kontribusi yang terbesar yaitu
sebesar Rp 6,001 Trilyun ( 29,9%) diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan
restoran sebesar Rp 3,7 trilyun (18,5%) dan sektor pertambangan dan
penggalian sebesar Rp 2,1 Trilyun (10,5%). Dengan rincian sebagaimana
dalam lampiran.
G. DEMOGRAFI
Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas 13 (tiga belas)
Kabupaten dan 1 (Satu) Kota memiliki total jumlah penduduk tahun 2011
sebesar 2.249.146 jiwa dengan rincian sebagaimana terdapat dilampiran. Dari
tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 kabupaten yang memiliki
jumlah penduduk terbanyak berturut turut adalah kabupaten Kotawaringin
Timur ( 380.443 jiwa ), kabupaten Kapuas (335.168 jiwa ) dan kabupaten
18

Kotawaringin Barat ( 239.753 jiwa ) sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk terkecil adalah kabupaten Sukamara ( 45.706 Jiwa ).
19

BAB III
DAYAK
A. SEJARAH
Secara umum kebanyakan penduduk kepulauan Nusantara adalah
penutur bahasa Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan
linguis seperti Peter Bellwood danBlust, yaitu bahwa tempat asal bahasa
Austronesia adalah Taiwan. Sekitar 4 000 tahun lalu, sekelompok orang
Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada
kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju kepulauan Indonesia
sekarang, dan ke timur menuju Pasifik. Namun orang Austronesia ini bukan
penghuni pertama pulau Borneo. Antara 60 000 dan 70 000 tahun lalu, waktu
permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang dan kepulauan
Indonesia berupa daratan (para geolog menyebut daratan ini "Sunda"),
manusia sempat bermigrasi dari benua Asia menuju ke selatan dan sempat
mencapai benua Australia yang saat itu tidak terlalu jauh dari daratan Asia.
Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan.
Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar
menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir
pulau Kalimantan. Tetek Tahtum menceritakan perpindahan suku Dayak dari
daerah hulu menuju daerah hilir sungai.
Di daerah selatan Kalimantan Suku Dayak pernah membangun sebuah
kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nansarunai
Usak Jawa, yakni kerajaan Nansarunai dari Dayak Maanyan yang dihancurkan
oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389. Kejadian
tersebut mengakibatkan suku Dayak Maanyan terdesak dan terpencar,
sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus
besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari kerajaan
Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1520).
20

Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur kalimantan yang
memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya
sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai atau orang
Banjar dan Suku Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam
kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-
daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Amas dan
Watang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak
pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian
Kotawaringin, salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal
adalah Lambung Mangkurat menurut orang Dayak adalah seorang Dayak
(Ma’anyan atau Ot Danum). Di Kalimantan Timur, orang Suku Tonyoy-
Benuaq yang memeluk Agama Islam menyebut dirinya sebagai Suku Kutai.
Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke
Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa
Dinasti Ming yang tercatat dalam Buku 323 Sejarah Dinasti Ming (1368-
1643). Dari manuskrip berhuruf hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama
dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang Pangeran yang
berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah I . Kunjungan tersebut
pada masa Sultan Hidayatullah I dan penggantinya yaituSultan Mustain
Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi tidak menetap oleh
pedagang jung bangsa Tionghoa dan Eropa (disebut Walanda) di Kalimantan
Selatan telah terjadi pada masa Kerajaan Banjar Hindu (abad XIV).
Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat
dekat pantai pada tahun 1736. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan
Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak
memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama
dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga
dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh
sebagian suku Dayak seperti piring malawen, belanga (guci) dan peralatan
keramik. Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan.
Pada abad XV Kaisar Yongle mengirim sebuah angkatan perang besar ke
21

selatan (termasuk Nusantara) di bawah pimpinan Cheng Ho, dan kembali ke
Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah
ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan
Mempawah menerima orang-orang Tionghoa (dari Brunei) yang sedang
mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang
dagangan diantaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring,
cangkir, mangkok dan guci.
B. SUB-SUKU BANGSA DAYAK
Berdasarkan pola menetapnya, suku bangsa ini dapat dikelopokkan
kedalam subsuku bangsa sebagai berikut :
1. Suku bangsa Punan, menetep di pedalaman Kalimantan tengah. Suku
bangsa ini sangat terisolasi dari dunia luar, mereka hidup secara
berpindah-pindah dari satu lokasi lingkungan hutan ke lingkungan hutan
lainnya.
2. Suku bangsa Ola Ngaju dan Ola Ot menetap di pedalaman Kalimantan
Tenggara.
3. Suku bangsa Dayak kayan, menetap di pedalaman Kalimantan Utara
sampai ke daerah pesisir.
4. Suku bangsa Dayak Ma’anyan/siung menetap di pedalaman Kalimnatan
Selatan sepanjang Sungai siung dan Sungai Barito.
5. Suku-suku bangsa dayak lainnya yang relatif menyebar di pedalaman
seperti Dayah Kenyah, Ot Danum, Iban, dan lain-lain.
C. SISTEM KEKERABATAN
Sistem kekerabatan orang Dayak Kalimantan Tengah, didasarkan pada
prinsip keturunan ambilineal, yang menghitungkan hubungan kekerabatan
melalui laki-laki maupun wanita. Pada masa dahulu, kelompok kekerabatan
22

yang terpenting masyarakat mereka adalah keluarga ambilineal kecil yang
timbul kalau ada keluarga luas yang utrolokal, yaitu sebagai dari anak-anak
laki-laki maupun perempuan sesudah kawin membawa keluarganya masing-
masing, untuk tinggal dalam rumah orang tua mereka, sehingga menjadi suatu
keluarga luas.
Pada masa sekarang, kelompok kekerabatan yang terpenting adalah
keluarga luas utrolokal yang menjadi isi dari suatu rumah tangga. Rumah
tangga ini berlaku sebagai kesatuan fisik misalnya dalam sistem gotong
royong dan sebagai kesatuan rohanian dalam upacara-upacara agama
kaharingan. Kewarganegaraan dari suatu rumah tangga tidak statis, karena
keanggotaannya tergantung pada tempat tinggal yang ditentukan sewaktu ia
mau menikah, padahal ketentuan itu dapat diubah menurut keadaan setelah
menikah. Jika orang bersama keluarganya kemudian pindah dari rumah itu,
pertalian fisik dan rohani dengan rumah tangga semula pun turut berubah.
Pada orang Dayak, perkawinan yang diangap ideal dan amat diingini oleh
umum, perkawinan antara dua orang saudara sepupu yang kakek-kakeknya
adalah sekandung, yaitu apa yang disebut hajenan dalam bahasa ngaju
(saudara sepupu derejat kedua) dan perkawinan antara dua orang saudara
sepupu dan ibu-ibunya bersaudara sekandung serta antara cross-cousin.
Perkawinan yang dianggap sumbang (sala horoi dalam bahasa Ngaju)
adalah perkawinan antara saudara yang ayah-ayahnya adalah bersaudara
sekandung (patri-parallel cousin), dan terutama sekali perkawinan antara
orang-orang dari generasi yang berbeda misalnya antara seorang anak dengan
orang tuanya, atau antara seorang gadis dengan mamaknya.
D. SISTEM RELIGI
Golongan islam merupakan golongan terbesar, sedangkan agama asli
dari penduduk pribumi adalah agama Kaharingan. Sebutan kaharingan
diambil dari Danum Kaharingan yang berarti air kehidupan. Umat Kaharingan
23

percaya bahwa lingkunan sekitarnya penuh dengan mahluk halus dan roh-roh
(ngaju ganan) yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon
besar, hutan belukar, air , dan sebagainya. Ganan itu terbagi kedalam 2
golongan, yaitu golongan roh-roh baik (ngaju sangyang nayu-nayu) dan
golongan roh-roh jahat (seperti ngaju taloh, kambe, dan sebagainya). Selain
ganan terdapat pula golongan mahluk halus yang mempunyai suatu peranan
peting dalam kehidupan orang dayak yaitu roh nenek moyang (ngaju liau).
Menurut mereka jiwa (ngaju hambaruan) orang yang mati meninggalkan
tubuh dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia
sebagai liau sebelum kembali kepada dewa tertinggi yang disebut Ranying.
Kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan mahluk-mahluk halus
tersebut terwujud dalam bentuk keagamaan dan upacara-upacara yang
dilakukan seperti upacara menyambut kelahiran anak, upacara memandikan
bayi untuk pertama kalinya, upacara memotong rambut bayi, upacara
mengubur, dan upacara pembakaran mayat. Upacar pembakaran mayat pada
orang ngaju menyebutnya tiwah (Ot Danum daro Ma’anyam Ijambe ). Pada
upacara itu tulang belulang (terutama tengkoraknya) semua kaum kerabat
yang telah meninggal di gali lagi dan dipindahkan ke suatu tempat
pemakaman tetap, berupa bangunan berukiran indah yang disebut sandung.
E. UPACARA ADAT
1. Perkawinan
Prosesi tradisi pernikahan Dayak Ngaju dilangsungkan dengan
berbagai tahap. Perkawinan adat ini disebut Penganten Mandai. Dalam
iring-iringan, seorang ibu yang dituakan dalam keluarga calon mempelai
pria, membawa bokor berisi barang hantaran. Sedangkan pihak keluarga
calon mempelai wanita menyambutnya di balik pagar. Sebelum memasuki
kediaman mempelai wanita. Masing-masing dari keluarga mempelai
24

diwakilkan oleh tukang sambut yang menjelaskan maksud dan tujuannya
datang dengan mengunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun sebelum
diperbolehkan masuk, rombongan mempelai pria harus melawan penjaga
untuk bisa menyingkirkan rintangan yang ada di pintu gerbang. Kemudian
setelah dinyatakan menang pihak pria, maka tali dapat dipotong kemudian
di depan pintu rumah, calon mempelai pria harus menginjak telur dan
menabur beras dengan uang logam. Yang maksud dan tujuannya supaya
perjalanan mereka dalam berumah tangga aman, sejahtera dan sentosa.
Setelah duduk di dalam ruangan, terjadi dialog diantara kedua pihak.
Masing-masing diwakilkan (Haluang Hapelek). Diatas tikar (amak
badere), disuguhkan minuman anggur yang dimaksudkan supaya
pembicaraan berjalan lancar dan keakraban terjalin di kedua belah pihak.
Sebelum dipertemukan dengan calon mempelai wanita, calon
mempelai pria terlebih dulu menyerahkan barang jalan adat yang terdiri
dari palaku (mas kawin), saput pakaian, sinjang entang, tutup uwan, balau
singah pelek, lamiang turus pelek, buit lapik ruji dan panginan jandau.
Sesuai dengan adat yang berlaku, sebelum kedua mempelai sah secara
adat, mereka harus menandatangani surat perjanjian nikah, yang
disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak. Dan bagi para hadirin yang
menerima duit turus, dinyatakan telah menyaksikan perkawinan mereka
berdua. Sebelum acara berakhir, masing-masing keluarga memberikan doa
restu kepada pengantin (tampung rawar). Dilanjutkan dengan hatata undus
yakni kegiatan saling meminyaki antara dua keluarga ini sebagai tanda
sukacita, dengan menyatukan dua keluarga besar.
2. Kelahiran
Menurut tradisi di kalangan masyarakat Dayak , pada saat
melahirkan biasanya diadakan upacara memukul gendang atau gimar dan
kelentangan dalam nada khusus yang disebut Domaq. Hal tersebut
25

dimaksud agar proses kelahiran dapat berjalan dengan lancer dan selamat.
Setalah bayi lahir, tali pusar dipotong dengan menggunakan sembilu
sebatas ukuran lutut si bayi dan kemudian diikat dengan benang dan diberi
ramuan obat tradisional, seperti air kunyit dan gambir. Alas yang
digunakan untuk memotong tali pusar, idealnya diatas uang logam perak
atau bila tidak ada adapat diganti dengan sepotong gabus yang bersih.
Langkah berikutnya bayi dimandikan, setelah bersih dimasukkan kedalam
Tanggok/Siuur yang telah dilapisi dengan daun biruq di bagian bawah.
Sedangkan di bagian atas, dilapisi daun pisang yang telah di panasi dengan
api agar steril. Kemudian bayi yang telah dimasukan dalam Siuur itu,
dibawa kesetiap sudut ruangan rumah, sambil meninggalkan potongan-
potongan tongkol pisang yang telah disiapkan pada setiap ruangan tadi.
Hal Itu dimaksudkan agar setiap makhluk pengganggu tertipu oleh
potongan tongkol pisang itu sebagai silih berganti. Setelah itu, bayi
tersebut dibawa kembali ke tempat tidur semula, kemudian disekeliling
bayi dihentakan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisi air, yang
disebut Tolakng, sebanyak delapan kali, dengan tujuan agar si bayi tidak
tuli atau bisu nantinya. Setelah mencapai usia empat puluh hari, diadakan
upacara Ngareu Pusokng, atau Ngerayah dalam bentuk upacara Belian
Beneq, selama dua hari. Hal itu dimaksud untuk membayar hajat,
sekaligus mendoakan agar si bayi sehat dan cerdas, serta berguna bagi
keluarga dan masyaraka. Pada upacara ini juga merupakan awal dari
diperbolehkannya si bayi di masukan dan ditidurkan dalam ayunan ( Lepas
Pati ). Sebelum bayi berumur dua tahun, diadakan upacara permandian
atau turun mandi di sungai untuk yang pertama kalinya. Pada upacara ini
tetap dipergunakan Belian Beneq, selama satu hari, dengan maksud
memperkenalkan si adak kepada dewa penguasa air yaitu Juata, agar kelak
tidak terjadi bahaya atas kegiatan anak tersebut yang berkaitan dengan air
(Nyengkokng Ngeragaq).
3. Kematian
26

Tradisi penguburan dan upacara adat kematian pada suku bangsa
Dayak diatur tegas dalam hukum adat. Sistem penguburan beragam sejalan
dengan sejarah panjang kedatangan manusia di Kalimantan. Dalam
sejarahnya terdapat tiga budaya penguburan di Kalimantan :
a) Penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal, dengan posisi kerangka
dilipat.
b) Penguburan di dalam peti batu (dolmen)
c) Penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, atau anyaman tikar.
Penguburan tidak lagi dilakukan di gua. Di hulu Sungai Bahau dan
cabang-cabangnya di Kecamatan Pujungan, Malinau, Kalimantan Timur,
banyak dijumpai kuburan tempayan-dolmen yang merupakan peninggalan
megalitik. Perkembangan terakhir, penguburan dengan menggunakan peti
mati (lungun) yang ditempatkan di atas tiang atau dalam bangunan kecil
dengan posisi ke arah matahari terbit.
Masyarakat Dayak mengenal tiga cara penguburan, yakni :
a) Dikubur dalam tanah
b) Diletakkan di pohon besar biasanya untuk anak bayi dikarenakan
terdapat getah yang dianggap sebagai air susu ibu
c) Dikremasi dalam upacara tiwah.
Prosesi penguburan :
a) Tiwah adalah prosesi penguburan sekunder pada penganut Kaharingan,
sebagai simbol pelepasan arwah menuju lewu tatau (alam
kelanggengan) yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah
penguburan pertama di dalam tanah.
27

b) Ijambe adalah prosesi penguburan sekunder pada Dayak Maanyan.
Belulang dibakar menjadi abu dan ditempatkan dalam satu wadah.
c) Marabia
d) Mambatur (Dayak Maanyan) Kwangkai Wara
F. SISTEM PENGETAHUAN
1. Dalam berpakaian dulu orang suku Dayak sering menggunakan ewah
(cawat) untuk pakaian asli laki-laki Dayak yang terbuat dari kulit kayu dan
Kaum wanita memakai sarung dan baju yang terbuat dari kulit kayu,
sedangkan pada masa sekarang orang Dayak di Kalimantan Tengah Sudah
berpakaian legkap seperti : laki-laki memakai hem dan celana dan kaum
wanita memakai sarung dan kebaya atau bagi anak muda memakai rok
potongan Eropa.
2. Zaman dulu para wanita sering menggunakan anting yang banyak agar
semakin panjangnya daun telinga semakin cantik wanita tersebut, para
lelakinya sering menggunakan tato bahwa semakin banyaknya tato ditubuh
lelaki tersebut maka ia akan terliahat gagah dan ganteng.
3. Terkadang mereka sering menggunakan bahasa inggris untuk komunikasi
tetapi masih bersifat pasif.
4. Menggandalkan atau menggunakan rasi bintang untuk mengetahui apakah
cocok untuk bertanam atau berladang.
G. SISTEM PERALATAN DAN PERLENGKAPAN HIDUP
Dalam kehidupan sehari-hari orang suku Dayak hidup dengan berburu.
Berikut alat-alat yang sedikit maju (berkembang) yang digunakan untuk
berburu :
1. Sipet / Sumpitan Merupakan senjata utama suku dayak. Bentuknya bulat
dan berdiameter 2-3 cm, panjang 1,5 – 2,5 meter, ditengah- tengahnya
berlubang dengan diameter lubang ¼ – ¾ cm yang digunakan untuk
28

memasukan anak sumpitan (Damek).Ujung atas ada tombak yang terbuat
dari batu gunung yang diikat dengan rotan dan telah di anyam. Anak
sumpit disebut damek, dan telep adalah tempat anak sumpitan.
2. Lonjo / Tombak. Dibuat dari besi dan dipasang atau diikat dengan
anyaman rotan dan bertangkai dari bambu atau kayu keras.
3. Telawang / Perisai. Terbuat dari kayu ringan, tetapi liat. Ukuran panjang 1
– 2 meter dengan lebar 30 – 50 cm. Sebelah luar diberi ukiran atau lukisan
dan mempunyai makna tertentu. Disebelah dalam dijumpai tempat
pegangan.
4. Mandau Merupakan senjata utama dan merupakan senjata turun temurun
yang dianggap keramat. Bentuknya panjang dan selalu ada tanda ukiran
baik dalam bentuk tatahan maupun hanya ukiran biasa. Mandau dibuat
dari batu gunung, ditatah, diukir dengan emas/perak/tembaga dan dihiasi
dengan bulu burung atau rambut manusia. Mandau mempunyai nama asli
yang disebut “Mandau Ambang Birang Bitang Pono Ajun Kajau”,
merupakan barang yang mempunyai nilai religius, karena dirawat dengan
baik oleh pemiliknya. Batu-batuan yang sering dipakai sebagai bahan
dasar pembuatan Mandau dimasa yang telah lalu yaitu: Batu Sanaman
Mantikei, Batu Mujat atau batu Tengger, Batu Montalat.
5. Dohong Senjata ini semacam keris tetapi lebih besar dan tajam sebelah
menyebelah. Hulunya terbuat dari tanduk dan sarungnya dari kayu.
Senjata ini hanya boleh dipakai oleh kepala-kepala suku, Demang, Basi.
H. SISTEM BAHASA
Bahasa yang sering dipakai oleh suku dayak dalam kehidupan sehari-
hari dibagi 2, yaitu :
1. Bahasa Pengantar
Seperti pada umumnya bagian negara Indonesia yang merdeka
lainnya, masyarakat Kalimantan Tengah menggunakan bahasa Indonesia
29

sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia telah digunakan untuk
sebagai bahasa pengantar di Pemerintahan dan pendidikan.
2. Bahasa sehari-hari
Keberagaman etnis dan suku bangsa menyebabkan Bahsa
Indonesia dipengaruhi oleh berbagai dialeg. Namun kebanyakan bahasa
daerah ini hanya digunakan dalam lingkungan keluarga dan tempat
tinggal, tidak digunakan secara resmi sebagai bahasa pengantar di
pemerintahan maupun pendidikan. Sebagian besar suku Kalimantan
Tengah terdiri dari suku bangsa Dayak. Suku bangsa dayak sendiri terdiri
atas beberapa sub-suku bangsa. Bahasa Dayak Ngaju adalah bahasa dayak
yang paling luas digunakan di Kalimantan Tengah, terutama didaerah
sungai Kahayan dan Kapuas, bahasa Dayak Ngaju juga terbagi lagi dalam
berbagai dialeg seperti seperti bahasa Dayak Katingan dan Rungan. Selain
itu bahasa selain itu bahasa Ma’anyan dan Ot’danum juga banyak
digunakan. Bahasa Ma’anyan banyak digunakan didaerah aliran sungai
Barito dan sekitarnya sedangkan bahasa Ot’danum banyak digunakan oleh
suku dayak Ot’danum di hulu sungai Kahayan dan Bahasa Barito timur
bagian Tengah-Selatan :
a) Bagian Selatan :
1) Bahasa Ma’anyam
2) Bahasa Dusun Malang
3) Bahasa Dusun Witu
4) Bahasa Dusun Witu
5) Bahasa Paku
b) Bagian Barito Barat :
1) Bahasa Barito Barat bagian Utara
2) Bahasa Kohin
30

3) Bahasa Dohoi
4) Bahasa Siang-Murung
5) Bahasa Barito barat bagian Selatan
6) Bahasa Bakumpai
7) Bahasa Ngaju
8) Bahasa Kahayan
I. SISTEM KESENIAN
1. TARI
a) Tari Gantar
Tarian yang menggambarkan gerakan orang menanam padi.
Tongkat menggambarkan kayu penumbuk sedangkan bambu serta biji-
bijian didalamnya menggambarkan benih padi dan wadahnya. Tarian
ini cukup terkenal dan sering disajikan dalam penyambutan tamu dan
acara-acara lainnya.Tari ini tidak hanya dikenal oleh suku Dayak
Tunjung namun juga dikenal oleh suku Dayak Benuaq. Tarian ini
dapat dibagi dalam tiga versi yaitu tari Gantar Rayatn, Gantar Busai
dan Gantar Senak/Gantar Kusak.
b) Tari Kancet Papatai / Tari Perang
Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak
Kenyah berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat
lincah, gesit, penuh semangat dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan
si penari. Dalam tari Kancet Pepatay, penari mempergunakan pakaian
tradisionil suku Dayak Kenyah dilengkapi dengan peralatan perang
seperti mandau, perisai dan baju perang. Tari ini diiringi dengan
lagu Sak Paku dan hanya menggunakan alat musik Sampe.
31

c) Tari Kancet Ledo / Tari Gong
Jika Tari Kancet Pepatay menggambarkan kejantanan dan
keperkasaan pria Dayak Kenyah, sebaliknya Tari Kancet Ledo
menggambarkan kelemahlembutan seorang gadis bagai sebatang padi
yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh
seorang wanita dengan memakai pakaian tradisionil suku Dayak
Kenyah dan pada kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu
ekor burung Enggang. Biasanya tari ini ditarikan diatas sebuah gong,
sehingga Kancet Ledo disebut juga Tari Gong.
d) Tari Kancet Lasan
Menggambarkan kehidupan sehari-hari burung Enggang,
burung yang dimuliakan oleh suku Dayak Kenyah karena dianggap
sebagai tanda keagungan dan kepahlawanan. Tari Kancet Lasan
merupakan tarian tunggal wanita suku Dayak Kenyah yang sama gerak
dan posisinya seperti Tari Kancet Ledo, namun si penari tidak
mempergunakan gong dan bulu-bulu burung Enggang dan juga si
penari banyak mempergunakan posisi merendah dan berjongkok atau
duduk dengan lutut menyentuh lantai. Tarian ini lebih ditekankan pada
gerak-gerak burung Enggang ketika terbang melayang dan hinggap
bertengger di dahan pohon.
e) Tari Leleng
Tarian ini menceritakan seorang gadis bernama Utan Along
yang akan dikawinkan secara paksa oleh orangtuanya dengan pemuda
yang tak dicintainya. Utan Along akhirnya melarikan diri kedalam
hutan. Tarian gadis suku Dayak Kenyah ini ditarikan dengan diiringi
nyanyian lagu Leleng.
32

f) Tari Hudoq Kita’
Tarian dari suku Dayak Kenyah ini pada prinsipnya sama
dengan Tari Hudoq dari suku Dayak Bahau dan Modang, yakni untuk
upacara menyambut tahun tanam maupun untuk menyampaikan rasa
terima kasih pada dewa yang telah memberikan hasil panen yang baik.
Perbedaan yang mencolok anatara Tari Hudoq Kita’ dan Tari Hudoq
ada pada kostum, topeng, gerakan tarinya dan iringan musiknya.
Kostum penari Hudoq Kita’ menggunakan baju lengan panjang dari
kain biasa dan memakai kain sarung, sedangkan topengnya berbentuk
wajah manusia biasa yang banyak dihiasi dengan ukiran khas Dayak
Kenyah. Ada dua jenis topeng dalam tari Hudoq Kita’, yakni yang
terbuat dari kayu dan yang berupa cadar terbuat dari manik-manik
dengan ornamen Dayak Kenyah.
g) Tari Serumpai
Tarian suku Dayak Benuaq ini dilakukan untuk menolak wabah
penyakit dan mengobati orang yang digigit anjing gila. Disebut tarian
Serumpai karena tarian diiringi alat musik Serumpai (sejenis seruling
bambu).
h) Tari Belian Bawo
Upacara Belian Bawo bertujuan untuk menolak penyakit,
mengobati orang sakit, membayar nazar dan lain sebagainya. Setelah
diubah menjadi tarian, tari ini sering disajikan pada acara-acara
penerima tamu dan acara kesenian lainnya. Tarian ini merupakan
tarian suku Dayak Benuaq.
i) Tari Kuyang
Sebuah tarian Belian dari suku Dayak Benuaq untuk mengusir
hantu-hantu yang menjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar
tidak mengganggu manusia atau orang yang menebang pohon tersebut.
33

j) Tari Pecuk Kina
Tarian ini menggambarkan perpindahan suku Dayak Kenyah
yang berpindah dari daerah Apo Kayan (Kab. Bulungan) ke daerah
Long Segar (Kab. Kutai Barat) yang memakan waktu bertahun-tahun.
k) Tari Datun
Tarian ini merupakan tarian bersama gadis suku Dayak Kenyah
dengan jumlah tak pasti, boleh 10 hingga 20 orang. Menurut
riwayatnya, tari bersama ini diciptakan oleh seorang kepala suku
Dayak Kenyah di Apo Kayan yang bernama Nyik Selung, sebagai
tanda syukur dan kegembiraan atas kelahiran seorang cucunya.
Kemudian tari ini berkembang ke segenap daerah suku Dayak Kenyah.
l) Tari Ngerangkau
Tari Ngerangkau adalah tarian adat dalam hal kematian dari
suku Dayak Tunjung dan Benuaq. Tarian ini mempergunakan alat-alat
penumbuk padi yang dibentur-benturkan secara teratur dalam posisi
mendatar sehingga menimbulkan irama tertentu.
m) Tari Baraga’ Bagantar
Awalnya Baraga’ Bagantar adalah upacara belian untuk
merawat bayi dengan memohon bantuan dari Nayun Gantar. Sekarang
upacara ini sudah digubah menjadi sebuah tarian oleh suku Dayak
Benuaq.
2. RUMAH ADAT
Rumah adat Kalimantan Tengah dinamakan rumah betang. Rumah
itu panjang bawah kolongnya digunakan untuk bertenun dan menumbuk
padi dan dihuni oleh ±20 kepala keluarga. Rumah terdiri atas 6 kamar,
antara lain untuk menyimpan alat-alat perang, kamar untuk pendidikan
gadis, tempat sesajian, tempat upacara adat dan agama, tempat penginapan
34

dan ruang tamu. Pada kiri kamam ujung atap dihiasi tombak sebagai
penolak mara bahaya.
3. PAKAIAN ADAT
Pakaian adat pria Kalimantan Tengah Berupa tutup kepala
berhiaskan bulu-bulu enggang, rompi dan kain-kain yang menutup bagian
bawah badan sebatas lutu. Sebuah tameng kayu dengan hiasan yang khas
bersama mandaunya berada di tangan. Perhiasan yang dipakai berupa
kalung-kalung manikdan ikat pinggang. Wanitanya memaki baju rompi
dan kain (rok pendek) tutup kepala berhiasakan bulu-bulu enggang, kalung
manic, ikat pinggang, danbeberapa kalung tangan.
J. SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi bagi orang Dayak di Kalimantan Tengah terdiri atas
empat macam, yaitu berladang, berburu, mencari hasil hutan dan ikan,
menganyam.
Dalam berladang mereka mengembangkan suatu sistem kerja sam
dengan cara membentuk kelompok gotong-royong yang biasanya berdasarkan
hubungan tetanggaan atau persahabatan. Masing-masing kelompok terdiri atas
12-15 orang yang secara bergiliran membuka hutan bagi-bagi ladang masing-
masing anggota. Apabila kekurangan tenaga kerja laki-laki maka kaum wanita
dapat menggantikan pekerjaan kasar itu, misalnya membuka hutan,
membersihkan semak-semak, dan menebang pohon-pohon. Siklus pengerjaan
ladang di Kalimantan sebagai berikut :
1. Pada bulan Mei, Juni atau Julio rang menebang pho-pohon di hutan,
setelah penebangan batang kayu, cabang, ranting, serta daun dibiarkan
mengering selama 2 bualan.
2. Bulan Agustus atau September seluruh batang, cabang, ranting, dan daun
tadi harus dibakar dan dan bekas pembakaran dibiarkan sebagai pupuk.
35

3. Waktu menanam dilakukan pada bulan Oktober.
Pada bulan Februari dan Maret, tibalah musim panen, sedangkan untuk
membuka ladang kembali, orang Dayak melihat tanda-tanda alam seperti
bintang dan sebagainya serta memperhatikan alamat-alamat yang diberikan
oleh burung-burung atau binatang-binatang liar tertentu. Jika tanda-tanda ini
tidak dihiraukan maka bencana kelaparan akibat gagalnya panen akan
menimpa desa.Alat yang sering digunakan untuk menganyam adalah kulit
rotan yang berupa tikar. Pakaian asli Dayak adalah Cawat yang terbuat dari
kulit kayu.
K. MATA PENCAHARIAN
Mata pencaharian orang dayak selalu berhubungan dengan hutan. Jika
mereka berburu mereka pergi ke hutan, kalau mereka berladang mereka
terlebih dahulu menebang pohon-pohon besar dan kecil di hutan, jika mereka
mengusahakan tanaman perkebunan, mereka cenderung memilih tanaman
yang menyerupai tanaman hutan seperti karet, otan, jati, tengkawang dan
sejenisnya. Kecenderungan seperti itu bukannya suatu kebetulan belaka, tetapi
mempunyai refleksi dari hubungan akrab yang telah berlangsung selama
berabad-abad dengan hutan dan segala isinya. Pilihan tersebut merupakan
“adaptive strategies” yang telah diuji oleh waktu dan pengalaman. Michael A.
Jochim (1981) menakan “strategy of survival” yang mempengaruhi perilaku
kultur dari orang-orang Dayak.
Mata pencaharian orang Dayak yang berotientasi kepada hutan
ternyata berpengaruh pula kepada kultur material orang Dayak. Rumah
panjang yang masih asli dibuat seluruhnya dari kayu. Tiang, lantai, dinding,
atap bahkan pengikat semuanya diambil dari huutan. Alat angkut berupa
sampan-sampan kecil biasanya dibuat dengan teknologi sederhana, yaitu
36

dengan mengeruk batang pohon. Peralatan kerja dan senjata seperti kapak,
beliung, parang, bakul, tikar, mandau, tabalang (perisai) dan sumpit semuanya
dibuat dari bahan-bahan dari hutan.
Kebudayaan non-material orang dayak juga banyak sekali hubungannya
dengna hutan. Cerita rakyat yang hidup dikalangan etnik dayak bertutur
tentang kehidupan di hitan atau di sekitar hutan, bahkan pohon-pohon besar
atau spesies kayu tertentu dipandang sebagai pelambang kekuatan atau mistik.
Seni tari dan nanyi banyak yang behubungan dengan burung-burung dan
makhluk-makhluk kasar dan halus yang berdiam di hutan.
37

BAB IV
PENINGKATAN PAD
A. Potensi Wisata
Sebagai pulau terbesar di Indonesia, Kalimantan memiliki 2 potensi
ekonomi utama yang terdiri dari Sektor Perkebunan dan Sektor Wisata.
Hingga saat ini, perekonomian Kalimantan ditopang oleh sektor perkebunan,
khususnya perkebunan Kelapa Sawit. Namun, menilik potensi alam yang
dimiliki, Kalimantan merupakan kawasan wisata yang bernilai ekonomis
diantaranya sebagai berikut :
1. Wisata hutan atau cagar alam dan Ujung Pandaran yang terletak di
Kotawaringin Timur
2. Bukit Sapat Hawung yang terletak di Barito Utara
3. Merang dan Tangkiling yang terletak di kota Palangkaraya
4. Suaka alam (darat dan laut) dan pantai yang terletak di Kotawaringin Barat
5. Air terjun Malau Besar dan Pauras yang terletak di Barito Utara
Selain kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki, Kalimantan juga
memiliki keunikan kebudayaan yang khas yang menjadi daya tarik wisatawan.
Dengan pemanfaatan dan pengelolaan secara baik, ramah lingkungan, terpadu
dan konsisten maka potensi ekonomi Kalimantan melalui sektor wisata dapat
meningkatkan PAD Kalimantan Tengah dan bahkan dapat menyejahterakan
masyarakat sekitar, berkenaan dengan penyerapan tenaga kerja untuk
mengakomodasi perusahaan di bidang wisata, serta adanya segala bentuk
bidang usaha yang dapat timbul dengan adanya potensi wisata yang ada di
Kalimantan Tengah.
B. Pembangunan Wisata
Dengan adanya potensi alam yang tersedia, dapat dibangun sebuah
perusahaan jasa maupun suatu bentuk usaha kreatif yang dapat berupa resort,
38

hotel, wisata kampung, tour & travel, restoran dan beragam jenis usaha kreatif
lainnya yang memiliki potensi ekonomis. Dari beberapa usaha kreatif tersebut,
penulis menilai bahwa usaha kreatif yang menarik adalah wisata kampung.
Penulis menilai bahwa wisata kampung, selain berpotensi mendongkrak PAD
dari sektor wisata juga dapat berperan sebagai sarana edukasi dan pelestari
budaya daerah. Pasalnya, di dalam wisata kampung, baik buatan maupun
tidak, terdapat suatu bentuk kebudayaan yang melekat sebagai identitas
kampung tersebut. Sesuai dengan pembahasan dalam makalah yang
bertemakan suku Dayak ini, penulis merencanakan suatu bentuk usaha Wisata
Kampung yang dikemas dalam kultur dan cita rasa Dayak dengan kualitas
Resort Internasional namun menyediakan fasilitas dengan harga yang
terjangkau.
Wisata Kampung yang akan dibangun, berlokasi di tepi PantaiSungai
Bakau yang terletak di Desa Sungai Bakau, Kabupaten Serunyan dengan jarak
kurang lebih 1 Km arah Timur dari pusat kota Serunyan, Kalimantan Tengah
dengan bernama “Dayak Land”. Dengan mengangkat tema Budaya Dayak,
seluruh properti, design bangunan Wisata Kampung Dayak Land dibuat
semirip mungkin dengan properti dan design khas Dayak, selain itu
lingkungan Kampung Wisata di-design sedemikian rupa layaknya kampung
Dayak yang sesungguhnya dengan lokasi Resort di tepi pantai Sungai Bakau.
Di tempat penjualan tiket disediakan beberapa tour guide bagi pengunjung
yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Dayak Land maupun suku
dayak. Selain itu ketika pengunjung berada di Dayak Land pengunjung harus
menggunakan pakaian khusus asli dayak yang akan disewakan di hotel. Di
Dayak Land terdapat 7 bangunan dengan Rumah Panjang sebagai bangunan
hotel seluas 16 x 42 m2 dengan ketinggian 8,5 m. Bagunan rumah panjang
terdiri dari 3 lantai, memiliki 40 kamar resort, 2 toilet umum, 2 ruang makan
dan 2 aula. Selain itu, interior bangunan rumah panjang dibuat sama dengan
rumah panjang yang sesungguhnya. Artinya, sekat kamar, langit-langit serta
perabotan yang ada akan terbuat dari kayu dan bahan-bahan alami lainnya
yang digunakkan dalam pembuatan rumah panjang. Didepan resort ini
39

disediakan tempat parkir dan halaman untuk pengunjung. Bangunan kedua
adalah pondok kesenian yang terdapat berbagai macam pertunjukan dan
hiburan berupa tarian dan berbagai wujud kebudayaan dayak yang ada. Yang
ketiga adalahpondok edukasi. Di pondok edukasi pengunjung dapat
menemukan penjelasan dan sekaligus dapat mempelajari berbagai kebudayaan
dayak. Yang keempat adalah Pondok industri kreatif yang berisi beberapa
stand didalamnya untuk disewakan kepada pengusaha kecil yang bergerak di
bidang kerajinan, di pondok kesenian pengunjung dapat mempelajari proses
pembuatan kerajinan khas dayak. Pondok industri kreatif sekaligus merupakan
pusat perbelanjaan yang terdapat berbagai macam produk dan cinderamata
khas kalimantan dan dayak. Kelima, Pondok Kuliner, dimana pengunjung
dapat merasakan kenikmatan berbagai kuliner asli dayak. Selain itu terdapat
kolam renang di tepi pantai dengan 3 kedalaman yang dimaksudkan agar
pengunjung semua umur dapat menikmati kolam renang. Yang terakhir adalah
Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
Untuk menu makan yang disajikan¸ dayak land mnyediakan 3 jenis
makanan yaitu makanan asli dayak, jawa dan internasional. Dengan demikian,
setiap pengunjung dapatmenikmati makanan sesuai selera masing-masing
sebagaimana terdapat dalam lampiran.
Sebagaimana tindak lanjut fenomena global warming, dayak land
menggunakan pohon-pohon asli dayak untuk peneduh. Supaya pengunjung
dapat mengetahui pohon tersebut, diberikan plat nama asli pohon dan nama
latinnya. Disetiap sudut jalan diberi penanda arah serta tempat sampah organik
dan anorganik.Sesuai dengan kebijakan perusahaan, privasi pengunjung baik
berupa aktivitas di tempat umum maupun di tempat tertutup sangat dihormati,
namun tetap dengan pengawasan manajemen hotel pada tempat-tempat umum
dengan cara pemasangan kamera CCTV untuk menghindari adanya tindak
asusila maupun tindakan yang merugikan pengunjung lain, staff hotel maupun
keamanan hotel. Dengan pemasangan CCTV keamanan hotel dapat lebih
terkendali karena seluruh kegiatan yang ada di tempat umum dapat terpantau
oleh pengawas, selain itu adanya CCTV dapat berfungsi sebagai kontrol etika
40

pengunjung, staff maupun pihak lainnya yang berdada di dalam hotel. CCTV
dipasang di beberapa titik di lokasi Dayak Land, yakni :
1. lorong atau koridor
2. aula
3. ruang makan
4. lobby
5. pondok
C. Realisasi Dan Pengelolaan
Sebagai wujud realisasi daripada pembangunan dan pendirian
perusahaan jasa di bidang resort dengan nama “Dayak Land”, diperlukan
sebuah perencanaan yang mencakup faktor internal dan faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi pembangunan “Dayak Land”. Faktor Internal yang
dipertimbangkan dalam perencanaan yakni : Modal, Perizinan, SDA, SDM
dan Sponsor. Sedangkan faktor external yang dipertimbangkan yakni :
pertumbuhan penduduk, persediaan ladang cadangan, pertumbuhan fasilitas,
kemajuan teknologi, kondisi lingkungan serta respon masyarakat.
Berikut adalah rincian Pembangunan “Dayak Land” :
1. Nama Perusahaan : CV.Nusantara Resort&Transportation
2. Jenis perusahaan : Resort, Tour
3. Nama Resort : Dayak Land
4. Lokasi : Kalimantan Tengah
5. Luas Lahan total : 4 ha
6. Jumlah bangunan : 7 bangunan,
terdiri dari : 1 Rumah panjang sebagai hotel
1 Kolam renang
1 Pondok kesenian
1 Pondok edukasi
41

1 Pondok industri kreatif
1 Pondok Kuliner
1 IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
7. Luas bangunan utama : 1488 m2 (24 x 62 m2)
8. Jumlah kamar hotel : 40
9. Total Estimasi Dana yang diperlukan :
a. Pembelian tanah....................................Rp 2.800.000.000
b. Pembangunan Rumah Panjang................Rp 2.000.000.000
c. Pembangunan Fasilitas...........................Rp 480.000.000
d. Pembelian Properti.................................Rp 250.000.000
e. Penyediaan transportasi...........................Rp 450.000.000
f. Pembangunan IPAL................................Rp 20.000.000
Total........................................Rp 6.000.000.000
Terbilang : Enam Miliar Rupiah
10. Estimasi pengenaan Tarif :
a. Kamar hotel terbagi atas 3 kelas atau jenis yang terdiri dari :
1) Dayak Imperial dengan tarif Rp 850.000 per malam
2) Dayak Extraordinary dengan tarif Rp 450.000 per malam
3) Dayak Nature dengan tarif Rp 200.000 per malam
b. Fasilitas kamar hotel sesuai kelas yakni :
1) Dayak Imperial (lantai 2) : 1 tempat tidur ukuran besar, AC, TV,
Kamar mandi dengan shower air panas dan dingin beserta kloset
duduk, balkon kamar, ruang tamu.
2) Dayak Extraordinary (lantai 1 dan 2) : 2 tempat tidur standart, AC,
TV, Kamar mandi dengan shower dan kloset duduk.
3) Dayak Nature (lantai 3) : 2 kamar tidur stadardan AC.
c. Fasilitas hotel yang dapat diakses sesuai dengan paket yang disediakan
yakni :
1) Unforgettable Dayak ( Rp 4.350.000,00)
Fasilitas : - Pesawat PP (Jakarta-Palangkaraya)
42

- Kamar Dayak Imperial
- Kuliner Suku Dayak
- Dayak Art (pelatihan kesenian, pelatihan
pembuatan handycraft)
2) Beautiful Dayak ( Rp 3.000.000,00)
Fasilitas : - Pesawat PP (Jakarta-Palangkaraya)
- Kamar Dayak Extraordinary
- Dayak Art
3) Nature Dayak ( Rp 2.000.000,00)
Fasilitas : - Pesawat PP (Jakarta-Palangkaraya)
- Kamar Dayak Nature
- Dayak Land
- Dayak Art
43

BAB V
PENUTUP
A. Keterkaitan Makalah Dengan Materi Ajar Sosiologi
Makalah Materi Ajar Deskripsi
BAB IIIBAB I (Kelas XI)
A. Struktur Sosial
B. Diferensiasi Sosial
Kehidupan masyarakat Suku
Dayak
BAB IIIBAB V (Kelas XI)
KebudayaanKesukuan
BAB IIIBAB VII (Kelas XI)
Masyarakat multikulturSub-suku Dayak
BAB IIIBAB VI (Kelas XI)
Kelompok Sosial
Sistem kekerabatan Suku
Dayak
BAB IVBAB VI (Kelas XI)
Kelompok Sosial
Anggota perusahaan resort
Dayak land dan sanggar seni
yang bekerjasama dengan
Dayak Land.
BAB IVBAB VI (Kelas XI)
Stratifikasi Sosial
Hierarki atau susunan pegawai
di perusahaan Dayak Land.
BAB IVBAB IV (kelas XI)
Mobilitas Sosial
Perubahan jabatan pegawai
Dayak Land dan masyarakat
sekitar yang telah bekerja di
Dayak Land, namun pada
mulanya tidak bekerja.
BAB IV BAB V (Kelas X)
A. Sosialisasi
Promosi wisata kampung
Dayak Land, berkenaan
dengan manajemen brand,
44

produk dan brand.
BAB IVBAB VII (Kelas X)
B. Pengendalian Sosial
Penjagaan keaamanan di
Dayak Land dengan security
dan pengawasan melalui
CCTV
B. Saran
Untuk adik tingkat selanjutnya diharap dapat lebih menyempurnakan
makalah ini. Beberapa hal yang perlu ditambahkan adalah sebagai berikut :
1. Agar resort lebih terlihat bersih, sebaiknya setiap beberapa meter diberi 2
tempat sampah yaitu sampah organik dan anorganik agar setiap
pengunjung tidak membuang sampah sembarangan dan memudahkan
dalam mengolah limbah.
2. Dalam membangun suatu kawasan wisata hendaknya kita juga disertai
dengan pelestarikan hewan khas daerah tersebut, selain melestarikan juga
dapat memperkenalkan kepada pengunjung. Di resort tersebut bisa
dibangun tempat penangkaran orang utan ( hewan langka asli Kalimantan)
yang letaknya tidak jauh dari resort.
3. Selain hewan langka juga perlu dibangun penangkaran tumbuhan langka
yang letaknya juga tidak jauh dari resort.
4. Suatu tempat kadangkala rawan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, lebih
baik resort yang dibangun dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan
alarm kebakaran di setiap tingkat lantai.
C. Kesimpulan
Diperlukan banyak upaya dalam rangka meningkatkan PAD
Kalimantan Tengah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah
satunya dengan pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki Kalimantan Tengah
dengan medirikan suatu bentuk bidang usaha kreatif yang berkenaan dengan
45

pengolahan dan pemanfaatan potensi wisata Kalimantan Tengah. Namun
dalam realisasinya diperlukan dukungan dari pemerintah yang dapat berupa
penyediaan infrastruktur dan sarana transportasi yang baik (bagi Kalimantan
Tengah secara universal) maupun modal (bagi pengusaha). Untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan ketersediaan
lapangan kerja, Badan usaha tersebut diharuskan mampu menyerap tenaga
kerja yang tersedia di masyarakat sekitar serta bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, operasional segala badan usaha yang bergerak di sektor wisata
harus mengolah potensi wisata Kalimantan Tengah secara ramah lingkungan,
terpadu dan konsisten.
DAFTAR PUSTAKA
46

Lestari, Puji. 2009. Antropologi Untuk SMA/MA Kelas XII Program Bahasa.
Jakarta : CV HaKa MJ
Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2012. Sosiologi Untuk SMA dan Ma Kelas XI.
Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
Wrahatnala, Bondet. 2009. Sosiologi Jilid 1 Untuk SMA Dan Ma Kelas X. Jakarta
: PT Sekawan Cipta Karya
Informasi Terbaru 2014. 2014. Daftar Upah Minimum Propinsi UMP/UMR 2014.
http://www.informasiterbaru.web.id/2013/11/daftar-upah-minimum-propinsi-
umpumr.html. Diakses : 03 Mei 2014
KP3EI. 2012. Kalimantan. http://kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/114/117.
Diakses : 16 April 2014
47