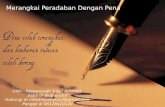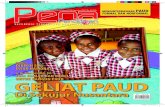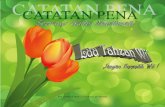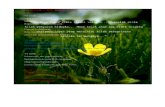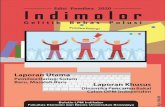pena
Click here to load reader
-
Upload
faizin-nurul -
Category
Documents
-
view
118 -
download
2
Transcript of pena

MODEL ASESMEN PEMBELAJARAN
AKHLAK MULIA Oleh: Dr. Zurqoni, M.Ag
1)
Pendahuluan
Akhlak mulia menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam posisinya
sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai bangsa. Penguatan akhlak mulia
dinilai strategis untuk mengatasi problem moral ditengah kompleksitas kehidupan
bermasyarakat. Selain itu akhlak mulia dapat menjadi barometer keshalehan seseorang di
hadapan Ilahi dan sesama, karenanya seseorang yang berakhlak mulia akan mendapatkan
sebutan dari masyarakat sebagai orang shaleh.
Pembinaan akhlak mulia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia diperkuat oleh berbagai regulasi kependidikan berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan menteri, dan aturan lainnya. Dalam konteks ini, setiap institusi
pendidikan harus mampu melakukan pembinaan terhadap akhlak peserta didiknya.
Pembinaan akhlak mulia melalui institusi pendidikan memiliki esensi bagi terwujudnya
kepribadian peserta didik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Pembinaan akhlak mulia yang dimaksud, yakni pembentukan karakter dan perilaku terpuji
peserta didik yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari syara’.
Pelaksanaan pendidikan akhlak pada institusi pendidikan Islam tidak terlepas dari
kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya. Sistem penilaian yang baik menurut Djemari
Mardapi (2005:11) akan mendorong guru dalam menentukan strategi mengajar yang baik dan
1 Makalah disampaikan dalam Studium General STAIN Samarinda, Samarinda, Maret 2011.
ABSTRAK
Pelaksanaan pendidikan akhlak mulia di sekolah-sekolah
tidak terlepas dari kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya. Penilaian akhlak mulia peserta didik sebagai hasil pembelajaran di sekolah masih bersifat parsial dan konvensional. Penilaian akhlak mulia lebih mengedepankan assessment of learning dari pada assessment for learning. Penilaian terjadi bias karena dilakukan secara parsial, subyektif, dan bersifat perabaan.
Tulisan ini merupakan pengembangan model asesmen akhlak mulia peserta didik, yang di dalamnya terdiri dari dimensi-dimensi willingness, conscience, value, attitude, dan moral behavior. Model asesmen ini menggunakan pendekatan self- dan peer-assessment secara terpadu dengan melibatkan peserta didik secara inter dan intra individu. Struktur internal model asesmen pembelajaran akhlak mulia yang terdiri yang dari dimensi-dimensi willingness, conscience, value, attitude, dan moral behavior melalui pendekatan self- dan peer-assessment ini dinyatakan tepat digunakan untuk menilai akhlak mulia peserta didik.

memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Penilaian menjadi aspek penting bagi upaya
peningkatan kualitas pendidikan, karena melalui kegiatan penilaian akan diperoleh informasi
mengenai pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa untuk dijadikan acuan pemberian
feed back bagi keduanya (Black & Wiliam, 1998: 139-148).
Penilaian akhlak mulia sebagai hasil dari pembelajaran dalam penerapannya dapat
memanfaatkan keterlibatan siswa secara inter dan intra individu siswa. Keterlibatan siswa
dalam penilaian akan mendorong partisipasi aktif yang bersangkutan untuk merealisasikan
ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus membuatnya sadar posisi dalam konteks
kompetensi yang harus dicapai.
Realita penilaian akhlak mulia hasil dari pembelajaran pada berbagai institusi
pendidikan selama ini masih menerapkan penilaian yang bersifat parsial dan konvensional.
Penilaian akhlak mulia siswa cenderung mengedepankan hasil akhir pembelajaran
(assessment of learning) dibanding penilaian secara berkelanjutan (assessment for learning).
Selain itu praktek penilaian akhlak siswa bersifat tunggal, bersifat ‘perabaan’, dimensi-
dimensi dan instrumen penilaian tidak jelas sehingga dapat menimbulkan bias penilaian.
Kondisi demikian memunculkan pemikiran mengenai pentingnya dikembangkan
model penilaian akhlak mulia dengan menetapkan dimensi-dimensi yang jelas, instrumen
yang tepat, dilakukan secara berkala dan memanfaatkan keterlibatan intra dan inter individu
siswa. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian disertasi, yang salah satunya
menghasilkan model pengukuran akhlak mulia. Model pengukuran (measurement model)
akhlak mulia merupakan struktur internal terdiri dari dimensi-dimensi akhlak yang baik
digunakan untuk menilai akhlak siswa. Model asesmen ini menggunakan pendekatan self-
dan peer-assessment secara terpadu dengan melibatkan siswa dalam melakukan penilaian
akhlak.
Konsepsi Akhlak Mulia
Akhlak merupakan kondisi internal psikologis yang mendorong seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan (Miskawaih, 1966: 49; Anis, 1972: 202; Al-Ghazali, t.th.: 56).
Perbuatan tersebut dilakukan secara reflektif tanpa adanya rekayasa dan didasarkan pada
kesadaran dan kehendak orang yang melakukannya (Amin, 1974:63). Akhlak mulia
(akhlaqul karimah) menurut Saefudin (2002: 70), yakni jenis-jenis perilaku yang memiliki
nilai kebajikan dan menjadi ukuran untuk menentukan suatu tindakan dinyatakan benar atau
salah berdasarkan norma Islam. Norma-norma Islam diwujudkan dalam bentuk perintah-
larangan, dorongan-cegahan, dan pujian-kecaman (Zulkabir, 1993: 98). Tindakan yang baik
dan benar adalah segala hal yang diperintahkan, didorongkan, dipuji dan diharapkan oleh
Islam untuk dilakukan. Sebaliknya tindakan yang dikecam dan dilarang dikategorikan
sebagai tindakan tercela.
Asmaran (2002:207) menegaskan, bahwa akhlak mulia itu sebagai sifat-sifat dan
perilaku sesuai dengan norma atau ajaran Islam secara lahiriyah dan bathiniyah. Akhlak
mulia secara lahiriyah merujuk pada perilaku terpuji yang tampak, sedangkan akhlak mulia
secara bathiniyah merujuk pada sifat-sifat terpuji dalam jiwa. Dengan demikian, akhlak
mulia pada hakekatnya adalah kondisi psikologis (kejiwaan) dan perilaku terpuji berdasarkan
norma-norma Islam. Perilaku tersebut sebagai refleksi jiwa secara wajar tanpa adanya
rekayasa. Akhlak mulia terdiri atas aspek-aspek bathiniyah dan lahiriyah.

Akhlak setiap individu merupakan manifestasi dari kondisi bathinnya. Akhlak mulia
sebagai manifestasi kondisi bathin terpuji, sebaliknya akhlak tercela sebagai manifestasi dari
kondisi bathin yang tidak terpuji (Asmaran, 2002:208). Dengan demikian akhlak mulia
seseorang dalam wujud perbuatan nyata (lahiriyah) memiliki keterkaitan erat dengan kondisi
bathinnya. Penetapan akhlak mulia tidak hanya dilihat dari eksistensinya (perbuatan
lahiriyah), tetapi juga dilihat dari esensinya (kondisi bathin) yang mendorong dan
menentukan perbuatan lahiriyah seseorang. Oleh karena itu dalam menilai akhlak
seseorang, Al-Ghazali mengingatkan agar dalam penilaian tersebut tidak semata-mata
didasarkan pada perbuatan lahiriyahnya, tetapi penilaian juga didasarkan pada sifat/kondisi
yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir macam-macam perbuatan.
Aspek-Aspek Akhlak Mulia
Aspek-aspek akhlak menurut Abdullah (2007: 200-232) meliputi akhlak kepada
Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak pada lingkungan. Akhlak kepada Allah
diwujudkan melalui pentauhidan, beribadah, bersyukur, bertaqwa, berdo’a, berdzikir, dan
bertawakkal kepada-Nya. Akhlak kepada sesama dipetakan atas akhlak kepada orang tua,
saudara, tetangga, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian akhlak pada lingkungan
(alam) dilakukan dengan cara memanfaatkan, memelihara dan melestarikannya.
Selanjutnya dinyatakan oleh Darraz (1973: 14), bahwa akhlak di dalam al-Qur’an
dapat dipetakan atas akhlak pribadi, akhlak kekeluargaan, akhlak kemasyarakatan, akhlak
kenegaraan dan akhlak keagamaan. Pemetaan akhlak tersebut masih bersifat global sehingga
Jalaluddin dan Said (1994: 47) membaginya menjadi sembilan kategori utama, yakni: akhlak
terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap Al-Quran, akhlak terhadap diri
sendiri, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap anak, akhlak dalam rumah
tangga, akhlak terhadap sesama manusia dan lingkungan. Pemetaan akhlak berdasarkan
pendapat di atas tampak keduanya menekankan pada realisasi atau penerapan akhlak dalam
kehidupan manusia sebagai pribadi, hamba, umat beragama, anggota keluarga dan
masyarakat.
Akhlak pribadi merujuk pada perlakuan seseorang pada dirinya sendiri secara Islami.
Akhlak sebagai hamba berkaitan dengan hubungan manusia dengan Ilahi. Akhlak umat
beragama diarahkan pelaksanaan ajaran agama dan pola relasi dengan agama lain. Akhlak
sebagai anggota keluarga mencakup hubungan antar pihak-pihak di dalam keluarga,
termasuk ketaatan dan penghormatan anak terhadap orang tuanya. Selanjutnya akhlak dalam
konteks kemasyarakatan mengatur relasi antar sesama di dalam suatu komunitas tertentu.
Berdasarkan uraian di atas jelas eksistensi manusia dalam menjalani kehidupan di
dunia ini memiliki keterkaitan dengan dirinya sebagai hamba sehingga berkewajiban
mengabdi kepada Allah. Selain itu manusia sebagai bagian komunitas masyarakat perlu
menjunjung tinggi tata aturan kehidupan bermasyarakat, kemudian memelihara diri dan
lingkungannya. Dengan demikian akhlak mulia memiliki aspek ketuhanan (hablun minallah)
dan aspek kemanusiaan (hablun minannas).
Terkait dengan aspek ketuhanan, bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah
yang berarti memiliki kecenderungan bertauhid kepada Allah. Manusia dalam hubungannya
dengan Ilahi berposisi sebagai makhluq (yang diciptakan) sedangkan Allah berposisi sebagai
al-Khaliq (pencipta). Manusia sebagai hamba memiliki kewajiban berakhlak mulia kepada

Allah dengan cara mengimani dan menjalankan segala hal yang telah diperintahkan.
Berakhlak mulia kepada Allah secara umum dapat diwujudkan melalui keimanan dan
ketaqwaan serta ibadah secara luas.
Mengenai aspek kemanusiaan, bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk
yang dilengkapi dengan akal sehingga dikategorikan sebagai makhluk paling sempurna
diantara makhluk-makhluk lainnya. Berdasarkan akal tersebut manusia menyatakan
kesanggupannya untuk memikul amanah, dan karena akal itu pula manusia dibebani
kewajiban selain mendapatkan hak-haknya dalam kehidupannya.
Islam mengajarkan bagaimana manusia memenuhi hak-haknya dengan tidak
merugikan hak orang lain. Islam juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban manusia
untuk menghindari pertentangan diantara sesamanya, mengingat dalam suatu hak seseorang
terdapat kewajiban oleh orang lain, demikian halnya dalam suatu kewajiban terdapat hak
yang diterima orang lain sehingga keduanya merupakan hubungan timbal balik.
Selain akhlak terhadap diri sendiri dan sesama, bahwa manusia hidup berdampingan
dalam suatu lingkungan, yakni segala sesuatu yang berada di sekitar tempat tinggal seseorang
baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan berbagai makhluk lainnya. Dengan demikian
lingkungan dapat dibedakan atas lingkungan masyarakat dan lingkungan dalam makna alam.
Lingkungan masyarakat adalah komunitas manusia yang berada di sekelilingnya, bekerja
bersama-sama, saling membutuhkan dan dapat mengorganisasikannya dalam lingkungan
tersebut sebagai suatu kesatuan sosial.
Lingkungan dalam konteks akhlak ini termasuk di dalamnya adalah alam beserta
isinya (QS. 2: 168; QS.28:77; QS. 30:41). Ayat-ayat ini menggambarkan pentingnya
keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam. Allah menyerahkan semua yang ada
dalam alam ini untuk kepentingan hidup manusia (QS. 2:29), manusia diberi kebebasan
untuk menggunakannya dengan mengikuti aturan dalam proses penggunaan alam (QS. 7:56;
28:77). Prinsip-prinsip akhlak mulia berkaitan dengan penggunaan alam telah diatur dalam
Islam, misalnya manusia perintahkan untuk menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan,
tidak membunuh binatang tertentu (yang tidak boleh dibunuh), tidak menebang pohon secara
sembarangan yang menyebabkan terjadinya erosi dan rusaknya lingkungan, tidak boros
menggunakan air, tidak kencing di tempat-tempat yang terdapat komunitas kehidupan
makhluk lain, menjaga kebersihan dan sebagainya (Hamzah Ya’cub, 1985: 171-173).
Akhlak mulia terhadap lingkungan seharusnya melekat pada diri peserta didik.
Perwujudan atas pemeliharaan lingkungan alam ini antara lain dengan menjaga kebersihan,
keasrian dan pelestarian lingkungan.
Dimensi-Dimensi Akhlak Mulia
Kondisi psikologis seseorang terkait dengan pembelajaran masuk dalam domain
afektif. Dimensi-dimensi afektif ini meliputi kehendak, kata hati (Amin, 1976: 61-80),
perasaan, nilai, sikap (Anderson, 1981: 32-35; Gable, 1986: 2; Djemari Mardapi, 2005: 63-
64), dan perilaku akhlak (behavior/moral action) (Derryberry, 2005:71; Peter Ji, 2004:2;
Hendrix, 2004:60; Rudd, 2004:156, dan Lickona,1991:52-62). Berdasarkan uraian di atas, maka
dimensi-dimensi akhlak setidaknya mencakup kehendak (willingness), kata hati (conscience),
nilai (value), sikap (attitude), dan perilaku akhlak (moral behavior).
Kehendak merupakan keinginan yang kuat (niat) untuk melakukan ataupun
menghindari suatu perbuatan. Kehendak menjadi daya penggerak yang dapat menimbulkan
perbuatan. Setiap perilaku manusia lahir dari kehendaknya, dan setiap kehendak lahir dari
keyakinan yang tertanam dalam jiwanya (Skinner, 1976: 11). Kehendak baik bila terefleksi

menjadi perbuatan, maka perbuatan tersebut dikategorikan baik. Perbuatan baik tidak dinilai
hanya dari tampilannya, namun juga dinilai dari kehendaknya (Amin, 1976:61). Penilaian
terhadap baik-buruknya suatu perilaku menurut Asmaran (2002: 36-38) harus menyertakan
aspek kehendak (niat).
Kata hati merujuk pada penciptaan manusia yang fitrah, sehingga memiliki
kecenderungan terhadap hal-hal yang benar, baik dan yang suci. Setiap orang mempunyai
potensi untuk berbuat baik disebabkan adanya fitrah yang tertahan dalam hati nurani. Dia
memiliki kecenderungan ingin berbuat sesuai dengan hukum-hukum akhlak, sehingga segala
perbuatan yang menyimpang dari padanya merupakan penyimpangan dan melawan fitrahnya
(Q.S. 30/30; 7/172). Dia merasa dalam jiwanya terdapat pertentangan, merasa berdosa dan
menyesal ketika melakukan perbuatan tidak terpuji. Kekuatan ini disebut sebagai kata hati
yang mendahului perbuatan, mengiringi dan menyusulnya (Amin, 1976: 80). Kata hati
menurut al-Ahwani (t.t: 102) dapat memantulkan bermacam-macam perilaku dan menilai
baik-buruknya suatu perbuatan. Kata hati dapat membimbing manusia untuk berbuat baik
dan menjauhkannya dari perbuatan buruk.
Selanjutnya, nilai adalah konsepsi keinginan yang seharusnya diinginkan terhadap
sesuatu (Getzels, 1966:98). Konsep nilai ini mengarah pada keyakinan terhadap sesuatu
yang seharusnya dipilih dan dilakukan. Allport (Mulyana, 2004:9) menegaskan, bahwa nilai
itu sebagai keyakinan yang mengarahkan seseorang bertindak atas dasar pilihannya.
Keyakinan tersebut ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah
lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Nilai dalam ilmu behavioral
lebih mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai perilaku. Nilai-nilai tersebut merupakan
petunjuk yang terinternalisasi dalam ekspresi perilaku yang ditampilkan seseorang.
Aktualisasi nilai kedalam akhlak terpancar dari konsepsi dan perseptual seseorang tentang
kehidupan dalam relasinya dengan Ilahi maupun sesama, dan nilai tersebut dapat berupa
aqidah Islamiyah/ keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama (Islam). Aqidah menjadi
sumber kekuatan batin bagi setiap orang, sehingga seseorang yang berpegang teguh padanya
akan mendapatkan ketenteraman bathin, sementara yang meninggalkan akan mengalami
keresahan dalam bathinnya.
Perihal sikap dinyatakan Gagne (1974:64), bahwa sikap itu sebagai keadaan internal
(internal state) yang mempengaruhi pilihan tindakan individu. Sikap terhadap perilaku
tertentu menurut Azwar (2005:12) dipengaruhi oleh keyakinan mengenai perilaku normatif
yang membentuk norma subyektif dalam diri individu. Sikap pribadi seseorang yang
berjiwa sosial-religius berkembang dalam pola hidup yang menghubungkan antara dirinya
dengan Allah SWT. (hablun minallah) dan dengan masyarakatnya (hablun minannas). Sikap
dapat dinyatakan dalam bentuk respons persetujuan atau penolakan terhadap suatu perbuatan.
Perilaku akhlak berdasarkan konsepsi moral dinamakan moral behavior. Perilaku
akhlak sebagai manifestasi dari kehendak, kata hati, nilai dan sikap. Perilaku akhlak
merupakan perbuatan atau tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-
hari. Derryberry (2005:71) menyatakan, bahwa perilaku akhlak merupakan kumpulan sifat-
sifat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Perilaku akhlak mencakup competence dan
habit (Lickona, 1991:52-62). Dimensi perilaku akhlak yang dimaksudkan, yakni
kemampuan seseorang untuk berperilaku terpuji secara nyata dalam kehidupannya. Perilaku
ini merupakan manifestasi dari seperangkat karakteristik afektif termasuk kehendak yang
dimiliki. Selain itu perilaku didasari oleh kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan
sesuatu yang dipikirkan untuk selanjutnya dibiasakan dalam berperilaku. Berdasarkan

dimensi-dimensi akhlak mulia yang perlu untuk dinilai selanjutnya dapat digambarkan
berikut ini.
Dimensi-dimensi akhlak mulia di atas dapat dijelaskan secara operasional sebagai
berikut:
1. willingness, yakni kehendak (niat) seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terpuji,
ataupun menghindari perbuatan tercela. Kehendak menjadi daya penggerak jiwa,
memberi alasan dan dasar setiap individu untuk melakukan perbuatan tertentu. Kehendak
peserta didik dalam melakukan suatu perbuatan (akhlak) dilihat berdasarkan arah dan
intensitasnya.
2. conscience yang berarti kata hati merujuk pada penciptaan manusia yang hanif, yakni
kecenderungan terhadap hal-hal yang benar, baik dan suci. Kecenderungan tersebut
menjadikan kata hati setiap individu merasa senang dapat melakukan perbuatan terpuji,
dan sebaliknya merasa bersalah, berdosa, was-was dan sejenisnya jika melakukan
perbuatan tidak terpuji maupun meninggalkan amalan yang diwajibkan. Dengan
demikian akhlak peserta didik dari dimensi ini dinilai berdasarkan kata hati mereka ketika
melakukan perbuatan terpuji ataupun tercela, dan ketika meninggalkan kewajibannya.
3. value (nilai) merupakan keyakinan seseorang yang mengarahkannya untuk berperilaku
berdasarkan keyakinannya. Nilai menjadi acuan yang terinternalisasi dalam ekspresi
perilaku seseorang. Nilai-nilai dalam kaitannya dengan akhlak mencakup nilai intelektual
(benar-salah) dan etika (baik-buruk). Nilai-nilai intelektual dan etika yang diyakini
peserta didik didasarkan pada ajaran Islam.
4. attitude (sikap) sebagai kondisi yang turut memberi kontribusi terhadap tindakan dan
perilaku. Sikap dalam hal ini merujuk pada respons peserta didik atas perbuatan tertentu
perlu dilakukan ataupun dihindari dalam konteks kewajiban-larangan dan
kemaslahatannya melalui pernyataan setuju-tidak setuju.
5. moral behavior, yakni perilaku akhlak seseorang yang secara nyata ditampilkan dalam
kehidupan sehari-hari. Perilaku akhlak ini teramati dan dapat dinilai oleh diri sendiri
maupun orang lain.
Pendekatan Asesmen Pembelajaran
Asesmen pembelajaran sebagai kegiatan pengumpulan informasi mengenai
proses dan hasil belajar. Praktek asesmen pembelajaran dapat memanfaatkan
keterlibatan inter dan intra individu siswa. Pelibatan inter individu siswa dalam
pelaksanaan asesmen pembelajaran dikenal dengan pendekatan self-assessment,
sedangkan pelibatan intra individu siswa dikenal dengan peer-assessment. Dikaitkan
asesmen akhlak sebagai hasil dari proses pembelajaran PAI, maka self-assessment
WillingnessWillingnessWillingnessWillingness ConscienceConscienceConscienceConscience ValueValueValueValue AttitudeAttitudeAttitudeAttitude Moral BehaviorMoral BehaviorMoral BehaviorMoral Behavior
Akhlak Akhlak Akhlak Akhlak MuliaMuliaMuliaMulia Gb. 1: Dimensi-Dimensi
Akhlak Mulia
D
I
M
E
N
S
I
A
K
H
L
A
K

dapat digunakan untuk menilai keseluruhan dimensi akhlak oleh dan untuk dirinya
sendiri. Selanjutnya peer-assessment digunakan untuk menilai akhlak teman
sejawatnya yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi akhlak yang
dapat dinilai oleh teman sejawat, yakni moral behavior. Kedua pendekatan tersebut
dapat diterapkan secara terpadu.
Penggunaan self-assessment didasarkan pada kondisi internal psikologis dalam
akhlak, sehingga siswa sendiri yang dapat memahami, merefleksi diri dan menilai
kondisi internal psikologis dalam dirinya. Penggunaan peer-assessment didasarkan
pada banyaknya jumlah siswa didalam kelas dibanding jumlah guru PAI yang sangat
kecil kemungkinan guru dapat mengamati perilaku masing-masing siswa secara detail.
Penilaian akhlak antar siswa dalam suatu kelompok diasumsikan dapat memberi
informasi secara memadai tentang akhlak para siswa. Penilaian akhlak oleh teman
sejawat dapat dijadikan pertimbangan dalam mengupayakan pembinaan akhlak mulia
siswa. Penilaian ini dikhususkan pada perilaku akhlaki yang termanifes dalam diri
setiap individu siswa.
Asesmen pembelajaran akhlak di madrasah didasarkan pada materi-materi
akhlak yang dinukil dari rumpun mata pelajaran PAI. Strategi penilaian dapat dilihat
pada Gambar 2.
Willingness
Conscience
Value
Attitude
Moral Behavior
Akhlak
Mulia
Aqidah Akhlak
F i q h
Al-Qur’an Hadis
Self-Assessment
Peer-Assessment
Gb. 2: Strategi Penilaian
Sebagaimana tampak pada gambar di atas, bahwa pendekatan self-assessment
digunakan untuk menilai akhlak dari dimensi willingness, conscience, attitude, dan
moral behavior. Sedangkan pendekatan peer-assessment hanya digunakan untuk
menilai akhlak dari dimensi moral behavior.
Validasi Model Asesmen Akhlak
Penetapan dimensi-dimensi willingness, conscience, value, attitude, dan moral
behavior untuk menilai akhlak mulia peserta didik didasarkan pada hasil penelitian
dan pengembangan (research and development). Prosedur pengembangan secara garis
besar dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tahap pra-pengembangan, pengembangan model
konseptual, dan penerapan model (Plomp, 1982; Cennamo & Kalk, 2005:6).
Proses pengembangan model penilaian ini melibatkan expert judgment yang dikemas
dalam bentuk Teknik Delphi. Selain itu proses pengembangan juga melibatkan para
akademisi dan praktisi melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Uji coba model
ditempuh melalui kegiatan uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba
lapangan (Tessmer, 1993), dengan melibatkan sebanyak 320 siswa.

Validitas isi dilakukan melalui
dilakukan melalui uji data empirik
setiap butir instrumen didasarkan pada
(Nunally, 1981: 346; Fernandes,
Perihal reliabilitas instrumen
minimal 0,7 (Koplan, 1982: 106; Allen & Yen, 1979: 121; N
estimasi reliabilitas composit
(1981: 248) sebagai berikut:
Penghitungan estimasi reliabilitas
formula estimasi inter rater
(2007:106). Formula tersebut, yakni:
inter-rater, penghitungannya menggunakan
Selanjutnya untuk mendapatkan suatu model pengukuran akhlak digunakan t
analisis Confirmatory Factor A
Lisrel. Model pengukuran dinyatakan
besar dari 0,05 (ρ >0,05), Root Mean Square Error of Approximation
Goodness of Fit Index (GFI)
Berdasarkan hasil uji coba lapangan
muatan faktor terendah 0,39, indeks reliabilitas
inter rater mencapai 0,76.
melebihi batas minimal tersebut dapat dinyatakan, bahwa butir
akhlak mulia dalam penelitian ini memenuhi syarat kehandalan.
Struktur internal model asesmen pembelajaran akhlak mulia yang terdiri dari dimensi
willingness, conscience, attitude, value,menilai akhlak mulia peserta
Analysis (CFA) seperti tampak pada gamber berikut:
rνν = 1
aliditas isi dilakukan melalui penilaian para ahli, sedangkan validitas konstruk
data empirik dengan menggunakan Analisis Faktor. Ukuran valid dari
didasarkan pada nilai factor loading sekurang
(Nunally, 1981: 346; Fernandes, 1984:28).
instrumen penilaian didasarkan pada koefisien Cronbach’s
minimal 0,7 (Koplan, 1982: 106; Allen & Yen, 1979: 121; Nunnally, 1978:230), sedangkan
posite linier menggunakan formula yang direkomendasikan Nunally
enghitungan estimasi reliabilitas penilaian akhlak oleh teman sejawat
reliability yang diadaptasi dari Ebel (1951; Saifuddin Azwar
(2007:106). Formula tersebut, yakni: rxx’ = (Ss2 – Se
2)/Ss2. Uji validitas dan reliabilitas
nya menggunakan software SPSS, dan Microsof Office Excel.
Selanjutnya untuk mendapatkan suatu model pengukuran akhlak digunakan t
tor Analysis (CFA), yang penghitungannya menggunakan software
dinyatakan baik (fit model), jika memenuhi kriteria
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
> 0,90.
uji coba lapangan (validasi model) penilaian akhlak
, indeks reliabilitas composite linier 0,94, dan indeks reliabilitas
. Dengan merujuk pada indeks validitas dan reliabilitas yang
melebihi batas minimal tersebut dapat dinyatakan, bahwa butir-butir instrumen penilaian
ak mulia dalam penelitian ini memenuhi syarat kehandalan.
Struktur internal model asesmen pembelajaran akhlak mulia yang terdiri dari dimensi
willingness, conscience, attitude, value, dan moral behavior dinyatakan baik untuk
menilai akhlak mulia peserta didik. Hal ini didasarkan pada hasil Confirmatory Factor
seperti tampak pada gamber berikut:
∑σi2 - ∑rii σi2
= 1 - -----------------
σ2ν
validitas konstruk
Ukuran valid dari
sekurang-kurangnya 0,3
Cronbach’s Alpha
unnally, 1978:230), sedangkan
yang direkomendasikan Nunally
penilaian akhlak oleh teman sejawat digunakan
yang diadaptasi dari Ebel (1951; Saifuddin Azwar
Uji validitas dan reliabilitas
Microsof Office Excel. Selanjutnya untuk mendapatkan suatu model pengukuran akhlak digunakan teknik
menggunakan software
kriteria ρ- value lebih
(RMSEA) < 0,08, dan
(validasi model) penilaian akhlak diperoleh
, dan indeks reliabilitas
indeks validitas dan reliabilitas yang
butir instrumen penilaian
Struktur internal model asesmen pembelajaran akhlak mulia yang terdiri dari dimensi
dinyatakan baik untuk
Confirmatory Factor

Gb. 3: Model Pengukuran Akhlak
Penentuan sebagai model pengukuran yang baik (goodness of fit) untuk menilai
akhlak mulia peserta didik didasarkan pada nilai Lambda terendah 0,39 (λ>0,30), ρ-value=
0,080 (p>0,05), RMSEA =0,074 (RMSEA < 0,08), dan GFI = 0,98 (GFI > 0,90). Dimensi
willingness adalah niat/kehendak yang mendasari peserta didik untuk melakukan perbuatan
tertentu, conscience merupakan kata hati yang menyertai setiap perbuatan, value adalah
nilai-nilai etika dan religius yang diyakini peserta didik dalam kaitannya dengan
pembentukan akhlak, attitude sebagai sikap terhadap suatu perbuatan akhlak, dan moral
behavior merupakan perilaku nyata yang ditampakkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Dimensi-dimensi tersebut menjadi satu kesatuan model penilaian akhlak mulia peserta didik
sebagai hasil dari proses pembelajaran.
Penutup
Struktur internal model asesmen pembelajaran yang baik digunakan untuk menilai
akhlak mulia siswa terdiri dari dimensi willingness, conscience, value, attitude dan moral
behavior. Dimensi-dimensi tersebut terkandung di dalamnya aspek akhlak kepada Allah,
akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri dan akhlak pada lingkungan.
Implikasi dikembangkannya model asesmen pembelajaran akhlak mulia ini dapat
dijadikan acuan sekaligus mendorong kreativitas guru-guru PAI dalam melakukan penilaian
akhlak siswa. Model asesmen ini bermanfaat bagi guru dan pihak sekolah dalam menentukan
kriteria kualitas akhlak siswa. Penilaian akhlak mulia peserta didik tidak bersifat tunggal
semata-mata dilakukan oleh guru, namun penilaian akhlak tersebut menuntut dilibatkannya
siswa secara inter dan intra individu.

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Amin. (1974). Kitab al-akhlaq. Beirut-Lubnan: Dar al-Kitab al-‘Araby.
Al-Ghazali. (1970). Khuluq al-muslim. Kuwait: Darul Bayan.
Allen, M.J. & Yen, W.M. (1979). Introduction to measurement theory. Colifornia: Broks/Cole
Publishing Company.
Anderson, L.W. (1981). Assessing affective characteristic in the schools. Boston: Allyn and
Bacon
Asmaran As. (2002). Pengantar studi akhlak. Jakarta: Rajawali
Azwar, S. (2005). Sikap manusia: Teori dan pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-------- (2007). Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Black, P. dan Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom
assessment. Phi Delta Kappa, 80, 2, 139-148.
Cennamo, K. & Kalk, D. (2005). Real world instructional design. Canada: Thomson Learning,
Inc.
Darraz, M.A. (1973). Dustur al-akhlaq fi al-Qur’an. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Derryberry, W.P. & Thoma, S. J. (2005). Moral judgment, self understanding, and moral action:
the role of multiple constructs. ProQuest education journals, 52, 1, 67-92.
Djemari Mardapi. (2005). Pengembangan instrumen penelitian pendidikan. Yogyakarta:
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.
Fernandes, H.J.X. (1984). Testing and measurement. Jakarta: National Education Planning,
Evaluating and Curriculum Development.
Gegne, E.D. (1981). The cognitive psychology of school learning. Boston: Little Brown.
Getzels, J.W. (1966). The problem of interest: A reconsideration. Dalam H.A. Robinson (ed.).
Reading: Seventy-five years of progress. Supplementary Education Monographs, 97-106
Ibrahim Anis. (1972). Al-Mu’jam al-wasit. Mesir: Darul Ma’arif.
Jőreskog, K.G. & Sőrbom, D. (1996). Lisrel 8: User’s reference guide. Chicago: Scientific
Software International.

Koplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (1982). Psychological testing: Principles, aplication and issue.
Monterey: Broks/Cole Publishing Company.
Lickona, T. (1991). Education for character: How our schools can teach respect and
responsibility. New York: Bantam Books.
Lickona, T. (Ed.). Moral development and behavior: Theory, research, and social issue. New
York: Holt. Rinehart and Winston.
Mulyana, R. (2004). Mengartikulasikan pendidikan nilai. Bandung: Alfabeta
Nunally, J.C. (1970). Introduction to psychological measurement. New York: McGraw-Hill Inc.
-----------. (1981). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill Inc.
Plomp,T. (1982). Design methodology and developmental research in education and training,
Enschende-Netherland: Faculty of Educational Science and Technology (FEST),
University of Twente.
Rudd, A. & Stoll, S. (2004). Measuring students' character in secondary education: The
development of the principled thinking inventory. Journal of research in character
education, 2, 109-120.
Skinner, B.F. (1976). About behaviorism. New York: Vintage Books.
Solimun (2002). Structural equation modelling (SEM), lisrel dan amos. Malang: FMIPA
UNIBRAW.
Tessmer, M. (1993). Planning and conducting formative evaluation. London: Kogan Page Ltd.
Diambil pada tanggal 16 April 2007, dari http:// www. geocities. com/
zulkardi/books.html.

CURRICULUM VITAE
Zurqoni, lahir di Lamongan 15 Maret 1971. Pendidikan MI-MA di Lamongan
(1990), S1 Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda (1991-1995), dan S2 UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1999-2001). Pendidikan S3 (2005-2009) pada PPs. UNY, Program
Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP).
Pengalaman pekerjaan, antara lain menjadi guru honorer SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, Dosen STAIN Samarinda (1995-sekarang), Sekretaris Jurusan Tarbiyah (1997-
1998), Ketua Jurusan Tarbiyah (2001-2005), dan Pembantu Ketua II STAIN Samarinda
(2009-sekarang).
Karya tulis yang dimuat dalam berbagai Jurnal Ilmiah, yakni: Paradigma Pendidikan
di Indonesia Abad 21 (2000); Islam dan Modernisasi: Menengok Akar Sejarah Pembaharuan
Islam (2001); Revolusi Abbasiyah: Latar Historis dan Implikasi bagi Pengembangan Ilmu
Pengetahuan serta Pembentukan Watak Kosmopolitanism Masyarakat Muslim (2003);
Aktualitas Filsafat Ilmu bagi Upaya Peningkatan Kualitas pendidikan Tinggi (2004); Speech
Disorder sebagai penyebab Kesulitan Belajar (2004); Urgensi Civic Education bagi
Perkembangan Demokratisasi di Indonesia (2004); Keberagamaan Masyarakat Modern:
Memotret Fenomena Gerakan Tasawuf dan “Sempalan” di Indonesia (2005); Analisis
Kinerja Guru Madrasah (2007); Mutu Pembelajaran Dosen PTAI (2008); Revitalisasi
Penerapan Active Learning pada PTAI (2008), Insan Saleh dalam Perspektif Psikologi Islam
dan Modern (2009), Kontekstualisasi Pembelajaran PAI di Madrasah (2009), dan
Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam (2009).
Beberapa karya dalam bentuk buku yang sedang dalam proses penerbitan, yakni:
“Strategi Penilaian Akhlak”, “Menakar Peran Pendidikan Tinggi Agama”, “Antologi
Keislaman”, dan “Pengantar Statistik Pendidikan”.
Beberapa karya lainnya dalam bentuk penelitian, dan makalah-makalah yang disampaikan
dalam berbagai forum seminar, workshop dan lokakarya pendidikan.