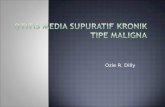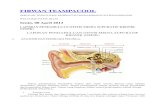OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK MALIGNA.doc
-
Upload
kurniakhoirunnisa -
Category
Documents
-
view
34 -
download
0
Transcript of OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK MALIGNA.doc
BAB I
PENDAHULUAN1.1. Pendahuluan Otitis media supuratif kronis (OMSK) adalah infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi membrane timpani dan secret yang keluar dari telinga tengah terus menerus atau yang hilang timbul. Secret mungkin encer atau kental, bening atau berupa nanah. OMSK dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:1. OMSK tipe aman (benigna) Proses perdangan pada OMSK tipe aman terbatas pada mukosa aja, dan biasanya tidak mengenai tulang, perforasi terletak di sentral. Umumnya OMSK tipe aman jarang menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Pada OMSK tipe aman tidak terdapat kolesteatoma.
2. OMSK tipe bahaya (maligna)
OMSK tipe maligna ialah OMSK yang di sertai dengan kolesteatoma. OMSK ini dikenal juga dengan OMSK tipe bahaya atau tipe tulang, perforasi pada tipe bahaya letak nya marginal atau di atik, kadang kadang terdapat juga kolesteatoma pada OMSK dengan perforasi subtotal. Sebagian besar komplikasi yang berbahaya atau fatal timbul pada OMSK tipe bahaya. Menurut survey yang dilakukan pada 7 propinsi di Indonesia pada tahun 1996 di temukan insiden otitis media supuratif kronis(OMSK) sebesar 3% dari penduduk Indonesia. Di Indonesia menurut survey kesehatan indra penglihatan dan pendengaran, depkes tahun 1993-1996 prevalensi OMSk adalah 3,1%-5,20% populasi. Usia terbanyak infeksi telinga tengah adalah usia 7-18 tahun, dan penyakit terbanyak OMSK.
BAB II
OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK MALIGNA2.1. Anatomi TelingaSecara anatomi telinga dibagi menjadi tiga bagian yaitu telinga luar, tengah dan dalam. Telinga luar adalah bagian telinga yang terdapat sebelah luar membran timpani. Bagian ini terdiri dari daun telinga dan saluran yang menuju membran timpani, yaitu liang telinga luar.11Telinga tengah adalah rongga berisi udara di dalam tulang temporalis yang terbuka melalui tuba eustachius ke nasofaring dan melalui nasofaring ke luar.12Telinga tengah terdiri dari:
1. Membran timpani2. Kavum timpani3. Prosesus mastoideus4. Tuba eustachiusTelinga dalam (labirin, rumah siput) terdiri dari 2 bagian, satu di dalam lainnya. Labirin tulang adalah serangkaian di dalam bagian petrosa tulang temporalis.12
Gambar 2.1. Anatomi Telinga13Telinga Tengah2.1.1. Membran Timpani
Membran timpani dibentuk dari dinding lateral kavum timpani yang memisahkan liang telinga luar dari kavum timpani. Membran ini memiliki panjang vertikal rata-rata 9-10 mm dan diameter antero-posterior kira-kira 8-9 mm dengan ketebalannya rata-rata 0,1 mm.15,16
Gambar 2.2. Membran Timpani17Membran timpani secara anatomis membran timpani dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Pars tensa merupakan bagian terbesar dari membran timpani suatu permukaan yang tegang dan bergetar dengan sekelilingnya yang menebal dan melekat di anulus timpanikus pada sulkus timpanikus pada tulang dari tulang temporal.
2. Pars flaksida atau membran Shrapnell, letaknya dibagian atas muka dan lebih tipis dari pars tensa. Pars flaksida dibatasi oleh 2 lipatan yaitu plika maleolaris anterior (lipatan muka) dan plika maleolaris posterior (lipatan belakang).
Permukaan luar dari membran timpani disarafi oleh cabang nervus aurikulotemporalis yang berasal dari nervus mandibula dan nervus vagus. Permukaan dalam disarafi oleh n. Yacobson cabang dari nervus glosofaringeal. Aliran darah membran timpani berasal dari permukaan luar dan dalam. Permukaan mukosa telinga tengah diperdarahi oleh cabang timpani arteri maksilaris interna dan oleh stilomastoid cabang dari arteri aurikula posterior.12.1.2. Kavum Timpani
Kavum timpani terletak di dalam pars petrosa dari tulang temporal, bentuknya bikonkaf, atau seperti kotak korek api. Diameter anteroposterior atau vertikal 15 mm, sedangkan diameter transversal 2-6 mm.1,14Menurut ketinggian batas superior dan inferior membran timpani dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Epitimpanum atau atik yaitu bagian kavum timpani yang lebih tinggi dari batas superior membran timpani.
2. Mesotimpanum yaitu ruangan di antara batas atas dengan batas bawah membran timpani.
3. Hipotimpanum yaitu bagian kavum timpani yang terletak lebih rendah dari batas bawah membran timpani.Kavum timpani mempunyai 6 dinding yaitu:
1. Dinding Superior Kavum Timpani
Atap kavum timpani dibatasi oleh lempengan tulang yang tipis disebut tegmen timpani (sering disebut juga dural plate) yang memisahkannya dengan fossa media. Di bagian ini terdapat sutura petroeskuamosa yang dilewati oleh serabut-serabut saraf dan pembuluh darah.
2. Dinding Inferior Kavum Timpani
Lantai kavum timpani ditempati oleh bulbus jugularis yang dinding superiornya dibatasi oleh lempeng tulang yang mempunyai ketebalan yang bervariasi, bahkan kadang-kadang hanya dibatasi oleh mukosa dengan kavum timpani.
3. Dinding Medial Kavum Timpani
Topografi dinding medial kavum timpani terdiri dari promontorium, tingkap lonjong, tingkap bulat, prominentia kanalis fasialis, pontikulus, subikulus, nervus Yacobson dan pleksus timpanikus.4. Dinding Lateral Kavum Timpani
Di bagian mesotimpanum, membran timpani merupakan dinding lateral kavum timpani, sedangkan di bagian epitimpanum, dinding lateralnya adalah skutum, yaitu lempeng tulang yang merupakan bagian pars skuamosa tulang temporal.5. Dinding Anterior Kavum Timpani
Dinding anterior sebagian besar berhadapan dengan a. karotis, dibatasi oleh lempeng tulang tipis. Di bagian atas dinding anterior terdapat semikanal nervus tensor timpani yang terletak persis di atas muara tuba Eustachius.
6. Dinding Posterior Kavum Timpani
Pada bagian epitimpani, kavum timpani tidak berdinding, mempunyai hubungan dengan rongga mastoid melalui aditus ad antrum. Pada bagian posterior ini, dari medial ke lateral, terdapat eminentia piramidalis yang terletak di bagian superior-medial dinding posterior, kemudian sinus posterior yang membatasi eminentia piramidalis dengan tempat keluarnya korda timpani. Terdapat juga fosa inkudis yang terletak persis di atas sinus lateralis.
Isi kavum timpani terdiri dari:
1. Tulang pendengaran
a. Maleus
Bagian-bagian tulang maleus terdiri atas kapitulum, leher, manubrium, prosesus lateral dan prosesus anterior.
b. Inkus
Tulang inkus terdiri dari badan, manubrium (prosesus longus) dan prosesus brevis.c. Stapes
Tulang stapes terdiri atas kapitulum stapes, basis stapes (stapes footpalte) dan krura.
2. Ada dua otot yaitu
a. Muskulus stapedius
Sebagian besar m. Stapideus terletak di dalam tulang, pada sulkus di bagian posterior kavum timpani berdekatan dengan kanalis fasialis; keluar dari sulkus itu pada orifisium di eminensia piramidalis sebagai tendo lalu melekat pada krura posterior.
b. Tensor timpani
Muskulus tensor timpani muncul dari bagian tulang rawan tuba Eustachius, berjalan pada semikanalnya.
3. Saraf korda timpani merupakan cabang dari nervus fasialis masuk ke kavum timpani dari kanalikulus posterior yang menghubungkan dinding lateral dan posterior.
4. Saraf pleksus timpanikus adalah berasal dari n. Yacobson cabang dari nervus glosofaringeus dan dengan nervus karotikotimpani yang berasal dari pleksus simpatetik di sekitar arteri karotis interna.1,142.1.3. Prosesus Mastoideus
Prosesus mastoideus yang disebut juga ujung mastoid (mastoid tip), merupakan suatu tonjolan di bagian bawah tulang temporal yang dibentuk oleh prosesus zigomatikus di bagian anterior dan lateralnya serta pars petrosa tulang temporal di bagian ujung dan posteriornya.
2.1.4. Tuba Eustachius
Tuba Eustachius menghubungkan kavum timpani dengan nasofaring, berjalan dari muaranya pada bagian atas dinding depan atas kavum timpani ke muaranya di nasofaring persis di belakang ujung konka inferior. Pada orang dewasa perbedaan tinggi muaranya di kedua tempat itu adalah sekitar 25 mm, sedangkan panjangnya sekitar 30 sampai 40 mm. Pada anak ukurannya lebih pendek dan lebih datar. Dinding tuba eustachius mempunyai bagian tulang rawan yang merupakan 2/3 seluruh panjangnya mulai dari muaranya di kavum timpani, sedangkan 1/3 bagian yang lain berdinding tulang rawan, turun ke arah nasofaring dan bermuara di situ. Dinding tulang rawan ini tidak lengkap, dinding bawah dan lateral bawah merupakan jaringan ikat yang bergabung dengan m. Tensor dan levator veli palatini.1 Tuba biasanya tertutup, tetapi selama mengunyah, menelan, dan menguap saluran ini terbuka, sehingga tekanan udara di kedua sisi gendang telinga seimbang.2.2. Fisiologi PendengaranGetaran suara ditangkap oleh daun telinga yang dialirkan ke liang telinga dan mengenai membran timpani, sehingga membran timpani bergetar. Getaran ini diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya stapes menggerakkan perilimf dalam skala vestibuli. Getaran diteruskan melalui membran Reissener yang mendorong timpani akan bergerak sehingga tingkap (foramen rotundum) terdorong ke arah luar.
Skala media yang menjadi cembung mendesak endolimf dan mendorong basal, sehingga menjadi cembung ke bawah dan menggerakkan perilimf pada skala timpani. Pada waktu istirahat ujung sel rambut menjadi lurus. Rangsangan fisik tadi berubahnya oleh adanya perbedaan ion Kalium dan ion Natrium menjadi aliran listrik yang diteruskan ke cabang-cabang n.VIII yang kemudian meneruskan rangsangan itu ke pusat sensorik pendengaran di otak (area 39-40) melalui saraf pusat yang ada di lobus temporalis.
2.3. Definisi OMSK tipe bahaya (maligna) ialah OMSK yang di sertai dengan kolesteatoma. OMSK ini dikenal juga dengan OMSK tipe tulang. Perforasi biasanya letaknya margina atau di atik, kadang kadang terdapat juga kolesteatoma pada OMSK dengan perforasi sub total. Sebagian besar komplikasi yang berbahaya atau fatal bisa timbul.
2.4. Epidemiologi
Prevelensi OMSK pada beberapa negara antara lain disebabkan, kondisi social, ekonomi, suku, tempat tinggal yang padat, hygiene dan nutrisi yang jelek. Kebanyakan melaporkan prevalensi OMSK pada anak termasuk anak yang mempunyai kolesteatom, tetapi tidak mempunyai data yang tepat, apalagi insiden OMSK saja, tidak ada data yang tersedia. Otitis media kronis merupakan penyakit THT yang paling banyak di negara sedang berkembang. Di negara maju seperti Inggris sekitar 0,9% dan Israel hanya 0,0039%. Di negara berkembang dan negara maju prevalensi OMSK berkisar antara 1-46%, dengan prevalensi tertinggi terjadi pada populasi di Amerika dan Inggris kurang dari 1% (Lasminingrum L,2000). Menurut survey yang dilakukan pada 7 propinsi di Indonesia pada tahun 1996 di temukan insiden otitis media supuratif kronis(OMSK) sebesar 3% dari penduduk Indonesia. Di Indonesia menurut survey kesehatan indra penglihatan dan pendengaran, depkes tahun 1993-1996 prevalensi OMSk adalah 3,1%-5,20% populasi. Usia terbanyak infeksi telinga tengah adalah usia 7-18 tahun, dan penyakit terbanyak OMSK.2.5. Etiologi Otitis Media Supuratif Kronik
Penyebab otitis media supuratif kronik antara lain:
1. Lingkungan
Hubungan penderita OMSK dan faktor sosial ekonomi belum jelas, tetapi mempunyai hubungan erat antara penderita dengan OMSK dan sosioekonomi, dimana kelompok sosioekonomi rendah memiliki insiden yang lebih tinggi. Tetapi hal ini dapat berhubungan dengan kesehatan secara umum, diet, tempat tinggal yang padat.
2. Genetik
Faktor genetik masih diperdebatkan sampai saat ini, terutama apakah insiden OMSK berhubungan dengan luasnya sel mastoid yang dikaitkan sebagai faktor genetik.
3. Otitis media sebelumnya
Secara umum dikatakan otitis media kronis merupakan kelanjutan dari otitis media akut dan/atau otitis media dengan efusi, tetapi tidak diketahui faktor apa yang menyebabkan satu telinga dan bukan yang lainnya berkembang menjadi keadaan kronis.
4. Infeksi
Bakteri yang diisolasi dari mukopus atau mukosa telinga tengah hampir tidak bervariasi pada otitis media kronik yang aktif menunjukkan bahwa metode kultur yang digunakan adalah tepat.5. Infeksi saluran napas atas
Banyak penderita mengeluh sekret telinga sesudah terjadi infeksi saluran napas atas. Infeksi virus dapat mempengaruhi mukosa telinga tengah menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap organisme yang secara normal berada dalam telinga tengah, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri.6. Autoimun
Penderita dengan penyakit autoimun akan memiliki insiden lebih besar terhadap otitis media kronik.
7. Alergi
Penderita alergi mempunyai insiden otitis media kronik yang lebih tinggi dibanding yang bukan alergi. Yang menarik adalah dijumpainya sebagian penderita yang alergi terhadap antibiotik tetes telinga atau bakteria atau toksin-toksinnya, namun hal ini belum terbukti kemungkinannya.
8. Gangguan fungsi tuba eustachius
Pada otitis kronik aktif, dimana tuba eustachius sering tersumbat oleh edema tetapi apakah hal ini merupakan foramen primer atau sekunder masih belum diketahui. Pada telinga yang inaktif berbagai metode telah digunakan untuk mengevaluasi fungsi tuba eustachius dan umumnya menyatakan bahwa tuba tidak mungkin mengembalikan tekanan negatif menjadi normal.2.6. Gejala klinis Berikut tanda dan gejala yang timbul pada penderita OMSK tipe maligna adalah :
1. Telinga berair ( otorhea)
Sekrek purulen, atau mukoid tergantung stadium perdangan. Pada OMSK ganas unsur mukoid dan secret telinga tengah berkurang atau hilang karena rusaknya lapisan mukosa secara luas. Secret yang bercampur darah berhubungan dengan adanya jaringan granulose dan polip telinga dan merupakan tanda adanya kolesteatomyang mendasarinya. 2. Gangguan pendengaran
Biasanya dijumpai tuli konduktif namun dapat pula bersifat campuran. Beratnya ketulian tergantung dari besar dan letak perforasi membrane timpani serta keutuhan dan mobilitas system penghantaran suara ke telinga tengah. Pada OMSK tipe maligna terdapat tuli konduktif berat.
3. Otalgia ( nyeri telinga)
Pada OMSK keluhan nyeri dapat karena terbendungnya drainase pus.
4. Vertigo
Keluhan vertigo seringkali merupakan tanda telah terjadinya fistel labirin akibat erosi dinding labirin oleh kolesteatom. Vertigo yang timbul biasanya akibat perubahan tekanan udara yang mendadak atau pada penderita yang sensitive keluhan vertigo dapat terjadi hanya karena perforasi besar membrane timpani yang akan menyebabkan labirin lebih mudah terangsang oleh perbedaan suhu.Tanda-tanda klinis OMSK tipe maligna yaitu:
1. Adanya abses atau fistel retroaurikular
2. Jaringan granulasi atau polip diliang telinga yang berasal dari kavum timpani
3. Pus yang selalu aktif atau berbau busuk (aroma kolesteatom)
4. Foto rontgen mastoid adanya gambaran kolesteatom2.7. Diagnosis a. Anamnesis (history-taking)
Penyakit telinga kronis ini biasanya terjadi perlahan-lahan dan penderita seringkali datang dengan gejala-gejala penyakit yang sudah lengkap. Pada maligna sekretnya lebih sedikit, berbau busuk, kadangkala disertai pembentukan jaringan granulasi atau polip, maka secret yang keluar dapat bercampur darah. Ada kalanya penderita datang dengan keluhan kurang pendengaran atau telinga keluar darah.
b. Pemeriksaan klinis1. Pemeriksaan otoskopiPemeriksan otoskopi akan menunjukkan adanya perforasi adanya letak perforasi. Dari perforasi dapat dinilai kondisi mukosa telinga tengah.2. Pemeriksaan audiologi
Pada pemerksaan audiometric penderita OMSK biasanya di dapati tuli konduktif. Tapi dapat pula di jumpai adanya tuli sensorineural, beratnya ketulian tergantung besar dan letak perforasi membrane timpani serta keutuhan dan mobilitas .3. Pemeriksaan radiologi
Radiologi konvensional, poto polos radiologi, posisi schuller berguna untuk menilai kasus kolesteatoma. 3.1. Proyeksi schuller
Memperlihatkan luasnya pneumatisasi mastoid dari arah lateral dan atas. Foto ini berguna untuk pembedahan karena memperlihatkan posisi sinus lateral dan tegmen. 3.2. Proyeksi mayer dam owen
Diambil dari arah dan anterior telinga tengah. Akan tampak gambaran tulang-tulang pendengaran dan atik sehingga dapat diketahui struktur dan kerusakan tulang.
3.3. Proyeksi stenver
Memperlihatkan gambaran sepanjang pyramid petrosus dan yang lebih jelas memperlihatkan kanalis auditorius interna, vestibulum dan kanalis semisirkularis. Proyeksi ini menempatkan antrum dalam potongan melintang sehingga dapat menunjukkan adanya pembesaran 3.4. Proyeksi chause III
Member gambaran atik secara longitudinal sehingga dapat memperlihatkan kerusakan dini dinding lateral atik. Politomografi dan atau ct scan dapat menggambarkan kerusakan tulang oleh karena kolesteatom.
4.Tomografi komputer (CT Scan), dan/atau magnetic resonance imaging (MRI).
a. Computer TomographyCompute tomography (CT Scan) dilakukan pada kecurigaan adanya kolesteatoma, juga akan memperlihatkan lebih baik ada-tidaknya erosi atau destruksi dinding lateral atik (skutum).
b. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Pemeriksaan ini dilakukan untuk menunjukkan patologi di telinga tengah sangat terbatas, untuk mencoba menunjukkan kehadiran kolesteatoma lebih baik daripada CT Scan, juga lebih memberikan keterangan tentang terkenanya n. fasialis.5. Pemeriksaan Bakteriologi
Bakteri yang diisolasi dari mukopus atau mukosa telinga tengah baik aerob ataupun anaerob menunjukkan organisme yang multipel. Organisme yang terutama dijumpai adalah gram negatif, bowel-type flora dan beberapa organisme lainnya. Organisme aerob umumnya Pseudomonas aeruginosa, proteus, E. coli, dan S. aureus, sedangkan yang anaerob Bacteroides fragilis dan Streptokokus.
2.8. Penatalaksanaan Otitis media supuratif kronik tipe bahaya bersifat progresif, kolesteatoma yang semakin luas akan mendestruksi tulang yang dilaluinya. Infeksi sekunder akan menyebabkan keadaan septik lokal dan menyebabkan apa yang disebut nekrosis septik di jaringan lunak yang dilalui kolesteatoma dan di jaringan sekitarnya sehingga juga menyebabkan destruksi jaringan lunak yang mengancam akan terjadinya komplikasi.
Pengobatan konservatif dengan pembersihan lokal melalui liang telinga pada kolesteatoma yang masih terbatas atau pasien yang karena kondisinya tidak mungkin menjalani operasi baik dalam anestesi lokal ataupun anestesi umum. Pengobatan pencegahan perluasan kolesteatoma dengan pemasangan pipa ventilasi untuk retrksi ringan, operatif bila meluas. Tergantung luas kerusakan dan pilihan ahli bedah dapat dilakukan beberapa pilihan.
Prinsip terapi OMSK tipe bahaya (maligna) ialah pembedahan,yaitu mastoidektomi. Bila terdapat OMSK tipe bahaya, maka terapi yang tepat ialah dengan melakukan mastoidektomi dengan atau tanpa timpanoplasti. Terapi konservatif dengan medikamentosa hanyalah merrupakan terapi sementara sebelum dilakukan pembedahan. Bila terdapat abses sub periosteal retroaurikuler, maka insisi abses sebaiknya dilakukan sendiri sebelum mastoidektomi.
1. Jenis pembedahan pada OMSK maligna
Ada beberapa jenis pembedahan atau teknik operasi yang dapat dilakukan pada OMSK maligna :a. Mastoidektomi radikalOperasi ini dilakukan pada OMSK bahaya dengan infeksi atau kolesteatoma yang sudah meluas. Pada operasi ini rongga mastoid dan kavum timpani di bersihkan dari semua jaringan patologik. Dinding batas antara liang telinga luar dan tengah dengan rongga mastoid di runtuhkan, sehingga ketiga daerah anatomi tersebut menjadi satu ruangan. Tujuan operasi ini ialah untuk jaringan patologik dan mencegah komplikasi ke intra cranial. Fungsi pendengaran tidak diperbaiki. Kerugian operasi ini ialah pasien tidak di perbolehkan berenang seumur hidupnya. Pasien harus datang dengan teratur untuk control, supaya tidak terjadi infeksi kembali. Modifikasi operasi ini ialah dengan memasang tandur (graft) pada rongga operasi serta membuat meatoplasti yang lebar, sehingga operasi kering permanen, tetapi terdapat cacat anatomi yaitu meatus liang telinga luar menjadi lebar
b. Mastoidektomi radikal dengan modifikasi (operasi bondy)
Operasi ini dilakukan pada OMSK dengan kolesteatoma didaerah atik, tetapi belum merusak kavum timpani. Seluruh rongga mastoid di bersih kan dan dinding posterior liang telinga di rendahkan. Tujuan operasi ini ialah untuk membuang semua jaringan patologik dari rongga mastoid, dan mempertahankan pendengaran yang masih ada.
c. Timpanoplasti dengan pendekatan ganda (combined approach tympanoplasty)
Operasi ini merupakan teknik operasi timpanoplasti yang di kerjakan pada kasus OMSK tipe bahaya atau OMSK tipe aman dengan jaringan granulasi yang luas. Tujuan operasi untuk menyembuhkan penyakit serta memperbaiki pendengaran tanpa melakukan teknik mastoidektomi radikal(tanpa meruntuhkan dinding posterior liang telinga). Membersihkan kolesteatoma dan jaringan granulasi di kavum timpani, di kerjakan melalui dua jalan(combined approach) yaitu melalui liang telinga dan rongga mastoid dengan melakukan timpanotomi postehrior. Teknik operasi ini pada OMSk tipe bahaya belum disepakati oleh para ahli, oleh karena sering terjadi kambuhnya kolesteatoma kembali.2.9. Komplikasi
Komplikasi intra cranial yang serius lebih sering terlihat pada ekseserbasi akut dari OMSK yang berhubungan kolesteatoma.
1. Komplikasi telinga tengah
a. Perforasi persisten
b. Erosi tulang pendengaran
c. Paralisis nervus facialis
2. Komplikasi telinga dalam
a. Fistel labirin
b. Labirintis supuratif
c. Tuli saraf (sensorineural)
3. Komplikasi ekstradural
a. Abses ekstradural
b. Thrombosis sinus lateralisc. Petrositis
4. Komplikasi kesusunan saraf pusat
a. Meningitis abses otak
b. Abses otak
DAFTAR PUSTAKA1. Soepardi, efiaty arsyad. Dkk, Telinga Hidung Tenghgorok Kepala dan Leher. Jakarta. FK UI. Edisi ke VI. 2014.
2. Riska,soraya. GAMBARAN GEJALA DAN TIPE OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIS RAWAT INAP TAHUN 2012-2013 DI RSU HAJI MEDAN.
3. Santoso, boedy setya, Titiek HA. Komplikasi ekstra kranial otitis media supuratif kronik maligna di depertemen THT KL RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA tahun 2004-2006.4. Adams,BOIES,HIGLER. Buku ajar penyakit THT. EDISI 6. EGC. 2012.17