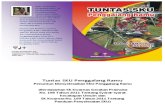NABILA NURRAHMADYANI YUNUS PROGRAM STUDI...
Transcript of NABILA NURRAHMADYANI YUNUS PROGRAM STUDI...

EVALUASI KEBIJAKAN SPIN OFF PADA INDUSTRI
ASURANSI JIWA SYARIAH
Oleh:
NABILA NURRAHMADYANI YUNUS
NIM.1113086000036
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019 M

i

ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

iv

v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Nabila Nurrahmadyani Yunus
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 Februari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Duta Kenanga III Blok D4 No.12 Perumahan Duta
Harapan Kel.Harapan Baru Kec.Bekasi Utara 17123
E-mail : [email protected]
Nomor telepon : 087789203344
PENGALAMAN ORGANISASI
2017 Kepala Staff Bantuan Kesehatan dan Sosial Korps Sukarela
Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
2016 Staff Hubungan Masyarakat dan Informasi Korps Sukarela
Palang merah Indonesia (KSR PMI) Unit UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
2016 Staff Biro Project. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2015 Staff Divisi Kemahasiswaan. Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ) Ekonomi Syariah Tahun 2015
2015-2016 Anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI)
unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2015-2016 Wakil Koordinator Divisi Kewirausahaan LiSEnsi (Lingkar
Studi Ekonomi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2014 Anggota LiSEnsi (Lingkar Studi Ekonomi Islam)

vi
PENDIDIKAN FORMAL
2013-2019 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
2006-2012 Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 Ngawi Jawa
Timur
2000-2006 SDN Kenari 10 Jakarta Pusat
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI
2016 Sekolah Pasar Modal Syariah Tingkat Dasar, Bursa Efek
Indonesia
2016 Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jasinga, Bogor
2016 Sekolah Pasar Modal Tingkat Dasar, Reksadana
2015 Kuliah Intensif Ekonomi Islam (KIEI), Kelas Ekonomi Islam,
KSEI SHINE Universitas Indonesia.
2014 Diklat Korp Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2014 Diklat Ekonomi Islam Lingkar Studi Ekonomi Syariah
(LISENSI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2012 Kursus Pembina Mahir Tingkat Lanjutan Golongan
Penggalang Gerakan Pramuka, Kwartir Cabang Ngawi
2010 Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD) Gerakan
Pramuka, Kwartir Cabang Ngawi

vii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemisahan pada unit
usaha syariah asuransi jiwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang
No.40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Perasuransian dan juga untuk memprediksi
target pertumbuhan yang harus dicapai unit usaha syariah asuransi jiwa terhadap
pertumbuhan perusahaan asuransi induknya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit usaha syariah pada perusahaan
asuransi jiwa di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling sebanyak 4 unit usaha syariah. Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi masing-masing unit usaha
syariah pada perusahaan asuransi jiwa dari tahun 2010 sampai tahun 2018, data dapat
diunduh melalui laporan publikasi situs (website) masing-masing perusahaan asuransi
jiwa.
Metode yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemisahan ini adalah
metode ARIMA dengan melakukan peramalan pada tingkat share dana peserta unit
usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa terhadap perusahaan induknya dan
simulasi untuk memprediksi target pertumbuhan yang harus dicapai unit usaha syariah
asuransi jiwa terhadap pertumbuhan perusahaan asuransi induknya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 4 unit usaha syariah hingga 10 tahun
setelah undang-undang berlaku atau tahun 2024 belum ada satupun yang mencapai
tingkat share 50% dana peserta asuransi terhadap dana peserta asuransi perusahaan
induknya. Selain itu, hasil simulasi menunjukan bahwa dibutuhkan tingkat
pertumbuhan yang tinggi rata-rata sebesar 50,53% dari unit usaha syariah asuransi
jiwa untuk mencapai tingkat share 50% dana peserta perusahaan induknya. Kebijakan
ini perlu dievaluasi kembali agar tidak memberatkan para pelaku usaha atau pemilik
perusahaan asuransi khususnya pada perusahaan asuransi jiwa.
Kata Kunci: Kebijakan Pemisahan (Spin Off), Asuransi Jiwa, Metode ARIMA,
simulasi

viii
ABSTRACT
This study aims to evaluate the spin off policy in sharia business unit of life
insurance as explained in Act No.40 of 2014 clause 87 paragraph 1 concerning
Insurance and also to predict the growth target that must be achieved by the sharia
business unit of life insurance on the growth of the parent’s insurance company.
The population in this study are all sharia business units in life insurance
companies in Indonesia. The sampling technique is used subjective sampling based on
4 sharia business units. This study uses secondary data obtained from the published
financial reports of each sharia business unit in life insurance companies from 2010 to
2018 that can be downloaded through the website of each life insurance companies.
The method that used to evaluate the spin off policy is ARIMA by forecasting
the share level of sharia business unit participant funds in life insurance company
towards the parent’s insurance company and simulation to predict the growth target
that must be achieved by the sharia business unit of life insurance on the growth of the
parent’s insurance company.
The results showed that from all the sample up to ten years or the year of 2024,
there are no sharia business unit of life insurance can achieve the fifty percent
participant funds towards the parent’s insurance company. Besides that, simulation
result showed that sharia business unit of life insurance needs high growth on average
50,53% to achieve the fifty percent participant funds towards the parent’s insurance
company. This policy needs to be evaluated in order to not be burden for an insurance
company owner especially life insurance company.
Key word: Spin Off Policy, Life Insurances, ARIMA method, simulation.

ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat
beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW.
Skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Spin Off pada Industri Asuransi Jiwa
Syariah” ini disusun dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak.
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa
belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta selalu
memberikan kesempatan kepada penulis untuk selalu belajar dari setiap
kejadian yang terjadi. Dengan ridho Allah SWT skripsi ini bisa terselesaikan
dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta bapak Triyudi Sunarko dan ibunda
tercinta ibu Nurul Hidayati serta kedua adik penulis Muhammad Zaidani
Yunus dan Rohada Nur Aisya Yunus yang telah memberikan cinta kasih serta
dukungan secara penuh kepada penulis, baik materil maupun non materil.
Terimakasih untuk segala doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis agar
bisa menyeselaikan studi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Amilin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Dr. M. Nur Rianto Al Arif, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi
yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dan
memotivasi penulis agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Erika Amelia, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu Dwi Nur’aini Ihsan, MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
7. Bapak Yoghi Citra Pratama, SE., M.Sc selaku dosen penasehat akademik yang
selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan pendidikan di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

x
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan dan mengamalkan ilmu
yang tidak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013. Terimakasih
untuk semua canda tawa dan pengalaman serta perjuangan kita bersama dalam
proses belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
10. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Nurul Hasanah S.E, Nadya Zakiyah
S.E, Putri Nurani S.E, Ulfah Fauziah S.E, dan Puspa Cahya Insani S.E yang
tidak pernah lelah menyemangati penulis dalam proses belajar dan dalam
proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh anggota KSR PMI Unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya
angkatan Satu Buana (SBN) yang selalu memberikan semangat kepada penulis
agar bisa menyelesaikan semua tanggungjawab penulis dengan baik.
12. Sahabat-sahabat alumni Gontor penulis Dara Puspa Dewi, Ghusny Minal
Jannati, Linda Hermawati yang selalu menyemangati penulis dalam proses
belajar dan dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang
banyak membantu penulis sehingga skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan
kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
penulis harapkan. Adapun segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Harapan penulis, semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.
Jakarta, 29 November 2019
Nabila Nurrahmadyani Yunus

xi
DAFTAR ISI
COVER
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................................... iii
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................................xv
BAB I ...................................................................................................................................1
PENDAHULUAN ...............................................................................................................1
A. Latar Belakang Penelitian ........................................................................................1
B. Identifikasi Masalah...............................................................................................11
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah .......................................................................12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................................................12
E. Sistematika Penulisan ............................................................................................14
BAB II ...............................................................................................................................15
TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................................15
A. LANDASAN TEORI.................................................................................................15
1. Kebijakan Pemisahan (Spin Off) ...........................................................................15
2. Konsep Asuransi ....................................................................................................21
3. Asuransi Syariah ....................................................................................................28
B. Penelitian Terdahulu ..................................................................................................35
C. Kerangka Pemikiran ..................................................................................................40
D. Hipotesis Penelitian ...................................................................................................42
BAB III ..............................................................................................................................43
METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................................43
A. Ruang Lingkup Penelitian .........................................................................................43
B. Metode Penentuan Sampel ........................................................................................44
C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................................45
D. Metode analisis data ..................................................................................................46
1. Uji Stasioner ..........................................................................................................46
2. Metode Box-Jenkins ..............................................................................................46

xii
a. Tahap Identifikasi ..............................................................................................50
b. Tahap Estimasi Model ARIMA .........................................................................52
c. Tahap Peramalan ...............................................................................................52
BAB IV ..............................................................................................................................54
ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................................................................54
A. Analisis Deskriptif Statistik .......................................................................................54
B. Analisis Deskriptif Objek Penelitian .........................................................................54
C. Analisis Pengujian Box-Jenkins (ARIMA) ...............................................................56
1. Tahap Identifikasi ..................................................................................................57
2. Estimasi Model ARIMA ........................................................................................61
3. Tahap Peramalan (Forecasting) .............................................................................66
BAB V ...............................................................................................................................73
KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................................................73
A. Kesimpulan ................................................................................................................73
B. Saran ..........................................................................................................................74
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................76
LAMPIRAN ......................................................................................................................79

xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah di Indonesia ............. 4
Tabel 1.2 Aset Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah) .............. 6
Tabel 1.3 Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah) ....... 6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 36
Tabel 3.1 Sampel Penelitian .................................................................................. 45
Tabel 3.2 Sifat-sifat ACF/PACF dari Model ARMA ........................................... 51
Tabel 4.1 Data share dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha syariah
terhadap perusahaan asuransi jiwa induknya ........................................................ 56
Tabel 4.2 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi AIA ....................................... 61
Tabel 4.3 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi PRUDENTIAL ..................... 63
Tabel 4.4 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi ALLIANZ ............................. 64
Tabel 4.5 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi AXA MANDIRI ................... 65
Tabel 4.6 Model ARIMA Terbaik ........................................................................ 66
Tabel 4.7 Hasil Peramalan ARIMA dari tahun 2019-2024 ................................... 67
Tabel 4.8 Simulasi pertumbuhan unit usaha syariah dan induk perusahaan asuransi68

xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ......................................................... 41
Gambar 3. 1 Metodologi ARIMA ......................................................................... 49
Gambar 4.1 Hasil Correlogram AIA (Tingkat Level) ........................................... 57
Gambar 4.2 Hasil Correlogram AIA (Tingkat Df 1) ............................................. 58
Gambar 4.3 Hasil Correlogram PRUDENTIAL (Tingkat Level) ......................... 58
Gambar 4.4 Hasil Correlogram ALLIANZ (Tingkat Level) ................................ 59
Gambar 4.5 Hasil Correlogram ALLIANZ (Tingkat Df 1) .................................. 60
Gambar 4.6 Hasil Correlogram AXA MANDIRI (Tingkat Level) ....................... 60

xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I: Tingkat Share Dana Peserta Unit Usaha Syariah .............................. 79
Lampiran II: Hasil Prediksi Model ARIMA ......................................................... 81
Lampiran III: Grafik Hasil Peramalan (Forecasting) ............................................ 87

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari peran industri keuangan,
Industri asuransi syariah merupakan salah satu Industri Keuangan Non Bank
(IKNB) syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur oleh
Undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara
dengan mayoritas penduduk muslim memiliki peluang besar dalam peningkatan
industri keuangan syariah perbankan maupun non perbankan, dimana lahirnya
industri keuangan syariah di Indonesia pun didasari dari permintaan masyarakat
di Indonesia yang membutuhkan suatu sistem keuangan alternatif yang selain
menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Perbedaan yang paling menonjol pada asuransi konvensional dan asuransi
syariah terletak pada sistem yang diterapkan, asuransi konvensional menerapkan
sistem risk transfer (perpindahan risiko), sedangkan asuransi syariah menerapkan
sistem risk sharing (berbagi risiko).
Menurut Undang-undang no.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1
ayat 1:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan
asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung
dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil
pengelolaan dana” .

2
Pengertian asuransi konvensional di atas mengacu pada sistem risk transfer
(perpindahan risiko), dimana risiko yang dimiliki peserta dipindahkan ke
perusahaan asuransi, jadi dimungkinkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.
Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa Dewan Syariah
Nasional–Majlis Ulama Indonesia (DSN – MUI) no.21 tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau
Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Pengertian asuransi syariah di atas
mengacu pada sistem risk sharing (berbagi risiko), dimana risiko yang dimiliki
peserta dibagikan ke peserta lain dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai
pengelola dana, jadi dalam sistem asuransi syariah tidak ada pihak yang dirugikan
karena pada dasarnya asuransi syariah berprinsip keadilan, tolong menolong dan
kesederajatan.
Menurut Nurcahya dan Paramita (2015:18) Islam memandang asuransi
syariah sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya Islam
senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara
maksimal. Asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial (social oriented)
daripada bernuansa ekonomi (profit oriented). Hal ini dikarenakan oleh aspek
tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek asuransi
dalam Islam.
Menurut laporan World Takaful Report (2016) pasar asuransi syariah secara
global terkonsentrasi pada negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) dan

3
Asia Tenggara. Kontribusi bruto asuransi syariah di negara Asia Tenggara
menempati posisi kedua terbesar setelah negara Saudi Arabia (Ernst & Young
Global Limited, 2014). Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Ernst & Young
Global Limited (2014) besarnya jumlah kontribusi bruto asuransi syariah di Asia
Tenggara didominasi oleh negara Malaysia sebesar 71,28 % dan negara Indonesia
sebesar 22,72% dan sisanya oleh negara lainnya. Hal ini dikarenakan populasi
masyarakat muslim di kedua negara tersebut cukup banyak, selain itu Malaysia
merupakan salah satu negara yang gencar dalam mengembangkan asuransi
syariah. Indonesia sebagai penyumbang kontribusi bruto asuransi syariah terbesar
kedua di Asia Tenggara tentu memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan premi perusahaan asuransi syariah di
Indonesia semakin berkembang dan menguatkan posisinya di pasar asuransi
Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
(Sabiti,dkk, 2017:69)
Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan
munculnya perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia pada tahun 1994,
yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang berdiri pada 24 Februari 1994.
Hingga saat ini perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia berkembang
cukup baik, dimana jumlah perusahaan perasuransian syariah di Indonesia relatif
terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dibuktikan dalam data pada
Tabel 1.1:

4
Tabel 1.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2017
Keterangan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asuransi Jiwa Syariah 3 3 3 3 5 5 7
Asuransi Jiwa (Unit Syariah) 17 17 17 18 19 20 23
Asuransi Umum Syariah 2 2 2 2 3 4 5
Asuransi Umum (Unit Syariah) 18 20 24 23 25 24 25
Reasuransi Syariah 0 0 0 0 0 1 1
Reasuransi (Unit Syariah) 3 3 3 3 3 2 2
Jumlah 43 45 49 49 55 56 63
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tabel 1.1 menunjukan bahwa adanya peningkatan, baik dari perusahaan
Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, Reasuransi Syariah, dan Unit
Usaha Syariah pada perusahaan perasuransian syariah di Indonesia dari tahun
2011 sampai tahun 2017. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan perasuransian
syariah di Indonesia yaitu sejumlah 43 bertambah menjadi sejumlah 63 pada
tahun 2017, dimana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 jumlah
perusahaan perasuransian syariah yang bertambah sejumlah 20 perusahaan
perasuransian syariah. Munculnya perusahaan asuransi baru, baik dari perusahaan
asuransi jiwa dan asuransi umum dengan prinsip syariah dan juga reasuransi
syariah yang mengalami perubahan komposisi, yaitu dari keseluruhan perusahaan
yang hanya berbentuk unit usaha syariah menjadi satu perusahaan yang berbentuk
syariah dengan melakukan spin off dapat meningkatkan persaingan usaha diantara
perusahaan perasuransian yang ada saat ini.
Jumlah perusahaan perasuransian syariah diprediksi akan terus bertambah
sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai spin off unit usaha asuransi

5
syariah dalam Undang-undang no.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 87
ayat (1) yang menyatakan:
“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi memiliki unit
usaha syariah dengan nilai Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta telah
mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi,
Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta pada perusahaan induknya atau 10
(sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan Reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan (spin off) unit
usaha syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi Syariah”.
Berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada
pasal 87, hal penting yang harus digaris bawahi adalah unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan spin off jika
dana tabarru’ dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi
peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya
Undang-undang tersebut. Lalu bagaimana dengan perkembangan dana aset dan
dana investasi perusahaan perasuransian syariah yang ada saat ini ? dan berapa
persen market share perusahaan perasuransian syariah terhadap perusahaan
asuransi nasional ?, berikut data aset perusahaan perasuransian syariah di
Indonesia beserta tingkat sharenya terhadap perusahaan asuransi nasional dari
tahun 2013 sampai dengan 2017 pada Tabel 1.2 dan data investasi perusahan
perasuransian syariah di Indonesia beserta tingkat sharenya terhadap perusahaan
asuransi nasional dari tahun 2013 sampai dengan 2017 pada Tabel 1.3.

6
Tabel 1.2 Aset Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017
Asuransi Jiwa Nasional 265,86 368,06 378,03 422,19 546,43
Asuransi Jiwa Syariah 12,79 18,08 21,73 27,08 33,48
Share Asuransi Jiwa Syariah 4,81% 4,91% 5,75% 6,41% 6,13%
Asuransi Umum dan Reasuransi
Nasional 103,14 126,75 138,83 145,64 133,32
Asuransi Umum dan Reasuransi
Syariah 3,87 4,31 4,96 6,17 5,37
Share Asuransi Umum dan
Reasuransi Syariah 3,75% 3,40% 3,57% 4,23% 4,03%
Asuransi Jiwa dan Reasuransi
Nasional 369,00 494,81 516,86 687,84 699,64
Asuransi dan Reasuransi
Syariah 16,66 22,39 26,69 33,24 40,52
Share Asuransi dan Reasuransi
Syariah 4,51% 4,52% 5,16% 4,83% 5,79%
Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2017
Tabel 1.3 Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017
Asuransi Jiwa Nasional 227,63 318,49 327,68 367,83 489,01
Asuransi Jiwa Syariah 11,54 16,4 19,60 24,57 30,42
Share Asuransi Jiwa Syariah 5,07% 5,15% 5,98% 6,68% 6,22%
Asuransi Umum dan Reasuransi
Nasional 57,81 63,66 70,4 73,96 69,69
Asuransi Umum dan Reasuransi
Syariah 2,76 3,11 3,50 4,24 3,68
Share Asuransi Umum dan
Reasuransi Syariah 4,77% 4,88% 4,97% 5,74% 5,28%
Asuransi Jiwa dan Reasuransi
Nasional 285,44 382,15 398,08 441,79 570,98
Asuransi dan Reasuransi
Syariah 14,3 19,51 23,10 28,81 35,31
Share Asuransi dan Reasuransi
Syariah 5,01% 5,10% 5,80% 6,52% 6,18%
Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2017

7
Berdasarkan data pada Tabel 1.2 total aset perusahaan perasuransian syariah
mencapai Rp40,52 triliun di akhir tahun 2017, total tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp7,28 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp33,24 triliun atau
meningkat sekitar 17,96%. Market share total aset perusahaan perasuransian
syariah terhadap asuransi nasional juga meningkat dari 4,83% di 2016 menjadi
5,79% di 2017. Meskipun share aset asuransi syariah terus meningkat tiap
tahunnya tetapi angka tersebut masih sangat kecil melihat pasar asuransi syariah
yaitu penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia.
Pada Tabel 1.3 total investasi perusahaan perasuransian syariah tahun 2017
adalah Rp35,31 triliun, total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6,5 triliun
dari tahun sebelumnya yaitu Rp28,82 triliun atau meningkat sekitar 18,40%.
Sedangkan market share total investasi perusahaan perasuransian syariah terhadap
asuransi nasional menurun dari 6,52% di 2016 menjadi 6,18% di tahun 2017.
Penurunan ini disebabkan karena peningkatan kinerja dan dana investasi pada
perusahaan asuransi nasional tidak sebanding atau lebih besar dibandingkan
dengan peningkatan kinerja dan dana investasi pada perusahaan perasuransian
syariah.
Jika spin off unit usaha syariah pada perusahaan asuransi merupakan salah
satu cara yang diambil pemerintah agar industri asuransi syariah di Indonesia
berkembang dengan pesat apakah cara itu sudah tepat ?, melihat dari total dana
aset dan total dana investasi asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah dan
reasuransi syariah pada perusahaan perasuransian syariah belum ada yang
mencapai 50% bahkan 10 % saja belum. Sedangkan waktu yang diberikan oleh
pemerintah hanya 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-undang

8
no.40 tahun 2014 yaitu pada tahun 2024 dan sisa waktu unit usaha syariah untuk
spin off menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum
syariah dan perusahaan reasuransi syariah hanya tinggal 5 tahun lagi, terhitung
dari tahun penelitian ini tahun 2019.
Menurut Sulistyawati (2014) dalam berita Republika, pembatasan jumlah
minimum aset syariah mencapai 50% dari perusahaan induk, penetrasi asuransi
syariah melambat pada tahun 2014 sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan
asuransi syariah merasa keberatan dengan kebijakan ini, praktisi dan pakar
asuransi Muhammad Syakir Sula berpendapat, presentase 50% itu terlampau besar
dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai puluhan tahun.
Menurut Pohan (2014) dalam berita media insurance yang membahas
tentang kebijakan spin off , pada kenyataannya unit usaha syariah belum siap
untuk melakukan pemisahan dengan induk perusahaannya, dan pemerintah pun
menunda waktu realisasi pelaksanaan spin off, seharusnya unit usaha syariah
dalam perusahaan asuransi mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau otoritas
jasa keuangan selaku regulator agar unit usaha syariah dapat segera menjadi
perusahaan yang mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Menurut Pitaningtyas dan Nababan (2015) pemisahan atau spin off unit
usaha syariah masih tetap menjadi pekerjaan rumah perusahaan asuransi. Meski
berkali-kali menyatakan siap, mereka mengkhawatirkan dampak jika harus
menyapih unit usaha syariah dalam waktu dekat. Selain itu dampak dari spin off
adalah melonjaknya biaya operasional sehingga harga produk pun dinaikkan.
Ramadani (2018) dalam penelitiannya tentang respon salah satu unit usaha
syariah perusahaan asuransi di Indonesia yaitu perusahaan asuransi Adira

9
Dinamika terhadap kebijakan spin off industri asuransi syariah dalam Undang-
undang no.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 67, menyatakan bahwa
perusahaan asuransi Adira Dinamika belum siap melakukan spin off dikarenakan
peraturan perundang-undangan tersebut dinilai memberatkan bagi pelaku bisnis
dan terkesan dipaksakan oleh pemerintah. Persiapan yang kurang matang,
manajemen kurang mendukung, bantuan ahli aktuaria yang sangat langka, serta
perusahaan induk yang melepas anak perusahaannya menjadi kendala-kendala
yang dihadapi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi Adira Dinamika dalam
melakukan spin off.
Konsep spin off atau pemisahan juga sedang dilakukan oleh unit usaha
syariah pada industri perbankan dengan peraturan yang sama dengan unit usaha
syariah pada industri asuransi syariah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir
industri perbankan syariah mengalami penurunan, terdapat beberapa penelitian
yang membahas tentang konsep spin off atau pemisahan unit usaha syariah pada
industri perbankan syariah. Menurut Al Arif (2014:169) Aturan mengenai
kebijakan pemisahan (spin off) ini sempat menjadi isu krusial. Riawan Amin
mengungkapkan bahwa pemisahan perbankan syariah dari UUS menjadi BUS
seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank syariah
baru sulit untuk mengembangkan diri. Menurut A.Riawan Amin seharusnya
pemisahan dilakukan ketika nasabah suatu bank dengan perbandingan telah
mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari bank induknya, sehingga
pemisahan merupakan alternatif agar unit usaha syariah bisa mandiri. Tapi yang
terjadi di Indonesia tidak demikian, pemisahan dilakukan hanya berdasarkan
informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.

10
A.Riawan Amin juga berharap kebijakan tersebut harus ditinjau lagi dan jangan
terlalu dipaksakan kepada bank syariah.
Dalam penelitian yang lain Al Arif (2015:303) juga menemukan bahwa
pemisahan unit usaha Syariah menjadi bank umum syariah ini menaikkan rasio
biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada industri perbankan
syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan unit usaha syariah
menjadi bank umum syariah menurunkan tingkat efisiensi operasional pada bank
syariah.
Hal yang sama ditunjukan pada penelitian Poerwokoesoemo (2016:160)
terkait kinerja bank konvensional pasca spin off unit usaha syariah pada tahun
2016 menunjukan bahwa terdapat perbedaan kinerja permodalan (CAR), kinerja
kualitas aset (NPL), kinerja profitabilitas (ROA), kinerja profitabilitas (BOPO),
dan kinerja likuiditas (LDR) antara sebelum dan setelah bank konvensional
pemilik Unit Usaha Syariah. Perbedaan tersebut menunjukan adanya kenaikan
pada nilai CAR, BOPO, dan LDR setelah spin off dan adanya penurunan pada
NPL dan ROA dibandingkan nilai sebelum spin off, hasil penelitian ini
menunjukan adanya indikasi penurunan kinerja bank yang melakukan spin off .
Jika melihat pada beberapa penelitian diatas mengenai konsep spin off atau
pemisahan pada industri perbankan syariah, dimana konsep spin off atau
pemisahan ini justru munurunkan kinerja keuangan dari bank hasil spin off .
apabila konsep spin off atau pemisahan ini tetap dipaksakan pada perusahaan
perasuransian syariah yang skala ekonominya kecil daripada industri perbankan
syariah, hal ini dapat berdampak pada tidak produktifnya pengembangan industri
asuransi syariah di Indonesia.

11
Dengan melihat dari berbagai hal yang telah disampaikan sebelumnya,
maka penulis ingin membuat penelitian lebih jauh mengenai evaluasi kebijakan
spin off unit usaha syariah pada perusahaan asuransi yang dijelaskan dalam
Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada industri asuransi
syariah di Indonesia menggunakan metode ARIMA (Autoregresif Integrated
Moving Average), dengan judul “EVALUASI KEBIJAKAN SPIN OFF PADA
INDUSTRI ASURANSI JIWA SYARIAH”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang
dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan pemisahan (spin off) yang sudah diterapkan dari tahun 2014
masih belum menunjukan pengaruh yang berarti terhadap perkembangan
industri asuransi syariah secara umum dan secara khusus pada
perkembangan pangsa pasar (market share) perusahaan perasuransian
syariah di Indonesia.
2. Total aset dan total dana investasi peserta Perasuransian Syariah yang di
dalamnya ada unit usaha syariah masih sangat kecil dari yang ditentukan
dalam Undang-undang no.40 tahun 2014.
3. Merujuk pada konsep spin off atau pemisahan yang sama dengan industri
perbankan syariah, beberapa bank umum syariah yang telah melakukan
pemisahan (spin off) mengalami penurunan kinerja.

12
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap masalah-masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka untuk memfokuskan masalah-
masalah yang akan diteliti dan untuk mendapat hasil yang optimal, diperlukan
perumusan dan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis hanya akan
meneliti tentang evaluasi kebijakan spin off unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi yang dijelaskan dalam Undang-undang No.40 Tahun
2014 tentang Perasuransian pada industri asuransi syariah di Indonesia.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah
kebijakan spin off unit usaha syariah pada perusahaan asuransi yang dijelaskan
dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada industri
asuransi syariah di Indonesia sudah tepat dan memadai ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengevaluasi kebijakan pemisahan pada unit usaha syariah
asuransi jiwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-
undang No.40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Perasuransian.
2. Untuk memprediksi target pertumbuhan yang harus dicapai unit usaha
syariah asuransi jiwa terhadap pertumbuhan perusahaan asuransi
induknya.

13
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagi akademisi, dapat menambah referensi dan wawasan yang lebih luas
tentang kebijakan pemisahan (spin off) serta metode-metode pemisahan
(spin off) dan pengaruhnya terhadap industri asuransi syariah di Indonesia.
b. Bagi lembaga keuangan syariah, dapat menjadi informasi dan bahan
pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pemisahan (spin off) terkait
bagaimana pengaruhnya terhadap industri asuransi syariah di Indonesia,
serta memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan kebijakan
pemisahan (spin off) unit usaha syariah pada perusahaan asuransi
kedepannya.
c. Bagi regulator, dapat menjadi pertimbangan untuk menganalisis kembali
kebijakan pemisahan (spin off) yang telah dibuat apakah sudah tepat
sasaran atau harus dikaji kembali dengan melihat pengaruh kebijakan
tersebut terhadap industri asuransi syariah di Indonesia .
d. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan terkait proses
pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia .
e. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan
dapat menjadi informasi dan referensi serta inspirasi untuk menjadi bahan
masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

14
E. Sistematika Penulisan
Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi
keseluruhan dari penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian yang
di ambil oleh penulis
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menerangkan tentang metode penelitian kuantitafif yang
digunakan seperti studi pustaka, pemaparan tentang data, serta menjelaskan
tentang metode analisis yang dipakai dalam penelitian
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis tentang: analisis deskriptif objek penelitian, hasil
pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.
BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan atas penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini
juga diuraikan mengenai keterbatasan dari penelitian dan saran-saran yang dapat
dijadikan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. LANDASAN TEORI
1. Kebijakan Pemisahan (Spin Off)
a. Definisi Pemisahan (Spin off)
Konsep pemisahan (Spin Off) di Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-
undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 ayat 12, Spin
Off dinyatakan sebagai sebuah pemisahan yang di definisikan sebagai berikut:
“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum
kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan
beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih”
Nasuha (2012:243) dalam penelitiannya tentang dampak kebijakan spin off
terhadap kinerja bank syariah menjelaskan bahwa spin off menggambarkan suatu
tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha
sebelumnya. pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan
perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur
lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepala pemilik
lama kepada induk kepala pemilik baru.
Pengertian pemisahan (spin off) juga dapat ditemukan dalam Black’s Law
Dictionary, yaitu sebagai berikut:
“spin off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes
an independent company and stock of the new company is distributed to the
corporation’s shareholder”.
“Pemisahan adalah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari sebuah
korporasi menjadi perusahaan independen dan saham perusahaan yang baru
didistribusikan kepada pemegang saham korporasi”. (Umam, 2010:609)

16
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemisahan (spin off) adalah
tindakan pemisahan sebuah divisi atau anak usaha dari perusahaan induknya
menjadi sebuah perusahaan tersendiri yang independen yang mengakibatkan
terjadinya peralihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban atau aktiva dan
pasivanya karena hukum. Pemisahan ini dimaksudkan agar unit usaha dapat
mengambil keputusan lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus
bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut.
Dalam kasus pemisahan (Spin Off) perbankan syariah, Ilyas dan
Joyosumarto dalam Al Arif (2018) menyatakan terdapat beberapa alasan
kehadiran aturan mengenai pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum
syariah: Pertama, meningkatkan pertumbuhan dari industri perbankan syariah.
Kedua, meningkatkan independensi bank syariah sehingga akan mampu
meningkatkan kinerja dari bank syariah. Ketiga, meningkatkan kepatuhan
terhadap prinsip syariah. Salah satu cara untuk dapat melihat peningkatan
pertumbuhan industri perbankan syariah adalah dengan melihat pangsa pasar bank
syariah.
Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) menggunakan istilah “Pemisahan” untuk spin off , “Penggabungan”
untuk merger, “Pengambilalihan” untuk akuisisi. Dalam spin off perseroan
beberapa pihak yang harus mendapat perlindungan hukum antara lain nasabah,
karyawan, dan para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan.
Pemegang saham dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan mengingat
proses spin off untuk perseroan bisa terjadi bukan hanya atas kehendak pemegang
saham, namun karena adanya ketentuan Undang-undang yang mewajibkan
pemisahan. Karena dalam perseroan, mekanisme spin off belum diakomodir

17
sebagai salah satu alternatif dalam penguatan struktur perseroan di Indonesia.
(Fred.B.G, 2008:39)
b. Jenis Pemisahan (Spin Off)
Pemisahan (Spin Off) Perseroan Terbatas dikenal ada 2 (dua) jenis
pemisahan (Spin Off), kedua jenis pemisahan tersebut dipengaruhi oleh cara
pemisahan dengan memperhatikan kuantitas usaha yang dipisahkan oleh
perseroan. 2 (dua) jenis pemisahan (Spin Off) tersebut tertera pada Pasal 135 ayat
2 dan 3 UUPT no.40 tahun 2007, yaitu :
1) Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena
hukum kepada 2 (dua) Perseroan Terbatas lain atau lebih yang menerima
peralihan Perseroan Terbatas yang melakukan pemisahan tersebut berakhir
karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini yang menjadi ciri pokok, perseroan
mengalihkan seluruh harta kekayaan, sehingga akan berakibat perseroan harus
ditutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi usaha yang diurusi.
2) Pemisahan tidak murni, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih
karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan Terbatas lain atau lebih yang
menerima peralihan Perseroan Terbatas yang melakukan pemisahan tetap ada
atau berakhir. Dalam pemisahan ini tidak sampai mengakibatkan perseroan
terdahulu menjadi bubar, karena harta kekayaan yang dialihkan hanya
sebagian saja. Perseroan tersebut masih mempunyai harta kekayaan sehingga
masih dapat menjalankan usaha. Berbeda dengan pemisahan murni yang
berakibat perseroan yang melakukan pemisahan menjadi bubar, karena harta
kekayaannya dialihkan seluruhnya.

18
c. Syarat Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off)
Menurut Iswanto (2017:35) terhadap perbuatan hukum pemisahan (Spin Off)
berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan pada pasal 126 ayat (1), sebagaimana
hal nya syarat ini berlaku terhadap penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan. Dengan demikian perbuatan hukum pemisahan (Spin Off) wajib
memperhatikan kepentingan pihak-pihak, sebagai berikut:
1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Menurut penjelasan 126 ayat (1) syarat yang disebutkan dalam ketentuan ini
merupakan penegasan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan
pemisahan tidak bisa dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak
tertentu.
d. Tujuan Kebijakan Pemisahan (Spin Off)
Apabila hanya melihat tujuan, terlihat bahwa kebijakan pemisahan (Spin
Off) yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) sebenarnya
lebih ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan perkembangan perseroan
dalam hal ini melalui pemisahan (Spin Off) dalam Undang-undang Perseroan
Terbatas (UUPT) tersebut induk menjadi anak perseroan. Sebenarnya pengertian
pemisahan (Spin Off) dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut
memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada perseroan untuk melakukan
penguatan restruktur usahanya.
Menurut Bahari (2010:24) penguatan struktur usaha dengan mekanisme
pemisahan (Spin Off), dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai sarana untuk
lebih mempertajam segmentasi pasar, khususnya melalui penguatan lini bisnis

19
yang lebih fokus dan spesialis. Selain dianggap dapat mempertajam suatu nilai
bisnis, mekanisme pemisahan (Spin Off) juga dapat melakukan pemisahan aset
bermasalahnya menjadi bahan usaha baru yang bukan merupakan perseroan
(menjadi semacam perseroan pengelola aset). Dalam hal ini maka keuntungan
bagi perseroan adalah milik perseroan baru menjadi kendaraan pengelola aset
bermasalah yang tetap dapat dikontrolnya, juga menjadi sarana yang efektif bagi
perseroan dalam melakukan pembersihan aset bermasalahnya.
Menurut Wachtell, Lipton, Rose & Katz (2014) tujuan dasar dilakukannya
pemisahan (spin off) oleh korporasi adalah:
1) Meningkatkan Fokus Bisnis. Dalam suatu pemisahan (spin off) setiap entitas
bisnis dapat berkonsentrasi dalam strategi dan rencana operasinya sendiri
tanpa mengalihkan sumber daya manusia atau sumber keuangan dari bisnis
lainnya.
2) Menciptakan Bisnis dengan Struktur Modal yang Lebih Sesuai. Dalam suatu
pemisahan (spin off) setiap entitas bisnis dapat menetapkan struktur
modalnya sendiri yang paling sesuai bagi bisnis dan strateginya. Setiap bisnis
dapat memiliki persyaratan modal berbeda yang mungkin saja tidak dapat
secara optimal dipenuhi hanya melalui satu strutkur modal.
3) Identitas Investasi yang Berbeda. Pemisahan (spin off) menciptakan peluang
investasi yang berbeda dan terarah. Sebuah perusahaan yang
menginvestasikan sumber dayanya hanya pada satu lini bisnis dapat dianggap
lebih transparan dan menarik bagi investor yang fokus pada sektor tertentu
atau pada strategi pertumbuhan, dan oleh karenanya berlawanan dengan
conglomerate discount dan meningkatkan nilai suatu bisnis.

20
4) Memeroleh Keefektifitasan dari Kompensasi Berbasis Ekuitas. Dalam suatu
pemisahan (spin off) akan meningkatkan keefektifan program kompensasi
berbasis ekuitas pada keduanya melalui pengaitan antara nilai kompensasi
ekuitas yang dihadiahkan kepada pegawai, para pejabat dan direktur yang
merupakan penghargaan terhadap kinerja bisnis mereka.
5) Memanfaatkan Ekuitas Sebagai “Mata Uang” Akuisisi. Dengan menciptakan
perdagangan saham kepada publik secara terpisah, suatu pemisahan (spin off)
akan meningkatkan kemampuan bisnis yang mengalami pemisahan (spin off)
untuk memengaruhi akuisisi dengan menggunakan sahamnya sendiri sebagai
pertimbangan.
Intinya tujuan dasar dari pemisahan (spin off) adalah untuk meningkatkan
nilai perusahaan atau dengan kata lain, suatu pemisahan (spin off) akan
berdampak kepada peningkatan kinerja entitas bisnis yang terlibat di dalamnya.
Sama halnya dalam kasus perusahaan perasuransian khususnya perusahaan
perasuransian syariah, pemisahan unit usaha syariah pada perusahaan asuransi
menjadi perusahaan asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan industri asuransi syariah.
Dalam kasus perbankan Nasuha (2012:244) menyatakan alasan pemisahan
(spin off) korporasi bank yang ditempuh sistem perbankan di Indonesia dapat
ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai berikut :
1) Secara ekonomis pemisahan ini memperluas kegiatan usaha UUS menjadi
setara BUS antara lain yaitu menjamin penerbitan surat berharga, penitipan
untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal,
pengurusan dana pensiun, dan menerbitkan, menawarkan serta
memperdagangkan surat berharga jangka panjang.

21
2) Secara ideologis pemisahan ini mendukung pemisahan sistem syariah dari
sistem konvensional. Dengan berpisahnya UUS menjadi BUS maka
lembaga ini terpisah dari induk konvesionalnya dan menumbuhkan
kepercayaan publik khususnya umat Islam akan kemurnian lembaga
keuangan syariah.
2. Konsep Asuransi
a. Definisi Asuransi
Kata asuransi berasal bahasa inggris, insurance yang dalam bahasa
Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa
disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).
Menurut Danarti (2011: 6) Asuransi atau yang dalam bahasa belanda
“verzekering” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi
yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya
akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai
akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula
belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.
Definisi asuransi di Indonesia juga telah di tetapkan dalam Undang-undang
Republik Indonesia no.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian. Asuransi atau
pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,

22
yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Pengertian Asuransi di atas akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal
246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa
asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan
diri kepada seorang yang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.
Menurut Al Arif (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme
perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang
akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan
ganti rugi dari pihak penanggung.
Menurut Rastuti (2011:2) Asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk
menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi)
kerugian-kerugian yang belum pasti. Adapun pendapat lain dari Wirjono
Prodjodikoro yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana
pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima
sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita
oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.
Sementara menurut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu
permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer risiko dengan
membayar sejumlah dana untuk menjauhi risiko kehilangan sejumlah harta yang
dimilikinya.

23
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi
merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana
didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada
pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin
akan terjadi di masa yang akan datang.
b. Unsur-Unsur dalam Asuransi
Berdasarkan definisi asuransi dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur
yang terkandung dalam asuransi, yaitu :
1) Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada
pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2) Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau
santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur
apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3) Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4) Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa
yang tak tertentu.
c. Prinsip Dasar Asuransi
Menurut Danarti (2011:18) ada 6 (enam) macam prinsip dasar yang harus
dipenuhi, yaitu :
1) Insurable Interest
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara
tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2) Utmost good faith
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta
material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta
maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan

24
dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si
tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek
atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3) Proximate Cause
Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang
menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara
aktif dari sumber yang baru dan indeenden.
4) Indemnity
Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam
upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat
sebelum terjadinya kerugian .
5) Subrogation
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6) Contribution
Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama
menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk
ikut memberikan indemnity.
d. Manfaat Asuransi
Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat,
khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko
di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi
masyarakat yang dikemukakan oleh Al Arif (2012:213):
1) Memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh
tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang
mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-

25
benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian
sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
3) Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi
yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki
substansi yang sama dengan tabungan.
4) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan
diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan
premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan
memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam
asuransi tersebut.
5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para
investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa
hal.
6) Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang
seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada
penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas
nilai pertanggungan.
e. Jenis-Jenis Asuransi
Menurut Umi Karomah dalam Dessy Danarti (2011:42), usaha asuransi dapat
dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
Dari segi sifatnya:
1) Asuransi social atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi
warga Negara. Asuransi social adalah program asuransi wajib yang
deselenggarakan pemerintah berdasarkan undang – undang. Maksud dan tujuaa

26
asuransi social adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan
untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh : Askes, Taspen, Asbri dll.
2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk
menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau
tidak Contoh: PT Jasa INDONESIA, PT Jiwasraya dll
Dari segi objek dan bidang usahanya:
1) Asuransi Orang
Asuransi orang meliputi:
a) Asuransi Jiwa
Pada hekekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang – orang yang
menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian,
risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi oleh perusahaan
asuransi , yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan
risiko kepada orang yang mau bekerja sama.
b) Asuransi Kesehatan
Ini adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya
kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh
sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan
yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yaitu rawat inap dan rawat jalan
c) Asuransi Dana Pensiun
Menjadi tua itu pasti, tetapi dalam kondisi seperti apa masa tua nantinya, tentu
masih menjadi pertanyaan karena berada dalam ketidakpastian. Itulah mengapa
diperlukan perencanaan hidup salah satu perencanaan financial untuk masa
pensiun agar hidup tetap terjamin dan tidak membebani orang lain.
Merencanakan tabungan hari tua sebaiknya dilakukan sebelum masa produktif
berakhir.Sebab dimasa tua nanti kita sudah tidak mampu bekerja lagi.Asurandi

27
dan Dana Pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua.
Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita
keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi.
2) Asuransi Umum atau Kerugian
Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan yaitu:
a) Asuransi Kebakaran (Fire Insuranc )
b) Asuransi Paket Rumah Tangga (Home Insurance)
c) Asuransi Paket Toko (Shophause Insurance)
d) Asuransi Prorerty All Risks
e) Asuransi Gempa Bumi (Eartquake Insurance)
f) Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance)
g) Asuransi Aneka (Miscellaneous)
Asuransi Pencurian (Burgery)
Asuransi Uang (Money Insurance)
Asuransi Kecelakaan (Personal Accident)
Asuransi Keluarga (Family Personal Accident)
Asuransi Kesehatan (Health Insurance)
Asuransi Perjalanan (Travel Insurance)
h) Asuransi Jaminan (Bonding/ Guarante)
Jaminan Tender (Bid Bond)
Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

28
3) Perusahaan Reasuransi Umum
Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang
usahanya menanggung risiko yang benar – benar terjadi dari pertanggungan
yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.
4) Perusahaan Asuransi Sosial
Perusahaan asuransi social merupakan perusahaan asuransi yang bidang
usahanya menanggung risiko financial masyarakat kecil yang kurang mampu
perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya: Perum Taspen, PT
Astek dan PT Jasa Raharja.
3. Asuransi Syariah
a. Definisi Asuransi Syariah
Dalam literatur Arab (Fiqh Islam), asuransi dikenal dengan sebutan At-
takaful dan At-tadhamun. Secara literal, At-takaful artinya pertanggungan yang
berbalasan atau saling menanggung, sedangkan At-tadhamun secara harfiah
berarti solidaritas atau hal saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.
Dalam Ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (At-ta’min)
adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu
berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan
jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa
pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. (Rastuti, 2011:3)
Asuransi syariah pada hakikatnya mempunyai artian yang sama akan tetapi
asuransi syariah mengartikan asuransi itu lebih kepada tolong-menolong. Dewan
Syariah Nasional–Majlis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dalam fatwanya no.21
tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan, Asuransi
Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan

29
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Menurut Sula (2004:28) definisi tabarru' adalah sumbangan atau derma
(dalam definis islam adalah Hibah). Sumbangan atau derma (Hibah) atau dana
kebajikan ini diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi syariah jika
sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi
lainnya. Dengan adanya dana tabarru' dari para peserta asuransi syariah ini maka
semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan
demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak
yang menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi, seperti pada asuransi
konvensional.
Dari definisi asuransi syariah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut
dengan “ta’awun” yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas
dasar ukhuwah islamiyah antar sesama anggota peserta asuransi syariah dalam
menghadapi malapetaka (risiko).
b. Prinsip Asuransi Syariah
:
Adapun prinsip umum asuransi syariah sudah ditetapkan dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional–Majlis Ulama Indonesia (DSN – MUI) no.21 tahun
2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, sebagai berikut:
a. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola

30
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang
sesuai dengan syariah.
b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang
tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan
komersial.
d. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
e. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana
kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Dalam pelaksanaan usahanya perusahaan asuransi syariah dilarang untuk
bertransaksi dengan cara-cara yang dilarang dalam transaksi syariah. Menurut
Jundiani (2009:128) larangan-larangan dalam transaksi syariah dan penjabarannya
adalah sebagai berikut:
c. Maysir: Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak
kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah,
namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada
permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda.
d. Gharar: Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan
kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang,
harga, ataupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang.

31
e. Riba: Pertukaran sesama barang ribawi sejenis dengan kadar yang berbeda.
Perbedaan itulah yang disebut riba.
f. Bathil: Akad jual beli atau kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun
penghasilan, namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan
adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika.
g. Ghabn: Penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar tanpa
disadari oleh pembeli.
h. Najash: Penawaran palsu, dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak
secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak
orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut, sehingga orang
ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari
harga sebenarnya.
i. Ikrah: Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk
melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free
consent. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan
keadaan seseorang yang sedang butuh.
j. Bay’ Al Mudtar: Jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam
keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh
pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan
sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.
k. Tadlis: Tindakan seorang penjaga yang sengaja mencampur barang yang
berkualitas baik dengan barang yang sama tetapi berkualitas buruk demi untuk
memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan
“oplos” termasuk dalam kategori ini.

32
l. Ghish: Menyembunyikan informasi tentang barang atau jasa yang akan
diperjualbelikan.
c. Sejarah Asuransi Syariah
Lembaga asuransi yang dikenal pada zaman sekarang sesungguhnya tidak
dikenal pada awal masa Islam, akibatnya banyak literatur dalam Islam yang
menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal.
Walaupun praktik asuransi tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat
beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah SAW yang mengarah
pada prinsip-prinsip asuransi khususnya asuransi syariah. Misalnya konsep
tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem “aqilah”. Sistem aqilah
adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam satu tabungan
bersama yang dikenal sebagai “kunz”. (Gemala,2007:137)
Dalam literatur Islam konsep aqilah yang sering terjadi dalam sejarah pra
Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku
Arab Pra-Islam melakukan pembunuhan, maka si pembunuh dikenakan diyat
(denda) dalam bentuk blood money (uang darah) yang dapat ditanggung oleh
anggota suku yang lain. (Ali,2004)
Kata asuransi sebenarnya tidak ada dalam agama Islam yang dibawa oleh
Rasulullah SAW. Namun, sistem yang mirip dengan asuransi khususnya asuransi
syariah telah dilakukan, yaitu suatu bentuk upaya tolong menolong diantara kaum
muslimin dan sistem inilah yang menjadi bagian sejarah asuransi dalam Islam.
Beberapa istilah yang dikenal dan menjadi dasar asuransi syariah antara lain,
sebagai berikut:
1) Al Aqilah yaitu saling memikul tanggung jawab untuk keluarganya. Jika
salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku lainnya

33
maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat atau denda)
sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat
dari pembunuh disebut aqilah. Lalu mereka mengumpulkan dana yang
diperuntukan untuk membantu keluarga yang teribat dalam pembunuhan
tidak sengaja. Imam Ibnu Hajar Al Asqolani mengemukakan bahwa sistem
aqilah ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari
hadist yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku huzail,
dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga
mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang
dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke
pengadilan. Rasulullah SAW memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi
pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki ataupun
wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah
(diyat atau denda) yang harus dibayar oleh aqilah (saudara pihak ayah) dari
yang tertuduh.
2) An-Tanahud adalah makanan yang dikumpulkan dari peserta safar yang
dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya
kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.
Dalam sebuah riwayat disebutkan “suku asy’ari ketika keluarganya
mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang
mereka miliki dalam satu kumpulan, kemudian dibagi secara merata, mereka
adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka” (HR. Bukhori).
Dalam hal ini makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau
berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama
porsinya atau berbeda-beda.

34
3) Aqad Al-Hirasah adalah kontrak pengawal keselamatan. Dalam Islam terjadi
berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat
lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya,
dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi
keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
4) Dhoman Khatr At-Thariq adalah jaminan keselamatan lalu lintas. Para
pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan
keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan
berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang dan pihak lain
menjaga keselamatan perjalanannya.
Berdasarkan istilah-istilah diatas, para ulama ahli di bidang ilmu fiqh
muamalah berpendapat dan membahas untuk membentuk suatu sistem muamalah
yang serupa asuransi dengan konsep dari istilah tersebut, maka lahirlah istilah
asuransi syariah yang menjadi tonggak sejarah asuransi dalam islam berbasis
ta’awun (tolong menolong) dan tabarru’ (Hibah). Sistem asuransi syariah di
dunia khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim sudah banyak
berkembang. Karena manfaatnya sangat besar, selain itu juga melatih para
anggota untuk selalu bersedekah dan menghibahkan sebagian rejekinya dijalan
yang benar. (Ramadani, 2018:37)
Menurut Masroni dalam Ramadani (2018:38) berikut adalah perjalanan asuransi
syariah di dunia:
1) Tahun 1979 berdiri asuransi syariah pertama Sudan, yaitu Sudanese Islamic
Insurance.

35
2) Tahun 1981 di Swiss berdiri asuransi syariah di yang bernama Dar Al Mal
Al Islamic yang juga memperkenalkan asuransi syariah yang ada di Jenewa.
3) Tahun 1983 di Luksemburg berdiri asuransi syariah yang bernama Islamic
Takafol Company.
4) Tahun 1983 di Kepulauan Bahamas berdiri asuransi syariah yang bernama
Islamic Takafol dan Re-Takafol Company.
5) Tahun 1983 di bahrain berdiri asuransi syariah yang bernama At Takafol Al
Islamiyah.
6) Tahun 1985 berdiri asuransi syariah pertama di Asia yang didirikan oleh
negara Malaysia yang bernama Takaful Malaysia.
7) Tahun 1994 Asuransi Syariah masuk ke Indonesia melalui PT. Syarikat
Takaful Indonesia (STI) dan menjadi bagian dari sejarah asuransi syariah di
Indonesia. Dikenalkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
lewat yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa
Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha muslin
Indonesia.
B. Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang diteliti oleh
penulis. Pada Tabel 2.1 penulis akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang
pernah dilakukan.

36
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Penelitian Isi Penelitian Perbedaan
1. Peneliti:
M Nur Rianto Al Arif,
Nachrowi D Nachrowi,
Mustafa E Nasution,
T.M. Zakir Mahmud
(Jurnal Iqtishadia IAIN
Kudus, Vol. 11 No.1,
2017)
Judul:
Evaluation of the
Spinoffs Criteria: A
Lesson from The
Indonesian Islamic
Banking Industry.
Variabel Penelitian
Independen (X):
Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak
Ketiga, BOPO, pada Bank Umum
Syariah, Dummy (Sebelum dan
Setelah Spin Off) Tingkat Inflasi,
Tingkat Rata-Rata Bunga pada
Bank, dan Tingkat pertumbuhan
ekonomi
Dependen (Y):)
Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak
Ketiga pada Bank Umum Syariah
Metode Penelitian:
Teknik difference in difference,
ARIMA, dan deskriptif kualitatif
Hasil Penelitian:
Kebijakan Pemisahan tidak
memberikan perbedaan terhadap
aset, pembiayaan, dan dana pihak
ketiga. Hasil peramalan
menunjukan bahwa tidak ada
satupun bank sampel yang mampu
Peneliti membahas
evaluasi kebijakan
pemisahan pada
industri asuransi
syariah yang
ditetapkan dalam
Undang-Undang
No.40 Tahun 2014
pasal 87 ayat 1
tentang
Perasuransian

37
mencapai 50% proporsi aset dari
bank induk konvensionalnya. Hal
ini menunjukan kebijakan
pemisahan yang didorong oleh
regulator harus dievaluasi
mengingat skala ekonomi dari
UUS yang masih kecil yang
dimiliki oleh Bank Pembangunan
Daerah (BPD)
2. Peneliti:
M Nur Rianto Al Arif
(Jurnal Keuangan dan
Perbankan Vol.19 no.2,
2015)
Judul:
Keterkaitan Kebijakan
Pemisahan terhadap
Tingkat Efisiensi pada
Indsutri Perbankan
Syariah di Indonesia
Variabel Penelitian
Independen (X):
Variabel dummy pemisahan, Dana
Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan,
total asset, NPF, Marjin deposito 1
bulan dan ROA
Dependen (Y):
Tingkat efisiensi Operasional
(BOPO)
Metode Penelitian:
Uji Regresi Linear
Hasil Penelitian:
Kebijakan Pemisahan berpengaruh
Peneliti membahas
evaluasi kebijakan
pemisahan pada
industri asuransi
syariah yang
ditetapkan dalam
Undang-Undang
No.40 Tahun 2014
pasal 87 ayat 1
tentang
Perasuransian

38
negatif terhadap tingkat efisiensi
operasional (BOPO), artinya
kebijakan pemisahan
menyebabkan penurunan tingkat
efisiensi industri perbankan
syariah. Selain itu, ROA dan
marjin deposito juga memiliki
pengaruh negatif dan signifikan
terhadap BOPO. Sedangkan DPK,
pembiayaan, total asset, dan NPF
tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap BOPO.
3. Peneliti:
Mustica Bintang Sabiti,
Jaenal Effendi, Tanti
Novianti (Jurnal Al-
Muzara’ah Vol.5, No.1,
2017)
Judul:
Efisiensi Asuransi
Syariah di Indonesia
dengan pendekatan Data
Envelopment Analysis
Variabel Penelitian
Independen (X):
Aset, Beban, Pembayaran Klaim
Dependen (Y):
Pendapatan dan Dana tabarru’
yang diperoleh
Metode Penelitian:
Metode Data Envelopment Analysis
(DEA)
Hasil Penelitian:
Peneliti membahas
evaluasi kebijakan
pemisahan pada
industri asuransi
syariah yang
ditetapkan dalam
Undang-Undang
No.40 Tahun 2014
pasal 87 ayat 1
tentang
Perasuransian

39
Perusahaan asuransi jiwa syariah
dan asuransi umum syariah di
Indonesia belum mencapai tingkat
efisien. Secara umum kinerja
efisiensi perusahaan asuransi jiwa
syariah di Indonesia mencapai
tingkat efisiensi rata-rata 0.82
untuk efisiensi teknis, efisiensi
teknis murni 0.86 dan efisiensi
skala sebesar 0.94. Begitu pula
pada perusahaan asuransi umum
syariah mencapai tingkat efisiensi
dengan skor efisiensi teknis
keseluruhan sebesar 0.71, efisiensi
teknis murni sebesar 0.80 dan
efisiensi skala sebesar 0.89. Oleh
karena itu baik perusahaan
asuransi jiwa syariah maupun
asuransi umum syariah harus
meningkatkan efisiensinya agar
mampu bersaing dalam industri
asuransi nasional.

40
4. Peneliti:
Sari Ramadani
(Skripsi,2018)
Judul:
Respon Unit Usaha
Syariah Di Indonesia
Terhadap Kebijakan
Spin Off yang Diatur
dalam Undang-Undang
Republik Indonesia
No.40 Tahun 2014 Dan
POJK No.67 Tahun
2016 (Studi Kasus pada
PT Asuransi Adira
Dinamika Unit Syariah)
Variabel Penelitian
Metode Penelitian:
Metode Survei (Data primer
dengan melakukan wawancara)
Teknik Penelitian:
Analisis data secara deskriptif
Hasil Penelitian:
Unit Syariah pada perusahaan
asuransi Adira Dinamika belum
siap melakukan spin off ,
dikarenakan peraturan pada
Undang-Undang no.40 tahun 2014
dinilai memberatkan bagi pelaku
bisnis syariah atau perusahaan
asuransi dengan unit syariah.
Peneliti membahas
evaluasi kebijakan
pemisahan pada
industri asuransi
syariah yang
ditetapkan dalam
Undang-Undang
No.40 Tahun 2014
pasal 87 ayat 1
tentang
Perasuransian
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dibuat oleh peneliti untuk memberikan gambaran
sistematis penelitian ini, dimana telah peneliti bahas sebelumnya bahwa penelitian ini
adalah penelitian yang menganalisa evaluasi kebijakan pemisahan (spin off) yang
ditetapkan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang
Perasuransian dengan memprediksi dana tabarru’ dan dana investasi pada unit usaha
syariah pada perusahaan asuransi pada tahun 2024 apakah sudah bisa mencapai 50%
dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada

41
perusahaan induknya atau belum, analisa prediksi dalam penelitian ini menggunakan
metode Box-Jenkins atau ARIMA. Jika dituangkan dalam bentuk skema, kerangka
pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
Tidak Ya
Dana tabarru’ dan Dana investasi
Unit Usaha Syariah Asuransi Jiwa
Estimasi Parameter Model
Identifikasi Model Pemilihan
p, d, q secara tentatif
Prediksi
Uji Diagnosis
Pendekatan ARIMA

42
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah
dengan menguji parsial masing-masing model ARIMA untuk mencapai model
yang terbaik dan dapat ditemukan prediksi di masa yang akan datang pada industri
asuransi syariah khususnya pada perusahaan perasuransian jiwa syariah. Sehingga
ditarik hipotesis atau dugaan sementara (H0), sebagai berikut:
H0 : Dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi jiwa mampu mencapai 50% dari total nilai dana asuransi,
dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya pada
tahun 2024 dengan pendekatan model ARIMA.

43
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode peramalan
(forecasting), hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kelayakan kebijakan spin off yang mewajibkan unit usaha syariah pada perusahaan
asuransi menjadi perusahaan asuransi syariah apabila dana tabarru’ dan dana
investasi peserta telah mencapai 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’,
dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 tahun setelah
disahkannya kebijakan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang
No.40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Perasuransian. Metode peramalan
(forecasting) ini dilakukan untuk melihat dalam waktu 10 tahun setelah Undang-
undang ini diberlakukan yaitu pada tahun 2024, apakah dana tabarru’ dan dana
investasi peserta dari unit usaha syariah pada perusahaan asuransi telah mencapai
50% nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta dari perusahaan
induknya. Serta dengan mempergunakan teknik ini akan dilakukan peramalan
(forecasting) berapakah nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta dari unit
usaha syariah pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah pada
tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Menurut Sugiyono
(2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,

44
analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan.
Penelitian ini menggunakan data nilai dana tabarru’ dan dana investasi
peserta dari unit usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa dibandingkan dengan
nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta dari perusahaan
induknya, dimana data yang dipergunakan berasal dari laporan keuangan publikasi
perusahaan asuransi jiwa.
B. Metode Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia. Pengambilan sampel pada
penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling atau teknik yang
dilakukan berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan
sampel yang representatif sesuai dengan kriteria berikut:
1. Unit usaha syariah dalam perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan.
2. Unit usaha syariah dalam perusahaan asuransi jiwa tersebut memiliki laporan
keuangan publikasi dari tahun 2010 sampai tahun 2018.
3. Dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha syariah pada perusahaan
asuransi jiwa diatas 1 Triliun rupiah pada tahun 2018.
Setelah dilakukan seleksi dengan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 4
unit usaha syariah dalam 4 perusahaan asuransi jiwa yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini, sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

45
Tabel 3.1 Sampel Penelitian
No Unit Usaha Syariah Dana Peserta Tahun 2018
(dalam jutaan rupiah)
1. PT. Asuransi Jiwa AIA Rp 6.995.341
2. PT. Asuransi Jiwa PRUDENTIAL Rp 6.574.212
3. PT. Asuransi Jiwa ALLIANZ Rp 2.194.631
4. PT. Asuransi Jiwa AXA MANDIRI Rp 1.144.798
Sumber: Data diolah
C. Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang
merupakan data berupa angka-angka yang memiliki satuan hitung dan dapat
dihitung secara matematis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Menurut Indriantoro dan
Supomo (2013:143) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan
keuangan publikasi 4 unit usaha syariah dalam 4 perusahaan asuransi jiwa dari
tahun 2010 sampai tahun 2018, data dapat diunduh melalui laporan publikasi situs
(website) masing-masing perusahaan asuransi. Peneliti juga melakukan penelitian
pustaka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti melalui buku, jurnal, laporan penelitian, tesis, artikel, dan perangkat lain
yang berkaitan dengan penelitian ini.

46
D. Metode analisis data
Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu menggunakan
pendekatan model ARIMA. Model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
prediksi nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta dari unit usaha syariah
pada perusahaan asuransi jiwa pada tahun 2024. Adapun penjelasannya sebagai
berikut :
1. Uji Stasioner
Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu harus dilihat apakah runtun
waktu (time series) yang digunakan sudah stasioner. Untuk itulah dibutuhkan
uji formal dalam menentukan stasioneritas data. Ada dua macam pengujian
secara formal yang dapat dilakukan, yaitu Korelogram atau Unit Root Test
(Nachrowi, 2006:346). Dalam penelitian ini menggunakan Korelogram. Jika
suatu variabel data mengandung unit root maka data tersebut tidak stasioner.
Jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner maka data tersebut harus di-
difference (beda) tingkat pertama (first difference). Kalaupun belum juga
stasioner maka data tersebut di-difference (beda) tingkat kedua (second
difference).
2. Metode Box-Jenkins
Model Box-Jenkins merupakan salah satu teknik peramalan model time
series yang hanya berdasarkan perilaku data variabel yang diamati (let the
data speak for themselves). Model Box-Jenkins ini secara umum dikenal
dengan sebagai model autoregressive integrated moving average (ARIMA).
Analisis ini berbeda dengan model struktural baik model kausal maupun

47
simultan dimana persamaan model tersebut menunjukkan hubungan antara
variabel-variabel ekonomi (Widarjono, 2009:275).
Teknik Box-Jenkins sebagai teknik peramalan berbeda dengan
kebanyakan model peramalan yang ada. Didalam model ini tidak ada asumsi
khusus tentang data historis dari runtut waktu, tetapi menggunakan metode
literatif untuk menentukan model yang terbaik. Model yang terpilih kemudian
akan dicek ulang dengan data historis apakah telah menggambarkan data
dengan tepat. Model terbaik akan diperoleh jika residual antara model
peramalan dan data historis kecil, didistribusikan secara random dan
independen. Namun bila model yang dipilih tidak mampu menjelaskan dengan
baik maka proses penentuan model perlu diulangi. Model Box-Jenkins ini
terdiri dari beberapa model yaitu autoregressive (AR), moving average (MA),
autoregressive-moving average (ARMA) dan autoregressive integrated
moving average (ARIMA) (Widarjono, 2009:275).
a. Model Autoregressive (AR)
Model pertama ARIMA adalah model autoregressive (AR)
menunjukkan nilai prediksi variabel dependen Yt hanya merupakan
fungsi linier dan sejumlah Yt aktual sebelumnya. Misalnya nilai variabel
dependen Yt hanya dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut satu periode
sebelumnya atau kelambanan pertama maka model tersebut disebut
model autoregressive tingkat pertama atau disingkat AR (1) (Widarjono,
2009:276).

48
b. Model Moving Average (MA)
Model kedua ARIMA adalah model moving average (MA),
model ini menyatakan bahwa nilai prediksi variabel dependen Yt hanya
dipengaruhi oleh nilai residual periode sebelumnya. Misalnya jika nilai
variabel dependen Yt hanya dipengaruhi oleh nilai residual satu periode
sebelumnya maka disebut dengan model MA tingkat pertama atau
disingkat dengan MA (1). Model MA adalah model prediksi variabel
dependen Y berdasarkan kombinasi linear dari residual sebelumnya
sedangkan model AR memprediksi variabel Y didasarkan pada nilai Y
sebelumnya (Widarjono, 2009:277)
c. Model Autoregressive-Moving Average (ARMA)
Seringkali suatu data time series dapat dijelaskan dengan baik
melalui penggabungan antara model AR dan model MA. Model
gabungan ini disebut Autoregressive-Moving Average (ARMA).
Misalnya nilai variabel dependen Yt dipengaruhi oleh kelambanan
pertama Yt dan kelambanan tingkat pertama residual maka modelnya
disebut dengan model ARMA (1,1) (Widarjono, 2009:277).
d. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA).
Model AR, MA dan ARMA sebelumnya mensyaratkan bahwa
data time series yang diamati mempunyai sifat stasioner. Data time series
dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria yaitu data time series
mempunyai rata-rata, varian dan kovarian yang konstan. Namun dalam
kenyataannya data time series seringkali tidak stasioner namun stasioner
pada proses diferensi (difference). Proses diferensi adalah suatu proses

49
mencari perbedaan antara data satu periode dengan periode yang lainnya
secara berurutan. Data yang dihasilkan tingkat pertama. Jika kemudian
melakukan diferensi data diferensi tingkat pertama akan menghasilkan
data diferensi tingkat kedua dan seterusnya (Widarjono, 2009:277)
Seandainya data time series yang kita gunakan tidak stasioner dalam
level maka data tersebut kemungkinan menjadi stasioner melalui proses
diferensi atau dengan kata lain jika data tidak stasioner pada level maka perlu
dibuat stasioner pada tingkat diferensi (difference). Model dengan data yang
stasioner melalui proses differencing ini disebut model ARIMA. Dengan
demikian, jika data stasioner pada proses differencing d kali dan
mengaplikasikan ARMA (p,q), maka modelnya ARIMA (p,d,q) dimana p
adalah tingkat AR, d tingkat proses membuat data menjadi stasioner dan q
merupakan tingkat MA (Widarjono, 2009:277).
Menurut Widarjono (2009:278), langkah-langkah yang harus diambil di
dalam menganalisis data dengan menggunakan teknik Box Jenkins secara
detail sebagai berikut:
Gambar 3. 1 Metodologi ARIMA
Tidak Ya
Sumber: Widarjono (2009:278)
Identifikasi Model Pemilihan
p, q, d secara tentatif
Estimasi Parameter Model
Uji Diagnosis
Prediksi

50
a. Tahap Identifikasi
Dalam identifikasi ini ditentukan nilai p, d, dan q. Dalam tahap
identifikasi, digunakan fungsi estimasi fungsi otokolerasi dan fungsi
otokolerasi parsial (ACF dan PACF).
1) Fungsi Otokolerasi Parsial
ACF merupakan mengukur kolerasi antar pengamatan dengan
lag ke-k. Sedangkan PACF merupakan pengukuran kolerasi antar
pengamatan dengan lag ke-k dan dengan mengontrol kolerasi antar
dua pengamatan dengan lag kurang dari k atau dengan kata lain,
PACF adalah kolerasi antara yt dan yt-k setelah menghilangkan efek
yt yang terletak di antara kedua pengamatan tersebut. Fungsi kolerasi
parsial ini hanya diharapkan dapat membantu dalam menentukan
orde dari proses AR.
2) Identifikasi Orde dan Model
Setelah mengetahui PACF, sekarang menggunakan ACF dan
PACF yang didapat untuk menentukan model ARIMA. Caranya
adalah dengan mencocokan pola ACF dan PACF berdasarkan data
yang kita gunakan untuk membuat fungsi tersebut, dengan pola
model standar seperti AR(1), MA(2), ARMA(1,1), ARMA(2,2) dan
seterusnya. Bila pola yang sedang dianalisis cocok dengan salah satu
pola model standar tersebut dijadikan model pilihan. Tetapi, model
terpilih masih perlu dilakukan tes diagnostik unutk mengetahui
apakah model terpilih memang akurat atau cocok dengan data yang
dimiliki.

51
Cara yang dilakukan dalam menetapkan nilai p, d, dan q dilakukan
dengan berbagai cara, salah satumnya jika tanpa proses differencing d
diberi nilai 0, jika menjadi stasioner setelah first order differencing d
bernilai 1 dan seterusnya. Dalam memilih berapa p dan q dapat dibantu
dengan menduga dan menentukan bentuk model ARMA yang diduga
tersebut dapat menggambarkan sifat-sifat data dengan membandingkan
plot ACF/PACF dengan sifat-sifat fungsi ACF/PACF dari model ARMA
seperti pada Tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Sifat-sifat ACF/PACF dari Model ARMA
Sampel ACF Sampel PACF Proses
Tidak ada yang melewati
batas minmal pada log > 0
Tidak ada yang melewati
batas minmal pada log > 0
White
Noise
Meluruh menuju nol secara
eksponensial
Di atas batas interval
maksimum sampai log ke-p
dan dibawah batas pada
log > p
AR (p)
Di atas batas interval
maksimum sampai log ke-p
dan dibawah batas pada
log > q
Meluruh menuju nol secara
eksponensial MA (q)
Meluruh menuju nol secara
eksponensial
Meluruh menuju nol secara
eksponensial
ARMA
(p,q)
Sumber : Rosadi (2012)
Dalam praktik pola autocorrelation dan partial autocorrelation
seringkali tidak menyerupai salah satu dari pola yang ada pada Tabel itu
karena adanya variasi sampling. Kesalahan memilih p dan q bukan

52
merupakan masalah, dan akan dimengerti setelah tahap diagnostic
checking.
b. Tahap Estimasi Model ARIMA
Setelah p dan q ditentukan, tahapan berikutnya adalah
mengestimasi parameter AR dan MA yang ada pada model. Estimasi ini
bisa menggunakan teknik kuadrat terkecil sederhana maupun dengan
metode estimasi tidak linier.
1) Tahap Tes Diagnostik
Setelah model ARIMA ditentukan dan parameternya telah
diestimasi, maka kemudian harus melihat apakah model yang terpilih
cocok dengan data atau tidak. Siapa tahu ada model ARIMA lain
yang lebih cocok atau sama cocoknya dengan model yang terpilih.
Salah satu tes yang dapat dilakukan adalah dengan mengamati apakah
residual dari model terestimasi merupakan white noise atau tidak. Jika
residual berupa white noise, berarti model terpilih cocok dengan data.
Sebaliknya bila residual tidak berupa white noise, berarti model
terpilih bukan merupakan model yang cocok. Akibatnya, kita harus
melakukan pilihan ulang dari awal lagi. Oleh sebab itulah, metode
Box-Jenkins disebut juga proses iterasi.
c. Tahap Peramalan
Peramalan baru dibuat setelah modelnya lolos tes diagnostik.
Peramalan ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari persamaan
berdasarkan koefisien-koefisien yang didapat, sehingga kita dapat

53
menentukan kondisi di masa yang akan datang. Masalah ini akan lebih
mudah dibicarakan berdasarkan contoh kasus.

54
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini, akan diuraikan hal-hal mengenai data-data yang sudah
dikumpulkan, hasil olahan data tersebut, beserta pembahasan.
A. Analisis Deskriptif Statistik
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data share dari dana
tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha syariah pada perusahaan asuransi
jiwa di Indonesia, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan asuransi
jiwa yang memiliki unit usaha syariah dan memenuhi kriteria yang diperlakukan
dengan tujuan penerapan operasional variabel dengan teknik purposive sampling
yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan asuransi jiwa dengan unit
usaha syariah yang dijadikan objek penelitian sebanyak 4 perusahaan asuransi
jiwa yang datanya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Data diperoleh dari laporan
keuangan tahunan masing-masing perusahaan asuransi jiwa yang dipublikasikan
melalui situs (website) masing-masing perusahaan asuransi jiwa.
B. Analisis Deskriptif Objek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan kebijakan
pemisahan yang dijelaskan dalam Undang-undang no.40 tahun 2014 tentang
Perasuransian pasal 87 ayat (1) yang menyatakan:
“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi memiliki unit
usaha syariah dengan nilai Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta telah
mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi,
Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta pada perusahaan induknya atau 10
(sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, Perusahaan Asuransi

55
atau Perusahaan Reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan (spin off) unit
usaha syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi Syariah”.
Beberapa hal penting yang harus digaris bawahi dalam Undang-undang
tersebut adalah unit usaha syariah pada perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi wajib melakukan spin off jika dana tabarru’ dan dana investasi
peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total dana
asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya
atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tersebut yaitu
pada tahun 2024. Sedangkan pada kenyataannya hingga tahun 2018 belum ada
unit usaha syariah pada perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa yang
mencapai 50% dari total dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta
pada perusahaan induknya, bisa dibuktikan dalam data 4 unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi jiwa dengan dana tabarru’ dan dana investasi peserta diatas
1 triliyun di tahun 2018 pada Tabel 4.1.

56
Tabel 4.1 Data share dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha
syariah terhadap perusahaan asuransi jiwa induknya
TAHUN AIA
PRUDENTIAL
ALLIANZ AXA
MANDIRI
2010 0.32 % 5.65 % 5.08 % 7.35 %
2011 0.67 % 5.88 % 4 % 6.05 %
2012 1.64 % 6.75 % 4.22 % 5.50 %
2013 4.03 % 8.98 % 5.02 % 5.29 %
2014 7.37 % 9.13 % 5.46 % 4.51 %
2015 10.20 % 9.97 % 5.85 % 4.26 %
2016 13.17 % 9.71 % 6.75 % 4.54 %
2017 13.59 % 9.35 % 6.77 % 4.27 %
2018 13.37 % 9.12 % 6.92 % 4.27 %
Sumber : Data diolah
Berdasarkan data dalam Tabel 4.1 share dana tabarru’ dan dana investasi
peserta unit usaha syariah terhadap perusahaan asuransi jiwa induknya paling
tinggi yaitu sebesar 13,59% pada perusahaan asuransi jiwa AIA pada tahun
2017. Sedangkan dalam Undang-undang disebutkan unit usaha syariah wajib
melakukan spin off jika Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta telah
mencapai paling sedikit 50% dari total dana asuransi, dana tabarru’, dan dana
investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak
diundangkannya Undang-undang yaitu pada tahun 2024.
C. Analisis Pengujian Box-Jenkins (ARIMA)
Model ARIMA merupakan model yang menggunakan series-nya sendiri
untuk melakukan peramalan. Model ARIMA ini sangat cocok untuk permalan
(forecasting) jangka pendek. Ada beberapa tahapan dalam permodelan yaitu
pertama adalah identifikasi model. Kedua adalah estimasi AR dan MA dalam

57
model. Selanjutnya melakukan tes diagnostik untuk mengetahui model yang
terpilih cocok dengan data atau tidak. Terakhir melakukan peramalan
(forecasting) untuk menentukan kondisi di masa yang akan datang. (Arifiani,
2009:50)
1. Tahap Identifikasi
Dalam tahap identifikasi ini ditentukan nilai p, d, dan q, dengan
menggunakan estimasi fungsi otokolerasi dan fungsi otokolerasi parsial
(ACF dan PACF) dalam correlogram berdasarkan tingkat data yang telah
dinyatakan stasioner. Pengujian stasioner dilakukan untuk masing-masing
variabel melalui correlogram setiap variabel.
Gambar 4.I Hasil Correlogram AIA (Tingkat Level)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat level menunjukkan grafik autokorelasi
yang menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menurun secara
signifikan pada lag 3. Hal ini ditunjukkan juga nilai AC yang mengalami
penurunan dari 0,764 menjadi 0,415, dan dilag ke-3 menjadi 0,018, dst. Pada
grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik masih terdapat nilai
diluar garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data belum stasioner. Salah
satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan proses differencing.

58
Gambar 4.II Hasil Correlogram AIA (Tingkat Df 1)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat df 1 menunjukkan grafik autokorelasi yang
menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menurun secara signifikan
pada lag 3. Pada grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik
berada didalam garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data sudah bersifat
stasioner. Berdasarkan hasil pada gambar 4.2 dapat diperkirakan model
prediksi variabel AIA adalah sebagai berikut: ARIMA (3,1,3);
ARIMA(3,1,1); dan ARIMA (1,1,1).
Gambar 4.III Hasil Correlogram PRUDENTIAL (Tingkat Level)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat level menunjukkan grafik autokorelasi
yang menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menurun secara
signifikan pada lag 3. Hal ini ditunjukkan juga nilai AC yang mengalami
penurunan dari 0,687 menjadi 0,280 dan dilag ke-3 menjadi -0,135, dst. Pada

59
grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik sudah berada didalam
garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data sudah stasioner. Berdasarkan
hasil pada gambar 4.6 dapat diperkirakan model prediksi variabel
PRUDENTIAL adalah sebagai berikut: ARIMA (1,0,0) ; ARIMA(1,0,1);
dan ARIMA (0,0,1).
Gambar 4.IV Hasil Correlogram ALLIANZ (Tingkat Level)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat level menunjukkan grafik autokorelasi
yang menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menurun secara
signifikan pada lag 3. Hal ini ditunjukkan juga nilai AC yang mengalami
penurunan dari 0,687 menjadi 0,280 dan dilag ke-3 menjadi -0,136, dst. Pada
grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik masih terdapat nilai
diluar garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data belum stasioner. Salah
satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan proses
differencing.

60
Gambar 4.V Hasil Correlogram ALLIANZ (Tingkat Df 1)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat df 1 menunjukkan grafik autokorelasi yang
menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menjadi negatif dilag 3.
Pada grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik berada didalam
garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data sudah bersifat stasioner.
Berdasarkan hasil pada gambar 4.4 dapat diperkirakan model prediksi
variabel ALLIANZ adalah sebagai berikut: ARIMA (3,1,3) ; ARIMA(3,1,0);
dan ARIMA (0,1,3).
Gambar 4.VI Hasil Correlogram AXA MANDIRI (Tingkat Level)
Sumber: Data diolah
Correlogram pada tingkat level menunjukkan grafik autokorelasi
yang menurun secara perlahan dimulai pada lag 2 dan menurun secara
signifikan pada lag 3. Hal ini ditunjukkan juga nilai AC yang mengalami
penurunan dari 0,519 menjadi 0,247 dan dilag ke-3 menjadi 0,071 dst. Pada
grafik autokorelasi parsial menunjukkan batang grafik sudah berada didalam

61
garis Bartlett (garis putus-putus) sehingga data sudah stasioner. Berdasarkan
hasil pada gambar 4.5 dapat diperkirakan model prediksi variabel AXA
MANDIRI adalah sebagai berikut: ARIMA (1,0,0) ; ARIMA(1,0,1); dan
ARIMA (0,0,1).
2. Estimasi Model ARIMA
Tahap selanjutnya adalah estimasi parameter model ARIMA untuk
menentukan nilai koefisien (p,d,q) berdasarkan ordo maksimal tentatif pada
setiap variabel. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan model yang tepat
yang akan dipilih dalam penelitian ini. Masing-masing variabel di estimasi
untuk mendapatkan model yang tepat untuk peramalan (forecasting).
Pemilihan model ARIMA terbaik juga dapat dilihat dari nilai Akaike Info
Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SIC). Model dengan nilai AIC dan
SIC yang lebih kecil, maka memiliki kualitas yang lebih baik dan model
itulah yang sebaiknya dipilih (Wahyu, 2007: 31)
Tabel 4.2 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi AIA
Model
ARIMA Parameter Koefisien Prob. AIC SIC
(3,1,3)
Constant
AR(3)
MA(3)
1.952079
-0.999851
0.970468
0.0040
0.0000
0.0004
3,793 3,832
(3,1,1)
Constant
AR(3)
MA(1)
1.999491
-0.882451
-0.995805
0.0004
0.0678
0.9940
3,869 3,909
(1,1,1)
Constant
AR(1)
MA(1)
1.376390
0.340515
0.442320
0.2968
0.7649
0.7019
3.925 3.965
Sumber : Data Diolah

62
Dari hasil estimasi berbagai model prediksi yang dilakukan untuk
mendapatkan model ARIMA yang terbaik agar mendapatkan peramalan yang
tepat untuk variabel AIA. Model ARIMA (3,1,3) adalah yang terbaik, dapat
dilihat pada Tabel 4.2 nilai probabilitas pada model ARIMA (3,1,3) sangat
kecil kurang dari 5%, sehingga sudah signifikan pada α = 5%. Dibandingkan
dengan model (3,1,1) dan model (1,1,1) yang nilai probabilitasnya lebih
besar dari 5% atau tidak signifikan pada α = 5%.
Nilai AIC dan SIC pada model (3,1,3) juga lebih kecil dibandingkan
2 model lainnya, maka ditetapkan bahwa model ARIMA yang terbaik untuk
variabel AIA adalah model ARIMA (3,1,3). Persamaan untuk model ARIMA
(3,1,3) pada variabel AIA yaitu:
yt = (1 – ρ1) δ + (1 + ρ1) yt-1 – ρ1 yt-2 + εt + θ1 εt-1
Berdasarkan ouput, kita telah mengetahui bahwa:
AR (3) = ρ1 = -0.999851
MA (3) = θ1 = 0.970468
C = δ = 1.952079
Maka persamaan untuk model ARIMA (3,1,3) yaitu :
yt = (1+ 0.999851) 1.952079 + (1- 0.999851) yt-1 + 0.999851yt-2 + 0.970468

63
Tabel 4.3 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi PRUDENTIAL
Model
ARIMA Parameter Koefisien Prob. AIC SIC
(1,0,1)
Constant
AR(1)
MA(1)
7.834556
0.793408
0.276425
0.0302
0.3936
0.8727
3.524 3.611
(1,0,0) Constant
AR(1)
7.770530
0.856127
0.0019
0.0500
3.411 3.476
(0,0,1) Constant
MA(1)
8.160443
0.705159
0.0003
0.4979
3.833 3.8985
Sumber : Data Diolah
Dari hasil estimasi berbagai model prediksi yang dilakukan untuk
mendapatkan model ARIMA yang terbaik agar mendapatkan peramalan yang
tepat untuk variabel PRUDENTIAL. Model ARIMA (1,0,0) atau AR (1)
adalah yang terbaik, dapat dilihat pada Tabel 4.5 nilai probabilitas pada
model ARIMA (1,0,0) adalah sebesar 5%, sehingga sudah signifikan pada α
= 5%. Dibandingkan dengan model (1,0,1) dan model (0,0,1) yang nilai
probabilitasnya lebih besar dari 5% atau tidak signifikan pada α = 5%.
Nilai AIC dan SIC pada model (1,0,0) juga lebih kecil dibandingkan
2 model lainnya, maka ditetapkan bahwa model ARIMA yang terbaik untuk
variabel PRUDENTIAL adalah model ARIMA (1,0,0) atau AR (1).
Persamaan untuk model ARIMA (1,0,0) pada variabel PRUDENTIAL yaitu:
yt = (1 – ρ1) δ + (1 + ρ1) yt-1 – ρ1 yt-2 + εt
Berdasarkan ouput, kita telah mengetahui bahwa:
AR (1) = ρ1 = 0.856127
C = δ = 7.770530

64
Maka persamaan untuk model ARIMA (1,0,0) yaitu :
yt = (1 - 0.856127) 7.770530 + (1 + 0.856127) yt-1 - 0.856127yt-2 + εt
Tabel 4.4 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi ALLIANZ
Model
ARIMA Parameter Koefisien Prob. AIC SIC
(3,1,3)
Constant
AR(3)
MA(3)
0.248230
-0.999677
0.992353
0.6342
0.0000
0.0374
2.703 2.743
(1,1,3)
Constant
AR(3)
MA(1)
5.693618
0.838186
-1.000000
0.0002
0.3096
1.0000
2.761 2.849
(3,1,1)
Constant
AR(1)
MA(1)
5.667537
-0.167037
1.000000
0.0001
0.9096
1.0000
2.995 3.083
Sumber : Data Diolah
Dari hasil estimasi berbagai model prediksi yang dilakukan untuk
mendapatkan model ARIMA yang terbaik agar mendapatkan peramalan yang
tepat untuk variabel ALLIANZ. Model ARIMA (3,1,3) adalah yang terbaik,
dapat dilihat pada Tabel 4.3 nilai probabilitas pada model ARIMA (3,1,3)
sangat kecil kurang dari 5%, sehingga sudah signifikan pada α = 5%.
Dibandingkan dengan model (1,1,3) dan model (3,1,1) yang nilai
probabilitasnya lebih besar dari 5% atau tidak signifikan pada α = 5%.
Nilai AIC dan SIC pada model (3,1,3) juga lebih kecil dibandingkan
2 model lainnya, maka ditetapkan bahwa model ARIMA yang terbaik untuk
variabel ALLIANZ adalah model ARIMA (3,1,3). Persamaan untuk model
ARIMA (3,1,3) pada variabel ALLIANZ yaitu:
yt = (1 – ρ1) δ + (1 + ρ1) yt-1 – ρ1 yt-2 + εt + θ1 εt-1

65
Berdasarkan ouput, kita telah mengetahui bahwa:
AR (3) = ρ1 = -0.999677
MA (3) = θ1 = 0.992353
C = δ = 0.248230
Maka persamaan untuk model ARIMA (3,1,3) untuk yaitu :
yt = (1 + 0.999677) 0.248230 + (1 - 0.999677) yt-1 + 0.999677yt-2 + 992353
Tabel 4.5 Hasil Estimasi ARIMA Model Prediksi AXA MANDIRI
Model
ARIMA Parameter Koefisien Prob. AIC SIC
(1,0,1)
Constant
AR(1)
MA(1)
0.847956
0.941935
-1.000000
0.0018
0.6657
1.0000
3.705 3.793
(1,0,0) Constant
AR(1)
5.574766
0.897380
0.073
0.0136
2.632 2.698
(0,0,1) Constant
MA(1)
5.234155
1.000000
0.0002
1.0000
2.841 2.907
Sumber : Data Diolah
Dari hasil estimasi berbagai model prediksi yang dilakukan untuk
mendapatkan model ARIMA yang terbaik agar mendapatkan peramalan yang
tepat untuk variabel AXA MANDIRI. Model ARIMA (1,0,0) atau AR (1)
adalah yang terbaik, dapat dilihat pada Tabel 4.4 nilai probabilitas pada
model ARIMA (1,0,0) kurang dari 5%, sehingga sudah signifikan pada α =
5%. Dibandingkan dengan model (1,0,1) dan model (0,0,1) yang nilai
probabilitasnya lebih besar dari 5% atau tidak signifikan pada α = 5%.
Nilai AIC dan SIC pada model (1,0,0) juga lebih kecil dibandingkan
2 model lainnya, maka ditetapkan bahwa model ARIMA yang terbaik untuk

66
variabel AXA MANDIRI adalah model ARIMA (1,0,0) atau AR (1).
Persamaan untuk model ARIMA (1,0,0) pada variabel AXA MANDIRI
yaitu:
yt = (1 – ρ1) δ + (1 + ρ1) yt-1 – ρ1 yt-2 + εt
Berdasarkan ouput, kita telah mengetahui bahwa:
AR (1) = ρ1 = 0.897380
C = δ = 5.574766
Maka persamaan untuk model ARIMA (1,0,0) yaitu :
yt = (1 - 0.897380) 5.574766+ (1 + 0.897380) yt-1 - 0.897380yt-2 + εt
Setelah dilakukan estimasi prediksi model ARIMA pada setiap
variabel, ditemukan model yang paling terbaik untuk digunakan dalam tahap
peramalan (forecasting) setiap variabel pada Tabel
Tabel 4.6 Model ARIMA Terbaik
No Variabel Model ARIMA
1 AIA 3,1,3
2 PRUDENTIAL 1,0,0
3 ALLIANZ 3,1,3
4 AXA MANDIRI 1,0,0
Sumber: Data diolah
3. Tahap Peramalan (Forecasting)
Setelah mendapatkan model ARIMA yang terbaik, maka tahap
selanjutnya adalah tahap peramalan. Dalam penelitian ini dilakukan
peramalan pada 4 variabel, yaitu : AIA, ALLIANZ, AXA MANDIRI, dan
PRUDENTIAL untuk melihat tingkat share dana tabarru’ dan dana
investasi peserta unit usaha syariah terhadap total dana asuransi, dana

67
tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya pada tahun
2019 sampai dengan tahun 2024.
Tabel 4.7 Hasil Peramalan ARIMA dari tahun 2019-2024
TAHUN AIA PRUDENTIAL ALLIANZ AXAMANDIRI
2019 15,74% 7,24% 6,51% 6,24%
2020 18,89% 7,32% 6,87% 6,17%
2021 21,58% 7,38% 7,12% 6,11%
2022 23,21% 7,44% 7,32% 6,06%
2023 23,96% 7,49% 7,46% 6,01%
2024 25,17% 7,53% 7,71% 5,96%
Sumber : Data diolah
Berdasarkan hasil peramalan pada Tabel 4.7 menunjukan bahwa
tingkat share dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit usaha syariah dari
4 perusahaan asuransi jiwa yang dijadikan objek sampel sampai pada tahun
2024 belum ada yang mampu mencapai tingkat share sebesar 50%.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.40 Tahun
2014 pasal 87 ayat 1 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa unit
usaha syariah pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib
melakukan spin off jika dana tabarru’ dan dana investasi peserta telah
mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana
Asuransi, Dana Tabarru’, dan Dana Investasi Peserta pada perusahaan
induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-undang
tersebut atau pada tahun 2024. Hasil peramalan pada Tabel 4.7 menunjukan
bahwa tingkat share dana peserta terbesar hanya sebesar 25,17% yaitu pada
perusahaan asuransi jiwa AIA pada tahun 2024.
Hasil peramalan juga menunjukan bahwa unit usaha syariah pada
perusahaan asuransi jiwa belum siap untuk melakukan pemisahan (spin off)

68
dan membentuk perusahaan asuransi jiwa syariah baru jika ketentuan yang
harus dipenuhi adalah tingkat share dana tabarru’ dan dana investasi peserta
telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana
asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan
induknya. Tabel 4.7 menunjukan peramalan sampai dengan tahun 2024,
dimana pada tahun tersebut seluruh unit usaha syariah pada perusahaan
asuransi harus melakukan pemisahan (spin off) sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 pasal
87 ayat 1 tentang Perasuransian.
Tabel 4.8 Simulasi pertumbuhan unit usaha syariah dan induk
perusahaan asuransi
Asumsi
pertumbuhan unit
usaha syariah
Asumsi
pertumbuhan
Induk
Estimasi proporsi
dana peserta
terhadap Induk
AIA
30.83% 5% 50.01%
37.10% 10% 50.10%
PRUDENTIAL
39.50% 5% 50.14%
46.20% 10% 50.26%
ALLIANZ
46.20% 5% 50.41%
53.00% 10% 50.09%
AXA
MANDIRI
58.30% 5% 50.15%
65.80% 10% 50.08%
Sumber: Data diolah
Setelah melakukan peramalan terhadap tingkat share dana tabarru’
dan dana investasi peserta unit usaha syariah pada 4 perusahaan asuransi jiwa
yang dijadikan objek sampel, maka selanjutnya akan dilakukan simulasi
perhitungan tingkat pertumbuhan dari perusahaan asuransi jiwa yang
merupakan induk dari unit usaha syariah asuransi jiwa sebesar 5% dan 10%,

69
pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 50% proporsi
tingkat share dana peserta unit usaha syariah membutuhkan tingkat
pertumbuhan dana peserta dari unit usaha syariah pada perusahaan asuransi
jiwa secara rata-rata sekitar 43,71% pada tingkat pertumbuhan 5% dan
50,53% pada tingkat pertumbuhan 10%.
Simulasi yang dilakukan ini menunjukan bahwa untuk mencapai
tingkat share dana peserta sebesar 50% dibutuhkan pertumbuhan dana
peserta yang cukup tinggi dari unit usaha syariah pada perusahaan asuransi
jiwa dan pertumbuhan dana peserta yang kecil dari perusahaan asuransi jiwa
induknya. Pertumbuhan dana peserta yang cukup tinggi dari unit usaha
syariah pada perusahaan asuransi jiwa dirasa cukup sulit untuk direalisasikan,
hal ini dapat dibuktikan dari data tingkat share dana peserta pada tahun 2010
sampai dengan tahun 2018 dari 4 perusahaan asuransi jiwa yang dijadikan
sampel, tingkat share dana peserta unit usaha syariahnya paling besar hanya
13,59% yaitu pada perusahan asuransi AIA pada tahun 2017 dan hasil
peramalan pada Tabel 4.7 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang
menunjukan bahwa tingkat share dana peserta terbesar hanya sebesar 25,17%
yaitu pada perusahaan asuransi jiwa AIA pada tahun 2024.
Kebijakan pemisahan (spin off) pada unit usaha syariah asuransi jiwa
perlu di evaluasi kembali melihat pada Tabel 4.7 diramalkan belum ada unit
usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang mampu mencapai tingkat
share dana tabarru’ dan dana investasi peserta sebesar 50% (lima puluh
persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi
peserta pada perusahaan induknya. Bahkan setelah dilakukan simulasi

70
pertumbuhan dari perusahaan asuransi jiwa induknya, unit usaha syariah
asuransi jiwa perlu meningkatkan pertumbuhan dana peserta dengan
presentase yang cukup tinggi untuk bisa mengimbagi pertumbuhan
perusahaan induknya, hal ini sangat menyulitkan bagi unit usaha syariah
pada perusahana asuransi jiwa.
Kebijakan pemisahan (spin off) unit usaha syariah juga dilakukan
pada industri perbankan syariah, menurut Al Arif,dkk (2018:95) dalam jurnal
Iqtishadia yang membahas tentang evaluasi kebijakan spin off pada
perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa hasil peramalan yang
dilakukan menunjukan bahwa dari 11 bank syariah yang dijadikan sampel
sampai dengan tahun 2023 belum ada yang mampu mencapai share aset
sebesar 50% dari aset bank induk konvesionalnya. Al Arif, dkk (2018: 100)
juga menyatakan bahwa regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan harus
memiliki fokus pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah,
bukan hanya pada banyaknya bank umum syariah, pemisahan (spin off)
bukanlah tujuan tetapi merupakan strategi untuk mencapai pangsa pasar yang
lebih besar.
Industri perbankan syariah yang mempunyai skala lebih besar jika
dibandingkan dengan industri asuransi syariah pun dirasa belum mampu
untuk melakukan pemisahan (spin off) unit usaha syariah dengan ketentuan
pada kebijakan pemisahan (spin off) unit usaha syariah yang ditetapkan oleh
pemerintah yaitu harus mencapai 50% dari tingkat share dana peserta
perusahaan induknya pada industri asuransi atau aset perusahaan induknya
pada industri perbankan. Jika kebijakan pemisahan (spin off) unit usaha

71
syariah yang ditetapkan oleh pemerintah ini tetap dipaksakan untuk
diterapkan, hal ini pasti akan sangat memberatkan bagi para pelaku usaha
atau pemilik perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa.
Beberapa peneliti yang meneliti tentang spin off unit usaha syariah
pada asuransi syariah menyatakan bahwa pemisahan atau spin off unit usaha
syariah masih tetap menjadi pekerjaan rumah perusahaan asuransi. Meski
berkali-kali menyatakan siap, mereka mengkhawatirkan dampak jika harus
menyapih unit usaha syariah dalam waktu dekat. Selain itu dampak dari spin
off adalah melonjaknya biaya operasional sehingga harga produk pun
dinaikkan. Pitaningtyas dan Nababan (2015). Menurut Pohan (2014) dalam
berita media insurance yang membahas tentang kebijakan spin off , pada
kenyataannya unit usaha syariah belum siap untuk melakukan pemisahan
dengan induk perusahaannya, dan pemerintah pun menunda waktu realisasi
pelaksanaan spin off, seharusnya unit usaha syariah dalam perusahaan
asuransi mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau otoritas jasa
keuangan selaku regulator agar unit usaha syariah dapat segera menjadi
perusahaan yang mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Ramadani (2016) dalam penelitiannya tentang respon salah satu unit
usaha syariah perusahaan asuransi di Indonesia yaitu perusahaan asuransi
Adira Dinamika terhadap kebijakan spin off industri asuransi syariah dalam
Undang-undang no.40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 67,
menyatakan bahwa perusahaan asuransi Adira Dinamika belum siap
melakukan spin off dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut
dinilai memberatkan bagi pelaku bisnis dan terkesan dipaksakan oleh

72
pemerintah. Persiapan yang kurang matang, manajemen kurang mendukung,
bantuan ahli aktuaria yang sangat langka, serta perusahaan induk yang
melepas anak perusahaannya menjadi kendala-kendala yang dihadapi unit
usaha syariah pada perusahaan asuransi Adira Dinamika dalam melakukan
spin off.

73
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemisahan (spin
off) dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang
Perasuransian yang menyatakan bahwa unit usaha syariah pada perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan spin off jika dana tabarru’
dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada
perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-
undang tersebut atau pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode Box
Jenkins ARIMA untuk melakukan peramalan (forecasting) pada tingkat share
dana peserta 4 unit usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang dijadikan
sampel.
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa setelah dilakukan
peramalan menggunakan metode Box Jenkins ARIMA dari tahun 2019 sampai
dengan tahun 2024 belum ada satupun unit usaha syariah asuransi jiwa yang
dijadikan sampel penelitian yang dapat mencapai proporsi 50% tingkat share
dana peserta perusahaan induknya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil peramalan
pada Tabel 4.7 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang menunjukan
bahwa tingkat share dana peserta terbesar hanya sebesar 25,17% yaitu pada
perusahaan asuransi jiwa AIA pada tahun 2024.

74
Hal ini diperkuat dengan simulasi sederhana yang dilakukan, dengan
menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan asuransi jiwa
induknya sebesar 5% per tahun dibutuhkan tingkat pertumbuhan rata-rata unit
usaha syariahnya sebesar 43,71% per tahun, dan jika tingkat pertumbuhan rata-
rata perusahaan asuransi jiwa induknya sebesar 10% per tahun dibutuhkan
tingkat pertumbuhan rata-rata unit usaha syariahnya sebesar 50,53%% per tahun.
Hasil ini jelas menunjukan bahwa proporsi tingkat share dana peserta unit usaha
syariah terhadap perushaan asuransi jiwa induknya sebesar 50% sulit untuk
dicapai.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan pemisahan (spin off) unit usaha syariah yang ditetapkan oleh
pemerintah ini harus dikaji ulang melihat penelitian-penelitian yang telah
dilakukan, belum ada satupun unit usaha syariah yang bisa melakukan
pemisahan (spin off) dengan perusahaan induknya jika ketentuan yang
ditetapkan salah satunya harus mencapai 50% dari tingkat dana peserta atau
aset perusahaan induknya. Regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan
harus mengkaji ulang kebijakan pemisahan (spin off) unit usaha syariah
pada perusahaan asuransi ini agar tidak memberatkan para pelaku usaha atau
pemilik perusahaan asuransi khususnya pada perusahaan asuransii jiwa
2. Unit usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa harus meningkatkan
kinerjanya seperti melakukan inovasi produk-produk asuransi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, supaya jika kebijakan

75
spin off ini tetap dipaksakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau
regulator, unit usaha syariah pada perusahaan asuransi jiwa siap untuk
melakukan spin off menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah.

76
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adib, Bahari. 2010. Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas. Yogyakarta :
Pustaka Yustisia.
Al Arif, M.Nur Rianto. 2012. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung :
Alfabeta.
Ali, AM. Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta : Kencana Prenada Media.
Dewi, Gemala. 2007. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian
Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media.
Ernst & Young Global Limited. 2014. Global Takaful Insight 2014 Market Update.
EY Global Limited.
Fred, Tumbuan. B.G. 2008. Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan. Jakarta :
Penerbit Ghalia.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi penelitian Bisnis untuk
Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE.
Jundiani. 2009. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Malang : UIN
Press.
Pohan, Rizky Andrianti. 2014. Spin Off Memakmurkan Asuransi Syariah. Berita
Media Insurance. Diterbitkan 18 November 2014.
Rastuti, Tuti. 2011. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta : Pustaka
Yustisia.
Rosadi, Dedi. 2012. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan
Eviews.Yogyakarta: CV. Andi Offset.

77
Silvanita, Ketut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi Kedua. Jakarta :
Erlangga.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian dan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.
Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan
Sistem Operasional. Jakarta : Gema Insani.
Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi”. Yogyakarta :
Ekonosia.
Jurnal
Al Arif, M.Nur Rianto. 2014. Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai
Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. Jurnal Kinerja, Vol.18
(2).hlm.169.
Al Arif, M.Nur Rianto. 2015. Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat
Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Keuangan
dan Perbankan, Vol.19 (2).hlm.303.
Al Arif, M.Nur Rianto, Nachrowi D Nachrowi, Mustafa E Nasution, T.M. Zakir
Mahmud. 2018. Evaluation of the Spinoffs Criteria: A Lesson from The
Indonesian Islamic Banking Industry. Jurnal Iqtishadia IAIN Kudus, Vol. 11
(1).hlm.95-100.
Nasuha, Amalia. 2012, Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank
Syariah. Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV (2). hlm.243-244.
Nurcahya dan Metti Paramita. 2015. Efektifitas Sosialisasi Asuransi Syariah PT.
PRU Syariah Bogor (Studi pada Pasar di Bogor). Jurnal Syarikah, Vol.1 (1).
hlm.18.

78
Poerwokoesoemo, Atman. 2016. Kinerja Bank Konvensional Pasca Spin Off Unit
Usaha Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.12 (2).hlm.160.
Sabiti, Mustica Bintang, Jaenal Effendi, Tanti Novianti. 2017. Efisiensi Asuransi
Syariah di Indonesia dengan pendekatan Data Envelopment Analysis. Jurnal
Al-Muzara’ah, Vol.5 (1).hlm.69.
Umam, Kotibul. 2010. Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin Off)
Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. Mimbar Hukum, Vol.22
(3).hlm.609.
Skripsi
Iswanto, Nawang Styanda. 2017. Implementasi Undang-Undang No.40 tahun 2014
Tentang Perasuransian terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off)
Asuransi (Studi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang
Malang). Skripsi, UIN Jakarta.
Ramadani, Sari. 2018. Respon Unit Usaha Syariah Di Indonesia Terhadap
Kebijakan Spin Off yang Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No.40 Tahun 2014 Dan POJK No.67 Tahun 2016 (Studi Kasus pada PT
Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah). Skripsi, UIN Jakarta.
Website
Pitaningtyas, Anaya Noor dan Christine Novita Nababan. 2015. Efek Pemisahan.
Website kontan.co.id. terbit 25 Juli 2015 dan diakses pada 28 September
2019; 11.00 am.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. 2014. Spin – Off Guide, Wachtell, Lipton, Rosen
& Katz Law Firm. Diunduh dari http://www.wlrk.com/files/.../Spin-Off
Guide.pdf pada 23 Juli 2018; 10.30 am.

79
LAMPIRAN
Lampiran I: Tingkat Share Dana Peserta Unit Usaha Syariah
TAHUN
JUMLAH INVESTASI
INDUK
(dalam jutaan rupiah)
DANA PESERTA
UNIT SYARIAH
(dalam jutaan rupiah)
SHARE (%)
ASURANSI JIWA AIA
2010 18,957,575 60,396 0.32
2011 21,606,272 145,254 0.67
2012 24,974,950 409,017 1.64
2013 26,169,965 1,053,950 4.03
2014 33,891,872 2,497,396 7.37
2015 35,004,259 3,569,682 10.20
2016 40,771,361 5,370,342 13.17
2017 51,239,455 6,961,715 13.59
2018 52,339,335 6,995,341 13.37
ASURANSI JIWA PRUDENTIAL
2010 22,240,943 1,256,643 5.65
2011 27,452,887 1,612,934 5.88
2012 34,492,603 2,329,894 6.75
2013 33,720,922 3,026,913 8.98
2014 46,176,074 4,213,605 9.13
2015 45,188,535 4,504,685 9.97
2016 59,752,813 5,803,527 9.71
2017 73,377,168 6,862,205 9.35
2018 72,099,942 6,574,212 9.12
ASURANSI JIWA ALLIANZ
2010 11,300,472 573,526 5.08
2011 14,837,779 594,115 4.00
2012 19,060,027 803,653 4.22
2013 19,977,768 1,003,492 5.02
2014 24,559,818 1,341,135 5.46
2015 25,223,498 1,474,859 5.85
2016 26,966,944 1,819,029 6.75
2017 32,382,230 2,193,406 6.77
2018 31,725,506 2,194,631 6.92

80
ASURANSI JIWA AXA MANDIRI
2010 8,035,481 590,699 7.35
2011 10,607,265 642,042 6.05
2012 13,753,886 756,740 5.50
2013 14,402,486 762,328 5.29
2014 21,054,617 948,669 4.51
2015 20,867,148 888,471 4.26
2016 23,616,096 1,072,429 4.54
2017 27,656,743 1,180,275 4.27
2018 26,805,313 1,144,798 4.27

81
Lampiran II: Hasil Prediksi Model ARIMA
AIA (3,1,3)
AIA (3,1,1)
Dependent Variable: D(AIA)
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/19/19 Time: 23:33
Sample: 2011 2018
Included observations: 8
Convergence not achieved after 500 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.999491 0.179887 11.11523 0.0004
AR(3) -0.882451 0.355080 -2.485220 0.0678
MA(1) -0.995805 124.3958 -0.008005 0.9940
SIGMASQ 0.400074 50.09545 0.007986 0.9940
R-squared 0.766801 Mean dependent var 1.630847
Adjusted R-squared 0.591901 S.D. dependent var 1.400239
S.E. of regression 0.894509 Akaike info criterion 3.869164
Sum squared resid 3.200588 Schwarz criterion 3.908885
Log likelihood -11.47666 Hannan-Quinn criter. 3.601264
F-statistic 4.384236 Durbin-Watson stat 1.470387
Prob(F-statistic) 0.093656
Inverted AR Roots .48+.83i .48-.83i -.96
Inverted MA Roots 1.00
Dependent Variable: D(AIA)
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2011 2018
Included observations: 8
Convergence not achieved after 500 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.952079 0.328138 5.948958 0.0040
AR(3) -0.999851 0.000520 -1921.547 0.0000
MA(3) 0.970468 0.089607 10.83021 0.0004
SIGMASQ 0.433124 0.324894 1.333126 0.2534 R-squared 0.747536 Mean dependent var 1.630847
Adjusted R-squared 0.558188 S.D. dependent var 1.400239
S.E. of regression 0.930724 Akaike info criterion 3.792797
Sum squared resid 3.464992 Schwarz criterion 3.832518
Log likelihood -11.17119 Hannan-Quinn criter. 3.524897
F-statistic 3.947944 Durbin-Watson stat 1.143240
Prob(F-statistic) 0.108920 Inverted AR Roots .50-.87i .50+.87i -1.00
Inverted MA Roots .50+.86i .50-.86i -.99

82
AIA (1,1,1)
PRUDENTIAL (1,0,1)
Dependent Variable: PRUDENTIAL
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Convergence achieved after 24 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.834556 2.613945 2.997215 0.0302
AR(1) 0.793408 0.850291 0.933102 0.3936
MA(1) 0.276425 1.639921 0.168560 0.8727
SIGMASQ 0.693275 0.650590 1.065609 0.3353 R-squared 0.728479 Mean dependent var 8.281443
Adjusted R-squared 0.565566 S.D. dependent var 1.694834
S.E. of regression 1.117092 Akaike info criterion 3.523655
Sum squared resid 6.239472 Schwarz criterion 3.611310
Log likelihood -11.85645 Hannan-Quinn criter. 3.334495
F-statistic 4.471595 Durbin-Watson stat 1.678349
Prob(F-statistic) 0.070218 Inverted AR Roots .79
Inverted MA Roots -.28
Dependent Variable: D(AIA)
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/19/19 Time: 23:30
Sample: 2011 2018
Included observations: 8
Convergence achieved after 17 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.376390 1.148266 1.198669 0.2968
AR(1) 0.340515 1.063553 0.320168 0.7649
MA(1) 0.442320 1.075298 0.411347 0.7019
SIGMASQ 1.010252 0.966444 1.045329 0.3549
R-squared 0.411133 Mean dependent var 1.630847
Adjusted R-squared -0.030517 S.D. dependent var 1.400239
S.E. of regression 1.421444 Akaike info criterion 3.925771
Sum squared resid 8.082012 Schwarz criterion 3.965491
Log likelihood -11.70308 Hannan-Quinn criter. 3.657870
F-statistic 0.930903 Durbin-Watson stat 1.714574
Prob(F-statistic) 0.503529
Inverted AR Roots .34
Inverted MA Roots -.44

83
PRUDENTIAL (1,0,0)
Dependent Variable: PRUDENTIAL
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Convergence achieved after 9 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.770530 1.483351 5.238496 0.0019
AR(1) 0.856127 0.350818 2.440374 0.0504
SIGMASQ 0.786137 0.362926 2.166110 0.0735 R-squared 0.692109 Mean dependent var 8.281443
Adjusted R-squared 0.589479 S.D. dependent var 1.694834
S.E. of regression 1.085912 Akaike info criterion 3.410624
Sum squared resid 7.075235 Schwarz criterion 3.476365
Log likelihood -12.34781 Hannan-Quinn criter. 3.268754
F-statistic 6.743723 Durbin-Watson stat 1.163209
Prob(F-statistic) 0.029187 Inverted AR Roots .86
PRUDENTIAL (0,0,1)
Dependent Variable: PRUDENTIAL
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Convergence achieved after 9 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.160443 1.121172 7.278494 0.0003
MA(1) 0.705159 0.977802 0.721168 0.4979
SIGMASQ 1.286528 0.918839 1.400166 0.2110 R-squared 0.496132 Mean dependent var 8.281443
Adjusted R-squared 0.328176 S.D. dependent var 1.694834
S.E. of regression 1.389169 Akaike info criterion 3.832795
Sum squared resid 11.57875 Schwarz criterion 3.898536
Log likelihood -14.24758 Hannan-Quinn criter. 3.690925
F-statistic 2.953936 Durbin-Watson stat 1.062826
Prob(F-statistic) 0.127924

84
ALLIANZ (3,1,3)
Dependent Variable: D(ALLIANZ)
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2011 2018
Included observations: 8
Convergence not achieved after 500 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.248230 0.482768 0.514181 0.6342
AR(3) -0.999677 0.027719 -36.06475 0.0000
MA(3) 0.992353 0.323635 3.066273 0.0374
SIGMASQ 0.298520 0.246612 1.210486 0.2927 R-squared 0.077265 Mean dependent var 0.230290
Adjusted R-squared -0.614786 S.D. dependent var 0.608057
S.E. of regression 0.772684 Akaike info criterion 2.702928
Sum squared resid 2.388160 Schwarz criterion 2.742648
Log likelihood -6.811710 Hannan-Quinn criter. 2.435027
F-statistic 0.111647 Durbin-Watson stat 1.235755
Prob(F-statistic) 0.948796 Inverted AR Roots .50+.87i .50-.87i -1.00
Inverted MA Roots .50-.86i .50+.86i -1.00
ALLIANZ (3,1,1)
Dependent Variable: ALLIANZ
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/19/19 Time: 23:57
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 9 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.667535 0.460505 12.30722 0.0001
AR(3) -0.167037 1.398782 -0.119416 0.9096
MA(1) 1.000000 54525.76 1.83E-05 1.0000
SIGMASQ 0.379676 467.5841 0.000812 0.9994
R-squared 0.642653 Mean dependent var 5.562565
Adjusted R-squared 0.428245 S.D. dependent var 1.093296
S.E. of regression 0.826691 Akaike info criterion 2.995614
Sum squared resid 3.417086 Schwarz criterion 3.083269
Log likelihood -9.480263 Hannan-Quinn criter. 2.806454
F-statistic 2.997334 Durbin-Watson stat 0.663360
Prob(F-statistic) 0.134033
Inverted AR Roots .28+.48i .28-.48i -.55
Inverted MA Roots -1.00

85
ALLIANZ (1.1.3)
AXA MANDIRI (1,0,1)
Dependent Variable: AXAMANDIRI
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 6 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.112456 0.847956 6.029153 0.0018
AR(1) 0.941935 2.053763 0.458639 0.6657
MA(1) -1.000000 17436.50 -5.74E-05 1.0000
SIGMASQ 0.953126 369.2578 0.002581 0.9980 R-squared 0.039140 Mean dependent var 5.115777
Adjusted R-squared -0.537375 S.D. dependent var 1.056383
S.E. of regression 1.309819 Akaike info criterion 3.705237
Sum squared resid 8.578134 Schwarz criterion 3.792892
Log likelihood -12.67357 Hannan-Quinn criter. 3.516077
F-statistic 0.067891 Durbin-Watson stat 0.303032
Prob(F-statistic) 0.974628 Inverted AR Roots .94
Inverted MA Roots 1.00
Dependent Variable: ALLIANZ
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/19/19 Time: 23:59
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 7 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.693618 0.573568 9.926673 0.0002
AR(1) 0.838186 0.741442 1.130481 0.3096
MA(3) -1.000000 19134.87 -5.23E-05 1.0000
SIGMASQ 0.242800 2322.901 0.000105 0.9999
R-squared 0.771479 Mean dependent var 5.562565
Adjusted R-squared 0.634366 S.D. dependent var 1.093296
S.E. of regression 0.661091 Akaike info criterion 2.761700
Sum squared resid 2.185204 Schwarz criterion 2.849356
Log likelihood -8.427652 Hannan-Quinn criter. 2.572540
F-statistic 5.626607 Durbin-Watson stat 1.285817
Prob(F-statistic) 0.046502
Inverted AR Roots .84
Inverted MA Roots 1.00 -.50-.87i -.50+.87i

86
AXA MANDIRI (1,0,0)
Dependent Variable: AXAMANDIRI
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Convergence achieved after 17 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.574766 1.401048 3.978998 0.0073
AR(1) 0.897380 0.259934 3.452338 0.0136
SIGMASQ 0.348420 0.282885 1.231668 0.2642 R-squared 0.648753 Mean dependent var 5.115777
Adjusted R-squared 0.531671 S.D. dependent var 1.056383
S.E. of regression 0.722932 Akaike info criterion 2.632003
Sum squared resid 3.135781 Schwarz criterion 2.697744
Log likelihood -8.844012 Hannan-Quinn criter. 2.490133
F-statistic 5.540995 Durbin-Watson stat 1.669194
Prob(F-statistic) 0.043335 Inverted AR Roots .90
AXA MANDIRI (0,0,1) Dependent Variable: AXAMANDIRI
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Sample: 2010 2018
Included observations: 9
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 13 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.234155 0.655762 7.981786 0.0002
MA(1) 1.000000 39223.31 2.55E-05 1.0000
SIGMASQ 0.398842 346.5105 0.001151 0.9991 R-squared 0.597922 Mean dependent var 5.115777
Adjusted R-squared 0.463896 S.D. dependent var 1.056383
S.E. of regression 0.773475 Akaike info criterion 2.841197
Sum squared resid 3.589579 Schwarz criterion 2.906938
Log likelihood -9.785386 Hannan-Quinn criter. 2.699327
F-statistic 4.461234 Durbin-Watson stat 1.160798
Prob(F-statistic) 0.065003 Inverted MA Roots -1.00

87
Lampiran III: Grafik Hasil Peramalan (Forecasting)
AIA
0
5
10
15
20
25
30
35
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AIAF ± 2 S.E.
Forecast: AIAF
Actual: AIA
Forecast sample: 2010 2024
Adjusted sample: 2014 2024
Included observations: 11
Root Mean Squared Error 0.974375
Mean Absolute Error 0.724136
Mean Abs. Percent Error 5.802806
Theil Inequality Coefficient 0.042629
Bias Proportion 0.496460
Variance Proportion 0.066607
Covariance Proportion 0.436933
Theil U2 Coefficient 0.410039
Symmetric MAPE 6.094025
PRUDENTIAL
0
2
4
6
8
10
12
14
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PRUDENTIALF ± 2 S.E.
Forecast: PRUDENTIALF
Actual: PRUDENTIAL
Forecast sample: 2010 2024
Adjusted sample: 2011 2024
Included observations: 14
Root Mean Squared Error 2.231658
Mean Absolute Error 1.981817
Mean Abs. Percent Error 21.42304
Theil Inequality Coefficient 0.145100
Bias Proportion 0.772806
Variance Proportion 0.194452
Covariance Proportion 0.032742
Theil U2 Coefficient 1.922218
Symmetric MAPE 24.68731
ALLIANZ
-5
0
5
10
15
20
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ALLIANZF ± 2 S.E.
Forecast: ALLIANZF
Actual: ALLIANZ
Forecast sample: 2010 2024
Adjusted sample: 2014 2024
Included observations: 11
Root Mean Squared Error 0.634696
Mean Absolute Error 0.541208
Mean Abs. Percent Error 8.114901
Theil Inequality Coefficient 0.052066
Bias Proportion 0.727104
Variance Proportion 0.219863
Covariance Proportion 0.053033
Theil U2 Coefficient 1.319267
Symmetric MAPE 8.582920

88
AXA MANDIRI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AXAMANDIRIF ± 2 S.E.
Forecast: AXAMANDIRIF
Actual: AXAMANDIRI
Forecast sample: 2010 2024
Adjusted sample: 2011 2024
Included observations: 14
Root Mean Squared Error 1.905461
Mean Absolute Error 1.863553
Mean Abs. Percent Error 40.14883
Theil Inequality Coefficient 0.164483
Bias Proportion 0.956497
Variance Proportion 0.036815
Covariance Proportion 0.006689
Theil U2 Coefficient 5.408884
Symmetric MAPE 32.97885