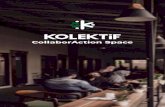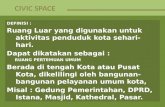mekanisme cleaning tangki (convence space), analisa potensi bahaya kondensor, inventarisasi...
-
Upload
elsa-fitriani -
Category
Documents
-
view
99 -
download
11
description
Transcript of mekanisme cleaning tangki (convence space), analisa potensi bahaya kondensor, inventarisasi...
Laporan Kerja Praktek
Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
BAB VITUGAS KHUSUS6.1 Analisis Potensi Bahaya Saat Maintenance Kondensor 5-2 BB. Distilasi PT Pertamina (Persero) RU III Kondensor merupakan salah satu alat yang digunakan pada proses produksi yang berfungsi sebagai pendingin minyak yang telah diolah pada proses sebelumnya. Proses pengolahan gas ini diharapkan menghasilkan produk yang diinginkan. Ada beberapa keadaan dimana suatu kondensor dilakukan maintenance seperti terdapat kerusakan pada komponen unit, kebocoran dan penyumbatan. Sehingga dapat menggangu proses pada alat tersebut dan hasil pengolahan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum dilakukan maintenance pada kondensor maka dilakukan tahapan-tahapan berikut yang bertujuan menghindari terjadinya unsaved act dan unsaved condition.Hal pertama yang harus dilakukan adalah pihak atau bagian produksi tempat kondensor itu berada (GSI) memastikan tempat dan unit yang akan dilakukan maintenance tersebut aman dari bahaya yang akan menggangu proses perbaikan dan keselamatan para pekerja terlebih dahulu dengan cara menutup aliran inlet kondensor agar tidak ada aliran masuk baik berupa gas, minyak maupun air. Kemudian kondensor dikosongkan, dimana gas, minyak dan air yang terdapat didalam kondensor dialirkan ke tempat lain. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan surat dalam memulai suatu pekerjaan sebagai pelengkap administrasi, dapat berupa JSA dan SIKA (jenis sika tergantung dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan).Setelah semua terpenuhi maka dilanjutkan dengan tahapan yang dilakukan dalam proses maintenance kondensor berupa:1. Melakukan isolasi energi terhadap kondensor dengan memasang sorokan buta pada inlet dan outlet. Pemasakan sorokan ini sebagai tanda/label yang menandakan bahwa dilakukannya perbaikan sehingga tidak diperbolehkan adaya aliran yang masuk dan keluar kondensor, sorokan dipasang pada inlet dan outlet;
2. Pembukaan cover/penutup luar bagian depan dan pembukaan channel/penutup luar bagian belakang;
3. Pembukaan floating, dimana floating ini berfungsi agar air dan minyak yang terdapat pada alat kondensor tidak tercampur;4. Cleaning kondensor dengan menggunakan air yang ditujukan pada tube yang terdapat didalam kondensor, untuk membersihkan tube yang mungkin tersumbat digunakan rotan;
5. Pemompaan pada tube yang berfungsi untuk memberikan tekanan gas yang berfungsi sebagai pengecekan awal;
6. Pemasangan ring untuk mengetahui adanya kebocoran tube;
7. Pemasangan floating;8. Melakukan test shell side;
9. Pemasangan cover dan channel;10. Final test;11. Pencabutan sorokan pada inlet dan outlet pertanda bahwa perbaikan kondensor telah selesai.
Selama perbaikan kondensor pekerja akan menemui berbagai jenis potensi bahaya, sehingga pemakaian APD standar diharuskan baik dalam melakukan pekerjaan ini. APD standar yang harus digunakan berupa helm keselamatan, coverall dan safety shoes. Setelah melihat semua tahapan yang dilakukan dalam proses maintenance kondensor, maka didapatkan beberapa potensi bahaya yang dapat timbul. Pada saat dilakukan maintenance lantai yang berada di bawah kondensor akan berkemungkinan menjadi basah akibat tercecernya air dari kondensor sehingga lantai akan menjadi licin dan berpotensi menbuat para pekerja tergelincir. Hal yang dapat dilakukan untuk pengendalian bahaya tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan tumpahan atau ceceran ke bagian yang tidak terdapat pekerjaan atau membersihkan tumpahan dengan oil sorban.Dalam pengerjaan kondensor ini para pekerja akan berada diketinggian diatas 1,8m sehingga diperlukan pemakaian full body harness untuk mencegah terjatuhnya pekerja dari ketinggian. Pada kondensor terdapat gas H2S, jika terjadi kebocoran maka penggunaan masker gas H2S diperlukan. Disamping itu bahaya yang ditimbulkan oleh unsafe act oleh pekerja juga dapat terjadi seperti potensi terjepit alat, tertimpa alat dan terpukul alat dapat terjadi karena pada saat maintenance dilakukan mengggunakan beberapa alat seperti palu dan alat pembuka sekrup. Kondensor terbuat dari logam sehingga untuk menghindari terjadinya percikan api saat memalu maka digunakan palu berbahan dasar dari kuningan.Menghindari terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja maka perlu dilakukan pengendalian bahaya Pengendalian bahaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1.Tabel 6.1 Pengendalian Potensi Bahaya saat Maintenace KondensorNo.Tahapan PelaksanaanPotensi BahayaPengendalian
1.Pemasakan sorokan untuk menutup aliran (dengan menutup inlet dan outlet kondensor yang telah dikosongkan).Bekerja di ketinggian sehingga kemungkinan para pekerja terjatuh, flash minyak/gas.Pasang sorokan pada saat kondensor free gas, menyediakan Alat Pemadam Api Ringan) APAR, menyediakan air untuk pengenceran gas/minyak release, menggunakan APD full body harness dan scafollding untuk bekerja di ketinggian > 1,8 m.
2.Pembukaan cover, channel dan floatingBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh. Saat pembukaan cover, channel dan floating maka kemungkinan terjadi bahaya terpukul alat, terjepit.Menggunakan APD full body harness dan sarung tangan.
3.Cleaning kondensorBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh. Saat melakukan cleaning dengan menggunakan air maka kemungkinan terjadi bahaya tergelincir karena licin dan bau gas H2S.Menggunakan APD full body harness, sarung tangan dan masker chemical apabila terjadi kebocoran gas diatas NAB
4.Pemompaan ke tubeBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh dan tergelincir. Saat melakukan pemompaan ke tube maka kemungkinan terjadi bahaya terjepit dan terpukul alat.Menggunakan APD full body harness dan sarung tangan.
5.Pemasangan ring dan floatingBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh dan tergelincir. Saat pemasangan dan floating, maka kemungkinan terjadi bahaya terpukul alat dan terjepit.Menggunakan APD full body harness dan sarung tangan, jangan berdiri dibawah aparat yang diangkat
6.Melakukan test shell sideBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh.Menggunakan APD full body harness
7.Penutupan cover dan channel Bekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh. Saat pembukaan cover dan channel, maka kemungkinan terjadi bahaya terpukul alat dan terjepit.Menggunakan APD full body harness dan sarung tangan
8.Final testBekerja di ketinggian sehingga kemungkinan terjatuh.Menggunakan APD full body harness
9.Pencabutan sorokan pada inlet dan outlet.Bekerja di ketinggian sehingga kemungkinan para pekerja terjatuh, flas gas/minyak stand by APAR, stand by air untuk pengenceran gas/minyak release, gunakan APD full body harness dan scafollding untuk bekerja di ketinggian > 1,8 m, genggunakan APD full body harness dan scaffolding.
6.2 Mekanisme Cleaning Tangki (Tangki O6) PT Pertamina (Persero) RU III Cleaning tangki merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk membersihkan tangki dari semua kontaminan yang akan berbahaya bagi pekerja yang akan melakukan pekerjaan pada tangki tergantung pada tujuan cleaning dilakukan. Pekerjaan cleaning tangki biasanya dilakukan jika tangki tersebut harus diperbaiki baik sebagian maupun secara keseluruhan dan tangki tersebut akan diisi dengan jenis minyak yang berbeda. Cleaning tangki merupakan salah satu contoh pekerjaan di ruang terbatas (confined space), sehingga memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk melakukan cleaning tangki.Tahapan cleaning tangki yang akan dijelaskan merupakan proses cleaning tangki dengan sampel tangki O6 yang akan dilakukan perbaikan sebagian, berikut merupakan proses cleaning tangki yang dilakukan:1. Pengosongan tangki, tahapan ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan atau mengalirkan minyak ke unit tangki lain dengan saluran yang telah tersedia;2. Melakukan isolasi energi terhadap tangki, yang bertujuan untuk memutus aliran energi (fluida) yang akan masuk dan keluar dari tangki. Isolasi energi dapat dilakukan dengan pemasangan sorokan buta (blind flange). Dalam cleaning tangki di petugas Oil Movement (OM) menentukan titiktitik yang akan dilakukan isolasi energi dan memberikan label/tagging pada sorokan berwarna kuning, kemudian melalui petugas Maintenance Area (MA) akan mengganti label/tagging kuning menjadi warna merah setelah blind flange dipasang. Langkah isolasi energi dapat dilakukan dengan:a. Isolasi sumber energi melalui alat isolasi energi yaitu menutup keran. Pada pekerjaan cleaning tangki, isolasi energi dilakukan dengan memasang sorokan buta;b. Mengunci dan memberi label pada alat isolasi energi untuk mencegah ketidaksengajaan orang lain mengoperasikan/membuka kembali energi berbahaya yang berkaitan dengan sistem ruang terbatas (confined space) seperti pembukaan keran, pemasangan sekring, atau menyalakan listrik melalui stop kontak. Dalam hal cleaning tangki sebelum pemasangan sorokan buta, seluruh aliran masuk tangki (saluran inlet dan outlet tangki) diberi label/tagging blind flange kuning oleh OM kemudian setelah sorokan buta dipasang, kemudian digantikan label diganti berwarna merah dan label kuning dilepas oleh MA. Apabila isolasi energi sudah selesai dan sorokan buta sudah dilepas maka label merah akan dilepas kembali;3. Membersihkan dan membuang gas serta cairan di dalam tangki;Setelah isolasi energi berbahaya dilakukan, maka tangki harus dibersihkan dari gas-gas dan cairan berbahaya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Jika masih terdapat sisa minyak yang tidak bisa dipindahkan lagi ke tangki lain dengan sistem sirkulasi tertutup, maka manhole akan dibuka dan minyak akan dihisap dengan vacuum truck melalui manhole yang telah dibuka;b. Jika minyak tidak bisa lagi dihisap dengan vacuum truck melalui manhole, maka tangki akan dicuci dengan air agar minyak berada di atas air sehingga dapat kembali dihisap dengan menggunakan vacuum truck hingga kandungan minyak tidak ada lagi. Sisa air dibuang ke kanal dan akan ditangkap oleh oil catcher jika masih mengandung minyak;c. Melakukan gas testing, apabila dalam pengukuran gas/uap hidrokarbon kurang dari 40% maka akan direkomendasikan pemasangan blower untuk mempercepat penurunan konsentrasi gas/uap hidrokarbon atau gas/uap yang bersifat toxic lainnya;d. Apabila gas campuran di dalam tangki telah mencapai titik di bawah sifat mudah terbakar (LEL), udara baru dialirkan ke dalam tangki hingga udara mengisi seluruh isi ruangan atau keadaan dimana kadar oksigen didalam tangki 19% - 21% dan kadar gas mudah terbakar berada di bawah batas paparan aman untuk kesehatan. Apabila ketika dilakukan pengukuran oleh petugas Occupational Health (OH) gas toxic yang ada di dalam ruang terbatas (confined space) masih jauh diatas nilai ambang batas (NAB) maka tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam tangki. Petugas HSE dalam hal ini bagian Occupational Health (OH) yang melakukan pengukuran gas toxic yang ada didalam tangki akan memasang tanda dilarang masuk dan menempel stiker tentang bahaya dari gas toxic yang ada di dalam tangki.Apabila saat diukur toksisitas masih tinggi dan pekerjaan cleaning tangki tidak dapat ditunda/emergency maka dapat dilakukan pengendalian sebagai berikut:
1) Apabila parameter yang diukur menunjukkan angka lebih dari 10 kali dan kurang dari 50 kali nilai ambang batas (NAB) maka APD pernafasan yang harus digunakan adalah full mask;2) Apabila parameter yang diukur menunjukkan angka kurang dari 10 kali nilai ambang batas (NAB) maka alat pelindung diri (APD) pernafasan yang harus digunakan adalah half mask dengan catridge3) Apabila parameter yang diukur menunjukkan angka lebih dari 50 kali dan dibawah nilai IDLH maka Alat Pelindung Diri (APD) Pernafasan yang harus digunakan adalah air line yang dilengkapi dengan botol penyelamat perseorangan;
4) Apabila parameter yang diukur menunjukkan angka Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH) maka APD yang harus digunakan adalah Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).
4. Melakukan sirkulasi udara, pada tangki dialirkan udara dengan menggunakan blower yang berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara di dalam tangki;5. Tangki dicuci dengan air untuk finishing tangki dan sisa air dibuang ke kanal dan akan ditangkap oleh oil catcher jika masih mengandung minyak.6.3 Peraturan Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Yang Masih Berlaku di Indonesia
1. Undang-Undang K3:
a. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;b. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenaga kerjaan.2. Peraturan Pemerintah terkait K3:
a. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida;b. peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;c. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;d. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.3. Peraturan Menteri terkait K3:
a. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;b. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;c. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan;d. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;e. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;f. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;g. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;h. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan;i. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las;j. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;k. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;l. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes;m. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;n. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;o. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi-instalasi Penyalur Petir;p. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;q. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;r. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;s. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja;t. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;u. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan tata Kerja Dokter Penasehat;v. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang;w. Permenaker RI No. 9 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut;x. Permenaker RI No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja.4. Keputusan Menteri terkait K3:
a. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;b. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi;c. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja;d. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja;e. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;f. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;g. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya;h. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja;i. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;j. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.5. Instruksi Menteri terkait K3:
a. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.6. Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3:
a. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan;b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift;c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.Mega Wahyuni (1110942016)VI-10Elsa Fitriani (1110942030)