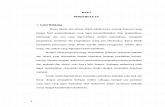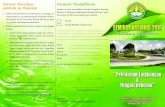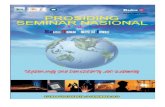makalah serosis
-
Upload
lovely99dyah -
Category
Documents
-
view
44 -
download
7
Transcript of makalah serosis
1.1 Latar Belakang Sirosis adalah penyakit hati kronis yang dicirikan dengan distorsi arsitektur hati yang normal oleh lembar-lembar jaringan ikat dan nodul-nodul regenenerasi sel hati yang tidak berikatan dengan vaskulatur normal. Nodul-nodul regenerasi ini dapat berukuran kecil (mikronodular) atau besar (makronodular). Sirosis dapat menggangu sirkulasi darah intrahepatik, dan pada kasus yang sangat lanjut dapat menyebabkan kegagalan hati secara bertahap. Penderita sirosis hati lebih banyak dijumpai pada kaum laki-laki jika dibandingkan dengan kaum wanita sekitar 1,6 : 1 dengan umur rata-rata terbanyak antara golongan umur 30 59 tahun dengan puncaknya sekitar 40 49 tahun. Di negara maju, sirosis hati merupakan penyebab kematian terbesar pada pasien yang berusia 45 46 tahun (setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker). Diseluruh dunia sirosis menempati urutan ke tujuh penyebab kematian. Sekitar 25.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Sirosis hati merupakan penyakit hati yang sering ditemukan dalam ruang perawatan Bagian Penyakit Dalam. Perawatan di Rumah Sakit sebagian besar kasus terutama ditujukan untuk mengatasi berbagai penyakit yang ditimbulkan seperti perdarahan saluran cerna bagian atas, koma peptikum, hepatorenal sindrom, dan asites, spontaneous bacterial peritonitis serta hepatosellular carsinoma. Gejala klinis dari sirosis hati sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala sampai dengan gejala yang sangat jelas. Apabila diperhatikan, laporan di negara maju, maka kasus penderita sirosis hati yang datang berobat ke dokter hanya kira-kira 30% dari seluruh populasi penderita penyakit ini, dan lebih kurang 30% lainnya ditemukan secara kebetulan ketika berobat untuk penyakit lain, sisanya ditemukan saat otopsi. Insiden penyakit ini sangat meningkat sejak perang dunia II, sehingga sirosis menjadi salah satu penyebab kematian yang menonjol. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh insiden hepatitis virus yang meningkat. Namun, yang lebih bermakna agaknya karena asupan alkohol yang sangat meningkat. Alkoholisme satu-satunya penyebab terpenting sirosis. Sirosis akibat alkohol merupakan penyebab kematian nomor sembilan pada tahun 1998 di Amerika Serikat dengan jumlah hingga 28.000 kematian (NIAAA, 1998). Berdasarkan informasi di atas, kami sebagai mahasiswa keperawatan merasa perlu untuk menuliskan segala sesuatu tentang penyakit sirosis hepatica ini, mulai dari definisi sampai tindakan keperawatan yang harus dilakukan kepada penderita sikrosis hepatika dalam bentuk sebuah makalah. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua.2.1 Definisi Serosis HepatikIstilah Sirosis hepatik diberikan oleh Laence tahun 1819, yang berasal dari kata Khirros yang berarti kuning orange (orange yellow) karena perubahan warna pada nodul-nodul yang terbentuk. Pengertian sirosis hepatik dapat dikatakan sebagai berikut yaitu suatu keadaan disorganisassi yang difuse dari struktur hati yang normal akibat nodul regeneratif yang dikelilingi jaringan mengalami fibrosis. Secara lengkap Sirosis Hepatik adalah suatu penyakit dimana sirkulasi mikro, anatomi pembuluh darah besar dan seluruh sitem arsitektur hati mengalami perubahan menjadi tidak teratur dan terjadi penambahan jaringan ikat (fibrosis) disekitar parenkim hati yang mengalami regenerasi.1Gambar 1. Sirosis hati2.2 EtiologiMeskipun etiologi berbagai bentuk sirosis masih kurang dimengerti, terdapat 3 pola khas yang ditemukan pada kebanyakan kasus-sirosis Lannec, pascanekrotik, dan biliaris. Diantaranya adalah: 1. Sirosis Laennec Sirosis Lannec (disebut juga sirosis alkoholik, portal, dan status gizi) merupakan suatu pola khas sirosis terkait penyalahgunaan alkohol kronis yang jumlahnya sekitar 75% atau lebih dari kasus sirosis. 10 hingga 15% peminum alkohol mengalami sirosis. Hubungan pasti antara penyalahgunaan alkohol dengan sirosis Lannec tidaklah diketahui, walaupun terdapat hubungan yang jelas dan pasti antara keduanya. Perubahan pertama pada hati yang ditimbulkan alkohol adalah akumulasi lemak secara bertahap didalam sel-sel hati (infiltrasi lemak). Pola infiltrasi lemak yang serupa juga ditemukan pada kwashiorkor (gangguan yang lazim ditemukan pada Negara berkembang akibat defisiensi protein berat), hipertiroidisme dan diabetes. Para pakar umunya setuju bahwa minuman berakohol menimbulkan efek toksik langsung pada hati. Akumulasi lemak mencerminkan adanya sejumlah gangguan metabolik yang mencakup pembentukan trigliserida secara berlebihan, dan menurunnya oksidase asam lemak. Individu yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan juga mungkin tidak makan selayaknya penyebab utama kerusakan hati nampaknya merupakan efek langsung pada sel hati, yang meningkat pada saat malnutrisi. Pasien dapat mengalami defisiensi beberapa nutrisi, termasuk tiamin, asam folat, piridoksin, niasin, asam askorbat dan vitamin A. Pengeroposan tulang sering terjadi akibat asupan nutrisi yang menurun dan gangguan metabolisme. Asupan vitamin K, besi dan seng juga cenderung menurun pada pasien-pasien ini. Defisiensi kalori protein juga sering terjadi. Degenerasi lemak tidak berkomplikasi pada hati seperti yang terlihat pada alkoholisme dini bersifat reversible bila berhenti minum alkohol, beberapa kasus dari kondisi yang relatife jinak ini akan berkembang menjadi sirosis. Secara makroskopik hati membesar, rapuh, tampak berlemak, dan mengalami gangguan fungsional akibat akumulasi lemak dalam jumlah banyak. Bila kebiasaan minum alkohol diteruskan, terutama apabila semakin berat, dapat terjadi suatu hal (belum diketahui penyebabnya) yang akan memacu seluruh proses sehingga akan terbentuk jaringan parut yang luas. Sebagian pakar yakin bahwa lesi kritis dalam perkembangan sirosis hati mungkin adalah hepatitis alkoholik. Hepatitis alkoholik ditandai secara histologis oleh nekrosis hepatoseluler, sel-sel balon, dan infiltrasi lekosit PMN (Poli Morfonuklear) di hati. Akan tetapi, tidak semua penderita lesi hepatitis alkoholik akan berkembang menjadi sirosis hepatik yang lengkap. Pada kasus sirosis Lannec sangat lanjut, lembaran-lembaran jaringan ikat akan terbentuk pada tepi yang lobulus, membagi parenkim menjadi nodul-nodul halus. Nodul-nodul ini dapatmembesar akibat aktivitas regenerasi sebagai upaya hati untuk mengganti sel-sel hati yang rusak. Hati tampak terdiri dari sarang-sarang sel-sel degenerasi dan regenerasi yang dikemas padat dalam kapsula fibrosa yang tebal. Pada keadaan ini sirosis sering disebut sebagai sirosis nodular halus. Hati akan menciut, keras, dan hampir tidak memiliki parenkim normal pada stadium akhir sirosis, yang menyebabkan terjadinya hipertensi portal dan gagal hati. Penderita sirosis Lannec lebih beresiko menderita karsinoma sel hati primer (hepatoseluler). 2. Sirosis Pasca Nekrotik Sirosis pasca nekrotik agaknya terjadi setelah nekrosis berbercak pada jaringan hati. Hepatosit dikelilingi dan dipisahkan oleh jaringan parut dengan kehilangan banyak sel hati dan diselingi dengan parenkim hati normal. Sekitar 75% kasus cenderung berkembang dan berakhir dengan kematian dalam satu hingga lima tahun. Kasus sirosis pasca nekrotik berjumlah sekitar 10% dari kasus sirosis, sekitar 25-75% kasus memiliki riwayat hepatitis virus sebelumnya. Banyak pasien yang memiliki hasil uji HBsAg positif, sehingga menujukkan bahwa hepatitis kronis aktif agaknya merupakan peristiwa penting. Kasus HCV merupakan sekitar 25% dari kasus sirosis. Sejumlah kecil kasus akibat intoksikasi yang pernah diketahui adalah dengan bahan kimia industri, racun, ataupun obat-obatan seperti fosfat, kontrasepsi oral, metildopa, arsenic dan karbon tetrakhlorida. Ciri khas sirosis pasca nekrotik adalah bahwa tampaknya sirosis ini adalah faktor predisposisi timbulnya neoplasma hati primer (karsinoma hepatoseluler). Resiko ini meningkat hamper 10 kali lipat pada pasien carier dibandingkan pada pasien bukan carier (Hildt, 1998). 3. Sirosis Biliaris Kerusakan sel hati yang dimulai disekitar duktus biliaris akan menimbulkan pola sirosis yang dikenal sebagai sirosis biliaris. Tipe ini merupakan 2% penyebab kematian akibat sirosis. Penyebab tersering sirosis biliaris adalah obstruksi biliaris pasca hepatik. Stasis empedu menyebabkan penumpukan empedu di dalam massa hati dan kerusakan sel-sel hati. Terbentuk lembarlembar fibrosa di tepi lobulus, namun jarang memotong lobulus seperti pada sirosis Lannec. Hati membesar, keras, bergranula halus, dan berwarna kehijauan. Ikterus selalu menjadi bagian awal dan utama dari sindrom ini, demikkian pula pruritus, malabsorbsi dan steatorea. Sirosis biliaris primer menampilkan pola yang mirip dengan sirosis biliaris sekunder yang baru saja dijelaskan di atas, namun lebih jarang ditemukan. Penyebab keadaan ini (yang berkaitan dengan lesi-lesi duktulus empedu intrahepatik) tidak diketahui. Sirosis biliaris primer paling sering terjadi pada perempuan usia 30-65 tahun dan disertai dengan berbagai gangguan autoimun (misalnya, tiroiditis autoimun atau artritis rheumatoid). Antibody antimitikondrial dalam sirkulasi darah (AMA) terdapat dalam 90% pasien. Sumbat empedu sering ditemukan dalam kapiler-kapiler dan duktulus empedu, dan sel-sel hati sering kali mengandung pigmen hijau. Saluran empedu ekstrahepatik tidak ikut terlibat. Hipertensi portal yang timbul sebagai komplikasi, jarang terjadi. Osteomalasia terjadi pada sekitar 25% penderita sirosis biliaris primer (akibat menurunnya absorbsi vitamin D). Dalam arti sederhana, ensefalopati hepatik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk intoksikasi otak yang disebabkan oleh isi usus yang tidak mangalami metabolisme dalam hati. Keadaan ini dapat terjadi bila terjadi kerusakan sel hati akibat nekrosis, atau terdapat pirau (patologis atau akibat pembedahan) yang memungkinkan darah portal mencapai sirkulasi sistemik dalam jumlah besar tanpa melewati hati. Metabolit yang menyebabkan timbulnya ensefalopati belum diketahui pasti. Mekanisme dasar tampaknya adalah karena intoksikasi otak oleh produksi pemecahan metabolisme protein oleh kerja 3bakteri dalam usus. Hasil metabolisme ini dapat memintas hati karena terdapat penyakit pada sel hati atau karena terdapat pirau. NH3 (yang dalam keadaan normal diubah menjadi urea oleh hati) merupakan salah satu zat yang diketahui bersifat toksik dan diyakini dapat mengganggu metabolisme otak. Ensefalopati hepatik biasanya dipercepat oleh keadaan seperti: pendarahan saluran cerna, asupan protein berlebihan, obat diuretik, parasentesis, hipokalemia, infeksi akut, pembedahan, azotemia, dan pemberian morfin, sedative, atau obat mengandung NH3. Azotemia adalah retensi zat nitrogenosa (misal, urea) dalam darah yang normalnya difiltrasi oleh ginjal. Efek berbahaya dari zat-zat ini dapat ditelusuri pada mekanisme yang mengakibatkan pembentukan ammonia dalam jumlah besar dalam usus. Ensefalopati yang menyertai kekurangan kalium atau parasentesis dapat dihubungkan dengan pembentukan NH3 yang berlebihan oleh ginjal dan perubahan keseimbangan asam atau basa.2.3 Manifestasi KlinisGejala dan tanda klinis ensefalopati hepatik dapat timbul sangat cepat dan berkembang menjadi koma bila terjadi gagal hati pada penderita hepatitis fulminan. Pada penderita sirosis, perkembangannya berlangsung lebih lambat dan bila ditemukan pada stadium dini masih bersifat reversibel. Perkembangan ensefalopati hepatik menjadi koma biasanya dibagi dalam empat stadium. Tanda-tanda pada stadium I tidak begitu jelas dan mungkin sukar diketahui. Tanda yang berbahaya adalah sedikit perubahan kepribadian dan tingkah laku, termasuk penampilan yang tidak terawat baik, pandangan mata kosong, bicara tidak jelas, tertawa sembarangan, pelupa, dan tidak mampu memusatkan pikiran. Penderita mungkin cukup rasional, hanya terkadang tidak kooperatif atau sedikit kurang ajar. Pemantauan yang seksama menunjukkan bahwa mereka lebih letargi atau tidur lebih lama dari biasa, atau irama tidurnya terbalik. Perawat berada dalam posisi yang strategis untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat meminta bantuan keluarga pasien untuk mencari perubahan kepribadian ringan tersebut karena perawat memiliki hubungan yang erat dengan penderita seperti ini. Tanda-tanda pada stadium II lebih menonjol daripada stadium I dan mudah diketahui. Terjadi perubahan perilaku yang tidak semestinya, dan pengendalian sfingter tidak dapat terus dipertahankan. Kedutan otot generalisata dan asteriksis merupakan temuan khas. Asteriksis (atau flapping tremer) dapat dicetuskan bila penderita disuruh mengangkat kedua lengannya dengan lengan atas difiksasi, pergelangan tangan hiperekstensi , dan jari-jari terpisah. Perasat ini menyebabkan gerakan fleksi dan ekstensi involuntar cepat dari pergelangan tangan dan sendi metakarpolafang. Asteriksis merupakan suatu manifestasi perifer gangguan metabolisme otak. Keadaan semacam ini dapat juga timbul pada sindrom uremia. Pada tahap ini, letargi serta perubahan sifat dan kepribadian menjadi lebih jelas terlihat. Apsraksia konstitusional adalah gambar lain yang mencolok dari ensefalopati hepatik. Penderita tidak dapat menulis atau menggambar dengan baik seperti menggambar bintang atau rumah. Sederetan tulisan tangan atau gambar merupakan cara yang berguna untuk menentukan perkembangan ensefalopati. Pada stadium III, penderita dapat mengalami kebingungan yang nyata dengan perubahan prilaku. Bila pada saat ini penderita hanya diberi sedatif dan bukan pengobatan untuk mengatasi proses toksiknya, maka ensefalopati mungkin berkembang menjadi koma, dan prognosisnya fatal. Selamastadium ini, penderita dapat tidur sepanjang waktu. Elektroensefalogram mulai berubah pada stadium II dan menjadi abnormal pada stadium III dan IV. Pada stadium IV, penderita masuk pada keadaan koma yang tidak dapat dibangunkan, sehingga timbul refleks hiperaktif dan tanda Babinsky. Pada saat ini bau apek yang manis (fetor hepatikum) dapat tercium pada nafas penderita, atau bahkan waktu masuk ke dalam kamarnya. Faktor hepatikum merupakan tanda prognasis yang buruk, dan intensitas baunya sangat berhubungan dengan derajat somnolensia dan kekacauan. Hasil pemeriksaan laboratorium tambahan adalah kadar amonia darah yang meningkat, dan hal ini dapat membantu mendeteksi ensefalopati. Gambaran klinis dan komplikasi sirosis hati umumnya sama untuk semua tipe tanpa memandang penyebabnya, meskipun beberapa tipe sirosis yang tersendiri mungkin memiliki gambaran klinis dan biokimia yang agak berbeda. Masa ketika sirosis bermanifestasi sebagai masalah klinis hanyalah sepenggal waktu dari perjalanan klinis selengkapnya. Sirosis bersifat laten selama bertahuntahun, dan perubahan patologis yang terjadi berkembang lambat hingga akhirnya gejala yang timbul menyadarkan akan adanya kondisi ini. Selama masa laten yang panjang, terjadi kemunduran fungsi hati secara bertahap. Gejala dini bersifat sama dan tidak spesifik yang meliputi kelelahan, anoreksia, dyspepsia, flatulen, perubahan kebiasaan defekasi ( konstipasi/diare), dan berat badan sedikit berkurang. Mual dan muntah lazim terjadi ( terutama pada pagi hari ). Nyeri tumpul atau perasaan berat pada episgastrium atau kuadran kanan atas terdapat pada sekitar separuh penderita. Pada sebagian besar kasus, hati keras dan mudah teraba tanpa memandang apakah hati membesar atau mengalami atropi. Manifestasi utama dan lanjut dari sirosis terjadi akibat dua tipe gangguan fisiologis: gagal sel hati dan hipertensi portal. Manifestasi hepato seluler adalah ikterus, edema perifer, kecenderungan perdarahan, eritema palmaris (telapak tangan merah), angioma laba-laba, fetor hepatikum, dan encepalohepatik. Gambaran klinis yang terutama berkaitan dengan hipertemnsi portal adalah splenomegali, varises esophagus dan lambung, serta manifestasi sirkulasi kolateral lain. Asites (cairan dalam rongga peritoneum) dapat dianggap sebagai manifestasi kegagalan hepatoselular dan hipertensi portal. Manifestasi Gagal Hepatoseluler Ikterus terjadi sedikitnya pada 60% penderita selama perjalanan penyakitnya dan biasanya hanya minimal. Hiperbilirubinemia tanpa ikterus lebih sering terjadi. Penderita dapat menjadi ikterus selama fase dekompensasi disertai gangguan reversibel fungsi hati. Misalnya, penderita sirosis dapat menjadi ikterus setelah bertanding minum alkohol. Ikterus intermitten merupakan gambaran khas sirosis biliaris dan terjadi bila timbul peradangan aktif hati dan saluran empedu (kolangitis). Penderita yang meninggal akibat gagal hati biasanya mengalami ikterus. Gangguan endokrin sering terjadi pada sirosis. Hormon korteks adrenal, testis, dan ovarium dimetabolisme dan diinaktifkan oleh hati normal. Angioma laba-laba terlihat pada kulit, terutama di sekitar leher, bahu, dan dada. Angioma ini terdiri atas arteriola sentral tempat memancarnya banyak pembuluh halus. Angioma laba-laba, atrofi testis, ginekomastia, alopesia pada dada dan aksila, serta eritema palmaris (telapak tangan merah) semuanya diduga akibat aktivitas hormon perangsang melanosit (melanocyte-stimulating hormone,MSH) yang bekerja secara berlebihan. Gangguan hematologik yang sering terjadi pada sirosis adalah kecenderungan pendarahan, anemia, leukopenia, dan trombositopena. Penderita sering mengalami pendarahan hidung, gusi, menstruasi berat,dan mudah memar. Masa protrombin dapat memanjang. Manifestasi ini terjadi akibat 5berkurangnyapambentukanfaktor-faktorpembekuanolehhati.Anemia,leukopenia,dantrombositopenia diduga terjadi akibat hipersplenisme. Limpa tidak hanya membesar (splenomegali) tetapi juga lebih aktif menghancurkan sel-sel darah dari sirkulasi. Mekanisme lain yang menimbulkan anemia adalah defisiensi folat, vitamin B12, dan besi yang terjadi sekunder akibat kehilangan darah dan peningkatan hemolisis eritrosit. Penderita juga lebih mudah terserang infeksi. Edema perifer umumnya terjadi setelah timbulnya asites dan dapat dijelaskan sebagai abibat hipoalbuminemia dan retensi garam dan air. Kegagalan sel hati ikut menginaktifkan aldosteron dan hormon antidiuritak merupakan penyebab retensi natrium dan air. Faktor hepatikum adalah bau apek manis yang terdeteksi dari napas penderita (terutama pada koma hepatikum) dan diyakini terjadi akibat ketidakmampuan hati dalam memetabolisme metionin. Gangguan nerologis yang paling serius pada sirosis klanjut adalah ensefalopati hepatik (koma hepatikum), yang diyakini terjadi akibat kelainan metabolisme amonia dan peningkatan kepekaan otak terhadap toksin. Berkembangnya ensefalopati hepatik sering merupakan keadaan terminal sirosis dan akan dibicarakan lebih mendalam kemudian. Manifestasi hipertensi portal Hipertensi portal didefinisikan sebagai peningkatan tekanan vena porta yang menetap di atas nilai normal yaitu 6 sampai 12 cm H2O. Tanpa memandang penyakit dasarnya, mekanisme primer penyebab hipertensi portal adalah peningkatan resistensi terhadap aliran darah melalui hati. Selain itu, biasanya terjadi peningkatan aliran arteria spalngnikus. Kombinasi kedua faktor itu yaitu menurunnya aliran keluar melalui vena hepatika dan meningkatnya aliran masuk bersama-sama menghasilkan beban berlebihan pada sistem portal. Pembebanan berlebihan sistem portal ini merangsang timbulnya aliran kolateral guna menghindari obstruksi hepatik (varises). Tekanan balik pada sistem portal menyebabkan splenomegali dan sebagian bertanggung jawa atas tertimbunnya asites. Asites merupakan penimbunan cairan encer intraperitonial yang mengandung sedikit protein. Faktor utama patogenesis asites adalah peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler usus (hipertensi porta) dan penurunan tekanan osmotik koloid akibat hipoalbuminemia. Faktor lain yang berperan adalah retensi natrium dan air serta peningkatan sintesis dan aliran limfe hati. Saluran kolateral penting yang penting yang timbul akibat sirosis dan hipertensi portal terdapat pada esophagus bagian bawah. Pirau darah melalui saluran ini ke vena cava menyebabkan dilatasi vena-vena tersebut (varises esophagus). Varises ini terjadi pada sekitar 70% penderita serosis lanjut. Perdarahan pada varises ini sering menyebabkan kematian. Sirkulasi kolateral juga melibatkan vena superficial dinding abdomen, dan timbulnya sirkulasi ini mengakibatkan dilatasi vena-vena sekitar umbilicus (kaput medusa). Sistem vena rectal membantu dekompensasi tekanan portal sehingga vena-vena terdilatasi dan dapat menyebabkan berkembangnya hemoroid interna. Perdarahan dari hemoroid yang pecah tidak hebat, karena tekanan di daerah ini tidak setinggi tekanan pada esophagus Karena jarak yang terlalu jauh dari vena porta. Splenomegali pada serosis dapat dijelaskan berdasarkan kongesti pasif kronis akibat aliran balik dan tekanan darah yang lebih tinggi pada vena lienalis.2.4 KomplikasiBeberapa komplikasi yang dapat terjadi pada sirosis hepatic adalah: 1. Pendarahan saluran cerna Penyebab pendarahan saluran cerna yang paling sering dan paling berbahaya pada sirosis adalahperdarahan dari varises esophagus yang merupakan penyebab dari sepertiga kematian. Penyebab lain dari perdarahan adalah tukak lambung dan duodenum (pada sirosis, insidensi gangguan ini meningkat), erosi lambung akut, dan kecenderungan perdarahan (akibat masa protrombin yang memanjang dan trombositopenia). Penderita datang dengan melena atau hematemesis. Tanda pendarahan kadang-kadang adalah ensefalopati hepatik. Hipovolemia dan hipotensi dapat terjadi bergantung pada jumlah dan kecepatan kehilangan darah. Berbagai tindakan telah digunakan untuk segera mengatasi perdarahan. Tamponade dengan alat seperti pipa Sengstaken-Blakemore (triple-lumen) dan Minnesota (quadruple-lumen) dapat menghentikan perdarahan untuk sementara waktu. Vena-vena dapat dilihat dengan memakai peralatan serat optik dan disuntik dengan suatu larutan yang akan membentuk bekuan di dalam vena, sehingga akan menghentikan perdarahan. Sebagian besar klinisi beranggapan bahwa cara ini hanya berefek sementara dan tidak efektif untuk pengobatan jangka panjang. Vasopresin (Pitressin) telah digunakan untuk mengatasi perdarahan. Obat ini menurunkan tekanan porta dengan mengurangi aliran darah splangnik, walaupun efeknya hanya bersifat sementara. Kendati telah dilakukan tindakan darurat, sekitar 35% penderita akan meninggal akibat gagal hati dan komplikasi. Bila penderita pulih dari perdarahan (baik secara spontan atau setelah pengobatan darurat), operasi pirau porta-kaval harus dipertimbangkan. Pembedahan ini mengurangi tekanan portal dengan melakukan anastomosis vena porta (tekanan tinggi) dengan vena kava inferior (tekanan rendah). Pirau merupakan terapi drastik untuk komplikasi utama sirosis ini. Operasi ini memperkecil kemungkinan perdarahan esophagus selanjutnya, tetapi menambah resiko ensefalopati hepatic. Harapan hidup penderita tidak bertambah karena masih ditentukan oleh perkembangan penyakit hati. Perdarahan saluran cerna merupakan salah satu faktor penting yang mempercepat terjadinya ensefalopati hepatik. Ensefalopati terjadi bila ammonia dan zat-zat toksik lain masuk dalam sirkulasi sistemik. Sumber ammonia adalah pemecahan protein oleh bakteri pada saluran cerna. Ensefalopati hepatik akan terjadi bila darah tidak dikeluarkan melalui aspirasi lambung, pemberian pencahar, dan enema, dan bila pemecahan protein darah oleh bakteri tidak dicegah dengan pemberian neomisin atau antibiotik sejenis. 2. Asites Asites adalah penimbunan cairan serosa dalam rongga peritoneum, merupakan manifestasi cardinal sirosis dan bentuk berat lain dari penyakit hati. Beberapa faktor yang turut terlibat dalam patogenesis asites pada sirosis hati: (1) hipertensi porta, (2) hipoalbuminemia, (3) meningkatnya pembentukan dan aliran limfe hati (4) retensi natrium, (5) gangguan ekskresi air. Mekanisme primer penginduksi hipertensi porta, seperti yang telah dijelaskan, adalah resistensi terhadap aliran darah melalui hati. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam jaringan pembuluh darah intestinal. Hipoalbuminemia menyebabkan menurunnya tekanan osmotik koloid. Kombinasi antara tekanan hidrostatik yang meningkat dengan tekanan osmotik yang menurun dalam jaringan pembuluh darah intestinal menyebabkan terjadinya transudasi cairan dari ruang intravaskuler ke ruang interstitial sesuai denagn hukum gaya Starling (ruang peritoneum dalam kasus asites). Hipertensi porta kemudian meningkatkan pembentukan limfe hepatic, yang menyeka dari hati ke dalam rongga peritoneum. Mekanisme ini dapat turut menyebabkan tingginya kandungan protein dalam cairan asites, sehingga meningkatkan tekanan osmotik koloid dalam cairan rongga peritoneum dan memicu terjadinya transudasi cairan dari rongga intravaskuler ke ruang peritoneum. Yang terakhir, retensi natrium dan 7gangguan ekskresi air merupakan faktor penting dalam berlanjutnya asites. Retensi air dan natrium disebabkan oleh hiperaldosteronisme sekunder (penurunan volume efektif dalam sirkualsi mengaktifkan mekanisme rennin-angiotensin-aldosteron). Penurunan inaktivasi aldosteron sirkulasi oleh hati juga dapat terjadi akibat kegagalan hepatoselular. Suatu tanda asites adalah meningkatnya lingkar abdomen. Penimbunan cairan yang sangat nyata dapat menyebabkan nafas pendek karena diafragma meningkat. Dengan semakin banyaknya penimbunan cairan peritoneum, dapat dijumpai cairan lebih dari 500 ml pada saat pemeriksaan fisik dengan pekak alih, gelombang cairan, dan perut yang membengkak. Jumlah yang lebih sedikit dapat dijumpai dari pemeriksaan USG atau parasentesis. Pembatasan garam adalah metode utama pengobatan asites. Obat diuretik juga dapat digunakan digabungkan dengan diet rendah garam. Kini telah tersedia berbagai obat dan program diuretik, namun yang penting adalah memberikan diuretik secara bertahap untuk menghindari diuresis berlebihan. Kehilangan cairan dianjurkan tidak lebih dari 1 kg per hari bila terjadi edema perifer dan asites. Ketidakseimbangan elektrolit harus dihindari, sebab obat diuretik dapat mencetuskan ensefalopati hepatikum. Parasentesis adalah tindakan memasukkan sesuatu kanula ke dalam rongga peritoneum untuk mengeluarkan cairan asites. Pada masa lalu, parasentesis adalah suatu bentuk pengobatan lazim untuk asites, namun tidak lagi digunakan karena memiliki efek yang merugikan. Terdapat bahaya tercetusnya hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia, ensefalpati hepatica, dan gagal ginjal. Cairan asites dapat mengandung 10-30 gram protein per liter, sehingga albumin serum mengalami deplesi, mencetuskan hipotensi, dan tetimbunnya kembali cairan asites. Oleh karena itu penggantian albumin melalui IV dapat diberikan saat parasentesis untuk menghindari timbulnya komplikasi ini. Parasentesis biasanya dilakukan hanya untuk alasan diagnostik dan bila asites menyababkan kesulitan bernafas yang berat akibat volume cairan yang besar. Beberapa penderita asites juga mengalami efusi pleura, terutama dalam hemitora kanan. Cairan ini diperkirakan memasuki thorax melalui air mata dalam pars tendinosa diafragma karena tekanan abdomen yang meningkat. Ensefalopati Hepatik Ensefalopati hepatik (koma hepaticum) merupakan sindrom neuropsikiatri pada penderita penyakit hati berat. Sindrom ini ditandai oleh kekacauan mental, tremor otot, dan flapping tremor yang disebut sebagai asteriksis. Perubahan mental diawali dengan perubahan kepribadian, hilang ingatan, dan iritabilitas yang dapat berlanjut hingga kematian akibat koma dalam. Ensefalopati hepatik yang berakhir dengan koma adalah mekanisme kematian yang terjadi pada sepertiga kasus sirosis yang fatal. Tabel 1. Faktor- Faktor yang Biasanya Dapat Mencetuskan Ensefaloti Hepatik ( Hepatic Encephalopathy, HE ) Faktor pencetus Mekanisme yang mungkin menyebabkan HEPeningkatan nitrogenbebanPerdarahan Saluran Cema Darah yang berlebihan dalam saluran cerna (10 hingga 20 g Makanan protein dalm mengandung protein /dl) atau makanan mengandung protein yang dalam jumlah protein berlebihan menyediakan subtrat bagi peningkatan banyak pembentukan amonia (NH3). Kerja bakteri usus pada proteinAzotema ( BUN yang menimbulkan NH yang diabsorpsi dan normalnya 3 meningkay) Konstipasi didetoksifikasi dalam hati melalui konversi menjadi urea. Kadar NH3 yang meningkat memasuki sirkulasi sistemik bila terdapat kegagalan hepatoseluler atau pirau portosistemik. NH3 ( dan mungkin metobilit toksik lainnya) dengan cepat meleati sawar darah otak, dan di tempat ini NH3 memiliki efek toksik langsung pada otak. Gangguan fungsi ginjal dan meningkatnya BUN menyebabkan lebih baik urea yang berdifusi dalam usus. Konstipasi meningkatkan produksi dan absorpsi NH4 karena kontak yang lama antara subtrat protein Ketidakseimbangan elektrolit Alkalosis Hipokalemia Hipovolemia Alkanosis dan hipokalemia seringkali disebabkan oleh hiperventilasi dan muntah, menyebabkan difusi NH3 dari cairan ekstrasel ke cairan intrasel, termasuk sel-sel otak yang menyebabkan efek toksik. Pada alkalosis, lebih banyak NH3 yang diproduksi dari glutamin dalam ginjal yang kembali memasuki sirkulasi sistemik dibandingkan yang disekresi sebagai sebagai ion amonium (NH4+). Hivolernia ( yang disebabkan oleh perdarahan saluran cerna ), pemakaian diuretik berlebihan, atau parasentesis, dapat mencetuskan HE dengan cara memnyebabkan gagal ginjal dan azotemia, yang Obat-obatan Obat Diuretik Tranquilizer,narkotika, sedatif, anestetik pada gilirannya menyebabkan meningkatnya NH3 darah. Pemakaian diuretik yang terlalu radikal dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, meliputi alkalosis, hipokalemia, dan hipovolemia. Oleh karena itu obat diuretik pendeplesi kalium sebaiknya dihindari. Obat sedatif dan obat-obatan lain yang menyebabkan defresi susunan saraf pusat bekerja secara sinergis dengan NH3. Metabolisme Lain-lain Infeksi Pembedahan Infeksi atau pembedahanmeningkatkan katabolisme jaringan, 9 obat-obatan ini yang terganggu dapat terjadi akibat kegagalan hepatoselular. dengan bakteri usus.menyebabkan Hipertermia,peningkatan dehidrasi,produksiBUNdanNH3. ginjaldangangguanfungsiberpotensi menyebabkan toksisitas NH3.Sindrom Hepatorenal Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah diketahui bahwa sindroma hepatorenal (SHR) merupakan komplikasi terminal pada pasien sirosis hati dengan ascites. Timbulnya gagal ginjal tanpa adanya gejala klinis dan bukti histologis yang diketahui sebagai penyebab timbulnya gagal ginjal tersebut. Pada SHR kelainan yang dijumpai pada ginjal hanya berupa kegagalan fungsi tanpa ditandai dengan kelainan anatomi. Hal ini dapat dibuktikan bila ginjal tersebut ditansplantasikan pada penderita lain yang tidak didapati kelainan hati, maka fungsi ginjal tersebut akan kembali normal atau penderita yang mengalami SHR dilakukan transpalantasi hati maka fungsi ginjalnya akan kembali normal. Selain perubahan fungsi ginjal, penderita SHR juga ditandai dengan perubahan sirkulasi arteri sistemik dan aktifitas sistim vasoactive endogen yang berperan dalam terjadinya hipoperfusi ke ginjal. Dengan alasan ini SHR merupakan kumpulan patofisiologi yang unik untuk diketahui hubungan antara sirkulasi sistemik dan fungsi ginjal serta pengaruh factor vasokonstriktor dan vasodilator pada sirkulasi ginjal. SHR dilaporkan pertama sekali oleh Austin Flint dan Frerichs (1863), yang masing-masing melaporkan timbulnya oligura pada pasien-pasien sirosis dengan asites, mereka tidak menemukan adanya perubahan histology ginjal yang nyata pada pemeriksaan post mortem. Pierre Vesin salah satu peneliti tentang aspek klinis fungsi ginjal pada sirosis, mengusulkan definisi SHR dengan nama terminal fungtional renal failure. Beliau menekankan gagal ginjal pada SHR tidak berhubungan dengan kerusakan struktur ginjal dan berkembangnya sindroma ini merupakan keadaan terminal dan orreversible pada sirosis dengan asites. Pada tahun 1956, Hecker dan Sherlock melaporkan sembilan pasien penyakit hati bersamaan dengan gagal ginjal yang ditandai dengan protein uria dan ekskresi NA+ yang rendah. Defenisi Sindroma Hepato Renal yang diusulkan oleh International Ascites Club (1994) adalah sindroma klinis yang terjadi pada pasien penyakit hati kronik dan kegagalan hati lanjut serta hipertensi portal yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal dan abnormalitas yang nyata dari sirkulasiarteri dan aktifitas system vasoactive endogen. Pada ginjal terdapat vasokonstriksi yang menyebabkan laju filtrasi glomerulus rendah, dimana sirkulasi diluar ginjal terdapat vasodilasi arteriol yang luas menyebabkan penurunan resistensi vaskuler sistemik total dan hipotensi. Meskipun sindroma hepatorenal lebih umum terdapat pada penderita dengan sirosis lanjut, hal ini dapat juga timbul pada penderita penyakit hati kronik atau penyakit hati akut lain seperti hepatitis alkoholik atau kegagalan hati akut. Dagher dkk melaporkan insiden SHR terjadi kira-kira 4% pada penderita sirosis hati dekompensata yang dirawat, dan kemungkinan mencapai 18% pada tahun pertama dan akan meningkat hingga 39% pada tahun ke lima. Gines dkk melaporkan insiden SHR pada penderita sirosis hati dengan ascites yang dirawat mencapai 10% kasus. Patofisiologi Hal yang sama ditemukan pada SHR adalah vasokonstriksi ginjal yang reversible dan hipotensi sistemik. Keberadaan vasokonstriksi ginjal yang nyata pada penderita SHR telah ditunjukkan dengan beberapa metode eksplorasi termasuk arteriografi ginjal, klirens para aminohipuric acid dan yang terbaru ultrasonografi Doppler. Pemakaian beberapa teknik ini mendapatkan beberapa perubahan dalam perfusi ginjal yang berkesinambungan pada penderita sirosis dengan ascites, dan SHR adalah akhir dari spectrum ini. Penyebab utama dari vasokonstriksi ginjal ini belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan melibatkan banyak factor antara lain perubahan system hemodinamik, meningginya tekanan vena porta, peningkatan vasokonstriktor dan penurunan vasodilator yang berperan dalam sirkulasi di ginjal Teori hipoperfusi ginjal menggambarkan manisfestasi dari kekurangan pengisian sirkulasi arteri terhadap adanya vasodilatasi pembuluh darah splanik. Pengurangan pengisian arteri ini akan menstimulasi baroreseptor mengaktifkan vasokonstriktor (seperti renin angiotension dan system saraf simpatis). Faktor-faktor Vasoaktif secara potensial berperan dalam pengaturan perfusi ke ginjal pada penderita sindroma hepatorenal. Vasokonstriktor Sistem rennin angiotension dan system saraf simpatik, beberapa dari system utama yang mempunyai efek vasokonstriksi pada sirkulasi ginjal berperan sebagai mediator utama vasokonstriksi ginjal pada sindroma hepatorenal. Aktifitas dari system vasokonstruksi ini meningkat pada penderita dengan sirosis dan ascites, terutama penderita dengan sindroma hepatorenal dan berkolerasi terbalik dengan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Kadar hormon anti diuretic atau vasopressin meninggi pada penderita SHR karena stimulasi non osmolar, walaupun sering timbul hiponatremia. Vasopressin ini menimbulkan vasokonstriksi di ginjal. Endothelin adalah substansi vasokonstriktor lain dalam plasma yang meningkat pada SHR, kemungkinan karena penambahan produksi peptide dalam hati atau dalam sirkulasi splandik yang hubungannya dengan vasokonstriksi ginjal masih controversial. Soper dkk melaporkan pada tiga penderita SHR memperlihatkan perbaikan fungsi ginjal setelah pemberian antagonis spesifik reseptor endhothelin A. Beberapa penelitian melaporkan peningkatan produksi cysteinyl leukotrienes sebagai vasokonstriksi ginjal yang kuat pada penderita SHR. Substansi vasoactive lainnya seperti adenisin, F2-isoprostanes dapat juga sebagai factor yang mempengaruhi patogenesa vasokonstriksi ginjal dalam SHR, tapi mekanisme yang pasti masih belum diketahui. 11Endotoksin dan sitokin juga berperan dalam timbulnya vasokonstriksi ginjal yang poten daan SHR timbul setelah infeksi bakteri yang berat pada sirosis. Hal ini diduga katrena peningkatan translokasi bakteri dan portosystemic shunting. Bagaimanapun peran endotoksin dan sitokin dalam disfungsi ginjal pada sirosis masih merupakan perdebatan. Vasodilator Sebuah penelitian pada penderita dengan sirosis atau percobaan pada binatang memperlihatkan bahwa sintesa factor vasodilator local pada ginjal memaikan peran yang penting dalam mempertahankan perfusi ginjal dengan melindungi sirkulasi ginjal dari efek yang merusak dari factor vasokonstriktor. Mekanisme vasodilator ginjal yang paling penting adalah prostaglandin (PGs). PGs membentuk sitem yang unik dimana ginjal mampu mengimbangi efek peningkatan kadar vasokonstriktor tanpa merusak fungsi sitemiknya. Bukti yang paling kuat menyokong peran PGs ginjal dalam mempertahankan perfusi ginjal pada sirosis dengan ascietes diperoleh dari penelitian yang menggunakan obat non steroid anti inflamasi untuk menghambat pembentukan prostaglandin ginjal. Pemberian NSAIDs, sekalipun dalam dosis tunggal pada penderita sirosis hati dengan ascites menyebabkan penurunan yang nyata dalam aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus, yang perubahannya menyerupai kejadian dalam SHR pada penderita dengan aktifitas vasokonstriktor yang nyata, tetapi tidak atau sedikit efek pada penderita dengan aktifitas vasokonstriktor yang nyata, tetapi tidak atau sedikit atau sedikit efek pada penderita tanpa aktifitas vasokonstriktor. Vasodilator ginjal lainnya yang mungkin berpartisipasi dalam mempertahankan perfusi ginjal pada sirosis adalah nitrit oksida. Jika produksi nitrit oksida dan PGs dihambat secara tidal langsung dalam percobaan sirosis dengan ascites terjadi penurunan perfusi ginjal Vasodilator lain yang mungkin mempengaruhi pengaturan perfusi ginjal pada sirosis adalah natriuretic peptide. Gulberg dkk menemukan peningkatan jumlah C Type natriuretic peptide (CNP) di urin penderita sirosis dan gagal ginjal fungsional, selanjutnya ditemukan hubungan yang terbalik antara CNP di urin dengan ekskresi natrium urin, CNP ini berperan dalam pengaturan keseimbangan natrium. Penemuan ini membuktikan aktifitas vasodilator ginjal meningkat pada sirosis dan berperan dalam pengaturan perfusi ginjal, terutama pada aktifitas yang berlebihan dari mekanisme vasokonstriktor ginjal Sistem saraf simpatis Stimulasi system saraf simpatis sangat tinggi pada penderita SHR dan menyebabkan vasokonstriksi ginjal dan meningkatnya retensi natrium. Hal ini telah diperlihatkan oleh beberapa peneliti adanya peningkatan sekresi katekolamin di pembuluh darah ginjal dan splanik. Kostreva dkk mengamati vasokonstruksi pada arteiol afferent ginjal menimbulkan penurunan aliran darah ginjal dan GFR dan meningkatkan penyerapan air dan natrium di tubulus. Patogenesia Ada dua jenis teori yang dianut untuk menerangkan hipoperfusi ginjal yang timbul pada penderita SHR. Teori pertama, menjelaskan hipoperfusi ginjal berhubungan dengan penyakit hati itu sendiri tanpa ada patogenetik yang berhubungan dengan gangguan system hemodinamik. Teori ini berdasarkan hubungan langsung hati ginjal, yang didukung oleh dua mekanisme yang berbeda yang mana penyakit hati dapat menyebabkan vasokonstriksi ginjal dengan penurunan pembentukan atau pelepasan vasodilator yang dihasilkan hati yang dapat menyebabkan pengurangan perfusi ginjaldan pada percobaan binatang diperlihatkan bahwa hati mengatur fungsi ginjal melalui refleks hepatorenal. Teori kedua menerangkan bahwa hipoperfusi ginjal berhubungan dengan perubahan patogenetik dalam system hemodinamik dan SHR adalah bentuk terakhir dari pengurangan pengisian arteri pada sirosis. Hipotesis ini menerangkan bahwa kekurangan pengisian sirkulasi arteri bertanggung jawab terhadap hipoperfusi yang bukan sebagai akibat penurunan volume vaskuler, tetapi vasodilatasi arteriolar yang luar biasa terjadi terutama pada sirkulasi splanik. Hal ini dapat menyebabkan aktifasi yang progresif dari mediator baroreseptor system vasokonstriktor, yang mana dapat menimbulkan vasokonstruksi tidak hanya pada sirkulasi ginjal tetapi juga pada pembuluh darah yang lain. Gambaran Klinis Mekanisme klinis penderita SHR ditandai dengan kombinasi antara gagal ginjal, gangguan sirkulasi dan gagal hati. Gagal ginjal dapat timbul secara perlahan atau progresif dan biasanya diikuti dengan retensi natrium dan air yang menimbulkan ascites, edema dan dilutional hyponatremia, yang ditandai oleh ekresi natrium urin yang rendah dan pengurangan kemampuan buang air (oligurianuria ). Gangguan sirkulasi sistemik yang berat ditandai dengan tekanan arteri yang rendah, peningkatan cardiac output, dan penurunan total tahanan pembuluh darah sistemik. Beberapa gangguan hemodinamik yang sering ditemukan pada sindroma hepatorena antara lain : cardiac output meninggi, tekanan arterial menurun, total tahanan pembuluh darah sistemik menurun, total volume darah meninggi, aktifasi system vasokonstriktor meninggi, tekanan portal meninggi, portosystemic shunting, tekanan pembuluh darah splanik menurun, tekanan pembuluh darah ginjal meninggi, tekanan arteri brachial dan femoral meninggi, dan tahanan pembuluh darah otak meninggi. Gambaran klinis dari uremia jarang dijumpai, begitu juga dengan analisa urin dalam keadaan normal. Secara klinis SHR dapat dibedakan atas 2 tipe yaitu: Sindroma Hepatorenal tipe I Tipe I ditandai oleh peningkatan yang cepat dan progresif dari BUN (Blood urea nitrogen) dan kreatinin serum yaitu nilai kreatinin >2,5 mg/dl atau penurunan kreatinin klirens dalam 24 jam sampai 50%, keadaan ini timbul dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Gagal ginjal sering dihubungkan dengan penurunan yang progresif jumlah urin, retensi natrium dan hiponatremi . Penderita dengan tipe ini biasanya dalam kondisi klinik yang sangat berat dengan tanda gagal hati lanjut seperti ikterus, ensefalopati atau koagulopati. Tipe ini umum pada sirosis alkoholik berhubungan dengan hepatitis alkoholik, tetapi dapat juga timbul pada sirosis non alkoholik. Kira-kira setengah kasus SHR tipe ini timbul spontan tanpa ada factor presipitasi yang diketahui, kadang-kadang pada sebagian penderita terjadi hubungan sebab akibat yang erat dengan beberapa komplikasi atau intervensi terapi (seperti inveksi bakteri, perdarahan gastrointestinal, parasintesis). Spontaneus bacterial peritonirtis (SBP) adalah penyebab umum dari penurunan fungsi ginjal pada sirosis. Kira-kira 35% penderita sirosis dengan SBP timbul SHR tipe I. SHR Tipe I adalah komplikasi dengan prognostic yang sangat buruk pada penderita sirosis, dengan mortalitas mencapai 95%. Rata-rata wktu harapan hidup penderita ini kurang dari dua minggu, lebih buruk dari lamanya hidup disbanding dengan gagal ginjal akut dengan penyebab lainnya. 2. Sindroma Hepatorenal Tipe II 13Tipe II SHR ini ditandai dengtan penurunan yang sedang dan stabil dari laju filtrasi glomerulus (BUN dibawah 50 mg/dl dan kreatinin serum < 2 mg / dl). Tidak seperti tipe I SHR, tipe II SHR biasanya terjadi pada penderita dengan fungsi hati relatif baik. Biasanya terjadi pada penderita dengan ascites resisten diuretic. Diduga harapan hidup penderita dengan kondisi ini lebih panjang dari pada SHR tipe I. Diagnosis Tidak ada tes yang spesifik untuk diagnostik SHR. Kriteria diagnostik yang dianut sekarang adalah berdasarkan International Ascites Clubs Diagnostic Criteria of Hepatorenal Syndromea antara lain : 1. Penyakit hati akut atau kronik dengan gagal hati lanjut dan hipertensi portal. 2. GFR rendah, keratin serum >1,5 mg/dl atau kreatinin klirens 24 jam < 40 ml/mnt. 3. Tidak ada syok,infeksi bakteri sedang berlangsung, kehilangan cairan dan mendapat obat nefrotoksik. 4. Tidak ada perbaikan fungsi ginjal dengan pemberian plasma ekspander 1,5 ltr dan diuretic (penurunan kreatinin serum menjadi < 1,5 mg/dl atau peningkatan kreatinin klirens menjadi > 40 ml/mnt) 5. Proteinuria < 0,5 g/hari dan tidak dijumpai bstruktif uropati atau penyakit parenkim ginjal secara ultrasonografi. Kriteria tambahan : 1. Volume urin < 500 ml / hari 2. Natrium urin < 10 meg/liter 3. Osmolalitas urin > osmolalitas plasma 4. Eritrosit urin < 50 /lpb 5. Natrium serum