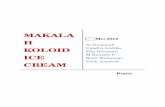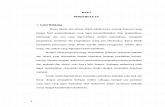makalah
-
Upload
achmad-machfud -
Category
Documents
-
view
78 -
download
0
description
Transcript of makalah
Bab IPENDAHULUAN
Perdarahan saluran cerna masih menjadi masalah klinis yang paling banyak dialami oleh pasien di seluruh dunia. Perdarahan saluran cerna dapat berasal dari saluran cerna bagian atas yaitu proksimal dari ligamentum Treitz, ataupun bawah yaitu distal dari ligamentum Treitz. Untuk keperluan klinis, perdarahan saluran cerna bagian atas (perdarahan SCBA) dibedakan lagi menjadi perdarahan akibat pecahnya varises esofagus (PVO) dan perdarahan non-varises, karena antara keduanya terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan prognosisnya.1 Penyebab utama perdarahan SCBA di Amerika Serikat adalah ulkus peptikum (31-59%), sedangkan perdarahan akibat PVO lebih jarang terjadi 7-20% namun memiliki angka mortalitas mencapai 70%. Sedangkan di Indonesia, dari penelitian retrospektif di Divisi Gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM Jakarta selama tiga tahun (1996-1998) diketahui bahwa penyebab utama perdarahan SCBA terbanyak adalah PVO (27,2%). 2,3Varises esofagus merupakan komplikasi dari sirosis yang diakibatkan oleh hipertensi portal yang dihasilkan dari peningkatan resistensi aliran portal dan peningkatan aliran darah vena portal. Ketika terjadi peningkatan perbedaan tekanan antara vena portal dengan vena cava inferior (Gradien Tekanan Portal), maka akan terbentuk aliran kolateral. Varises esofagus adalah kolateral yang paling penting, karena seiring dengan peningkatan tekanan dan aliran kolateral, varises terus tumbuh dan pada suatu waktu dapat ruptur dan mengakibatkan perdarahan yang dapat berakiba fatal.4 Dalam keadaan yang parah, perdarahan ini dapat menyebabkan kematian, walaupun kematian ini lebih disebabkan karena dekompensasi dari penyakit lain yang sudah dialami oleh pasien, yang diperburuk dengan perdarahan saluran cernanya. Karena itulah diperlukan penatalaksanaan yang baik dan sistematis agar perdarahan tidak menimbulkan komplikasi yang berat sampai kematian.1-3Selama ini terdapat berbagai pilihan terapi dalam penanganan PVO. Pilihan terapi ini terdiri dari terapi farmakologis seperti vasopressin dan somatostatin, terapi endoskopi seperti ligasi (Endoscopic Band Ligation/EBL) dan skleroterapi, terapi tamponade balon, terapi angiografi, dan terapi bedah. Banyaknya pilihan jenis terapi PVO masih menimbulkan keraguan bagi klinisi untuk menentukan jenis terapi apa yang terbaik bagi pasien dengan PVO. Hal inilah yang diangkat dalam sajian kasus ini, yaitu pemilihan terapi bagi pasien dengan PVO. Pengetahuan dalam pemilihan terapi, dan pengetahuan akan prognosis dari setiap terapi yang dipilih akan berpengaruh pada penanganan perdarahan akibat PVO yang lebih optimal, sehingga pasien dengan risiko tinggi akan mendapatkan terapi agresif lebih dini, dan pasien dengan risiko rendah akan terhindar dari prosedur yang tidak diperlukan.
BAB IIILUSTRASI KASUS
Seorang perempuan berinisial AN, usia 48 tahun, dan beralamat di Jakarta datang ke IGD RS Fatmawati dengan diantar keluarganya. Pasien adalah seorang ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir tamat SLTA. Suami pasien bekerja sebagai pedagang, dengan pendidikan terakhir tamat SLTA. Pasien masuk ke RS Fatmawati dengan status pembayaran SKTM, pada pada tanggal 12 Agustus 2012.Pasien masuk IGD RS Fatmawati dengan keluhan utama muntah darah sejak 4 jam SMRS. Muntah berupa cairan berwarna merah seperti darah, sedikit kehitaman, sebanyak tiga kali, masing-masing sebanyak 1 gelas belimbing (200cc). Muntah didahului nyeri ulu hati dan mual yang bertambah berat, pertama kali dirasakan 8 jam SMRS. Pada saat itu pasien muntah satu kali, isi cairan berwarna kuning, tidak ada darah.1 hari SMRS, pasien mengeluhkan nyeri pada kedua tungkai, berobat ke dokter umum, dan diberikan obat-obatan: dexamethasone, ibuprofen, neuralgin, allopurinol, dan bufantacid. Keluhan nyeri tungkai dirasa membaik setelah minum obat, namun muncul rasa mual yang disertai dengan dada terasa panas dan nyeri ulu hati. Keluhan demam, sesak, nyeri dada, kelemahan sesisi, dan penurunan kesadaran tidak ada. Pasien tidak memiliki keluhan dalam buang air kecil maupun buang air besar. BAB tidak hitam. Tidak ada perubahan pola tidur, perubahan mood, maupun penurunan kesadaran.2 tahun SMRS, pasien mengalami keluhan serupa dan berobat ke RS Fatmawati. Pasien didiagnosis menderita Varises Esofagus dan dilakukan endoskopi sebanyak dua kali, dan dilakukan pengikatan pada pembuluh darah yang mengalami varises. Setelah dilakukan pengikatan, pasien tidak pernah mengeluhkan mual, muntah darah, ataupun BAB hitam. Ini adalah keluhan yang pertama sejak dilakukan pengikatan 2 tahun yang lalu.Pada saat perawatan tersebut, pasien ditransfusi darah karena Hb 4g/dL. Pada saat itu pasien juga dikatakan sakit liver, namun pasien tidak mengerti sakit liver jenis apa. Pasien juga didiagnosis menderita DM, dan mendapat obat Glibenklamid 5 mg diminum 1x/hari. Pasien tidak rutin kontrol dan tidak rutin minum obat karena alasan biaya.Pasien mengatakan tidak merokok ataupun minum alkohol. Pasien juga mengatakan jarang mengkonsumsi jamu-jamuan ataupun obat herbal.Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesan sakit tampak sakit sedang, kesadaran pasien compos mentis. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit isi cukup dan regular, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, dan suhu aksila 36.7C. Dari pemeriksaan status gizi didapatkan kesan baik dengan tinggi badan 150 cm, dan berat badan 50 kg. Indeks Massa Tubuh pasien adalah 22.2 kg/m2 (normoweight).Pasien tampak pucat, namun kelembapan dan turgor kulit baik. Tidak terdapat kelainan pada kepala maupun rambut. Pada mata ditemukan konjunctiva pucat, sedangkan sklera tidak ikterik. Pupil isokor, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif. Pada hidung ataupun telinga tidak didapatkan adanya perdarahan aktif. Pada pemeriksaan fisik leher didapatkan tekanan vena jugularis 5-2 cm.H2O, tidak teraba adanya kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan fisik paru, didapatkan pergerakan dada simetris pada saat inspirasi maupun ekspirasi, tidak didapatkan retraksi iga, pelebaran sela iga, maupun penggunaan otot nafas tambahan. Pada palpasi didapatkan ekspansi dada kanan sama dengan kiri, fremitus taktil kanan sama dengan kiri. Pada perkusi didapatkan sonor pada kedua paru, dengan batas paru-hati terletak pada ICS VI linea midklavikula kanan dan batas paru-lambung ICS VIII linea aksilaris anterior kiri. Pada auskultasi didapatkan bunyi napas vesikular tidak didapatkan adanya rhonki maupun wheezing. Dalam pemeriksaan fisik jantung, pada inspeksi iktus kordis tidak terlihat namun pada palpasi teraba pada sela iga V, 1 jari medial dari linea midklavikula kiri. Pada perkusi didapatkan batas kanan jantung pada ICS V linea sternalis kanan, batas kiri jantung pada ICS V 1 jari medial linea midklavikula kiri, dan pinggang Jantung pada ICS III linea parasternalis kiri. Pada auskultasi didapatkan bunyi jantung I-II regular, tidak ada murmur maupun gallop. Pada pemeriksaan inspeksi abdomen didapatkan perut datar dan lemas. Pada palpasi hepar teraba 2 jari bawah arcus costae dan 4 jari bawah processus xyphoideus, dan lien teraba Schuffner 2. Pada pasien didapatkan nyeri tekan epigastrium. Pada perkusi didapatkan bunyi timpani, tidak ada shifting dullness dan bising usus 4 kali dalam waktu satu menit. Pada ekstremitas didapatkan akral hangat dan tidak ada edema. Dari pemeriksaan laboratorium di IGD pada saat pasien pertama kali masuk didapatkan anemia dengan hemoglobin 7,7 g/dL, hematokrit 24%, leukosit 6.800 sel/L, dan trombositopeni 70.000 sel/L. SGOT meningkat yaitu 38 U/L sedangkan SGPT dalam batas normal yaitu 22 U/L). Didapatkan hipoalbuminemi 2,80 g/dL, hiperglobulinemi 3,90 g/dL. Ureum darah 66 mg/dL dan kreatinin 1,3 mg/dL. Gula darah sewaktu pasien adalah 258 mg/dL. Kadar elektrolit dalam batas normal (natrium 139 mEq/L, kalium 3,98 mEq/L dan klorida 103 mEq/L). Pada gambaran EKG didapatkan kesan irama sinus, normoaksis, laju QRS 75 kali per menit, interval PR 0,16 detik, interval QRS 0,08 detik, tidak ada perubahan gelombang ST, inversi T, hipertropi maupun blok.Pada pagi hari pertama perawatan di ruangan (tanggal 13 Agustus 2012), didapatkan produksi NGT 100 cc, cairan berwarna merah kecoklatam. Pasien diperiksa kembali darah rutin, didapatkan anemia dengan hemoglobin 6,9 g/dL, hematokrit 21%, leukosit 6.000 sel/L, dan trombositopeni 66.000 sel/L. Retikulosit dalam batas normal (0.6%), dan hemostasis juga dalam batas normal (APTT 1,19 x kontrol, PT 1,2 x control). Dari pemeriksaan morfologi darah tepi didapatkan sel darah merah mikrositik hipokromik dan anisositosis, sel darah putih kesan jumlah dan morfologi normal, sedangkan trombosit kesan jumlah menurun, morfologi normal. Pasien juga diperiksakan seroimunologi untuk hepatitis dan didapatkan hasil non reaktif baik untuk HbsAg maupun Anti HCV. Urinalisa didapatkan hasil dalam batas normal. Pada pasien ditegakkan daftar masalah Hematemesis ec PVO, Sirosis Hepatis dengan Child Pugh B, dan DM tipe 2 NW Gula darah belum terkontrol. Pasien diberikan terapi berupa pemasangan O2 2lt/mnt dengan nasal kanul bila sesak, pasien dipuasakan dan dilakukan pemasangan NGT, dialirkan, dan bila dalam 12 jam tidak ada perdarahan makan direncanakan untuk diet cair lambung dimulai dari 3x100 cc lalu dinaikkan bertahap. Terapi cairan berupa NaCl 0,9% 500 cc/12 jam, dipasang three way dengan aminofluid /24jam. Pasien direncanakan untuk transfusi PRC hingga target Hb > 8g/dL, dengan premedikasi diphenhydramine 1 ampul. Untuk obat-obatan intravena pada pasien diberikan OMZ 1 ampul drip dalam NaCl 0,9% 500 cc/8 jam selama 3x24 jam, Transamin 3x1 ampul, Vit. K 3x1 ampul, dan Cefotaxime 3x1gr. Sedangkan untuk obat-obatan oral diberikan Propanolol 3x10 mg, Spironolactone 1x100mg, dan Lactulac 3xCI. Sebagai terapi untuk DM, pada pasien diberikan Insulin dalam drip, 0.5 unit/jam dengan correctional dose pada GDS kelipatan 50 diberikan Insulin kelipatan 3 unit. Pasien dijadwalkan untuk dilakukan ligase bila perdarahan sudah berhenti. Pada hari ke dua perawatan (14 Agustus), dikatakan bahwa malamnya pasien menjadi sulit tidur, kesadaran pasien menjadi CM-Apatis, dan pada pemeriksaan fisik didapatkan flapping tremor, sehingga ditegakkan masalah Ensefalopati Hepatikum gr. II. Pemberian Spironolactone 1x100mg ditunda karena pasien EH gr. II. Dari hasil pemeriksaan USG abdomen, didapatkan kesan penyakit hati kronik, splenomegali, kolelitiasis, dan penebalan dinding kantung empedu dengan ascites masif, yang sesuai dengan hasil hipoalbuminemia. Pada pasien diberikan tambahan terapi Hepamerz 3x1 sachet.Pada hari ke tiga perawatan (15 Agustus), dilaporkan bahwa BAB pasien hitam. Kesadaran pasien masih apatis. Pada hari ke empat perawatan (16 Agustus), kesadaran pasien mulai baik, dan kontak sudah adekuat. Produksi NGT sudah negatif, sehingga pada pasien direncanakan untuk dimulai diit hati cair 4x100cc, selanjutnya akan dinaikkan bertahap.Pada hari ke enam perawatan (18 Agustus) ditegakkan rumusan masalah pasien adalah Sirosis hepatis dengan Ensefalopati Hepatikum perbaikan, riwayat Hematemesis Melena ec PVO, dan DM tipe 2 NW Gula darah dalam regulasi. Dilakukan pemeriksaan darah rutin kembali dan didapatkan hasil anemia dengan hemoglobin telah mencapai target pertama yaitu 8,6 g/dL, hematokrit 27%, leukopeni 4.700 sel/L, dan trombositopeni 68.000 sel/L. Pasien sudah bisa makan per oral dan makan habis 1 porsi sehingga drip Insulin dihentikan dan sebagai regulasi gula darah diberikan Insulin fixed dose 3x5 unit 30 ac. Setelah dilakukan reassessment terhadap kurva gula darah harian pasien keesokan harinya, Insulin menjadi 5-5-8 unit 30 ac. Pasien direncanakan untuk rawat jalan bila Hb > 10 g/dL, dan dijadwalkan untuk dilakukan EBL dari poliklinik.Pada hari ke dua belas perawatan (24 Agustus), didapatkan hasil pemeriksaan Hb 10 g/dL, hematokrit 31%, leukopeni 4.000 sel/L, dan trombositopeni 73.000 sel/L. Pasien sudah diberikan diit DM biasa 1500 kal/hari, dan untuk regulasi gula darah pada pasien Insulin dihentikan dan diberikan OHO Glurenorm 30 mg tab - 0 - . Pasien diizinkan untuk rawat jalan setelah dilakukan EBL pada tanggal 28 Agustus 2012.
Bab IIIDISKUSI
Perdarahan saluran cerna dapat berasal dari saluran cerna bagian atas ataupun bawah. Untuk keperluan klinis, perdarahan saluran cerna bagian atas (perdarahan SCBA) dibedakan lagi menjadi perdarahan varises esofagus dan non-varises, karena antara keduanya terdapat perbedaan dalam pengelolaan dan prognosisnya.1 Perdarahan saluran cerna bagian atas dapat bermanifest dalam bentuk muntah darah ataupun BAB hitam. Hematemesis adalah muntah darah (merah segar atau hematin yaitu hitam seperti kopi) yang merupakan tanda adanya perdarahan saluran cerna bagian atas. Melena adalah adalah feses berwarna hitam seperti ter, dan berbau busuk. Melena terjadi ketika hemoglobin dikonversi menjadi hematin atau hemokrom lainnya oleh bakteri setelah 14 jam. Melena biasanya berasal dari perdarahan SCBA, walaupun perdarahan usus halus dan proksimal kolon dapat juga bermanifes dalam bentuk melena. Perdarahan SCBA yang mengakibatkan melena biasanya berlangsung sejumlah 50-100 ml atau lebih.5 Pada pasien ini didapatkan keluhan utama muntah darah 4 jam SMRS, sebanyak tiga kali, berisi darah berwarna merah kehitaman, masing-masing sebanyak 200 cc. Hal ini mengarahkan pada pemikiran bahwa terdapat perdarahan saluran cerna bagian atas pada pasien ini. Selanjutnya perlu dicari etiologi yang menyebabkan perdarahan saluran cerna bagian atas pada pasien ini.Penyebab utama perdarahan SCBA di Amerika Serikat adalah ulkus peptikum (31-59%). Perdarahan varises esofagus lebih jarang terjadi (7-20%) namun memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi yaitu mencapai 70%. Sedangkan di Indonesia, dari penelitian retrospektif di Divisi Gastroenterologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM Jakarta selama tiga tahun (1996-1998) diketahui bahwa penyebab utama perdarahan SCBA terbanyak adalah pecahnya varises esofagus (27,2%).2,3
Tabel 1. Penyebab Perdarahan Saluran Cerna Bagian Atas di Indonesia.3Penyebab Persentase (%)
Pecah varises esofagusKombinasiGastritis erosifGastropati hipertensi portalTukak duodenumTukak lambungPecah varises fundus27.222.119.011.75.75.51.9
Varises esofagus merupakan komplikasi dari sirosis yang diakibatkan oleh hipertensi portal. Hipertensi portal dihasilkan dari peningkatan resistensi aliran portal dan peningkatan aliran darah vena portal akibat perubahan arsitektur vaskular hati oleh fibrosis dan nodul regeneratif. Gradien tekanan portal (hepatic venous pressure gradient/HPVG) adalah perbedaan tekanan antara vena portal dengan vena cava inferior. Hipertensi portal didapatkan pada HPVG > 5 mmHg, namun signifikan secara klinis jika > 10 mmHg, dan memberikan akibat yang fatal jika > 20 mmHg.4 Ketika HPVG meningkat, aliran kolateral terbentuk di tempat di mana terjadi hubungan sirkulasi sistemik dengan portal. Varises esofagus adalah kolateral yang paling penting, karena seiring dengan tekanan dan aliran yang meningkat, varises terus tumbuh dan pada suatu waktu dapat ruptur dan mengakibatkan perdarahan SCBA yang dapat berakiba fatal.4Pada pasien ini, kecurigaan ke arah pecahnya varises esofagus lebih mudah ditegakkan karena pasien memiliki riwayat keluhan yang sama dua tahun yang lalu, dan telah ditegakkan diagnosis varises esofagus dan telah pula dilakukan ligasi pada pembuluh darah yang mengalami varises. Pasien dengan varises esofagus biasanya memberikan gejala trombositopenia, splenomegali, ascites, ensefalopati, dan dengan atau tanpa perdarahan. Sedangkan pasien dengan perdarahan akibat pecahnya varises esofagus biasanya memberikan gejala berupa hematemesis, melena, penurunan tekanan darah, atau anemia. Pada pasien ini ditemukan gejala berupa hematemesis sebagai keluhan utama yang membawa pasien berobat ke RS Fatmawati, ditemukan tanda splenomegali (Schuffner II), anemia, dan trombositopenia. Melena tidak menjadi keluhan awal pada pasien ini, namun pada hari perawatan ke tiga pasien mengalami BAB hitam. Pada pasien tidak ditemukan ascites maupun ensefalopati. Namun pada hari perawatan ke dua pasien mulai terjadi gangguan tidur, lalu terjadi penurunan kesadaran, sehingga pada pasien disimpulkan terjadi ensefalopati. Sekali seseorang teridentifikasi sirosis, maka risiko untuk mengalami perdarahan varises adalah sebesar 25-35%. Risiko ini secara kasar dapat diperkirakan melalui klasifikasi Child-Turcotte-Pugh. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan terapi pencegahan terjadinya perdarahan varises.6Prediktor terpenting untuk perdarahan akibat pecahnya varises esofagus adalah ukuran varises, skor Child-Pugh, dan penemuan tanda red wale pada endoskopi. Umumnya yang digunakan dalam klasifikasi ukuran adalah tiga grade yaitu kecil, sedang, dan besar (small, medium, dan large). Namun konsensus terkini dari the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) hanya menggunakan dua tingkatan, yaitu kecil dan besar (small dan large), dengan cut-off size-nya adalah 5 mm.7 North Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment of Esophageal Varices membuat stratifikasi risiko untuk perdarahan akibat pecahnya varises esofagus, yang terdiri dari ukuran varises, skor Child-Pugh, dan penemuan tanda red wale pada endoskopi. Kelas risiko ditentukan dari jumlah angka dari nilai masing-masing prediktor, dan semakin tinggi total nilainya, maka semakin besar pula risiko terjadi perdarahan varises esofagus.8
Tabel 2. Stratifikasi Risiko untuk Perdarahan Varises Esofagus.8Ukuran varisesTanda red wale Skor Child-Pugh
Kecil (50% lumen radius) 17.4Sedang 9.6C 19.5
Berat 12.8
Kelas risiko
1 (40)
Tabel 3. Sistem Penilaian Child-Turcotte-Pugh.6 NilaiKriteria123
AsitesNihil Mudah dikontrol Sulit dikontrol
Ensefalopati Nihil Grade I atau IIGrade III atau IV
Bilirubin(mg/dl)3
Albumin (g/dl)>3.52.8-3.56
KlasifikasiABC
Jumlah poin total5-67-910-15
Persentase hidup dalam satu tahun pertama100%80%45%
Adanya tanda-tanda sirosis hati yang khas dengan dugaan terdapat hipertensi portal tidak langsung menyingkirkan penyebab pendarahan lain seperti gastropati hipertensi portal. Oleh karena itu,pemeriksaan endoskopi merupakan modalitas yang penting dalam mendiagnosis varises esofagus. Karena varises esofagus adalah komplikasi dari sirosis hepatis, maka setiap penderita sirosis hati sebaiknya dilakukan endoskopi pada saat diagnosis sirosis dibuat. Bila pada saat endoskopi pertama tidak ditemukan varises, maka dilakukan endoskopi berkala dengan jarak dua hingga tiga tahun. Namun bila pada endoskopi pertama ditemukan varises kecil, maka endoskopi berkala dilakukan setiap tahun. Secara umum, faktor risiko perdarahan akibat varises esofagus adalah skor Child-Pugh yang buruk, infeksi bakteri, peningkatan level aspartate amino transferase, HPVG yang lebih dari 20 mmHg, ukuran varises, lokasi varises, dan ditemukannya stigmata endoskopi khusus seperti tanda red wale, hematocystic spots, eritema difus, warna kebiruan, cherry-red spots, atau white-nipple spots. Pasien dengan ascites yang berat juga berisiko tinggi mengalami perdarahan.9-11
Tabel 4. Rekomendasi Profilaksis Perdarahan Varises Primer 4, 12Profilaksis
Tanpa varisesSkrining dengan endoskopi setiap 2-3 tahun untuk mencari gambaran varises
Varises kecil(< 5 mm)Skrining setiap 1-2 tahun untuk melihat pembesaran varisesSaat ini, tidak ada bukti untuk merekomendasikan pengobatan untuk pencegahan perdarahan varises pada pasien tersebut.
Varises sedang atau besar( 5 mm) Tidak ada kontraindikasi beta-blocker: obati dengan beta-blocker nonselektif. Dosis propanolol dapat dimulai dengan dosis 2x20 mg atau 2x40 mg dinaikkan hingga 2x80 mg bila perlu. Pemakaian long acting propanolol dalam dosis 80 atau 160 mg dapat dipakai untuk memperbaiki ketaatan pasien. Nadolol dapat juga digunakan dengan dosis awal 1x40 mg. Pemantauan denyut nadi diperlukan, dimana batas minimal adalah 55x/menit. Kontraindikasi terhadap beta-blocker: Pertimbangkan untuk dilakukan EBL (ligasi varises endoskopi). EBL dilakukan tiap 2-4 minggu sampai varises menutup/obliterasi (biasanya terjadi setelah 2-4 sesi) 1-3 bulan setelah obliterasi dilakukan endoskopi pemantauan pertama, selanjutnya setiap 6-12 bulan.
Pasien pada kasus ini pertama kali didiagnosis menderita Varises Esofagus pada bulan Juni 2010. Pada saat itu pasien mengalami keluhan serupa dengan keluhan saat ini, yaitu muntah darah berwarna merah kehitaman. Pasien dilakukan endoskopi sebanyak dua kali (interval tiga bulan), dan dilakukan pengikatan pada pembuluh darah yang mengalami varises. Setelah dilakukan pengikatan, pasien tidak pernah mengeluhkan mual, muntah darah, ataupun BAB hitam. Pasien dikatakan untuk kontrol kembali namun pasien tidak kontrol karena alasan biaya.Sesuai dengan rekomendasi profilaksis, pada pasien sirosis hati tanpa varises sebaiknya dilakukan skrining dengan endoskopi setiap 2-3 tahun untuk mencari gambaran varises. Sedangkan pada pasien dengan varises ukuran kecil, yaitu dengan ukuran varises lebih dari 5 mm, dilakukan skrining setiap 1-2 tahun untuk melihat pembesaran varises. Dan pada pasien dengan varises ukuran lebih dari sama dengan 5 mm diberikan terapi beta blocker non selektif, namun bila terdapat kontraindikasi terhadap beta blocker dilakukan ligasi varises endoskopi. Ligasi dilakukan setiap 2-4 minggu sampai varises menutup (mengalami obliterasi). Biasanya obliterasi tercapai setelah 2-4 sesi. 1-3 bulan setelah obliterasi, dilakukan endoskopi pemantauan pertama, dan selanjutnya setiap 6-12 bulan.Pada pasien ditemukan varises ukuran lebih dari 5 mm, sehingga setelah dilakukan ligasi yang pertama pasien disarankan untuk kontrol kembali untuk melihat pembesaran varises. Pasien kontrol sebanyak satu kali, dan tidak kontrol kembali dikarenakan alasan biaya. Hal ini menjadi pitfall yang mengakibatkan varises pasien tidak diketahui apakah mengalami obliterasi dengan sempurna atau tidak, dan berisiko terjadi perdarahan kedua pascaligasi.Rekomendasi terapi terkini untuk varises esofagus adalah mengkombinasikan terapi farmakologis dan endoskopis untuk terapi inisial pada perdarahan akut akibat varises esofagus. Pasien dengan kriteria Child A atau B atau HPVG < 20 mmHg yang mengalami perdarahan varises esofagus untuk pertama kalinya, diberikan terapi standar yang merupakan pendekatan paling baik diantara terapi lainnya. Terapi standar terdiri atas kombinasi terapi farmakologis dan endoskopis.4,13Terapi farmakologis meliputi pemberian obat-obatan vasoaktif seperti somatostatin atau terlipressin, yang harus segera dimulai pada saat perdarahan akibat varises esofagus dicurigai dan tetap diberikan hingga 2-5 hari. Terapi endoskopi diagnostik emergensi dilakukan setelah stabilisasi pasien dengan terapi cairan dan transfusi darah telah dilakukan, dan apabila tersedia Sumber Daya Manusia yang memadai maka harus segera dilakukan terapi endoskopis (yaitu ligasi atau skleroterapi apabila ligasi tidak dapat dilakukan) dalam waktu 12 jam setelah pasien datang. 13Vasopressin dapat menghentikan perdarahan SCBA lewat efek vasokonstriksi pembuluh darah splanknik, menyebabkan aliran darah dan tekanan vena porta menurun. Pemberian dilakukan dengan mengencerkan sediaan vasopressin 50 unit dalam 100 ml Dekstrose 5% diberikan 0,5-1 mg/menit IV selama 20-60 menit dan dapat diulang tiap 3-6 jam atau setelah pemberian pertama dilanjutkan per infus 0,1-0,5 U/menit. Vasopressin dapat menimbulkan efek samping serius berupa insufisiensi koroner mendadak, oleh karena itu pemberiannya disarankan bersamaan preparat nitrat, misalnya nitrogliserin intravena dengan dosis awal 40 mcg/menit kemudian secara titrasi dinaikkan sampai maksimal 400 mcg/menit dengan tetap mempertahankan tekanan sistolik di atas 90 mmHg.5 Terlipressin, suatu analog sintetik dari vasopressin yang memiliki aktivitas biologis yang lebih lama dan efek samping yang lebih sedikit, cukup efektif dalam mengontrol perdarahan varises akut dan penurunan kematian. Terlipressin diberikan 2 mg IV untuk dosis awal setiap 4 jam dan dititrasi sampai 1 mg IV setiap 4 jam hingga perdarahan terkontrol.5Somatostatin dan analognya (ocreotide) diketahui dapat menurunkan aliran darah splanknik, menurunkan sekresi asam lambung dan pepsin serta menstimulasi produksi mukus. Khasiatnya lebih selektif dibandingkan vasopressin. Somatostatin dapat menghentikan perdarahan akut varises esofagus pada 70-80% kasus, dan dapat pula digunakan untuk perdarahan nonvarises. Dosis somatostatin diawali dengan bolus 250 mcg/iv, dilanjutkan per infus 250 mcg/jam selama 12-24 jam atau sampai perdarahan berhenti; okreotide dosis bolus 100 mcg/iv dilanjutkan per infus 25 mcg/jam selama 8-24 jam atau sampai perdarahan berhenti.5Dari suatu studi meta analisis yang melakukan review terhadap 20 studi, didapatkan hasil bahwa penggunaaan obat-obatan vasoaktif seperti terlipressin berhubungan dengan penurunan mortalitas yang signifikan dibandingan dengan pemberian placebo. Sedangkan pada meta analisis mengenai perbandingan antara obat-obatan vasoaktif didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemberian obat terlipressin dan somatostatin. 15Non-selective beta-blockers merupakan pilihan terapi untuk mencegah perdarahan awal, namun, tidak dapat mencegah pembentukan varises esofagus. Pemberian vitamin K pada pasien dengan penyakit hati kronis yang mengalami perdarahan SCBA diperbolehkan, dengan pertimbangan pemberian tersebut tidak merugikan dan relatif murah.5Profilaksis antibiotik harus dianggap sebagai bagian dari terapi perdarahan akut akibat pecahnya varises esofagus dan harus segera dimulai pada saat admisi RS, khususnya untuk pasien dengan asites karena dapat menurunkan risiko infeksi bakteri dan menurunkan mortalitas. Antibiotik tetap dipertahankan hingga minimal tujuh hari.4 Pada pasien ini diberikan antibiotik Cefotaxime 3x1 gr.Cefotaxime yang diberikan pada pasien ini merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang bersifat bakterisidal dan bekerja dengan menghambat sintesis mukopeptida pada dinding sel bakteri. Cefotaxime memiliki aktivitas spektrum yang lebih luas terhadap organisme gram positif (Staphylococci, Streptococci aerob dan anaerob, Streptococcus pneumoniae, Clostridium sp.) dan gram negatif. (E. coli, H. influenzae, Klebsiella sp., Proteus sp., Serratia sp. Neisseria sp, dan Bacteroides sp). 14Dari studi meta analisis didapatkan hasil bahwa penggunaan obat-obatan Proton Pump Inhibitor menunjukkan tingkat pengurangan yang signifikan pada kebutuhan akan terapi endoskopi. 16 Pada pasien ini diberikan omeprazole, diberikan secara drip sebanyak 1 ampul dalam NaCl 0,9% 500 cc/8 jam selama 3x24 jam.Endoskopi dapat menentukan lokasi perdarahan dan tingkat risiko terjadi perdarahan ulang. Selama ini, EBL merupakan terapi endoskopi pilihan untuk PVO, baik untuk keadaan perdarahan akut, maupun untuk profilaksis sekunder. Sedangkan untuk profilaksis primer, EBL dibatasi hanya pada pasien yang memiliki kontraindikasi atau intoleran terhadap beta-blocker. EBL biasanya dilakukan berulang dengan interval 1-2 minggu hingga penutupan lengkap dari seluruh varises esofagus telah tercapai. 90% pasien mencapai penutupan lengkap setelah 2-4 kali EBL. Namun 20-75% pasien membutuhkan EBL ulang setelahnya, akibat terbentuknya varises esofagus yang baru.9 Faktor risiko yang dapat dilihat dari endoskopi antara lain perdarahan aktif, pembuluh darah yang tampak jelas maupun bekuan darah yang menyatu. Komplikasi yang dapat terjadi selama endoskopi adalah aspirasi (terutama pasien yang tersedasi maupun dalam keadaan ensefalopati), hipoventilasi, hipotensi. Sedangkan komplikasi setelahnya biasanya berhubungan dengan faktor hemostasis, meliputi perburukan perdarahan maupun perforasi. Pasien harus diresusitasi terlebih dahulu sebelum dilakukan endoskopi. Setelah keadaan umum pasien stabil, segera dilakukan pemeriksaan endoskopi darurat untuk menentukan penyebab perdarahan dan menentukan pengobatan yang tepat.17EBL merupakan pilihan pertama untuk mengatasi perdarahan varises esofagus dibandingkan dengan terapi endoskopi lainnya yaitu skleroterapi. Tindakan ligasi varises dilaporkan memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan dengan skleroterapi. Untuk mencegah perdarahan pertama, seluruh pasien yang telah didiagnosis memiliki varises esofagus harus dilakukan EBL pada saat endoskopi yang pertama kali.17,18Pasien ini dilakukan endoskopi dan ligasi pada saat pertama kali didiagnosis menderita varises esofagus pada bulan Juni 2010. Pada endoskopi yang pertama kali, pasien dilakukan ligasi pada pembuluh darah yang mengalami varises. Pasien saat itu dikatakan untuk kontrol tiga bulan kemudian. Pasien kontrol tiga bulan kemudian dan dilakukan endoskopi ulang. Dari gambaran endoskopi didapatkan kesan ligasi berjalan dengan baik. Setelah itu pasien tidak kontrol lagi hingga datang kemballi dengan keluhan yang sama kali ini.Skleroterapi merupakan alternatif bila ligasi endoskopik sulit dilakukan karena perdarahan yang masif, terus berlangsung, atau teknik tidak memungkinkan. Sklerosan yang bisa digunakan antara lain campuran sama banyak antara Polidokanol 3%, NaCl 0,9%, dan alkohol absolut. Campuran dibuat sesaat sebelum skleroterapi dilakukan.17 Terapi varises esofagus yang lainnya adalah penggunaan tamponade balon, paling populer adalah Sengstaken-Blakemore tube (SB-tube) yang mempunyai tiga pipa serta dua balon masing-masing untuk esofagus dan lambung. Tamponade balon digunakan pada pasien yang masih mengalami perdarahan setelah pemberian farmakologi, apabila tidak tersedia terapi endoskopi, atau sebagai terapi jembatan dalam rangka prosedur penyelamatan untuk kemudian dilakukan terapi definitif. Tamponade balon memberikan penekanan langsung pada titik perdarahan dengan balon yang dapat dikembangkan dan ditempatkan pada selang nasogastrik khusus (contoh: Minnesota tube). Komplikasi terapi balon adalah pneumoni aspirasi, laserasi sampai perforasi. Pengembangan balon pada esofagus sebaiknya tidak melebihi 24 jam. Sekali bakon dikempeskan dianjurkan untuk segera dilakukan pengobatan lanjutan untuk mencegah perdarahan ulang, karena perdarahan ulang setelah pengempesan SB tube terjadi sekitar lebih dari 80%. Saat ini terapi dengan balon SB tube sudah jarang digunakan.5, 6, 17Pada pasien yang gagal atau tidak memberikan respon dengan terapi standar, atau pada pasien dengan tingkat kerusakan hati yang tinggi, dapat dipertimbangkan tindakan TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt). Shunt yang dimaksud merupakan stent logam yang dapat dikembangkan dan kemudian ditempatkan melintasi jalur yang dibuat di antara vena hepatica dan sistem porta.5, 17 Terdapat hubungan antara pemasangan awal TIPS (dalam 24-48 jam setelah pasien datang) dengan peningkatan tingkat kesintasan yang signifikan pada pasien dengan risiko tinggi (HPVG > 20 mmHg atau kriteria Child C).4 Pembedahan pada dasarnya dilakukan bila terapi medik, endoskopi dan radiologi dinilai gagal, namun sebaiknya ahli bedah dilibatkan sejak awal terapi.17
Bab IVKESIMPULAN
Pasien perempuan usia 48 tahun pada kasus ini disimpulkan menderita perdarahan saluran cerna bagian atas akibat pecahnya varises esofagus, karena terdapat keluhan muntah darah berwarna merah kehitaman dan BAB hitam. Karena varises esofagus adalah komplikasi dari sirosis hepatis, maka setiap penderita sirosis hati sebaiknya dilakukan endoskopi pada saat diagnosis sirosis dibuat. Bila pada saat endoskopi pertama tidak ditemukan varises, maka dilakukan endoskopi berkala dengan jarak dua hingga tiga tahun. Namun bila pada endoskopi pertama ditemukan varises kecil, maka endoskopi berkala dilakukan setiap tahun. Secara umum, faktor risiko perdarahan akibat varises esofagus adalah skor Child-Pugh yang buruk, infeksi bakteri, ukuran varises, dan ditemukannya stigmata endoskopi khusus seperti red wale signs. Rekomendasi terapi terkini untuk varises esofagus adalah mengkombinasikan terapi farmakologis dan endoskopis untuk terapi inisial pada perdarahan akut akibat varises esofagus. Terapi farmakologis meliputi pemberian obat-obatan vasoaktif seperti somatostatin atau terlipressin, yang harus segera dimulai pada saat perdarahan akibat varises esofagus dicurigai dan tetap diberikan hingga 2-5 hari. Terapi endoskopi diagnostik emergensi dilakukan setelah stabilisasi pasien telah dilakukan, dan apabila fasilitas memungkinkan maka harus segera dilakukan terapi endoskopis (yaitu ligasi atau skleroterapi apabila ligasi tidak dapat dilakukan) dalam waktu 12 jam setelah pasien datang.
DAFTAR PUSTAKA
1. Abdullah M. Perdarahan saluran cerna bagian bawah (hematokezia) dan perdarahan samar (occult). In: Sudoyo WA, Setyohadi B, Alwi I, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2009. p. 453-9.2. Albeldawi M, Qadeer MA, Vargo JJ. Managing acute upper GI bleeding, preventing recurrences. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2010;77(2):131-42.3. Simadibrata M. Penatalaksanaan perdarahan saluran cerna bagian atas. In: Gustaviani R, Mansjoer A, Rinaldi I, editors. Naskah Lengkap Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Penyakit Dalam 2007; 2007; Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2007. p. 207-15.4. Garcia-Tsao G, Bosch J. Management of varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. New England Journal of Medicine. 2010;362(9):823-32.5. Adi P. Pengelolaan perdarahan saluran cerna bagian atas. In: Sudoyo WA, Setyohadi B, Alwi I, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 5 ed. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI; 2009. p. 447-52.6. Sharara AI, Rockey DC. Gastroesophageal variceal hemorrhage. New England Journal of Medicine. 2001;345(9):669-81.7. Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, et al. In: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Hepatology. 2007;46:922-38. 8. North Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment of Esophageal Varices. Prediction of the first variceal hemorrhage in patients with cirrhosis of the liver and esophageal varices. A prospective multicenter study. N Engl J Med. 1988;319:983-9.9. Petrasch F, Grothaus J, Mssner J, et.al. Differences in bleeding behavior after endoscopic band ligation: a retrospective analysis. BMC Gastroenterology. 2010;10:5.10. Abraldes J, Aracil C, Catalina M, Monescillo A, Baares A, Villanueva C, Garcia-Pagan J, Bosch J. Value of hvpg predicting 5-day treatment failure in acute variceal bleeding. Comparison with clinical variables. Journal of Hepatology. 2006; 44 (Supplement 2):S12.11. Yang MT, Chen HS, Lee HC, Lin CL: Risk factors and survival of early bleeding after esophageal variceal ligation. Hepatogastroenterology. 2007; 54(78):1705-9.12. Bosch J, Abraldes JG, Groszmann R. Current management of portal hypertension. Journal of Hepatology. 2003;(38):854-68.13. Li L, Yu C, Li Y. Endoscopic band ligation versus pharmacological therapy for variceal bleeding in cirrhosis: A meta-analysis. Canadian Journal of Gastroenterology. 2011; 25(3): 147-55.14. Beta-Lactam and Other Cell Wall-and Membrane-Active Antibiotics. In: Katzung BG, editors. Basic and Clinical Pharmacology. 10 ed. Jakarta: Lange-McGraw Hill; 2006.15. Ioannou GN, Doust J, Rockey DC. Terlipressin for acute esophageal variceal hemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2003, Issue 1. 16. Sreedharan A,Martin J, Leontiadis GI, Dorward S,Howden CW, Forman D,Moayyedi P. Proton pump inhibitor treatment initiated prior to endoscopic diagnosis in upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2010, Issue 7.17. Kusumobroto H. Penatalaksanaan perdarahan varises esofagus. In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. 5 ed. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2009. p. 297-305.18. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of acute upper and lower gastrointestinal bleeding. A national clinical guideline. Edinburgh (Scotland): Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); 2008 Sep. 57 p. SIGN publication no.105).[194references]7