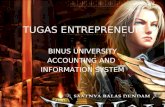Lap akhir prak karmat2 fadli
-
Upload
mohammad-fadli -
Category
Education
-
view
5.862 -
download
5
description
Transcript of Lap akhir prak karmat2 fadli

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
BAB I: Laporan Awal Metalografi dan HST
A. Preparasi/Persiapan Sampel
1. Mounting
1.1 Tujuan Percobaan
Percobaan bertujuan untuk menempatkan sampel pada suatu media, untuk memudahkan
penanganan sampel yang berukuran kecil dan tidak beraturan tanpa merusak sampel.
1.2 Dasar Teori
Spesimen yang berukuran kecil atau memiliki bentuk yang tidak beraturan akan sulit untuk
ditangani khususnya ketika dilakukan pengamplasan dan pemolesan akhir. Sebagai contoh adalah
spesimen yang berupa kawat, spesimen lembaran metal tipis, potongan yang tipis, dll. Untuk
memudahkan penanganannya, maka spesimen-spesimen tersebut harus ditempatkan pada suatu
media (media mounting). Secara umum syarat-syarat yang harus dimiliki bahan mounting adalah :
Bersifat inert (tidak bereaksi dengan material maupun zat etsa)
Sifat eksoterimis rendah
Viskositas rendah
Penyusutan linier rendah
Sifat adhesi baik
Memiliki kekerasan yang sama dengan sampel
Flowabilitas baik, dapat menembus pori, celah dan bentuk ketidakteraturan yang terdapat
pada sampel
Khusus untuk etsa elektrolitik dan pengujian SEM, bahan mounting harus kondusif
Media mounting yang dipilih haruslah sesuai dengan material dan jenis reagen etsa yang
akan digunakan. Pada umumnya mounting menggunakan material plastik sintetik. Materialnya
dapat berupa resin (castable resin) yang dicampur dengan hardener, atau bakelit. Penggunaan
castable resin lebih mudah dan alat yang digunakan lebih sederhana dibandingkan bakelit, karena
tidak diperlukan aplikasi panas dan tekanan. Namun bahan castable resin ini tidak memiliki sifat
mekanis yang baik (lunak) sehingga kurang cocok untuk material-material yang keras. Teknik
Page 1 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
mounting yang paling baik adalah menggunakan thermosetting resin dengan menggunakan
material bakelit. Material ini berupa bubuk yang tersedia dengan warna yang beragam.
Thermosetting mounting membutuhkan alat khusus, karena dibutuhkan aplikasi tekanan (4200
lb/in2) dan panas (1490C) pada mold saat mounting.
Ketika melakukan proses mounting, umumnya sampel dipotong melintang untuk
mendapatkan struktur mikro dari material. Pemilihan resin juga sebaiknya disesuaikan dengan
material yang dimounting. Proses Mounting yang mengaplikasikan tekanan sering menimbulkan
berbagai permasalahan. Berikut permasalahan yang sering timbul dan solusi untuk mengatasinya :
1. Adanya Gelembung yang relative besar pada resin Acrylic
Penyebab: Tekanan Mounting tidak cukup
Solusi: Meningkatkan tekanan mounting atau menurunkan temperature
2. Permukaan yang halus pada cetakan
Penyebab : Mount tidak sempurna terpolimerisasi karena polimer tidak
kompatibel dengan mold release atau minyak di permukaan specimen
Solusi: Bersihkan specimen dan mesin mounting untuk menghilangkan
incompatible coating. Gunakan mold release yang lebih kompatibel.
3. Void / cracks
Penyebab: Tegangan internal yang tinggi akibat pendinginan yang sangat cepat
Solusi: Dinginkan mount lebih lambat dan lama
4. Bentuk tidak beraturan (haze) disekitar specimen (pada cetakan acrylic)
Penyebab: Spesimen mengandung uap, atau specimen mengandung tembaga atau
beberapa paduan yang menghambat polimerisasi.
Solusi: Gunakan desicator atau oven temperature rendah untuk mengeringkan
specimen. Lapisi specimen dengan pernis yang tepat sebelum mounting.
5. Cetakan Phenolic terlepas keluar akibat peningkatan jumlah alcohol
Page 2 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Penyebab: Temperatur mounting tidak mencukupi
Solusi : Tingkatkan temperatur mounting atau periksa elemen pemanas.
6. Distorsi atau cracking pada specimen
Penyebab: Tekanan terlalu besar
Solusi: Kurangi tekanan mounting atau gunakan castable resin
1.3.1 Metodologi Penelitian
Bahan : Sampel representatif
Alat :
- Cetakan silinder
- Resin
- Hardener
1.3.2 Flowchart Proses
Castable mounting Compression mounting
Page 3 of 67
Siapkan permukaan SampelSiapkan cetakan
Letakan piston (hingga naik ke bagian atas silinder)
Tutupi silinder dengan isolasi
Letakan permukaan sampel
Letakan sampel pada dasar cetakan
Kurangi tekanan (hingga piston naik)

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Page 4 of 67
Tuangkan bubuk bakelit kedalam silinder
Siapkan resin (1/3 bagian cetakan)
Tutup bagian atas silinder
Campur resin (15 tetes hardener)
Tambahkan tekanan
Aktifkan pemanasTuangkan ke dalam cetakan (hingga mengeras) ± 30
menit
Pertahankan tekanan
Keluarkan mounting dari cetakan
Stabilkan tekanan
Lepaskan pemanas & pasang blok pendingin
Turunkan tekanan hingga 1 atm
Keluarkan sampel

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
1.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI
2. PENGAMPLASAN/GRINDING
2.1 Tujuan Percobaan
Untuk meratakan dan menghaluskan permukaan sampel dengan cara menggosokan sampel
pada kain abrasif/amplas.
2.2 Dasar Teori
Sampel yang baru saja dipotong, atau sampel yang telah terkorosi memiliki permukaan yang
kasar. Permukaan yang kasar ini harus diratakan agar pengamatan struktur mudah untuk
dilakukan. Pengamplasan dilakukan dengan menggunakan kertas amplas yang ukuran butir
abrasifnya dinyatakan dengan mesh. Urutan pengamplasan harus dilakukan dari nomor mesh yang
rendah (hingga 150 mesh) ke nomor mesh yang tinggi (180 hingga 600 mesh). Ukuran grit pertama
yang dipakai tergantung pada kekasaran permukaan dan kedalaman kerusakan yang ditimbulkan
oleh pemotongan. Lihat tabel berikut
Jenis alat potongUkuran kertas amplas (grit)
untuk pengamplasan pertama
Gergaji pita 60 – 120
Gergaji abrasif 120 – 240
Gergaji kawat / intan kecepatan
rendah
320 – 400
Hal yang harus diperhatikan pada saat pengamplasan adalah pemberian air. Air berfungsi
sebagai pemidah geram, memperkecil kerusakan akibat panas yang timbul yang dapat merubah
Page 5 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
struktur mikro sampel dan memperpanjang masa pemakaian kertas amplas. Hal lain yang harus
diperhatikan adalah ketika melakukan perubahan arah pengamplasan, maka arah yang baru
adalah 450 atau 900 terhadap arah sebelumnya.
Ada beberapa Abrasif yang umum digunakan dalam proses grinding metalografi,
diantaranya sebagai berikut :
Silicon Carbide (SiC)
Abrasif SiC diproduksi oleh reaksi temperatur tinggi antara silika dan karbon. Material ini
memiliki struktur kristal heksagonal-rhombohedral dan memiliki kekerasan hingga mendekati 2500
HV. Material ini merupakan abraif yang ideal untuk cutting dan grinding karena kekerasan dan
sangat mudah memproduksi bentuk ujung yang tajam. Untuk preparasi metalografi, SiC digunakan
di pisau abrasi bdan untuk melapis kertas ginding abrasif (amplas) dalam rentang bervariasi, dari
sangat kasar 60 grit hingga sangat halus 1200 grit
Alumina
Alumina merupakan material yang terbentuk secara alami (dari bauksit). Kekerasannya
dapat mencapai 2000 HV, atau ( dalam skala mohs). Abrasif Alumina terutama sering digunakan
sebagai tahapan akhir dalam pemolesan dikarenakan kekerasan dan ketangguhannya yang tinggi.
Tidak seperti Sic, Alumina terpecah lebih mudah kedalam ukuran submicron atau partikel colloidal
(Abrasif Halus).
Diamond
Merupakan material yang paling keras yang diketahi manusia. Kekerasannya sekitar 8000
HV dan 10 dalam skala Mohs. Memiliki struktur kristal kubik, dan tersedia dalam bentuk alami
maupun buatan. Meskipun diamong ideal untuk grinding kasar, namun harganya yang relatif
mahal membuat proses tersebut menjadi tidak lagi efisien.
Suatu proses grinding yang sukses ditentukan oleh parameter parameter sebagai berikut :
Tekanan Grinding
Page 6 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Kecepatan relatif
Arah Grinding
2.3 Metodelogi Penelitian
2.3.1 Alat dan Bahan
Bahan :
o Sampel representatif yang telah dimounting
o Air
Alat :
o Kertas amplas ukuran grit 120 dan grit 200
o Mesin amplas
2.3.2 Flowchart Proses
Page 7 of 67
Buat bentuk lingkaran pada kertas amplas 120#
Pasang pada mesin amplas
Nyalakan dengan kecepatan rendah
Tuangkan air secara kontinu pada permukaan kertas

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
2.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
3. POLES
3.1 Tujuan Percobaan
Pemolesan bertujuan untuk mendapatkan permukaan sampel yang halus dan mengkilat
seperti kaca tanpa gores.
Page 8 of 67
Letakkan sample pada permukaan amplas
Tambahkan kecepatan putaran sesuai kebutuhan
Ubah arah pengamplasan (45o atau 90o terhadap arah sebelumnya)
Ganti amplas dengan grit yang lebih tinggi
Sampel halus dan rata

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
3.2 Dasar Teori
Dalam pengamatan menggunakan mikroskop, permukaan sampel yang akan diamati harus
rata. Apabila permukaan sampel kasar atau bergelombang, maka pengamatan struktur mikro akan
sulit untuk dilakukan karena cahaya yang datang dari mikroskop dipantilkan secara acak oleh
permukaan sampel. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar berikut:
Permukaan halus Permukaan kasar
Tahap pemolesan dimulai dengan pemolesan kasar terlebih dahulu kemudian dilanjutkan
dengan pemolesan halus. Ada 3 metode pemolesan antara lain yaitu sebagai berikut :
1) Pemolesan Elektrolit Kimia
Hubungan rapat arus & tegangan bervariasi untuk larutan elektrolit dan material yang
berbeda dimana untuk tegangan, terbentuk lapisan tipis pada permukaan, dan hampir tidak ada
arus yang lewat, maka terjadi proses etsa. Sedangkan pada tegangan tinggi terjadi proses
pemolesan.
2) Pemolesan Kimia Mekanis
Merupakan kombinasi antara etsa kimia dan pemolesan mekanis yang dilakukan serentak di
atas piringan halus. Partikel pemoles abrasif dicampur dengan larutan pengetsa yang umum
digunakan.
3) Pemolesan Elektro Mekanis (Metode Reinacher)
Merupakan kombinasi antara pemolesan elektrolit dan mekanis pada piring pemoles.
Metode ini sangat baik untuk logam mulia, tembaga, kuningan, dan perunggu.
Page 9 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
3.3 Metodelogi Penelitian
3.3.1 Alat dan Bahan
Bahan : sampel pengujian, kain poles, alumina
Alat : mesin poles
3.3.2 Flowchart Proses
Page 10 of 67
Pasang kain poles pada mesin poles
Tuangkan sedikit alumina pada kain poles
Nyalakan mesin dengan kecepatan sedang
Poles sampel (sampel diputar secara kontinyu & perlahan pd porosnya )
Poles halus sampai mengkilap
Tambahkan alumina jika perlu

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
3.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
4. ETSA
4.1 Tujuan Percobaan
- Mengamati dan mengidentifikasi detil struktur logam dengan bantuan mikroskop optik
setelah terlebih dahulu dilakukan proses etsa pada sampel
- Mengetahui perbedaan antara etsa kimia dengan elektro etsa serta aplikasinya
- Dapat melakukan preparasi sampel metalografi secara baik dan benar
4.2 Dasar Teori
Etsa merupakan proses penyerangan atau pengikisan batas butir secara selektif dan
terkendali dengan pencelupan ke dalam larutan pengetsa baik menggunakan listrik maupun tidak
ke permukaan sampel sehingga detil struktur yang akan diamati akan terlihat dengan jelas dan
tajam. Untuk beberapa material, mikrostruktur baru muncul jika diberikan zat etsa. Sehingga perlu
pengetahuan yang tepat untuk memilih zat etsa yang tepat. Berikut ini adalah jenis-jenis etsa:
1. Etsa Kimia
Merupakan proses pengetsaan dengan menggunakan larutan kimia dimana zat etsa yang
digunakan ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga pemilihannya disesuaikan dengan sampel
yang akan diamati. Contohnya antara lain :
a) Nitrid acid/acital: asam nitrit + 95% (khusus untuk baja karbon) yang bertujuan untuk
mendapatkan perlit, ferit, danferit dari martensit.
b) Picral: asam picric + alkohol (khusus untuk baja)yang bertujuan untuk mendapatkan perlit,
ferit, dan ferit dari martensit.
c) Ferric chloride: ferric chloride + HCL + air untuk melihat struktur pada SS, nikel austenitic,
dan paduan tembaga.
d) Hydroflouric acid: HF + air untuk mengamati struktur pada alumunium dan paduannya.
Page 11 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Keterangan:
1. Hindari waktu etsa yang terlalu lama (umunya sekitar 4-30 detik)
2. Setelah di etsa, segera dicuci dengan air mengalir lalu dengan alkohol kemudian dikeringkan
dengan hair dryer.
2. Elektro Etsa
Merupakan proses etsa dengan menggunakan reaksi elektoetsa. Cara ini dilakukan dengan
pengaturan tegangan dan kuat arus listrik serta waktu pengetsaan. Etsa jenis ini biasanya khusus
untuk stainless steel karena dengan etsa kimia susah untuk medapatkan detil strukturnya. Skema
peralatan elektro etsa standar dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar diatas mrupakan rangkaian dasar alat elektro etsa yang umum digunakan dalam
skala percobaan laboratorium. Hubungan kuat arus dan tegangan dalam etsa dapat dijelaskan
pada gambar dimana kurva tersebut terbagi menjadi beberapa daerah karakteristik, antara lain,
yaitu:
Daerah A – B : daerah proses etsa, dimana ion logam sebagai anoda, larut dalam
larutan elektrolit.
Daerah B – C : daerah tidak stabil, karena permukaan logam merupakan gabungan dari
daerah pasif dan aktif yang disebabkan oleh perbedaan energi bebas antara butir dan batas
butir.
Daerah C – D : daerah poles, terjadi kestabilan, meskipun tegangan ditambahkan. Hal ini
disebabkan oleh stabilnya larutan. Meskipun pada daerah ini logam berubah menjadi logam
oksida, tetapi oleh larutan elektrolit logam itu dilarutkan kembali.
Page 12 of 67
(Grafik hubungan rapat arus dan
tegangan)

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Daerah D – E : terjadi evolusi oksigen pada anoda, dimana gelembung gas melekat dan
menetap pada permukaan anoda untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan pitting.
Dengan penambahan tegangan, rapat arus melonjak tinggi tak terkendali.
4.3 Metodelogi Penelitian
4.3.1 Alat dan Bahan
Alat:
1. Blower
2. Cawan gelas dan pipet
3. Alat elektro-etsa (rectifier, amperemeter, penjepit sampel konduktif)
Bahan:
1. Zat etsa: FeCl3, Nital 2%, HF 0,5%, dan asam oksalat (H2C2O4) 15 g/100ml air.
2. Air, alkohol, dan tissue
4.3.2 Flowchart Proses
Page 13 of 67
Bersihkan sampel dengan air &alkohol
Celupkan pada zat etsa selama 5-10 detik
Bersihkan dengan alkohol
Keringkan dengan blower

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
4.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
B. Pembuatana Foto dan Analisa Struktur Makro dan Mikro
5. PENGAMATAN STRUKTUR MIKRO
5.1 Tujuan Percobaan
- Mengetahui proses pengambilan foto mikrostruktur
- Menganalisa struktur mikro dan sifat-sifatnya
- Mengenali fasa-fasa dalam struktur mikro
5.2 Dasar Teori
Metalografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu
logam dan paduannya serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya tersebut. Ada
beberapa metode yang dipakai yaitu: mikroskop (optik maupun elektron), difraksi (sinar x,
elektron dan neutron), analisis (X-ray flouresence, elektron mikroprobe) dan juga stereometric
metalografi. Pada praktikum metalografi ini digunakan metode mikroskop sehingga pemahaman
akan cara kerja mikroskop dapat diketahui, khususnya mikroskop optik.
Pengamatan metalografi dengan mikroskop umunya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Metalografi makro, yaitu pengamatan struktur dengan perbesaran 10-100x.
2. Metalografi mikro, yaitu pengamatan struktur dengan perbesaran di atas 100x.
Berikut ini akan dijelaskan mikrostruktur beberapa logam:
- Mikrostruktur Baja Karbon
Page 14 of 67
Lap dengan tissue

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Baja karbon, merupakan material ferrous dengan < 2.14% C. Terbagi atas 2 jenis, yaitu baja
hypoeutectoid (< 0.8%C) dan hypereutectoid (> 0.8%C). Pada kadar 0.8%C terbentuk fasa perlit
(cementit 6.67%C + ferit 0.02%C). Fasa dan kandungan karbon pada baja direpresentasikan dalam
diagram berikut :
Meskipun diagram fasa diatas pada dasarnya merupakan hasil pada kondisi kesetimbangan,
namun dapat pula diaplikasikan untuk memprediksikan sifat pada baja yang sedikit mengalami
proses pelunakan atau yang didinginkan pada pendinginan yang sangat lambat. Terlihat pada
diagram bahwasannya peningkatan temperatur pada baja akan menghasilkan fasa austenit yang
disebut juga dengan besi gamma yang memiliki struktur FCC. Jika pendinginan pada fasa ini
dilakukan dengan tidak kontinyu, maka dapat didaptkan fasa metastabil seperti martensit ataupun
bainit yang idak terlihat pada diagram normal.
- Mikrostrktur Besi Tuang
Besi tuang, yaitu material ferrous dengan kadar karbon 2.14% - 6.67% . Besi tuang komersial
2.5 – 4%C, karena kadar C yang terlalu tinggi membuat besi tuang rapuh. Secara metalografi besi
Page 15 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
tuang dibagi menjadi 4 tipe berdasarkan kadar karbon, impurities, paduan, serta proses perlakuan
panas, yaitu :
- Besi tuang putih: merupakan besi tuang dimana semua kadar karbonnya terpadu dalam
bentuk sementit
- Besi tuang melleable: dimana hampir semua karbonnya dalam bentuk partikel tak beraturan
yang dikenal dengan karbon temper. Besi tuang melleable diperoleh dengan memberikan
perlakuan panas pada besi tuang.
- Besi tuang kelabu: dimana semua atau hampir semua karbonnya dalam bentuk flake.
- Besi tuang nodular: dimana semua atau hampir semua karbonnya dalam bentuk spheroidal.
Bentuk spheroidal ini terjadi akibat adanya penambahan elemen paduan khusus yang
dikenal nodulizer.
- Mikrostruktur Baja karbon pada heat & surface treatment
Baja karbon pada heat & surface treatment, dimana dasarnya adalah transformasi fasa dan
dekomposisi austenite. Proses perlakuan panas antara lain annealing, spheroidisasi, normalisasi,
tempering & quenching. Dasarnya adalah diagram TTT dan CCT, dimana perlakuan panas ini akan
menyebabkan pembentukan fasa martensit dan bainite.
- Mikrostruktur Baja Perkakas
Baja perkakas, adalah baja dengan kualitas tinggi yang digunakan sebagai
perkakas.Tingginya kualitas baja perkakas diperoleh melalui penambahan paduan Cr, W, dan Mo,
dan perlakuan khusus. Umumnya mikrostrukturnya berupa matriks martensite dengan partikel
karbida, grafit dan presipitat.
- Mikrostruktur Paduan Aluminium
Aluminium alloys, terdiri atas kristal utama padatan aluminium (dendritik) ditambah produk
hasil reaksi dengan paduan. Elemen paduan yang tidak berada dalam keadaan padat biasanya
membentuk fasa campuran pada eutektik, kecuali silikon yang muncul sebagai produk utama.
Pada paduan aluminim silikon , eutektik terjadi pada sekitar 12% Si.
- Mikrustruktur Paduan Tembaga
Page 16 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Copper alloys, umumnya dengan elemen dasar seng. Contohnya adalah kuningan (paduan
tembaga seng dengan timbal, timah dan aluminium). Pada diagram fasa Cu-Zn, kelarutan seng
dalam larutan padatan fasa α meningkat dari 3,25% pada temperatur 903 °C ke 39% pada
temperatur454 °C. Fasa α berbentuk FCC, sementara fasa β berbentuk BCC
- Mikrostruktur Material Hasil Lasan
Hasil proses pengelasan pada suatu material akan mempengaruhi struktur asli dari material
tersebut. Pada baja, akan terbentuk austenit hingga tingkat kedalaman tertentu. Semakin dekat
dengan daerah fusi, temperatur baja semakin tinggi, kecepatan pendinginan akan semaki tinggi.
Berikut gambar yang menjelaskan daerah daerah yang terbentuk setelah proses pengelasan :
Pada Logam las terbentuk beberapa area, diantaranya :
a. Area Fusi (Fusion Zone), daerah dimana logam filler yang cair bercampur dengan logam
induk yang dipanaskan sampai temperatur cair. Bentuknya butir columbar dan
widmanstatten, yaitu bentuk memanjang karena logam cair mendapat pendinginan yang
amat cepat, seperti struktur produk cor.
b. Daerah Pertumbuhan butir, dimana logam induk yang tidak mencair butirnya tumbuh
membesar karena pemanasan yang amat tinggi akibat proses pengelasan.
c. Daerah rekristalisasi/penghalusan butir, karena temperatur sedikit lebih rendah dari
daerah b, austenit mengalami rekristalisasi, pembentukan butir baru yang lebih halus,
pada pendinginan akan terjadi ferit dan perlit yang lebih halus.
Page 17 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
d. Daerah transisi, ketika proses welding sebagian fasa austenit masih menjadi ferit, jadi
waktu pendinginan, terdapat campuran ferit baru dan ferit yang ada sebelumnya. Daerah
b, c, dan e disebut daerah terpengaruh panas (HAZ)
e. Daerah tak terpengaruh panas, fasa logam induk yang tidak berubah fasa karena tidak
terkena panas pada pengelasan.
5.3 Metodelogi Penelitian
5.3.1 Alat dan Bahan
Identifikasi dan Foto Mikrostruktur
Bahan :
o Sampel representatif
o Lilin
Alat :
o Preparat
o Mikroskop optik kamera
Pengambilan Foto Mikro
Bahan :
o Sampel representatif
Alat :
o Preparat
o Mikroskop kamera
Perhitungan Besar Butir
Bahan :
Page 18 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
o Sampel representatif
Alat :
o Preparat
o Mikroskop optik kamera
5.3.2 Flowchart Proses
Identifikasi Pengambilan foto mikro
foto mikro dan makrostruktur
Penghitungan besar butir
Page 19 of 67
Letakan sampel pada preparat
Beri lilin pada bawah sampel
Ratakan peletakan sampel (dengan alat penekan)
Nyalakan lampu mikroskop
Tentukan perbesaran mikroskop (dari kecil ke besar) dan atur lensa
obyektif
Letakan sampel di bawah lensa obyektif
Tentukan fokus
Tentukan diafragma dan pencahayaan
Pengambilan foto
Tentukan metode yang dipilih

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
5.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
6. PENGAMATAN STRUKTUR MAKRO
6.1 Tujuan Percobaan
Mengetahui bentuk – bentuk perpatahan pada sampel makro
6.2 Dasar Teori
Metalografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu
logam dan paduannya serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya tersebut. Ada
beberapa metode yang dipakai yaitu: mikroskop (optik maupun elektron), difraksi (sinar x,
elektron dan neutron), analisis (X-ray flouresence, elektron mikroprobe) dan juga stereometric
Page 20 of 67
Atur focus dengan mengatur lensa
Amati dan gambar mikrostruktur
Gunakan perbesaran 100x
Siapkan tabel
Hitung besar butir
Ambil sample dari meja objektif dan matikan mikroskop
Catat hasil yang didapat

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
metalografi. Pada praktikum metalografi ini digunakan metode mikroskop sehingga pemahaman
akan cara kerja mikroskop dapat diketahui, khususnya mikroskop optik.
Pengamatan metalografi dengan mikroskop umunya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Metalografi makro, yaitu pengamatan struktur dengan perbesaran 10-100x.
2. Metalografi mikro, yaitu pengamatan struktur dengan perbesaran di atas 100x.
Berikut ini akan dijelaskan pengamatan makrostruktur beberapa logam:
6.2.1 Mode Perpatahan Material
Sampel hasil pengujian tarik dapat menunjukkan beberapa tampilan perpatahan seperti
yang ditunjukkan pada gambar:
Perpatahan ulet memberikan karakteristik berserabut (fibrous) dan gelap (dull), sementara
perpatahan getas ditandai dengan permukaan patahan berbutir (granular) dan terang. Perpatahan
ulet umumnyalebih disukai karen bahan ulet umumnya lebih tangguh dan memberikan peringatan
lebih dahulu sebelum terjadinya kerusakan.
Pengamatan kedua tampilan perpatahan itu bisa diamati dengan mata telanjang ataupun
menggunakan SEM. Berikut ciri-ciri perpatahan ulet dan getas:
a. Perpatahan ulet
Page 21 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
1. Dapat terlihat jelas deformasi plastis yang terjadi
2. Karakteristik berserabut (fibrous) dan gelap (dull)
b. Perpatahan getas
1. Tidak ada atau sedikit sekali deformasi plastis yang terjadi pada material
2. Retak/perpatahan merambat sepanjang bidang-bidang kristalin membelah atom-atom
material (transgranular)
3. Pada material lunak denga butir kasa (coarse grain) maka dapat dilihat pola-pola yang
dinamakan chevrons or fan-like pattern yang berkembang keluar dan dareah awal
kegagalan.
4. Material amorphous (seperti gelas) memiliki permukaan patahan yang bercahaya dan
mulus.
6.3 Metodelogi Penelitian
6.3.1 Alat dan Bahan
Identifikasi dan Foto Mikrostruktur
Bahan :
o Sampel representatif
o Lilin
Alat :
o Preparat
o Mikroskop optik kamera
Pengambilan Foto Mikro
Bahan :
o Sampel representatif
Alat :
Page 22 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
o Preparat
o Mikroskop kamera
Perhitungan Besar Butir
Bahan :
o Sampel representatif
Alat :
o Preparat
o Mikroskop optik kamera
6.3.2 Flowchart Proses
Identifikasi Pengambilan foto mikro
foto mikro dan makrostruktur
Page 23 of 67
Letakan sampel pada preparat
Beri lilin pada bawah sampel
Ratakan peletakan sampel (dengan alat penekan)
Nyalakan lampu mikroskop
Letakan sampel di bawah lensa obyektif
Tentukan fokus
Tentukan diafragma dan pencahayaan
Pengambilan foto

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Penghitungan besar butir
6.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
C. Percobaan Jominy
7. PERCOBAAN JOMINY
7.1 Tujuan Percobaan
Page 24 of 67
Tentukan perbesaran mikroskop (dari kecil ke besar) dan atur lensa
obyektif
Atur focus dengan mengatur lensa
Amati dan gambar mikrostruktur
Tentukan metode yang dipilih
Gunakan perbesaran 100x
Siapkan tabel
Hitung besar butir
Ambil sample dari meja objektif dan matikan mikroskop
Catat hasil yang didapat

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
- Mendapatkan hubungan antara jarak permukaan pada pendinginan langsung dengan
sifat kemampukerasan bahan.
- Mendapatkan hubungan antara kecepatan pendinginan dengan fasa yang terbentuk
serta mendapatkan sifat kekerasan dari fasa tersebut.
-
7.2 Dasar Teori
Proses kombinasi pemanasan dan pendinginan yang bertujuan mengubah struktur mikro
dan sifat mekanis logam disebut perlakuan panas (heat treatment). Logam yang didinginkan
dengan kecepatan dan media pendingin berbeda memberikan perubahan struktur mikro yang
berbeda pula. Setiap struktur mikro yang terbentuk (martensit, bainit, ferit dan perlit) merupakan
hasil transformasi fasa austenit. Tiap fasa tersebut terbentuk pada kondisi pendinginan yang
berbeda-beda sebagaimana yang dapat dilihat pada diagram CCT dan TTT. Tiap fasa memiliki nilai
kekerasan yang berbeda-beda. Dengan pengujian Jominy (jominy test) dapat dibuktikan bahwa
laju pendinginan yang berbeda-beda akan menghasilkan kekerasan bahan yang berbeda. Pada
percobaan ini, sampel dipanaskan hingga suhu austenit, selanjutnya didinginkan secara merata,
lalu dihitung nilai kekerasannya. Nilai kekerasan berbanding lurus dengan jarak dari tempat
berakhirnya quenced. Makin lambat laju pendinginan logam, makin banyak matriks perlit yang
ditampilkan dan kekerasan makin turun. Sifat logam tersebut disebut Haredenability atau
kemampukerasan. Secara definisi, hardenability adalah Sifat yang menntukan kedalaman dan
distribusi kekerasan yang ditimbulkan pada proses quenching dari austenit. Sifat ini Ditentukan
oleh berbagai factor diantaranya:
Komposisi Kimia
Ukuran butir austenit
Struktur baja sebelum quenching
Metode Jominy menggunakan batang diameter 4 inch, metodenya adalah dengan
meletakkan standar sampel Jominy dengan bagian ujungnya didinginkan dengan air. Setelah
pendinginan, sampel di amplas rata pada satu sisi, dan diukur kekerasan sepanjang batang
sampel.Kemudian sampel dipotong untuk dianalisa struktur mikronya , dari struktur mikro
tersebut dapat dilihat hubungannya dengan kekerasan. Sehingga nanti didapat bahwasannya laju
pendinginan mempengaruhi sifat mekanisnya, dan dapat pula dibuat diagram CCT dengan
mengetahui jumlah struktur mikro dan kekerasannya.
Page 25 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Berikut contoh diagram CCT yang dihasilkan oleh percobaan Jominy :
Hubungan antara kekerasan dengan jarak quench umumnya dijelaskan dengan kurva seperti
berikut :
Page 26 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Makin lambat laju pendinginan logam, makin banyak matriks perlit yang ditampilkan dan
kekerasan makin turun. Penambahan kadar karbon atau paduan atau bertambah besarnya ukuran
butir akan menyebabkan grafik bergeser kekanan sehingga memudahkan pembentukan struktur
martensit. Pergeseran grafik kekanan juga menggambarkan sifat kemampukerasan bahan
tersebut. Untuk pendinginan lambat akan mendapatkan struktur:
- Bainit bawah; struktur seperti jarum mirip martensit
- Bainit atas; struktur seperti perlit dengan sifat lapisanyang lebih halus
- Perlit halus; struktur perlit yang halus dengan lapisan ferit dan sementit
- Perlit kasar; struktur sam dnegan perlit halus namun lamel lebih kasar dan kekerasan
lebih rendah.
7.3 Metodelogi Penelitian
7.3.1 Alat dan Bahan
- Batang baja sebagai benda uji (d = 2.5 cm, L = 10 cm)
- Oven Muffle temperatur max. 11000C
- Kran air dengan tekanan cukup
- Amplas
- Alat penguji kekerasan Brinell
- Mikroskop pengukur jejak
7.3.2 Flowchart Proses
Page 27 of 67
Siapkan benda uji

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Page 28 of 67
Amplas salah satu sisi untuk penjejakan
Panaskan batang uji dari oven
Keluarkan dari oven
Letakan pada alat bangku Jominy
Semprot ujung bawah logam dengan air, biarkan sampai
dingin
Bersihkan bagian penjejakan
Lakukan penjejakan (15 titik berjarak sama)
Ukur besarnya diameter jejak
Hitung kekerasan dgn Brinnel
Preheating
(350o, 15 menit)
Austenisasi
(900o, 30 menit)

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
7.4 Daftar Pustaka
Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Lab. Metalografi dan HST, Departemen Teknik
Metalurgi dan Material FT UI.
Bab II Paper Praktikum
Pengaruh Perlakuan Panas Normalisasi Terhadap Sifat Mekanis dan
Struktur Mikro dari Baja Karbon Rendah
Normalisasi adalah proses perlakuan panas yang dilakukan pada suatu material logam untuk
memperhalus butiran kristal, sehingga mempengaruhi nilai kekerasan dan kekuatan. Dalam
beberapa hal juga dapat menaikkan machinabiliti yaitu kemampuan material untuk dapat dilakukan
proses permesinan. Pada normalisasi selain diperoleh butiran yang lebih halus juga struktur menjadi
lebih homogen. Normalisasi didapatkan dengan memanaskan baja setidaknya 55 C (100F) di atas
upper critical line dari digram fasa Fe-Fe3C, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, dimana di
atas A3 untuk hypoeutectoid - komposisinya kurang dari eutectoid (<<0,76%C) – dan di atas Acm
untuk hypereutectoid – komposisinya lebih dari eutectoid (>>0,76%C). Pada perlakuan normalisasi,
proses pemanasan dilakukan hingga menghasilkan fasa austenitic yang homogen sebelum dilakukan
pendinginan. Gambar 2 menampilkan perbandingan pada siklus temperatur dan waktu dari
normalizing dan full anneal.
Page 29 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Normalisasi juga sering dipertimbangkan dalam mikrostruktur yang dihasilkan. Daerah
mikrostruktur yang terkandung 0.8%C adalah peralitic dan daerah mikrostruktur yang lebih rendah
dari itu adalah ferritic. Pada baja hypereutectoid, proeutectoid Fe3C pertama membentuk
Page 30 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
ssepanjang batas butir austenite. Transformasi ini berlanjut hingga kadar karbon dalam austenite
mencapai mendekati 0.8%C yang mana waktu terjadinya reksi eutectoid diindikasikan dengan
pembentukan pearlite.
Tujuan normalisasi beragam tergantung aplikasinya. Normalisasi bisa meningkatkan dan
menurunkan kekuatan pada produk baja, tergantung suhu dan mekanis produk baja tersebut
sebelumnya. Pada umumnya, alasan melakukan normalisasi adalah untuk mendapatkan butir yang
homogen, penghalusan butir, meningkatkan machibilitas dan menghilangkan tegangan sisa yang
akan mempengaruhi sifat mekanis material tersebut. Sebagai contoh, normalisasi dilakukan pada
produk coran untuk menghilangkan struktur dendrit sehingga menghasilkan mikrostruktur yang
seragam. Begitu pula pada wrought product, normalisasi bisa menghilangkan ketidakseragaman
butir selama pengerolan panas atau saat forging. Tabel berikut ini akan menampilkan pengaruh
perlakuan panas seperti full anneal, normalisasi, dan temper terhadap sifat mekanik beserta
alasannya dilakukan perlakuan panas tersebut.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, normalisasi akan mempengaruhi sifat mekanis dan
struktur mikro baja. Ada beberapa parameter penting yang mempengaruhi sifat mekanis dan
struktur mikro tersebut seperti temperatur austenisasi dan lama waktu tahannya. Makin tinggi
temperatur austenisasi dan makin lama waktu tahan, kekuatan baja makin menurun, namun
ketangguhannya akan meningkat. Keseragaman struktur mikro juga meningkat dengan perlakuan
panas normalisasi ini.
Page 31 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Hal ini karena temperatur yang makin tinggi tersebut ditambah dengan energi sisa yang ada
pada logam, memberikan energi yang cukup untuk menghasilkan butir baru yang kecil dan
seragam. Butir yang kecil ini akan menyebakan logam menjadi tangguh, kekuatan meningkat,
kekerasan menurun, dan semakin ulet. Fenomena ini dijelaskan dengan persamaan Hall-Petch yang
menjelaskan hubungan ukuran butir dengan kekutan luluh.
Jika temperatur dinaikkan dan waktu tahan diperlama, proses pembentukan butir baru ini
akan semakin sempurna dan didapat butir yang homogen. Namun, apabila terlalu berlebih maka
terjadi pertumbuhan butir yang tak terkendali sehingga butir akan tumbuh menjadi besar sehingga
ketangguhannya menurun, kekerasannya meningkat, kekuatan menurun dan getas. Oleh karena itu
ada suhu dan waktu optimum dalam melakukan normalisasi.
Berikut ini contoh mikrostruktur baja SCMnCr2 yang dilakukan normalisasi pada 850 C selama 20
menit:
Sebelum Sesudah
Daftar Pustaka
ASM Metals Handbook Vol.4: Heat Treating
Calister, William.D . Materials Science and Engineering An introduction 7th Ed. 2007. Wiley: New York
Darmawan, Agung Setyo; Masyrukan dan Ariyandi, Riski. PROSES NORMALIZING DAN TEMPERING PADA SCMnCr2 UNTUK MEMENUHI STANDAR JIS G 5111. Jurnal Media Mesin Vol.8. 2007: Surakarta
Rochiem, Rochman; Purwaningsih, Hariyati dan Susanto, Edwin Setiawan. PENGARUH PROSES PERLAKUAN PANAS TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO BAJA AISI 310 S. ITS: Surabaya
Widyatmadji. Pengaruh Perlakuan Panas Normalisasi Terhadap Sifat Mekanik Dan Struktur Mikro Baja 1K3816AT Untuk Aplikasi Casing & Tubing Spesifikasi API 5CT K55. 2001. UI: Depok
Page 32 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Bab III Pembahasan Praktikum
III. 1 Pengujian Metalografi
1.1 Hasil Mounting
Mounting bertujuan untuk mempermudah penanganan sampel pada proses selanjutnya.
Karena tujuannya hanya untuk mempermudah, maka sebelumnya ditentukan terlebih dahulu
apakah sampel harus dimounting atau tidak didasarkan pada bentuk dan ukuran sampel. Sampel
yang berukuran kecil dan tidak memungkinkan atau sulit untuk dipegang pada proses selanjutnya
(dalam hal ini pengamplasan, pemolesan, dan etsa), perlu dilakukan proses mounting terlebih
dahulu. Sebaliknya, sampel yang berukuran cukup besar yang memungkinkan untuk dipegang,
maka proses mounting tidak perlu dilakukan terhadap sampel.
Kondisi sampel individu yang didapatkan oleh praktikan telah dipotong dan dimounting
sebelumnya oleh asisten, sehingga praktikan menjadi lebih mudah dan cepat saat melakukan
rangkaian proses karena tidak perlu lagi melakukan mounting sampel, tetapi tinggal melanjutkan
proses selanjutnya yakni pengamplasan.
Pada praktikum ini, media mounting yang digunakan oleh praktikan adalah castable resin
dengan teknik mountingnya adalah castable mounting. Teknik castable mounting ini merupakan
teknik mounting yang lebih sederhana dibandingkan dengan teknik compression mounting yang
menggunakan media bakelit, karena pada teknik castable mounting ini tidak memerlukan aplikasi
panas dan tekanan. Selain itu peralatan dan bahan yang digunakan cukup simpel yaitu seperti
plastik bekas tempat rol film yang dipotong menjadi 2 bagian yang digunakan sebagai cetakan,
lakban yang digunakan untuk menutupi bagian bawah cetakan, castable resin, dan hardener.
Untuk melakukan teknik mounting ini hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut.
Prosedur kerja mounting :
Menutupi bagian bawah cetakan dengan menggunakan lakban, setelah itu masukkan sampel
uji kedalam cetakan bagian bawah cetakan hingga sampel tersebut terlihat menempel dengan
lakban.
Membuat campuran antara castable resin dengan hardener ditempat lain (tempatnya juga
menggunakan plastik bekas tempat rol film yang masih utuh), perbandingan antara volume
Page 33 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
castable resin dengan hardener yaitu castable resin yang volumnya 1/3 bagian dari plastik
tempat rol film diteteskan sebanyak 15 tetes hardener, pencampuran dilakukan sambil diaduk
agar pencampuran antara castable resin dan hardener terjadi secara merata, tetapi
pengadukannya jangan terlalu cepat untuk menghindari terbentuknya gas hole pada
mounting.
Setelah dilakukan pencampuran, kemudian castable resin dimasukkan ke dalam cetakan yang
telah disiapkan, setelah dimasukkan ke dalam cetakan kemudian tunggu antara 25 - 30 menit.
Setelah mounting mengeras, melepas lakban dari cetakan lalu mengeluarkan mounting dari
cetakan.
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil mounting dengan proses castable mounting
adalah :
Pemasangan Cetakan
Pada pemasangan lakban serta cetakan harus benar-benar diperhatikan, diusahakan
serapat mungkin dan rapi.
Pengadukan
Pengadukan yang terlalu cepat saat pencampuran castable resin dan hardener dapat
menyebabkan timbulnya gelembung udara.
Hardener
Jumlah dari hardener yang digunakan akan sangat mempengaruhi hasil mounting yang
didapat. Semakin banyak hardener yang dimasukkan ke dalam resin maka semakin cepat
mounting mengering, namun juga akan memperkeruh mounting itu sendiri dan akan
menimbulkan asap. Untuk itu maka jumlah komposisi hardener yang tepat akan
menghasilkan warna mounting yang jelas dan tidak timbul asap sehingga tidak ada cacat
seperti gelembung gas dan retak. Pada hasil mounting praktikan dapat dilihat hasil
mounting yang tidak keruh, bagian atas permukaannya rata, tidak terdapat rongga udara
dan retak, hal ini menandakan hardener yang diberikan sudah sangat sesuai dengan
kebutuhannya.
Ketebalan Resin
Semakin tebal resin maka akan semakin lambat waktu pengeringannya, namun juga akan
mempermudah dalam pemegangan sample.
Page 34 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Waktu Pengeringan
Waktu pengeringan sampel biasanya sekitar 30 menit. Jika waktu pengeringan
berlangsung lebih lama, hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya hardener atau
akibat pengadukan yang tidak merata.
Sampel 618 quench udara
Dari kondisi sampel yang diterima oleh praktikan, hasil mounting sampel praktikan cukup baik.
Hanya saja permukaan mounting tidak rata karena pemasangan cetakan yang kurang baik. Lakban
yang menutupi cetakan kurang rapat dan rapi sehingga permukaan sampel agak miring. Disamping
itu permukaan sampel sudah sedikit terkorosi dan terdapat mikropitting.
Beberapa kendala yang mungkin terjadi saat kita melakukan proses castable mounting adalah
sebagai berikut :
Masalah yang timbul Penyebab Penyelesaian
Resin Panas
Retak radial Cuplikan terlalu besar Besarkan ukuran molding
dan kurangi ukuran
cuplikan
Pengkerutan Suhu terlalu tinggi Turunkan suhu
Retak melingkar Udara lembab terjebak di dalam
resin
Hilangkan uap air,
turunkan tekanan pada
fasa cair
Remuk Waktu pemadatan terlalu
singkat, tekanan tidak sesuai
Tambah waktu
pemadatan, sesuaikan
tekanan
Tidak terjadi
penggabungan
Kondisi tidak sesuai Evaluasi kondisi molding
Resin dingin
Page 35 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Retak Waktu pemadatan tidak cocok,
suhu terlalu tinggi, komposisi
padatan dan pelarut tidak sesuai
Koreksi kekurangan
tersebut
1.2 Hasil Amplas
Proses yang berikutnya setelah dilakukan mounting yaitu grinding atau pengamplasan. Proses
pengamplasan ini dilakukan menggunakan mesin amplas otomatis, dalam artian mesin
pengamplasan tersebut telah berputar dengan kecepatan tertentu secara konstan sehingga yang
perlu kita lakukan adalah mengatur posisi sampel, meletakkan diatas permukaan dan memberikan
penekanan sesuai kebutuhan, tentunya juga perlu dilakukan penggantian kertas amplas untuk
mendapatkan hasil pengamplasan yang sesuai dengan yang dinginkan. Penggunaan mesin amplas
ini bertujuan untuk menghasilkan hasil amplas yang lebih baik dan homogen dibandingkan proses
pengamplasan manual. Proses pengamplasan dilakukan secara bertahap dan berurutan agar
didapatkan permukaan yang sangat halus karena di bawah mikroskop diperlukan permukaan yang
halus agar didapat hasil pengamatan yang baik yaitu permukaan sampel yang bebas dari goresan
sehingga tidak akan terjadi pemantulan acak cahaya pada saat pengamatan dengan mikroskop.
Perlu diperhatikan agar selama pengamplasan tekanan ke seluruh bagian sampel dijaga uniform
sehingga seluruh permukaan sampel mengalami pengamplasan yang merata agar tidak dihasilkan
bidang-bidang yang berlainan pada sampel.
Pada proses pengamplasan, dimulai dengan menempatkan kertas amplas pada mesin amplas
dan kemudian dijepit sesuai dengan ukuran mesin amplasnya. Pada saat pemasangan kertas
amplas ini juga harus diberi air pada permukaan mesin amplas agar nantinya kertas amplas yang
dipasang tidak bergelombang dan juga agar kertas amplas dapat melekat dengan baik. Jika
terbentuk gelombang pada mesin amplas, maka akan menghasilkan permukaan yang tidak rata
atau dua permukaan yang terhaluskan dan juga dapat menyebabkan kertas amplas robek. Selain
itu air berguna untuk pemindah geram, memperkecil gesekan agar sampel tidak rusak dan
memperpanjang pemakaian kertas amplas. Kemudian saat menjalankan mesin amplas, dimulai
dari kecepatan yang rendah ke kecepatan tinggi. Tujuannya agar sampel ketika diamplas, pada
kecepatan yang besar permukaannya akan semakin cepat halus dan rata. Terutama untuk sampel
dengan kekerasan yang tinggi akan dibutuhkan kecepatan pengamplasan tinggi pula agar sample
lebih mudah untuk dihaluskan.
Page 36 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Dan proses pengamplasannya melalui lima tahap ukuran grit yang berbeda yakni 240, 400,
600, 800, 1200, dan 1500. Pada setiap ukuran gritnya, penampakan permukaan sampel
berangsur-angsur memiliki goresan yang semakin kecil.
Kemudian, untuk pengamplasan sampel HST, S50, diamplas dengan menggunakan kertas
amplas yang kasar,grit 240 kemudian dilanjutkan dengan kertas amplas yang lebih halus yaitu dari
yang bernomor mesh 400, 600, 800, 1200 dan 1500. Tidak semua permukaan sampel bersih dari
lapisan oksida. Masih ada beberapa bagian kecil yang sulit untuk dihilangkan karena permukaan
sampel yang tidak rata. Namun, masih banyak daerag yang bersih dari oksida untuk dilakukan uji
kekerasan dan pengamatan struktur mikro.
Sampel HST S50 setelah di amplas
Beberapa parameter yang mempengaruhi kerja pengampelasan:
Pemberian air pada saat pengampelasan
Air yang dituangkan seharusnya konstan dan tidak tidak terlalu banyak. Namun saat
praktikum, air yang dituang tidak konstan dan jumlahnya juga tidak sama.
Perubahan arah ampelas
Arah ampelas setiap melakukan pergantian grit kertas amplas harus disesuaikan. Diubah
45o atau 90o. Pada saat praktikum saya melakukan hal itu, sehingga permukaan yang
dihasilkan lumayan baik walaupun tidak 100% permukaannya baik.
Pengoperasian mesin ampelas
Mesin ampelas harus diatur konstan dan tidak terlalu kencang agar permukaan sampel
tidak cepat tergerus.
Pada saat ampelas beberapa sampel di atas 1 mesin ampelas terdapat beberapa sampel.
Dan sampel tersebut jenisnya berbeda. Untuk sampel yang jenis medium carbon steel
seharusnya jangn bersamaan dengan baja karena permukaan sampel medium carbon steel
akan rusak karena terkena bekas ampelas jenis baja.
Page 37 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
1.3 Hasil Poles
Pemolesan merupakan proses untuk memperhalus permukaan sampel hingga skala mikron
agar permukaan sampel yang dipoles dapat memantulkan cahaya dengan baik, sehingga pada saat
pengamatan mikrostruktur dapat terlihat lebih jelas. Pemolesan yang dilakukan oleh praktikan
merupakan pemolesan tipe mekanik. Kain poles yang digunakan praktikan ialah kain poles
beludru dan bahan polesnya adalah alumina yang berwarna putih yang telah dilarutkan dengan
air. Untuk sampel yang bertipe ferrous dan non ferrous harus dilakukan di mesin poles yang
berbeda. Hal ini ditujukan agar geram yang dihasilkan oleh sampel ferrous tidak akan merusak
permukaan halus dari sampel non-ferrous.
Mesin Poles Sampel non-Ferrous
Seperti halnya pada proses pengamplasan, proses pemolesan pun harus diberikan air.
Pemberian air saat pemolesan harus tetes demi tetes (tidak boleh terlalu banyak), pemberian air
ini sebenarnya hanya untuk meratakan alumina keseluruh bagian kain beludru, sekaligus
memudahkan praktikan dalam melakukan pemolesan karena jika tidak diberikan air maka
pemegangan terhadap sampel akan semakin sulit karena koefisien gesek kain beludru terhadap
sampel uji menjadi semakin besar. Tetapi jika pemberian air terlalu berlebih maka akan membuat
pemakaian alumina semakin tidak hemat karena akan banyak alumina yang larut oleh air dan
akhirnya terbuang. Berbeda dari proses pengamplasan, pada proses pemolesan sampel harus
digerakkan dan diputar-putar terus menerus pada porosnya untuk menghindari terbentuknya
cacat berupa ekor komet. Ekor komet adalah cacat berupa goresan melingkar pada pemukaan
sampel akibat pemolesan yang statis atau tidak bergerak.
Pada saat pemolesan yang diperhatikan adalah goresan-goresan yang masih ada pada
permukaan sampel hasil ampelas. Karena larutan alumina akan mengisi goresan-goresan tersebut
sehingga akan terjadi kesalahan pada foto mikro.
Page 38 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Dari hasil pemolesan sampel praktikan 618 quench udara, terlihat sanagat mengkilap seperti
kaca dikarenakan baja 618 mengandung unsur Cr. Sedangkan sampel HST, setelah dilakukan
pemolesan masih terdapat gores kecil dan tidak begitu mengkilap seperti baja 618.
1.4 Hasil etsa
Proses etsa merupakan tahap akhir dari serangkain proses preparasi sampel dan dilakukan
setelah proses pemolesan. Proses etsa yang dilakukan adalah pengetsaan kimia, yaitu dengan jalan
mencelupkan spesimen ke dalam larutan pengetsa selama beberapa detik tergantung dari jenis
sampel yang akan diuji. Etsa sendiri bertujuan untuk mengikis batas butir dengan menggunakan
prinsip korosi yang terkontrol.
Proses etsa yang dilakukan diawali dengan membersihkan bagian permukaan sampel yang
telah dipoles dengan air lalu kemudian dikeringkan menggunakan blower. Setelah itu sampel
dicelupkan ke dalam kaca arloji yang berisi zat etsa yang akan digunakan dan ditahan sampai batas
waktu yang telah ditentukan sambil digoyang-goyang. Untuk sampel ferrous, pada saat
pengetsaan ditahan selama 5-10 detik. Setelah ditahan sampai waktu yang ditentukan tersebut
sampel segera diangkat dan dibersihkan dengan air lalu ditetesi alkohol. Setelah dibersihkan
dengan alkohol sampel segera dikeringkan dengan blower. Dan berikut ini adalah tabel sampel dan
jenis etsa,
Sampel Zat etsa Waktu
618 Nital 2 % 10 detik
S50( sampel HST) Nital 2 % 10 detik
Hal yang perlu diperhatikan dalam proses etsa adalah penentuan zat etsa yang sesuai untuk
setiap jenis material sampel. Jika penggunaan zat etsa yang tidak sesuai dapat menimbulkan cacat
terutama pada proses etsa kimia yang disebabkan oleh mekanisme pengikisan batas butir tidak
akan menghasilkan hasil etsa yang baik. Selain itu juga harus diperhatikan waktu pengetsaan
karena terkait dengan kecepatan penyerangan zat etsa. Pengetsaan yang terlalu cepat
mengakibatkan batas butir tidak terkikis dengan baik sehingga mikrostruktur tidak tampak dengan
Page 39 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
baik. Sedangkan jika terlalu lama maka zat etsa akan mengikis butir dari material dan
menyebabkan material menjadi hangus. Untuk mengatasi masalah pengetsaan yang kurang baik
dapat diperbaiki dengan mengulang kembali proses pemolesan hingga kembali didapatkan
permukaan sampel yang mengkilap kemudian dietsa kembali dengan zat etsa yang sama.
Sedangkan untuk proses etsa yang berlebihan atau sering disebut dengan istilah over-etching
dapat diatasi dengan mengamplas kembali sampel yang hangus kemudian dipoles dan dietsa.
Kemudian ketika dilakukan pengeringan dengan blower juga terdapat hal yang harus diperhatikan
yaitu posisi sampel yang harus tepat agar didapat pengeringan yang sempurna (semua permukaan
sampel kering).
Hasil pengetsaan yang baik jika dilihat dengan mata telanjang akan terlihat permukaan
sampel yang agak keburaman. Setelah dilakukan pengetsaan, maka selanjutnya melakukan
pengamatan mikro. Bagian yang diamati di bawah mikroskop optik adalah bagian permukaan yang
berwarna buram, yang menandakan bahwa daerah tersebut telah mengalami pengetsaan dengan
baik. Proses pengetsaan yang agak kurang lebih baik daripada pengetsaan yang berlebihan. Proses
pengetsaan yang agak kurang dapat diperbaiki dengan proses pemolesan kembali. Tetapi
pengetsaan yang berlebihan akan menghasilkan permukaan yang gosong dan struktur yang sukar
untuk diamati di bawah mikroskop optik, sehingga harus diamplas kembali untuk memperbaikinya.
Pada proses pengetsaan, sampel praktikan, 618, dietsa selama 5 detik tapi batas butirnya
belum terkikis dengan baik sehingga ketika diamati dengan mikroskop mikrostruktur 618 terlihat
dengan samar-samar. Oleh karena itu dilakukan etsa ulang dengan waktu 10 detik. Setelah dietsa
terlihat perbedaan dari sebelumnya. Permukaan sampel terdapat korosi. Berarti sampel sudah
teretsa dengan baik. Ketika diamati dengan mikroskop, mikrostruktur terlihat jelas. Sedangkan
sampel HST tidak mengalami masalah ketika proses pengetsaan.
1.5 Hasil Pengamatan Struktur Mikro
Foto Struktur Mikro AISI 618 Quench udara
Foto Literatur (Atlas of Time Temperature Diagrams for Irons &Steel, G.F Van der Voort)
Page 40 of 67
Foto sampel hasil praktikum
Material : AISI 618 (Quench udara)
Perbesaran : 500 x
Etsa: Nital 2 % selama 10 s
Fasa : Martensite, sedikit austenit sisa, dan sedikit ferrite
Foto Literatur
Material : Baja tipe Fe-Ni-Cr-Mo (AISI 618)
Perbesaran : 200 x
Etsa: Nital 2 %
Martensite
Ferrite
Austenite

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Penjelasan Sampel
Sampel AISI 618 ketika sebelum dilakukan pengamatan dibawah struktur mikro pada awalnya
memunculkan pola berupa garis – garis memanjang yang merupakan pola mikro pitting yang
semakin parah akibat etsa. Disamping itu, terdapat daerah yang terkorosi akibat proses etsa. Bisa
dikatakan sampel sudah teretsa dengan baik. Setelah dilakukan pengamatan struktur mikro
terlihat sedikit lapisan menempel pada sampel yang menunjukkan bahwasannya sampel telah
terkontaminasi oleh lemak yang dapat saja berasal dari jari akibat tidak sengaja terpegang.
Kemudian terdapat pula kotoran – kotoran dipermukaan karena bekas tisu ketika pengelapan.
Namun hal ini tidak menjadi masalah karena pengamatan mikro hanya membutuhkan area yang
relative sempit, sehingga dapat dicari area yang masih bersih. Kemudian setelah didapatkan
tempat yang tepat dilakukan pengamatan struktur mikro, hasil pengamatan memperlihatka
struktur yang didominasi oleh struktur martensite yang relative halus dan tajam sehingga
praktikan menyimpulkan bahwa sampel tersebut didominasi fasa martensit dengan jenis lath, atau
bilah. Disamping itu, terdapat beberapa daerah kecil yang berwarna putih dan kecoklatan. Daerah
yang berwarna putih adalah ferrite sedangkan yang berwarna coklat adalah austenite sisa yang
belum bertransformasi menjadi martensite.
Menurut literature (ASM Vol 01) , baja AISI 618 merupakan baja dengan komposisi :
Unsur C Cr Fe Mn Mo Ni Si
Kadar (%) 0,37 2,00 94,73 1,40 0,20 1,00 0,30
Dengan sifat mekanik:
Page 41 of 67
Foto Literatur
Material : Baja tipe Fe-Ni-Cr-Mo (AISI 618)
Perbesaran : 200 x
Etsa: Nital 2 %

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
- UTS: 485 Mpa
- Yield Strength: 345 Mpa
- % Elongation: 19 in 200mm
Diagram Fasa Fe-Fe3C
Baja AISI 618 adalah paduan baja Cr-Ni-Mo yang melalui proses vacuum degassing. Baja
jenis ini dimanufaktur dengan kandungan sulfur (S) yang dikontrol secara ketat, yaitu pada kadar
maksimum 0,015%. Setelah praktikan mencocokan dengan diaram TTT dari tipe Fe-Ni-Cr-Mo yang
komposisinya mendekati komposisi AISI 618 dan disesuaikan dengan kurva pendinginan dengan
udara, maka benar didapat mikrostruktur martensit dengan sedikit austenit sisa dan ferrite.
Page 42 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Gambar diagram TTT tipe Fe-Ni-Cr-Mo
Kurva pendinginan dengan media udara
Aplikasi
Aplikasi AISI 618 adalah sebagai baja tahan panas untuk aplikasi seperti pada komponen
mesin mobil atau heat exchanger dimana mikrostruktur martensite untuk meningkatkan kekuatan
agar tahan terhadap beban/tekanan saat aplikasinya. Namun dalam penggunaannya perlu di
tempering terlebih dahulu karena sifatnya yang sangat keras namun getas agar didapatkan sifat
yang kuat, keras dan cukup ulet.
Sampel HST
Foto Struktur Mikro S-50C / AISI 1050 Kelompok 16
Sampel : Baja S-50C / Baja AISI 1050
Etsa : Nital 2%
Page 43 of 67
Martensite
Austenite
Ferrite

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Waktu etsa : 6 detik
Perbesaran : 500x
Keterangan : Austenisasi pada 9000C dengan media pendinginan minyak (oil)
Proses Heat Treatment di Oven (kiri) dan Proses Quenching di Media Minyak (kanan)
Foto Struktur Mikro S-50C / AISI 1050 Literatur
Sampel : Baja AISI 1050
Etsa : Nital 2%
Perbesaran : 500x
Keterangan : Media Pendinginan Minyak
Penjelasan Mengenai Sampel
1. Karakteristik
Baja S-50C merupakan salah satu baja karbon menengah karena memiliki kadar
karbon sekitar 0.48 – 0.55 wt% C. Karena kadar karbonnya yang kurang dari 0.8 wt% C,
maka baja karbon ini tergolong baja hypoeutectoid. Baja ini umumnya digunakan
setelah melalui proses hardening dan tempering. Dengan memvariasikan media quench
Page 44 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
dan temperatur temper-nya, maka akan dihasilkan sifat mekanik yang berbeda-beda
atau bervariasi.
Pada baja S-50C terdapat beberapa unsur paduan yang terkandung dalam
medium carbon steel seperti Mn, P, dan S. Kandungan mangan sebagai elemen paduan
yang terdapat pada medium carbon steel ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan,
sedangkan unsur P dan S merupakan impurities yang juga berfungsi untuk
meningkatkan kekuatan dari baja medium carbon steel ini.
2. Komposisi S-50C
C : 0.48-0.55
Mn : 0.60-0.90
P (max) : 0.04
S (max) : 0.05
3. Sifat Mekanis S-50C
Density : 7.7-8.03 (x 1000 kg/m3)
Poisson’s Ratio : 0.27-0.30
Modulus Elastis : 190-210 GPa
Tensile Strength : 636 Mpa
Yield strength : 365.4 MPa
Elongasi : 23.7%
Reduksi Area : 39.9%
Hardness : 187 HB
Impact Strength : 16.9 J
4. Diagram Fasa
Page 45 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Berdasarkan pengamatan struktur mikro, pada foto sampel HST kelompok 16
terdapat fasa ferrite berwarna putih, austenite sisa berwarna coklat dan martensite
berwarna hijau.
Aplikasi Baja S-50C
Baja S-50C ini memiliki kekerasan tinggi, tahan aus, kekuatan tinggi, machinability
baik, dan tahan terhadap pemakaian yang lama. Aplikasi untuk material ini adalah alat
potong (pisau, pedang), gear, pembuatan injection plastic mould, general machine parts
dan plastic tool.
1.6. Hasil Pengamatan Struktur Makro
Foto Struktur Makro dan Perbandingan dengan Foto Literatur yang Bersesuaian
Foto Struktur Makro Sampel Uji Tarik
Page 46 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Sampel : Kuningan (Cu-Zn)
Perlakuan : Uji Tarik
Perbesaran : 7x
Keterangan : Perpatahan Getas
Foto Struktur Makro Literatur
Page 47 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Analisa Karakteristik Permukaan
Bila dilihat dari foto struktur makronya, sampel merupakan sampel uji tarik dengan
perpatahan getas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penampakan perpatahan granular
atau berbutir-butir yang tampak terang saat dilihat.
Penjelasan Mekanisme yang Dapat Menyebabkan Sifat dan Bentuk Penampakan pada
Sampel Makro
Jenis perpatahan sampel kuningan (Cu-Zn) yang kami dapat merupakan sampel uji
tarik yang menunjukkan adanya perpatahan getas di permukaannya. Hal ini dapat dilihat
pada foto makro bahwa adanya perpatahan granular atau kristalin pada sampel.
Contoh Bentuk Perpatahan Getas Hasil Uji Tarik
Ciri-ciri fenomena perpatahan getas adalah sebagai berikut:
Tidak ada atau sedikit sekali deformasi plastis yang terjadi
Retak atau perpatahan merambat sepanjang bidang kristalin membelah atom
material (transgranular)
Pada material lunak dengan butir kasar (coarse grain) dapat terlihat pola fan like
yang berkembang keluar dan daerah awal kegagalan
Pada material amorphous (glass), permukaan patahan bercahaya dan mulus
Analisa Bahan Material yang Digunakan Sebagai Sampel berdasarkan Sifat-Sifat yang
Terdapat Pada Sampel Makro
Dengan memperhatikan segala karakteristik yang muncul setelah melakukan
pengamatan terhadap permukaan patahan tersebut serta berdasarkan pengamatan fisik
dari sampel pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah sampel
kuningan (Cu-Zn). Sampel tersebut dilakukan pengujian tarik dengan menggunakan Mesin
Page 48 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Shimadzu di Laboratorium Pengujian Merusak. Hal ini juga diperkuat dengan
membandingkan kuningan yang diperiksa struktur makronya disini dengan kuningan yang
pernah dipakai saat Praktikum Uji Tarik (Praktikum Karakterisasi Material I).
Analisa Pemakaian Sampel dan Lingkungannya
Kuningan merupakan salah satu material yang banyak digunakan di masyarakat.
Material ini merupakan material serbaguna yang digunakan karena kekuatannya,
ketahanan korosinya, penampilannya dan kemudahannya untuk digunakan dan
disambung. Contoh aplikasi yang menggunakan kuningan antara lain:
Terali sebagai pengganti besi (Grillwork)
Perhiasan (Jewelry)
Lencana (Badge)
Pegangan Pintu (Door Handle), dan lain-lain.
III.2. Percobaan Jominy
2.1. Data Percobaan
Jenis Baja : AISI 1430
Temperatur Austenisasi : 850oC
Jenis Indentor : Hardened Steel Ball
Diameter Indentor : 3,15 mm
Beban Indentasi : 187,5 kg
Waktu Indentasi : 15 detik
Page 49 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
2.2. Tabel Hasil Penjejakan dan Nilai BHN
NoJarak dari end-
quench (mm)
Diameter Penjejakan (mm)BHN
Dx (mm) Dy (mm) Davg (mm)
1 6 0.545 0.558 0.552 768.92
2 12 0.943 0.964 0.954 256.55
3 18 1.009 0.974 0.992 236.78
4 24 1.015 0.978 0.997 234.36
5 30 1.019 1.018 1.019 223.84
6 36 1.071 1.024 1.048 211.28
7 42 1.073 1.070 1.072 201.64
8 48 1.089 1.083 1.086 196.31
9 54 1.119 1.136 1.128 181.47
10 60 1.133 1.156 1.145 175.96
11 66 1.156 1.160 1.158 171.88
12 72 1.159 1.160 1.160 171.27
13 78 1.159 1.158 1.159 171.58
14 84 1.158 1.174 1.166 169.44
15 90 1.174 1.180 1.177 166.17
Contoh perhitungan:
P = 3.15 mm, D = 187.5 kg
BHN= 2 P
(πD )(D−√D 2−d2)
BHN= 2×187.5
(π ×3.15 ) (3.15−√3.152−1.1772 ) =166.17 BHN
Page 50 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
2.3. Grafik Hardenability
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
100200300400500600700800900
Grafik Hardenability
Jarak dari Sumber Air (mm)
Keke
rasa
n (B
HN)
2.4. Pembahasan Hasil
Analisa Penyebab Perbedaan Kekerasan Dihubungkan dengan Transformasi Fasa yang
Terjadi di Setiap Daerah atau Perbedaan Jarak dari Titik Quench
Percobaan jominy memanfaatkan perbedaan kecepatan pendinginan dari sampel.
Bagian yang paling dekat dengan air adalah yang paling cepat pendinginannya. Semakin
jauh dari air, semakin lama laju pendinginannya. Sesuai dengan diagram TTT, dari bagian
yang cepat pendinginannya sampai bagian terlama, mikrostrukturnya akan
bertransformasi membentuk full martensite; martensite, bainite; martensite, ferit, bainite;
full bainite; bainite ferit. Mikrostruktur tersebut berhubungan dengan kekerasan dimana
semakin banyak martensitenya, maka makin keras dan sebaliknya seperti pada grafik
berikut
Page 51 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Kurva distribusi nilai kekerasan terhadap jarak dari Quench End
Prinsip Percobaan Jominy berkaitan dengn Temperatur dan Waktu Tahan yang
Dihubungkan dengan Kemampukerasan Material
Percobaan Jominy memanfaatkan prinsip kecepatan pembekuan dalam mengukur
kemampukerasan logam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampukerasan adalah
komposisi, ukuran butir austenit dan mikrostruktur sebelum quenching. Jika kita kaikan
dengan waktu tahan dan temperatur, maka akan berkaitan dengan ukuran butir austenit
dan mikrostruktur sebelum quenching. Saat austenisasi jika temperatur besar, maka
terjadi pertumbuhan butir sehingga butir-butir austenit menjadi besar dan ketika di
quench martensite yang terbentuk menjadi lebih banyak. Itu artinya hardenability
meningkat. Begitu pula jika waktu tahan besar, difusi karbon ke austenit menjadi lebih
banyak sehingga didapatkan austenit yang sempurna. Jika dilakukan quenching, maka
martensite yang terbentuk juga sempurna sehingga hardenability meningkat.
Page 52 of 67
TEM
PERA
TUR
( °C)
18 Kekerasan
setelah kuens (Rockwell C)
18 42 56 63-65
60-62 57-58
a
e
d
c
b
f 7
50
850
950
Waktu tahan yang
benar

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Kesesuaian Hasil Percobaan dengan Grafik Jominy dari Literatur, serta Variabel-Variabel
yang Berpengaruh pada Percobaan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
200400600800
1000
Grafik Hardenability
Jarak dari Sumber Air (mm)
Keke
rasa
n (B
HN)
Bila dibandingkan dengan kurva Jominy praktikan, secara umum sudah benar, yaitu
semakin jauh dari sumber air, kekerasan akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan laju
pendinginan dekat sumber air berlangsung cepat sehingga pembentukan fasa
martensitenya semakin banyak dan memiliki kekuatan paling tinggi. Namun pada kurva
Jominy praktikan, apabila dilihat secara detail menghasilkan nilai-nilai kekerasan yang
fluktuatif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh:
Pengamplasan yang kurang bersih, masih terdapat oksida-oksida pada
permukaan dimana nilai kekerasannya akan menjadi lebih besar. Karena saat
uji kekerasan yang terkena beban Brinnel adalah oksidanya bukan materialnya.
Pengukuran jejak pada measuring microscope yang kurang tepat. Hal ini karena
bentuk jejaknya tidak tepat seperti lingkaran mulus, sehingga penentuan ujung-
ujung lingkarannya hanya berdasarkan perkiraan yang menyebabkan nilai
kekerasannya menjadi kurang akurat.
Adanya coretan bekas spidol yang digunakan untuk menandai daerah
penjejakan yang menghalangi proses pengamatan pada measuring microscope.
Page 53 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Alat Measuring Microscope
Pada saat penjejakan, waktu yang digunakan tidak tepat 15 detik untuk semua
posisi penjejakan (ada yang kelebihan, ada yang kekurangan).
Aplikasi Percobaan Jominy
Aplikasi dari percobaan Jominy bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam
kekerasan yang dicapai sehingga diperoleh hubungan antara jarak permukaan pada
pendinginan langsung dengan sifat kemampukerasan bahan dan hubungan antara
kecepatan pendinginan dengan fasa yang terbentuk serta mendapatkan sifat kekerasan
dari fasa tersebut. Dasar grafik Jominy yaitu kurva CCT yang dapat menjelaskan
kemampukerasan bahan dari suatu pendinginan dengan media pendingin tertentu
sehingga dapat diketahui fasa apa saja yang terbentuk. Laju pendinginan juga berpengaruh
dalam kemampukerasan baja. Semakin cepat laju pendinginan maka semakin mudah
mendapatkan fasa martensit.
Jadi, percobaan Jominy ini dapat dijadikan sebagai dasar penentuan
kemampukerasan baja terhadap laju pendinginan dan media pendinginan yang berbeda.
Selain itu, dapat diketahui fasa-fasa apa saja yang terbentuk dan nilai kekerasan yang
diperoleh.
Page 54 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Page 55 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
III.3. Pengujian HST
3.1. Data Percobaan
Kelompok 16
Jenis sampel : S-50C (AISI 1050)
Temperatur austenisasi : 900oC
Waktu tahan : 25 menit
Media quench : Oil
Waktu quench : -
Jenis indentor : Hardened Steel Ball
Diameter indentor : 3.15 mm
Beban indentasi : 187.5 kg
Waktu indentasi : 15 detik
Kelompok 15
Jenis sampel : S-50C (AISI 1050)
Temperatur austenisasi : 900oC
Waktu tahan : 10 menit
Media quench : Oil
Waktu quench : -
Jenis indentor : Hardened Steel Ball
Diameter indentor : 3,15 mm
Beban indentasi : 187,5 kg
Waktu indentasi : 15 detik
3.2. Tabel Hasil Pengujian Kekerasan
Kelompok 16
No. d1(mm) d2(mm) drata-rata(mm) BHN BHNrata-rata
1 0.965 0.976 0.971 247.33243.472 0.989 0.976 0.983 241.16
3 0.993 0.969 0.981 241.92
Page 56 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Contoh perhitungan :
BHN= 2 P
(πD )(D−√D 2−d2)
BHN= 2×187.5
(π ×3.15 ) (3.15−√3.152−0.9832 ) = 241.16 BHN
Kelompok 15
No. d1(mm) d2(mm) drata-rata(mm) BHN BHNrata-rata
1 0.963 0.975 0.969 248.21
240.702 1.001 1.010 1.006 230.073 0.977 0.978 0.978 243.55
Contoh perhitungan :
BHN= 2 P
(πD )(D−√D 2−d2)
BHN= 2×187.5
(π ×3.15 ) (3.15−√3.152−1.0062 ) = 230.07 BHN
Perbandingan Foto Mikrostruktur Kelompok 16 dan 15
Kelompok 16
Kelompok 15
Page 57 of 67

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
3.3. Pembahasan Hasil
Penyebab Perbedaan Kekerasan
Nilai kekerasan yang diperoleh dari tiga daerah yang dilakukan penjejakan adalah
berbeda-beda. Terdapat daerah yang lebih lunak dan lebih keras. Hal ini dapat disebabkan
oleh:
Pengamplasan yang kurang bersih, masih terdapat oksida-oksida pada permukaan
dimana nilai kekerasannya akan menjadi lebih besar. Karena saat uji kekerasan yang
terkena beban brinnel adalah oksidanya bukan materialnya.
Pengukuran jejak pada measuring microscope yang kurang tepat. Hal ini karena bentuk
jejaknya tidak tepat seperti lingkaran mulus, sehingga penentuan ujung-ujung
lingkarannya hanya berdasarkan perkiraan yang menyebabkan nilai kekerasannya
menjadi kurang akurat.
Waktu indentasi yang tidak tepat sama, kadang suka terlebih atau kekurangan
beberapa detik.
Pada percobaan dilakukan perbandingan nilai kekerasan suatu material yang sama dan
media pendinginan yang juga sama (minyak / oil) antara Kelompok 16 dan Kelompok 15. Nilai
kekerasan yang dihasilkan pun tidak jauh berbeda antara Kelompok 16 (243.47 BHN) dan
Kelompok 15 (240.70 BHN). Nilai kekerasan yang diperoleh oleh Kelompok 16 sedikit lebih
besar dibandingkan nilai kekerasan Kelompok 15. Jika dilihat lebih detail lagi, terdapat
perbedaan variable antara praktikum yang dilakukan oleh Kelompok 16 dan Kelompok 15.
Variabelnya adalah waktu tahan yang dilakukan pada suhu austenisasi baja S-50C, yaitu 25
menit untuk Kelompok 16 dan 10 menit untuk Kelompok 15.
Waktu tahan diberikan dalam suatu proses perlakuan panas dengan tujuan
memberikan pada unsur-unsur suatu bahan untuk melakukan difusi. Dengan pemberian
waktu tahan diharapkan karbon dapat larut dalam austenit dan austenit menjadi lebih
homogen. Jadi waktu tahan yang lebih lama akan memberikan kekerasan yang tinggi.
Analisa Variabel-Variabel yang Berpengaruh pada Percobaan
Kecepatan Pendinginan
Media quenching akan sangat mempengaruhi tingkat kekerasan yang didapatkan.
Media quenching akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pendinginan terhadap
material tersebut, dimana kecepatan pendinginan akan mempengaruhi struktur apa
yang terbentuk pada material tersebut. Berikut adalah skema singkat perbandingan
media quenching terhadap waktu pendinginan.

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Terlihat bahwa air memiliki waktu pendinginan yang paling singkat, yang berarti
bahwa air memiliki kecepatan pendinginan yang paling tinggi. Sedangkan minyak berada
di posisi berikutnya, yang berarti kecpatan pendinginan tidak secepat pendinginan
dengan air.
Kecepatan pendinginan mempengaruhi fasa yang akan terbentuk dan tingkat
kekerasan dari suatu material. Dapat dilihat dari diagram CCT di bawah, ditunjukkan
bahwa pendinginan dengan media air akan menghasilkan martensit lebih cepat karena
laju pendinginannya lebih cepat dibandingkan dengan media minyak ataupun udara. Hal
ini tidak terlalu terlihat untuk percobaan yang kelompok kami lakukan dengan kelompok
pembanding (Kelompok 15) karena sama-sama menggunakan media pendingin yang
sama, yaitu minyak / oil.
Diagram CCT (Continous Cooling Transformation)
Water
TimeTem
pera
ture
, C950
0Skema pendinginan berbagai media
OilFB2 bar over pressure quenching
Air

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Temperatur Austenisasi
Temperatur austenisasi akan mempengaruhi pertumbuhan butir dari suatu
material. Jika temperatur austenitnya tinggi, maka akan didapatkan butir austenit yang
besar. Sedangkan bila temperatur austenitnya rendah maka akan didapatkan butir yang
kecil. Pengaruh temperatur austenit tidak hanya pada pertumbuhan butir tetapi juga
pada nilai kekerasan. Tingginya temperatur austenisasi akan menghasilkan kekerasan
yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan dengan tingginya temperatur autenisasi akan
membantu terlarutnya karbon dalam austenit yang akan bertransformasi menjadi
martensit karena kadar karbon yang terperangkap dalam struktur kristal lebih banyak.
Sedangkan dengan temperatur yang lebih rendah, tidak akan menghasilkan kekerasan
yang maksimum. Hal ini disebabkan kadar karbon yang terlarut belum banyak selain itu
kemungkinan dapat terjadi belum tercapainya daerah austenisasi. Sehingga masih
terdapat ferrit yang akan tetap berupa ferrit pada temperatur kamar.
Waktu Tahan Austenisasi
Waktu tahan diberikan dalam suatu proses perlakuan panas dengan tujuan
memberikan pada unsur-unsur suatu bahan untuk melakukan difusi. Dengan pemberian
waktu tahan diharapkan karbon dapat larut dalam austenit dan austenit menjadi lebih
homogen. Jadi waktu tahan yang lebih lama akan memberikan kekerasan yang tinggi.
Pengaruh Waktu Tahan & Temperatur terhadap Kekerasan Hasil Quench yang Diperoleh
Temperatur austenisasi Kelompok 16 dan 15 tidak berbeda dan sama-sama
berada pada daerah austenit, namun waktu tahan temperatur austenitnya lebih lama
pada kelompok 16 (25 menit). Bila dilihat pada grafik di atas, waktu tahan yang benar
untuk proses ini sekitar 56-63 menit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan waktu

9000C
5400C
T(0C)
T0
T1
T2
t (menit)25 menit51 menit
Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
tahan austenisasi yang dilakukan ini berakibata pada nilai kekerasan yang diperoleh dan
dibuktikan dengan percobaan ini dimana Kelompok 16 dengan waktu tahan lebih lama
(25 menit) memiliki nilai kekerasan yang lebih besar dibandingkan nilai kekerasan
Kelompok 15 yang hanya ditahan selama 10 menit di fasa austenite.
Pengaruh Temperatur dan Waktu Tahan Temper
Proses tempering merupakan suatu proses untuk melunakkan baja yang telah
dikeraskan dengan maksud mendapatkan sifat ketangguhan dengan mengorbankan sifat
kekerasannya. Hal ini dilakukan dengan cara memanaskan kembali material yang telah
didinginkan yang bertujuan agar karbon yang terperangkap dapat berdifusi. Banyaknya
karbon yang berdifusi tergantung pada temperatur tempernya dan waktu tahan temper.
Semakin tinggi temperaturnya dan semakin lama waktu tahan, maka semakin banyak karbon
yang berdifusi sehingga kekerasannya semakin rendah dan keuletan meningkat.
Diagram Perlakuan Panas Sampel HST S-50C Kelompok 16

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
BAB IV
TUGAS TAMBAHAN
1. Sebutkan jenis-jenis cacat saat preparasi sampel!
a. Cacat-cacat yang umumnya terjadi pada sampel castable mounting antara lain:
Cracking: retaknya media mounting, disebabkan oleh terlalu banyaknya hardener dan
temperatur yang terlalu tinggi.
Bubbles: terdapat gelembung gas pada media mounting, disebabkan karena pengadukan
yang terlalu kasar atau cepat saat pencampuran resin dan hardener, sehingga ada udara
yang terperangkap di dalam campuran tersebut. Pencegahannya adalah mengaduk secara
perlahan campuran resin dan hardener.
Discoloration: pengotoran, perubahan warna, dan perusakan warna, yang terjadi karena
rasio resin dan hardener tidak seimbang, dan hardener teroksidasi.
Soft mounts: media mounting terlalu lunak, perbandingan resin dan hardener tidak
seimbang, dan juga hardener terlalu sedikit.
Tacky tops: Permukaan mounting tidak rata, disebabkan oleh tidak ratanya permukaan
cetakan saat dituang atau karena perbandingan resin dan hardener yang kurang tepat. Cara
pencegahannya adalah dengan benar-benar meratakan permukaan isolasi yang akan
dituang resin dan memperhitungkan perbandingan resin dan hardener.
Unfused: retakan di sekeliling sampel, disebabkan oleh tegangan permukaan dan tekanan
yang berlebihan.
b. Cacat pada proses pemolesan:
Cacat Ekor Komet: cacat berupa goresan melingkar pada
pemukaan sampel. Hal ini dapat terjadi akibat
penumpukan alumina pada celah-celah mikro di sampel
ketika pemolesan dilakukan secara statik. Ketika
pemolesan dilakukan static, terdapat kemungkinan
adanya partikel-partikel alumina yang terperangkap di
dalam celah-celah mikro ,seperti goresan yang dapat saja
terbentuk pada saat pengamplasan, dan membentuk
suatu garis putih layaknya sebuah ekor komet. Apabila
menggunakan teknik poles satu arah, bubuk alumina akan
berkumpul dan tertahan pada satu bagian sampel. Dan lama kelamaan bubuk alumina akan
menimbulkan goresan pada sampel dan terbentuklah ekor komet. Untuk mengatasinya,
maka ketika proses pemolesan berlangsung, sampel harus terus menerus diputar.

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
c. Cacat pada proses etsa:
Cacat Hangus: cacat berupa hangusnya (gosong) permukaan sampel akibat terlalu lamanya
proses etsa berlangsung.
Cacat Micropitting: cacat berupa terbentuknya sumuran-sumuran kecil pada saat
pengamatan struktur mikro akibat pengetsaan terlalu lama.
2. Berikan gambar mikrostruktur yang memiliki pearlite band hasil dari pengerolan!
Gambar mikrostruktur baja paduan rendah yang menunjukkan adanya butir ferrite dan pita pearlite dengan
menggunakan etsa picral 4% dan nital 2% dan perbesaran 200x
3. Mengapa pearlite band harus dihilangkan?
Pearlite band atau juga sering disebut sebagai ferrite-pearlite band merupakan suatu
distribusi tidak homogen dari susunan ferrite dan pearlite sebagai filament atau pelat yang sejajar
dengan arah pengerjaannya (biasanya pengerolan). Pearlite band ini tidak diinginkan dalam
produk hasil pengerolan karena perbedaan distribusi ferrite dan pearlite tersebut dapat
mengakibatkan menurunnya sifat mekanis. Hal ini disebabkan karena sifat ferrite yang ulet
terpisah dengan sifat sementit yang getas sehingga ada perbedaan distribusi kekuatan pada
produk.
4. Berikan perbandingan mikrostruktur sebelum dan sesudah pengerolan yang memiliki pearlite
band!

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Mikrostruktur Baja Paduan Rendah Sebelum Pengerolan (kiri) dan Sesudah Pengerolan (kanan)
5. Bagaimana cara mendapatkan foto HSLA dengan fasa austenite?
HSLA dimanufaktur melalui proses Thermo Mechanical Control, dimana ia dilakukan canai panas
dan langsung di anil normalisasi dan didinginkan agak cepat. Setelah didinginkan agak cepat
terdapat fasa asutenite yang belum bertransformasi. Oleh karena itu kita amati mirostruktur HSLA
setelah pendinginan untuk menlihat fasa austenit.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.I. Kesimpulan
Mounting
Mounting bertujuan untuk menempatkan sampel pada suatu media agar memudahkan
penanganan sampel yang berukuran kecil dan tidak beraturan.
Terdapat dua metode mounting yaitu castable mounting dan compression mounting.
Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah castable mounting karena lebih mudah
dan alat yang digunakan lebih sederhana.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses mounting yaitu
perbandingan resin dan hardener, proses pengadukan, ketebalan resin dan pemasangan
perekat pada cetakan.
Terdapat beberapa cacat hasil mounting pada sampel, antara lain terdapat gelembung-
gelembung dan permukaan mounting tidak rata.

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Pengamplasan
Pengamplasan bertujuan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan sampel dengan
cara menngosokan sampel dangan kertas amplas.
Pengamplasan dilakukan dari grid yang rendah (kasar) ke grid yang tinggi (halus). Hal ini
untuk menghilangkan goresan-goresan yang terbentuk sebelumnya.
Setiap pergantian grid selalu diikuti dengan pergantian arah pengamplasan sebesar 45o atau
90o.
Pada saat pengamplasan harus dilakukan pemberian air secara kontinyu karena air
berfungsi untuk pemindah geram, memperkecil kerusakan akibat dan memperpanjang
masa pemakaian kertas amplas.
Pengamplasan sampel ferrous dan non ferrous yang dilakukan bersamaan harus
diperhatikan. Sampel ferrous diletakkan di bagian luar sedangkan sampel non ferrous
diletakkan di bagian agak dalam, hal ini agar geram hasil amplas ferrous tidak merusak
permukaan sampel non ferrous.
Terdapat cacat hasil amplas seperti cacat bidang.
Pemolesan
Pemolesan bertujuan untuk untuk mendapatkan permukaan sampel yang halus dan
mengkilap seperti kaca.
Pemolesan ada tiga macam, yaitu pemolesan kimia mekanis, pemolesan elektrolit kimia dan
pemolesan elektromekanis.
Pada saat pemolesan, sampel harus diputar-putar untuk menghindari cacat ekor komet.
Jenis zat poles yang digunakan pada percobaan ini adalah cairan alumina.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pemolesan adalah tekanan poles, pemutaran sampel,
pemberian air dan zat poles.
Etsa
Etsa adalah suatu proses penyerangan atau pengikisan batas butir yang selektif dan
terkendali dengan pencelupan ke larutan pengetsa baik menggunakan listrik maupun tidak
ke permukaan sampel sehingga detil struktur yang akan diamati akan terlihat jelas dan
tajam.
Dua proses etsa yang dipakai ialah etsa kimia dan elektroetsa.
Pada etsa kimia, untuk melihat struktur baja menggunakan zat nital, Al dengan zat HF, dan
paduan tembaga dengan zat FeCl3.
Variabel etsa yang penting untuk proses etsa kimia adalah pemilihan zat etsa, waktu
pengetsaan, dan pemberian alkohol.

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Pengamatan Struktur Mikro dan Makro
Tujuan dari pengamatan mikro adalah mengetahui pengambilan foto mikrostruktur,
menganalisa struktu mikro dan sifat-sifatnya, dan mengenali fasa-fasa yang terdapat dalam
struktur mikro.
Tujuan dari pengamatan struktur makro adalah mengetahui jenis perpatahan dari sampel.
Sebelum dilakukan pengamatan, sampel untuk pengamatan struktur mikro harus dilakukan
persiapan sampel dengan baik, agar hasilnya dapat dilihat dengan jelas dan tajam serta
dapat dibandingkan dengan literatur yang ada.
Sampel pengamatan struktur makro pada percobaan ini adalah sampel hasiil uji tarik
dengan jenis perpatahan getas.
Hal yang penting pada saat pengamatan struktur adalah pencahayaan, fokus, dan
perbesaran yang tepat agar dapat terlihat ada fasa, karbida, presipitat dan komponen apa
saja pada sampel pengamatan struktur mikro dan patahan apa yang terjadi pada sampel
pengamatan struktur makro.
Percobaan Jominy
Percobaan Jominy bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh material tersebut berfasa
martensit, memprediksi seberapa dalam kekerasan yang dicapai, membandingkan
kekerasan suatu material dengan standardnya.
Dengan kurva Jominy dapat diketahui hubungan antara kecepatan pendinginan dengan fasa
yang terbentuk serta mendapatkan sifat kekerasannya.
Semakin dekat dengan sumber air, maka sifat kekerasannya makin tinggi, karena laju
pendinginannya semakin cepat sehingga martensit lebih mudah terbentuk.
Nilai kekerasan untuk percobaan Jominy dilakukan dengan metode Brinell.
Semakin landai grafik kekerasan dan jarak end-quench, menunjukan bahwa
kemampukerasan material akan semakin baik.
Pengujian HST
Perlakuan panas merupakan proses kombinasi pemanasan dan pendinginan yang bertujuan
mengubah struktur mikro dan sifat mekanis logam.
Laju pendinginan suatu proses ditentukan oleh media pendinginnya, dapat berupa air,
minyak, udara, dan lain-lain.
Laju pendinginan yang berbeda akan menghasilkan fasa yang berbeda. Masing - masing fasa
tersebut terjadi dengan kondisi pendinginan yang berbeda-beda dimana untuk setiap
paduan bahan dapat dilihat pada diagram CCT dan TTT. Dan masing-masing fasa memiliki
nilai kekerasan yang berbeda.

Laporan Akhir Praktikum Karakterisasi Material 2 Mohammad Fadli 0806331771
Pada percobaan ini, dilakukan perlakuan panas dengan media pendinginnya minyak (oil).
V.2. Saran
Praktikan diberi kesempatan untuk melakukan proses mounting untuk lebih memahami
dan mengerti proses mounting itu tersebut.
Jumlah mesin amplas otomatis ditambah serta diadakan perbaikan terhadap sistem
saluran air di mesin tersebut agar memudahkan praktikan.
Praktikan diberikan kesempatan untuk belajar mengoperasikan atau mensetting
mikroskop agar gambar yang dihasilkan bagus.
Pengamatan struktur mikro dilakukan lebih lanjut dengan menggunakan SEM.
6. Daftar Pustaka
ASM Handbook Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
ASM Handbook Volume 3: Alloy Phase Diagrams
ASM Handbook Volume 4: Heat Treating
ASM Handbook Volume 9: Metallography and Microstructures
Ariati MS, Dr. Ir. Myrna. Bahan Kuliah (slide) Heat Treatment & Surface Engineering. 2010. Depok:
DTMM FT UI
Callister, William. Material Science and Engineering An Introduction Seventh Edition. 2007. New
York: Wiley
Lab Metalografi & HST. Modul Praktikum Karakterisasi Material 2. 2011. Depok: DTMM FT UI
Voort, G.F Van der. Atlas of Time Temperature Diagrams for Irons &Steel. 1991. ASM International