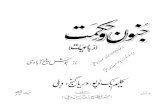Kontribusi Jasa Lingkungan Hutan Konservasi by Hikmat Ramdan
-
Upload
hikmat-ramdan -
Category
Documents
-
view
288 -
download
1
Transcript of Kontribusi Jasa Lingkungan Hutan Konservasi by Hikmat Ramdan
KONTRIBUSI DAN KERJASAMA PARA PIHAK DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DI HUTAN KONSERVASI1olehDr. Ir.HIKMAT RAMDAN Pendahuluan Hutan menyediakan beragam jasa dan barang, baik berupa manfaat tangible maupun manfaat intangible yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan perlindungan ekologis. Kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan merupakan barang dan jasa ekosistem hutan yang keberadaan nilai manfaatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, misalnya apabila tegakan hutan rusak, maka jasa lingkungan pun akan rusak atau hilang pula. Keunikan karakter hutan ini mengharuskan hutan dikelola secara komprehensif, sistemik, interdisiplin, dan berkelanjutan. Hutan konservasi sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, memiliki sejumlah jasa lingkungan (environmental services) seperti jasa lingkungan air, penyimpanan karbon (carbon stock), wisata alam, serta biodiversitas flora dan fauna. Jasa lingkungan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara terus menerus, walaupun masih banyak pengguna jasa lingkungan (environmental services users) hutan konservasi yang tidak menyadari dan mengapresiasi kontribusi jasa lingkungan hutan konservasi yang dinikmati dan digunakannya tersebut. Jasa lingkungan hutan yang belum diapresiasi dengan baik telah menyebabkan meningkatnya laju degradasi ekosistem hutan, padahal makin tinggi laju degradasi ekosistem hutan maka nilai jasa lingkungan pun makin menurun. Dalam hal ini jasa lingkungan dapat dianggap sebagai output dari kualitas kinerja ekosistem hutan (Ramdan et.al.,2003; Ramdan, 2004; Verweij, 2002). Salah satu jasa lingkungan terpenting hutan konservasi adalah air. Acreman (2004) menyatakan bahwa sebatang pohon di hutan alam sepanjang daur hidupnya mampu memompa air +2,5 juta galon air ke atmosfer, didaur-ulang, dan tidak hilang dari kawasan hutan. Air merupakan jasa lingkungan hutan yang merupakan output hidrologis (H) hutan konservasi yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan tidak bisa disubstitusi dengan sumberdaya lainnya. Air sebagai hydrological output mungkin masuk secara langsung ke dalam kegunaan individu (seperti air konsumsi dan keperluan rumah tangga), mungkin menjadi input ke dalam produksi kegunaan rumah tangga (household production of utility) dalam menghasilkan barang dan jasa, dan atau mungkin menjadi suatu faktor 1
Makalah Utama disampaikan pada Workshop Kontribusi Dan Kerjasama Para Pihak Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Kawasan Hutan Konservasi, Balai Besar Ksda Jawa Barat Tahun 2010. Bandung, 28 Juli 2010.
1
input dalam produksi barang yang dipasarkan (seperti pembangkit tenaga listrik). Aliran air yang mengalir dari ekosistem hutan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi dan ekonomi, walaupun banyak pihak pengguna air (water users) tidak menyadari atau mempertimbangkannya. Misalnya di dalam analisis usahatani sering tidak memasukan sumberdaya air sebagai bagian dari input produksi tani, padahal tanpa pasokan air yang memadai tidak mungkin panen terjadi. Kondisi yang hampir sama terjadi di dalam kegiatan industri dan ekonomi lainnya dimana air dinilai sangat rendah (mendekati nol) karena dianggap sebagai barang publik dengan akses terbuka (open access). Perubahan paradigma didalam pemanfaatan hutan yang berbasis sumberdaya hutan (forest resources based management) saat ini telah membuka peluang bagi pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang selama ini masih terabaikan. Jasa lingkungan (environmental services) dapat dinyatakan sebagai output ekosistem yang dihasilkan dari interaksi komponen penyusun ekosistem hutan dengan komponen non hayati lainnya yang berjalan secara sinergis. Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan konservasi dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian, efisiensi dan keadilan. Prinsip kelestarian menekankan bahwa pemanfaatan harus dapat mendorong terwujudnya kelestarian lingkungan. Prinsip efisiensi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan memperhitungkan nilai jasa lingkungan dalam kegiatan ekonomi melalui pembayaran jasa lingkungan. Sedangkan prinsip keadilan dilakukan untuk terjadinya distribusi manfaat dan biaya pemanfaatan jasa lingkungan secara adil, melalui penerapan sistem imbal jasa dari penerima manfaat kepada penyedia jasa lingkungan dan juga dari pencemar kepada penyedia jasa lingkungan. Kontribusi Hutan Konservasi Kontribusi nilai manfaat hutan konservasi terhadap kehidupan masyarakat sesungguhnya sangatlah beragam, tetapi dalam tulisan ini kontribusi hutan konservasi dibatasi pada jasa lingkungan air, khususnya di Cagar Alam/TWA Kamojang, Guntur, dan Tampomas yang kajiannya dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Desember 2008. Selain itu untuk memberikan gambaran tentang penerapan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan mengambil hasil riset Ramdan (2006) di wilayah Gunung Ciremai. Kontribusi hidrologis Cagar Alam/TWA Papandayan, TWA Guntur, dan TWA Tampomas dideskripsikan berikut ini.
Sebaran Kontribusi Jasa Lingkungan Hidrologis Cagar Alam/TWA Kamojang dan TWA GunturSumber-sumber mata air di Kawasan TWA Gunung Guntur dan TWA/CA Kamojang memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan air terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan dan umumnya bagi masyarakat yang berada di luar kawasan. Situ Cibeureum merupakan salah satu sumber mata air yang berbatasan langsung dengan
2
Kawasan TWA Kamojang. Secara geografis situ ini berada pada koordinat 7 9 42.6 LS dan 107 48 23.8 BT. Resapan air yang keluar di Situ Cibeureum berada di kawasan TWA Kamojang. Debit rata-rata air dari Situ Cibeureum berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan alat current meter adalah 1,85 m3/detik dengan suhu 24 C dan nilai TDS sebagai salah satu indikator kualitas air sebesar 52 ppm. Di dalam kawasan Cagar Alam Kamojang terdapat salah satu sumber mata air Danau Ciharus. Danau ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, yang secara geografis terletak pada koordinat 7 9 45,2 LS dan 107 45 7,2 BT. Danau Ciharus memiliki debit rata-rata sebesar 16,50 m3/detik dengan nilai TDS 58 ppm dan suhu 24 C. Salah satu sumber mata air yang berada di TWA Gunung Guntur adalah Curug Citiis. Sumber mata air ini secara geografis berada pada koordinat 7 9 26.2 LS dan 107 51 58.1 BT. Hasil pegukuran di lapangan menunjukkan potensi sumberdaya air Curug Citiis memiliki debit rata-rata sebesar 2,33 m3/detik. Hasil analisis spasial TWA Gunung Guntur dan Kawasan TWA/CA Kamojang menunjukkan sebaran luas areal kontribusi sumber mata air dari Kawasan TWA/CA Kamojang seluas 33.997,189 Ha. Luasan tersebut tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung seluas 14.359,511 Ha dan Kabupaten Garut seluas 19.637,678 Ha. Areal kontribusi sumber mata air dari kawasan tersebut meliputi 6 (enam) kecamatan dan 44 (empat puluh empat) desa dengan jumlah penduduk sebanyak 389.296 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 95.595 KK yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, serta 9 (sembilan) kecamatan dan 67 (enam puluh tujuh) desa dengan jumlah penduduk 379.164 jiwa terdiri dari 85.498 KK yang berada di wilayah administratif Kabupaten Garut. Hasil analisis spasial sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan TWA/CA Kamojang dan TWA Gunung Guntur secara signifikan memberikan kontribusi yang besar untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun sejauh ini apresiasi dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya konservasi kedua kawasan tersebut sebagai resapan dari sumber airnya masih rendah, sehingga upaya untuk membangun kepedulian dan apresiasi nilai konservasi resapan airnya menjadi sangat penting dilakukan. Masyarakat pengguna air perlu dibangun rasa tanggung-jawabnya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya konservasi kawasannya, sehingga kesinambungan pasokan air dengan kualitas yang memadai dapat terjamin. Prinsip pengguna manfaat jasa lingkungan perlu memberikan kontribusinya (users must pay) dapat diterapkan untuk membangun kesamaan tanggung-jawab antara pengguna dan pengelola kawasan, karena selama ini pengelola kawasan sebagai provider jasa lingkungan air dituntut untuk bertanggung-jawab atas upaya konservasi tetapi pengguna air hampir sama sekali tidak peduli akan kelestarian resapannya. Padahal apabila ekosistem hutan yang selama ini menjadi resapan airnya terdegradasi, maka sistem tata
3
air wilayah tersebut akan terganggu pula. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pengelola kawasan, terutama keterbatasan sarana dan dana konservasi dibandingkan dengan luasnya areal yang harus dipertahankan sebagai resapan airnya pada akhirnya akan menuntut pengguna air untuk bersedia memberikan kontribusinya.10740'00" 10744'00" 10748'00" 10752'00"
74'00"
74'00"
MAJALAYA CIKANCUNG
PASEH
KADUNGORA
78'00"
IBUN
LELES
78'00"
LEUWIGOONG PACET
# Sumber AirCiharus
#
Sumber Air Cibeureum
Citiis #Sumber AirBANYURESMI
SAMARANG KERTASARI712'0 0"
TAROGONG712'00"
PASIRWANGI
KARANGPAWITAN
10740'00"
10744'00"
10748'00"
10752'00"
Gambar 1 Wilayah Kontribusi Aliran Air TWA/CA Kamojang dan TWA Gunung Guntur
Sebaran Kontribusi Jasa Lingkungan HidrologisTWA TampomasKawasan TWA Tampomas di bagian puncaknya merupakan wilayah dengan air tanah langka atau tidak berarti, sementara sesudahnya merupakan akuifer produktif dengan sebaran mulai setempat sampai luas. Hasil survey dan pengukuran lapangan pada beberapa lokasi sumber mata air menunjukkan potensi debit air yang paling tinggi terdapat pada sumber mata air Cikandung dengan rata-rata debit sebesar 14.40 m3/detik. Sumber mata air ini secara geofrafis terletak pada koordinat 6 47 27.6 LS dan 107 55 26.5 BT. Potensi debit air pada sumber mata air Narimang, Cigirang, Padayungan, dan Ciemutan adalah 9.47, 1.41, 9.49, dan 3.50 m3/detik dengan total estimasi debit mencapai 38,27 m3/detik atau 3.306.528 m3/hari. Sumber-sumber mata air yang berada di dalam dan sekitar Kawasan TWA Tampomas memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan 4
air bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Hasil analisis spasial pada Kawasan TWA Tampomas menunjukkan sebaran luas areal kontribusi dari sumber mata air di Kawasan TWA Tampomas meliputi 113 (seratus tiga belas) desa di 15 (lima belas) kecamatan yang secara administratif seluruhnya berada di Kabupaten Sumedang. Luas areal kontribusi sumber mata air dari Kawsan TWA Tampomas adalah 49.402 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 394.195 jiwa. Areal kontribusi dari sumber mata air di Kawasan TWA Tampomas paling luas bagi wilayah di Kecamatan Buahdua dengan luas 10.018,437 Ha atau 20,28% dari total luas areal kontribusi sumber mata air. Jumlah penduduk di kecamatan ini berdasarkan data BPS 2006 adalah sebanyak 31.552 jiwa. Areal kontribusi dari sumber mata air di Kawasan TWA Tampomas dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Sumedang Selatan sebanyak 57.860 jiwa dengan luas areal kontribusi 3.862,5 Ha (7,82%).10750'00" 10752'00" 10754'00" 10756'00" 10758'00" 10800'00" 1082'00" 1084'00"
640'00"
640'00"
SURIAN
BUAHDUA642'00" 642'00"
CONGGEANG
TANJUNG MEDAR
644'00"
644'00"
646'00"
TANJUNGKERTA
646'00"
CIMALAKA648'00"
RANCAKALONG648'00"
PASEH
SITURAJA
650'00"
650'00"
SUMEDANG UTARA
CISARUA
652'00"
652'00"
GANEAS
SUMEDANG SELATAN10750'00" 10752'00" 10754'00" 10756'00" 10758'00" 10800'00" 1082'00" 1084'00"
Gambar 2 Wilayah Kontribusi Aliran Air TWA Tampomas
Estimasi Nilai Kontribusi Hutan KonservasiMasyarakat pengguna jasa lingkungan air sebenarnya telah menyadari pentingnya upaya konservasi resapan air, khususnya di TWA/CA yang dikaji. Masyarakat pun bersedia untuk memberikan kontribusinya berupa Dana Kompensasi Konservasi (DKK) untuk membantu
5
kegiatan konservasi daerah resapan airnya yang berada di hutan konservasi tersebut. Nilai DKK identik dengan nilai WTP (willingness to pay) dari pengguna air untuk memberikan kontribusi finansialnya bagi upaya konservasi air di kawasan hutan yang menjadi resapan airnya. Nilai DKK yang bersedia diberikan oleh masyarakat pengguna jasa lingkungan air dari Kawasan TWA Tampomas, TWA Gunung Guntur dan TWA/CA Kamojang untuk upaya konservasi kawasan TWA/CA sebagai daerah resapan air disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa estimasi total nilai DKK dari pengguna air di TWA Tampomas adalah sekitar Rp.1,714 milyar/bulan dan untuk TWA/CA Gunung Guntur dan Kamojang adalah sekitar Rp.1,75 milyar/bulan. Apabila nilai masing-masing DKK di setiap kawasan dibagi dengan luasnya, maka rata-rata nilai DKK untuk TWA Tampomas dengan luas 1.250 ha serta rata-rata nilai DKK untuk TWA/CA Kamojang dan Gunung Guntur dengan luas 8.298 ha masing-masing adalah Rp. 1.371.608,82/ha/bulan dan Rp.210.901,47/ha/bulan. Apabila nilai rata-rata DKK per ha tersebut diasumsikan sebagai nilai keberadaan kawasan tersebut, maka nilai kontribusi kawasan TWA/CA dalam menyediakan jasa lingkungan air terhadap masyarakat di sekitar dan bagian hilirnya berada pada kisaran antara Rp.200.000 sampai dengan Rp.1,3 juta/ha/bulan. Tabel 1 Estimasi Dana Kompensasi Konservasi per bulan di Wilayah StudiKawasan Konservasi TWA Tampomas Keterangan WTP rata-rata Jumlah (KK) Total WTP/bulan (Rp) Total DKK per bulan TWA/CA Gunung Guntur dan Kamojang WTP rata-rata Jumlah (KK) Total WTP/bulan (Rp) Total DKK per bulan 7,194 181,093 1,302,783,042 4,704 89,929 423,026,016 7,359 3,254 23,946,186 Sektor Rumah Tangga 9,729 141,733 1,378,920,357 Sektor Pertanian 4,241 75,575 320,513,575 Sektor Industri 4,125 3,623 14,944,875 Sektor Fasilitas Publik 4,722 28 132,216 1,714,511,023 2,794 124 346,456 1,750,101,700
Sumber: Hasil Analisis
Sektor rumah tangga merupakan pengguna air yang bersedia memberikan DKK terbesar dengan persentase kontribusi mencapai 80% di TWA Tampomas, serta 74% di TWA/CA Kamojang dan TWA Guntur. Adapun kontribusi DKK dari pertanian untuk di TWA Tampomas adalah 19% serta di TWA/CA Kamojang dan TWA Guntur adalah 24%. Kontribusi terkecil adalah dari industri sebesar 1% di masing-masing kawasan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sektor rumah tangga cenderung memiliki apresiasi nilai yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan bahwa kebutuhan air untuk konsumsi rumah tangga merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat disubstitusi oleh komoditas lainnya, sedangkan untuk kegiatan pertanian masyarakat masih bisa
6
menggunakan air hujan dan air yang kualitasnya di bawah air baku minum. Perbedaan nilai DKK yang diberikan masyarakat bagi kawasan TWA/CA tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktifitas ekonominya serta adanya persaingan pemanfaatan air. Kawasan dengan jumlah penduduk, tingkat aktivitas ekonomi dan persaingan pemanfaatan air tinggi cenderung meningkatkan nilai air. Sehingga, masyarakat bersedia untuk memberikan nilai DKK lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat dengan jumlah penduduk, tingkat aktivitas ekonomi dan persaingan pemanfaatan air lebih rendah. Selain faktor tersebut di atas, tingkat apresiasi masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya air memegang peranan penting dalam menentukan besarnya nilai DKK. Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hutan konservasi yang kelihatannya diam ternyata memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Tetapi besarnya kontribusi tersebut belum diimbangi dengan apresiasi yang memadai dari pengguna jasa lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu pengembangan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, terutama jasa lingkungan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus dilakukan. Pengembangan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan tersebut dilakukan untuk membangun tanggungjawab bersama dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam hal ini kelestarian jasa lingkungan hutan konservasi tidak hanya menjadi tanggung-jawab pengelola kawasan sebagai provider-nya, tetapi juga menjadi tanggung-jawab semua stakeholders yang menjadi penggunanya melalui berbagai mekanisme diantaranya dengan kerjasama yang dibangun dengan pendekatan instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi
lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pengembangan sistem pembayaranjasa lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan yang mungkin diterapkan dalam kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Prinsip, Azas, dan Tahapan KerjasamaDasar dalam kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi adalah adanya kesepahaman dalam melihat penerapan sistem insensif dalam pengelolaan jasa lingkungan hutan konservasi antara provider dengan users jasa lingkungan hutan konservasi. Kementerian Negra Lingkungan Hidup (2006) menyebutkan beberapa prinsip kerjasama tersebut sebagai berikut : a. Berbasis pembangunan berkelanjutan Kerjasama yang idjalin untuk meningkatkan kapasitas antar pihak dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; b.Saling menghormati
7
Setiap anggota menghormati seluruh pihak yang menjadi mitra kerjasamanya melalui pengakuan terhadap nila-nilai kehormatan (dignity) serta mengedepankan kebersamaan dalam menggagas suatu keputusan bersama; c.Kolaboratif, membangun kemitraan strategis Kerjasama yang dibentuk memberikan keuntungan semua anggota melalui pengembangan kemitraan sinergis serta sikap kooperatif dan akomodatif yang tinggi dengan menjungjung pengakuan kesejajaran. Kunci membangun kemitraan sinergis adalah bila seluruh pihak merasa diuntungkan dan saling membutuhkan serta tidak ada pihak yang merasa dimanfaatkan oleh pihak lain; d.Mengikuti aspek legalitas Kerjasama yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak serta tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia e.Kejelasan hak, kewajiban, dan aturan main Setiap kerjasama harus menjelaskan hak, kewajiban, dan aturan main. Dalam hal ini merupakan hak dan kewajiban kolektif, yang diserahkan kepada pemimpin atau wakil delegasi yagn melakukan kerjasama. f.Partisipatif Sedapat mungkin melibatkan representasi stakeholders; g.Pengakuan Kesepakatan harus dibangun dengan persetujuan legislatif dan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapat pengakuan bersama. Adapun azas-azas kerjasama yang perlu diperhatikan adalah (KMLH, 2006) : a) Azas manfaat Kerjasama yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan pengelola yang menjalin kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; b) Azas persamaan dan kebersamaan Kerjasama dibangun aatas persamaan dan rasa kebersamaan, salah satu pihak tidak merasa lebih superior dibandingkan dengan pihak lainnya; c) Azas kepercayaan Seluruh pihak harus dapat membangun kepercayaaan bahwa setiap pihak memiliki komitmen, kemampuan, dan kapasitas melaksanakan kerjasama. d) Azas demokrasi dan keterbukaan Setiap anggota yang bekerjasama menjunjung demokrasi dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap permasalahan ditangani; 8
e) Azas keadilan Setiap anggota merasa mendapatkan keadilan, baik dalam memperoleh hasil kerjasama maupun dalam menentukan beban dan kontribusi setiap anggota. Adapun tahapan dalam pembentukan kerjasama jasa lingkungan hutan konservasi adalah sebagai berikut (KMLH, 2006) : 1. Mengidentifikasi dan merumuskan cakupan permasalahan strategis Daerah dan atau para pihak yang menginisiasi kerjasama dan daerah lain yang akan terlibat kerjasama mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi dan selanjutnya merumuskannya ke dalam permasalahan strategis yang dihadapi bersama; 2. Menentukan pihak-pihak yang terlibat Daerah dan atau para pihak yang bermaksud menjalin kerjasama selanjutnya menyusun daftar pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama, dapat meliputi pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha/kegiatan, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan; 3. Menentukan batas wilayah yang akan dikelola Batas wilayah yang akan dikelola dalam kerjasama ditentukan dengan menggunakan pendekatan wilayah sesuai dengan batas administrasi masing-masing daerah yang akan melakukan kerjasama 4. Perumusan kesepakatan bersama Para pihak yang akan menjalin kerjasama merumuskan kespakatan bersama yang merupakan simbol telah disepakati adanya kerjasama; 5. Merumuskan dasar hukum lembaga yang akan dibentuk Jika dibentuk lembaga baru yang perlu status huku, sebagai pemegan hak dan kewajiban, oerlu dirumuskan dasar hukumnya. Dasar hukum kerjasama dapat berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur/Bupati/walikota/pengelola kawasan. Berdasarkan penilaian pihak-pihak yang bekerjasama, bentuk kerjasama ini dapat juga tidak perlu mempunyai dasar hukum, seperti hanya setingkat forum; 6. Penyusunan dan Pengesahan Program Kerja Para pihak yang terlibat kerjasama melalui lembaga kerjasama yang telah terbentnuk selanjutnya dapat menyusun program kerja, misalnya dapat dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk lokakarya. Pada pertemuan tersebut juga dapat dilakukan pengesahan dan pelantikan pengurus lembaga yang telah terbentuk.
9
Contoh Penerapan Kerjasama Jasa Lingkungan Antar Daerah : PES di Wilayah Gunung CiremaiPenerapan skema PES (Payment for Environmental Srvices) mengandung dua komponen penting, yaitu adanya proses terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak terkait mengenai kesediaan salah satu pihak untuk memberikan pembayaran atas jasa lingkungan yang disediakan oleh pihak lain, serta bentuk dari skema PES itu sendiri. Dalam kasus konflik antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon atas sumber daya air minum, kedua komponen tersebut adalah proses terjadinya kesepakatan antara kedua daerah mengenai adanya pembayaran oleh Kota Cirebon kepada Kabupaten Kuningan, serta Perda Tata Ruang Gunung Ciremai yang dijadikan sertifikat komitmen oleh Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan konservasi di kawasan Gunung Ciremai. Kedua aspek tersebut menjadi inti dalam bagian pembahasan. Proses menuju kesepakatan antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon dalam memanfaatkan sumber air minum lintas wilayah merupakan proses yang cukup panjang, mulai dari tahun 1999 sampai akhir tahun 2004. Pada tahun 1999 Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama LSM RISSAPEL Kabupaten Kuningan melakukan studi tentang potensi sumber mata air di kawasan Gunung Ciremai yang hasilnya digunakan untuk menetapkan zona resapan air kawasan tersebut. Studi tersebut pada awalnya ditujukan untuk memutakhirkan hasil kajian konsultan IWACO dan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1990, namun dalam prosesnya tim melihat bahwa potensi sumber mata air tersebut memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan dan di wilayah lain di sekitarnya, terutama memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat besarnya potensi sumber mata air dengan total debit keseluruhan mencapai + 8.000 liter/detik, tim selanjutnya mendelineasi zona resapan air di kawasan Gunung Ciremai. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Kuningan, DPRD Kabupaten Kuningan, dan masyarakat sepakat untuk mengkonservasi kawasan tersebut sebagai zona resapan air. Pada tahapan selanjutnya dilakukan proses legal untuk menindaklanjuti hasil studi zona resapan air kawasan tersebut dengan menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang tata ruang Gunung Ciremai dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai. Pada saat proses pembuatan perda tersebut belum ada rencana untuk menjadikannya sebagai jaminan komitmen pemanfaatan jasa lingkungan air antar daerah. Pada awal tahun 2004 sengketa tentang pemanfaatan air minum yang berasal dari Kabupaten Kuningan yang dimanfaatkan Kota Cirebon, terutama mata air Paniis, mengemuka secara terbuka. Kronologis proses implementasi PES air minum lintas wilayah di kawasan tersebut disajikan pada Tabel 1. Mata air Paniis, salah satu mata air di kawasan Gunung Ciremai, berada pada ketinggian 375 m di atas permukaan laut. Air yang berasal dari mata air Paniis ini memasok air minum untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon.
10
Pada saat ini air dialirkan melalui pipa berdiameter 700 mm dari sumur pengumpul ke instalasi pengolahan di Plangon yang berjarak sekitar 8,2 Km dari Paniis. Debit air total mata air Paniis saat ini adalah 860 l/detik yang pada musim hujan dapat meningkat di atas 1.000 l/detik. Mata air Paniis merupakan sumber air minum andalan utama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Cirebon. Alternatif sumber air minum lainnya yang berasal dari air tanah dalam di sekitar Kota Cirebon dari jumlah dan kualitasnya kurang memenuhi standar air minum bagi masyarakat (Wahyudin, 2000). Oleh karena itu sumber air minum dari mata air di kawasan Gunung Ciremai merupakan prioritas pertama untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di Kota Cirebon. Mata air Paniis dikelola oleh PDAM Kota Cirebon untuk melayani penduduk Kota Cirebon dan beberapa daerah wilayah Kabupaten Cirebon dengan 51.344 pelanggan air minum sampai bulan Maret tahun 2003. Kapasitas terpasang yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Cirebon adalah 860 l/detik, tetapi debit yang diijinkan oleh Pemda Kabupaten Kuningan adalah sebesar 750 l/detik berdasarkan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) yang dikeluarkan oleh Kantor Sumberdaya Air dan Mineral Kabupaten Kuningan Nomor 616/039/SDAM/2003. Pengambilan air yang melebihi SIPA memicu konflik antara Pemda Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon yang terjadi pada pertengahan sampai akhir tahun 2004. Peningkatan konsumsi air minum masyarakat di Kota Cirebon yang terus meningkat menjadi alasan bagi PDAM Kota Cirebon untuk mengambil air di atas tingkat yang diijinkan. Di sisi lain Pemda Kabupaten Kuningan pun merasa bahwa perhatian Pemda Kota Cirebon untuk memelihara kelestarian kawasan sumber air minumnya dianggap kurang, padahal tanpa upaya untuk melestarikan kawasan sumber air tersebut maka pasokan air minum dari wilayah Paniis akan terganggu kesinambungannya. Pemda Kabupaten Kuningan berupaya mengajak Pemda Kota Cirebon untuk bekerjasama dalam memelihara kelestarian Gunung Ciremai sebagai kawasan resapan air dari sejumlah mata air yang selama ini digunakan oleh masyarakat Kota Cirebon. Upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan Gunung Ciremai selama ini menjadi tugas dari Pemda Kabupaten Kuningan yang berada di bagian hulunya, sedangkan manfaat hidrologis dari kegiatan konservasi dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di hilirnya, sehingga kelestariannya menjadi tanggung-jawab bersama dari semua pengguna air. Upaya untuk membangun kesepahaman dalam pengelolaan sumber air minum lintas wilayah didukung pula oleh komitmen politik dan dukungan publik yang kuat. Komitmen politik diantara dua Pemda, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, dalam menyelesaikan permasalahan sumber air minumnya tampaknya sangat kuat. Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon langsung terlibat memimpin rapat untuk mendiskusikan penyelesaian masalah air lintas wilayah. Komitmen kedua pimpinan daerah tersebut didukung oleh pihak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif dari masing-masing daerah dan juga masyarakat di dua wilayah tersebut. Sebagai badan legislatif dan wakil rakyat, DPRD merasa berkepentingan untuk ikut mendorong penyelesaian masalah sumber air minum lintas wilayah tersebut. Oleh karena itu
11
komitmen politik dan dukungan publik yang kuat ternyata mampu mendorong penyelesaian sengketa sumber air minum lintas wilayah tersebut secara damai dan saling menguntungkan. Dalam beberapa pertemuan antara Pemda Kabupaten Kuningan dengan Kota Cirebon untuk membahas penyelesaian konflik penggunaan air dari Paniis, isu utama yang menjadi pembahasan adalah kontribusi konservasi daerah resapan sumber mata air. Pertemuan antara kedua Pemda yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Cirebon telah mendorong adanya kesepahaman antara kedua belah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kesamaan visi untuk berbagi (shared vision) dalam mengalokasikan air minum di kawasan tersebut telah mendorong pemahaman dari pihak-pihak yang bersengketa akan pentingnya tanggung-jawab pengelolaan bersama sumber air tersebut. Visi untuk berbagi tersebut dibangun dengan mengintegrasikan pentingnya aspek kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air berkelanjutan. Tabel 1. Kronologis Proses Implementasi PES Air Minum Lintas di Kawasan Gunung CiremaiNo 1 2 3 Proses Implementasi PES Identifikasi Potensi Sumber Air di Kawasan Gunung Ciremai (Studi) Penetapan zona resapan air kawasan Gunung Ciremai (Studi) Proses Legal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana umum Tata Ruang Gunung Ciremai Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Rencana umum Tata Ruang Gunung Ciremai Negosiasi mata air Paniis Kuningan-Cirebon Penandatangan Kesepakatan Pemanfaatan Mata Air Paniis Implementasi Kesepakatan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
4 5 6 7
28 Nop 2002 Kon flik 17 Des 2004
Untuk menjamin alokasi air lintas wilayah secara berkelanjutan, maka kerjasama antar daerah diatur dalam suatu peraturan kerjasama pemanfaatan air yang disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan pemanfaatan air dan kontribusi dana konservasi di kawasan Gunung Ciremai telah diatur oleh suatu nota kesepakatan (memorandum of understanding) antara Bupati Kuningan dan Walikota Cirebon yang ditandatangani tanggal 17 Desember 2004, yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian sumber air serta untuk kesejahteraan masyarakat diantara kedua daerah tersebut. Perjanjian tersebut mengatur mengenai
12
kewajiban pihak pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan diantaranya adalah: (a) menjaga/melindungi sumber air mata air sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi air; dan (b) menerima dan menggunakan dana konservasi dari pengguna air minum di Kota Cirebon untuk kepentingan konservasi yang dapat menjamin kelestarian sumber mata air, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat. Adapun kewajiban Pemerintah Kota Cirebon adalah : (a) memanfaatkan sumber mata air Paniis sesuai ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan (b) membantu kepentingan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (catchment area) sumber mata air sesuai dengan kemampuannya. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa besarnya dana kompensasi konservasi dihitung dengan mempertimbangkan produksi air dari sumber air, tarif yang berlaku sebelum diolah bagi pelanggan di Kota Cirebon, dan tingkat kebocoran air. Kesepakatan besaran dana kompensasi untuk konservasi Gunung Ciremai dari Kota Cirebon berdasarkan rumusan tersebut adalah Rp.1,75 milyar untuk tahun 20052. Dana kompensasi konservasi ini secara khusus harus dialokasikan untuk mendanai kegiatan konservasi di zona resapan air Paniis sebagai sumber mata airnya. Perlu ditegaskan bahwa dana kompensasi konservasi tidak dibuat dalam kerangka tradable water yang memandang air sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi dana tersebut dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung-jawab dari pengguna jasa lingkungan air di bagian hilir untuk berkontribusi membantu kegiatan konservasi di bagian hulunya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap hak airnya, misalnya hak akses. Pada umumnya di kawasan tersebut masyarakat memandang bahwa air dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan hukum Islam yang banyak dianut di daerah tersebut. Pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Sarwan et al. (2003) yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat atas hak-hak air di Indonesia dilatarbelakangi oleh pandangan hukum Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2002 tentang RUTR Gunung Ciremai selain berfungsi untuk mengalokasikan ruang dalam kawasan tersebut, juga bernilai ekonomi berkaitan dengan jaminan komitmen wilayah hulu (Kabupaten Kuningan) untuk memasok air dalam jumlah dan kualitas yang stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu RUTR Gunung Ciremai merupakan sertifikat dari komitmen Pemda dan masyarakat
Kabupaten Kuningan untuk mempertahankan wilayah Gunung Ciremai sebagai resapan air yang memasok kebutuhan air minum bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. PelaksanaanRUTR sebagai sebuah sertifikat komitmen dari daerah hulu untuk hilirnya tersebut merupakan terobosan kebijakan dalam kerjasama antar daerah di era otonomi daerah ini. Bagi bidang perencanaan wilayah, proses pembuatan perda ini menjadi bukti bahwa dokumen RUTR tidak hanya bermanfaat dalam mengalokasikan ruang saja, namun 2 Perjanjian terbaru tahun 2009 mengatur nilai besaran dana kompensasi sebesar Rp.80/m3. 13
berdampak ekonomi dalam meningkatkan pendapatan daerah hulu. Wilayah pengguna air di bagian hilir cenderung lebih merasa aman apabila wilayah hulu sebagai pemasok air mampu menunjukkan komitmen dalam menjaga kawasan resapan airnya, sehingga kesediaan wilayah hilir untuk membayar atas air yang digunakannya diperkirakan akan meningkat. Peningkatan apresiasi nilai ini dari wilayah hilir ini berkaitan dengan adanya komitmen yang jelas dari wilayah hulu sebagai pemasok air untuk melindungi wilayahnya sebagai resapan air. Upaya-upaya penyelesaian konflik sumber air minum lintas didorong oleh suatu kemitraan yang luas (broad based partnerships) antara pemerintah, lembaga legislatif, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Kesepahaman untuk memberikan kontribusi dari hilir ke hulu diharapkan akan meningkatkan upaya kelestarian lingkungan sumber mata air, sehingga distribusi manfaat air diantara pihakpihak yang berkepentingan dapat berjalan lebih adil. Selain ketiga faktor sebelumnya, partisipasi publik untuk membangun mekanisme alokasi air lintas wilayah yang lebih adil dan berkelanjutan perlu lebih didorong oleh masing-masing Pemda sehingga proses kerjasama antar daerah dapat diimplementasikan secara efektif. Kesimpulan Hutan konservasi memiliki jasa lingkungan yang bernilai penting bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup lainnya. Jasa lingkungan tersebut merupakan output ekosistem hutan yang sepanjang kualitas ekosistemnya terjaga baik akan tetap memberikan manfaat jasa lingkungan. Tanggung-jawab untuk menjaga jasa lingkungan tersebut tidak hanya tanggung-jawab pengelola kawasan sebagai provider jasa lingkungan tersebut, tetapi juga merupakan tanggung-jawab para pihak (stakeholders) yang menjadi pengguna jasa lingkungan tersebut. Oleh karena itu kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan asas-asas kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan hidup dengan mengembangkan sistem kemitraan kerjasama yang luas. Daftar Pustaka Acreman, M. 2004. Water and Ecology. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO). Paris Asian Development Bank (ADB). 2001. Handbook for Economic Analysis of Water Supply Projects. Http : //www.adb.org//. [20 Dec 2001]. Cruz, R.V.O. , L.A. Bugayong, P.C. Dolom, and N.O.Esperitu. 2000. Market-Based Instruments for Water Resource Conservation in Mt Makiling, Philippines : A Case Study. Paper for the 8th Biennal Conference of The International Association for the Study of Common Property, 31 May 4 June 2000 at Bloomington, Indiana. Hoekstra, A.Y. 1998. Appreciation of water : four perspectives. Water Policy 1 (1998) : 605-622.
14
Johnson, N., A.White, and D.P. Maitre. 2001. Developing Markets for Water Services from Forests : Issues and Lessons for Innovators. Forest Trends. Washington, DC. Karyono Dan Subarudi. 2001. Study Perbandingan Nilai Produk Jasa Wisata Dan Kayu Pada Hutan Produksi Di Jawa Barat. Jurnal Sosial Ekonomi, 2 (1): 71- 78. KMNLH. 2006. Pedoman Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta. Ramdan, H. 2004. Analisis Kebijakan Prospek Alokasi Air Lintas Wilayah dari Gunung Ciremai Propinsi Jawa Barat. Jurnal Penelitian Kehutanan Wana Mukti, 2 (2) : 28-35. Ramdan, H. 2006. Pengelolaan Sumber Air Minum Lintas Wilayah di Kawasan Gunung Ciremai Propinsi Jawa Barat. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. Ramdan, H., Yusran, dan D. Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah : Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Penerbit Alqa Print. Jatinangor, Sumedang. Verweij, P.2002. Innovative Financing Mechanisms for Conservation and Sustainable Management of Tropical Forest : Issues and Perspective. Paper for International Seminar on Forest Valuation and Innovative Financing Mechanisms for Consevation and Sustainable Management of Tropical Forests. Tropenbos International, The Hague, 20-21 March 2002. Wahyudin, 2000, Potensi Cekungan Airtanah Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Bandung. Biodata Penulis Dr.Ir.Hikmat Ramdan, M.Si. LahirdiGarutpadatanggal26Nopember1971.Lulusdari Jurusan Manajamen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1994, menempuhpendidikanMagisterSainspadaProgramStudiPengelolaanDaerahAliranSungai (DAS)ProgramPascaSarjanaIPBtahun19951999,danmeraihgelarDoktorpadaProgram PengelolaanSumberdayaAlamdanLingkungan(PSL)SekolahPascaSarjanaIPBtahun2006. Bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kehutanan UNWIM sejak tahun 1995. Di samping sebagaidosendiFahutanUNWIM,jugamengajar/membimbingmahasiswaprogramdoktordi Program Studi PSL IPB dan Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Di luar kesibukannya sebagai pengajar, aktif sebagai peneliti dan konsultan bidang manajemen sumberdaya alam dan lingkungan. Tercatat sebagai anggota Tim Kormonev Pemberantasan Ilegal Logging di Indonesia (Kantor Menkopolhukam) sejak tahun 2007. Bidang kajian riset dalam lima tahun terakhir : kebijakan pengelolaan air lintas wilayah, ekonomi politik sumberdayaair,politikekologi,asuransilingkungan,dankajiankejahatanbidangkehutanan (forestrycrimes).Email:[email protected]
15







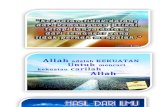

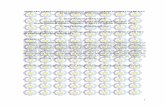




![SERI TERANG ILAHI Seruan Hikmat - Santapan Rohanicdn.santapanrohani.org/files/STI-Seruan-Hikmat-web.pdfkeuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga [ 3] SERUAN HIKMAT](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/60811737f0ba114f8264870f/seri-terang-ilahi-seruan-hikmat-santapan-keuntungan-perak-dan-hasilnya-melebihi.jpg)