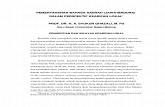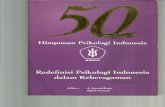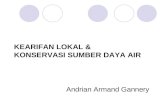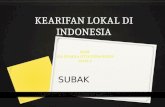Kearifan Lokal Tugas Kita
-
Upload
luthfi-affandhy -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
description
Transcript of Kearifan Lokal Tugas Kita

TUGAS PLH
Kearifan Lokal Lingkungan
Disusun oleh:
Anwi Kusuma (04)
Destya Budi A. (07)
Dwi Nurul A. (09)
Innovan Ade P. (14)
Komang Yogastara (17)
Luthfi Rizky A. (19)
Nur Afidah (24)
Ragadisa Dyah F. (27)
Rizka Dwi L. (29)

Kearifan Lokal
1. Wiwitan
Wiwitan yang dalam bahasa Indonesia berarti memulai panen, sebenarnya memiliki makna yang tinggi dalam masyarakat Jawa. Didalam wiwitan terjadi interaksi horizontal antara manusia, dan alam, sedangkan interkasi vertikal terjadi antara manusia dan sang pencipta.
Letak interaksi horizontal antara manusia dan alam ditunjukan dalam prosesi “ngguwaki” (membuang). Prosesi ini dilakukan dengan membuang sesaji di pojok-pojok sawah. Pada upacara wiwitan pada umumnya menggunakan sesaji seperti: nasi, buah-buahan dan snack-snack makanan kecil. Bagi masyarakat tertentu prosesi membuang sesaji dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia, karena dalam prosesi ini yang dia buang adalah makanan.
Dari sudut pandang ilmu pertanian, prosesi membuang sesaji adalah hal yang positif. Mengapa demikian? Ketika makanan dibuang di pojok-pojok sawah, makanan seperti nasi, buah-buahan, dan makanan yang lain akan menjadi makanan bagi cacing-cacing tanah dan mikroorganisme lain, sehingga cacing dan mikroorganisme dalam tanah berkembang lebih baik dan tanah akan menjadi subur. Bila tanah subur diharapkan hasil panenan pun akan melimpah. Disinilah telah terjadi interaksi antara manusia dengan alam dimana interaksi tersebut saling menguntungkan.Interaksi vertikal dalam prosesi wiwitan terlihat bahwa prosesi ini adalah sebagai alat untuk rasa bersyukur terhadap sang pencipta atas hasil panen yang melimpah. Rasa syukur ini diwujudkan dengan membagi-bagikan makanan yang sekaligus sebagai sesaji kepada masyarakat di sekelilingnya yang pada umumnya adalah anak-anak kecil.
Bila dilihat pada penjelasan diatas, maka sangatlah tidak tepat bila budaya wiwitan untuk memulai penen padi adalah membuang makanan sebagai sesuatu yang sia-sia. Untuk itulah budaya wiwitan yang sudah lama ada dalam masyarakat Jawa perlu dilestarikan.
2. Pembukaan Ladang
Ada beberapa etnik yang bersinggungan langsung dengan alam diantaranya etnik Rejang dan Serawaiyang. Etnik Rejang memiliki kearifan dengan mengetahui zonasi hutan, mereka sudah menentukan imbo lem (hutan dalam), imbo u'ai (hutan muda) dan penggea imbo (hutan pinggiran). Dengan zonasi yang mereka buat, maka ada aturan-aturan tentang penanaman dan penebangan kayu. Hampir mirip dengan Etnik Rejang, Serawaiyang dikenal sebagai tipikal masyarakat peladang telah mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan ladang yaitu "celako humo" atau "cacat humo", dimana dalam

pembukaan ladang mereka melihat tanda-tanda alam dulu sebelum membuka ladang dimana ada 7 pantangan yaitu:- ulu tulung buntu, dilarang membuka ladang di hutan tempat mata air- sepelancar perahu- kijang ngulangi tai- macan merunggu- sepit panggang- bapak menunggu anak- dan nunggu sangkuptujuh pantangan ini jika dilanggar akan berakibat alam dan penunggunya (makhluk gaib) akan marah dan menebar penyakit.
Sedangkan dilihat dari segi lingkungan 7 pantangan tersebut ada benarnya seperti dilarang membuka ladang di tempat mata air karena akan mengganggu sumber mata air bukan saja mengganggu juga merusak.
3. Pohon Beringin
Pohon beringin yang dikeramatkan oleh hampir di banyak daerah di nusantara, bukan tanpa tujuan dan kajian ilmiah, yang notabene moyang-moyang kita dengan kesederhanaan sikap hidup mereka telah memiliki daya telaah dan misi yang tak sekedar untuk jangka pendek. Ya, beringin (Ficus benjamina dan beberapa jenis lain, suku ara-araan atau Moraceae) sangat akrab dengan budaya asli Indonesia. Sebagai pohon yang ampuh menangkap gas karbondiaoksida dan produsen oksigen yang handal, beringin juga merupakan tanaman yang memiliki akar yang cukup banyak dapat menampung air tanah. Itu mengapa alasan jaman dulu moyang kita mengkeramatkan beringin, memberi sesajen dan melekatkan kata “angker” pada beringin, semata adalah sebagai wujud terima kasih mereka pada beringin, menghindarkan beringin dari penebangan yang nantinya akan berakibat tak baik juga pada masyarakat karena sumber kelestarian mereka terampas.
4. Tumpek Wariga
Tumpek Wariga/Tumpek Uduh di Bali, yaitu hari khusus untuk melakukan penghormatan kepada sang Pencipta dalam hal ini yang telah menganugerahkan tetumbuhan pada bumi dan manusia. Hal ini juga tak lepas dari kepedulian nenek moyang kita yang merasa begitu bergantung pada alam dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kearifan lokal bagi kita manusia modern, ada baiknya memang ditelusuri asal muasalnya sehingga tak asal menghakimi bahwa perilaku nenek moyang dan warisan kearifan lokal hanya semata kepercayaan belaka tanpa manfaat dan latar belakang ilmiah; yang selalu dibutuhkan manusia modern untuk menjadi alasan untuk mau menerima sesuatu dari masa silam.

5. Kearifan Lokal Desa Gunung Malang Khususnya Kampung Cimanggu
Cimanggu merupakan salah satu kampung yang terdapat di Desa Gunung Malang. Kearifan lokal yang ada di Desa Cimanggu berupa sistem penanggalan dalam pertanian, misalnya penanggalan musim tanam. Sistem penanggalan ini adalah sistem penanggalan sunda yang dalam penentuannya dilihat dari perkiraan posisi bulan. Misalnya masa tanam dilakukan pada saat sebelum bulan ramadhan dan dihitung dari satu muharam. Dahulu sekitar tahun 60-an, Penduduk Desa Gunung Malang memegang sebuah budaya tersendiri dalam mengolah lahan pertanian mereka. Mereka tidak mengenal perhitungan bulan konvensional , tetapi hanya mengenal perhitungan bulan-bulan Islam, dan menyakini bahwa hanya terdapat 30 hari dalam satu bulan. Dalam menentukan penanggalan waktu tanam umumnya petani menggunakan bulan sebagai petunjuk, ketika bulan terlihat terang berarti menunjukkan tanggal muda (1-10), tanggal satu ditetapkan ketika bulan tepat di atas kepala dan ketika bulan gelap berarti menunjukkan bulan tua (17-30). Petani di Desa Gunung Malang memiliki semacam “ilmu batin” yang bisa menunjukkan kapan seharusnya menanam, dan kapan seharusnya tidak menanam. Ketika pada waktunya tidak boleh menanam, berarti seluruh petani harus serentak tidak boleh menanam, jika ada yang menanam umumnya terjadi “malapetaka” tertentu seperti lahan pertaniannya terkena hama, atau tidak tumbuh dengan subur.
Selain itu pada saat panen, para petani biasanya membuat acara rujakan dan juga beberapa makanan tambahan seperti ayam dan telur. Ritual ini biasanya dilakukan di pusat air yang sudah dibubuhi dengan doa-doa dengan tujuan mendapat berkah dari Sang Khaliq. Namun kebiasaan ini telah pudar, hanya orang-orang tertentu yang melaksanakan yaitu orang-orang tua. Bahkan ritual ini menimbulkan pro dan kontra karena sistem tersebut tidak dapat diterima secara logis oleh masyarakat angkatan muda.
Tradisi yang juga biasa dilaksanakan oleh masyarakat Cimanggu adalah ketika maulid nabi, dedaunan diikatkan ke pohon. Tradisi ini dipercaya dapat menjaga pohon dari serangan hama dan pohon cepat berbuah.
Selain contoh kearifan lokal yang ada diatas, di Desa Gunung Malang juga terdapat kearifan lokal dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri adalah apa saja yang mempunyai kaitan dengan kehidupan pada umumnya dan kehidupan manusia (Sastrosupeno, 1984). Salah satu contoh pemeliharaan lingkungan hidup yang ada di Desa Cimanggu adalah gotong royong. Misalnya pada saat hari-hari besar seperti pada perayaan 17 Agustus masyarakat Cimanggu melakukan gotong royong. Namun sekarang gotong royong tersebut sudah tidak lagi dilaksanakan, karena tidak lagi diagendakan oleh kepala desa setempat. Sehingga sekarang pemeliharaan lingkungan hidup dengan gotong royong tidak lagi dilaksanakan. Akibat dari pemeliharaan lingkungan hidup yang tidak lagi dilaksanakan, keadaan kampung tersebut kurang terurus kebersihannya. Meskipun begitu, masyarakat kampung tersebut membuat inisiatif sendiri dengan membuat lubang di pekarangan rumah sebagai tempat pembuangan sampah, kemudian di bakar.