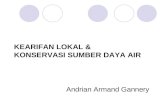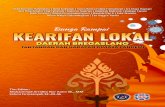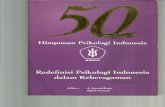Makalah Filsafat Hukum kearifan lokal
-
Upload
rokhi-maghfur -
Category
Documents
-
view
158 -
download
19
description
Transcript of Makalah Filsafat Hukum kearifan lokal

PENEGAKAN HUKUM SENGKETA TANAH ADAT YANG BERBASIS
KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU PADA MASYARAKAT TALANG
MAUR PAYAKUMBUH
MATA KULIAH FILSAFAT HUKUM
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S.
Disusun Oleh:
Nama : ROKHI MAGHFUR
Nim : 11010115410079
Kelas : HUKUM EKONOMI DAN TEKHNOLOGI (HET)
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tanah memiliki arti yang sangat krusial bagi setiap individu dalam
masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan sebagai
investasi di masa yang akan datang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam
lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat untuk
bermukim, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah mati pun masih
memerlukan tanah. Bagi pandangan mayoritas masyarakat, memiliki tanah seperti
halnya bahan makanan maupun bahan sandang yang mengandung kebutuhan
primer bagi individu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sedemikian pentingnya arti tanah bagi manusia, Indonesia sebagai negara
agraris memandang perlu mengatur politik hukum di bidang pertanahannya
(konsepsi agraria dalam arti sempit) dalam konstitusi UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Konstitusi kita mengamanatkan agar sumber
daya alam termasuk tanah dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Politik hukum pertanahan kita ini setidaknya
mengalami 2 (dua) kali masa penyusunan. Masa penyusunan pertama adalah
tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkannya UUD RI Tahun 1945. Pada era
reformasi, politik hukum pertanahan diatur dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan
Sosial yang memuat satu pasal yaitu Pasal 33 yang berisi ketentuan bahwa bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga ditengah-
tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan
tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut juga sebagai harta
1

pusaka.1 Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
maka sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar
1945 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat (UUPA), yang dalam
Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2043. Hak menguasai dari Negara sebagai
mana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) bukan berarti hak untuk memiliki,
tetapi Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia pada
tingkatan tertinggi telah diberi wewenang mengatur untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Atas dasar hak menguasai dari Negara dalam pelaksanaannya dikuasakan
kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.
Pelaksanaan hak menguasai dari Negara kepada masyarakat hukum adat. Di
dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah
yang dikuasainya, terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat pada
pandangan religio magis. Hubungan erat dan bersifat religio magis ini,
menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah
tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang
hidup di atas tanah itu dan juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di
wilayah persekutuan tersebut.
Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat,
karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami
keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula dari segi ekonomis.
Kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat,
memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal
dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal
para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Dalam
hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kasatuan dengan tanah yang
1 “Harta benda peninggalan orang yang telah meninggal”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, 2002.
2

didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada
pandangan yang bersifat religio-magis.2
Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta
kekayaan yang selalu dipertahankan, luas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum
atau oleh seseorang akan sangat mempengaruhi wibawa seseorang atau suatu
kaum dalam kehidupan masyarakat. Orang (kaum) yang memiliki tanah yang luas
akan lebih dihormati dan dihargai dibandingkan orang (kaum) yang tanahnya
sedikit atau tidak ada sama sekali. Begitu juga halnya dalam menentukan asli atau
tidak nya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah, seseorang (suatu
kaum) yang tidak memiliki tanah disuatu daerah atau nagari, maka dapat
dipastikan orang (suatu kaum) tersebut bukanlah penduduk asli daerah tersebut.
Oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai
seseorang bersangkut paut dengan tanah. Maka sebab itu tanah di Minangkabau
tidak boleh dipindah tangankan dengan begitu saja layaknya menjual rumah atau
barang-barang lainnya seperti mobil, emas, motor dan lainnya baik dalam bentuk
menggadaikannya, apa lagi menjualnya, apalagi menjualnya.
Pada dasarnya hak untuk menguasai tanah oleh masyarakat hukum adat
dapat disebut hak ulayat. Sejak berlakunya UUPA tentang kedudukan hak ulayat
di atur dalam Pasal 3 UUPA, yang menentukan bahwa:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan ayat (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.
Sifat dan karakteristik tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau
tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terutama yang berkaitan dengan
tanah ulayat, khususnya di kenagarian Talang Maur. Permasalahan terkait tanah
ulayat biasa disebut dengan sengketa tanah ulayat. Diskusi mengenai tanah ulayat
merupakan kegiatan yang selalu menarik bagi kalangan praktisi maupun
2 Muhammad. Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal 103.3

akademisi, karena keberadaannya yang tekait dengan banyak kepentingan. Tanah
ulayat merupakan tanah yang memiliki secara bersama-sama oleh masyarakat
hukum adat, menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh
diperjualbelikan yang dinyatakan sebagai berikut :
a. Dijua indak dimakan bali (dijual tidak dimakan beli)
b. Digadai indak dimakan sando (digadai tidak dimakan sando)3
Sengketa tanah ulayat merupakan sengketa tanah adat yang banyak terjadi
di Propinsi Sumatera Barat, terutama di daerah yang masih menggunakan dan
melestarikan hukum adat Minangkabau dalam kesehariannya khususnya di Nagari
Talang Maur yang masih kental dengan hukum adatnya, Dalam tataran hidup
bernagari, segala permasalahan yang ada disuatu nagari harus diselesaikan
secara bajanjang naik dan batangga turun, artinya semua permasalahan harus
diselesaikan mulai dari bawah yaitu mulai dari mamak terus kepada kepala kaum.
Jika tidak selesai di kepala kaum di teruskan kepada penghulu suku. Apabila tidak
selesai juga baru sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Demikian juga
dengan segala hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN) disampaikan kepada anak
kemenakan melalui tingkatan atau batangga turun. Penghulu suku menyampaikan
kepada kepala kaum dan seterusnya kepada mamak kepala waris seterusnya
kepada kemenakan dan anak.
Berdasarkan tataran implementasinya berbagai persoalan yang ada dalam
kehidupan beranak kemenakan, berkaum, bersuku, berkorong, berkampung dan
beradat serta bernagari tetap saja terjadi berbagai persoalan yang sulit diselesaikan
pada tingkat Kerapatan Adat Nagari. Salah satu bentuk sengketa yang sering
terjadi didalam nagari adalah tanah, baik dengan pihak interen kaum maupun
dengan pihak lain.
Oleh karena permasalahan mengenai adanya sengketa tanah yang terjadi di
Talang Maur Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, maka kiranya perlu dikaji
secara mendalam mengenai” PENEGAKAN HUKUM SENGKETA TANAH
3 Idrus Hakimy, Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau, Bandung:Rosda,1978 , hal.42-444

ADAT YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU PADA
MASYARAKAT TALANG MAUR PAYAKUMBUH”.
B. RUMUSAN MASALAH
Untuk memudahkan pembaca memahami isi makalah, penulis mencoba
mempersempit uraian-uraian dalam makalah ini menjadi beberapa garis besar
yang pada intinya membahas:
1. Apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah adat pada Masyarakat
Talang Maur Payakumbuh?
2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat
yang berbasis kearifan lokal Minangkabau pada Masyarakat Talang Maur
Payakumbuh?
C. TUJUAN PENULISAN
Sejalan dengan permasalahan diatas maka hal ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui penyebab utama terjadinya sengketa tanah adat pada
Masyarakat Talang Maur Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum dalam penyelesaian sengketa tanah
adat yang berbasis kearifan lokal Minangkabau pada Masyarakat Talang
Maur Payakumbuh.
Sementara itu, penyusunan makalah ini juga bertujuan untuk melengkapi
tugas pada Matakuliah Filsafat Hukum Tahun 2015 Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro.
D. RUANG LINGKUP
Pembahasan dalam makalah ini terbatas pada ruang lingkup makna dan
kronologis dalam hubungannya dengan topik dan judul makalah ini.
E. METODE PENULISAN
Metode yang penulis gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi
kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber dari buku-buku maupun
tulisan-tulisan lain yang menjadi acuan penulis.
5

BAB II
PEMBAHASAN
A. PENYEBAB UTAMA TERJADINYA SENGKETA TANAH ADAT PADA
MASYARAKAT TALANG MAUR PAYAKUMBUH
1. Pengertian Tanah Adat(Tanah Ulayat)
Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan
kuno disebut dengan hak eigendom (eigendomsrecht) dan hak yasan komunal
(communal bezitsrecht). Maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal
itu dengan Beschikkingrecht (hak pertuanan), yang akhirnya menjadi istilah
teknis.4
Ciri-ciri dari kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum
adat terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar adalah, Pertama, hak ulayat
berlaku kedalam bahwa masyarakat atau anggota-anggotanya, berwenang
menggunakan hak ini dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta
binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang terdapat di wilayah
kekuasaannya. Kedua, kewenangan yang berlaku keluar bahwa orang hanya
boleh memungut hasil pertuanan setelah mendapat izin dari persekutuan,
orang luar tersebut harus membayar uang pengakuan dimuka dan dibelakang.
Sedangkan sifat dari hak ulayat itu sendiri adalah mempunyai hubungan yang
abadi dengan masyarakat hukum pendukungnya, yang berarti tetap ada
sepanjang tanah sebagai objeknya dan masyarakat adat sebagai subjeknya
ada.5
Sedangkan Iman Sudiyat menyebut hak ulayat sama dengan istilah
Djojodiguno yaitu hak purba. Menurutnya, hak purba ini adalah hak yang
dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa – desa
(dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja, untuk menguasai seluruh
tanah seisinya dalam wilayahnya.6
4 Ter, Haar, Asas–asas dan susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 71-72.5 Iman Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 236 Ibid, hal. 23.
6

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu
masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda
utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level
internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak
Masyarakat Adat (United Nation Declaration on The Rights of Indegenous
Peoples) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September
2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara
masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat,
sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi
secara universal.
Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan
ulayat (sumber daya alam) di Indonesia acap terbentur oleh kebijakan agraria
nasional dan atau kebijakan yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat
kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci dan
jelimet. Kondisi kebijakan tersebut diperparah lagi oleh berbagai distorsi
penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak
ulayat oleh masyarakat adat.
Dengan lahirnya Perda No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya (TUP) memberikan suasana tersediri bagi dinamika
penguatan masyarakat nagari, Perda serupa sebenarnya telah ada di daerah
lain seperti Perda Kabupaten Kampar No. 12/1999 tentang Hak Tanah Ulayat
dan Perda Kabupaten Lebak No. 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak
Ulayat Masyarakat Baduy. Dalam konteks Perda TUP pada level provinsi
membuat tingkat abstraksi Perda TUP lebih tinggi karena harus
menggambarkan keberagaman struktur sosial yang ada di dalam masyarakat.
Prinsip utama pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau
sebagaimana diadopsi menjadi asas utama pembentukan Perda TUP adalah
“jua indak makan bali, gadai indak makan sando” yang maksudnya bahwa
tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat dipindahtangankan
pada orang lain. Tetapi masyarakat boleh memanfaatkannya, mengelola,
mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap
7

menjadi milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Filosofi ini
menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan tanah
ulayat bersifat abadi.
Pemanfaatan tanah ulayat bagi kepentingan anggota masyarakat
adat dilakukan berdasarkan hukum adat. Pemanfaatan tanah ulayat bagi
kepentingan umum dilakukan “sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Perda
TUP tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan “sesuai dengan
ketentuan yang berlaku” itu didasarkan kepada hukum adat atau kepada
hukum nasional. Bila mengacu kepada hukum nasional maka akan merujuk
kepada Perpres 36/2005 juncto Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Perpres ini sejak
kelahirannya banyak dikritik oleh kalangan masyarakat sipil sebab dianggap
sebagai landasan legitimasi perampasan tanah masyarakat.
Pemanfaatan tanah ulayat bersama atau oleh pihak luar (pemerintah
atau investor) bila berakhir masa perjanjiannya akan kembali kepada
masyarakat adat sesuai dengan adagium”Kabau tagak kubangan tingga,
pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan lakek di badan.”
Tanah ulayat tetap menjadi milik dari masyarakat adat. Yang dibawa oleh
pengusaha adalah hasil-hasil usaha yang diperoleh dari. Mengelola tanah
ulayat. Setelah usaha selesai maka tanah dikembalikan kepada masyarakat
adat.
2. Macam-Macam Tanah Adat Menurut Hukum Adat Minangkabau
Tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat berdasarkan adat
Minangkabau, dapat dibedakan ke dalam tiga golongan besar dari macam–
macam status, JenisHak Ulayat, Sifat dan Status pengemban atau pemilik hak
pengurusan.
a. Tanah Ulayat Nagari, Penguasaan/ Publik HGU, Hak Pakai, Hak
Pengelolaan Secara adat dimiliki oleh anak nagari Pengurusan oleh Ninik
mamak KAN (Kerapatan Adat Nagari). Pengaturan pemanfaatan oleh
Pemerintah Nagari.
8

b. Tanah Ulayat Suku, Kepemilikan/perdata Hak Milik Milik kolektif
anggota suatu suku Pengaturan dan pemanfaatan oleh penghulu- penghulu
suku.
c. Tanah Ulayat Kaum, Kepemilikan/ perdata, Hak Milik Milik kolektif
anggota suatu kaum. Pengaturan dan pemanfaatan oleh mamak jurai/
mamak kepala waris.
d. Tanah Ulayat Rajo, Kepemilikan/perdata Hak Pakai dan Hak Kelola Laki
- laki tertua dari garis keturunan ibu Laki-laki tertua dari garis keturunan
ibu.
Hal diatas merumuskan bahwa tanah ulayat nagari memilik aspek
publik yang penguasaan dan pengurusannnya dilakukan oleh ninik mamak
KAN (Kerapatan Adat Nagari). Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum
merupakan hak milik kolektif anggota suatu suku atau kaum. Sedangkan
tanah ulayat rajo merupakan tanah ulayat yang penguasaan dan
pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari dari garis keturunan ibu.
Tanah Ulayat Nagari di bawah pengawasan penghulu-penghulu
yang bernaung dalam kerapatan nagari. Tanah ulayat nagari adalah milik
bersama rakyat dalam nagari itu. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan-
hutan, semak belukar maupun tanah-tanah yang berada dalam lingkup dan
pengelolahan nagari. Nagari merupakan gabungan dari beberapa koto, yang
mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu. Pada umumnya di
dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari
dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari,
digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti
pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau
kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas
kesepakatyan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu.
Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu
diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum.
Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama. Kesepakatan pembagian
9

tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam
suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa
Melayu dan ditanda tangani bersama. Dapat juga status pemakaian tanah
ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.
Tanah ulayat suku, terpegang pada penghulu suku, dan dikelola
anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian
darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku
sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Dimana anggota suku itu
berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa
persaudaraan sesuku.
Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk
menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya
diawasi oleh kepala penghulu suku dan dia juga membawahi beberapa rumah
gadang milik kaum atau jurai. Mengingat begitu pentingnya tugas seorang
penghulu sebagai pemimpin dalam suatu suku, maka tidak semua laki-laki
dalam sukunya yang dapat diangkat menjadi penghulu suku melainkan
seorang laki- laki dewasa berilmu yang luas, baik dalam pengetahuan adat
maupun pengetahuan umum, adil, arif dan bijaksana serta sabar. Pada
mulanya suku di Minangkabauu berjumlah empat suku yaitu Bodi, Caniago,
Koto dan Piliang. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan
bertambahnya penduduk maka suku-suku di Minangkabau berjumlah lebih
kurang 96 suku diantaranya suku Tanjung, Jambak, Koto, Sikumbang, Guci,
Panyalai, Melayu, Banu Hampu, Kampai, Pitopang, Mandaliku, Sako dan
lain-lain.
Setiap orang Minangkabau mempunyai suku dan seorang yang
memiliki keturunan darah yang sama dianggap satu suku. Dalam adat
Minangkabau orang yang satu suku umumnya dilarang untuk menikah karena
dianggap mempunyai satu keturunan genelogis yang sama yaitu matrilineal
menurut garis keturunan ibu.
Setiap kaum, suku dan nagari di Minangkabau memiliki harta
pusaka yang dipelihara secara turun temurun dari satu generasi ke generasi
10

berikutnya. Harta pusaka ini merupakan tanggung jawab dari mamak waris
untuk memeliharanya. Harta pusaka ada yang berujud matrial disebut sako
yaitu berupa tanah, rumah dan barang-barang berharga lainnya. Disamping
itu juga ada harta pusaka yang bersifat immaterial yang berupa gelar
kebesaran suku yang diturunkan dari mamak (saudara laki-laki dari ibu) ke
kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan). Harta pusaka terutama
tanah yang merupakan milik komunal dalam suku bukan milik perorangan.
Tanah merupakan syarat yang pokok bagi orang Minangkabau. Dalam
pepatah adat dikatakan, bahwa orang yang tidak punya tanah dibumi
Minangkabau orang itu bukanlah asli daerah tersebut.
Tanah ulayat kaum, adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum
secara bersama. Kaum adalah gabungan dari pada paruik (seibu) yang berasal
dari satu nenek. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka tinggi yang
dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk
memenuhi ekonominya. Tanah ulayat kaum yang dimiliki secaral komunal
itu merupakan harta yang diberikan haknya kepada anggota kaum untuk
memungut hasilnya, sedangkan hak milik atas nama kaum tersebut. Harta ini
jika digadaikan harus mendapat persetujuan dari kepala kaum dan seluruh
anggota kaum lainnya.
Pengawasan tanah ulayat kaum atau harta pusaka tinggi ini,
merupakan tugas dari kepala kaum yang disebut tungganai (mamak rumah
yang dituakan) dalam jurai dan dihormati seperti yang diungkapkan dalam
pepatah adat didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang (didahulukan
selangkah dan ditinggikan seranting) oleh anggota kaumnya.
3. Penyebab Utama Terjadinya Sengketa Tanah Adat
Menurut Loockwood (dalam Soekanto dan Ratih, 1988)
menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat dapat berupa perbedaan
taraf kekuasaan yang dipegang individu dalam masyarakat, sumberdaya yang
terbatas, kepentingan yang tidak sama. Konflik dapat juga disebut sebagai
11

hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang
memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.7
Kasus pertanahan di Sumetera Barat dan khususnya di Talang Maur
Payakumbuh, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan
hak milik, pencegahan dan gangguan, serta tindakan kekerasan. Semua,
umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut
mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang-gadai
dan pewarisan adalah masalah utama yamg sering mendorong terjadinya
sengketa. Sebab sistem ekonomi ini umumnya dilakukan secara lisan ataupun
kalau ada surat bawah tanngan, kurang kuat keabsahannya sesuai dengan
perundang-undangan umum.
Semua itu tidak bisa lepas dari perubahan sosial ekonomi. Pada saat
sistem adat matrilineal mulai meluntur perlahan-lahan, dan masalah-masalah
ekonomi mulai mendesak maka tanah sebagai katup pengaman dalam
perekonomian sering menjadi masalah. Ada banyak model sengketa yang
terjadi, mulai dari perselisihan pebatasan nagari, perampasan sawah atau
kebun, pengkhianayan hak milik dan pengaduan ke penghulu, pengaduan ke
polisi, ke nagari, ke kecamatan serta ke pengadilan. Dalam hal ini tentu tidak
jarang terjadi tindakan kekerasan seperti perkelahian atau ada juga main
racun atau tubo.
Kasus perselisihan tanah diperbatasan nagari sering terjadi, hal ini
dipicu oleh antara lain tidak jelasnya batas-batas nagari, apabila diantara
kedua nagari dibatasi oleh jurang ataupun bukit, dimana masing warga nagari
sama ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk berladang, ataupun buat
menggembala ternaknya, hal ini bisa menimbulkan perkelahian antar
masyarakat kampung. Kasus perselisihan tanah sepadan (batas-batas), hal ini
disebabkan tidak jelasnya batas sepadan, antara tanah ulayat yang satu
dengan tanah yang lainnya, dimana masing-masing tanah tersebut sudah
7 Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, Fungsionalisme dan Teori Konflik. Jakarta: Gunung agung, 1988, hal 65.
12

terpisah nagarinya. Tidak berperannya masing-masing mamak kepala waris
serta tidak berfungsinya Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
Kasus warisan, karena tidak jelasnya ranji juga sering menimbulkan
sengketa antara para pewarisnya, hal mana yang penulis bahas juga terjadi di
Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Muara Panas, begitu kompleknya
masalah ini yang disamping menyangkut warisan juga ada hibah serta
menyangkut juga dengan sako (gelar adat), sehingga hal ini dipertanyakan
mengenai dapatkan diselesaikan oleh Nagari atau Kerapatan Adat Nagari.
B. PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ADAT YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU PADA
MASYARAKAT TALANG MAUR PAYAKUMBUH
Pemahaman mengenai sengketa dalam hal ini menurut kamus besar
bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan
perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum
adalah bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi
keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, perioritas
maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian
secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Didalam hukum perdata perkara dapat dibagi menjadi 2 (dua)
macam yaitu: perkara Voluntair dan perkara contentiosa, seperti yang
dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa yurisdiksi contentiosa yaitu
perkara sengketa yang bersifat partai(ada pihak penggugat dan tergugat) dan
juga perkara Voluntair, yaitu: gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada
pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.8
Dikaitkan dengan kearifan lokal Minangkabau di masyarakat
Talang Maur Payakumbuh pada dasarnya menganut sistem kekerabatan
matrilinial, yaitu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu
masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu.
8 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika,2010, hal. 28.13

Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota dari kaum
ibunya. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam sebagaimana
yang berlaku dalam sistem patrilineal. Nenek moyang minang kabau
meninggalkan warisan (harta) untuk generasi selanjutnya. Harta tersebut
dapat berupa bukan benda (tidak berwujud) dan benda (berwujud). Harta
yang tidak berwujud disebut sako itu ialah gala (gelar). Sedangkan harta
yang berwujud disebut pusako. Sako adalah milik kaum secara turun
temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material,
seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang
diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini menyebabkan sako menjadi hak
bagi laki-laki dalam kaumnya.
Sengketa harta pusaka tinggi berupa tanah ini disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain:
1. Karena pada waktu dahulu, sewaktu menggadaikan
ataupun meminjamkan harta pusaka tinggi, tidak
dituangkan dalam bukti tertulis. Hanya disaksikan oleh
beberapa orang saksi, sehingga seiringnya waktu yang terus
berjalan, saksi-saksi tersebut meninggal dunia dan anggota
kaum penerus lainnya mengalami kesulitan untuk menebus
harta pusaka tinggi itu.
2. Tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang
berbentu tanah, sehingga dapat menimbulkan
persengketaan antar kaum.
3. Tidak terjadinya kesesuaian antara ninik mamak dengan
kemenakan tentang pembagian harta pusaka tinggi.
4. Adanya klaim dari keturunan pihak/kaum yang menerima
gadaian tanah pusako tinggi dahulunya menyatakan kalau
tanah pusako tinggi itu telah dibeli oleh nenek moyang
mereka.
Karena pada dasarnya Pada Masyarakat Minangkabau harta yang
akan diwariskan tersebut dapat berupa:
14

a. Harta Pusako
b. Harta Pencaharian
Harta pusako dapat dibedakan lagi menjadi harta pusako tinggi
dan harta pusako randah. Harta pusako tinggi, terdiri dari sako dan pusako.
Sako biasanya berbentuk gelar kehormatan, sedangkan pusako berbentuk
tanah atau hak ulayat. Sako dan pusako diturunkan dari seorang mamak
kepada keponakannya. Harta pusako tinggi adalah harta yang telah diwarisi
lebih dari tiga generasi secara turun temurun sehingga bagi penerima harta
itu sudah kabur asal usulnya. Yang berhak mewarisi adalah para kemenakan
menurut garis ibu. Pewarisan harta pusako tinggi tersebut dilakukan secara
kolektif dan hak yang diperolah para ahli waris secara individual hanya
sebatas Hak Pakai. Sedangkan harta pusako randah/ Tanah pusaka rendah
adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruik berdasarkan
pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan pencaharian. Harta
pencaharian dibagi menurut hukum agama (Islam), sedangkan harta pusaka
tetap dimiliki oleh suku yang bersangkutan dan diwariskan. Ini merupakan
kesadaran baru bagi orang Minangkabau untuk mengurangi kekuasaan
penghulu dan mamak dalam keluarga. Sebab sebelumnya, pencaharian
seorang ayah melekat di rumah isteri tetap dikuasai oleh pihak keluarga
isteri termasuk mamak.9
Mengenai sengketa tanah juga disebabkan karena ketidak jelasan
silsilah keluarga juga dalm hal mawaris harta pusako (tanah adat). Sehingga
setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertangga
turun mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku, dan nagari. Jika
penyelesaian dalam kaum tidak dipoleh dapat diajukan ketingkat suku, dan
jika pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat diajukan ke
tingkat Kerapatan Adat Nagari.
Dapat diuraikan kembali bahwa sengketa dalam penyelesaiannya
dapt ditempuh melalui dua tahap, yaitu:
9 Hamka, Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Naim (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968, hal. 46
15

a. Litigasi
Yakni dengan mengajukan gugatan atupun permohonan kepada
pengadilan negeri yang didasari aturan-aturan hokum dari negara.
b. Non litigasi
Merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan konvensional
yang didasari atas kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak
yang bersengketa.
Dalam penulisan ini penulis mengupas mengenai penyelesaian
sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi
memiliki berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa serta memiliki
keunggulan daripada cara litigasi yakni”:
a. Sifat kesukarelaan dalam proses.
b. Prosedur yang cepat.
c. Keputusan non yudisial.
d. Prosedur yang rahasia (confidential).
e. Fleksibelitas yang besar.
f. Hemat waktu.
g. Hemat biaya.
h. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.
Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi:
a. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua
orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal
ataubersengketa saling melakukan kompromi atau tawar
menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau
sengketa untuk mencapai kesepakatan.
b. Mediasi
Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa diluar peradilan
yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi, bedanya
adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai
16

penengah ataumemfasilitasi mediasi tersebut yang biasa
disebut mediator.
c. Konsiliasi
Konsiliasi merupakan salah satu lembaga penyelesaian
diluar pengadilan yakni para pihak bersama-sama mencari
solusi terhadap sengketa mereka.
d. Arbitrasi
Arbitrasi adalah metode penyelesaian sengketa yang mirip
dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakn sebagai
“litigasi swasta” dimana yang memeriksa perkara tersebut
bukanlah hakim tetapi seorang arbiter.
Sengketa tanah pusaka tinggi di Minangkabau diselesaikan
menurut adat, yaitu secara musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan
pepatah, “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat”. Azas
musyawarah mufakat tersebut juga didasari oleh bajanjang naiak batanggo
turun. Tingkat peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan
berlakunya perda nomor 13 tahun 1983 adalah sebagai berikut:
a. Untuk sengketa yang terjadi dalam suatu kaum, maka
peradilannya terdiri atas tiga tingkat yaitu:
1. Tingkat kaum, pada tingkat ini sengketa diselesaikan oleh
mamak kepala waris.
2. Tingkat suku, jika sengketa dalam kaum tidak dapat
diselesaikan maka dapat diajukan ketngkat suku. Yang
diselesaikan oleh penghulu suku.
3. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), jika suatu
sengketa tidak dapat diselesaikan pada tingkat suku maka
dapat diajukan ke Kerapatan Adat Nagari.
b. Untuk sengketa yang terjadi antar kaum maka peradilannya terdiri
atas dua tingkatan yaitu:
1. Tingkat antar kaum, juka terjadi sengketa antar kaum
maka dapat diselesaikan oleh “penghulu nan ampek”
17

(penghulu yang empat).
2. Tingkat Kerapatan Adat Nagari, juka sengketa tidak dapat
diselesaikan dalam tingkat antar suku maka
penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui Kerapatan Adat
Nagari.
Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan
secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak
jarang terjadi dalam peradilan KAN, suatu keputusan diambil tiga kali
sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan
sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan,
merupakan suatu keputusan (vonis) bersifat tetap atau hasil akhir suatu
persengketaan.
Prosedur persidangan sampai dengan pengambilan keputusan,
KAN, sebagai berikut:
a. Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
b. Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan
adat.
c. Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota
sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah,
keinginan pihak penggugat, dsb.
d. Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak
e. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana
hal diatas.
f. Kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji
oleh KAN dengan ketentuan sidang:
1) Tiga kali sidang untuk penggugat
2) Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali
sidang sebagaimana penggugat
3) Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat,
terjadi daksaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang
18

NO TAHUNPIHAK YANG
BERSENGKETASUKU
JUMLAHSENGKETA
KETERANGAN PUTUSAN
1 02 Maret 2006 Si Er dan Khaidar Caniago 2 Diterima Kedua belah Pihak2 30 Juni 2007 Imih dan Ati Piliang
2Diterima Kedua belah Pihak
3 04 Agustus 2007 Izel dan Si Na Kampai dan Dalimo Diterima Kedua belah Pihak4 25 Juli 2009 Sosmina dan Sumar Dalimo 1 Diterima Kedua belah Pihak5 12 Mei 2012 Yusmar dan Mansur Kampai
2Diterima Kedua Belah Pihak
6 16 Juni 2012 Tuti Hasni dan Si Er Caniago Diterima Kedua Belah Pihak7 09 November 2013 Asti Neka dan Si Har Dalimo dan Kampai 2 Diterima Kedua Belah Pihak
Jumlah 9
diajukan selama persidangan berlangsung.
4) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun
berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan.
5) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara.
6) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala
Rukun Tetangga (RT) dan Lurah.
g. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya
karena ibarat pepatah ”sudah siang hari, sudah nampak bulan” telah jelas
dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan keputusan (vonis)
berupa kesimpulan.
Keputusan atau kesimpulan yang diambil majelis hakim dalam
KAN dapat berupa :
1) Mengabulkan gugatan, jika gugatan terang (jelas)
2) Memenangkan tergugat jika gugatan tidak terang
3) Jika dalam perkara itu keterangan para pihak sama kuat maka
dianjurkan untuk melaksanakan pembagian harta tersebut sama
banyak
4) Hukum bersumpah, jika persengketaan pembagian harta sama
banyak tidak dapat dilakukan karena para pihak tidak mau
melaksanakan, maka melalui sumpah ini salah satu pihak akan
melepaskan harta tersebut.
Tabel 1: Jenis Sengketa Pusako Tinggi (tanah adat) pada Kantor
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur yang terselesaikan
Sumber: Kantor KAN Kenagarian Talang Maur
19

Tabel 2 : Jenis Sengketa Pusako Tinggi (tanah adat) pada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang Maur yang tidak terselesaikan
NO TAHUNPIHAK YANG
SUKUJUMLAH
KETERANGAN PUTUSANBERSENGKETA SENGKETA
1 28 Juli 2006 Rusna dan Kulih Picancang dan Dalimo 1 Tidak diterima dan dilanjutkan ke pengadilan2 10 November 2013 Akam dan Niar Picancang 2 Tidak diterima dan dilanjutkan ke PengadilanJumlah 3
Sumber: Kantor KAN Kenagarian Talang Maur
Data tabel diatas dapat penulis uraikan, bahwa Kerapatan Adat
Nagari (KAN) dalam menjalankan peranannya dalam menyelesaikan
semua sengketa yang dilaporkan ke Kantor kerapatan Adat Nagari
Kenagarian Talang Maur dapat terselesaikan dengan baik oleh Lembaga
Peradilan Adat. Dari sebelas sampel kasus diatas Sembilan diantaranya
diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Adat Nagari dan dua diantara
sengketa dilanjutkan atau diajukan oleh pihak yang bersengketa ke
Pengadilan Negeri. Sehingga kearifan lokal disini lebih dikedepankan dari
pada hukum normatif dalam penyelesaian sengketa tanah Adat (tanah
ulayat).
20

PENUTUP
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyebab timbulnya sengketa tanah di Talang Maur Payakumbuh
disebabkan karena tidak jelasnya silsilah, sehingga hal tersebut
mengakibatkan beberapa pihak yang merasa bahwa kepada dialah harta
pusaka tinggi yaitu tanah tersebut berhak diwariskan, seseorang mewariskan
hasil jerih payahnya yang telah didirikan atau berada di atas tanah kaum
istrinya kepada anak-anaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan
nantinya harta warisan tersebut akan disangka sebagai harta pusaka kaum
istrinya atau menjadi harta pusako randah dan harta pusaka tinggi tersebut
di jual oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan anggota kaum yang
bersangkutan. Serta anggota masyarakat di dalam kaum di Talang Maur
tidak mengetahui atau kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang
berlaku.
2. Dalam penyelesaian perkara sengketa tanah yang terjadi di Talang Maur
Payakumbuh yang menggunakan kearifan lokal minangkabau tercermin dari
peran Kerapatan Adat Nagari ( K A N ) di Kenagarian Talang Maur yang
berfungsi sebagai penengah atas setiap sengketa-sengketa yang berkaitan
dengan sengketa tanah pusako tinggi di Kenagarian Talang Maur. KAN
berfungsi untuk menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi yang mana
sebelum lanjut ketingkat KAN para pihak telah melakukan langkah
penyelesaian dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat di tingkat
Paruik, Kaum, Suku dan Sudut. KAN dapat bertindak sebagai penengah
dalam menyelesaikan sengketa apabila langkah tersebut telah di tempuh
para keluarga yang bersengketa dan tidak menemukan penyelesaiannya
Sehingga kearifan lokal disini lebih diunggulkan untuk didahulukan dalam
menyelesaikan masalah dalam masyarakat.
21

DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Harahap, M. Yahya, 2010, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
Hamka, 1968, Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Naim
(Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris, Padang: Center For
Minangkabau Studies Press.
Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1978, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang
dan Pidato Dua Di Minangkabau, Bandung: Remaja Karya.
Muhammad. Bushar, 2000, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudiyat. Iman, 1918, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty.
Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, 1988, Fungsionalisme dan Teori Konflik.
Jakarta: Gunung agung.
Ter. Haar, 1999, Asas–asas dan susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya
Paramita.
22