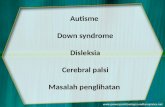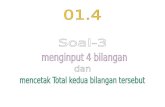jawabn (2)
-
Upload
muchtarul-barry -
Category
Documents
-
view
65 -
download
0
Transcript of jawabn (2)
NO.5 Pendahuluan Komunisme sebagai sebuah ideologi sering kali disalahtafsirkan. Sebagai sebuah ideologi, komunisme sering dianggap berbahaya. Akan tetapi, ada kalanya serangan-serangan yang ditujukan kepada ideologi ini tidak tepat. Hal ini terjadi karena kritik yang dilontarkan itu hanya didasarkan pada prasangka belaka. Mereka yang melakukan kritik sering kali tidak paham sama sekali terhadap komunisme. Mereka cenderung jatuh pada simplifikasi bahwa komunisme itu jahat dan ateis. Akibatnya kesimpulan bahwa komunisme itu jahat, berbahaya, dan ateis menjadi tidak relevan karena tidak didasarkan pada argumentasi logis dan kritis tapi hanya didasarkan pada prasangka belaka. Oleh sebab itu, penting sekali mempelajari komunisme dengan menanggalkan segala prasangka. Tujuannya agar kita bisa memahami ideologi ini secara an sich, apa adanya. Sehingga jikalau pun ideologi ini dianggap tidak memiliki kegunaan secara praktis dan buruk, maka kritik dan penolakan terhadapnya pun bisa dilakukan secara bertanggung jawab. Sebagai sebuah ideologi, komunisme memiliki berbagai macam argumen yang mendasari fondasi bangunannya. Akan tetapi, secara garis besar komunisme berbicara mengenai ekonomi politik sebagai dasar bagi perubahan sosial masyarakat. Di dalam komunisme dikenal dua bangunan utama yang menjadi fondasi struktur masyarakat yaitu suprastruktur (bangunan atas atau uberbau) dan infrastruktur (bangunan bawah atau basis). Bangunan atas terdiri dari agama, negara, dan ideologi. Sedangkan bangunan bawah terdiri dari struktur kekuasaan ekonomis dimana terdapat hubungan produksi material dari kelas yang saling bertentangan yaitu buruh dan majikan. Untuk mengubah keadaan sosial maka, menurut komunisme, yang harus diubah adalah bangunan bawah (basis) yaitu perubahan struktur kekuasaan ekonomi kapitalis ke struktur kekuasaan ekonomi sosialis komunis. Apabila bangunan bawah (basis) ini telah berubah, maka niscaya bangunan atas (uberbau) pun akan ikut berubah. Perubahan bangunan bawah (basis) ini dilakukan melalui perjuangan kelas, yaitu pertentangan (konflik) antara dua kelompok yang bertentangan dalam relasi struktur ekonomi yaitu buruh dan majikan. Perjuangan kelas ini bisa dimulai apabila telah munculnya kesadaran kelas, yaitu suatu kondisi dimana para buruh menyadari
ketertindasannya sebagai objek penghisapan para majikan yang memiliki alat-alat produksi. Akan tetapi, para majikan selalu berusaha agar para buruh ini tidak memiliki kesadaran kelas yang akan berujung pada perjuangan kelas dan perubahan relasi ekonomi. Para majikan selalu berusaha meninabobokan para buruh untuk melanggengkan relasi ekonomi yang menguntungkan mereka dan menghisap para buruh. Salah satu cara meninabobokan para buruh ini adalah dengan agama. Dari sinilah kritik terhadap agama muncul dan ungkapan agama sebagai candu masyarakat bermula. Agama Sebagai Candu Masyarakat Kritik Karl Marx (sebagai pendiri komunisme) terhadap agama sebagai penghambat bagi kesadaran kelas didasari dari pemikiran Feuerbach. Feuerbach mengatakan bahwa perkara-perkara rohani (agama) itu sebenarnya tidak nyata dan hanya berada dalam alam pikiran. Tuhan tak lain dari ciptaan manusia belaka. Manusia memandang dirinya sebagai makhluk yang tidak sempurna dan lemah, kemudian ia memproyeksikan dirinya tersebut ke dalam sosok Tuhan yang memiliki sifat yang lain sekali dengan manusia. Apabila manusia tidak sempurna, maka Tuhan mahasempurna. Apabila manusia lemah, maka Tuhan mahakuat. Oleh sebab itu, Tuhan tidak lain hanya proyeksi (gambaran) manusia itu sendiri. Maka Tuhan pun sering disifati sebagai sama dengan manusia (antropomorfis), hanya saja sifatnya tersebut Maha. Tuhan dianggap memiliki kehendak, sama dengan manusia. Tuhan dianggap memiliki keinginan, sama dengan manusia. Secara ringkas, Tuhan adalah pantulan manusia itu sendiri yang sedang mencari seorang sosok manusia super di dalam kenyataan fantasi surgaloka. Dan Tuhan tidak lain dari sosok manusia super itu sendiri. Akan tetapi, Feuerbach tidak menjelaskan mengapa manusia harus lari ke alam fantasi dan menciptakan Tuhan sebagai proyeksi dirinya? Lalu bagaimana mengatasi keterasingan manusia dalam agama? Di sinilah Marx berperan. Menurut Marx, alasan mengapa manusia lari ke dalam alam fantasi agama terjadi karena keadaan miskin masyarakat yang menciptakan suasana represif terhadap manusia. Kemiskinan (akibat kapitalisme) membuat manusia tidak bisa mengembangkan dirinya. Oleh sebab ketertekanan hidup inilah, manusia kemudian lari ke dalam dunia khayalan (scheinwelt), alam surga dimana Tuhan berada. Menurut
Marx, agama adalah keluh kesah makhluk yang tertekan, perasaan dari dunia yang tak berhati... Masyarakat ini menciptakan agama.Dengan agama manusia bisa melarikan diri dari keadaannya yang miskin. Hanya saja agama kemudian meninabobokan masyarakat lewat khayalan surgawi. Kemiskinan yang dialami dianggap sebagai takdir dan atau ujian, yang apabila dihadapi dengan tabah maka akan memperoleh imbalan surga dan pahala. Agama membuat kondisi buruk masyarakat seolah-olah merupakan kehendak Tuhan, bukan akibat ketidakadilan dalam relasi ekonomi kapitalis yang menghisap. Alih-alih berjuang mengubah nasibnya, manusia kemudian terjerembab ke dalam ritus-ritus dan doa-doa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Agama menjadi candu bagi masyarakat. Agama tidak bersifat emansipatoris yang mampu membebaskan manusia dari keadaan miskinnya. Agama meninabobokan orang lewat khayalan surgawi. Seperti candu, agama membuat orang terlena dalam fantasi. Candu (dalam hal ini analogi untuk agama) diberikan oleh kelas kapitalis kepada kelas buruh untuk melanggengkan kekuasaannya. Sehingga kelas buruh menjadi tidak sadar akan kondisi ketertindasannya karena menganggapnya sebagai nasib dan takdir. Apabila kesadaran kelas ini tidak timbul, maka mustahil perjuangan kelas juga bisa terlaksana. Apabila perjuangan kelas tidak terlaksana, maka mustahil timbul perubahan sosial. Agama akan menghambat munculnya kesadaran kelas yang akan menimbulkan perjuangan kelas yang berujung pada perubahan bangunan bawah (basis) struktur masyarakat. Marx berpendapat, bangunan bawahlah (basis) yang perlu untuk diubah. Perubahan bangunan bawah ini akan otomatis menyebabkan perubahan pada bangunan atas (uberbau) struktur masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Marx, apabila masyarakat sudah mencapai kondisi yang makmur dan sejahtera secara merata di dalam suatu masyarakat komunis maka agama akan hialng dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan masyarakat komunis memungkinakan semua manusia mengembangkan dirinya dan tidak mengizinkan adanya penghisapan manusia yang satu terhadap manusia lainnya di dalam relasi ekonomi. Penutup Kritik agama Marx ini sebenarnya tidak menyerang esensi agama itu sendiri. Marx justru menyerang praktik-praktik keberagamaan
manusia. Marx menyerang kemandulan agama yang tidak mampu membebaskan manusia dari kondisinya yang buruk. Apabila dicermati secara seksama, kritik Marx terhadap agama ini ada benarnya dan bahkan masih relevan hingga saat ini. Agama cenderung menjadi candu. Agama menuntut kepatuhan total terhadap dogma dan ajarannya. Tetapi pada saat yang sama agama tidak mampu memperbaiki kondisi buruk masyarakat. Perilaku beragama kemudian hanya menjadi ritus belaka. Ajaranajaran dan etika agama tidak dijalankan dalam kehidupan praktis. Akibatnya agama tidak membebaskan malah sering dianggap membelenggu dan melanggengkan status quo masyarakat yang buruk. Daftar Pustaka: Boangmanalau, Singkop Boas. (2008). Marx, Dostoievsky, Nietzsche: Menggugat Teodisi dan Merekonstruksi Antropodisi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Elster, Jon. (2000). Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Ramly, Andi Muawiyah. (2009). Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materlisme Historis. Yogyakarta: LKIS. Tjahjadi, SP. Lili. (2010). Karl Marx dan Masalah Agama sebagai Opium. Bahan kuliah Extension Course Filsafat STF Driyarkara Jakarta. Semester Genap 2009-2010.
NO.4 Ibn Khaldun : Solidaritas sosial, Monopolitik, dan Syarat PemimpinDalam buku Muqadimmah karya Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Khaldun atau Ibn Khaldun, menyatakan runtuh atau kokohnya suatu kekuasaan sangat tergantung pada ashabiyah (solidaritas sosial). Konsep ashabiyah ini, menyiratkan perlunya ruang bagi konflik kepentingan antar-penguasa dan yang dikuasai sehingga kedua belah pihak saling memiliki posisi tawar menawar untuk mencapai kepentingan yang saling menguntungkan. Konflik kepentingan yang bersifat internal atau eksternal selalu berakibat kepada perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga solidaritas social harus merupakan alat perjuangan dan alat penyelesaian persoalan tanpa kekerasan. Kuat lemahnya kekuasaan suatu pemerintahan pun akan sangat tergantung kepada ikatan solidaritas sosial. Tetapi apabila, solidaritas sosial ini, dikerdilkan atau bersifat monopolitik, dimana hanya segelintir orang atau kelompok tertentu (hanya sebatas hubungan keluarga atau kekerabatan maupun kelompoknya) yang dekat kekuasaan sajalah yang mendapatkan
kue-kue kekuasaan, hal ini, menurut Ibn Khaldun menjadi embrio bagi keruntuhan suatu kekuasaan. Karena hal tersebut, menjadikan penguasa lupa terhadap kewajibannya menjalankan amanat rakyat. Menurut Ibn Khaldun, ada enam syarat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Ke enam syarat itu : Pertama, ia harus berpengetahuan dan memiliki kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan hukum. Ke dua, ia harus memiliki sikap dan perilaku jujur, berpegang teguh kepada keadilan, sifatsifat moral yang baik sehingga perkataan dan tindakannya dapat dipercaya. Ke tiga, bahwa ia mempunyai kesanggupan dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya sebagai kepala negara termasuk melaksanakan hukum yang diputuskan secara konsekwen. Ke empat, ia secara fisik dan mental harus bebas dari cacat yang tidak memungkinkan ia menjalankan tugas sebagai kepala negara dengan baik. Ke lima, kepala negara harus dipilih dari bangsa sendiri. Ke enam, seorang pemimpin itu harus lemah lembut dan sopan santun terhadap pengikutnya, dan harus mengutamakan kepentingan pengikut serta harus membela mereka sehingga ia tidak mencari-cari kesalahan rakyat. Masyarakat beragama itu bukan saja memerlukan rasa solidaritas sosial (ashabiyah) untuk menghadapi lawan, tetapi Ibn Khaldun tidak membenarkan bila rasa solidaritas sosial (ashabiyah) itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan hidup yang berlainan daripada yang dikehendaki agama, misalnya untuk kemegahan, untuk menikmati kemenangan yang diperoleh tanpa memperhitungkan batas-batas yang harus dipegang, ini baginya berlawanan dengan yang diingatkan Nabi.
NO.3
KARL MARX Dan EMILE DURKHEIM
Marx tidak semata-mata menjadi seorang komunis dengan begitu saja. Banyak tokoh yang ikut andil dan berperan dalam menjadikan Marx seorang yang berpandangan komunisme, antara lain Hegel, Feuerbach, Smith, juga Engels. Keempatnya, terutama filsafatnya Hegel, Feuerbach dan Engels, sangat kental mewarnai pemikiran Marx. Secara spesifik memang filsafatnya Hegel, yaitu yang berkaitan dengan konsep dialektik, menjadi titik tolak pemikiran Marx meskipun Marx mengkritisi filsafat itu karena dianggapnya sangat idealistik dan memiliki konsep yang terbalik. Marx sendiri mengemukakan konsep dialektika materialistik yang mengacu kepada berbagai struktur sosial yang di dalamnya tercermin konflik sosial dan juga menggambarkan upaya-upaya pembebasan atas eksploitasi para majikan kepada kaum buruh dalam semua proses produksi. Marx, juga menyoroti perkembangan dan kebangkitan
kapitalisme, di mana pandangan-pandangannya dianggap identik dengan gerakan pembebasan kaum buruh yang miskin dan tertindas oleh mereka yang memiliki berbagai sarana produksi, yaitu kaum borjuis. Konflik atau pertentangan kelas serta upaya-upaya pembebasan inilah yang menjadi titik sentral ajarannya Marx. Dialektika dan Struktur Masyarakat Kapitalis Perkembangan pemikiran Marx memang tidak lepas dari pengaruh filsuf-filsuf hebat seperti Hegel, Feuerbach, Smith, juga Engels. von Magnis membagi lima tahap perkembangan pemikiran marx yang dibedakan ke dalam pemikiran Marx muda (young Marx) dan Marx tua (mature Marx). Gagasan dan pemikirannya terutama diawali dengan kajiannya terhadap kritik Feuerbach atas konsep agamanya Hegel yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Marx yang materialistik benar-benar menolak konsep Hegel yang dianggapnya terlalu idealistik dan tidak menyentuh kehidupan keseharian. Bagi Marx, agama hanya sekedar realisasi hakikat manusia dalam imajinasinya belaka, agama hanyalah pelarian manusia dari penderitaan yang dialaminya. Agama inilah yang merupakan simbol keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Marx mengadopsi sekaligus mengkritisi dialektikanya Hegel yang dianggapnya tidak realistik itu. Marx juga menganggap filsafatnya Hegel, yang idealistik itu, memiliki konsep yang terbalik. Atas hal ini, Marx mengemukakan konsep dialektika materialistik yang mengacu kepada berbagai konsep struktur sosial. Dimana di dalamnya tercermin konflik sosial dengan yang menggambarkan upayaupaya pembebasan atas eksploitasi para majikan kepada kaum buruh dalam semua proses produksi yang melibatkan dua kelas sosial yang berbeda, proletar dan borjuis. Kelas sosial inilah yang nantinya harus tidak ada karena, menurut Marx, pada suatu saat akan terwujud masyarakat komunisme; yaitu masyarakat sosialis karena runtuhnya kapitalisme, di mana di dalamnya tidak ada lagi kelas-kelas sosial dan tidak ada lagi hak kepemilikan pribadi. Inilah masyarakat yang menjadi obsesi Marx. Untuk mewujudkan hal ini, menurutnya, perlulah dilakukan analisis terhadap sistem ekonomi kapitalis. Durkheim dan Fakta Sosial Durkheim yang dikenal taat pada agama tetapi sekuler itu, dalam perjalanan karirnya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat dan sosiologi, seperti Montesquieu, Rosseau, Comte, Tocquueville, Spencer, dan Marx. Durkheim menyoroti solidaritas sosial sampai patologi sosial yang juga mengkaji tentang kesadaran bersama, morfologi sosial, solodaritas mekanik dan organik, perubahan sosial, fungsi-fungsi sosial, termasuk solidaritas dan patologi sosial. Durkheim memang berangkat dari asumsi bahwa sosiologi itu merupakan studi mengenai berbagai fakta sosial di mana di dalamnya ia menguraikan mengenai konsep sosiologinya serta berbagai karakteristik dari fakta-fakta sosial dimaksud. Ia juga menjelaskanmengenai cara-cara mengobservasi berbagai fakta sosial dengan melakukan analisi
sosiologis. Sedangkan mengenai fenomena moralitas yang menyangkut berbagai keyakinan, nilai-nilai, dan dogmadogma (yang membentuk realitas metafisik) ia dekati juga dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Durkheim memang sepaham dengan pemikiran Comte bahwa ilmu pengetahuan itu haruslah dapat membuat manusia hidup nyaman. Upayanya untuk memahami berbagai fenomena bunuh diri melahirkan salah satu karya besarnya Suicide (Bunuh Diri)
Bunuh Diri, Agama, dan Moralitas Bagi Durkheim, bunuh diri, yang bermacam-macam bentuk (egoistic suicide, altruistic suicide, anomic suicide, dan fatalistic suicide), itu memang merupakan penyimpangan perilaku seseorang. Bagaimana bunuh diri itu terjadi atau dilakukan oleh seseorang, menurut Durkhiem, disebabkan oleh benturan dua kutub integrasi dan regulasi di mana kuat dan lemahnya kedua kutub itu akan menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Di sinilah, begitu Durkheim menekankan, pentingnya agama bagi seseorang untuk menghindarkan dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. di mana unsur-unsur esensial dari agama itu mencakup berbagai mitos, dogma, dan ritual, yang kesemuanya merupakan fenomena religius yang dihadapi manusia. Dalam kaitan ini, ada hal-hal yang sifatnya suci (sacred) dan juga ada hal-hal yang sifatnya tidak suci (profane) yang pemisahan antara keduanya menunjukkan kepada pemikiran-pemikiran religius yang dilakukan manusia. Harus diperhatikan bahwa di dalam agama, khususnya yang menyangkut ritual keagamaan, ada yang dinamakan ritual negatif dan juga ritual positif. Bagi Durkheim, moralitas itu merupakan suatu aturan yang merupakan patokan bagi tindakan dan perilaku manusia (juga dalam berinteraksi). Konsepnya mengenai moralitas ini merujuk pada apa yang dinamakan norms (norma-norma) dan rules (aturanaturan) yang harus dijadikan acuan dalam berinteraksi. Sumber Buku Teori Sosiologi Klasik Karya Boedhi Oetoyo, dkk.
NO.21.
ETIKA PROTESTAN (MAX WEBER)
ETIkA PROTESTAN (MAX WEBER)
Weber dilahirkan di Erfurt 1864 sebagai anak tertua dari delapan orang bersaudara. Ayahnya seorang otoriter sedangkan ibunya adalah seorang saleh yang teraniaya. Oleh karena itu, terjadi cekcok hebat antara Max Weber dengan a s eh i n gg a d i a m en g u s i r a y a h n y a . Ia
lebih banyak dipengaruhi paman clan tantenya. Webermengecap berbagai pendiclikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia meraih gelar doktor dalam studi organisasi clagang Abad Pertengahan. la diangkat jadi guru besar dalam studi sejarah agraria Romawi di Berlin serta menjadi guru besar ekonomi di Freiburg 1894 clan 1896 di Heidelberg. Meskipun Marx dan para pengikutnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke20 setae berada di luar arus utama sosiologi Jerman, pada batas-batas tertentu arch perkembangan sosiologi Jerman awal dapat dikatakan berlawanan dengan teori Marxian. Weber dan Marx. Albert Salomon, misalnya, menyatakan bahwa teori-teori awal sosiolog besar Jerman, Max Weber, berkembang "dalam perdebatan panjang dan melelahkan dengan hantu Marx" (1945: 596). Mungkin ini terlalu dibesarbesarkan, namun dalam banyak hal teori Marxian memang memainkan pecan negatif dalam teori Weberian. Namun, dalam hal lain, Weber justru bekerja di dalam tradisi Marxian, di mana dia mencoba "melengkapi" teori Marx. Selain itu juga, banyak pengaruh lain selain teori Marxian yang memasuki teori Weberian (Burger, 1976). Kita dapat mengklarifikasi sumber-sumber sosiologi Jerman yang memaparkan pandangan masing-masing tentang hubungan antara Marx dan Weber (Antonio dan Glassman, 1985; Schroeter, 1985). Hams diingat bahwa Weber tidak terlalu terbiasa dengan karya Marx (yang sebagian besar belum diterbitkan sampai meninggalnya Weber) dan Weber lebih banyak menanggapi karya-karya kalangan Marxis daripada karya Marx sendiri (Antortio, 1985: 29; Turner, 1981: -20).
Dalam The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Webermenyatakan bahwa keteliteian yang khusus, perhitungan dan kerja keras dari Bisnis Barat didorong oleh perkembangan etika Protestan yang muncul pada abad ke- 16 dan digerakkan oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan keeclakaan. Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah seorang yang terpilih. Dalam kondisi seperti mi menurut Weber, pemeluk Calvinisme mengalami
"panikterhadap keselamatan." Cara untuk menenangkan kepanikan tersebut adalah orang harus berpikir bahwa seseorang tidak akan berhasil tanpa diberkahi Tuhan. Oleh karena itu keberhasilan adalah tanda dari keterpilihan. Untuk
mencapai keberhasilan, seseorang harus melakukan aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan politik, yang dilandasioleh disiplin clan bersahaja, menjauhi kehidupan bersenangsenang, yang didorong oleh ajaran keagamaan.
Menurut Weber etika kerja dari Calvinisme yang berkombinasi dengan semangat kapitalisme membawa masyarakat Barat kepada perkembangan masyarakat kapitalis modern. Jadi, doktrin Calvinisme tentang takdir memberikan days dorong psikologis bagi rasionalisasi clan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap pembentukannya.
Hubungan antara semangat kapitalisme dan etika Protestan, oleh karena itu, memiliki kaitan konsistensi logic dan pengaruh motivasional yang bersifat menclukung secara timbal balik. Hubungan semacam itu disebut sebagai elective affinity. Hubungan tersebut menghantarkan kapitalisme mentransformasi din dalam bentuk modern, yang bercirikan: tata buku/akuntansi rasional, hukum rasional,
teknik rasional (mekanisasi), clan massa buruh menerima upah di pasar bebas karena mereka perlu untuk memperoleh penghasilanWeber memang cenderung memandang Mars dan kaum Marxis pada zamannyaSebagai determines ekonomi yang menawarkan teori sebab tunggal kehidupan sosial. Jade, teori Marxian mereka pandang sebagai teori yang hanya melacak seluruh perkembangan historis ke dalam basis ekonomi dan melihat seluruh struktur dibangun di atas basis ekonomi saja. Meskipun tidak berlaku pada teori Marx sendiri (seperti akan kita baca pada Bab 2), ini merupakan pendapat sebagian besar pemikir Marxis yang lebih belakangan. Salah satu contoh determinisme ekonomi yang tampaknya paling tidak disukai Weber adalah pandangan bahwa ide hanyalah refleksi dari kepentingan material (kbususnya ekonomi), bahwa kepentingan material menentukan ideologi. Dari sudut pandang ini, Weber dianggap telah "membalikkan Marx" (persis seperti Marx telah membalikkan Hegel). Alih-alih berfokus pada faktor ekonomi dan efeknya pada ide, Weber lebih mencurahkan perhatiannya pada ide dan efeknya bagi ekonomi. Ketimbang memandang ide sebagai refleksi sederhana dari faktorfaktor ekonomi, Weber memandang keduanya sebagai kekuatan otonom yangmampu memengaruhi dunia ekonomi. Weber sangat menaruh perhatian pada masalah gagasan-gagasan, terutama sistem gagasan keagamaan, dan dia secara khusus membahas dampak gagasan-gagasan keagamaan pada ekonomi. Dalam buku The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904-05/1958), ia memberikan perhatian pada agama Protestan, terutama sebagai sistem ide, dan dampaknya terlhadap, kelahiran sistem gagasan lain, "semangat kapitalisme", dan pada akhirnya, dampak yang ditimbulkannya terhadap sistem ekonomi. Weber memiliki minas serupa terhadap agama-agama dunia lainnya, dengan melihat bagaimana sifat agama-agama
tersebut menghambat perkembangan kapitalisme pada masyarakat tempat agamaagama tersebut tumbuh. Berdasarkan karya ini, beberapa orang ilmuan sampaipada kesimpulan bahwa Weber mengembangkan gagasan yang bertentangan dengan gagasan Marx. Pandangan kedua tentang hubungan Weber dengan Marx, sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, adalah bahwa ia sebetulnya tidak berlawanan dengan Marx karena ia justru mencoba melengkapi perspektif teoretisnya. Dalam hal ini Weber dipandang lebih banyak bekerja di dalam tradisi Mandan daripada
menentangnya. Karyanya tentang agama, yang ditafsirkan dari sudut pandang ini, adalah upaya untuk menunjukkan bahwa bukan hanya faktor materi yang memengaruhi ide, namun ide juga memengaruhi struktur materi. Contoh yang baik dari pandangan ini adalah bahwa Weber terhbat dalam proses melengkapi teori Mandan dalam teori stratifikasi. Dalam karyanya tentang stratifikasi, Marx memusatkan perhatiannya pada kelassosial, yakni dimensi ekonomi dari stratifikasi sosial. Meskipun Weber menerima and penting faktor ini, namun ia berpendapat bahwa dimensi-dimensi stratifikasi lain pun sama pentingnya. Menurut dia, pengertian stratifikasi sosial ini harus diperluas sehingga mencakup stratifikasi yang didasarkan pada prestise (status) dan kekuasaan. Dimasukkannya dua dimensi ini tidak became penolakan atas Marx namun justru melengkapigagasan-gagasannya. Kedua pandangan yang disinggunk di atas mengakui arti penting teori Marxian bagi Weber. Kedua posisi tersebut sama-sama benar; di beberapa titik tertentu, Weber memang menentang Marx, sementara itu di titik lain, ia memperluas gagasan Marx. Namun, pandangan ketiga dari masalah ini memberikan penjelasan yang lebih baik perihal hubungan Marx dengan Weber.
Pandangan yang terakhir ini, memandang Marx hanya sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pemikiran Weber. 2. PENGARUH- PENGARUH LAIN TERHADAP PEMIKIRAN WEBER Kita dapat meng- idetifikasi sumber-sumber teori Weberian
termasuk sejarawan, filsuf, ekonom, dan teoretisi politik Jerman. Di antara pemikir yang paling menonjol pengaruhnya terhadap Weber adalah filsuf Immanuel Kant (17241804). Namun kita tidak boleh mengesampingkan dampak Friedrich Nietzsche (18441990) (Antonio, 2001) -khususnya penegasannya tentang pahlawan- terhadap karya Weber tentang kebutuhan individu untuk melawan dampak birokrasi dan struktur lain masyarakat modern. Pengaruh Immanuel Kant terhadap Weber dan sosiologi Jerman pada umumnya menunjukkan bahwa sosiologi Jerman dan Mar)dsme tumbuh dari akar-akar filosofis yang berlainan. seperti telah kita ketahui, adalah Hegel, bukan Kant, yang memberikan pengaruh filosofis penting pada teori Marxian. Kalau filsafat Hegel mendorong Marx dan kalangan Marxis lain untuk mencari hubungan, konflik, dan kontradiksi, maka filsafat Kantian paling tidak menggiring beberapa orang sosiolog Jerman untuk mengambil perspektif yang lebih statis. Bagi Kant, dunia tersusun dari sejumlah peristiwa membingungkan yang tidak dapat diketahui secaralangsung. Dunia ini hanya dapat diketahui dengan proses pemikiran yang menyaring, memilih, dan
mengategorikan peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh Kant, isi dunia nyata dibedakan dari bentuk yang digunakan untuk memahami isinya. Penekanan pada bentuk ini memberi karya-karya sosiolog dalam tradisi Kantian kualitas yang lebih statis bila dibandingkan dengan filsafat Marxis dalam. tradisi Hegelian.
Teori Weber. Kalau Karl Marx menawarkan teori tentang kapitalisme, maka karya Weber merupakan teori tentang proses rasionalisasi (Brubaker, 1984; Kalberg, 1980, 1990, 1994). Weber tertan.k pada pertanyaan umum mengapa institusi di dunia Barat tumbuh begitu progresif ke arah rasional, sementara sejumlah hambatan yang begitu kuat tampak mencegah perkembangan serupa di belahan dunia lain. Meskipun rasionalitas digunakan dalam berbagai pengertian yang berlainan dalam karya Weber, yang menjadi minas kita dalam pembahasan ini adalah proses yang melibatkan salah satu dari empat tipe yang diidentifikasikan oleh Kalberg (1980, 1990, 1994; baca juga Brubaker, 1984; Levine, 1981a), yakni rasionalitas formal. Rasionalitas formal, sebagaimana yang dipahami Weber, meliputi perhatian pada aktor yang memilih sarana dan tujuan. Namun, dalam hal ini, pilihan tersebut dijadikan sebagai rujukan bagi aturan, regulasi, dan hukum yang berlaku secarauniversal. Pada gilirannya, rasionalitas formal ini berasal dari struktur yang skalanya lebih besar, khususnya birokrasi dan ekonomi. Weber mengembangkan teorinya dalam konteks banyaknya kajian perbandingan sejarah Barat, Cina, India, dan kawasan-kawasan lain di dunia. Dalam, studi-studi ini, ia berusaha menguraikan sejumlah faktor yang membantu mendorong atau merintangi perkembangan rasionalisasi. Weber melihat birokrasi (dan proses historis birokratisasi) sebagai contoh klasik rasionalisasi, namun kini rasionalisasi sangat tepat bila diilustrasikan oleh restoran cepat saji (Ritzer, 2000a). Secara formal, restoran cepat saji adalah sistem rasional di mana (pelayan dan pelanggan) digiring untuk mengupayakan sarana paling rasional dalam mencapai tujuan. Jendela drive-
through, misalnya, adalah sarana rasional di mana pelayan dapat menyuguhkan, dan pelanggan dapat mengambil, makanan secara cepat dan efisien. Kecepatan dan efisiensi ditunjukkan oleh restoran cepat saji dan aturan Berta regulasi yang menjalankannya. Weber meletakkan pembahasan proses birokratisasi dalam, diskusi yang lebih luas tentang institusi politik. Ia membedakan tiga tipe sistem kekuasaan -tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Hanya di dunia Barat modern-lah otoritas rasionallegal dapat berkembang, dan hanya di dalam sistem tersebutlah orang dapat menemukan perkembangan menyeluruh birokrasi modern. Di belahan dunia lain, masyarakat tetap didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik, yang secara umum menghambat perkembangan sistem otoritas rasional-legal dan birokrasi modern. Singkat kata, otoritas tradisional lahir dari sistem kepercayaan yang telah berlangsung lama. Contohnya adalah pemimpin yang berkuasa karena keluarga atau marganya selalu menjadi pemimpin kelompok tersebut. Pemimpin ,karismati,k mengambil otoritasnya dari kemampuan atau sifatnya yang istimewa, atau hanya sekadar dari kepercayaan pengikutnya bahwa sang pemimpin memiliki keistimewaan. Meskipun kedua jenis otoritas ini penting secara historis, Weber percaya bahwa di Barat, clan pada hakikatnya di seluruh dunia, kecenderungan ini mengarah pada sistem otoritas rasional-legal. Dalam sistem seperti isu, otoritas berasal dari aturan yang diputuskan secara legal dan rasional. Jadi, pada hakikatnya presiders Amerika Serikat menclapatkan otoritasnya dari hukum masyarakat. Evolusi otoritas rasional-legal, dengan birokrasi yang menyertainya, hanyalah satubagian dari argumen umum Weber tentang rasionalisasi dunia Barat.
Weber juga melakukan analisis yang begitu terperinci dan cermat tentang rasionalisasi fenomena-fenomena seperti agama, hukum, kota, dan bahkan musik. Namun kita dapat mengilustrasikan cara berpikir Weber dengan sebuah contoh lain -rasionalisasi institusi ekonomi. Pembahasan ini diletakkan pada analisis Weber yang lebih luas tentang hubungan agama dengan kapitalisme. Dalam satu studi historisnya, Weber berusaha memahami mengapa sistem ekonomi rasional (kapitalisme) berkembang di Barat dan mengapa sistem ini gagal berkembang di belahan dunia lain. Weber sepakat dengan peran agama dalam proses ini. Di satu level, ia terlibat dalam dialog dengan pars Marxis dalam menunjukkan bahwa, berlawanan dengan yang diyakini sebagian besar kaum Marxis hari ini, agama bukanlah sekadar epifenomena. Namun, agama memainkan peran kunci dalam lahirnya kapitalisme di Barat dan dalam kegagalannya untuk berkembang di belahan dunia lain. Weber berpendapat bahwa adalah sistem agama rasional (Calvinisme) yang memainkan peran sentral dalam, lahirnya kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia lain yang ia kaji, Weber menemukan sistem agama yang lebih irasional (misalnya, Konfusianisme, Taoisme, Hinduisme), yang merintangi berkembangnya sistem ekonomi rasional. Namun, pada akhimya orang merasa bahwa agama-agama ini hanya menjadi kendala sesaat, karena sistem ekonomi -dan seluruh sistem sosial- masyarakat-masyarakat ini pada akhirnya akan terasionalkan. Meskipun rasionalisasi ada di pusat teori Weberian, namun ini sama sekali tidak berlaku bagi teorinya. Sekarang belum saatnya untuk membahas lebih dalam masalah ini. Kita lebih balk kembali lagi ke perkembangan teori sosiologi. Isu kunci dalam perkembangan ini adalah: Mengapa teori Weber terbukti lebih me-
narik perhatian para. teoretisi sosiologi akhir-akhir-akhir ini dibandingkan dengan teori Mandan?
3.
PENERIMAAN ATAS TEORI WEBER Alasannya adalah bahwa Weber terbukti lebih dapat diterima secara politis. Alihalih mengambil radikalisme Marxian, Weber lebih bersikap liberal terkait dengan sejumlah isu dan lebih konservatif untuk isu lain (misalnya, peran negara). Meskipun ia adalah seorang pengkritik berbagai sisi masyarakat kapitalis modern dan sampai pada kesimpulan kritis yang sama dengan Marx, ia bukanlah orang yang mengusulkan solusi radikal atas sejumlah masalah (Heins, 1993). Sebaliknya, ia merasa bahwa reformasi radikal yang ditawarkan oleh kalangan Marxis dan sosialis lain akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan. Para teoretisi sosiologi akhir-akhir ini, khususnya di Amerika, melihat masyarakat mereka diserang oleh teori Marxian. Karena sebagian besar berorientasi konservatif, mereka berusaha membangun alternatif teoretis bagi Marxisme. Salah seorang yang terbukti memiliki daya tarik adalah Max Weber. (Durkheim dan Vilfredo Pareto adalah dua orang lainnya). Sebenarnya, rasionalisasi tidak hanya memengaruhi kapitalis namun juga masyarakat sosialis. Memang, dari sudut pandang Weber, rasionalisasi menimbulkan lebih banyak masalah di masyarakat sosialis daripada di masyarakat kapitalis. Weber lebih dipilih juga karena caranya menyajikan penilaian. Ia menghabiskar, sebagian besar hidupnya dengan melakukan kajian sejarah terperinci, dan kesimpulan politisnya sexing kah dibuat berdasarkan konteks penelitiannya.
Jadi, kesimpulan-kesimpulan
tersebut
terkesan
ilmiah
dan
akademis.
Marx,
meskipun banyak melakukan penelitian serius, juga banyak menulis bahan-bahan yang jelas polemis. Bahkan karyanya yang lebih akademis sarat dengan penilaian politis. Sebagai contoh, dalam bukuCapital (1867/1967), ia menggambarkan kapitalis sebagai "pengisap darah" dan "serigala jadi-jadian". Gaya Weber yang lebih
akademismenyebabkan ia lebih diterima oleh para sosiolog di kemudian hari. Alasan lain dari lebih diterimanya. Weber adalah bahwa ia bergerak di atas tradisi filosofis yang juga membantu membentuk karya sosiolog-sosiolog lain di kemudian hari. Jadi, Weber bergerak di atas tradisi Kantian, dan itu berarti ia cenderung berpikir dengan model sebab-akibat. Cara berpikir semacam ini lebih diterima oleh para sosiolog di kemudian hari, yang sebagian besar tidak terbiasa dan merasa tidak cocok dengan logika dialektis yang memengaruhi karya Marx. Akhirnya, Weber menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap dunia sosial ketimbang Marx. Kalau Marx hampir secara keseluruhan mendalami ekonomi, Weber tertarik pada berbagai fenomena sosial. Keragaman fokus ini tampaknya memberikan lebih banyak bahan bagi para sosiolog di kemudian hari, bila dibandingkan dengan perhatian Marx yang lebih berkacamata tunggal. Weber menghasilkan karya-karyanya pada akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Karier awal Weber membuatnya lebih diidentikkan Sebagai sejarawan yang memberikan perhatian pada isu-isu sosiologi, namun pada awal tahun A900-an fokusnya semakin mengarah ke isu sosiologi. Pada zamannya, ia memang menjadi sosiolog dominan di Jerman. Pada tahun 1910, ia membangun Masyarakat Sosiologi Jerman (di antaranya bersama dengan Georg Simmel, yang akan kita diskusikan di bawah ini) (Glatzer, 1998). Rumahnya di Heidelberg adalah pusat intelektual tidak hanya bagi sosiolog
namun juga bagi para ilmuwan dari berbagaibidang. Meskipun karyanya memang berpengaruh lugs di Jerman, karyanya jauh lebih terasa di Amerika Serikat, khususnya setelah Talcott Parsons memperkenalkan gagasan-gagasan Weber (dan teoretisi Eropa lainnya, khususnya Durkheim) kepada audien Amerika. Kalau gagasan-gagasan Marx tidak membawa dampak signifikan bagi para teoretisi sosiologi Amerika sampai dengan tahun 1960-an, maka Weber telah begitu berpengaruh pada akhir 1930-an.
T e o r i W e b e r m e m persoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. MaxWeber adalah sosiolog Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Dia membahas bermacam gejala kemasyarakatan, misalnya tentang perkembangan bangsabangsa di dunia, tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting bagi masalah pembangunan yang dibahas oleh Max Weber adalah tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pembahasan ini diterbitkan dalam duo buah esei pada tahun 1904 dan 1905, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judulThe Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai Etika Protestan.
Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Di sini muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka. Tetapi, orang yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya. Karena itu, mereka menjadi tidak tenang, menjadi cemas, karena ketidak-jelasan nasibnya ini.
Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik ke surga setelah dia coati nanti. Kalau kerjanya selalu gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan pergi ke neraka. Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut agama Protestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja tanpa pamrih; artinya mereka bekerja bukan untuk mencari kekayaan material, melainkan terutama untuk mengatasi kecemasannya. Inilah yang disebut sebagai Etika Protestan oleh Weber, yakni cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya. (Memang, orang ini kemudian menjadi kayo karena keberhasilannya, tetapi ini adalah produk sampingan yang tidak disengaja. Mereka bekerja keras sebagai pengabdian untuk agama mereka, bukan untuk mengumpulkan harta. Tetapi Weber sendiri mengakui bahwa hal ini kemudian berubah jadi sebaliknya.) Etika Protestan inilah yang menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa. Calvinisme kemudian menyebar ke Amerika Serikat, dan di sang pun berkembang kapitalisme yang sukses.
Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Kalau agama kita perluas menjadi kebudayaan, studi Weber ini menjadi perangsang utama bagi munculnyastudi tentang aspek kebudayaan terhadap pembangunan. Dalam melakukan penelitian tentang aspek kebudayaan ini, peran agama pun menjadi sangat penting sebagai salah satu nilai kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat tersebut. Sementara itu, istilah Etika Protestan menjadi sebuah konsep umum yang tidak dihubungkan lagi dengan agama Protestan itu sendiri. Etika Protestan menjadi sebuah nilai tentang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai sukses.Dia bisa ada di luar agama Protestan, dapat menjelma menjadi nilai-nilai budaya di luar agama. Misalnya, salah seorang pengikut Weber di Amerika Serikat, Robert Bellah, melakukan penelitian pada agama Tokugawa d.i Jepang. Dalam bukunya yang terkenal, Tokugawa Religion, dia menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai Etika Protestan itu juga ada pada agama Tokugawa. Karena itulah, Jepang berhasil membangun kapitalisme dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
NO 1.BIOGRAFI SINGKAT TALCOTT PARSONS [1] Talcott Parsons dilahirkan di Colorado Springs pada tahun 1902. Pada 1920 Ia masuk ke Amherst College. Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di London School of Economics tahun 1924. Pada tahun 1925, Parsons pindah ke Heidelberg, Jerman. Pada tahun 1927, ia menjadi instruktur dalam ekonomi di Amherst. Sejak tahun 1927 hingga wafat pada tahun 1979 ia berprofesi sebagai pengajar di Harvard, Amerika Serikat. Pada 1937, ia mempublikasikan sebuah buku yang menjadi dasar bagi teori-teorinya, yaitu buku The Structure of Social Action.
Sejak tahun 1944, ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard, Amerika Serikat. Pada tahun 1946, ia menjadi ketua jurusan hubungan sosial di universitas tersebut. Pada tahun 1949, ia dipilih sebagai Presiden Assosiasi Sosiologi Amerika. Dan pada tahun 1951, ia menjadi tokoh dominant sosiologi Amerika seiring dengan terbitnya buku karyanya The Social System. Pada akhir 1960-an, Parsons mendapat serangan oleh sayap radikal sosiologi Amerika karena ia dipandang konservatif (dalam sikap politiknya maupun teori-teorinya). Selain itu teori-teorinya juga dipandang hanya sebagai skema kategorisasi panjang-lebar. Pada tahun 1980-an, teori-teorinya diminati diseluruh dunia. Menurut Holton dan Turner (1986), karya-karya parsons memberikan kontribusi lebih besar bagi teori sosiologi, daripada Marx, Weber maupun Durkheim. Selain itu, ide-ide pemikiran Parsons maupun teori-teorinya, tidak hanya mempengaruhi para pemikir konservatif namun juga teoretisi Neo-Marxian (khususnya Jurgen Habermas). Berdasarkan semua hasil karyanya, Talcott Parsons adalah tokoh fungsionalis struktural modern terbesar hingga saat ini. FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup[2]. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan Teori Fungsionalisme Talcott Parsons bersifat kompleks. Teori Fungsionalisme Struktural mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Teori Fungsionalisme Struktural Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Akan tetapi optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang
kelihatannya mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldner (1970: 142): untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan realitas personal kehidupan seharihari yang sama-sama kita miliki. Teori struktural fungsional mengansumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. Pemikir fungsionalis menegaskan bahwa perubahan diawali oleh tekanan-tekanan kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Artinya teori ini melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi yang akan berlangsung seperti sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Variabel yang menjadi perhatian teori ini adalah struktur sosial serta berbagai dinamikanya. Penyebab perubahan dapat berasal dari dalam maupun dari luar sistem sosial. Gagasan-gagasan inti dari fungsionalisme ialah perspektif holistis (bersifat menyeluruh), yaitu sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh bagian-bagian demi tercapainya tujuantujuan dari keseluruhan, kontinuitas dan keselarasan dan tata berlandaskan konsensus mengenai nilai-nilai fundamental. Teori fungsional ini menganut faham positivisme, yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa spesialisasi harus diganti dengan pengujian pengalaman secara sistematis[3], sehingga dalam melakukan kajian haruslah mengikuti aturan ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, fenomena tidak didekati secara kategoris, berdasarkan tujuan membangun ilmu dan bukan untuk tujuan praktis. Analisis teori fungsional bertujuan menemukan hukum-hukum universal (generalisasi) dan bukan mencari keunikan-keunikan (partikularitas). Dengan demikian, teori fungsional berhadapan dengan cakupan populasi yang amat luas, sehingga tidak mungkin mengambilnya secara keseluruhan sebagai sumber data. Sebagai jalan keluarnya, agar dapat mengkaji realitas universal tersebut maka diperlukan representasi dengan cara melakukan penarikan sejumlah sampel yang mewakili. Dengan kata lain, keterwakilan (representatifitas) menjadi sangat penting. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu kajian tentang struktur-struktur sosial sebagai suatu unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling terkait. Pendekatan fungsionalisme-struktural dapat dikaji melalui anggapan -anggapan dasar berikut[4]: a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain b. Hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian suatu sistem bersifat timbal balik c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapi dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah keseimbangan yang bersifat dinamis.
d. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi dan penyimpangan. e. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial, terjadi secara gradual (perlahan-lahan atau bertahap), melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. f. Faktor paling penting yang memiliki daya integrasi suatu sistem sosial adalah konsensus atau mufakat di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Demi memudahkan kajian teori-teori yang digagas oleh Parsons, Peter Hamilton berpendapat bahwa Teori Parsonian dapat dibagi kedalam 3 fase [5]:
1. Fase Permulaan. Fase ini berisi tahap-tahap perkembangan atas teori Voluntaristik(segi Kemauan) dari tindakan sosial dibandingkan dengan pandangan-pandangan sosiologi yang positivistis, utilitarian, dan reduksionis.
2. Fase Kedua. Fase ini berisi gerakannya untuk membebaskan diri dari kekengan teoritindakan sosial yang mengambil arah fungsionalisme struktural ke dalam pengembangan suatu teori tindakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting.
3. Fase Ketiga Fase ini terutama mengenai model sibernetik (elektronik pengendali)dari sistem-sistem sosial dan kesibukannya dengan masalah empiris dalam mendefinisikan dan menjelaskan perubahan sosial. Dari ketiga fase tersebut, dapat dinyatakan bahwa Parsons telah melakukan tugas penting, yaitu: Ia mencoba untuk mendapatkan suatu penerapan dari sebuah konsep yang memadai atas hubungan-hubungan antara teori sosiologi dengan ekonomi. Ia juga mencari kesimpulan-kesimpulan metodologis & epistemologis dari apa yang dinamakan sebagai konsep sistem teoretis dalam ilmu sosial. Ia mencari basis-basis teoretis dan metodologis dari gagasan tindakan sosial dalam pemikiran sosial.[6] Dalam mengkategorikan tindakan atau menggolongkan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial, Parsons mengembangkan 5 buah skema yang dilihat sebagai kerangka teoritis utama dalam analisa sistem sosial. 5 buah skema itu adalah[7]:
1. Affective versus Affective Neutrality, maksudnya dalam suatu hubungan sosial,orang dapat bertindak untuk pemuasan Afeksi (kebutuhan emosional) atau bertindak tanpa unsur tersebut (netral).
2. Self-orientation versus Collective-orientation, maksudnya, dalam berhubungan,orientasinya hanya pada dirinya sendiri atau mengejar kepentingan pribadi. Sedangkan dalam hubungan yang berorientasi kolektif, kepentingan tersebut didominasi oleh kelompok.
3. Universalism versus Particularism, maksudnya, dalam hubungan yanguniversalistis, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang. Sedangkan dalam hubungan yang Partikularistis, digunakan ukuran/kriteria tertentu.
4. Quality versus Performance, maksudnya variable Quality ini menunjukpadaAscribed Status (keanggotaan kelompok berdasarkan kelahiran/bawaan lahir). Sedangkan Performance (archievement) yang berarti prestasi yang mana merupakan apa yang telah dicapai seseorang.
5. Specificity versus Diffusness, maksudnya dalam hubungan yang spesifik, individuberhubungan dengan individu lain dalam situasi terbatas . 4 FUNGSI IMPERATIF SISTEM TINDAKAN (AGIL)[8]
Dalam teori struktural fungsional Parsons ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatifimperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency).
1. Adaptasi, sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terusberlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.
2. Goal (Pencapaian), sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas dapatberusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.[9]
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadikomponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
4. Latensi, Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara danmemperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Berdasarkan skema AGIL di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi fungsi sistem adalah sebagai Pemeliharaan Pola (sebagai alat internal), .Integrasi (sebagai hasil internal), Pencapaian Tujuan (sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal). Adapun komponen dari sistem secara general (umum) dari suatu aksi adalah: Keturunan & Lingkungan yang merupakan kondisi akhir dari suatu aksi, Maksud & Tujuan, Nilai Akhir, dan hubungan antara elemen dengan faktor normatif.[10] Asumsi Parsons terkait dengan tatanan sistem: Sistem memiliki bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga suatu sistem tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, sistem tindakan itu mendapat pengaruh maupun dapat memberi pengaruh pada sistem kepribadian. Sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya, dapat menjadi statis/mengalami proses perubahan secara tertata. Sifat satu bagian sistem berdampak pada bagian yang lain. Sistem memelihara batas dengan lingkungan mereka. Alokasi & Integrasi adalah 2 proses fundamental bagi kondisi ekuilibrium sistem. Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas & hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecendrungan untuk mengubah sistem dari dalam. Sistem harus terstruktur agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan juga harus harmonis dengan sistem lain. Sistem juga harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain, artinya suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi antara satu sustem dengan sistem lainnya akan saling terkait. Sistem juga dituntut untuk mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional (imbang), melahirkan partisipasi yang
memadai dari para aktornya, Mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, dapat dikendalikan bila terjadi konflik atau menimbulkan kekacauan dan memiliki bahasa dan aktor sosial. Menurutnya persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses Sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. 1. Sistem Tindakan Dalam sistem tindakan, Parsons melandaskan pada teori aksi ( the structure of social action) yang menujun titik sentral konsep perilaku voluntaristik. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa Individu memiliki kemampuan untuk menentukan cara & alat dari berbagai alternative yang ada untuk mencapai suatu tujuan.[11] Sistem Tindakan berdasarkan Orientasi Motivasi:[12] 1. Kognitif (merujuk pada definisi seorang aktor tentang situasi dalam terminologi kepentingannya, yang didorong oleh apa yang diketahui oleh obyek ). 2. Katektik (pengujian seorang aktor untuk kepuasannya yang seringkali merupakan tanggapan atas obyek). 3. Evaluatif (merujuk pada pilihan sang aktor dan tatanan dari alternatifnya yang dilakukan dengan cara dimana obyek dininlai dan diurutkan satu sama lain agar saling menyerang). 2. Sistem Sosial Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik/lingkungan, aktor yang termotivasi kearah optimisasi kepuasan, dan hubungan dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama. Sistem sosial dibentuk oleh norma, kepercayaan, nilai-nilai yang diorganisasikan dan dapat diukur sebagai keleompok yang terpola dari peran-peran sosial yang berjalan baik. Prasyarat fungsional bagi sistem sosial[13]: 1. Terstruktur, dapat beroperasi dengan baik bersama sistem lain. 2. Didukung sebelumnya oleh sistem lain, agar dapat bertahan hidup. 3. Signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya. 4. Menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. 5. Memiliki kontrol minimum terhadap perilaku yang berpotensi merusak. 6. Mmerlukan bahasa agar bertahan hidup. Batasan-batasan dari sistem sosial:[14] a. Sistem sosial merupakan jaringan hubungan-hubungan antar aktor atau jaringan hubungan interaktif. b. Sistem sosial menyediakan kerangka konseptual untuk menghubungkan tindakan individu dalam situasi yang bervariasi. c. Pandangan Aktor tentang alat & tujuan didapat pada situasi yang dibentuk oleh kepercayaan, norma & nilai yang diorganisasikan dalam harapan peran d. Aktor tidak menghadapi situasi sebagai individu, tetapi sebagai posisi dalam peran sosial yang menyediakan perilaku yang sesuai dan juga berhubungan dengan peran-peran sosial lain (Timasheff & Theodorson, 1976:254). 3.Aktor dari Sistem Sosial
Proses internalisasi & sosialisasi merupakan hal terpenting dalam integrasi.Biasanya aktor adalah penerima pasif dalam proses sosialisasi. Sosialisasi harus terus menerus dilengkapi dalam siklus kehidupan dengan serangkaian pengalaman sosialisasi yang lebih spesifik.Sosialisasi & Kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan ekuilibriumnya[15]. 4. Masyarakat Masyarakat merupakan sistem sosial yang paling spesifik & penting, yaitu sebuah kolektivitas yang relatif mandiri, anggotanya mampu memenuhi kebutuhan individual & kolektif, dan sepenuhnya hidup dalam kerangka kerja kolektif. Contoh Sub sistem masyarakat: ekonomi, politik. 5. Sistem Kultural (kebudayaan) Kebudayaan adalah kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen dunia sosial atau sistem simbol yang terpola, tertata, yang merupakan sasaran orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan dan pola-pola yang terlembagakan dalam sistem sosial. Dalam sistem sosial, kebudayaan menubuh dalam norma dan nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian, kebudayaan ditanamkan kepada individu oleh aktor kedalam dirinya. Sistem kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai aspek tindakan yang mengorganisasikan karakteristik dan urgensi yang membentuk sistem yang stabil. Contoh dari sistem kultural diantaranya adalah: klen (marga). 6. Sistem Kepribadian Kepribadian adalah organisasi sistem orientasi & motivasi tindakan aktor individual. Komponen dasar kepribadian: kebutuhan-disposisi, yaitu sebagai unit paling signifikan dari motivasi tindakan. Cara Parsons mengaitkan kepribadian dengan sistem sosial: pertama, aktor harus belajar melihat dirinya dengan cara yang sesuai dengan status mereka dalam masyarakat. Kedua, harapan-harapan peran melekat pada setiap peran yang dimainkan oleh aktor individu. Lalu terjadi pembelajaran disiplin diri, internalisasi orientasi nilai, identifikasi, dsb. 7. Organisme Behavioral Meskipun memasukan organisme behavioral dalam salah satu sistem tindakan, Parsons tidak begitu detil membahasnya. Organisme behavioral dalam karya Parsons merupakan sistem bekas dan merupakan sumber energi bagi seluruh sistem. Sistem ini kemudia berubah nama menjadi sistem perilaku. [16] 8. Perubahan dan Dinamika Teori Parsonsian Berdasarkan karya-karya Parsons, seperti empat sistem tindakan dan imperatif fungsional mengundang tuduhan bahwa ia menawarkan teori struktural yang tidak mampu menangani perubahan sosial. Hal ini dikarenakan, ia peka terhadap perubahan sosial, namun ia berpendapat bahwa meskipun studi perubahan diperlukan, tapi itu harus didahului dengan studi tentang struktur. 9. Teori Evolusi Dalam membahas perubahan sosial, terdapat pradigma perubahan evolusioner. Dalam paradigma tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu: Proses Differensiasi[17] dan Integrasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa masyarakat mengalami evolusi & pertumbuhan sehingga menjadi semakin mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Evolusi tersebut berlangsung melalui berbagai siklus (tahap) yaitu, tahap primitif, pertengahan dan modern. 10. Media Pertukaran yang Digeneralisasi
Media pertukaran yang digeneralisasi adalah media yang beredar diantara keempat sistem tersebut, yang mana eksistensi dan gerakannya mendinamiskan sebagian besar analisis struktural Parsons. Contoh model media ini dapat berupa uang ( sebagai media pertukaran dalam bidang ekonomi), jabatan (sebagai media prtukaran dalam bidang politik). Kritik terhadap Parsons: 1. Orientasinya statis, sehingga terlalu banyak mencurahkan perhatian pada perubahan.Karya-karyanya tentang perubahan sosial dinilai sangat statis & terstruktur.[18] 2. Pada saat dia melakukan elaborasi (pengerjaan dengan teliti) sisi sistem & teori, tindakan dia telah menerapkan seluruh terminologi dan asumsi kaum fungsionalis yang telah diketahui bahwa begitu problematis dari berbagai sudut pandang. 3. Parsons tidak pernah berhasil menjelaskan secara tepat, realitas sosial empirik yang bagaimana ia bicarakan. 4. Definisi yang ia buat, tetap merupakan pengujian neoskolastik (sesuatu yang berhubungan dengan penyelidikan hukum-hukum filsafat baru) yang mencoba mengatasi suatu ketidakjelasan melalui sarana lainnya. Inti dari kritik untuknya, Parsons tidak menyadari bahwa sebagian besar pernyataannya yang dibuat tentang suatu masyarakat harus dibatasi keumumannya. Salah satu alasan yang paling pokok tentang ketidakjelasan Parsons adalah bahwa dia mendefinisikan terminologinya tanpa ada tujuan penelitian maupun problema yang masuk akal. Kelemahan teori fungsionalisme-struktural & AGIL: Bahwa pandangan pendekatan ini terlalu bersifat umum atau terlalu kuat memegang norma, karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang, dan mapan. Ini terjadi karena analogi dari masyarakat dan tubuh manusia yang dilakukan oleh Parson bisa diilustrasikan, bahwa tidak mungkin terjadi konflik antara tangan kanan dengan tangan kiri, demikian pula tidak mungkin terjadi ada satu tubuh manusia yang membunuh dirinya sendiri dengan sengaja. Demikian pula karakter yang terdapat dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu sistem sosial, akan selalu terkait secara harmonis, berusaha menghindari konflik, dan tidak mungkin akan menghancurkan keberadaannya sendiri. Hal-hal yang bersifat menguji pendapat Parsons[19]: 1. Sistem Kekerabatan Kekerabatan selalu ada dalam masyarakat. Menurut Parsons, kekerabatan telah masuk kedalam rangkaian jenis struktural yang bersifat kolektif. Bentuk-bentuk kekerabatan saat ini dan masa lalu memperlihatkan bahwa ada keharusan struktural dan fungsional yang sudah pasti & tidak ada masyarakat yang dapat melanggarnya. 2. Stratifikasi Sosial Dalam masalah ini, Parsons gagal untuk membedakan antara proses diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ia juga tidak begitu menggali permasalahan (berupa pertanyaan) itu di dalam suatu sikap ilmiah & kritis, tetapi semata-mata hanya meyakini berdasarkan bahasan yang tidak menganalisa suatu permasalahan. 3. Territorial & Tekanan Dalam hal ini diskusi Parsons secara keseluruhan tentang pengklasifikasian yang bersifat empirik terlihat dominan. Dia juga mengulas tentang kekuasaan (dalam hal ini territorial
diartikan sebagai wilayah kekuasaan), konflik, dan tekanan. Tetapi ia tidak menerapkan konsep ini dalam skema analisanya. Selain itu, ia juga gagal untuk menghadapi problema peranan tekanan di dalam melestarikan tatanan tersebut di dalam sutau model yang logis atau empiris. 4. Agama & Integrasi Nilai Dalam hal ini, agama merupakan suatu lembaga yang diperlukan didalam suatu masyarakat dan merupakan suatu keseluruhan yang mendasari suatu nilai. Daftar Pustaka George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. M.Zeitlin,Irving. Memahami Kembali Sosiologi. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Dwi Susilo,Rachmad K.. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. M.Poloma,Margaret. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Prof.Dr.Wardi Bachtiar, MS. Sosiologi Klasik, Dari Comte hingga Parsons. 2006. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Bisri, Mustofa S.Sos & Vindi, Elisa S.S. Kamus Lengkap Sosiologi. 2008. Yogyakarta : Panji Pustaka. Tim Prima Pena. Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap. 2006. Surabaya : Gitamedia Press. [1]. Teori Sosiologi. Ritzer,George & J.Goodman, Douglas. 2009. Yogyakarta : Kreasi Wacana. halaman 254 255. & Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. halaman 107 109. [2] Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. halaman 107. [3] Bisri, Mustofa S.Sos & Vindi, Elisa S.S. Kamus Lengkap Sosiologi. 2008. Yogyakarta : Panji Pustaka. halaman 241. [4] George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. hal 258 259 [5] Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. halaman 111. [6] Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. halaman 112. [7] M.Poloma, Margaret. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 173 174. [8] George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. hal 257 & Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. halaman 121. [9] Rahmat K Dwi Susilo,. 2008. 20 Tokoh Sosiologi Modern. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. Halaman 121. [10] Bachtiar, Wardi Prof.Dr. 2006. Sosiologi Klasik, Dari Comte hingga Parsons.Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Halaman 312. [11] Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media halaman 114. [12]. Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media halaman 116. [13] George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. halaman 260. [14] Rachmad K.Dwi Susilo. 20 Tokoh Sosiologi Modern, 2008, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media halaman 120. [15] Ekuilibrium yaitu kondisi dimana terjadi suatu keseimbangan. (Kamus Ilmiah Populer, hal 108).
[16] George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. halaman 265 [17] Yaitu perbedaan hak dan kewajiban. (kamus ilmiah popular, hal 88). [18] George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori sosiologi. 2008, Yogyakarta : Kreasi Wacana. halaman 259. [19] M.Zeitlin, Irving. Memahami Kembali Sosiologi . Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Halaman 37 44.




![[XLS]FILE Exceltapteng.go.id/images/page/File Pengumuman/JADWAL UJIAN.xlsx · Web view1 1 5204 2 5204 2. 2 5204 2 5204 2. 3 5204 2 5204 2. 4 5204 2 5204 2. 5 5204 2 5204 2. 2 1 5204](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5af571717f8b9a190c8e54ef/xlsfile-pengumumanjadwal-ujianxlsxweb-view1-1-5204-2-5204-2-2-5204-2-5204-2.jpg)