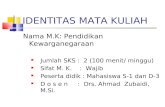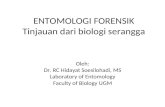forensik ku1.docx
-
Upload
david-suhendra -
Category
Documents
-
view
236 -
download
3
Transcript of forensik ku1.docx

Menurut ILCOR (Internasional Liaison Committee on Resuscitation) tenggelam didefinisikan sebagai
proses yang menyebabkan gangguan pernafasan primer akibat submersi/imersi pada media cair. Submersi
merupakan keadaan dimana seluruh tubuh, termasuk sistem pernafasan, berada dalam air atau cairan.
Sedangkan imersi adalah keadaan dimana terdapat air/cairan pada sistem konduksi pernafasan yang
menghambat udara masuk. Akibat dua keadaan ini, pernafasan korban terhenti, dan banyak air yang tertelan.
Setelah itu terjadi laringospasme. Henti nafas atau laringospasme yang berlanjut dapat menyebabkan hipoksia
dan hiperkapnia. Tanpa penyelamatan lebih lanjut, korban dapat mengalami bradikardi dan akhirnya henti
jantung sebagai akibat dari hipoksia.
Di negara maju seperti Amerika Serikat, 15% dari anak sekolah mempunyai risiko meninggal akibat
tenggelam dalam air. Ini dihubungkan dengan perubahan musim. Pada musim panas anak-anak lebih tertarik
bermain di kolam renang, danau, sungai, dan laut karena mereka menganggap bermain air sama dengan santai
sehingga mereka lupa terhadap tindakan pengamanan.
Di Indonesia, kita tidak banyak mendengar berita tentang anak yang mengalami kecelakaan di kolam
renang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi negara kita. Tetapi, mengingat keadaan Indonesia yang
dikelilingi air, baik lautan, danau, maupun sungai, tidak mustahil jika banyak terjadi kecelakaan dalam air
seperti hanyut dan terbenam yang belum diberitahukan dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.
Kejadian hampir tenggelam, 40% terjadi pada sebagian besar anak-anak laki-laki untuk semua
kelompok usia dan umumnya terjadi karena kurang atau tidak adanya pengawasan orang tua. Beberapa faktor
lainnya yang menyebabkan kejadian hampir tenggelam pada anak adalah tidak ada
pengalaman/ketidakmampuan berenang, bernapas terlalu dalam sebelum tenggelam, penderita epilepsi,
pengguna obat-obatan dan alkohol, serta kecelakaan perahu mesin dan perahu dayung. Dalam hal ini, maka
pertolongan kegawat daruratan dengan pasien tenggelam harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk
menghindari terjadinya kolaps pada alveolus, lobus atas atau unit paru yang lebih besar.
Penatalaksanaan tindakan kegawat daruratan ini tentunya harus dilakukan secara benar dengan tujuan
untuk mencegah kondisi korban lebih buruk, mempertahankan hidup serta untuk peningkatan pemulihan.
DEFINISI TENGGELAM
Tenggelam dapat diartikan sebagai kematian akibat pembenaman di dalam air. Konsep asli mekanisme
kematian akibat tenggelam adalah asfiksia, ditandai dengan masuknya air ke dalam saluran pernapasan.
Penelitian pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an menyebutkan bahwa kematian akibat tenggelam
disebabkan oleh gangguan elektrolit atau aritmia jantung, yang dihasilkan oleh sejumlah besar air yang masuk
ke sirkulasi melalui paru-paru. Sekarang, konsep dasar tersebut benar, dan fisiologi kematian yang terpenting

pada kasus tenggelam adalah asfiksia.1
Diagnosis kematian akibat tenggelam kadang-kadang sulit ditegakkan, bila tidak dijumpai tanda yang
khas baik pada pemeriksaan luar atau dalam. Pada mayat yang ditemukan tenggelam dalam air, perlu pula
diingat bahwa mungkin korban sudah meninggal sebelum masuk ke dalam air.
Beberapa istilah drowning
1. Wet drowning. Pada keadaan ini cairan masuk ke dalam saluran pernapasan setelah korban tenggelam.
2. Dry drowning. Pada keadaan ini cairan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, akibat spasme
laring. Paru-paru tidak menunjukkan bentuk yang bengkak (udem). Tetapi, terjadi hipoksia otak yang
fatal akibat spasme laring. Dry drowning terjadi 10-15% dari semua kasus tenggelam. Teori
mengatakan bahwa sejumlah kecil air yang masuk ke
laring atau trakea akan mengakibatkan spasme laring yang tiba-tiba yang dimediasi oleh
1 2
refleks vagal. ’
3. Secondary drowning/near drowning. Terjadi gejala beberapa hari setelah korban tenggelam (dan
diangkat dari dalam air) dan korban meninggal akibat komplikasi.
4. Immersion syndrome. Korban tiba-tiba meninggal setelah tenggelam dalam air dingin akibat refleks
vagal. Alkohol dan makan terlalu banyak merupakan faktor pencetus.
FISIOLOGI TENGGELAM

Ketika manusia masuk ke dalam air, reaksi dasar mereka adalah mempertahankan jalan napas mereka.
Ini berlanjut sampai titik balik dicapai, yaitu pada saat seseorang akan menarik napas kembali. Titik balik ini
terjadi karena tingginya kadar CO2 dalam darah dibandingkan dengan kadar O2. Ketika mencapai titik balik,
korban tenggelam akan kemasukan sejumlah air, dan sebagian akan tertelan dan akan ditemukan di dalam
lambung. Selama interval ini, korban mungkin muntah dan mengaspirasi sejumlah isi lambung. Setelah proses
respirasi tidak mampu mengompensasi, terjadilah hipoksia otak yang bersifat ireversibel dan merupakan
penyebab kematian.1
Mekanisme kematian pada korban tenggelam:
1. Asfiksia akibat spasme laring
Gambar 1. Mekanisme hipoksia otak pada kasus tenggelam (dikutip dari kepustakaan 3)

2. Asfiksia karena gagging dan chocking
3. Refleks vagal
4. Fibrilasi ventrikel (dalam air tawar)
5. Edema pulmoner (dalam air asin)
GEJALA KLINIS
Gambaran klinik korban tenggelam sangat bervariasi berhubungan dengan lamanya tenggelam. Conn dan
Barker mengembangkan suatu klasifikasi yang dianggap bermanfaat untuk pedoman yang sangat berguna bila
digunakan pada 10 menit pertama.

TENGGELAM DALAM AIR TAWAR
Pada keadaan ini terjadi absorpsi cairan yang massif. Karena konsentrasi elektrolit dalam
air tawar lebih rendah daripada konsentrasi dalam darah, maka terjadi hemodilusi darah, air
masuk ke dalam cairan darah sekitar alveoli dan mengakibatkan pecahnya sel darah merah
2
(hemolisis).
Akibat pengenceran darah yang terjadi, tubuh mencoba mengatasi keadaan ini dengan
melepaskan ion Kalium dari serabut otot jantung sehingga kadar ion dalam plasma Kalium
meningkat, terjadi perubahan keseimbangan ion K+ dan Ca++ dalam serabut otot jantung dan
dapat mendorong terjadinya fibrilasi ventrikel dan penurunan tekanan darah, yang kemudian
2
menyebabkan kematian akibat anoksia otak. Kematian terjadi dalam waktu 5 menit.
TENGGELAM DALAM AIR ASIN
Konsentrasi elektrolit cairan air asin lebih tinggi daripada dalam darah, sehingga air akan
ditarik dari sirkulasi pulmonal ke dalam jaringan interstitial paru yang akan meninbulkan edema
pulmoner, hemokonsentrasi, hipovolemi, dan kenaikan kadar Magnesium dalam darah.
payah jantung. Kematian terjadi kira-kira dalam waktu 8-9 menit setelah tenggelam.2
PENATALAKSANAAN
Prinsip pertolongan di air :

1) Raih ( dengan atau tanpa alat ).
2) Lempar ( alat apung ).
3) Dayung ( atau menggunakan perahu mendekati penderita ).
4) Renang ( upaya terakhir harus terlatih dan menggunakan alat apung ).
Penanganan pada korban tenggelam dibagi dalam tiga tahap, yaitu:
1. Bantuan Hidup Dasar
Penanganan ABC merupakan hal utama yang harus dilakukan, dengan fokus utama pada
perbaikan jalan napas dan oksigenasi buatan, terutama pada korban yang mengalami penurunan
kesadaran. Bantuan hidup dasar pada korban tenggelam dapat dilakukan pada saat korban masih
berada di dalam air. Prinsip utama dari setiap penyelamatan adalah mengamankan diri
penyelamat lalu korban, karena itu, sebisa mungkin penyelamat tidak perlu terjun ke dalam air
untuk menyelamatkan korban. Namun, jika tidak bisa, penyelamat harus terjun dengan alat bantu
apung, seperti ban penyelamat, untuk membawa korban ke daratan sambil melakukan
penyelamatan. Cedera servikal biasanya jarang pada korban tenggelam, namun imobilisasi
servikal perlu dipertimbangkan pada korban dengan luka yang berat.
2. Penilaian pernapasan
Penanganan pertama pada korban yang tidak sadar dan tidak bernapas dengan normal setelah
pembersihan jalan napas yaitu kompresi dada lalu pemberian napas buatan dengan rasio 30:2.
Terdapat tiga cara pemberian napas buatan, yaitu mouth to mouth, mouth to nose, mouth to mask,
dan mouth to neck stoma.
Penanganan utama untuk korban tenggelam adalah pemberian napas bantuan untuk
mengurangi hipoksemia. Pemberian napas buatan inisial yaitu sebanyak 5 kali. Melakukan
pernapasan buatan dari mulut ke hidung lebih disarankan karena sulit untuk menutup hidung
korban pada pemberian napas mulut ke mulut. Pemberian napas buatan dilanjutkan hingga 10 -
15 kali selama sekitar 1 menit. Jika korban tidak sadar dan tenggelam selama <5 menit,
pernapasan buatan dilanjutkan sambil menarik korban ke daratan. Namun, bila korban tenggelam
lebih dari 5 menit, pemberian napas buatan dilanjutkan selama 1 menit, kemudian bawa korban
langsung ke daratan tanpa dKompresi dada diindikasikan pada korban yang tidak sadar dan tidak

bernapas dengan normal, karena kebanyakan korban tenggelam mengalami henti jantung akibat
dari hipoksia. Pemberian kompresi ini dilakukan di atas tempat yang datar dan rata dengan rasio
30:2. Namun, pemberian kompresi intrinsik untuk mengeluarkan cairan tidak disarankan, karena
tidak terbukti dapat mengeluarkan cairan dan dapat berisiko muntah dan aspirasi.
Selama proses pemberian napas, regurgitasi dapat terjadi, baik regurgitasi air dari paru
maupun isi lambung. Hal ini normal terjadi, namun jangan sampai menghalangi tindakan
ventilasi buatan. Korban dapat dimiringkan dan cairan regurgitasinya dikeluarkaniberikan napas
buatan.
3. Bantuan hidup lanjut
Tersedianya sarana bantuan hidup dasar dan lanjutan ditempat kejadian merupakan hal
yang sangat penting karena beratnya cedera pada sistem saraf pusat tidak dapat dikaji dengan
cermat pada saat pertolongan diberikan.4
Pastikan keadekuatan jalan napas, pernapasan dan Sirkulasi. Cedera lain juga harus
dipertimbangkan dan perlu tidaknya hospitalisasi ditentukan berdasarkan keparahan kejadian dan
evaluasi klinis. Pasien dengan gejala respiratori, penurunan saturasi oksigen dan perubahan
tingkat kesadaran perlu untuk dihospitalisasi. perhatian harus difokuskan pada oksigenasi,
ventilasi, dan fungsi jantung. Melindungi sistem saraf pusat dan mengurangi edema serebri
merupakan hal yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan hasil akhir.
Bantuan hidup lanjut pada korban tenggelam yaitu pemberian oksigen dengan tekanan
lebih tinggi, yang dapat dilakukan dengan BVM (Bag Valve Mask)atau tabung Oksigen. Oksigen
yang diberikan memiliki saturasi 100%. Jika setelah pemberian oksigen ini, keadaan korban
belum membaik, dapat dilakukan intubasi trakeal.5
1.

.
Penanganan Rumah Sakit
Pengobatan dilakukan sesuai dengan kategori klinis. Korban pada
pasien kategori A dan B biasanya hanya membutuhkan perawatan medis
supportif, sedangkan pasien kategori C membutuhkan tindakan untuk
mempertahankan kehidupan dan perawatan intensif. Penolong juga harus
mencari dan menangani trauma yang timbul seperti trauma kepala dan leher
serta mengatasi masalah yang melatarbelakanginya seperti masalah kejang.
Kategori A
Pertolongan dimulai dengan memberikan oksigen, pemeriksaan fisik,
dan pemeriksaan PaO2 arteri, PaCO2, pH, jumlah sel darah, elektrolit, serta
rontgen thorax. Pada asidosis metabolik yang belum terkompensasi, dapat
diberikan O2, pemanasan, dan pemberian Bik-Nat. Infiltrat kecil pada paru
tidak memerlukan pengobatan apabila cairan yang terhisap tidak
terkontaminasi. Sebagian korban yang tidak mempunyai masalah dapat
dipulangkan sedangkan sebagian lagi yang bermasalah dapat diobservasi dan
diberi pengobatan simptomatik di ruang perawatan sampai baik. Biasanya
korban dirawat selama 12 sampai 24 jam.
Kategori B
Korban ini membutuhkan perawatan dan monitoring ketat terhadap
sistem saraf dan pernapasan. Masalah pernapasan biasanya lebih menonjol
sehingga selain pemberian oksigen perlu diberikan: Bik-Nat untuk asidosis
metabolik yang tidak terkompensasi; Furosemid untuk oedem paru; Aerosol B
simptometik untuk bronchospasme; serta Antibiotik untuk kasus teraspirasi
air yang terkontaminasi.
Pasien yang awalnya diintubasi setelah menampakkan fungsi
pernapasan dan neurologi yang baik dapat dilakukan ekstubasi. Di sini steroid
tidak diindikasikan. Sebagian kecil korban tenggelam mengalami kegagalan
pernapasan. Biasanya terjadi setelah aspirasi masif atau teraspirasi zat kimia
yang mengiritasi sehingga korban ini membutuhkan ventilasi mekanis.
Pemberian infus sering diberikan untuk meningkatkan fungsi hemodinamik.
Cairan yang biasanya digunakan adalah cairan isotonik (Ringer lactat, NaCl
fisiologis) dan cairan yang dipakai harus cukup panas (40-43oC) untuk pasien
hipotermi. Bila cairannya seperti suhu kamar (21oC) bisa memancing

timbulnya hipotermi. NGT harus dipasang sejak pertama pasien ditolong,
yang berguna untuk mengosongkan lambung dari air yang terhisap. Status
neurologis biasanya membaik bila oksigenasi jaringan terjamin. Perawatan
biasanya memakan waktu beberapa hari dan sangat ditentukan oleh status
paru.
Kategori C
Tindakan yang paling penting untuk kategori ini adalah intubasi dan
ventilasi. Vetilasi mekanis direkomendasikan paling tidak 24 sampai 48 jam
pertama, termasuk mereka yang usaha bernapasnya baik setelah resusitasi
untuk mencegah kerusakan susunan saraf pusat akibat hipoksia dari
pernapasan yang tidak efektif. Pedoman ventilasi awal FiO2 1,0 digunakan
selama fase stabilisasi dan transfer. Kecepatan ventilasi awal 1,5 sampai 2 kali
kecepatan pernapasan normal sesuai dengan usia korban, tekanan espirasi 4
sampai 6 Cm H2O. Penyesuaian ini harus dilakukan untuk mendapatkan nilai
gas darah arteri sebagai berikut: PaO2 100 mmHg atau 20-30 mmHg. Bik-Nat,
bronchodilator, diuretik, dan antibiotik diberikan apabila korban tenggelam.
Penelitian membuktikan bahwa mortalitas setelah 5 hari pengobatan menurun
dari 50% menjadi 25% sampai 35%. Surfactan yang sering digunakan adalah
surfactan sintetik (Exosurf) dengan dosis 5 ml/kgBB diberikan melalui
nebulizer terus-menerus selama priode pengobatan.
Disfungsi kardiovaskular harus dikoreksi dengan cepat untuk
menjamin tranfer oksigen yang adekuat ke jaringan. Resusitasi jantung paru
perlu dilanjutkan pada korban yang mengalami hipotensi dan syok setelah
membaiknya ventilasi dan denyut nadi harus diberikan bolus cairan kristaloid
20 ml/kgBB. Tindakan ini harus diulangi bila tidak memberikan respons yang
memuaskan1,5. Apabila tekanan darah tetap rendah, obat inotropik IV harus
diberikan. Dopamin dan Dobutamin harus digunakan pada pasien yang
mengalami takikardi sedangkan epinefrin diberikan pada pasien bradikardi.
Pasien dengan suhu tubuh < 30oC harus segera dipanaskan untuk menjamin
fungsi jantung. Kejang diatasi secara konvensinal: pada awal diberikan
benzodiazepin diikuti dengan pemberian phenobarbital seperti Vecuronium
atau Pancuronium 0,1--0,2 mg/kgBB IV bisa digunakan untuk pasien yang
gelisah agar pemberian ventilasi lebih efisien, mengurangi kebutuhan
metabolik, serta bisa menekan risiko atau ekstubasi yang tak terencana akibat

trauma jalan napas. Bila pasien tetap gelisah, diberikan morfin sulfat 0,1
mg/kgBB IV atau Benzodiazepin 0,1 mg/kgBB IB diberikan setiap 1--2 jam
untuk sedasi. Pasien kategori C3 dan C4 harus mendapat pengawasan dan
tindakan untuk mempertahankan sistem metabolik, ginjal, hematologi,
gastrointestinal, dan neurologis serta dievaluasi dengan ketat setelah
pengobatan dimulai.
KESIMPULAN
Kegawatdaruratan pada korban tenggelam terkait erat dengan masalah
pernapasan dan kardiovaskuler yang penanganannya memerlukan penyokong
kehidupan jantung dasar dengan menunjang respirasi dan sirkulasi korban dari
luar melalui resusitasi dan mencegah insufisiensi. Terhadap air laut atau air
tawar akan mengurangi perkembangan paru, karena air laut bersifat hipertonik
sehingga cairan akan bergeser dari plasma ke alveoli. Tetapi, alveoli yang
dipenuhi cairan masih bisa menjalankan fungsi perfusinya sehingga
menyebabkan shunt intra pulmonary yang luas. Sedangkan air tawar bersifat
hipotonik sehingga dengan cepat diserap ke dalam sirkulasi dan segera
didistribusikan. Air tawar juga bisa mengubah tekanan permukaan surfaktan
paru sehingga ventilasi alveoli menjadi buruk sementara perfusi tetap
berjalan. Ini menyebabkan shunt intrapulmonary dan meningkatkan hipoksia.
Di samping itu, aspirasi air tawar atau air laut juga menyebabkan oedem paru
yang berpengaruh terhadap atelektasis, bronchospasme, dan infeksi paru.
Perubahan kardiovaskuler yang terjadi pada korban hampir tenggelam
terutama akibat dari perubahan tekanan parsial (PaO2) dan keseimbangan
asam basa. Sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh adalah perubahan
volume darah dan konsentrasi elektrolit serum. Korban hampir tenggelam
kadang-kadang telah mengalami bradikardi dan vasokonstriksi perifer yang
intensif sebelumnya. Oleh sebab itu, sulit memastikan pada waktu kejadian
apakah aktivitas mekanik jantung terjadi. Bradikardi bisa timbul akibat refleks
divingfisiologis pada air dingin, sedangkan vasokonstriksi perifer bisa juga
terjadi akibat hipotermi atau peninggian kadar katekolamin.
Hipoksia dan iskemia selama tenggelam akan terus berlanjut sampai ventilasi,
oksigenasi, dan perfusi diperbaiki. Sedangkan iskemia yang berlangsung lama

bisa menimbulkan trauma sekunder meskipun telah dilakukan resusitasi
jantung paru yang adekuat. Oedem cerebri yang difus sering terjadi akibat
trauma sitotoksik yang disebabkan oleh anoksia dan iskemia susunan syaraf
pusat yang menyeluruh. Kesadaran yang hilang bervariasi waktunya, biasanya
setelah 2 sampai 3 menit terjadi apnoe dan hipoksia. Kerusakan otak yang
irreversiblemulai terjadi setelah 4 sampai 10 menit anoksia. Ini memberikan
gambaran bahwa hipoksia mulai terjadi dalam beberapa detik setelah orang
tenggelam, diikuti oleh berhentinya perfusi dalam 2 sampai 6 menit. Otak
dalam suhu normal tidak akan kembali berfungsi setelah 8 sampai 10 menit
anoksia walaupun telah dilakukan tindakan resusitasi. Anoksia dan iskemia
serebri yang berat akan mengurangi aktivitas metabolik akibat peninggian
tekanan intrakranial serta perfusi serebri yang memburuk. Ini dipercayai
menjadi trauma susunan saraf pusat sekunder.
Hampir sebagian besar korban tenggelam memiliki konsentrasi
elektrolit serum normal atau mendekati normal ketika masuk rumah sakit.
Hiperkalemia bisa terjadi karena kerusakan jaringan akibat hipoksemia yang
menyeluruh.
DAFTAR PUSTAKA
1. DiMaio VJ, DiMaio D. Death by drowning. DiMaio VJ, DiMaio D, editors. In:
Forensic pathology second edition. USA: CRC Press LLC; 2001.
2. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Mun’im TWA, Sidhi, Hertian
S, dkk. Kematian akibat asfiksia mekanik. Dalam: Ilmu kedokteran
forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia; 2007: 64-70.
3. Rijal S. Near Drowning.Bagian Ilmu Anak Universitas Sumatera Utara.
2011. Available at: http://www.tempo.co.id/medika/arsip/062001/pus-
2.htm. Accessed: July 2013.
4. Idries AM. Pedoman ilmu kedokteran forensik edisi pertama. Jakarta:
Binarupa Aksara; 2007: 182-8.
5. Dix J. Asphyxia (suffocation) and drowning. Dix J, editor. In: Color atlas
of forensic pathology. USA: CRC Press LLC; 2000.