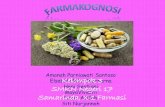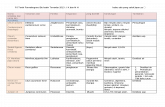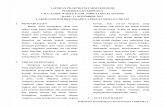evaluasi simplisia
-
Upload
lialestari -
Category
Documents
-
view
537 -
download
46
description
Transcript of evaluasi simplisia

Pengujian Parameter Non Spesifik
Ekstrak
Identifikasi Simplisia (Depkes, 1989)
Identikasi simplisia dilakukan dengan memeriksa pemerian dan melakukan pengamatan
simplisia baik secara makroskopik maupun secara mikroskopik.
Pemeriksaan makroskopik
Pemeriksaan makroskopik dilakukan terhadap simplisia meliputi warna, ukuran dan tekstur
rimpang
Pemeriksaan maksroskopik
Dilakukan dengan cara menaburkan serbuk simplisia di atas kaca objek yang telah
diteteskan dengan kloralhidrat dan ditutuo dengan kaca penutup kemudian dilihat di bawah
mikroskop. Dilkakukan juga uji dengan menggunakan aquadest sebaai pengganti
kloralhidrat.
Parameter nonspesfik
Penetapan kadar air
Penetapan kadar air di dalam ekstrak, dilakukan secara destilasi. Tujuan penetapan kadar air
adalah mengetahui besarnya kandungan air, terkait dengan kemurnian dan kontaminasi
yang mungkin terjadi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa ekstrak etanol rimpang kunyit
yang diuji mempunyai kisaran kadar air 6,0 – 7,0 % v/b, sedangkan ekstrak terpurifikasi
mempunyai kadar air 2,0 % v/b. Kandungan air maksimal yang di-perbolehkan terdapat di
dalam ekstrak rimpang kunyit dalam buku Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia
adalah 4,0 % (Azizah, 2013).
Dilakukan dengan azeotropi (destilasi toluena) dnegan menggunakan labu 500 ml yang
dihbungkan dengan pendingin air ballik dengan pertolonga alat penampung, tabung peneria
5 ml berskala 0,1 ml. Pemansa yang digunakan adalah pemansa listrik yang suhunya dapat
diatur

Cara kerja: ke dalam labu alas bulat dimasukkan 200 ml tolena dan 2 ml air suling, didestilasi
selaam 2 jam. Toluena didinginkan selama 30 emnit dan volume air dlaam tabung penerima
dibaca. Kemudian ke dalam labu tersebut dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah
ditimbang seksaa, labu dipanaskan selama 15 menit. Setelah toluena mendidih, kecepatan
tetesan diatur 2 etes untuk setipa detik samapi sebagaina besar air terdestilasi, kemudian
kecepatan destilasi dinaikkan samapi 4 tetes per detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian
dalam pendingiin dibilas dengan toluena. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian
tabung penerima dibiarkan mendingin sampai suhu kamar. Sete;ah air dan toluena memisah
sempurna baca volume air dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua volume air yang dibaca
sesuai denagn kandungan air yang ada di dalam bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung
dalam persen (WHO,1992).
Penetapan kadar abu total
Penetapan kadar abu total dan kadar abu tak larut asam dilakukan dengan pengabuan
ekstrak dalam krus di dalam tanur pada suhu 800oC. Disini terjadi pemanasan bahan pada
temperatur dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga
yang tertinggal hanya unsur mineral dan anorganik. Tujuannya adalah untuk memberikan
gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai
terbentuknya ekstrak. Selain itu penetapan kadar abu juga dimaksudkan untuk mengontrol
jumlah pencemar benda-benda organik seperti tanah, pasir yang seringkali terikut dalam
sediaan nabati. Kadar abu total yang diperbolehkan dalam ekstrak rimpang kunyit tidak
lebih dari 0,4%dan kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,08 % (Azizah, 2013).
Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama dimasukkan ke dalam krus
porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan. Kus dipijarkan perlahan-lahan
hingga arang habis, kemudian didinginkan dan ditimbang hingga diperoleh boot tetap. Kadar
abuu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989).
Penetapan kadar sari yang larut air
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24 jam dalam 100
ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air suling sampai 1 liter) dalam labu bersumbat
sambil sekali-sekali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam.

Saring, diuapkan 20 ml filtrat hiingga kering dalam cawac dangkal berdasar rata yang telah
ditara, dipanaskan sisa pada suhu 105 oC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air
dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989)
Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol
Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikerigkan di udara dimaserasi selama 24 jam dalam 100 ml
etanol 95% dalam labu tersumbat sambil sekali-sekali diocok selama 6 jam pertama,
kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat untuk menghindari penguapan
etanol, 20 ml filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah
ditara dan dipanaskan pada suhu 105 oC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air
dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Ditjen POM, 1989)
Karakterisasi Simplisia
Penetapan Susut Pengeringan
1 gram simplisia ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam krus porselen bertutup yang
sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105oC selama 30 menit dan telah ditara. Simplisia
diratakan dalam krus porselen dengan menggoyangkan krus hingga merata. Masukkan ke
dalam oven, buka tutup krus, panaskan pada temperatur 100oC sampai dengan 105oC,
timbang dan ulangi pemanasan sampai didapat berat yang kostan (Depkes, 1989 ; Depkes,
1979)
Perhitungan Rendemen
Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui % perubahan suatu bahan pangan
setelah mengalami proses pengolahan. Perhitungan rendemen mie basah dan ekstrak
kunyit dapat dilihat sebagai berikut
% rendemen ekstrak kunyit = bobot ekstrak kunyit
bobot kunyit (g )+air(ml)x100 %
Pola dinamolisis
Proses dinamolisis dilakukan untuk memberikan gambaran secara kualitatif dari kandungan
kimia yang terdapat dalam ekstrak karena masing-masing ekstrak memiliki pola dinamolisis
yang berbeda. Uji dinamolisis dilakukan dengan cara menuangkan sekitar 1/3 ekstrak cair ke

dalam cawan petri, kemudian ditutup dengan kertas saring bersumbu vertical yang
menghubungkan cairan ekstrak dengan kertas saring. Uji dinamolisis dilakukan selama lebih
kurang 10 menit sampai dihasilkan noda pada kertas saring, lalu diamati polanya.
Pola kromatogram
Uji paremeter selanjutnya adalah pola kromatogram Lapis Tipis (KLT). KLT merupakan salah
satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan
komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Prinsip kerjanya
memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang
digunakan. Mula-mula kertas silica gel dipotong dengan ukuran (10 cm x 1 cm), lalu kertas
tersebut ditandai dengan garis di ujung atas dan bawah masing- masing 1 cm, lalu hasil
maserat ditotolkan diujung bawah titik. Penotolan dilakukan berulang pada tempat yang
sama dengan rentang waktu tertentu untuk menghindari kemungkinan totolan waktu
terlalu lebar dan menghindari terjadinya tailing. Tailing ini terjadi sebagai akibat dari
kesalahan penotolan senyawa, sehingga pita yang terbentuk berekor, dapat pula disebabkan
karena pengembang yang tidak sesuai. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari
bentuk plat silica dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan.
Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran
antara sampel dengan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut.
Untuk KLT kali ini digunakan silica gel GF 254, ini adalah jenis silica yang akan menunjukkan
fluoresensi kuning-hijau di bawah sinar UV 254 nm. Fase diam adalah fase yang terikat pada
pendukung, sedangkan fase gerak adalah fase yang bergerak melalui fase diam.
Pengembang yang digunakan pada metode ini adalah kloroform : etanol : asam asetat
glacial dengan perbandingan (9,4 : 0,5 : 0,1). Pengembang dibiarkan di dalam chamber
sampai jenuh, setelah jenuh plat KLT dimasukkan ke dalam chamber sampai fase gerak
mencapai batas atas dari plat KLT. Dipilih pengembang ini karena larutan pengembang ini
mampu memisahkan komponen-komponen kurkuminoid. Pengembang yang digunakan
untuk proses KLT ini bersifat non-polar. Silika gel dapat membentuk ikatan hydrogen di
permukaannya, karena pada permukaannya terikat gugus hidroksil. Oleh karenanya, silica
gel sifatnya sangat polar. Sementara itu, fase gerak yang digunakan dalam percobaan ini

bersifat non-polar, maka pada saat campuran dimasukkan, senyawa-senyawa yang semakin
polar akan semakin lama tertahan di fase stasioner, dan senyawa-senyawa yang semakin
tidak (kurang) polar akan terbawa keluar kolom lebih cepat. Setelah fase gerak sampai pada
batas atas dari plat KLT, kemudian plat tersebut dikeluarkan dari chamber, dan dilihat
dibawah sinar UV dan dihitung RF-nya. Dari hasil KLT terdapat 3 titik (spot) yang tertarik
pada fase diam. Spot pertama memiliki Rf = 0,625; spot kedua Rf = 0,7125; dan spot ketiga
Rf = 0,875. Menurut literature senyawa kurkuminoid yang merupakan zat aktif untuk
antiinflamasi dapat terdeteksi pada RF 0,6, maka dari itu hasil KLT ini menunjukkan nilai Rf
yang sudah sesuai dengan literature. Senyawa kurkumin dapat mengalami penurunan
dengan lepasnya gugus –OCH3 dalam setiap penurunan. Kurkumin akan mengalami dua kali
penurunan, dimana turunan pertamanya adalah demetoksi kurkumin dan turunan keduanya
adalah bis-demetoksi kurkumin. Kurkumin akan terelusi paling akhir (berada paling bawah)
karena sifatnya yang polar.
Bobot jenis
Penetapan bobot jenis ekstrak dapat dilakukan sebagai berikut:
Ditimbang piknometer dengan volume tertentu dalam keadaan kosong. Piknometer ini
berfungsi sebagai alat untuk menentukan bobot jenis ekstrak. Kemudian piknometer diisi
penuh dengan air dan ditimbang ulang. Kerapatan air dapat ditetapkan. Kemudian
piknometer dikosongkan dan diisi penuh dengan ekstrak, lalu ditimbang. Melalui berat
ekstrak yang mempunyai volume tertentu, dapat ditetapkan kerapatan ekstrak.
Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Selain menggunakan spektrofotometer FTIR, profil kimiawi
tiga ekstrak yang memiliki nilai IC50 paling rendah dianalisis pula menggunakan
kromatografi lapis tipis (KLT). Profil kimiawi yang dianalisis adalah jumlah senyawa yang
terkandung dalam ekstrak ramuan terbaik yang ditunjukkan oleh jumlah spot yang terpisah
ketika dielusi menggunakan eluen yang sesuai. Ekstrak kental hasil maserasi dilarutkan
dengan etanol 96% hingga diperoleh konsentrasi 10000 mg/L. Ekstrak tersebut selanjutnya
ditotolkan pada fase diam, yaitu silika gel F254 menggunakan aplikator Camag Linomat 5.
Pelarut yang digunakan sebagai fase gerak (eluen) adalah campuran kloroform dan
diklorometana dengan perbandingan 0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30,

80:20, 90:10, dan 100:0. Sebelum dilakukan pengembangan, bejana kromatografi
dijenuhkan terlebih dahulu menggunakan pelarut. Setelah itu, plat yang sudah ditotolkan
ekstrak dimasukkan ke dalam bejana kromatografi dan pengembangan dilakukan hingga
eluen mencapai jarak kurang lebih 0.5 cm dari tepi atas plat. Setelah dilakukan
pengembangan, plat diangkat dan dideteksi profil kromatogramnya menggunakan lampu UV
dengan panjang gelombang 366 nm (Lestari, 2010).
Uji Kualitatif dan Kuantitatif Kurkumin
Analisis kromatografi lapis tipis (KLT) kualitatif dan kuantitatif kurkumin menggunakan fase
diam lempeng silika gel 69 F254 dan fase gerak kloroform : etanol : asam asetat glasial (94 :
5 : 1 v/v). Sebelum dilakukan penotolan sampel, fase diam harus diaktifkan dengan cara
dipanaskan terlebih dahulu dalam oven pada suhu 110o C selama 15 menit. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan daya absorbsi dari fase diam. Pembuatan kurva baku
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan luas area. Larutan
standar dibuat dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,4; dan 1,6 μg/μl. Sedangkan larutan
sampel dibuat dengan konsentrasi 10 mg/ml dengan volume penotolan sebanyak 5 μl.
Sebelum dilakukan pengembangan, bejana pengembang dijenuhkan dengan uap fase gerak
agar pemisahan sampel dapat optimal dan untuk mempercepat elusi (Azizah, 2013).
Pembuatan kurva baku bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan
luas area. Larutan standar dibuat dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,4; dan 1,6 μg/μl.
Sedangkan larutan sampel dibuat dengan konsentrasi 10 mg/ml dengan volume penotolan
sebanyak 5 μl. Sebelum dilakukan pengembangan, bejana pengembang dijenuhkan dengan
uap fase gerak agar pemisahan sampel dapat optimal dan untuk mempercepat elusi. Profil
kromatografinya terlihat pada Gambar 1.
Menurut pengamatan dengan UV 366 nm (Gambar 1), deteksi tidak digunakan dengan
pereaksi semprot karena kurkumin sudah berwarna jika dilihat pada UV 366 nm. Pada
pengamatan dengan UV 366 nm terdapat bercak dengan Rf 0,51 (bercak 1) baik pada
pembanding kurkumin maupun bercak ekstrak etanol dan ekstrak terpurifikasi. Bercak
tersebut merupakan senyawa kurkumin karena adanya kesamaan warna dan nilai Rf pada
masing-masing bercak ekstrak dan pembanding kurkumin. Pada sampel masing-masing
ekstrak terdapat bercak dengan nilai Rf 0,36 (bercak 2) yang merupakan senyawa demetoksi

kurkumin dan bercak dengan nilai Rf 0,25 (bercak 3) yang merupakan senyawa bisdemetoksi
kurkumin. Kurkuminoid dalam rimpang kunyit meliputi senyawa kurkumin, demetoksi
kurkumin dan bisdemetoksi kurkumin. Bercak senyawa demetoksi kurkumin dan
bisdemetoksi kurkumin tidak ditemukan pada pembanding kurkumin (Azizah, 2013).
Gambar 1. Profil KLT ekstrak etanol,
ekstrak terpurifikasi dan kurkumin standar
Keterangan :
Bercak 1 (Rf 0,51) = senyawa kurkumin
Bercak 2 (Rf 0,36) = senyawa demetoksi kurkumin
Bercak 3 (Rf 0,25) = senyawa Bisdemetoksi kurkumin.
Bercak a – f = ekstrak etanol terpurifikasi
Bercak g – l = ekstrak etanol
Bercak m – r = standar kurkumin 1.6; 1.4; 1.2; 0.8; 0.4 dan 0.2 μg/μl
Fase gerak = kloroform : etanol : asam asetat glasial (94 : 5 : 1)
Fase diam = Silica gel 60 F 254
Dapus

Lestari, T.A, 2010. Profil Kimiawi Ekstrak Ramuan Kunyit, Temulawak, Dan
Meniran Berdasarkan Aktivitas Antioksidan. Institut Pertanian Bogor.
Azizah, B., Nina Salamah. 2013. Standarisasi Parameter Non Spesifik dan Perbandingan Kadar Kurkumin Ekstrak Etanol dan Ekstrak Terpurifikasi Rimpang Kunyit. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Ratna, T.S. 2009. Uji efek antiinflamasi dari kombinasi ekstrak rimpang jahe merah (zingiber officinale) dan ripang kunyit (curcuma domestica Val.) dalam sediaan topikal pada mencit jantan. Universitas Sumatera Utara
WHO Collaborating Center for Quality Assurance of Esential Drugs. Prosedur Operasional Baku Uji Toksisitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan RI, 1991; 39-44, 120-144.
World health organization (2007). Monograph on selected medicinal plants, (Vol. 3) geneva. World helath organization.
BPOM, 2010a, Acuan Sediaan Herbal Volume V Edisi 1. BPOM RI, Jakarta.
BPOM, 2010b, Monografi Ekstrak Tumbuhan Indonesia, Direktorat Standardisasi Obat Trandisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM RI, Jakarta.
Depkes, 2008, Farmakope Herbal Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Dtjen Pom. 1989. Materia medika indonesia. Jilid IV. Departemen kesehatan RI. Jakarta.
Depkes Republik Indonesia. (1989). Materia Medika Indonesia (Jilid V). Jakarta : Depkes Republik Indonesia. Depkes Republik Indonesia. (2000). Parameter Standar Umum Pembuatan Ekstrak Tumbuhan Obat. Jakarta: Depkes Republik Indonesia. Depkes Republik Indonesia. (1979). Farmakope Indonesia (Edisi III). Jakarta : Depkes Republik Indonesia.