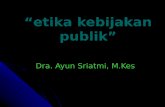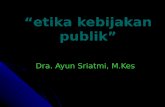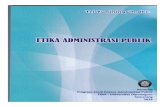Etika Kebijakan Publik
-
Upload
hedicupiadi -
Category
Documents
-
view
267 -
download
4
Transcript of Etika Kebijakan Publik

BAB 1
PENDAHULUAN
Masalah tentang etika dalam kebijakan publik di Indonesia kurang dibahas
secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah
disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam kebijakan publik di Indonesia
adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang
berkaitan dengan kebijakan publik. Padahal, dalam literatur tentang kebijakan
publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan
publik yang dilayani sekaligus keberhasilan kebijakan publik itu sendiri.
Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase kebijakan publik mulai
dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan,
sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan
tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat
dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor
telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan yang
lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six
great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan
(liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah
para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak
adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong
atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen kebijakan.
Dalam kebijakan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit
ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang
orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu,
1

kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian
etika kebijakan publik terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan
secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi
beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa
pelanggaran moral atau etika dalam kebijakan publik di Indonesia akan terus
meningkat
Pentingnya Etika dalam Kebijakan Publik.
Saran klasik di tahun 1900 sampai 1929 untuk memisahkan antara
administrasi dan politik (dikotomi) menunjukan bahwa administrator harus
sungguh-sungguh netral, bebas dari pengaruh politik ketika memberikan
pelayanan publik. Akan tetapi kritik bermunculan menentang ajaran dikotomi
administrasi – politik pada tahun 1930-an, sehingga perhatian mulai ditujukan
kepada keterlibatan para administrator dalam keputusan-keputusan publik atau
kebijakan publik. Sejak saat ini mata publik mulai memberikan perhatian khusus
terhadap “permainan etika” yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan.
Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak
semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip
administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap
kontribusinya terhadap public interest atau kepentingan umum (Henry, 1995).
Alasan mendasar mengapa kebijakan publik harus diberikan adalah adanya public
interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena
pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam
membuat/menatapkan kebijakan ini pemerintah diharapkan secara profesional
2

melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai
siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dan sebagainya.
Padahal, kenyataan menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki
tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa
semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela
kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus
membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan
struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat
pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam
bertindak etis, atau dengan kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”. Alasan
lain lebih berkenaan dengan lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan
pelayanan itu sendiri. Desakan untuk memberi perhatian kepada aspek
kemanusiaan dalam organisasi (organizational humanism) telah disampaikan oleh
Denhardt. Dalam literatur tentang aliran human relations dan human resources,
telah dianjurkan agar manajer harus bersikap etis, yaitu memperlakukan manusia
atau anggota organisasi secara manusiawi. Alasannnya adalah bahwa perhatian
terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannya sangat relevan
dengan upaya peningkatan produktivitas, kepuasan dan pengembangan
kelembagaan.
Alasan berikutnya berkenaan dengan karakteristik masyarakat publik yang
terkadang begitu variatif sehingga membutuhkan perlakuan khusus.
Mempekerjakan pegawai negeri dengan menggunakan prinsip “kesesuaian antara
orang dengan pekerjaannya” merupakan prinsip yang perlu dipertanyakan secara
etis, karena prinsip itu akan menghasilkan ketidak adilan, dimana calon yang
3

dipekerjakan hanya berasal dari daerah tertentu yang relatif lebih maju. Kebijakan
affirmative action dalam hal ini merupakan terobosan yang bernada etika karena
akan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum minoritas, miskin, tidak berdaya,
dsb untuk menjadi pegawai atau menduduki posisi tertentu. Ini merupakan suatu
pilihan moral (moral choice) yang diambil oleh seorang birokrat pemerintah
berdasarkan prinsip justice –as – fairness sesuai pendapat John Rawls yaitu
bahwa distribusi kekayaan, otoritas, dan kesempatan sosial akan terasa adil bila
hasilnya memberikan kompensasi keuntungan kepada setiap orang, dan
khususnya terhadap anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satu contoh
yang populer saat ini. Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan
tindakan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam penyusunan
kebijakan publik sangat besar. Kebijakan publik tidak sesederhana sebagaimana
dibayangkan, atau dengan kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan
dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik
pemberian pelayanan publik itu sendiri.
Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pengambil keputusan
dalam kebijakan publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan
kepada “keleluasaan bertindak” (discretion). Dan keleluasaan inilah yang sering
menjerumuskan pembuat kebijakan publik atau aparat pemerintah untuk bertindak
tidak sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada. Dalam pembuatan
kebikajakan yang berhubungan dengan pelayanan publik khususnya di Indonesia,
pelanggaran moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik
(pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas
4

kenyataan), desain organisasi pelayanan publik (pengaturan struktur, formalisasi,
dispersi otoritas) yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu, proses
manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase (mulai dari
perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, SDM, informasi, dsb.), yang
semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak
akuntabel, tidak adil, dsb.
Tidak dapat disangkal, semua pelanggaran moral dan etika ini telah
diungkapkan sebagai salah satu penyebab melemahnya pemerintahan Indonesia.
Alasan utama yang menimbulkan tragedi tersebut sangat kompleks, mulai dari
kelemahan aturan hukum dan perundang-undangan, sikap mental manusia, nilai-
nilai sosial budaya yang kurang mendukung, sejarah dan latar belakang
kenegaraan, globalisasi yang tak terkendali, sistim pemerintahan, kedewasaan
dalam berpolitik, dsb. Bagi Indonesia, pembenahan moralitas yang terjadi selama
ini masih sebatas lip service tidak menyentuh sungguh-sungguh substansi
pemenahan moral itu sendiri. Karena itu pembenahan moral merupakan “beban
besar” di masa mendatang dan apabila tidak diperhatikan secara serius maka
proses “pembusukan” terus terjadi dan dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.
5

BAB 2
KERANGKA TEORITIS
2.1 Konsep dan Definisi Etika
Secara etimologik, etika berasal dari kata Yunani “Ethos” yang berarti
watak kesusilaan atau adat. Identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata
Latin “Mos” yang bentuk jamaknya “Mores” yang berarti adat atau cara hidup.
Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari terdapat
sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang
dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.
Istilah lainnya yang identik dengan etika; susila (sansekerta) yang berorientasi
kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su) dan akhlak
(arab) yang berarti moral.
Pakar teori administrasi seperti Poedjawijatna (1972:3) menggambarkan
konsep etika merupakan cabang dari filsafat, dimana sebagai filsafat etika mencari
keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya, dengan kata lain etika hendak
mencari tindakan manusia manakah yang baik atau manakah yang buruknya.
Sedangkan Bertens dan Keban (2004:147), menggambarkan konsep etika dengan
beberapa arti salah satu diantaranya dan biasa diginakan orang adalah kebiasaan,
adat atau akhlak dan watak.
Selanjutnya Salam Burhanuddin (1991:1) mengungkapkan bahwa etika
adalah sebuah refelksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang
menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara
pribadi maupun sebagai kelompok. Pakar lainnya, Magnis Suseno (1990),
6

mengatakan bahwa etika adalah ilmu dan bukan sebuah ajaran, yang memberi kita
norma tentang bagaimana kita hidup adalah moralitas. Hobbes dalam Widodo
(2006:48), mengatakan bahwa etika berkaitan dengan standar perilaku diantara
orang-orang dalam kelompok sosial.
Penjelasan mengenai etika yang lebih detil diungkapkan oleh Bratawijaya
(1992:243), adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak dan moral, yang
diuraikan menjadi dua jenis etika yaitu:
1. Etika Umum adalah menyajikan suatu pendekatan yang teliti mengenai norma-norma yang berlaku umum bagi setiap warga masyarakat, yang terbagi dalam tiga bagian yaitu; norma santun, norma hukum, dan norma moral.
2. Etika Khusus adalah penerapan etika umum dalam kegiatan pofesi, misal etika dosen, etika sekertaris, etika dokter, etika bisnis dan etika pelayanan.
Dari beberapa uraian definisi tentang etika tersebut dapat disimpulkan
bahwa terdapat tiga arti penting etika, yaitu (1) sebagai nilai-nilai moral dan
norma-norma moral yang menjadi rujukan bagi setiap orang atau suatu kelompok
dalam mengatur perilakunya, atau yang disebut dengan “sistem nilai”, (2) sebagai
kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”, dan (3)
sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”.
Secara umum nilai-nilai moral nampak dari enam nilai besar atau yang
dikenal dengan “six great ideas” Denhardt (1988), yaitu nilai kebenaran (truth),
kebaikan (goodness), keindahan (beauty), kebebasan (liberty), kesetaraan
(equality), dan keadilan (justice).
Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartika
sebagai filsafat dan “professional standards” (kode etik), atau “rights rules of
conduct” (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi
pelayanan publik atau administrasi publik (Denhardt, 1988:17), etika didefinisikan
7

sebagai cabang filsafat yang berkenaan dengan nilai-nilai yang berhubungan
dengan perilaku manusia, dalam kaitannya dengan benar atau salah suatu
perbuatan, dan baik atau buruk motif dari tujuan perbuatan tersebut.
2.2 Etika Administrasi Publik
Etika merupakan bagian dari filsafat, niali dan moral. Etika bersifat
abstrak dan berkenaan dengan persoalan “baik” dan “buruk”, sedangkan
Administrasi Publik bersifat konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan
publik. Artinya kedua hal tersebut saling bertolak belakang yang menimbilkan
masalah yaitu bagaimana menghubungkan gagasan administrasi seperti
keteraturan, efisiensi, kemanfaatan dan kinerja yang dapat menrapkan etika dalam
prakteknya sehingga terwujud suatu hal yang baik dan menghindari yang buruk
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab administrator.
Menurut Chandler dan Plano (1988), dalam etika terdapat empat aliran
utama, yaitu:
1)Empirical theory, berpendapat bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum.
2)Rational theory, berasumsi bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari alasan rasional dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman.
3)Intuitive theory, berasumsi bahwa manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk.
4)Relevation theory, berasumsi bahwa yang benar dan salah berasal dari kekuasaan di atas manusia yaitu dari Tuhan.
Disamping keempat aliran tersebut, yang sering dipertentangkan dalam
administrasi publik karena pengaruhnya kepada administrator adalah pendekatan
teleologis atau utilitarianisme, deontologist dan virtue ethics.
Pendekatan teleologis dan utilitarianisme merupakan pendekatan yang
berorientasi kepada tujuan dan difokuskan kepada akibatnya Heichelbech
8

(2003:1189-1191). Teologi secara khusus berkenaan dengan maksud dan tujuan,
sementara utilitarian berkaitan dengan akibat yang dirasakan apakah memenuhi
kepentingan atau meningkatkan kepuasan.
Menurut Aristoteles, tujuan dan maksudlah yang menentukan apakah
sesuatu itu baik atau bermanfaat. Dengan kata lain, etis tidaknya suatu tindakan
ditentukan oleh motif atau tujuannya seseorang melakukan tindakan tersebut.
Sayangnya pernyataan tersebut ditentang oleh “scientific revolution” yang
berpendapat bahwa bukan tujuan atau maksud yang menentukan sesuatu itu baik
atau tidak baik suatu tindakan, tetapi lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip ilmiah
atau rasionalisasi yang digunakan dalam suatu tindakan.
Aliran utilitarianisme pertama muncul di Inggris pada akhir abad ke
delapan belas. Aliran ini menolak rationalisme dengan memberikan
argumentasinya bahwa sesuatu itu etis (baik) atau tidak etis (atau buruk), sangat
tergantung bukan pada alasan yang digunakan tetapi kemampuan menghasilkan
suatu kenikmatan, atau mengurangi kesengsaraan seseorang dalam proses hidup
dan kehidupan manusia. Jeremy Bantham dalam tulisannya berjudul The
Principles of morals and Legislation, berpendapat bahwa prinsip etis atau tidak
etisnya suatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan
kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan. Dengan kata lain, etika benar-benar
peduli terhadap kebahagiaan setiap orang dalam proses hidup dan kehidupan.
Mengikuti Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill dalam tulisan utilitarianism
setuju bahwa sesuatu kegiatan dianggap baik secara etis tergantung kepada utility
atau kegunaannya yaitu apakah kegiatan itu akan meningkatkan kebahagiaan atau
kesenangan, dan dianggap buruk secara etis bila tidak mendatangkan kesenangan,
9

akan tetapi ia akan lebih menekankan bahwa tidak hanya sekedar meningkatkan
kebahagiaan atau mengurangi kesengsaraan bagi yang berkepentingan, tetapi lebih
penting lagi menghasilkan kebahagiaan paling tinggi bagi setiap orang di muka
bumi ini. Jadi dalam Pandangan Mill, suatu kegiatan itu etis bila menghasilkan
kebahagiaan yang lebih besar dan lebih luas lagi cakupannya. Untuk menghasikan
yang lebih besar ini diperlukan peningkatan efisiensi, bila efisiensi telah
dimaksimalisasikan dalam suatu birokrasi maka menurut pandangan utilitarian,
birokrasi tersebut telah bertindak etis.
Apa yang disampaikan dalam utilitarianisme ini dikritik karena dalam
kenyataannya tidak mudah menghitung utilitas atau kegunaan secara tepat.
Demikian pula tidak dipersoalkan kebahagiaan siapa, apakah yang ingin
dibahagiakan itu adalah legitimate berhak mendapatkannya, atau kepada orang
atau kelompok orang tertentu yang tidak pantas membahagiakannya. Atau
kepentingan yang dilayani harus benar-benar kepentingan dari orang-orang yang
membutuhkannya secara sah. Kritik yang lain datang dari kelompok utilitarian
kontemporer atau dikenal dengan nama consequenialists, dimana mereka
mempertanyakan mengapa harus kebahagiaan yang dijadikan ukuran, apakah
tidak sebaiknya mempertimbangkan juga kepentingan lain seperti hak-hak dasar
atau hak asasi manusia.
Deontologi merupakan salah satu cabanmg etika yang menekankan
kewajiban, tugas, tanggungjawab dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Tokoh
utamanya adalah Imanuel Kant dan Jhon Rawls dalam Keban (2004:151).
Dentologi berbeda dengan utilitarianisme dalam hal tidak memperhatikan atau
memperdulikan konsekuensi atau akibat dari suatu perubahan sebagai
10

pertimbangan moral, tetapi lebih menekankan compliance dan enforcement
(ketaatan dan kesesuaian) terhadap suatu kewajiban, tanggungjawab, aturan dan
prinsip-prinsip yang berlaku. Bagi kaum deontologist, ada banyak hubungan
nonconsequensil yang perlu diperhatikan, hubungan bapak dan anak, afiliansi
bisnis, yang dapat memperkaya kehidupan moral. Jhon Rawis menekankan bahwa
etis tidaknya sangat tergantung kepada apakah prinsip-prinsip utama telah diikuti
atau tidak, misalnya dalam mendistribusikan pelayanan publik atau barang publik,
telah menerapkan prinsip justice as fairness atau tidak. Deontologi di kritik karena
lebih menekankan rasionalitas, dan tidak memperhatikan unsur manusianya.
Karenanya sering dinilai sebagai konsep etika yang dangkal. Virture Ethics
berasal dari filsafat Yunani kuno, yang muncul sebagai reaksi terhadap aliran
utilitarianisme dan deontologi. Berdasarkan aliran ini baik atau buruk, benar atau
salah tidak tergantung dari akibat atau konsekunsi(utilitarianisme), tetapi dari
“The excellences of character” yang ditunjukkan dari integritas Bowman
(2003:1259-1263). Maka substansi aktual dari etika atau moral ini tidak dapat
dipahami dengan memprediksi hasil atau akibat, atau kesesuaian dengan
kewajiban, tetapi dipahami dari “internal imperative to do right”. Ketiga aliran
tersebut, menurut Bowman, membentuk segitiga etika (Ethical Triangel), dimana
aliran deontologi memusatkan perhatian pada kewajiban dan prinsip yang harus
diikuti. Ketiga aliran tersebut mewarnai isu etika atau moral dalam praktik
administrasi publik. Ada yang mempersoalkan apa yang dikerjakan pemerintah
dari aspek ketaatan dan pemenuhan kewajiban dan prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan (deontologi). Karena itu, etika jenis ini lebih berkenaan dengan cara
atau metode administrasi publik. Sementara itu ada yang mempersoalkan akibat
11

yang dirasakan atau dinikmati (utilitarianisme). Karena itu, etika ini berkenaan
dengan tujuan.
Dalam pemberian pelayanan publik, telah terjadi pergeseran paradigma
etika. Pergeseran tersebut dapat ditelusuri dalam tulisan Denhardt yang berjudul
The Ethics of Public Service (1988). Penulis ini menggambarkan sejarah etika
pelayanan publik melalui karya Wayne A. R. Leys tahun 1944, yang oleh penulis
disebut model-The 1940’s. Leys memberikan saran kepada pemerintah Amerika
Serikat tentang bagaimana menghasilkan suatu “good public policy decisions”. Ia
berpendapat bahwa sudah waktunya meninggalkan kebiasaan atau tradisi yang
selama ini selalu menjadi pegangan utama dalam menentukan suatu perumusan
kebijakan karena pemerintah terus berhadapan dengan berbagai masalah baru.
Denhardt (1988:6), mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan etika harus
digunakan dalam menilai apakah suatu kebijakan sudah dianggap baik atau buruk.
Singkatnya, dalam model ini dikatakan bahwa agar menjadi etis, diperlukan
seorang administrator selalu menguji dan mempertanyakan standar yang
digunakan dalam pembuatan kebijakan daripada yang hanya sekedar menerima
atau tergantung pada kebiasaan dan tradisi yang ada.
Hurst A. Anderson di tahun 1953 mengungkapkan dalam suatu pidatonya
dengan judul Ethical Values in Administration (nilai-nilai etika dalam
administrasi), katanya masalah etika sangat penting dalam setiap kebijakan
administratif, tidak hanya mereka yang memformulasikan kebijakan publik. Etika
itu sendiri harus dipandang sebagai asumsi-asumsi yang menuntun kehidupan dan
pekerjaan kita semua. Dengan kata lain, kita harus memiliki apa yang disebut
“philosophi of personal and soail living”. Denhardt (1988), pendapat ini
12

diklasifikasikan sebagai model II-The 1950’s yang berintikan bahwa agar
dianggap etis maka seorang administrator hendaknya mengevaluasi dan
mempertanyakan standar dan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar
perumusan suatu kebijakan. Standar-standar tersebut harus merefleksikan nilai-
nilai dasar yang ada pada suatu masyarakat, dan tidak sekedar bergantung semata
pada kebiasaan dan tradisi. Yang dimaksud nilai-nilai dasar (core values)
masyarakat meliputi antara lain kebebasan, kesetaraan, keadilan, kebenaran,
kebaikan dan estetika.
Tahun 1960-an memunculkan nuansa baru dalam etika pelayanan publik.
Robert T. Golembiewski memaparkan dalam tulisannya yang berjudul Man,
Management dan Morality tahun 1965, bahwa praktik-praktik birokrasi yang telah
berlangsung sekian lama yang didasarkan pada teori-teori birokrasi tradisional
telah membawa dampak negatif pada individu-individu yang bekerja dalam
birokrasi itu sendiri. Para individu tersebut merasa tertekan dan frustasi dan
karena itu sisi etika dari praktik tersebut perlu mendapatkan perhatian. Standar-
standar yang perlu ditetapkan dalam birokrasi jaman dulu belum tentu cocok
sepanjang masa, karena itu harus dilihat apakah masih pantas dipertahankan atau
tidak, disini Golembiewski melihat etika sebagai sesuatu yang harus disesuaikan
dengan waktu. Karena itu, Denhardt (1988), melihat pendapat ini Sebagai Model
III-The 1960’s, yang pada intinya agar menjadi etis seorang administrator
sebaiknya mengevaluasi dan mempertanyakan standar, atau asumsi yang
melandasi pembuatan suatu kebijakan, standar-standar tersebut harus
merefleksikan nilai-nilai dasar yang ada pada publik dan tidak semata bergantung
pada kebiasaan dan/atau budaya. Standar etika bisa berubah ketika seseorang
13

mencapai suatu pemahaman yang lebih baik terhadap standar-standar moral yang
berlaku secara umum.
Para ahli administrasi publik yanng tergolong dalam masyarakat New
public administration yang muncul di tahun 1970an, memberikan nuansa baru
atau kondisi baru yang mengharapkan agar administrator memperhatikan
“administratic responsibility”. David K. Hart, salah satu intelektualnya, menilai
bahwa administrasi publik saat itu sudah bersifat “impartial” dan sudah waktunya
mengubah paradigma lama untuk memperbaiki kepercayaan publik yang waktu
itu sudah pudar. Nilai keadilan yang disarankan disini sebenarnya hanya
merupakan sebagian dari “core values” yang telah disebutkan diatas, sehingga
pengalaman di tahun 1970an tersebut lebih menggambarkan penyempuarnaan
“content” atau isi dari etika itu sendiri, sebagai pelengkap dari tinjauan tentang
“process” dan “context” yang telah diungkapkan dalam model-model sebelumnya.
Model ini disebut model IV- The 1970’s, yang merupakan akumulasi
penyempurnaan dari model-model sebelumnya dimana dikatakan bahwa dengan
menjadi etis seorang administrator harus benar-benar memberi standar, atau
asumsi yang melandasi pembuatan kebijakan administratif. Denhardt (1988:16),
mengatakan bahwa standar-standar ini mungkin berubah dari waktu ke waktu dan
administrator harus mampu merespon tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan
baru dengan memperbaharui standar-standar tersebut. Isi dari standar-standar
tersebut harus merefleksikan komitmen terhadap nilai-nilai dasar masyarakat dan
administrator harus memahami bahwa yang akan bertanggungjawab penuh
terhadap standar yang digunakan dan terhadap kebijakan-kebijakan itu sendiri.
14

Setelah model keempat diatas, muncul beberapa pendapat secara
signifikan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan paradigma etika
pelayanan publik. Dua tokoh yang memberi kontribusi tersebut adalah John Rohr
dalam karyanya Ethics for Administrator tahun 1986. John Rohr Denhardt dalam
tulisannya memberikan sumbangan yang sangat berarti yaitu bahwa dalam proses
pengujian dan mempertanyakan standar dan asumsi yang digunakan dalam
pengambilan kebijakan diperlukan “indevendensi”, dan tidak boleh tergantung
dari pemikiran pihak luar seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri dan
sebagainya. Karena itu, Denhardt (1988), menyebutnya sebagai model V-After
Rohr, dimana dikatakan bahwa dapat disebut etis maka seorang administrator
harus secara independen masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan
standar-standar yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Isi dari standar
tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu ketika nilai-nilai sosial dipahami
secara lebih baik atau ketika masalah-masalah sosial baru diungkapkan.
Denhardt, (1988:22) mengatakan bahwa administrator harus memahami bahwa ia
akan bertanggungjawab baik secara perorangan maupun kelompok terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuat dan tahap standar etika yang dijadikan dasar
kebijakan-kebijakan.
Setelah model V yang didasarkan pada pendapat Denhardt (1988:26),
menggambarkan suatu model akhir yang disebut model VI-After Cooper. Model
ini menggambarkan pemikiran Cooper bahwa administrator, birokrasi dan etika
terdapat hubungan penting dimana etika para administrator justru sangat
ditentukan oleh konteks birokrasi dimana ia bekerja. Jadi lingkungan birokrasi
menjadi sangat menentukan, bahkan begitu menentukan sehingga seringkali para
15

administrator hanya memiliki sedikit “otonomi beretika”. Sehingga agar dapat
dikatakan etis apabila seorang administrator harus mampu mengatur secara
independen proses menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam
pembuatan kebijakan, paling tidak kebijakan yang secara sah dibuat pada
tingkatan birokrasi itu. Isi dari standar tersebut mungkin berubah dari waktu ke
waktu bila nilai-nilai sosial dipahami secara lebih baik dan masalah-masalah
sosial baru nulai terungkap. Administrator dalam hal ini harus siap menyesuaikan
standar-standar tersebut dengan perubahan-perubahan tersebut, senantiasa
merefleksikan komitmennya pada nilai-nilai dasar masyarakat dan tujuan
birokrasinya. Administrator bertanggungjawab secara perorangan dan profesional,
dan bertanggungjawab dalam birokrasi terhadap kebijakan yang dibuat dan
standar etika yang digunakan dalam kebijakan itu.
Dari gambaran singkat tentang pergeseran paradigma etika pelayanan
publik di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini etika dan moralitas sudah
mendapatkan perhatian yang serius dalam dunia pelayanan publik atau
administrasi publik. Tiga hal pokok yang menarik perhatian dalam paradigma ini
yaitu (1) proses menguji dan mempertanyakan standar etika dan asumsi, secara
independen; (2) isi standar etika yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar
masyarakat dan perubahan standar tersebut baik sebagai akibat dari
penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, maupun
sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru dari waktu ke waktu; (3)
konteks birokrasi dimana para administrator bekerja berdasarkan tujuan birokrasi
dan peranan yang dimainkan mereka, yang dapat mempengaruhi otonomi mereka
dalam beretika.
16

2.3 Implementasi Nilai-Nilai Etik
Implementasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik
yang dimiliki oleh administrator publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas
pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran., sedangkan pada
profesi yang lain masih belum ada. Tidak adanya kode etik ini memberikan
peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan
publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku
dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap
melalui aturan/tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik.
Kita perlu belajar dari negara yang sudah maju dan memiliki kedewasaan
bertika, seperti Amerika Serikat yang menetapkan nilai-nilai yang dijadikan kode
etik bagi administrator publik adalah menjaga integritas, kebenaran., kejujuran,
ketabahan, respek, perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan
kepentingan publik, perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia,
dukungan terhadap “sistem merit” dan program ”affirmative action”. Semua nilai
yang terdapat dalam kode Etik Administrasi ini tidak muncul dengan tiba-tiba
tetapi melalui suatu kajian yang mendalam dan membutuhkan waktu yang
lama,dan didukung oleh diskusi dan dialog yang berkelanjutan.
Untuk membantu menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral di
Indonesia, pengalaman negara-negara lain perlu diadopsi dan perlu berupaya
keras menerapkannya. Etika perumus kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika
evaluator kebijakan, etika administrasi publik/birokrat publik, etika perencana
publik, etika PNS, dan sebagainya harus diprakarsai dan mulai diterapkan
sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan dengan moral dan etika.
17

Salah satu etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai rujukan
atau referensi bagi para birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya yaitu American Society for Administration (ASPA), yang dikutip
oleh Widodo (2006:70) sebagai berikut:
1. Pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan di atas kepentingan sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah dan pada akhirnya bertanggungjawab kepada rakyat.
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Dalam artian bahwa semua tindakan birokrasi seharusnya mengacu kepada kepentingan rakyat.
4. Manajemen yang efektif dan efisien merupakan dasar bagi birokrasi. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan dan/atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan.
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan dan dikembangkan.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan, hadiah atau faviritisme yang merendahkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis).
7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan kasih sayang. Birokrasi publik harus menghargai sifat-sifat tersebut secara arif dan bijak untuk melaksanakannya.
8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan dan pengkajian tentang prioritas nilai tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tidak beretika.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggungjawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.
Nilai etika tersebut di atas dapat digunakan sebagai rujukan bagi birokrat
khususnya para pemimpin dalam bersikap, bertindak, berperilaku, dalam
merumuskan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi,
kewenangan dan tangungjawabnya, sekaligus dapat digunakan standar untuk
menilai, apakah sikap, tindakan, perilaku dan kebijakan-kebijakan itu dinilai baik
atau buruk oleh publik.
18

Selanjutnya yang dapat digunakan untuk menilai baik buruknya suatu
pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dapat dilihat dari baik buruknya
penerapan nilai-nilai sebagai berikut :
1. Efisiensi, yaitu para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat. Dalam artian bahwa para birokrat secara
berhati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik.
Dengan demikian nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber
daya yang dimilki secara cepat dan tepat, tidak boros dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi dapat dikatakan baik (etis) jika
birokrat publik menjalankan tugas dan kewenangannya secara efisien.
2. Efektivitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan
kepada publik harus baik (etis) yaitu memenuhi target atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan publik
dalam pencapaian tujuannya, bukan tujuan pemberi pelayanan (birokrat
publik).
3. Kualitas layanan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat
kepada publik harus memberikan rasa kepuasan kepada yang dilayani. Dalam
artian bahwa baik (etis) tidaknya pelayanan yang di birokrat kepada publik
ditentukan oleh kualitas pelayanan.
4. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan tanggungjawab birokrat dalam
merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Birokrat dalam
menjalankan dinilai baik (etis) jika responsibel dan memiliki profesional atau
kompetensi yang sangat tinggi.
19

5. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan administrasi publik. Birokrat yang baik
(etis) adalah birokrat yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya.
Etika administrasi publik tersebut di atas belum cukup menjamin untuk
menghapus perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada birokrasi publik.
Beberapa hal yang terpenting yaitu tergantung pada karakter dari masing-masing
pelaku atau orangnya masing-masing. Maka kesadaran melalui keimanan dan
ketaqwaan harus melekat pada diri orang tersebut. Orang yang mempunyai tingkat
religius yang tinggi tentu tidak akan melakukan KKN, jika orang tersebut
mengetahui dan meyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perilaku
yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji, terutama jika dilihat dari keyakinan dan
keagamaan yang mereka anut, karena segala perilaku harus
dipertanggungjawabkan di kemudian hari di hadapan Allah SWT. Dengan adanya
keimanan dan ketaqwaan yang kuat pada diri manusia sudah pasti tercegah
munculnya niat untuk melakukan KKN sekalipun kesempatan terbuka lebar untuk
melakukannya.
Oleh karena itulah menurut Widodo (2006:74), mengatakan bahwa
tindakan KKN pada dasarnya terjadi karena hasil pertemuan antara “niat” dan
“kesempatan” yang terbuka. Tindakan KKN bisa terjadi, baik pada birokrasi
publik tingkat tinggi, menengah, maupun rendahan. Karena itu untuk mencegah
KKN menurut Widodo adalah diupayakan untuk tidak mempertemukan antara
“niat” dan “kesempatan”, melalui mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung
tinggi dan mernegakkan etika administrasi publik pada jajaran birokrasi publik.
20

BAB 3
PEMBAHASAN
Dibutuhkan Kode Etik dalam administrasi publik. Kode etik administrasi
publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan
kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak.
Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita
telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah
pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah,
namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi
para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran
kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku
para pegawai atau pejabat dalam bekerja.
Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik adalah kode etik
yang dimiliki ASPA (American Society for Public Administration) yang telah
direvisi berulang kali dan terus mendapat kritikan serta penyempurnaan dari para
anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara
lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, menaruh perhatian,
keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan
lain, bekerja profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka dan
transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk
kepentingan publik, beri perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya
dirahasiakan, dukungan terhadap sistim merit dan program affirmative action.
21

3.1 Studi Kasus pada Universitas Garut
3.1.1 Sekilas Universitas Garut
Pembangunan kualitas sumberdaya dalam pembangunan nasional manusia
merupakan faktor kunci yang harus ditingkatkan. Sejalan dengan pemikiran
tersebut, maka pembangunan kualitas sumberdaya manusia merupakan sesuatu
keharusan. Apalagi saat ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diikuti oleh arus globalisasi dan informasi sangat membutuhkan tenaga-
tenaga ahli (sumberdaya manusia) yang handal dan bermutu.
Pendirian Universitas Garut yang berada di bawah naungan Yayasan
Universitas Garut (YUNGA), bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang
mampu memahami dan ahli dalam bidangnya serta menyesuaikan diri dengan
perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Berorientasi kepada
pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia dan pembangunan nasional.
Menganut paham pendidikan seumur hidup dan kemudian dalam mengembangan
diri serta berkeyakinan bahwa unsur sikap dan kemampuan hidup sama
pentingnya dengan pengetahuan. Juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
dalam mewujudkan sosok ilmuwan yang memiliki daya tranformasi iman-amanah
kekuatan ilmu-alamiah, keseyogyaan intelektual-integritas, keterjangkauan
visidiner-imajinatif, keharusan perspektif-inovatif, ketegaran kritis-etis, kearifan,
mandiri, terbuka, dan kesungguhan dedikasi patriotik.
Universitas Garut didirikan di Garut - Jawa Barat pada tanggal 21
Desember 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor: 0173/ D/ O/ 1998. Pembentukan Universitas Garut merupakan
22

penggabungan (merger) dari 5 (lima) perguruan tinggi swasta di Garut dan
sekaligus berubah bentuk menjadi Universitas Garut. Sampai saat ini, Universitas
Garut memiliki 7 (tujuh) Fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu:
Fakultas Ekonomi yang mengelola tiga program studi (Akuntansi-S1,
Manajemen-S1 dan Akuntansi-D3), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
mengelola dua program studi (Ilmu Administrasi Negara-S1, Kesejahteraan
Sosial-S1), Fakultas Teknik yang mengelola satu program studi (Telekomunikasi-
D3), Fakultas Agama yang mengelola satu program studi (Pendidikan Agama
Islam-S1), Fakultas Pertanian mengelola dua program studi (Agronomi-S1 dan
Peternakan S-1), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang
mengelola satu program studi (Farmasi-S1), Fakultas Ilmu Komunikasi, serta
Program Pascasarjana (S2) dengan kosentrasi Administrasi Negara.
3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Garut
Visi Universitas Garut adalah “Menjadi universitas terkemuka dalam
mengembangkan ilmu dan teknologi, serta menghasilkan sumberdaya manusia
terdidik, beriman, berkualitas, dan berahlak mulia dengan multi kompetensi
yang mampu bersaing pada tataran nasional, regional, dan global”.
Misi Universitas Garut yaitu:
1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari pendidikan,
penelitian, pengabdian masyarakat, serta meneguhkan agama dan budaya
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Garut pada
khususnya;
23

3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berkompetisi pada dunia
kerja;
4. Menggalakan kegiatan penelitian yang ditujukan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemaslahatan umat;
5. Mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membantu masyarakat
untuk memecahkan masalah rekayasa dalam hal meningkatkan mutu kerja
dan pendapatan masyarakat;
6. Menyelenggarakan sistem administrasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
Tujuan Universitas Garut yaitu:
1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian,
berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan
terampil serta sehat jasmani dan rohani;
2. Menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal
semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial;
3. Menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang
inovatif dan kreatif;
4. Memberikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan
keterampilan bagi anak yang berasal dari daerah/ bertempat tinggal di
daerah terpencil;
5. Memperhatikan dan mengembangkan anak didik yang berbakat istimewa
sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya;
24

6. Meningkatkan penulisan, penerjemahan serta penyebaran buku karya ilmiah
dan hasil penelitian di dalam maupun di luar negeri dalam rangka
pengembangan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
7. Membina dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
8. Menciptakan suasana lingkungan kampus yang sehat jasmani dan rohani.
Untuk menegaskan tujuan dan harapan dari pendirian Universitas Garut
serta sekaligus mengembangan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka
Universitas Garut berusaha secara bertahap dengan jalan melakukan pembenahan-
pembenahan dalam rangka menopang peningkatan pembangunan daerah
khususnya dan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan pada umumnya.
Dengan pembenahan-pembenahan yang dilakukan maka diharapkan Universitas
Garut dapat berperan sebagai perguruan tinggi handal khususnya di Wilayah
Priangan dan Jawa Barat pada umumnya. Namun dalam rangka pembenahan dan
pengembangan tersebut, Universitas Garut dihadapkan dengan berbagai
tantangan, yaitu antara lain:
1. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dari
berbagai sektor,
2. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan lebih maju terhadap
perkembangan teknologi dan informasi,
3. Keterbatasan dana yang dimiliki universitas.
Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan di atas, maka Universitas
Garut menyusun suatu rencana strategis (Renstra) Universitas Garut yang disusun
berdasarkan tujuan Universitas Garut, yakni menghasilkan ilmuwan yang mampu
25

memahami dan ahli dalam bidangnya serta menyesuaikan diri dengan
perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Berorientasi kepada
pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia dan pembangunan nasional.
Menganut paham pendidikan seumur hidup dan kemudian dalam mengembangan
diri serta berkeyakinan bahwa unsur sikap dan kemampuan hidup sama
pentingnya dengan pengetahuan. Juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
dalam mewujudkan sosok ilmuwan yang memiliki daya tranformasi iman-amanah
kekuatan ilmu-alamiah, keseyogyaan intelektual-integritas, keterjangkauan
visidiner-imajinatif, keharusan perspektif-inovatif, ketegaran kritis-etis, kearifan,
mandiri, terbuka, dan kesungguhan dedikasi patriotik. Sehingga dapat
menempatkan Universitas Garut pada kedudukan yang lebih baik dan semakin
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan
dan memanfaatkan peluang dengan segala keterbatasan yang ada secara efektif
dan efisien.
3.1.3 Landasan Pengembangan Universitas Garut
Latar belakang kesejarahan lahirnya Yayasan Universitas Garut sebagai
pencetus lahirnya Universitas Garut, memberikan makna tersendiri dalam sistem
pendidikan yang akan dilaksanakan Universitas Garut, yang berupaya
mencitrakan diri sebagai suatu model yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya
bangsa, serta berfungsi sebagai pengusung nilai religiusitas Islami dengan
bercirikan penguasaan yang ideal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Karenanya, Universitas Garut berusaha menterjemahkannya dalam
suatu model pendidikan sebagai sub sistem pendidikan tinggi nasional yang
mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tetap menjamin terpelihara dan
26

berkembangnya nilai luhur budaya bangsa, menjunjung tinggi nilai agama, serta
mengaktualisasikan nilai-nilai ajarannya dalam keseluruhan aspek kehidupan,
terutama dalam masyarakat dan kehidupan ilmiah.
Dalam pada itu, Universitas Garut sebagai subsistem pendidikan tinggi
nasional mendasarkan diri pada dasar-dasar filosofi lembaga pendidikan sebagai
berikut:
1. Universal hakikiyah dan objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk mencapai kebenaran dan kenyataan.
2. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar dalam lapangan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara arif dan bertanggung jawab
3. Ketahanan kampus yang mandiri, dinamis, tangguh dan berwibawa sebagai
garda depan kehidupan masyarakat ilmiah.
4. Sikap berbudaya dan berkeadaban serta teologis ilahiyah usaha ilmu
pengetahuan dan teknologi guna kemanfaatan, kebahagiaan dan peradaban
manusia.
5. Orientasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam memaknai
dan menyikapi globalisasi dan arus pluralisme, sebagai wujud keterlibatan
yang bersifat holistik dan integralistik pada perkembangan internasional.
6. Kinerja research dan development, yang mencitrakan penelitian dan
pengembangan keilmuan yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spektrum
keilmuan yang luas, mengidentifikasi dan membuat solusi masalah
masyarakat dan industri yang perlu segera di atasi, serta senantiasa mengacu
pada tantangan dan masa depan.
27

7. Citra dan kinerja lembaga pendidikan yang sistemik, berencana, terarah
yang lebih menyeluruh dan makin meningkat sebagai langkah mewujudkan
kemampuan untuk senantiasa berkembang.
3.1.4 Strategi Pengembangan Universitas Garut
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan
Universitas Garut diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional, baik yang
diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Undang-Undang tentang
Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi.
Universitas Garut diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pendidikan
tinggi, yaitu:
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/
atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Di samping itu, peranan Universitas Garut diarahkan untuk menjadi:
1. Pusat pemeliharaan, penelitian, serta pengembangan ilmu, teknologi, dan/
atau kesenian sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2. Tempat mendidik mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki
jiwa besar yang bertanggungjawab terhadap masa depan dan negara
Indonesia.
28

3. Tempat membina mahasiswa sehingga bermanfaat bagi pembangunan
nasional dan pembangunan daerah.
4. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu,
teknologi dan/ atau kesenian.
Untuk pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan
sistem pendidikan nasional, peraturan tentang pokok-pokok dan penataan
organisasi, tata cara penyusunan kurikulum, dan sebaginya, agar terdapat
keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan di semua perguruan tinggi.
Tujuan dari pengembangan sarana dan SDM adalah sebagai bagian dari
rencana strategis Universitas Garut dalam mengikuti perubahan di dunia
pendidikan. Dengan dukungan sarana fasilitas dan SDM yang berkualitas
diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang lebih kompeten, sehingga
pada gilirannya UNIGA dapat memainkan perannya secara maksimal, untuk
mampu bersinergi dengan komponen lainnya dalam rangka peningkatan
kemampuan SDM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut.
3.2 Etika Kebijakan Publik dalam Lingkungan Universitas Garut
Implementasi etika administrasi publik dalam lingkungan Universitas
Garut secara umum telah dilakukan sedemikian rupa dengan menyesuaikan
kondisi yang ada di lingkungan Universitas Garut. Hal ini tentunya terdapat
perbedaan antara dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi dengan etika
administrasi publik yang dilakukan atau diterapkan pada organisasi pemerintah,
namun selain perbedaan tersebut adapula persamaan antara keduanya.
29

Untuk menilai sejauhmana penerapan etika administrasi publik yang
dilakukan di lingkungan Universitas Garut dengan dasar rujukan yaitu ASPA
(American Society for Administration) yang dikutip oleh Widodo (2006:70) dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Pelayanan yang dilakukan dalam artian pelayanan publik yang ditujukan
kepada stakeholders secara umum berlandaskan di atas kepentingan sendiri,
namun tidak jarang suatu kebijakan ditetapkan digunakan kepentingan sendiri
atau kalangan tertentu.
2. Tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepada pegawai relatif besar dan
berdasarkan atas kemauan atau perintah untuk kepentingan pihak tertentu.
3. Kebijakan yang diambil tidak jarang berdasarkan kepentingan pribadi,
sehingga dampak yang diinginkan oleh lapisan managemen selalu tidak
tercapai, hal ini tentu mengganggu aktivitas organisasi secara keseluruhan.
4. Pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien terkadang berbenturan
dengan kebijakan yang dibuat demi kepentingan kelompok tertentu, dan
terkadang terjadi penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, dan
penyelewengan dalam hal kekuasaan dan kewenangan.
5. Belum ada sistem penilaian kecakapan atau etika baku yang dilaksanakan di
lingkungan Universitas Garut, penilaian lebih sering berdasarkan
subjektivitas pimpinan terhadap aktivitas para pegawainya.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan pegawai, kinerja pegawai, prestasi
pegawai kurang mendapat perhatian, yang pada akhirnya para pegawai
melakukan aktivitas pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi. Konflik
kepentingan masih saja terjadi antara pimpinan yang menyebabkan pegawai
30

tidak konsentrasi/fokus terhadap pekerjaan, tidak jarang pekerjaan yang
dilakukan untuk kepentingan pimpinan.
7. Pelayanan yang dilakukan kurang berdasarkan etika administrasi publik yang
baik dan benar, hal ini dipengaruhi oleh subjektivitas pelaksana pelayanan
dan terkadang tidak menerapkan etika tersebut.
8. Pelaksanaan kegiatan/aktivitas terkesan dilakukan secara ganda, dalam artian
bahwa kegiatan/aktivitas tersebut menyalahi apa yang diungkapkan nurani
kita dan tidak mengikuti cara-cara yang beretika, sehingga menimbulkan
tekanan bagi pegawai dalam pelaksanaannya.
9. Masih terdapat pimpinan yang berlaku kurang etis dalam pelaksanaan
administrasi publik yang berdampak pada kinerja organisasi keseluruhan.
Penjelasan tersebut diatas bersifat analisasis kasuatif, artinya bahwa
analisis yang dilakukan tidak secara global pada tataran/lingkup organisasi
Universitas Garut, namun secara parsial yang didasarkan pada
kegiatan-kegiatan/aktitas-aktivitas yang dilakukan pada proses pelaksanaan
administrasi publik pada lingkup Universitas Garut. Hal tersebut dilakukan
dengan alasan tidak semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan Universitas
Garut melalui cara-cara yang tidak beretika.
Untuk lebih memperdalam hasil analisis tersebut untuk menilai baik
buruknya suatu pelayanan publik yang dilakukan oleh anggota organisasi di
lingkungan Universitas Garut berdasarkan faktor efisiensi, efektivitas, kualitas
pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas, dapat dilihat pada uraian berikut:
1. Faktor Efisiensi
Dari sisi efisiensi masih terdapat penyelewengan atau pemborosan sumber
31

daya, dalam artian hasil yang diperoleh atau diberikan melalui pertimbangan
finansial/ekonomis semata sehingga kurang mengedapankan prestasi/kinerja
dari para pegawai. Namun secara umum dinilai cukup baik dengan kondisi
yang ada dalam usaha meningkatkan etika pelayanan kepada publik
2. Faktor Efektivitas
Keefektifan pelayanan dan aktivitas yang dilakukan cukup baik, namun pada
kondisi tertentu membutuhkan pengertian para pegawai dalam pelaksanaan
aktivitas pekerjaan yang harus menyesuaikan dengan keinginan pimpinan
dengan kebijakannya yang bersifat insidental.
3. Faktor Kualitas Pelayanan
Etika dalam kualitas pelayanan kepada publik dirasakan kurang, hal ini terlihat
dari kemampuan komunikasi sumber daya manusia yang ada masih kurang
dan sering terjadi kesalahfahaman antar pegawai.
4. Faktor Responsivitas
Dengan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia relatif kurang
menyebabkan tingkat respon relatif kurang memadai dalam hal pelayanan
kepada publik. Respon yang tinggi terjadi apabila pimpinan mempunyai
kebijakan atau kepentingan yang insidental diluar pelayanan publik.
5. Faktor Akuntabilitas
Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk akuntabilitas
relatif kurang disebabkan semua kebijakan bersifat top down yang lebih
mengedepankan kepentingan pimpinan, selama kondisi ini masih berlangsung
akan mengakibatkan akuntabilitas yang dikehendaki akan rendah.
32

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Dari paparan dan analisis yang telah disampaikan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Penerapan etika administrasi publik sebagai perwujudan pelayanan yang baik
kepada publik di Universitas Garut relatif cukup baik, hal ini tidak terlepas
dari lembaga Universitas Garut sebagai lembaga pendidikan yang
mengajarkan, mendidik, dan membentuk manusia sebagai insan yang
mempunyai budi pekerti dan ilmu pengetahuan yang baik sebagai bekal masa
depan.
b. Tolok ukur yang dijadikan penilaian dalam analisis tidak serta merta dapat
diterapkan secara ideal, hal ini tentunya disesuaikan dengan situasi yang
terjadi dimana kondisi dari organisasi, sumber daya manusia dan sumber-
sumber daya lainnya belum secara sempurna menerapkan atau
mengimplementasikan etika administrasi yang baik.
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka kami memberikan saran
yang diharapkan dapat membantu atau memberikan solusi dalam penerapan etika
administrasi publik untuk mewujudkan pelayanan yang memuaskan kepada publik
sebagai berikut:
a. Sumber daya manusia sebagai unsur utama dalam pelaksanaan etika
administrasi yang baik harus secara sadar dan paham bahwa pelayanan
33

kepada publik mempunyai konsekuensi yang dapat merugikan jika kualitas
etika yang dimiliki rendah.
b. Untuk menilai secara objektif diperlukan analisis lebih dalam mengenai
penerapan etika administrasi terutama dalam kebijakan yang berhubungan
dengan publik, hal ini disebabkan masih banyak faktor yang harus
dianalisis sehingga dapat dilihat secara komprehensif.
34

DAFTAR PUSTAKA
.................................(2000). Teori Administrasi Publik,. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Bertens, K. (2000). Etika. Seri Filsafat Atma Jaya. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Denhardt, Kathryn G. (1988). The ethics of Public Service. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Henry, Nicholas. (1995). Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.
Perry, James L. (1989). Handbook of Public Administration. San Fransisca, CA: Jossey- Bass Limited.
Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. (1997). Introducing Public Administration. New York, N.Y.: Longman.
35