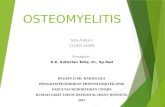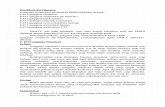CSS Journal Vol. III
-
Upload
jurnal-kajian-studi-kemasyarakatan-unpas -
Category
Documents
-
view
297 -
download
4
description
Transcript of CSS Journal Vol. III
-
CSS Journal
Vol. III
Kami mengajak para pembaca untuk berkontribusi dengan mengirimkan tulisan seputar ekonomi-politik, hubungan internasional, kebudayaan dan pergerakan sosial maksimal 5000 kata.
CSS JOURNAL terbit berkala secara mandiri , konten dalam jurnal ini bebas dikutip atau digandakan untuk tujuan distribusi informasi.
-
Tahun ini rakyat Indonesia akan kembali merayakan pesta demokrasi lima tahunan, menentukan siapa yang layak berkuasa untuk lima tahun kedapan. Semua calon wakil rakyat dengan berbagai varian cangkang dalam wadah yang sama berjanji men-gencangkan skrup yang mulai mengendor, menu-tup lubang-lubang yang semakin mengaga. Klasik.
Namun CSS Jurnal edisi kali ini tidak akan meny-elami isu seputar kontestasi politik nasional yang sudah kepalang keruh, kami kembali hadir untuk membawa kita berpetualang pada isu keseharian yang tidak sempat kita renungkan karena berpolitik itu setiap hari bukan lima tahun sekali. CSS Journal edisi ke-3 di buka oleh Agama Finansial dan Mo-ralitas Cacing Pita dalam Kapitalisme Zombi dari Stanley Khu, analisis mendalam mengenai kapital-isme kontemporer yang menampilkan bagaimana finansialisasi menjadi sesuatu yang diagungkan layaknya Agama. Kolom selanjutnya di isi oleh Boundary karya FIrman Eko Putra yang mengajak kita untuk mendiskusikan kembali tema sentral dalam studi geopolitik, terkait persoalan batas ke-daulatan negara bangsa. Checkpoint selanjutnya menampilkan critical review atas film Blame it on Fidel! karya Rifqi Fadhlurrachman berjudul Cerita isi kepala Anggota Keluarga. Disusul oleh Tin-jauan Kritis Fenomena Lorde : Apresiasi Karya atau Komoditi oleh Rizky Satria, ulasan apik ten-tang fenomena penyanyi muda asal Auckland yang memboyong 2 piala pada Grammy Award akhir Jan-uari lalu. Di penghujung edisi kali ini kami menya-jikan resensi buku Konsep Kemanusiaan Menurut Marx karya Erich Fromm yang digarap oleh Firman Eko Putra dengan tajuk Humanisme Marx dan Kerja Mengepel Erich Fromm.
TIM REDAKSIRifqi Fadhlurrachman - @rifqifaadhFirman Eko Putra - @firman_ep
KONTRIBUTORStanley KhuRizky Satria - @Rizky__Satria
#3PASUNDANCENTER OF SOCIETALSTUDIESJOURNAL
"I crossed an imaginary line with a bunch of plants. I mean, you say I'm an outlaw, you say I'm a thief, but where's the Christmas dinner for the people on relief? "Geogre Jung (Johnny Depp) - Blow (2001).
-
AGAMA FINANSIAL KRISIS demi krisis yang kita saksi-kan dalam sejarah ekonomi menyediakan kerangka sempurna untuk me-mahami narasi-narasi yang menjadi landasan bagi kemunculan kapitalisme kontemporer. Salah satunya adalah pembagian ekonomi ke dalam dua ranah berbeda: ekonomi riil (ra-nah tempat relasi produksi dan pertukaran yang terprediksi didasarkan pada kebutu-han) dan ekonomi spekulatif (ranah non-produktif, ketamakan, dan kesia-siaan yang membuat kita semakin dekat menuju ki-amat). Seperti yang kita tahu, sebagian besar orang di dunia ini melakukan kerja riil yang menghasilkan nilai riil, selagi minoritas kecil lain di Wall Street (mis: Gordon Gekko-nya Michael Douglas) secara tak bertanggung jawab menghamburkan surplus yang dihasil-kan dalam sebuah arena bak kasino yang kita kenal sebagai pasar finansial. Gambaran tentang trader dan speculator tak bermoral telah lama muncul dalam literatur Barat, misalnya melalui so-sok Shylock-nya Shakespeare di The Mer-chant of Venice dan Ebenezer Scrooge-nya Dickens di A Christmas Carol. Dan dalam tingkat yang lebih ekstrem, sanksi terhadap para perantara ini dapat berakhir dengan genosida, seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Armenia. Meski begitu, kita tetap tak boleh melupakan bahwa kaum perantara ini (trader, speculator, hedge-fund manager)
hanyalah individu-individu yang melakukan tugas mereka dalam sebuah sistem tempat para pembuat kebijakan dan politisi gagal melakukan tugas mereka. Contoh sederhananya: prinsip fi-nansial yang menyatakan bahwa utang adalah harta. Investor-investor seperti R. Kiyosaki selalu mendengungkan prinsip ini. Karena negara tak mampu memberdayakan rakyatnya, maka negara mengimbau mer-eka untuk menjalankan hidup dengan utang. Para bankir berbondong-bondong mencip-takan produk-produk yang akan mengemas utang menjadi bentuk sekuritas baru. Pun-caknya, pada 2005, mereka menawarkan utang/sekuritas bernama subprime mort-gage. Dan butuh 3 tahun sebelum dunia me-nyadari bahwa utang selamanya tetap akan menjadi utang. Dengan demikian, sukses gagalnya seseorang dengan utang di tangan-nya tak dianggap sebagai tanggung jawab negara, melainkan si individu yang bersang-kutan. Ini sesuai prinsip lainnya yang juga digemari pasar finansial: individualisme. Istilah finance sendiri berasal dari bahasa Latin, finis, yang berarti akhir, untuk merujuk pada tanggal jatuh tempo sebuah utang. Dalam dunia finansial modern, finis secara konstan diredefinisi: ditunda, direne-gosiasi, dan diubah. Intinya, sebisa mungkin diulur tanggal jatuh temponya; utang tak bo-leh lenyap karena ia adalah harta.
4 C S S J o u r n a l V o l . I I I 5C S S J o u r n a l V o l . I I I
KAPITAL-
Kita menciptakan uang dan menggunakannya, tapi kita tak bisa memahami hukum-hukum-nya dan mengontrol tindakan-nya. Ia punya hidup sendiri.
-Lionel Trillling-
DAN MORALITAS CACING PITA DALAM
ISME ZOMBI
analisa ekonomi-politik
Stanley KhuAlumnus Jurusan Ilmu Antropologi Universitas Padjadjaran
-
Dunia yang kita tinggali saat ini sangat dipengaruhi prinsip-prinsip finan-sial. Situasi ini mungkin bisa kita sebut se-bagai finansialisasi. Para penganut agama finansialisasi bisa saja menyatakan bahwa dunia ini sejak dari sananya telah menganut paham mereka: bahwa setiap masyarakat di dunia ini adalah rasional. Di masa kini, para pedagang bursa memiliki program komputer otomatis yang bisa mengambil alih peker-jaan tersebut. Program akan menjual Dollar secara otomatis bila harganya jatuh atau naik sampai titik tertentu. Program bisa mengukur perubahan arus nilai mata uang, suku bunga relatif, tingkat pinjaman pemerintah, harga komoditas, turunnya neraca perdagangan, dan variabel lain yang dianggap penting. Tapi satu hal yang dilupakan: 75 persen fluk-
tertentu memungkinkan penyetarafan pem-bunuhan atau pernikahan dengan nilai uang tertentu, mereka bisa saja berargumen bah-wa setiap masyarakat di dunia pada hakikat-nya memiliki kapasitas berpikir secara eko-nomi formal. Satu hal yang terlewatkan oleh mereka, perbandingan macam ini menuntut penciptaan rasio-rasio kuantitatif di antara barang-barang yang berbeda ke perbedaan-perbedaan yang setaraf dalam nilai, dan beberapa jenis pertukaran, seperti misalnya pembunuhan yang bisa dikompensasi den-gan uang, secara antropologis sebenarnya lebih merupakan upaya untuk menciptakan analogi daripada rasio. Jika kita terpesona dengan hitungan di dalam pertukaran hadiah pada masyarakat tertentu, maka kita, mengutip Maurer, telah sepenuhnya dibutakan oleh matematika dari penyetarafan moneter dalam masyarakat modern, karena kita terus bersikukuh dalam memandang uang sebagai ekspresi komoditi yang paling dapat dihitung, sebagai ekspre-si, indeks, dan ukuran kesetarafan. Sebenarnya kita tak perlu jauh-jauh merujuk ke masyarakat non-modern, karena pada masyarakat yang sudah modern-pun terdapat kesulitan dalam penyetaraan mone-ter. Misalnya: meski kita berupaya menerap-kan aneka kebijakan pajak terhadap individu dengan pendapatan yang berbeda-beda, pada akhirnya kebijakan inflasi yang diam-bil suatu negara hanya akan menyengsara-kan individu dengan pendapatan pas-pasan. Bila dilihat sekilas, inflasi mungkin tampak-nya akan paling keras menghantam individu dengan kekayaan terbesar (karena jumlah uangnya paling banyak), namun harus diin-gat bahwa laju inflasi adalah indeks numerik dengan sistem pukul rata. Dengan laju inflasi sebesar x, individu A dengan kekayaan 1 mi-lyar akan kehilangan 100 juta, sedangkan individu B dengan kekayaan 100 juta akan kehilangan 10 juta dari kekayaannya. Antara kehilangan 100 juta dan 10 juta memang se-buah gap yang jauh, tapi mari kita lihat dari sisi yang lain. Individu A masih memiliki 900 juta, selagi individu B kini hanya punya 90 juta untuk dibelanjakan.
Dan yang lebih hebat lagi, tipe-tipe seperti individu A biasanya tak menyimpan semua uangnya dalam bentuk tunai. Karena menyadari rapuhnya uang tunai, mereka bi-asanya akan menginvestasikan sebagian be-sar kekayaan mereka, dan kalau beruntung, mungkin malah dapat menangguk keuntun-gan dari terjadinya inflasi (inilah lingkaran keharusan berinvestasi). Di lain pihak, tipe-tipe seperti individu B biasanya adalah para penerima gaji dan pensiunan. Kehilangan 10 juta secara substansial telah mengurangi daya beli mereka. Dan mereka ini biasanya tak tahu-menahu tentang investasi. Keter-gantungan mereka terhadap uang tunai dalam bentuk pendapatan tetap dan tunjan-gan pemerintah (yang nilainya selalu jauh di belakang laju inflasi) secara perlahan telah memiskinkan mereka. Kebiasaan berhemat dan menabung ala Etika Protestanisme Max Weber adalah sia-sia belaka dalam hal ini, karena bila pajak seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai hanya memajaki apa yang dibelanjakan individu, maka inflasi me-majaki semua uang tunai yang dimiliki individu, dan bahkan sampai ke pendapa-tan yang masih be-lum kita terima di masa kini. Mengutip Anatole France: Hanya orang miskin yang membayar tunai, dan itu bukan karena ke-luhuran, tapi karena kredit mereka ditolak. Namun, masalah ihwal nilai finan-sial bukan terletak pada seberapa fiktifnya ia, melainkan pada kenyataan bahwa kini ia telah menjadi realitas tempat kita tinggal di dalamnya; sebuah sistem sosio-ekonomi yang tumbuh semakin dominan. Dalam tiga puluh tahun terakhir, industri finansial telah menduduki peran penting dalam masyara-kat sebagai jaringan pertukaran global tem-pat aset-aset dari seluruh dunia diciptakan, dibandingkan, diperdagangkan, dan dile-nyapkan. Kita mungkin bertanya-tanya: ke-napa industri finansial yang dalam satu abad terakhir ini setidaknya telah empat kali jatuh
bangun dihantam krisis (dekade 30-an, 70-an, 90-an, 2008) selalu mampu bangkit kem-bali dalam wujudnya yang lebih anggun dan canggih? Jawabannya sederhana: karena ke-lihaian para pelaku di dalamnya dan sarjana penyokong ideologinya dalam berinovasi. Melebihi kecepatan para ahli sosial seperti antropolog dan sosiolog dalam mengkaji fenomena ekonomi kontemporer, ekonom-ekonom seperti Robert Merton atau Merton Miller selalu mampu menciptakan berbagai produk dan kebijakan yang didesain agar dapat berkelit di antara berbagai regulasi. Jika kita melihat hal ini secara sinis, tidakkah semua upaya ini adalah wujud pemenuhan dari kepercayaan neoliberal mereka: bahwa keberadaan aturan-aturan bahkan negara hanya menghambat perekonomian? Kita bisa melihat satu contoh seder-hana tentang inovasi ini, misalnya MERS (Mortgage Electronic Registration System). Korporasi ini dibuat di pertengahn 90-an un-tuk memudahkan pencatatan transaksi jual-beli di AS. Dengan sistemonline ini, semua
transaksi perumahan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Individu tak perlu lagi pergi ke kantor-kantor pemerintah un-tuk mencatatkan transaksi mereka. Mereka bahkan tak perlu lagi membayar biaya ini-itu. Dengan demikian, keberadaan MERS telah membuat individu yang terlibat dalam jual-beli rumah dapat menghemat waktu, energi, dan bahkan uang mereka. Akan tetapi, tentu selalu terdapat keburukan dari sistem M-C-M. Ketika kita mulai menganggap rumah bukan sebagai tempat tinggal kita dan keluarga, melainkan hanya sekadar komoditi perantara untuk me-numpuk kekayaan, maka azab hanya tinggal menunggu waktu untuk datang menimpa. Di tahun 2008, MERS akhirnya kena batunya akibat krisis subprime mortgage; ketika
sirkulasi barang tak pernah bersifat netral ataupun sederhana secara hakiki, melainkan adalah sebuah fenomena resiprokal yang mel-ibatkan seluruh individu dalam masyarakat
7C S S J o u r n a l V o l . I I I
tuasi mata uang disebabkan oleh faktor-fak-tor non-ekonomi, dan hanya 25 persen yang bisa dikorelasikan dengan satuan kuantitatif dan indikator statistik. Hal ini menjelaskan kenapa Dolar AS merangkak naik melampaui nilai riilnya ketika Ronald Reagan mendudu-ki kursi presiden: masyarakat menganggap kemampuan Reagan menjalankan tugas ke-presidenan sama baiknya dengan kemam-puannya berakting. Meski begitu, orang-orang ini, dengan mengutip dari sana-sini tentang bagaimana budaya di beberapa masyarakat
6 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
rumah-rumah dibeli bukan untuk ditempati, ketika harga rumah terus naik hanya karena dikerek oleh emosi (bukan rasio, seperti yang diagungkan finansialisasi), dan ketika kita bahkan tak lagi tahu rumah mana yang dimiliki siapa. Saat ini, keberadaan MERS mulai digugat. Tapi tentu saja, ia tetap akan berumur lebih panjang daripada pencetus-nya: Fannie Mae dan Freddie Mac, yang telah lebih dulu masuk liang kubur. Bila teori ekonomi klasik meli-hat komoditi sebagai sesuatu yang netral, sederhana, dan transparan, maka dapat kita katakan bahwa teori finansial sungguh-sung-guh meyakini hal tersebut. Semua komoditi di pasar finansial tampak begitu sederhana. Asumsinya, dengan jibunan informasi yang saat ini tersedia dengan gratis di Abad Infor-masi, maka setiap individu memiliki hak dan risiko yang sama untuk menangguk untung-rugi. Dan berbicara tentang risiko, kini kono-tasi negatifnya telah jauh berkurang dengan adanya disiplin ilmu risk management (yang balik lagi ke atas, mengasumsikan bahwa risiko bisa diukur di abad timbunan informa-si). Pengaruh dari prinsip-prinsip kuan-titatif tertentu dalam kapitalisme kontem-porer adalah faktor yang merubah khayalan sosial. Instrumen finansial modern bera-sumsi bahwa beberapa bentuk spesifik dari resiko dapat dikumpulkan menjadi suatu bentuk abstrak dan dapat ditentukan oleh kalkulasi matematis. Objektivikasi, kalkulasi, dan distribusi risiko bersandar pada koleksi data yang lebih luas dan akurat dan juga pada tenaga komputer yang canggih secara matematis. Terdapat satu idiom tentang mana-jemen risiko ini: jangan pernah menaruh semua telur di satu keranjang. Bagi para bankir, bila sebuah sistem memungkinkan kita untuk melabeli segala sesuatu dengan harga tertentu dan, dengan demikian, mem-buatnya dapat diperdagangkan, maka kita bisa menyebarkan risiko ke pihak-pihak yang paling mampu menanggungnya. Namun, satu hal yang luput dari perhatian, para bankir bi-asanya selalu menyebarkan risiko dengan
memperkenalkan risiko jenis baru ke dalam sistem. Produk finansial seperti derivatif adalah contohnya. Hakikat derivatif, tak lain tak bukan, adalah secondary bet; sejenis ta-ruhan kedua. Ilustrasinya: bila babak pertama pertandingan antara MU vs. WBA berakhir dengan keunggulan tim tamu 0-1, dan kita semua tahu bahwa tim sekelas MU tentu tak akan takluk di kandang sendiri (atau, dengan kata lain, MU adaah jenis saham yang baik), maka saya dan semua orang yang rasional serta berani mengambil risiko akan men-cuci taruhan, dan kembali memegang MU di babak kedua. Skor akan kembali ke 0-0, dan pertandingan dilanjutkan. Tapi, ternyata
WBA kembali unggul satu gol. Skor akhir: 0-2. Saya dan orang-orang senasib kalah di taru-han pertama sekaligus taruhan kedua. Gambaran di atas tak hendak me-nyatakan bahwa produk derivatif takkan per-nah membawa profit, seperti halnya men-gatakan bahwa MU tak mungkin selalu kalah ketika telah tertinggal satu gol di babak per-tama. Tapi, seringkali, yang terjadi juga bu-kan seperti itu. Faktor-faktor tak terukur seperti psikologi dapat muncul. Seringkali, yang terjadi adalah kekalahan ganda; kejatu-
han beruntun. Atau istilahnya: dampak yang bersifat sistemik. Sebenarnya, dan ini juga ironinya, pandangan tentang hakikat komoditi seb-agaimana dilihat teori ekonomi klasik dan diresapi teori finansial telah jauh-jauh hari dibantah. Kita bisa merunut tahunnya sam-pai ke 1923, ketika Marcel Mauss menulis The Gift. Menurutnya, lingkaran penerimaan dan pemberian hadiah dalam masyarakat adalah cara mencegah perang. Atau, dengan kata lain, sirkulasi barang tak pernah bersi-fat netral ataupun sederhana secara hakiki, melainkan adalah sebuah fenomena resipro-kal yang melibatkan seluruh individu dalam masyarakat. Dan jika berbicara tentang ket-
erlibatan seluruh individu, maka sekali lagi pandangan ekonomi formal yang berprinsip ekonomi untuk ekonomi akan tumbang. In-dividu-individu kaya yang menangguk uang dari pasar finansial yang bak kasino tak boleh mengesampingkan kesadaran dan tanggung jawab moral mereka terhadap anggota ma-syarakat lainnya dengan, misalnya, bersilat lidah bahwa ranah ekonomi tak ada sangkut pautnya dengan ranah sosial-politik-budaya, sehingga seluruh aktivitas mereka di dalam kasino tak akan berdampak apapun pada
kehidupan masyarakat. Jika kita ingat rumusan J.M. Keynes tentang MV=PY, maka sudah terang sekali bahwa jumlah uang di pasar harus selalu setara dengan jumlah barang. Para pelaku finansial di Wall Street telah mengabaikan logika sederhana ini dengan terus-menerus menggoreng harga saham sampai setinggi langit, sedangkan output barang yang di-hasilkan Main Street takkan pernah menca-pai tingkat yang sama dengan jumlah uang yang beredar. Pasar mata uang berbeda dari semua jenis pasar lain. Bila di pasar lain ped-agang menukar barang dengan uang, maka para pedagang valas bertransaksi tanpa melibatkan barang konkret apapun. Seka-rang, bagaimana mungkin seseorang bisa mengelak dari kenyataan sederhana ini dan tetap bersikukuh bahwa kebijakan ekonomi hanya untuk kepentingan ekonomi? Bahkan ekonom seperti David Ri-cardo pun telah mengingatkan kita: tak ada negara maupun bank dengan kekuasaan tak terbatas untuk menerbitkan uang kertas yang tak akan menyalahgunakan kekuasaan itu. Namun faktanya kini, uang modern tak hanya dicirikan sebagai unit akun dan alat pembayaran, tapi juga tempat penyimpan nilai. Uang jenis ini, tak seperti garam atau kakao misalnya, tak hanya digunakan untuk memperoleh barang, tapi juga bisa disim-pan sebagai bentuk kekayaan dalam dirinya sendiri. Uang modern yang dicetak secara tak terbatas, yang secara intrinsik tak berni-lai, hanya bisa terus berlaku bila ada institusi kuat seperti negara yang menjaminnya. Mis-alnya Dolar AS, yang diasumsikan sebagai as good as gold. Karena besarnya hegemoni AS di planet kita, maka pada akhir tahun 90-an, 70 persen cadangan devisa dunia memakai dolar. Tapi sebelumnya, kita dapat ber-henti sejenak untuk bertanya: Dengan apak-ah negara kuat seperti AS menjamin Dolar AS yang disimpan oleh tiap-tiap kita di rumah masing-masing?; Apakah jaminannya adalah sesuatu yang konkret? Jawaban untuk ked-uanya: ternyata tidak.
9C S S J o u r n a l V o l . I I I 8 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
Kita bisa merunut kembali ke zaman Presiden Abraham Lincoln ketika sedang ter-jadi perang saudara di AS. Pada 28 Februari 1862, pemerintah AS mencetak uang kertas untuk membiayai ha-hal seperti pembayaran gaji tentara. Namun hal ini pada gilirannya menciptakan sistem mata uang berlapis, karena pemerintah tetap menghendaki agar pajak impor tetap dibayar dalam koin emas atau perak, selagi di lain pihak mereka mem-bayar para serdadu dan kreditor dengan uang kertas yang hanya ditopang oleh janji. Sederhananya, pemerintah berjanji untuk membayarkan nilai pada lembaran kertas pada satu waktu tertentu. Artinya, uang ker-tas tak lain daripada aktivitas pemerintah memaksakan berutang pada warganya send-iri; dan hebatnya lagi, utang ini adalah obli-gasi tanpa bunga. Jadi ironinya di sini: individu dipak-sa meminjamkan hartanya pada pemerintah, dan pemerintah berjanji akan mengemba-likannya kelak suatu hari di masa depan. Tanpa bunga. Bahkan tanpa kepastian bahwa harta akan benar-benar kembali ke pangkuan pemiliknya. Mungkin sebagian dari kita akan segera terpikir tentang Federal Reserve atau Fort Knox, bunker penyimpan emas di AS, dan berargumen bahwa timbunan emas di sana mewakili sistem moneter AS; semacam jaminan keamanan psikologis untuk meng-garansi lembar uang di dompet kita. Namun hal ini juga keliru. Emas di Fort Knox dan Fed-eral Reserve sama sekali tak ada kaitannya dengan Dolar AS. Ketika Presiden Richard Nixon secara resmi memutus ikatan antara Dolar dan emas pada Agustus 1971 karena kebijakan perang Vietnam yang membuat suplai Dolar meningkat di pasar (yang pada gilirannya menimbulkan inflasi), sistem Bret-ton Woods pun berakhir. Bagi Nixon yang khawatir kalau-kalau negara-negara lain yang merasa dirugikan karena Dolar AS yang mereka pegang saat itu terdevaluasi hampir sepertiga nilainya terhadap emas (di tahun 1995, Dolar AS bahkan sudah terdevalu-asi hampir 12 kali lipat terhadap emas) akan berbondong-bondong menukarkan emas
mereka, putus hubungan antara uang kertas dan emas tampaknya menjadi keputusan ter-cerdas yang pernah dibuatnya. Kini, tak satu ons pun emas di du-nia ini yang berdiri di balik Dolar AS. Den-gan kata lain, uang kertas yang kini nilainya mengambang bebas tak ubahnya lembaran cek kosong. Kertas di saku kita bukan emas, tak juga perak. Negara tak akan menukar ker-tas kita selain dengan kerta lainnya. Kertas di saku kita hanyalah mata uang fiat. Ia ber-tumpu pada hegemoni pemerintah, dan pada keyakinan orang-orang yang menggunakan-nya; orang-orang seperti kita. Frase yang disodorkan kepada kita bukan lagi Payable to the Bearer on Demand, melainkan diganti menjadi In God We Trust. Dalam General Theory, Keynes me-nyebut karakter uang yang seperti ini seb-agai the fetish of liquidity (jimat likuiditas). Disebut jimat karena, dari perspektif mak-roekonomi Keynesian, tak ada sesuatu yang bisa kita namai sebagai likuiditas dalam ko-muniti secara keseluruhan. Faktanya, uang bukanlah kekayaan, dan oleh karenanya, sistem finansial modern akan terus-menerus menderita karena kontradiksi intrinsik antara apa yang mungkin dilakukan oleh individu dan apa yang tepat bagi komuniti. Kontra-diksi ini akan menciptakan krisis bagi sistem finansial kapanpun individu memutuskan untuk menimbun uangnya atau menunda konsumsi dan investasi. Untuk mengatasi jimat likuiditas ini, Keynes sampai merasa perlu dilakukan sebuah reformasi moneter, yang akan memahami uang hanya sebagai perantara yang dioper dari tangan ke tangan, diterima dan dibagikan, dan lenyap ketika tu-gasnya rampung. Bila jimat likuiditas tak teratasi, maka kita akan dikungkung oleh jerat kapi-talisasi. Sebagai cara menilai sesuatu dari sudut pandang finansial, dapat didefinisikan bahwa kapitalisasi adalah proses memper-timbangkan expected return yang akan di-hasilkan dari sebuah investasi. Aturan-aturan untuk mengalokasikan uang dalam masyara-kat saat ini hampir semuanya dicirikan oleh teknik penilaian finansial yang demikian.
Segala sesuatu mulai dari proyek-proyek sains, proyek pemberdayaan, ide-ide kre-atif, sampai ke penanggulangan bencana dinilai dengan apa yang disebut oleh para spesialis penilaian finansial sebagai biaya kapital, yakni: mengukur seberapa berharg-anya membiayai hal-hal tersebut berkenaan dengan ketidakpastian yang melingkupinya (biasanya dihitung dengan suku bunga). Aki-batnya, tentu saja segala sesuatu kini ter-orientasi karena penilaian yang demikian, dan mungkin akhirnya malah dimungkinkan untuk terbentuk semata-mata untuk tujuan kapitalisasi. Saat ini, jerat kapitalisasi telah mengalihkan kekayaan dari para pedagang (berjaya di zaman penaklukan kolonial) dan industrialis (berjaya di zaman industri) ke
tangan para pemodal. Produksi tak lagi men-gontrol perekonomian, karena para pemilik alat produksi sudah bukan merupakan suatu kelas tertentu. Kelas pemodal tak perlu me-miliki alat-alat produksi; mereka hanya perlu mengontrol pergerakan arus uang dan ben-tuk uang. Produk-produk finansial yang dicip-takan para pelaku pasar finansial, tak bisa tidak, adalah sesuatu yang teramat canggih. Contohnya saja uang elektronik seperti kartu kredit. Kemunculan kartu kredit merevolusi pola konsumsi dan pembayaran. Ia menawar-
kan kesempatan bagi para individu untuk memakai uang yang belum mereka peroleh, tapi diperkirakan akan diperoleh suatu saat nanti. Dengan mengandalkan pendapatan di masa depan ini, seorang pemegang kartu mampu bertindak layaknya bank sentral; ia mampu menciptakan uang, dan itu dilaku-kannya hanya dengan melakukan konsumsi. Pembelian sebuah barang di toko seharga x akan meningkatkan jumlah uang beredar di pasar seharga x. Toko tak ambil pusing apakah konsmen benar-benar memiliki uang di Bank. Satu hal yang pasti, mereka mener-ima uang, para pegawainya bisa digaji, dan pemerintah mendapat pajak penjualan. Dengan kata lain, pembelian yang dilakukan individu telah menciptakan uang
dengan meminjamnya dari hari esok dan mengonsumsinya di pasar hari ini. Kartu kredit dengan limit tagihan tertentu tak ubahnya kebijakan uang mengalir bebas yang dijalankan negara-negara saat ini; kita boleh menciptakan uang sebanyak yang kita mau, asal tak menyerempet jurang inflasi. Kartu kredit juga melakukan prosedur lay-aknya bank; limit tagihan tak ubahnya ke-bijakan cadangan wajib di bank yang dapat menggandakan uang dari ketiadaan. Bila cadangan wajib yang harus disimpan sebuah bank adalah sebesar 10 persen , maka bila
11C S S J o u r n a l V o l . I I I 10 C S S J o u r n a l V o l . I I I
Kemunculan kartu kredit merevolusi pola konsumsi dan pembayaran. Ia menawarkan ke-sempatan bagi para individu untuk memakai uang yang belum mereka peroleh, tapi di-perkirakan akan diperoleh suatu saat nanti.
-
*Artikel ini sebelumnya pernah di muat pada Jurnal Indoprogress http://indoprogress.com/agama-finansi-dan-moralitas-cacing-pita-dalam-kapitalisme-zombiDimuat ulang disini untuk tujuan pendidikan.
Kepustakaan:
- Doria, Luigi and Luca Fantacci. Community and Money, Local and European. Theorizing the Con-temporary, Cultural Anthropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/575
- Elyachar, Julia. The Passions of Credit and the Dangers of Debt. Theorizing the Contemporary, Cultural Anthropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/577
- Guyer, Jane I. Life in Financial Calendrics. Theorizing the Contemporary, Cultural Anthro-pology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/565
- Hertz, Ellen, Leins, Stefan. The Real Economy and its Pariahs: Questioning Moral Dichotomies in Contemporary Capitalism. Theorizing the Con-temporary, Cultural Anthropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/576
- Lepinay, Vincent Antonin. What Can Anthropolo-gists of Finance Teach Us About the MERS We Now Find Ourselves In? Theorizing the Contemporary, Cultural Anthropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/572
- Maurer, Bill. 2006. The Anthropology of Money. Annu. Rev. Anthropol. 35:1536.
- Muniesa, Fabian. Coping with the Discount Rate. Theorizing the Contemporary, Cultural An-thropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/566
- Ortiz, Horacio. Why Does (or Doesnt) Finance Need an Anthropology? Theorizing the Contem-porary, Cultural Anthropology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/568
- Poon, Martha. Why Does Finance Need an Anthropology? Because Financial Value is Real. Theorizing the Contemporary, Cultural Anthro-pology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/564
- Tett, Gillian. An Anthropologist on Wall Street. Theorizing the Contemporary, Cultural Anthro-pology Online. May 17, 2012. http://culanth.org/?q=node/580
- Weatherford, Jack. 2005. Sejarah Uang. Yogya-karta: Bentang Pustaka
13C S S J o u r n a l V o l . I I I 12 C S S J o u r n a l V o l . I I I
saya menabung 1 juta, bank dapat menggan-dakannya sampai mencapai 10 juta, karena ketika sebuah bank mencantumkan angka 10 juta di saldonya, maka dana likuid yang dibutuhkannya sebagai jaminan bahwa ia sehat hanyalah 10 persen dari totalnya, yakni 1 juta (diperoleh dari tabungan saya). Sisa 9 juta adalah uang gaib yang bebas dipakai bank untuk kepentingan bisnisnya. Dan demikianlah bank beserta kartu kredit bertindak layaknya lemak di dalam tubuh. Jika terlalu banyak, maka ia akan mengha-langi kelincahan. Jika terlalu sedikit, ia akan membuat badan menjadi sakit. Namun yang seringkali terjadi, le-mak finansial ini memang diproduksi terlalu banyak berhubung betapa gampang dan lapangnya jalan yang disediakan oleh sistem untuk membuat kita menjadi konsumtif (dan memang itulah prasyarat agar tak ter-jadi overproduction) persis seorang pen-derita gangguan pencernaan yang tak tahu kapan saatnya berhenti makan karena terus-menerus merasa lapar. Komoditi tak pernah merupakan sesuatu yang sederhana, terlebih dalam sistem finansial saat ini. Kemampuan mer-eka untuk selalu berkelit dari regulasi mem-buktikan hal ini. Dengan demikian, hujan informasi takkan pernah berbanding lurus dengan kemudahan dalam berspekulasi dan mengukur risiko. Selain itu, produk-produk yang diciptakan dalam sistem pasar bebas sebenarnya malah terlalu rumit untuk di-perdagangkan. Produk dibuat, dijual, masuk ke dalam neraca saldo seseorang, dan hanya berakhir di situ. Sama sekali tak ada pene-tapan harga ala pasar bebas. Asumsi bahwa nilai sebuah aset adalah harganya ketika diperdagangkan di pasar jauh lebih mudah diucapkan ketimbang diterapkan. Buktinya, bank-bank hanya dapat menebak harga den-gan memakai model. Dengan kata lain, mer-eka hanya berandai-andai. Dengan memakai analogi sepak-bola sekali lagi, maka hal ini akan tampak jelas. Bila MU membuka kompetisi dengan menang 19 kali berturut-turut di liga Inggris dengan skor konstan 5-0, maka pada partai
ke-20, apa yang bisa kita harapkan? Bila di partai ke-1 MU hanya memberi handicap 1, maka seiring kemenangannya dari pekan ke pekan,handicap yang diberikannya, tak bisa tidak, hanya akan terus naik. Di pekan ke-20, kita akan menyaksikan MU memberi handicap 3. Tapi, kita bahkan tak sedang ber-bicara tentang berapa gol lagi yang mampu dan akan dilesakkan MU. Kita membicarakan tentang apakah MU bahkan akan mampu menang lagi di partai ke-20. Model yang berbasis ilmu probabilitas akan memberikan jawaban iya, sedangkan kita semua tahu bahwa tak ada tim yang akan menang sela-manya. Sama halnya, harga saham yang ditebak dengan memakai model juga se-benarnya tak pernah menunjukkan nilai aslinya. Yang ditunjukkan semata-mata adalah kecenderungan yang akan terjadi di masa depan dengan memakai fakta dan data di masa lampau. Buktinya, perusahaan kadangkala membeli sahamnya untuk men-gurangi supply dan meningkatkan demand untuk menaikkan harga. Hal serupa juga di-lakukan pemerintah, dengan bank nasional yang bisa membeli mata uang sendiri dalam jumlah besar untuk mendongkrak harga, atau melakukan hal sebaliknya untuk memaksa harga turun. Tak ada kepastian; yang ada hanya harapan demi harapan dan intervensi sesekali. Demikianlah yang marak terjadi di era finansialisasi: kegemaran untuk meramal dan menjadikannya sebagai standar nilai; se-hingga fenomena seperti bubble dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Karl Popper sendiri butuh waktu lama untuk meyakinkan dirinya bahwa ilmu probabilitas layak digolongkan ke dalam di-siplin ilmu matematika. Resolusinya adalah sebagai berikut: bahwa probabilitas tak bisa dijerat dengan teknik falsifikasi karena ia hanya membuat kepastian dan ketepatan perhitungan tentang kecenderungan yang akan terjadi di jangka panjang. Jadi, bila kita melempar satu koin dan terdapat kemung-kinan 50/50 untuk keluarnya gambar dan angka, hal ini tidaklah menyiratkan bahwa tiap dua kali lemparan akan menghasilkan
masing-masing sekali gambar dan sekali angka. Bisa saja kita melempar lima kali dan mendapati bahwa yang keluar terus-menerus adalah angka. Namun hal tersebut, menurut Popper, tak akan memfalsifikasi probabilitas karena ilmu ini memang tak berniat menyatakan kepastian untuk jangka waktu saat ini. Bagi saya pribadi, semuanya seder-hana saja. Aktivitas di pasar finansial se-benarnya tak ada bedanya dengan kegiatan taruhan bola. Di jangka panjang, hanya indi-vidu-individu bermodal besar dan para spe-kulan yang akan selalu menangguk keuntun-gan. Dan dari segi risiko maupun argumen tentang open information, kedua jenis ak-tivitas berbagi kemiripan yang sama persis. Bedanya bagi saya, taruhan bola, terutama yang online, masih sedikit lebih bermoral daripada pasar finansial, karena sebelum masuk ke situs, biasanya kita akan ditanya tentang kesediaan kita menaggung risiko bila kalah. Artinya, setiap individu yang ma-suk ke dalam situs, ceteris paribus, adalah orang-orang dengan kesadaran yang sama. Hal ini berbeda dengan aktivitas di pasar fi-nansial, tempat segelintir orang tanpa rasa tanggung jawab dan moral di nuraninya ber-judi dengan selubung nama spekulasi dan investasi. Anggota masyarakat lain tak ta-hu-menahu tentang aktivitas mereka dan tak pernah menyatakan kesediaan untuk turut serta dalam permainan. Dan ajaibnya, bila menang, pelaku pasar akan naik ke surga sendiri, namun bila kalah, ia akan menarik anggota masyarakat yang tak tak tahu-mena-hu ini bersama-sama terjun ke neraka. Tapi, tentu saja, takkan ada yang bisa disalahkan bila kita meyakini pandan-gan neoliberal, mengutip Margaret Thatcher, bahwa tak ada sesuatu yang dinamakan ma-syarakat; yang ada hanya individu pria dan wanita, dan keluarga. Bila finansialisasi adalah A-Gama (sesuatu yang tak membuat kacau), maka tentulah ia adalah agama paling individu-alis dalam pengertian hakikat, subjek, mau-pun egoisme yang pernah tercipta di muka bumi.***
-
Bagian I ; Ihwal Batas Model Pasca-Westphalia
BOUNDARY
Kenichi Ohmae (1995), dalam magnum opus fenomenalnya the Borderless World, mengajukan tesis provokatif dengan menyatakan bahwa kita, manusia kosmopolit1, kini tengah hidup dalam du-nia tak berbatas yang mana Negara-bangsa sedang menarik nafas terakhirnya sembari secara bersamaan bentuk baru regionalisasi ekonomi2 kian signifikan (Anssi Passi, dalam John Agnew et al 2006). Pernyataan ini, bagi sebagian pelajar Ilmu Hubungan Internasi-onal yang dibesarkan dalam tradisi Realisme tentunya terdengar konyol. Bagaimana tidak, Ohmae dengan (over) confident mengajukan tesis Borderless ditengah spasialitas dunia yang masih terkavling-kavling berdasarkan Batas-batas Negara (State-Border), percis karena entitas Negara-bangsa lengkap den-gan berbagai simbol politiknya (Bendera, Angkatan Bersenjata, Simbol Negara, hing-
1 Kosmopolitan menurut Beck adalah the development of multiple loyalties as well as the increase in diverse transnational forms of life, the emergence of non-state political actors. Beck, 2006.2 ASEAN Economic Community, Uni Eropa, etc
Definitions(the Merriam-Webster Online Dictionary)Boundary : Something that indicates or fixes a limit or extent.
ga Upacara Bendera) masih bercokol tegak di panggung Politik Internasional, bahkan studi Hubungan Internasional, in defini, tak lain adalah studi mengenai interaksi antar Negara-bangsa melintasi batas-batas terito-rialnya. Singkat kata pengertian Batas (Fixed Border), dalam konteks Hubungan Interna-sional, belum banyak berubah, sejak kali pertama di invensi Westphalia Treaty 1648. Dengan demikian tesis Ohmae tak ubahnya gimmick-gimmick murahan a la Dewi Perssik atau Syahrini yang gemar membuat sensasi di saluran-saluran infotainment, benarkah seperti itu? Mari kita buktikan. Persoalan Batas sejatinya bukan hanya priviledge para penstudi ilmu Hubun-gan Internasional, par excellence. Sejauh pembacaan penulis, justru diskursus Geo-grafi lah, sebagai inventor, yang memin-jamkan perangkat analisisnya (topografi, Geostatistik, et cetera) untuk kemudian digunakan sebagai sarana penentu posi-sionalitas strategis territorial suatu area, bukankah penelitian-penelitian Hubungan
Hubungan Internasional
15C S S J o u r n a l V o l . I I I 14 C S S J o u r n a l V o l . I I I
Internasional tradisional dijejali studi-studi mengenai Batas-negara?. Ketertarikan ter-hadap studi mengenai Batas (Boundaries), sebagaimana tampil dalam literatur-literatur beberapa dekade terakhir, semakin menun-jukan peningkatan (Newman and Passi, 1998). Terdapat peningkatan ketertarikan terhadap Batas sebagai konstruksi Geo-grafi dan Sosial. Bertolak belakang dengan studi-studi mengenai Batas, yang menaruh perhatian secara eksklusif pada persoalan kontur fisikal territorial dan institusi Negara, belakangan perhatian mulai bergeser pada sebentuk konsepsi baru mengenai Batas sebagai garis yang memisahkan, menutup, dan mengeksklusikan, sejumlah skala spasial dan social tertuntu, maka sebagai konsekue-nsi logisnya, perhatian terhadap persoalan perbatasan internasional yang kaku, dalam pengertiannya dalam hukum positif, menjadi kian kehilangan daya tarik seksual-nya. Analisis lintas disiplin (cross-dici-plinary analysis), menjadi suatu keniscayaan bagi terbangunnya pemahaman mengenai persoalan Batas/Perbatasan (Boundary/Bor-der) yang holistik. Barangkali tesis Ohmae mengenai lenyapnya batas-batas Negara-bangsa formal, tidak dapat secara kasar dipa-hami sebagai suatu keserampangan analisis sensasional semata, sebaliknya dibutuhkan suatu kapasitas pengetahuan yang menye-diakan tempat bagi pengertian dan pemak-naan alternatif bagi terma Batas (Boundary) dan Perbatasan (Border), di luar pemahaman tradisional yang disediakan oleh aparatus keilmuan Hubungan Internasional/ilmu Poli-tik. Penggunaan pendekatan lintas disiplin bukan berarti hendak menyingkirkan kon-sep-konsep tradisional, yang terrepresentasi melalui terma-terma; demarkasi, frontiers, permeability, dan lanskap perbatasan, se-baliknya relevansi terminologi-terminologi tersebut bagi banyak Geografer Politik masih sama bernas, dan relevannya, dengan kon-teks politik-sosio-historis epos Globalisasi saat ini. Melalui essay ini penulis hendak melakukan pembuktian atas tesis Ohmae tersebut, sembari mencoba menelusuri dis-kursus Perbatasan Internasional (Interna-
tional Boundaries), baik dalam pengertian tradisionalnya maupun kontemporer.
Batas : Lanskap Tradisional
Perjanjian Westphalia3 menjadi penanda sejarah bagi lanskap spasial dunia, yang dihuni oleh Negara-bangsa, lengkap dengan komponen penyangga eksistensi utamanya; Teritori tetap (Fixed Teritory). Al-hasil, Konstruksi Negara pasca-Westphalia mesti menentukan batas-batas kedaulatan teritorialnya masing-masing, menggunakan metode-metode pengukuran geografis dan data-data spasial, yang berguna untuk me-nentukan mana wilayah kita, mana orang kita, mana the Others. Pada gilirannya penentuan perbatasan ini kerap menjadi pemicu konflik diantara Negara-negara bangsa berdaulat tersebut, kita tentu ingat betul bagaimana perebutan Sipadan dan Ligitan antara In-donesia dengan Malaysia yang memuncak pada tahun 2001, dimana jab telak Malaysia di arena Mahkamah Internasional men-T.K.O para diplomat terbaik kita (kata kita ; menjadi contoh terbaik dari apa yang dimaksud den-gan Border). Pada era Negara Westphalia pra-Globalisasi, perbatasan menentukan area spesifik mana yang kedaulatan suatu Negara menegakan dirinya, teritori pada situasi ini bersifat tertutup dan mendefinisikan luasan spasial dari suatu Negara tertentu (Minghi, 1963). Meskipun kedaulatan (Sovereignty) kian terabrasi oleh pergerakan lintas-batas dari komoditi, penduduk, dan gagasan-gaga-san, namun pengertian tradisional mengenai perbatasan tetap menduduki posisi penting bagi para Geografer dan aparatur pemerin-tahan. Penelitian-penelitian awal menge-
3 Serangkaian perjanjian damai ditandata-ngani antara Mei dan Oktober 1648 di Osnabrck dan Mnster. Perjanjian ini mengakhiri perang tigapuluh tahun (1618-1648) dalam Kekaisaran Romawi Suci, dan Delapan Puluh Tahun Tiga Puluh Tahun Perang (1568-1648) antara Spanyol dan Republik Belanda, dengan Spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda.
Firman Eko PutraMahasiswa Ilmu Hubungan InternasionalUniversitas Pasundan
-
17C S S J o u r n a l V o l . I I I 16 C S S J o u r n a l V o l . I I I
nai Batas (Boundary), terkonsentrasi pada ih-wal karakteristik kontur topografi suatu ruang, area, yang hendak diselidiki. Sifat determin-isme-naturalis ini barangkali sesuai dengan wabah demam Darwinisme yang sedang me-landa Eropa-barat dan dunia keilmuan khusus-nya. Darwinism fever ini bisa kita lacak dalam karya-karya Fredrick Ratzel, Fredrick Engels, Mackinder, hingga Haushoffer. Dalam menen-tukan Batas, mula-mula, dan terutama seorang Geografer mesti memerhatian fitur fisikal dari suatu lanskap (seperti sungai, pegunungan, lembah-lembah, dan sebagainya), yang pada
gilirannya menentukan bentuk-bentuk dan garis pembatas dari suatu perbatasan (David Newman, 2006). Penentuan perbatasan antara dua atau lebih wilayah berdaulat dengan melandaskan pada fitur alamiah suatu laskap pada kenyata-annya hingga saat ini masih menjadi metode penentuan perbatasan yang umum digunakan oleh berbagai level unit politik (political units)4
4 Multilevel politik yang digunakan disini mem-injam dari tesis yang ditawarkan John Allen yang berbunyi the exercise of power in a globally re-ordered world is less than straight forward. Increasingly, there is talk of
mulai dari pemerintah nasional, daerah, hingga komunitas warga, sejauh penggunaan metode ini diterima oleh pihak-pihak terkait dan tidak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pendistribusian kelompok etnis, kepemilikan dan kontrol atas sumberdaya, dan persoalan-persoalan politik lainnya (Newman, 2006). Konstruksi perbatasan akan terus mengalami modifikasi sesuai dengan upaya penyelesaian persoalan-per-soalan tersebut, baik yang dilakukan secara diplomatis maupun konflik terbuka seperti peperangan.
Meskipun klaim para penganut kos-m o p o l i t a n i s m e , seperti Ohmae, kian lantang terden-gar namun model penentuan perba-tasan berdasarkan fitur ekologis, ke-nyataannya tetap memainkan peranan penting dalam me-nentukan pola spa-sial manusia di area-area terpencil, yang tak begitu tersen-tuh tangan-tangan ajaib teknologi, di wilayah-wilayah di-mana kemampuan anggota masyarakat untuk memanipulasi
dan mentransformasi lanskap lingkungannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekono-mi-politiknya masih amat terbatas. Tak ayal parade pembentukan dan distribusi identitas kultural, pada masa lalu, dan masih berlang-sung hingga kini di daerah-daerah terpencil, sedikit banyak dikondisikan oleh karakter-istik lingkungan yang secara natural mem-multi-tier or multi-level governance, where power is no longer seen to operate in either a top-down or center-out fashion, but rather upwards and downwards through the different scales of political activity, both transna-tional and subnational (see, Rosenau, 1997; Newman; 1999).
bentuk pembatas-pembatas alamiah seperti gunung, sungai, lembah, hingga lautan, yang pada gilirannya menghambat mobilitas dan konsekuensinya interaksi antar kelompok social yang berada di dua area berbeda. Pem-bentukan identitas kultural berdasarkan fitur topografis ini, menjadi persoalan mana kala model perbatasan pasca-Westphalia mulai diperkenalkan, yang pada banyak kasus tidak mengindahkan sama sekali keberadaan dan distribusi kelompok etnis yang telah menem-pati suatu ruang spasial tertentu, kesepaka-tan Kerajaan Belanda dan Inggris pada 1824 yang membagi-bagi daerah koloni di asia tenggara mengkonfirmasi hal tersebut. Segregasi antara model perbatasan berdasarkan kontur alamiah dengan model pembatasan bersifat politis-fungsional ; ben-tuk political border dunia pasca-Westphalia, dan dampaknya terhadap evolusi lanskap spasial dunia menjadi salah satu tema sen-tral dalam penelitian Geografi Politik be-lakangan ini. Perhatian utamanya ditujukan pada relasi politik yang terjalin diantara kelompok-kelompok masyarakat yang ter-pisahkan oleh perbatasan administratif ; ka-bupaten/kota, provinsi, hingga Negara, dan pada sejauh mana interaksi lintas batas ini terjalin. Pada model kedua inilah rekayasa perkembangan masyarakat, menampakan dampak paling revolusionernya. Kebijakan pemerintah, berperan penting dalam penen-tuan pola perkembangan masyarakat, me-lalui kewenangannya untuk mendesain tata ekonomi-politik. Negara, dengannya dapat menentukan tingkat perkembangan (devel-opment) lanskap perbatasan, beberapa con-toh kontemporer dapat ditampilkan disini : Perbatasan Jerman Barat Timur selama empat puluh tahun, perbatasan green line antara Israel dan West Bank antara 1949 hingga 1967, serta garis lurus pemisah dua Korea, ketiganya ditinggali oleh satu etnis yang terpaksa dipisahkan satu sama lain oleh sebab-sebab politik, yang menjalankan model perencanaan pembangunan yang ber-beda satu sama lain, akibatnya kedua area tersebut memiliki pola perkembangan so-
sio ekonomi yang berbeda. Pada gilirannya pola pembangunan ini menentukan pilihan desain lanskap lingkungan di area tersebut; pembangunan yang di sesuaikan dengan kebutuhan Industri manufaktur di satu sisi, dan kebutuhan ketersediaan pangan model ekstraksi Agraris disisi lain, sebagai contoh. Ketiga contoh diatas sesungguhnya mengi-lustrasikan bagaimana rejim politik dapat memberikan dampak yang sedemikian kuat terhadap lanskap di suatu area untuk waktu yang relative singkat (bandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh pembatasan berdasarkan kontur alamiah lingkungan). Revolusi di bidang teknologi Infor-masi-komunikasi dan manajemen industri pasca-fordisme5 pada dekade 70an berkon-tribusi bagi keterhubungan (interconnec-tion)sebagian besar wilayah di seluruh dunia dalam suatu jejaring produksi global (Global Production Network), yang pada gilirannya melahirkan fenomena baru yang kita kenal dengan Globalisasi. Seperti yang dicatat oleh Dede Mulyanto , pasca-Fordisme, mengem-bangkan pranata subkontrak dan pembuba-ran pabrik-pabrik raksasa model Fordis6, mengurangi kebutuhan akan pasokan tenaga kerja nasional. Apabila lebih murah membi-ayai produksi dengan memecah lini-lini ke banyak negara miskin, kenapa pusing-pusing
5 Post-Fordisme adalah nama yang diberikan oleh beberapa sarjana untuk apa yang mereka gambar-kan sebagai sistem yang dominan produksi ekonomi, konsumsi dan fenomena sosial-ekonomi terkait, di sebagian besar negara-negara industri sejak akhir abad ke-20. Hal ini kontras dengan Fordisme, sistem dirumuskan dalam pabrik-pabrik otomotif Henry Ford, di mana pekerja bekerja pada lini produksi, melakukan tugas-tugas khusus berulang-ulang. Dede Mulyanto, Apabila lebih murah membiayai produksi dengan memecah lini-lini ke banyak negara miskin, kenapa pusing-pusing mempertahankan model manufaktur raksasa di dalam negeri? Di titik ini, apa yang disebut orang proses deindustrialisasi, terjadi di banyak pusat manufaktur negara-negara kapitalis..
6 Fordisme, diinisiasi oleh Henry Ford, adalah sebentuk gagasan tentang sistem ekonomi dan sosial modern berdasarkan bentuk industri dan standar produksi massal.
-
19C S S J o u r n a l V o l . I I I 18 C S S J o u r n a l V o l . I I I
mempertahankan model manufaktur raksasa di dalam negeri? Di titik ini, apa yang dise-but orang proses deindustrialisasi, terjadi di banyak pusat manufaktur negara-negara kapitalis, konsekuensinya Negara-negara du-nia ke-tiga seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, mengalami Industrialisasi. Maka lan-skap spasial pun mesti disesuaikan dengan logika Industri ini. Keruntuhan Unisoviet, Unifikasi Jerman, pembukaan dialog antara Istrael-Palestina, proyek dua korea melalui Kaesong Industrial Region di Korea Utara, ledakan interaksi lintas perbatasan AS-Mek-siko, hingga signifikansi regionalism model Uni Eropa sedikit banyak dikondisikan oleh revolusi-revolusi sarana produksi diatas. Bagi para penganut Globalisme, seperti Ohmae, interkoneksi antar wilayah ini menjadi suatu pembuktian bahwa konsep perbatasan, dalam pengertian sebagai garis pembatas ke-daulatan administrative suatu wilayah, telah semakin kehilangan taringnya.
Henrikson (2000) bahkan mengaju-kan argumentasi lebih jauh, bahwa interaksi lintas area yang dilakukan oleh actor-non-negara yang semakin meningkat ini, kian memengaruhi kondisi hubungan antara Neg-ara, skema periphery to center yang diperke-nalkannya didukung oleh data-data lapangan yang ia temukan di Eropa dan Amerika Seri-kat. Tipe interaksi antar kelompok masyara-kat ini bersifat bottom up, dalam arti hubun-gan social ekonomi yang dilakukan oleh dua kelompok masyarakat yang dipisahkan oleh perbatasan Negara (State-Border) pada taha-pan tertentu dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, tengok kebijakan Imigran yang diterapkan oleh Pemerintah AS bagi imigran dari Meksiko. Kesimpulan yang penulis ta-warkan pada kesempatan ini adalah bahwa, narasi geografis mengenai perbatasan ter-ritorial bersifat dinamis, dalam arti sejauh ia merupakan konstruksi social maka bentuk-bentuknya akan senantiasa berubah selama
kondisi ekonomi-politik-sosial menghenda-kinya untuk berubah, namun hal ini bukan berarti perbatasan yang bersifat politik sep-erti yang dikehendaki oleh Negara menjadi sama sekali tidak signifikan, ia tetap berdiri kendati diderai penetrasi ekonomi yang dahsyat melalui fitur modernitas baru ber-nama globalisasi. Terang kiranya kini bagi sebagian daripada kita yang sempat terjerembab kedalam lembah tautologis logika pemban-gun Negara-berdaulat, terutama terkait hal ikhwal perbatasan dan wilayah kedaulatan yang mengikatnya, bahwa persoalan perba-tasan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kesejarahannya; asal usulnya yang dapat dilacak hingga ke perjanjian Westphalia yang menjadi landasan legitimasi Negara-berdaulat. Bahwa perbatasan merupakan konstruksi social, yang didesain khusus untuk mengkonsolidasikan sumberdaya-sumberdaya yang berguna bagi keberlang-
sungan suatu komunitas politik. Pada ba-gian selanjutnya kita akan mengelaborasi lebih jauh perkembangan logika perba-tasan/batas yang berkembang pasca rev-olusi industry abad ke-19 hingga bentuk termutakhirnya kini; seperti yang dibayang-kan Ohmae. Tugas kita selanjutnya adalah menelanjangi dan menguji relevansi tesis Borderless World Ohmae tersebut. Silakan nantikan bagian ke-2 dan terakhir tulisan ini pada edisi CSS Journal berikutnya. Semoga tak ada batas diantara kita...
-
Ini bukanlah film tentang cerita cinta Fidel Castro yang berjumpa dengan seorang ga-dis desa pada saat bergerilya di pedalaman Kuba atau tarian Castro ditengah gemuruh rev-olusi dengan set kerumunan massa berikat ke-pala warna merah yang menuntut nasionalisasi pabrik gula milik pengusaha Kanada di Havana. Blame It On Fidel! adalah film drama/komedi besutan Julie Gavras , Putri sutradara kawakan Costa Gavras yang dikenal melalui film-filmnya yang bertemakan politik, salah-satunya Missing (1982) yang mendapat larangan tayang di Chili pada saat Augusto Pinochet berkuasa. Sebelum-nya Julie Gavras telah membuat tiga film doku-menter Pirate, The Wizard, The Thief dan The Children. Ketika kita selama ini hanya menyak-
Diadaptasi dari novel autobiografi karya novelis Italia, Domitilla Calamai. Kese-luruhan set dalam film ini bertempat di Paris pada awal 1970-an. Menceritakan tentang kehidupan Anna De La Messa (Nina Kervel) seorang gadis berusia sembilan tahun yang terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga borjuis tulen bahagia, sehari-hari Anna dan adiknya Franois (Benjamin Feuillet) beru-sia 4 tahun lebih muda darinya diasuh oleh Filomena. Sang Ayah, Fernando (Stefano Ac-corsi) berprofesi sebagai seorang pengacara, berasal dari keluarga aristokrat Spanyol yang mendukung berkuasanya Jendral Franco dan Ibunya Marie De La Messa (Julie Depardieu) bekerja untuk Marie Claire, majalah wanita populer Prancis.
Anna sangat menikmati keseharian-nya yang begitu menyenangkan, tinggal di-rumah yang megah, duduk di sekolah Katho-lik dan unggul dalam studi catechismus, pandai dalam seni memotong buah juga se-dikit sombong. Namun, Anna mulai merasa tidak nyaman dan merasakan ada yang ber-beda dengan suasana didalam rumah ketika Pilar, sepupunya yang tinggal di Spanyol har-us menetap bersama di rumahnya, sang Ayah memberitahu bahwa pamannya Quino (ayah Pilar, seorang aktivis politik anti-Franco) meninggal dan Pilar harus tinggal bersama dirumahnya untuk waktu yang cukup lama karena mendapatkan teror jika harus tetap tinggal di Spanyol. Filomena menceritakan bahwa Quino adalah
Ce r i t a i s i k e p a l a a nggo t a k e l u a rg a
movie review
Blame it on Fidel!Sutradara : Julie GavrasGenre : DramaDurasi : 99 MenitRilis : September 2006Pemeran : Nina Kervel Julie Depardieu StefanoAccorsi Benjamin Feuillet
21C S S J o u r n a l V o l . I I I 20 C S S J o u r n a l V o l . I I I
sikan narasi konflik ideologi atau politik yang dibungkus dalam sinema populer pada tataran high politics dengan para agen intelejen yang keluar masuk markas militer. Dalam debut fea-ture filmnya ini Gavras memberikan cerita kecil atmosfir sosio-politik dunia awal 1970-an me-lalui bahasa visual kehidupan sebuah keluarga kecil, yang dalam sinema karya para anak bang-sa pun-hollywood keluarga digambarkan penuh dengan kehangatan dan cerita-cerita meny-enangkan didalam rumah, ayah dan ibu yang pergi bekerja pada pagi sampai sore hari agar bisa membayar sewa dan melunasi kredit mobil kedua, meskipun nyatanya sangat menyebal-kan karena hidup untuk membuat hutang dan membayarnya esok hari, akhirnya harus tetap bahagia, bagaimanapun caranya.
Rifqi FadhlurrakhmanMahasiswa Ilmu Hubungan InternasionalUniversitas Pasundan
-
seorang komunis, mereka adalah barbudos (para laki-laki brewokan) orang-orang yang ingin mengambil semua yang kita miliki, mereka sangat jahat karena ingin meledakan dunia dengan bom otom, itulah mengapa ia harus meninggalkan Kuba dan sangat mem-benci Fidel Castro. Anna mulai bingung ketika ayahnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan pergi ke Chili bersama ibunya selama beber-apa minggu untuk bergabung bersama ger-
akan sayap kiri pendukung Salvador Allende. Sepulangnya kedua orangtuanya dari Chile, Anna merasakan ada perubahan yang tidak biasa, kenyamanannya mulai terusik karena harus pindah ke apartmen sederhana dengan makanan yang se-adanya, dilarang membaca komik Mickey Mouse yang merupakan simbol fasisme oleh ayahnya, dilarang mengikuti pelajaran Al Kitab dan setiap malam selalu mendapati orang-orang asing dirumahnya karena sang ayah bekerja untuk mendukung pemerintahan Allende bersama para eksil Chile yang berada di Prancis. Semenjak Filo-mena tidak lagi bekerja pada keluarganya, ia di asuh oleh Panayota, eksil Yunani kemu-dian digantikan oleh Mai Lahn, seorang ga-dis muda Vietnam, dari mereka Anna belajar mitologi Yunani dan Asia. Tidak mudah bagi seorang gadis belia meninggalkan nilai-nilai yang ia dapatkan dari lingkungan sebelum-
nya, disekolah ia mendapatkan pendidikan untuk menjadi seorang konservatif, ditanam-kan nilai-nilai borjuasi oleh neneknya dan cerita horor tentang komunis. Sosok Anna di gambarkan sebagai anak yang penuh rasa keingintahuan den-gan mencari informasi dari orang-orang yang ditemuinya, mendengar istilah dan nama-nama seperti Allende, Franco, De Gaulle, Pinochet yang sangat asing di telinga anak seumurannya. Marie dan Fernando yang
sejak awal tidak pernah terpikir akan terjun dalam kegiatan politik sangat su-lit menjelaskan apa yang sedang dihadapi oleh ked-uanya kepada putri mer-eka. Menjelang akhir dari film ini ada scene menarik yang harus pembaca saksi-kan sendiri yang meng-haruskan Anna pindah ke sekolah umum, dialog antara Anna dan suster di sekolahnya melalui cerita seekor kambing. Alur cerita utama dalam Blame it on Fidel! Bukan sekedar ke-nje-
limetan kehidupan orangtua melalui sudut pandang anak atau cerita heroisme tentang Fernando dan Marie pasangan suami istri berlatar belakang real borjuis yang melaku-kan bunuh diri kelas dengan memilih jalan untuk menjadi aktivis politik radikal karena sedang memasuki masa puber iman dan-gan mengorbankan kepastian masa depan anak-anaknya, Fernando yang mendapatkan segala kenyamanan dari orangtuanya diha-dapkan pada satu pilihan paling sulit ketika kakak iparnya dibunuh karena menentang rezim Franco, jendral yang disokong keluar-ganya sendiri untuk berkuasa dan memilih untuk melawan. Begitupula dengan Marie harus meninggalkan gaya hidup sosialita Paris 70-an dan kebun anggur yang luas mi-lik orangtuanya sebagai jaminan masa depan namun lebih memilih untuk mengikuti naluri kemanusiaannya ketika Pilar harus ditinggal-
kan oleh ayahnya karena aktivitas politiknya. Jadi, film ini sama-sekali tidak menghibur untuk anda yang ingin menyaksikan kisah heroisme keluarga komunis yang mengabdi-kan hidupnya untuk seluruh umat manusia. Jika menempatkan Fernando dan Marie dalam konteks masyarakat hari ini mungkin kita akan menganggap mer-eka melakukan hal yang konyol, banyak orang akan berkata Fernando hanya cukup mendirikan yayasan amal untuk membantu orang-orang malang nan-jauh dibelahan bumi lain, Marie hanya perlu memuat artikel tentang para anak-anak busung lapar di Af-rika pada Merie Claire edisi khusus dengan catatan jika ingin membantunya hanya perlu mengirimkan kartu pos kepada sekjen PBB yang berupa kecaman untuk melakukan kun-jungan ke Mozambik tanpa harus meneng-gelamkan diri secara militan dalam dinamika politik yang kompleks, namun itu adalah pilihan setiap orang dan siapapun tidak ber-hak menghakiminya lagi pula mereka hidup dalam konsteks ruang dan waktu yang ber-beda dengan hari ini, dimana setiap orang bingung untuk mencari musuh yang sebena-rnya. keluarga itu mengejawantahkan hasrat hipokrit mereka dan meninggalkan prinsip yang penting gue bisa konsumsi idiom yang
akan selalu kita jumpai dalam kisah kelas menengah ngehek dari jaman baheula. Namun tetap saja, ditengah kena-kalan orangtua Anna yang menjadi komu-nis, mereka mempunyai urusan dapur yang juga harus selalu ngebul sama seperti dapur keluarga lain, bukan hanya berdiskusi sam-pai larut malam untuk mengkonsolidasikan pergerakan, menelanjangi teks-teks Marx dan Lenin sepanjang hari. Di dalam rumah hidup seorang anak yang selalu ingin tahu apa yang dikerjakan oleh orangtuanya, ari-san keluarga setiap akhir bulan, pergi men-gunjungi rumah kerabat pada saat hari raya. Film ini bukan hanya merupakan konstruksi imajiner sang sutradara, namun begitulah ad-anya, komunis atau bukan Fernando adalah seorang manusia yang juga berkeluarga. Satu hal yang sangat jelas disampai-kan dalam film ini adalah keberpihakan, titik keberangkatan dari apa yang sedang diper-juangkan dan menyiratkan pesan untuk tidak menghiraukan sentilan waktu yang meng-ingatkan bahwa dunia yang ada di dalam kepala kita tidak akan terwujud begitu saja dengan hanya meyakininya, melalui sudut pandang seorang gadis berusia sembilan ta-hun.***
23C S S J o u r n a l V o l . I I I 22 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
TINJAUAN KRITIS FENOMENA LORDE:
APRESIASI KARYAATAU KOMODITI
Akhir Januari lalu dunia musik kembali dimeriahkan oleh ajang penghargaan bergengsi Grammy Awards 2014 di Staples Center, Los Angeles, Amerika. Fenomena menarik di ajang Grammy kali ini adalah kemunculan Lorde, penyanyi muda asal Selandia Baru yang memenangkan kat-egori Song of the Year dan Best Pop Solo Performance. Kesuksesan Lorde terutama karena debut terbaiknya dalam lagu Royals yang secara lirik cukup menyentil dan secara nada, jelas sangat ear catching.
Lirik yang dibawakan Lorde dalam lagu Roy-als berisi kritik terhadap nilai kemapanan, terutama untuk setiap imaji dalam serang-kaian video clip lagu-lagu hip hop kon-temporer yang sering menghadirkan gaya hidup lux nan mewah. Royals merujuk ke-pada segolongan kaum hartawan yang men-citrakan standar mimpi American Dreams yang terkadang jauh panggang dari api, den-gan realitas keadaan masyarakat umum seb-agai partisipan media. Lorde, alih-alih hidup dalam raihan mimpi semu tersebut, justru tegas melantunkan sebuah penolakan:
Atas hal ini banyak orang merasa terwakili oleh lirik tersebut dan mulai menggemari Lorde sebagai penguak realitas undercover dengan ide nyentil yang seksi. Namun, se-buah ironi klise justru baru dimulai pasca keadaan ini semakin populer. Dalam hal ini saat fenomena Lorde mengarah kepada apa yang dinamakan - saya lebih senang menye-butnya sebagai Komoditi Otokritik. Sesuatu hal yang diperjual-belikan dengan menjual nilai kritik terhadap dirinya sendiri.
Baik Royal sebagai produk maupun Lorde sebagai personal kian tereduksi ke dalam se-buah komoditi yang menghasilkan nilai jual yang tinggi. Di satu sisi kondisi ini akan men-gantarkannya menjadi seorang popstar kelas dunia yang mahal, namun di sisi lain semakin menjauhkannya dari ide dasar yang ia bawa. Sebuah paradoks yang menjelaskan menga-pa Cobain kian merasa tertekan saat dirinya semakin bersinar sebagai seorang rockstar.
Perhatian selanjutnya terhadap hal ini akan mengantarkan kita kepada sebuah analisis studi budaya mengenai pertalian dilematis antara seni dan industri. Bagaimana skema
industri bisa menyediakan fasilitas yang baik untuk menghasilkan produk seni yang disu-kai pasar secara kontinyu, namun di sisi lain semakin mereduksi karya dan penciptanya sendiri menjadi sekedar komoditi, yang ke-mudian juga mereduksi bentuk apresiasi seni menjadi sekedar kegiatan konsumsi dengan cara membeli.
Kembali melihat fenomena Lorde secara kri-tis, setidaknya bahasan ini akan memperte-gas kemampuan distingsi kita dalam meman-dang suatu hal secara lebih tajam. Dalam hal ini, antara Lorde sebagai kreator seni atau ar-tis popstar yang mahal, antara Royal sebagai karya atau komoditi, dan kita sendiri, sebagai apresiator seni atau sekedar konsumen ko-moditi, an sich.
And well never be royals, It dont run in our bloodThat kind of luxe just aint for us, We crave a different kind of buzz.
Untuk kemudian menurut saya lirik selanjut-nya dengan tegas pula melantunkan sebuah gagasan kontra kultur mengenai upaya pen-galihan power dalam relasi kuasa:
Let me be your ruler, You can call me Queen BeeAnd baby ill rule, ill rule, ill rule, ill rule. Let me live that fantasy
Kutipan tersebut berasal dari reff lagu yang notabene selalu membawa gagasan utama dari keseluruhan isi liriknya. We arent caught up in your love affair, tukasnya untuk menegaskan penolakan terhadap hasrat pur-suit of happiness di tengah nilai kemapanan kontemporer yang cenderung kapitalistik, atau lebih parahnya seperti yang diungkap-kan Fieldy Dreams dalam lagu Just For Now: you can rape me take from me, but you aint got me!.
culture
25C S S J o u r n a l V o l . I I I 24 C S S J o u r n a l V o l . I I I
Rizky SatriaStaff PengajarSalah satu SMP Swasta di Kota Bandung
-
Humanisme Marx dan Kerja Mengepel Erich Fromm
Catatan pembacaan atas Konsep Manusia Menurut Marx (Marxs Concept of Man) karya Erich Fromm
Manusia mengetahui dirinya sebanyak pengetahuannya tentang dunia; manusia mengetahui dunia hanya dalam dirinya sendiri dan dia menyadari dirinya sendiri hanya dalam dunia ini. Setiap objek yang benar-benar baru dikenal membuka sebuah organ baru dalam diri kita. ` -Goethe, Faust.-
KONSEP MANUSIA MENURUT MARX
Judul Buku Asli : Marx's Concept of ManPenulis : Erich FrommPenerjemah : Agung PrihantoroPenyunting : KamdaniTebal Buku : xiv+352 halaman dan indeksTahun Penerbitan : 2001Penerbit : Pustaka Pelajar
resensi buku
Kesalahpahaman dan kekeliruan mema-hami bangunan teori Marx baik oleh para oposan maupun dari kalangan pendaku Marxis sendiri sudah setua sejarah perkembangan teori-teori yang Marx bangun sejak kali pertama ia menuliskan kritiknya se-bagai seorang borjuis-radikal terhadap sang soko guru filsafat jerman Hegel, yang adalah juga mentor filsafatnya dalam Critique of Hegel's Philosophy of Right . Laiknya ilmu-ilmu sosial pada umumnya teori-teori Marx tak luput dari distorsi pengetahuan baik di-lakukan secara sengaja, atas motif-motif ide-ologis maupun tak sengaja, karena kekurang cakapan (lackness) dalam pencerapan peng-etahuan atas karya-karyanya. Apa yang menjadi pembeda adalah perlakuan khusus yang diberikan oleh komunitas intelektual, media pengkabaran, politikus-politikus, serta konsekuensinya man-on-the-street terhadap karya-karya Marx. Dengan mudah
kita dapat menunjukan contoh pemelitiran-pemelitiran kecil atas pemikirannya seperti yang terkandung dalam pernyataan Hey bung, hindarilah membaca teks-teks bera-cun seperti tulisan-tulisan Karl Marx itu, ia adalah seorang Materialis, cum, atheis!1, dengan percaya diri sang kritikus kemudian menubuhkan kritiknya tersebut, Marx itu cuma percaya kalau motif psikologis manu-sia yang tertinggi adalah keinginannya untuk memperoleh dan bersenang-senang dengan uang, dan bahwa upaya untuk memperoleh keuntungan merupakan pendorong utama dalam kehidupan pribadinya dan manusia pada umumnya , thus, sebagai sapu jagat ia lengkapi dengan kesimpulan akhir bahwa Marx cuma memikirkan hal-hal duniawi dan memandang hal surgawi (teologis) se-bagai suatu imajinasi manusia belaka, maka
1 Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx (Pustaka Pelajar, 2001).
Oleh : Firman Eko Putra
27C S S J o u r n a l V o l . I I I 26 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
tujuan Marx adalah pembebasan spiritual manusia, pembebasan manusia dari be-lenggu determinasi ekonomi, restitusi ma-nusia dalam keseluruhan kemanusiaannya, membuat manusia agar dapat menemukan kesatuan dan harmoni dengan sesamanya dan alam semesta
dengan itu ia tak lebih dari seorang murtad al kafirun yang mesti kita buang jauh-jauh kekeranjang sampah neraka jahanam!. Maka neraka adalah ganjaran setimpal bagi mereka wahai para pembaca Marx, sungguh mengesan(l)kan, bahkan seri komik siksa api neraka Tatang S ataupun dunia Inferno yang dibayangkan Dante Aligierhi pun dibuatnya turun kasta jadi dongeng-dongeng taman firdaus. Erich Fromm, seorang ilmuan den-gan latar belakang ilmu Psikologi, dalam bukunya bertajuk Konsep Manusia Menurut Marx, yang terbit pertama kali tahun 1961, mencoba memikul tugas besar, mirip lakon sisipus dalam sastra Camus untuk mereha-bilitasi teori-teori Marx tentang Manusia dari penyalah tafsiran ekstrim yang dilakukan oleh dua kubu yang sesungguhnya saling bertentangan secara antagonis, setidaknya dilapangan politik, kaum Oposisi yang dire-presentasikan oleh koalisi Teoritisi-Politisi-Masyarakat Sipil pengagung Kapitalisme-Liberal-Demokrasi dengan kalangan yang menandai identitas diri mereka dengan panji-panji Kiri/Komunis/Anarcho/Sosial-Demokrat, et cetera. Selain kerja menge-pel noda-noda bandel yang menempel di lantai Filsafat Marx, pekerjaan Fromm yang tak kalah penting lainnya adalah upayanya untuk mengumpulkan kepingan-kepingan konsep pokok Marx tentang eksistensi ma-nusia dan alienasi, yang ia sajikan ulang bagi khalayak pembaca dengan apik mela-lui laku pembacaannya terhadap beberapa teks Marx berkenaan dengan pokok pikiran tersebut terutama yang berceceran dalam Economic and Philosophical Manuscript dan Capital. Dalam edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar, buku yang dialih bahasakan dengan judul Konsep Manusia Menurut Marx ini memuat tiga Bab yang dibagi menjadi beberapa sub Bab. Sejatinya tulisan-tulisan tangan Fromm hanya mengisi satu dari tiga bab dalam buku ini, yang mana diantaranya terdapat pokok-pokok bahasan yang terbagi menjadi delapan sub bab, yang merentang dari hal-ichwal Kesalahpahaman terhadap konsep-
konsep Marx, hingga uraian mengenai Marx sebagai seorang Manusia, yang akan kita diskusikan satu persatu dalam tulisan ini. Manuskrip-manuskrip Tentang Ekonomi dan Filsafat, Marx, sengaja disisipkan pada Bab kedua sebagai sumber primer dari petu-alangan penelitian Fromm yang disajikan pada bab sebelumnya, namun Bab terakhir lah yang paling memanusiakan seorang Karl Marx, sebagai seorang Ayah, Suami, Sahabat, sekaligus Aktivis gerakan Komunis Interna-sional yang memiliki kualitas kemanusiaan dengan aktivitas keseharian dengan berba-gai fragmen personal laiknya manusia pada umumnya.
Erich Fromm dan Kain Pel Ajaib
Barangkali pekerjaan rumah paling membosankan sekaligus melelahkan adalah pekerjaan menyapu dan mengepel lantai, butuh ketekunan dan kejelian untuk menyi-sir sudut-sudut paling sulit dijangkau oleh peranti pembersih yang digunakan. Kiranya jenis pekerjaan ini lah yang dilakukan oleh Fromm, tentunya kata kerja mengepel kami pinjam sekedar sebagai metafor untuk menunjukan kerja (re)produksi pengetahuan yang ia lakukan dalam merehabilitasi teori Marx tentang logika gerak laju sejarah per-adaban masyarakat, khususnya berkenaan dengan hal-ikhwal Manusia sebagai pelaku dan bagian dari sejarah itu sendiri, lebih jauh lagi tentang Manusia dengan segala kategori kemanusiaan yang mengikutinya. Fromm mengambil bidang kerja penelitian Human-isme Marx yang pada masanya, medio abad ke-20, dianggap asing bagi para pembaca berbahasa inggris, yang kebetulan berada tepat di lintasan sejarah Perang Dingin. Keti-ka diterbitkan pertama kali pada 1961, buku ini dengan sengaja diterbitkan untuk mem-bantu meluruskan pemahaman atas filsafat Marx yang terdistorsi habis-habisan kanan-kiri-depan-belakang. Pada masa itu buku-buku terjemahan Marx dalam bahasa inggris masih amat terbatas jumlahnya, tak heran kesempatan yang minim untuk membaca tu-lisan-tulisan tangan pertama Marx ditambah
doktrin-doktrin politik Containment Policy a la dunia berbahasa inggris menjadi dua dari sekian banyak peubah (variable) yang me-mengaruhi kekeliruan pembacaan atas pe-mikiran Karl Heinrich Marx. Hembusan semangat jaman rupan-ya membawa angin ide-ide Marx ke Sembilan penjuru mata angin, khususnya ke Negara-negara berbahasa inggris. Tumbuhnya mi-nat terhadap bacaan-bacaan berplat Marxis sedikit banyak dibantu oleh meningkatnya signifikansi pemikiran humanis dalam waca-na Kristen disatu sisi, dan dalam wacana So-sialis disisi lain. Seperti dicatat oleh Fromm, Pentingnya Humanisme yang mendapatkan angin segar di dalam Gereja Katolik Roma da-pat dilihat dari fatwa-fatwa Paus John XXIII, Teilhard de Chardin, dan Teolog-teolog sep-erti Karl Rahner dan Hans Kung; di Gereja Protestan kita bisa menyebut teolog-teolog seperti Paul Tillich dan Albert Schweitzer., sedangkan melangkah keseberang kiri jalan kita menemukan, di sudut spektrum filosofis lainnya, terdapat bukti bahwa para pemikir Marxis juga tertarik dengan humanisme baru, khususnya dianta-ra filsuf-filsuf Marxis di Yugoslavia, Polandia, dan Cekoslovakia, serta di Eropa Barat dan Amerika. Nama-nama sep-erti George Lukacs, Adam Schaff, Vejko Korac, Ernst Bloch, dan banyak lagi lainnya melon-tarkan pemikiran yang menunjukan bang-kitnya humanism sosialis ini2. Humanisme seolah menjadi bahasa universal yang mendamaikan kedua poros filsafat itu, meski dengan sangat jelas per-debatan teoritik diantara keduanya seolah saling menegasikan satu sama lain, namun cukuplah kita dapat menarik benang merah pemikiran dan semangat yang sama dalam Humanisme. Renaisans Humanisme dalam dua tradisi filsafat ini tak lepas dari persepsi ancaman yang mengancam kemanusiaan,
2 Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx (Pustaka Pelajar, 2001)
Fromm membaginya kedalam dua jenis; per-tama, ancaman terhadap eksistensi spiritual manusia yang berasal dari masyarakat indus-tri dimana manusia menjadi semakin teral-ienasi, manusia sekedar menjadi homo con-sumes, sebuah benda diantara benda-benda lain, tersubordinasi di bawah kepentingan Negara dan ekonomi; kedua, ancaman ter-hadap eksistensi fisik manusia oleh senjata nuklir yang makin besar. Kedua ancaman ini buta gender, ras, kelas, hobi, ataupun katego-ri-kategori identitas manusia lainnya, ia uni-versal pada dirinya sendiri. Pada momen ini lah Humanisme manusia mengalami resurek-sinya kembali, seraya merayakan riak per-lawanan terhadap hantu peradaban (pasca)modern ini. Renaisance Humanisme Marxis abad ke-20 menyelinap dibalik tirai besi birokrasi Negara Stalinis, lengkap dengan serba-serbi kolektivisme rijid yang menge-
kang kebebasan individu, meski secara ma-teri merealisasikan kebutuhan material ma-nusia, namun sejatinya ia telah mencerabut individualitas dan menyerahkannya pada segelintir elit politik yang mengendalikan sekaligus menyediakan bahasa kebenaran (truth). Eksperimen Sosialisme gaya Soviet ini rupanya turut membangun imaji kolektif mengenai Marx dan proyek Komunismenya, yang tampak anti-spiritual, dipenuhi has-rat gila akan keseragaman, dan subordinasi birokratis. Fromm berada di garis terdepan untuk memoles bersih-bersih kekeliruan ini, baginya tujuan Marx adalah pembebasan spiritual manusia, pembebasan manusia dari belenggu determinasi ekonomi, restitusi ma-nusia dalam keseluruhan kemanusiaannya, membuat manusia agar dapat menemukan
29C S S J o u r n a l V o l . I I I 28 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
kesatuan dan harmoni dengan sesamanya dan alam semesta, Filsafat Marx baginya berdiri sebagai sejenis Messianisme Profe-tik dalam bahasa non-theistik sekuler, yang pada inti bangunan filsafatinya mengarah pada kesadaran manusia secara utuh, sejalan dengan semangat renaisans. Kekeliruan memahami Marx, dinilai Fromm, disebabkan oleh; Pertama, ketidak-tahuan yang berkenaan dengan kebebasan setiap orang untuk berpikir, berbicara, dan menulis tentang sesuatu sesuka hatinya tan-pa dilatari pengetahuan tentang Marx yang cukup. Kedua, terletak pada fakta bahwa Ko-munis Rusia mengapropriasi teori Marx dan berusaha meyakinkan dunia bahwa praktek dan teori mereka mengikuti ide-ide Marx, yang kemudian Barat menelan mentah klaim propagandis itu secara apriori. Sebenarnya, manakala Komunis Soviet (yang dijadikan model Negara persemakmuran sosialis), juga para sosialis reformis, percaya bahwa dirinya adalah musuh-musuh Kapitalisme, menurut Fromm, mereka memahami komunisme atau sosialisme dalam semangat kapitalisme. Bagi mereka, sosialisme bukanlah sebuah masyarakat yang secara kemanusiaan berbe-da dari kapitalisme, tetapi lebih sebagai ben-tuk kapitalisme dimana kelas pekerja telah meraih status yang lebih tinggi; sosialisme, kata Engels secara ironis, adalah masyarakat kekinian yang tanpa cela, Fromm merujuk pada Komunisme terror Stalin dan Negara polisi Kruschev. Kekeliruan-kekeliruan diatas sesungguhnya hanyalah gejala yang meny-embul kepermukaan, mirip fenomena ice berg, dari suatu kegagalan memahami secara utuh Materialisme dan Materialisme Historis Marx. Model pernyataan seperti Material-isme adalah filsafat yang mengklaim bahwa kebutuhan manusia akan materi dan has-ratnya untuk memperoleh semakin banyak materi merupakan motivasi utama manusia melupakan fakta bahwa Materialisme Marx tidak pernah terkait dengan motivasi psikis manusia yang dikaitkan dengan kesadaran spiritual tertentu. Untuk memahami Mate-rialisme, Fromm menganjurkan pembaca
untuk, memberikan distingsi antara Materi-alisme (naturalism), dalam terminologi fil-safat secara umum, yang menyatakan bahwa materi yang bergerak adalah konstituen yang fundamental dari alam semesta. Se-bentuk pandangan filosofis yang merentang sejak Aristoteles hingga pada ilmuan-ilmuan alam progresif yang mengklaim bahwa sub-stratum dari semua fenomena mental dan spiritual adalah materi dan proses material, konsekuensinya, materialism semacam ini mengajarkan bahwa perasaan dan ide-ide cukup dijelaskan sebagai hasil proses kimia
tubuh. Marx tentunya menentang Material-isme model ini yang mengabaikan sejarah dan prosesnya3 , sebaliknya materialisme atau metode dialektika, dalam bahasa Marx, mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia, yang melibatkan peneli-tian terhadap kehidupan ekonomi dan sosial manusia yang nyata berkebalikan dengan filsafat jerman, Tulis Marx, merujuk pada idealisme Hegel sembari memukul para Nat-
3 Karl Marx, Capital I (Chicago, 1906); 406.
uralis, yang turun dari langit ke bumi, disini kami jutru naik dari bumi ke langit. Dengan kata lain, kami tidak berangkat dari apa yang sedang dibayangkan, dipahami manusia pada zaman dulu, menuju manusia berdaging. Kami berangkat dari manusia yang nyata dan aktif, dan berdasarkan proses kehidupannya yang nyata, kami menunjukan perkembangan gerak refleks dan gema ideologis dari proses kehidupan ini4. Kemudian secara ringkas Marx mendeskripsikan metode historisnya sebagai, cara dimana manusia memproduk-si alat-alat penghidupannya pertama-tama
tergantung pada sifat dari alat aktual yang ditemukan manusia dalam eksistensinya dan yang harus dibuatnya kembali. Modus produksi ini tidak bisa dianggap begitu saja sebagai reproduksi eksistensi fisik individu-individu ini. Tetapi lebih sebagai bentuk aktivitas individu-individu yang jelas. Se-buah modus kehidupan manusia yang pasti. Individu-individu tersebut ada ketika mereka
4 Karl Marx dan Fredrick Engels, German Ideology (New York, 1939); 14
mengekspresikan kehidupannya. Seperti apa mereka, oleh karenanya, serupa dengan produksinya, yaitu dengan apa yang mere-ka produksi dan bagaimana mereka mem-produksinya. Sifat individu makanya tergan-tung pada kondisi-kondisi materialnya, yang untuk selanjutnya menentukan produksi5 . Dalam tulisan polemisnya dengan Feurbach, Marx menerangkan posisi filosofisnya yang melihat sebuah objek dalam gerakannya, yakni dalam proses menjadinya, dan tidak sebagai objek yang statis, yang dapat dijelas-kan dengan menemukan sebab fisiknya. Melalui pemaparan singkat yang pa-dat, Fromm menyimpulkan bahwa, ide yang popular mengenai sifat Materialisme Historis itu keliru. Suatu pandangan yang menyata-kan bahwa, motif psikologis manusia adalah ekonomi, jika motif ini merupakan kekuatan utama dalam diri manusia, maka begitulah materialisme historis ditafsirkan, kunci un-tuk memahami sejarah adalah nafsu manusia terhadap materi; maka kunci untuk menje-laskan sejarah dapat dicari di perut manusia dan kerakusannya. Kesalahpahaman model ini berasal dari asumsi bahwa materialisme historis ialah sebuah teori psikologi yang berkenaan dengan dorongan dan nafsu ma-nusia. Materialisme historis tidak mengacu pada dorongan psikis melainkan pada modus produksi; bukan pada faktor subjektif-psikol-ogis tetapi pada faktor ekonomi-sosiologis yang objektif. Adapun dorongan-dorongan yang bersifat manusiawi, ditemukan Fromm dalam pemikiran-pemikiran Marx, dibagi menjadi dua yakni; pertama, dorongan yang konstan atau tetap yang ada di semua kondisi dan yang bentuk dan arahannya dapat diubah oleh kondisi sosial, dan kedua, dorongan yang relative, yang asal-mulanya datang dari organisasi sosial tertentu. Lanjutnya, doron-gan seksual dan kelaparan termasuk pada kategori pertama, sedangkan dorongan un-tuk meraih keuntungan ekonomi pada yang terakhir, kebutuhan akan uang diantaranya masuk kedalam golongan ini, sejauh uang sebagai suatu medium pertukaran adalah produk dari modus produksi tertentu pada
5 Idem 4; 13-14.
31C S S J o u r n a l V o l . I I I 30 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
kurun sejarah tertentu, yakni kapitalisme. Inti keseluruhan kritik Marx terhadap kapitalisme adalah, bahwa kapitalisme telah menjadikan hasrat terhadap uang dan materi sebagai mo-tif utama manusia, dan konsepnya tentang sosialisme sepenuhnya merupakan konsep tentang masyarakat di mana hasrat terhadap materi ini tidak akan menjadi dominan lagi.
Masalah-masalah Psikologi : Kesadaran, Watak, dan Keterasingan Manusia
Seorang rekan diskusi saya di kam-pus sekali waktu, sesungguhnya berkali-kali, ditengah obrolan di malam yang dingin mengutip satu kalimat penuh yang ia da-patkan, konon, dari Karl Marx yang berbunyi bukan kesadaran manusia yang menen-tukan keadaannya, melainkan, sebaliknya, keadaan sosialnyalah yang menentukan (?) kesadarannya!, di momen berikutnya saya akan mengerenyitkan dahi untuk mencer-nanya sambil bertanya dalam kepala, namun sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kesadaran itu? Fromm punya jawaban un-tuk itu. Fromm memperkenalkan kita den-gan dunia kesadaran, dengan klaim bahwa Marx, Spinoza, hingga Freud, percaya bahwa sebagian besar dari apa yang dipikirkan ma-nusia secara sadar adalah kesadaran palsu (false consciousness), yaitu ideologi dan ra-sionalisasi; bahwa dorongan utama perilaku manusia yang sebenarnya tidaklah disadari. Bagi Freud, dorongan tersebut berakar pada dorongan libinal manusia, menurut Marx, dorongan itu berakar pada keseluruhan or-ganisasi sosial manusia yang mengarahkan kesadarannya menuju titik tertentu dan menghalanginya dari kesadaran akan fakta dan pengalaman tertentu.6 Marx tidak hen-dak mengatakan bahwa dunia ide itu tidak nyata, Marx dalam konteks ini membicarakan kesadaran bukan ide-ide. Kebutaan pikiran sadar manusialah yang mencegahnya dari ke-sadaran akan kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesungguhnya, dan akan ide-ide yang berakar pada kebutuhan tersebut. Hanya
6 Lihat; Suzuki, Fromm, de Martino, Zen Budhism and Psychoanalysis (New York, 1960).
jika kita mampu mentransformasi kesadaran palsu ini menjadi kesadaran sejati, yang sa-dar akan realitas, kita dapat menjadi sadar akan kebutuhan-kebutuhan kita yang nyata. 7 Kiranya persoalan kesadaran men-jadi semakin tidak mudah untuk dipahami mengingat Fromm tidak menerangkan leb-ih jauh mengenai konsep tersebut dalam buku ini, diskusi lebih lanjut mengenai ke-sadaran menjadi suatu keharusan untuk da-pat betul-betul memahami terma ini secara utuh, baiklah kiranya jika pembaca turut ber-bagi pengetahuannya melalui tulisan khu-sus mengenai konsep ini, di ruang yang lain. Untuk sementara kita kembali ke persoalan yang saya hadapi dalam memahami kuti-pan kalimat empu-nya Marx yang gandrung diselip sana-sini oleh kawan saya, Dayat (ups yat!), pernyataan bahwa keadaaan so-sialnyalah yang menentukan kesadarannya menempatkan keadaan sosial determinan terhadap kesadaran, bahwa keadaan sosial menjadi fundamen dalam bangunan rumah eksistensi Manusia seolah melupakan fakta kecil bahwa untuk dapat mencipta, pada titik tertentu Manusia menggunakan kesadarann-ya untuk mereproduksi dunia objektif (kead-aan sosial), manusia seolah dianggap seba-gai objek otomat-pasif-reseptif bagai robot Jaegers dalam film Pacific Rim yang mem-butuhkan entitas dluar dirinya untuk mem-buatnya memiliki kesadaran. Benarkah Marx senaif, deterministik, itu? Fromm ke-mudian menjawabnya dengan meminjam kutipan panjang dari German Idology yang berbunyi, penciptaan ide, konsepsi, dan kesadaran, pada mulanya terjalin langsung dengan aktivitas material dan hubungan material sesama manusia sebagai baha-sa kehidupan nyata. Memahami, berpikir, hubungan mental sesama manusia, muncul pada tahap ini sebagai akibat langsung dari perilaku materialnya. Hal yang sama ber-laku pada produksi mental yang diekspresi-kan dalam bahasa politik, hukum, moralitas, agama dan metafisika suatu masyarakat. Ma-nusia yang nyata dan aktif adalah produsen
7 Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx (Pustaka Pelajar, 2001)
konsepsi, ide, dan seterusnya karena mereka dikondisikan oleh perkembangan hubungan-nya dengan kekuatan-kekuatan produksi ini sampai pada bentuk terjauhnya. Kesadaran tidak pernah dapat menjadi selain eksistensi sadar dan eksistensi manusia dalam proses kehidupan aktualnya. Jika di dalam semua ideology, manusia dan lingkungannya tam-pak terbalik sebagaimana sebuah camera obscura8 , fenomena ini menimbulkan, se-bagaimana dari proses kehidupan historis manusia, inversi objek di retina.9 Jelaslah bahwa Marx tidak memandang relasi kead-aan-kesadaran dalam relasi yang determinis, melainkan relasi dialektikal keadaan-meng-kondisikan-kesadaran hingga pada titik-titik tertentu kesadaran dapat mempengaruhi balik keadaan sejauh dimungkinkan oleh yang pertama, seperti pada permainan sepak bola; para pemain boleh sebebas mungkin berkreasi dalam lapangan, mengatur strate-gi, memainkan bola, dst untuk dapat meme-nangkan pertandingan, namun hanya sejauh batas-batas yang telah ditentukan, ada lapa-ngan beserta garis-garis pembatasnya, ada wasit sebagai juru adil, ada peraturan-per-aturan yang telah di sepakati bersama, dan lain sebagainya. Para tataran aktual hal ini percis terjadi seperti pada momen-momen revolusi, kekuatan politik, melalui penge-naan kekerasan, dapat merubah keseluruhan struktur ekonomi-politik-sosial-hukum yang telah ajeg sebelumnya. Sebagai seorang individu yang di-lahirkan dalam sebuah keluarga bertradisi Muslim, pada momen-momen hari raya saya terbiasa mendengar ungkapan-ungkapan seperti Alhamdullilah, setelah berjuang se-lama 30 hari, insyaallah kita akan kembali ke fitri, kemudian sebagai seorang anak ingu-san pernah sekali waktu dengan polosnya bertanya fitri itu siapa sih? si bibi? Ngapain
8 Camera obscura adalah sebuah alat yang ditemukan pada akhir abad pencerahan, untuk meng-gambar, dengan menggunakan cermin, imaji sebuah objek di permukaan datar. Alat ini digunakan untuk menentukan proporsi objek yang tepat. Imaji muncul di kertas yang terbalik, dan dengan menggunakan lensa imaji ini dapat diluruskan.9 Idem 4; 197-198.
main ke rumah bibi?, dengan bijak orang tua saya akan menjawabnya dengan penuh kehangatan bahwa fitri itu artinya kita kem-bali jadi seperti bayi, yang gak punya dosa, putih bersih seperti kertas (HVS) yang belum dicorat-coreti sama tangan mu yang jahil itu nak!. Jawaban sederhana itu mengantarkan saya pada kesimpulan rumit, bahwa manu-sia pada hakikatnya lahir ke bumi dengan kepolosannya, tak bernoda, tanpa dosa, dan akhirnya setelah mampu berpikir abstrak, kesimpulan tersebut menjadi lebih rumit lagi, bahwa manusia dengan segala kategori dibelakangnya dibentuk oleh lingkungan so-sialnya (kebudayaan). Kesimpulan yang telah bertahan dalam waktu yang cukup lama, bah-kan sampai belakangan ini ketika usia saya sudah menginjak kepala dua!. Keadaan men-jadi semakin membingungkan, secara bersa-maan mencerahkan, ketika pada bab empat, Fromm rupanya mengajak kita mendiskusi-kan asal-usul watak manusia, bagi Fromm, Marx memiliki pandangan yang berkebalikan dengan relativisme sosiologis, seperti model kesimpulan yang saya dapatkan tadi, Marx sebaliknya melontarkan ide bahwa manusia qua manusia adalah entitas yang dapat dike-nali dan diketahui; bahwa manusia dapat didefinisikan sebagai manusia, bukan hanya secara biologis, anatomis, dan fisik tetapi juga secara psikologis. Bagi Marx, juga Hegel, konsep ten-tang watak manusia bukanlah sebuah ab-straksi, melainkan esensi historis manusia, sebagaimana dikatakannya, esensi manu-sia bukanlah abstraksi yang inheren dalam setiap individu terpisah10 , dengan ini ia hendak menyatakan bahwa esensi manusia bersifat historis dalam arti ia terus dimodi-fikasi oleh setiap periode sejarah. Potensi manusia, bagi Marx, adalah potensi yang konstan, dalam arti sejak genus manusia be-radab muncul hingga saat ini struktur fisikal, termasuk otak, manusia tidak banyak men-galami perubahan besar, adapun kemajuan peradaban manusia disebabkan oleh relasi metabolisnya dengan alam, dengan men-transformasi alam sesuai dengan kebutuhan
10 Idem 4; 198.
33C S S J o u r n a l V o l . I I I 32 C S S J o u r n a l V o l . I I I
-
Kemerdekaan dan kebebasan bagi Marx adalah jika dia menegaskan individuali-tasnya sebagai seorang manusia yang total di setiap hubungannya dengan dunia...
"alienasi adalah bahasa kita semua, bahasa yang diungkapkan dalam kerja oleh Kapitalisme"
eksistensialnya, melalui proses produksi-reproduksi melalui tenaga kerja, manusia ke-mudian mentransformasi dirinya sendiri, dan sejarah adalah perwujudan dari relasi me-tabolis tersebut. Untuk melacak asal-usulnya manusia cukup menoleh kebelakang, seperti dinyatakan Marx keseluruhan dari apa yang disebut dengan sejarah dunia tidak lain kec-uali sejarah penciptaan manusia oleh tenaga kerja, dan terciptanya alam untuk manusia; oleh karenanya, manusia memiliki bukti yang tidak dapat disangkal atas penciptaan dirinya, asal-usulnya. Maka aktivitas mem-produksi sarana material bagi kehidupan ma-nusia, tak lain adalah proses produksi kesa-daran diri manusia, yang diekspresikan ulang melalui proses reproduksi dunia. Sebagai konsekuensi dari pengidentikan Uni Soviet dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx, maka Marx kemudian sering dituduh me-nyediakan landasan filosofis terha-dap rejim totaliter lunatik model Sta-lin, yang hanya menyediakan sedikit ruang bagi kebebasan individu. Anggapan ini dapat dimaklumi mengingat bagaimana kuatnya doktrin perang dingin, serta ter-batasnya bacaan tangan pertama Marx yang beredar, ditambah kuatnya mitos-mitos warisan orde baru bagi penduduk Indonesia mengenai Komunisme dengan segala per-sonifikasiannya. Beruntung bagi saya, seba-gai generasi yang tak sempat menikmati orde baru, sehingga bisa memiliki sedikit kelelu-asaan untuk melihat dunia secara lebih ob-jektif melalui olimpian view yang disediakan oleh teks-teks bacaan, seperti buku yang saya baca ini. Bertentangan dengan komunisme soviet, yang jauh-jauh hari Marx telah perin-gatkan akan bahaya komunisme kasar, yang dengan dominasi kekayaan materi tampak sangat besar yang bertujuan menghancur-kan segala sesuatu yang tidak dapat dimi-liki oleh setiap orang sebagai kepemilikan pribadi. Dominasi ini hendak mengelimi-nasi bakat dan sebagainya dengan kekuatan. Kepemilikan fisik, baginya, tampak menjadi tujuan hidup dan eksistensi yang unik. Per-an pekerja tidak dihapuskan tetapi dikem-
bangkan untuk semua manusia. Hubungan kepemilikan pribadi masih tetap merupakan hubungan antara komunitas dengan barang-barang. Akhirnya, kecenderungan untuk mempertentangkan kepemilikan pribad