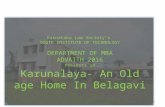CSR
-
Upload
vonny-paulin -
Category
Documents
-
view
339 -
download
1
Transcript of CSR

Menanamkan Nilai CSR: Pengembangan Struktur Penguasaan Industri Sepatu Global
ABSTRAK
Banyak perusahaan transnasional dan organisasi internasional telah merangkul corporate social responsibility (CSR) (tanggung jawab sosial badan hukum) untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi kerja dan lingkungan pada pabrik-pabrik subkontraktor. Meski ‘peraturan pelaksanaan’ CSR mudah disusun, pemenuhan oleh leveransir sudah menjadi sangat sulit. Bahkan pemantauan oleh pihak ke tiga telah membuktikan solusi yang tidak komplit. Artikel ini menawarkan suatu perubahan dalam menyediakan penguasaan jaringan, dari model pasar perpanjangan tangan ke perkongsian kolaboratif, akan sering dibutuhkan untuk melaksanakan CSR. Model pasar memaksa para kontraktor tetap fokus pada harga dan pengiriman karena mereka bersaing untuk memimpin bisnis perusahaan. Kepatuhan terhadap CSR adalah hal kedua. Suatu perkongsian di mana perusahaan pemimpin memberikan aturan memilih penyedia produk yang aman dan keuntungan lain, mengesampingkan disintensif dan menambahkan dorongan demi pelaksanaan CSR. Saat ini, kebiasaan penyedia CSR harus mengubah filosofi bisnisnya dengan menjalankan CSR demi CSR itu sendiri, tanpa menghiraukan dorongan pembeli dan pemantauan. Artikel ini menguji hipotesis ini dalam konteks sektor sepatu atletik dengan Nike, Inc. dan leveransirnya sebagai studi kasus spesifik. Data dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai menawarkan strategi memperluas CSR yang masih pada tingkat superficial dan sering tidak mempengaruhi ‘peraturan pelaksanaan’ (code of conduct).
KATA KUNCI: CSR, rangkaian nilai global, Nike, industri sepatu atletik, penguasaan.
Pendahuluan
Penguasaan rangkaian nilai global (global value chains/GVCs) telah masuk ke dalam literatur politik ekonomi dan manajemen selama lebih dari satu dekade. Penelitian membuktikan bahwa pengecer tidak lagi memiliki fasilitas pabrik tetapi kontrak dengan banyak leveransir, biasanya di negara-negara kurang berkembang (less developed countries/LDCs). Ini sering membawa mereka saling bersaing untuk mencapai harga terbaik, kualitas tertinggi, dan pengiriman paling cepat. Meski secara ekonomis menguntungkan pembeli dan konsumen di bawahnya, kompetisi dalam pasar berorientasi rangkaian nilai global ini biasanya membawa leveransir ke gaji yang lebih rendah dan pekerja penjual keringat/ standar lingkungan.
Salah satu jalan menuju kondisi pabrik yang lebih baik adalah CSR. CSR sering kali dihadirkan sebgai suatu pendekatan yang mencerahkan oleh perusahan transnasional. CSR kerap dikritik sebagai hubungan publik (public relations) yang menyangkut bisnis di dalamnya. Tahap-tahap perkembangan CSR dalam kultur sebuah perusahaan telah dicatat (Zadeck, 2004) dan masalah bisnis dalam CSR dianalisis (Capaldi, 2005; Vogel, 2005). Hal yang kurang didiskusikan dan dipahami adalah peran CSR dalam evolusi penguasaan GVC dan bagaimana penguasaan itu mengubah perkembangan pelaksanaan CSR di antara para kontraktor.
Pandangan kami adalah bahwa kepedulian CSR pembeli global dapat memicu

transformasi dalam GVC dari struktur pasar perpanjangan tangan yang kompetitif ke ‘perkongsian kolaboratif’ di mana leveransir mempunyai hubungan yang lebih dalam dan aman dengan pembeli. Hubungan yang lebihh dalam dan aman ini akan mengarah pada realisasi aturan pelaksanaan perusahaan transnasional (TNCs) yang lebih baik, tetapi pada akhirnya menuju pada pengembangan komitmen etis yang independen terhadap CSR oleh para leveransir.
Model orientasi penguasaan pasar radisional sudah jauh dari aturan CSr pembeli karena prestasi leveransir dinilai hanya berdasarkan harga, kualitas, dan pengiriman. Tekanan ekonomis ini mendorong leveransir untuk mengintip CSR demi menghindari perubahan yang mahal dan kehilangan persaingan. Akibatnya, kami menarik hipotesis bahwa perkembangan CSR menuntut adanya relasi ekonomis yang lebih aman bagi leveransir dan membuat pemenuhan aturan pelaksanaannya menguntungkan secara ekonomis. Leveransir tidak hanya akan mau tetapi lebih intensif berpartner dengan pembeli dalam menjalankan aturan. Dengan mengikuti kebiasaan CSR, kontraktor akan lebih dekat dengan nnilai moral CSR dan mendukungnya sebagai nilai moral itu sendiri tanpa memperhitungkan dorongan pembeli.
Hipotesis-hipotesis ini dapat salah. Kami mengujinya dalam sebuah penelitian terhadap industri sepatu atletik, khususnya Nike dan subkontraktornya di Korea dan Taiwan. Untuk meningkaktkan pelaksanaan CSR, Nike berpindah dari relasi pasar ke perkongsian kolaboratif di mana leveransir mempunyai hubungan yang lebih dalam dan aman dengan pembeli. Pelaksanaan CSR oleh leveransir pada awalnya berkembang karena keamanan ekonomi dan insentif, tetapi subkontraktor telah berpindah melewati pertimbangan fiscal ini untuk menginternalisasi nilai dan praktik CSR.
Sebagai tambahan terhadap kesimpulan spesifik ini, artikel ini menawarkan pendekatan interdisipliner terhadap pemahaman dan ketaatan terhadap CSR dengan menggabungkan elemen politik ekonomi, ekonomi dan sosiologi. Keuntungan praktis dari predikasi terhadap hipotesis kami termasuk mengganti hal-hal yang tidak praktis dan regulasi mahal dan memantau dengan suatu perubahan etis sikap CSR leveransir.
Presentasi kronologis artikel dimulai dengan review terhadap penguasaan pasar tradisional sepatu atletik. Setelah menjelaskan mengapa model ini tidak mengakomodasi tujuan CSR Nike, kami membuktikan dan menganalisis perpindahan Nike ke perkongsian koloboratif dan menanamkan nilai-nilai CSR ke dalam basis kontraktor.
Sektor sepatu atletik: Penguasaan berorientasi pasar memakan biaya.
Rangkaian penyediaan sepatu atletik merupakan subjek yang tepat untuk meneliti konflik dan akomodasi antara penguasaan GVC dan CSR. Sektor berpindah dari penguasaan pabrik secara langsung ke model desentralisasi dan berorientasi pasar yang menyulitkan pelaksanaan CSR menjadi perkongsian kolaboratif dengan leveransir dalam kasus Nike. Sepatu atletik merupakan ekspansi GVC yang menggabungkan agroekstraaktif (ternak untuk pemasukan kulit dan minyak mentah untuk plastic dan karet sintetis), industry (pabrik sepatu), dan servis (ekspor, pemasaran, dan pengeceran sepatu). Hal ini berorientasi kepada pembeli dengan jumlah pengecer yang besar dan penjual merek yang memimpin perusahaan (Gereffi dan Korzeniewicz 1990, 50; Gereffi 1999).
Cerita tentang rangkaian nilai simbolis ini dimulai pada tahun 1960-an ketika merek memiliki pabrik, mereka memproduksi untuk hampir semua pasar local (Donaghu dan Barff,

1990, 544); dan pemenang nasional menikmati dominasi regional: Converse dan Keds di Amerika, Tiger di Jepang, dan Adidas dan Puma di Jerman. Memasuki 1970-an terjadi restrukturisasi radikal. Nike, sejalan dengan merek sepatu atletik yang lain mulai membangun system produksi neo-Fordist. Mereka melepaskan kepemilikan pabrik dan menandatangani kontrak dengan penguasaha pabrikan, terutama di Asia yang biasa memakai proses produksi assembly line, mempekerjakan karyawan dengan keterampilan dan gaji rendah (Vanderbilt, 1998, 85).
Banjir penggunaan pertama GVC ini terjadi di Jepang, tetapi seiring naiknya harga minyak dan revaluasi yen, sebagian besar produk merek Nike dialihkan ke Korea Selatan dan Taiwan. Kedua Negara ini memiliki pekerja yang kurang mahal, relatif otoritarian, rezim politik anti pekerja, dan jaringan leveransir local yang maju. Dalam waktu kira-kira setahun, fasilitas Korea dan Taiwan memproduksi alas kaki dan sepatu tinggi dalam jumlah besar (Donaghu dan Barff, 1990, 541).
Karena negara-negara industrialisasi baru ini berubah melalui reformasi demokrasi, aktivitas pekerja, meningkatnya biaya pekerja, dan naiknya bea ekspor Amerika, Nike memindahkan GVCnya ke Indonesia, Cina (Shaw, 1999, 27), Thailand, dan kemudian ke Vietnam. Berlawanan dengan perpindahan awal, kepemilikan pabrik tetap ada pada subkontrakto, yakni orang Korea dan Taiwan (Sage, 1999, 208-209).
Dalam rencana ini, keuntungan terutama berasal dari aktivitas utama Nike yakni inovasi, strategi pemasaran, distribusi dan desain. Tekanan kompetitif dari pabrikan – harga murah, pemenuhan order, pengiriman cepat – dialihkan kepada leveransir (Carty, 1999, 98-99). ‘Spesifikasi kontrak’ ini sering memasukkan OEM (Original Equipment Manufacturing/peralatan pabrik original), menjadikan leveransir agen pasif dalam jaringan. Mereka semata-mata membuat barang-barang konsumen yang dipasarkan dan didistribusikan Nike secara global.
Struktur memungkinkan pembeli global mengubah produksi di antara pabrik dan negara, merespon tutntutan pekerja dan masalah lain terkait biaya secara fleksibel (Donaghu dan Barff, 1990, 547). Nike beruntung secara ekonomis seiring perlombaan leveransir memproduksi sepatu dengan biaya paling efektif. Ini merupakan system penguasaan berorientasi pasar yang umumnya diterapkan pembeli TNC di berbagai sektor dari sepatu dan pakaian hingga LCD dan komputer. Meski demikian, sejak 1990-an, pemimpin perusahaan, seperti Nike menghadapi masalah baru yang melampaui kalkulasi ekonomi yakni CSR.
Kurangnya CSR dalam penguasaan pasar: Respon Nike dengan code of conduct
Nike telah berubah menjadi merek ‘nyata’ dengan keuntungannya dari fungsi desain dan pemasaran. Secara serentak, sepatu karet dimodifikasi bersama-sama, memberikan image esensial pada merek hingga Nike memiliki siri tersendiri di pasar global (Goldman dan Papson, 2000, 24-25). Sayangnya, bagi Nike, produksi bersumber dari luar berarti bahwa image Swoosh-nya secara signifikan tergantung dari aktivitas leveransir yang berada di luar control penuh Nike. Sejak terlepas pada tahun 1990an, leveransir-leveransir ini dituduh secara meyakinkan telah melanggar undang-undang upah pekerja, pekrja anak, waktu lembur berlebihan, penyiksaan fisik terhadap pekerja, dan kondisi kerja yang tidak aman. Untuk menanggapi konflik antara prilaku subkontraktor dengan image public yang dibangun dengan teliti, Nike mengembangkan code of conduct sejak tahun 1992.
Kritik signifikan terhadap leveransir Nike muncul pertama kali pada tahun 1992 oleh Jeff

Ballinger, Country Program Director for the Asian-American Free Labor Institute in Indonesia, dalam artikenya di Harper’s Mounthly (Ballinger, 1992). Ballinger mempublikasikan pemotongan gaji seorang pekerja wanita Indonesia di subkontraktor Nike berbasis Korea: (1) ia mendapatkan 14 sen per jam, kurang dari ketetapan pemerintah Indonesia untuk kebutuhan fisik minimum, dan (2) ia bekerja 6 hari per minggu, 10,5 jam per hari, termasuk 63 jam lembur di mana ia mendapatkan 2 sen ekstra per jam. Laporan lain seputar para [ekerja tersebut berkaitan dengan penyiksaan fisik dan keracunan (Sage, 1999, 26, 211, & 217). Nike mulai mempunyai image sebagai ‘sweatshop’ (pasar keringat) yang terus menghantuinya sepanjang dekade ini.
Nike melawannya dengan mengatakan, “kami bukan pemilik pabrik” dan berargumentasi bahwa ketidaksempurnaan jaringan subkontraktornya adalah suatu jalan pemgembangan LDC dan tangga sosial ekonomi bagi para pekerja (Katz, 1994). Korporasi trans nasional mengikuti praktiknya secara tepat karena tidak terlihat adanya perbedaan pada sepatu atletik dan sektor-sektor global- sourcing yang sama. Pihak lain tidak menerima tanggung jawab outsourcing (sumber luar) ini (Kahle et al., 2000, 50).
Menyadari perlunya manajemen public relation, Nike menyebarkan Code of Conduct dan MoU pada 1992 (www.nikebiz.com). Disusun untuk ‘partner bisnis’ Indonesia, aturan tersebut menuntut subkontraktornya mengikuti hokum local yang mengatur gaji dan kondisi kerja dan membuktikan pelaksanaannya. Para kontraktor menerapkan praktek yang aman dan tidak membuat diskriminasi ras, gender, agama, usia, etnik, atau jenis kelamin (Shaw, 1999, 20). Aturan pertama bersifat sepihak yakni mekanisme sertifikasi voluntaris yang dioperasikan Nike dan jaringan subkontrak globalnya. Membuat aturan relative mudah, tetapi cukup sulit menjalankannya.
Alasan fundamental yang membuat implementasi aturan ini lemah adalah GVC Nike yang berorientasi pasar. Tiga kategori pabrik yang dimiliki dan dioperasikan secara independen menempati system produksi ini: ‘developed partners’ (partner yang maju), ‘volume producers’ (produser volume), ‘developing sources’ (sumber yang berkembang) (lihat gambar 1) (Donaghu dan Barff, 1990).
‘Developed partners’ mewakili eselon/tingkat atas. Dengan teknologi canggih dan keterampilan manufaktur yang inovatif , pabrik mereka bertanggung jawab membuat produk terbaru dan termahal Nike yang mendasari harga premium eceran. Meski penelitian banyak dilakukan di pusat Nike di Beaverton, developed partners juga terlibat dalam ‘pengembangan produk bersama’ (joint product development) dari produk sepatu baru melalui input material atau pengembangan proses produksi.
‘Volume producers’ adalah pabrik dengan ukuran dan kapasitas besar. Produksi massa yang terintegrasi secara vertical ini telah mampu menghasilkan antara 70.000 sampai 85.000 pasan sepatu setiap hari. Ini lima kali lebih besar dari kapasitas produksi sebuah developed partners. Kebanyakan volume producers adalah perusahaan-perusahaan Korea. Biasanya mereka tegabung dalam ‘capacity subcontracting’ (subkontrak kapasitas) untuk memenuhi gelombang permintaan yang tidak dapat dipenuhi developed partners. Tidak seperti halnya developed partners yang mempertahankan relasi khususnya dengan Nike atau membatasi kontraknya dengan banyak pembeli, volume producers sering memproduksi bagi sekurang-kurangnya sepuluh pembeli.
Kategori ketiga, ‘Developing sources’ berlokasi di Thailand, Indonesia, dan Cina, membagi Nike ke dalam wilayah dengan biaya pekerja yang lebih rendah. Meski pabrik di negara-negara tersebut hanya mempunyai kemampuan manufaktur dasar, Nike secara aktif

mendukung peningkatan kapasitas produksinya. Nike berharap agar melalui pengawasan ini proporsi signifikan developing sources akan matang dan menggantikan developed partners (Donaghu dan Barff, 1990, 542-546).
Mengambil keuntungan penuh dari system subkontrak tiga tingkat ini, Nike membuat pabrikan saling berhadapan dan memutuskan hubungan dengan leveransir yang gagal memenuhi target produksi dan standar harga. Transaksi perpanjangan tangan memungkinkan Nike bersaing dengan rivalnya dalam harga dan perbedaan produk. Nike menawarkan 900 gaya sementara competitor utamanya seperti Adidas dan L.A. Gear menawarkan kira-kira 500 (Korzeniewicz, 1994, 249).
Meski berkuasa secara ekonomis, system kontrak perpanjangan tangan merusak Code of Conduct Nike yang pertama. Dengan ancaman pembeli untuk memutuska relasi jika harga yang ditentukan leveransir terlalu tinggi, pelaksanaan aturan (code) menjadi pilihan kedua bagi kontraktor. Tekanan harga yang besar telah mamaksa pabrik-pabrik untuk meninjau kembali kontrak, materi dan proses sampai tujuh lapis penjual keliling,dan menghalangi pelaksanaan aturan ke depan. Focus ekonomi Nike menuntut suatu relasi CSR yang lebih kolaboratif antara pembeli dan leveransir. Perhatian Nike tertuju pada pajak dasar dan pabrik-pabrik subkontrak telah siap untuk berpindah ke pembeli lain dengan deal ekonomi yang lebih baik. Karena keterpisahan ini (urusan saya adalah urusan saya; urusanmu adalah urusanmu),tidak satu pihakpun yang punya komitmen serius meningkatkan kondisi kerja.
Dengan ketidakmampuan Nike memenuhi peraturan, tekanan public dan politik terhadap perusahaan ini meningkat. Pada 1996, New York Times melaporkan kondisi pekerja pada kontraktor-kontraktor Nike. Nike menghadapi kritik pemegang saham dari Inter-faith Center of Corporate Responsibility (mewakili grup investor ekumenis) dan General Board of Pension and Health Benefits of the United Methodist Church. Debat antara NAFTA dan GATT membawa kebijakan dagang negara-negara berkembang ke dalam diskusi popular. Kolumnis New York Times Bob Herbert menyerang kontradiksi antara iklan Nike tentang pemberdayaan perempuan dan perlakuan subkontraktornya terhadap pekerja perempuan, antara tingginya pembayaran terhadap artis pendukung dan rendahnya upah pekerja (Shaw, 1999, 23, 31, & 36).
Dokumentasi CBS pada tahun 1996 terpusat pada pabrik-pabrik Nike, termasuk serangan manajer pabrik terhadap pekerja di Vietnam (seorang pengawas pabrik dituduh memperkosa 15 pekerja perempuan). Dikerahkan sebuah jaringan transnasional anti-Nike termasuk Global Exchange (Amerika), Press for Change (Amerika), Vietnam Labor Watch (Amerika, Vietnam), Nike: Fair Play? (Belanda), Let’s Go Fair (Swiss). Clinton Administration menyorot CSR dengan mengumpulkan Apparel Industry Partnership (AIP) (perkongsian industri pakaian) yang termasuk Nike, perusahaan-perusahaan besar lain, serikat pekerja dan hak asasi manusia, agama, dan organisasi konsumen. Tujuannya adalah menetapkan kesepakatan industri untuk mengurangi ‘sweatshop’ (pasar keringat) (Sage 1999, 33, 47-51).
Nike secara gigih mempetahankan pelaksanaan CSRnya dan bergabung dengan AIP. Meski demikian Nike menolak monitor dari pihak ketiga (misalnya Nike tidak mengijinkan NGO, Global Exxchange untuk mengunjungi pabrik-pabrik di Indonesia atau bertemu dengan perusahaan monitoring Nike, Ernst & Young). Phil Knight menentang resolusi monitoring independen pada pertemuan pemegang saham pada tahun 1996 (Shaw, 1999, 46-47).
Image Nike terus memburuk. Pada tahun 1997, lembaga pengawas pekerja Amerika yang berbasis di Vietnam mengunjungi pabrik Nike di Vietnam dan mengeluarkan sebuah

penelitian kritis yang didukung Global Exchange dan New York Times. Penelitian ini menegaskan bahwa para pekerja tersiksa dengan panas, kelelahan, makanan yang buruk dan pukulan. (Nike mengijinkan kunjungan dengan harapan untuk maksud positif). Mahasiswa Vietnam pun bergerak yang mengakibatkan buruknya publisitas Nike. Koran asal kota Nike, Oregonian dan Doonesbury mendorong adamya perubahan. Kelompok anti-Nike membawa kritiknya ke sekolah-sekolah melalui jalan-jalan seperti artikel Scholastic Update pada Maret 1997 tentang sebuah pabrikan sepatu Nike. Sebuah poling tentang Nike pada 1996 memperlihatkan daftar praktek pekerja buruk sebagai saslah satu karakteristik yang berkaitan dengan Swoosh (Shaw, 1999, 47-51, 54, 74-77).
Nike mencoba untuk memvalidasi CSR dengan mempekerjakan mantan pemimpin hak sipil, Atlanta Mayor, dan utusan PBB Andrew Young untuk melakukan penelitian. Laporannya pada Juni 1997 menyebutkan bahwa Nike “melakukan pekerjaan bagus…tetapi Nike dapat dan harus lebih bagus.” Kelemahan metodologis mengurangi nilai laporan ini (misalnya Young salah merepresentasikan NGO dengan kelompok yang ditemuinya), dan ditemukan bahwa banyak manajer pabrik mengetahui Code of Conduct Nike (Sage, 1999, 220-221; Shaw, 1999, 65-69). Sebuah penelitian tentang dana Nike yang dilakukan oleh mahasiswa MBA dari Dartmouth College pada 1997 diremehkan metodologi dan kemampuan penelitinya. Penelitian ini berisi data yang bertentagan dengan kesimpulan positif yang diramalkan Nike (Sage, 1999, 221). Penelitian ini juga lemah karena koneksi penelitinya yang dekat dengan Nike. Nike membatasi monitor mendanainya, dan dalam kasus Young menyediakan dukungan logistic (misalnya ia tergantung pada penerjemah Nike).
Toko Town Nike di San Fransisko dan Portland menjadi tempat protes yang signifikan (Sage, 1999, 217). Pada Oktober 1997, pertemuan anti-Nike dilaporkan berlangsung di 50 kota dan 11 negara lain (Beder, 2002, 25), dan perlawanan ini terus berlanjut di Indonesia dan Vietnam (Goldman dan Papson, 2000, 180; Sage, 1999, 217). Pada April 1998 ESPN menampilkan sebuah dokumen tentang kondisi pekerja yang tidak aman dan kasar di pabrik Nike Vietnam (Shaw, 1999, 90-91).
Pada Mei 1998, CSR Nike mencapai tonggak sejarah ketika Phil Knight berjanji mereformasi praktek pekerja pada perusahaan dengan (1) menetapkan usia minimum baru bagi pekerja yakni 18 tahun, (2) memenuhi standar kualitas udara ruangan Occupational Safety and Health Administrration Amerika, (3) menigkatkan program pendidikan pekerja, (4) meningkatkan program pinjaman bisnis untuk keluarga-keluarga di Vietnam, Indonesia, Pakistan, dan Thailand, (5) mengijinkan kelompok hak asasi manusia/pekerja untuk memonitor pabrik (Sage, 1999, 226; Shaw, 1999, 93). Setelah tampilnya Knight perusahaannya memperkenalkan standar CSR baru – suatu revisi Code of Conduct – yang meredam banyak kritik.
Meski demikian memastikan pelaksanaan CSR oleh sub kontraktor tetap menjadi tantagan yang perlu dipertimbangkan, dan struktur GVC Nike yang berorientasi pasar akan terus memicu pelanggaran selama leveransir terus terfokus pada criteria pajak. Pada saat ini mendirikan ‘Future Vision’. GVC ini menawarkan kontraktor yang terpilih suatu relasi yang lebih luas dan order sepatu yang lebih aman. Dengan demikian mengurangi intensitas kompetisi ekenomi dan memperkenalkan suatu motivasi kepada pelaksana CSR lainnya. Relasi yang berubah ini melahirkan suatu partnersip/perkongsian CSR kolaboratif dan menanamkan nilai-nilai CSR dalam filsafat berbisnis para kontraktornya.

‘Partnersip Kolaboratif’: menciptakan model penguasaan baru
Nike telah berusaha menanamkan aturan CSRnya ke dalam GVC berorientasi pasar. Model penguasaan ini telah terbukti menguntungkan secara ekonomis bagi pembeli transnasional yang sumbernya berbasis harga dan pengiriman, siap berganti leveransir (Schmitz, 2004). Kerugian, sebagaimana dipelajari Nike, adalah bahwa pihak-pihak dalam rangkaian penyedia tidak membangun partnersip yang berkomitmen pada CSR. Sebaliknya kontraktor ditekan untuk menjauhkan diri dari CSR demi mencapai permintaan lain dari pembeli. Sejauh Nike benar-bemar memakai standar ekonomi dalam menyeleksi dan mempertahankan relasi dengan leveransir, hubungan antarpabrikan tidak akan mendukung tujuan CSR.
‘Future Vision’ merestruktur jaringan persediaan dengan mengkonsolidasi kontraktor ke dalam lima ‘Manufacturing Leadership Partnership’ (MLPs): Pou Chen dari Taiwan, Tae Kwong dari Korea Selatan, Pan-Asia Group dari Thailand, dan Changshin International (CSI) dari Korea (Rothenberg-Aalami, 2002, 40).tidak ada lagi pembedaan di antara kontraktor sebagi developed, developing, atau volume producers (Donaghu dan Barff, 1990), Nike mengijinkan leveransir elit ini untuk memainkan multi peran dalam relasi dengan cabang-cabangnya di Asia. Sebagai contoh, Feng Tay dari Taiwan memproduksi sepatu tinggi di Taiwan, volume sepatu lewat cabangnya di Cina dan model standar di Indonesia dan Vietnam. Sekarang, pusat MLP di Kore dan Taiwan telah menumpukkan kapasitas produksinya demi R&D, mengubah semua pabrikan menjadi sekitar 20 pabrik sepatu di Cina, Thailand, Indonesia, dan Vietnam (Rothenberg-Aalami, 2002) (gambar 2).
Berlawanan dengan kontrak berorientasi pasar yang kompetitif, MLP – format Nike meniru partnersip kolaboratif (meskipun sebenarnya sama) yang dicirikan dengan saling ketergantungan tingkat tinggi berdasarkan kehendak baik dan kepercayaan. Susunan MLP kolaboratif ini memfasilitasi penyaluran informasi di antara leveransir dalam GVC (Interview, N4). Sebagai contoh, seorang manajer senior di Korea menginformasikan kepada kami bahwa, jika mereka merintis peningkatan simpanan pekerja yang signifikan, Nike akan mengatur MLP lain untuk mengobservasi ‘praktik terbaik’ ini (Interview, VT1). Wawancara dengan MLP lain di Vietnam mengkonfirmasi adanya pengaturan (Interview, VC2, VC3, VP1, VF1). Pembagian infomasi tersebut hamper tidak mungkin dalam perpanjangan tangan GVC di mana para kontraktor bersaing secara intens untuk sejumput keuntungan.
Future Vision juga melakukan monitoring CSR pada kontraktor dan komponen tingkat leveransir. Nike mengirim ke pabrik-pabrik MLP ‘ekspatriat teknisi pabrik’ dan sebuah tim CSR untuk mengevevaluasi kondisi lingkungan dan pekerja dan menangani persoalan (Rothenberg-Aalami, 2004, 342-343). MLP juga mengirim petugas CSR untuk mengawagi kegiatan vendor. Komponen leveransir ini harus mendengarkan Approved Vendors List Nike (Daftar Vendor Berijin) yang mensyaratkan bahwa mereka mengobservasi Code of Conduct dan berkualifikasi secara teknis (Interview, SS1).
Future Vision mengubah GVC menjadi sebuah nexus produksi dan monitoring. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3, Nike mempertahankan relasi produksi primer dengan MLP yang pada gilirannya menjadi pihak subkontraktor dan komponen produksi pabrik yang terdapat dalam daftar vendor Nike.
Nike sekarang telah melengkapi GVC dengan sedikit pekerja pabrik tetapi lebih mampu yang berbagi tanggung jawab dalam R & D, produksi dan terutama CSR. Ciri-ciri ini belum bisa menggambarkan ketidakamanan ekonomi kontraktor. Kegagalan CSR sebelumnya

berakar dalam tekanan terhadap pasar GVC yang memaksa leveransir memasang harga dan pengiriman istimewa untuk pelaksanaan CSR. Meski demikian, Future Vision memiliki komponen lain: Nike membangun relasi eksklusif dengan setiap MLP dan menjamin order minimum bulanan (Frenkel, 2001). Model kontrak ini member kepastian lebih besar bahwa Nike dan MLP akan menjaga relasi pada saat baik maupun buruk, dan MLP mengharapkan ikatan khusus yang berlangsung “selama Nike eksis” (Interview, VF1, CT1).
Konversi CSR: mematuhi dan menanamkan standar CSR
Dalam model penguasaan baru, Nike sekali lagi mencoba memaksakan Code of Conductnya kepada leveransir. “CSR mulai memainkan peran yang besar dalam pilihan kami terhadap sebuah pabrik (Nike)” dan penyelidikan terhadap standar CSR menjadi “pertanyaan pertama yang diajukan” (Interview, N1). Melanjutkan bisnis dengan pabrikan partner sekarang didasarkan pada pemenuhan standar CSR, sama halnya seperti kualitas produk, harga, dan system pengiriman (Interview, N2). Saat ini subkontraktor umumnya memenuhi aturan, dan teori game menjelaskan mengapa.
Sebelum adanya Future Vision, leveransir berada dalam Penghuni Penjara Dilema (Prisioner’s Dilemma) klasik. Pelaksanaan CSR mereka akan menguntungkan seluruh GVC dengan meningkatkan image pemimpin jaringan yakni Nike. Seperti yang kami ceritakan, mulai tahun 1990an, CSR sudah menjadi salah satu factor bagi konsumen dalam memilih sepatu atletik. Jika merek global memiliki image CSR yang baik, ia dapat menghindari publisitas yang merugikan, boikot, dan ekspos media masa yang akan mempengaruhi penjualan secara negative. Leveransir akan mendapat untung dari tingginya kesan konsumen terhadap merek. Dalam hal tersebut, peralihan leveransir dari kerja sama CSR akan memberikan keuntungan paling besar bagi kontraktor tersebut, karena ia bebas menunggang di atas pelaksanaan CSR kontraktor lain dan image merek yang sudah tinggi. Scenario yang mirip dibuktikan oleh Prisioner’s Dilemma, dan ditunjukkan dalam penguasaan perpanjagan tangan GVC, merupakan peralihan kebanyakan leveransir dan mengarah pada hasil yang kurang optimal.
Di bawah Future Vision, Nike sebagai kekuatan hegemonis dalam GVC menaikkan biaya peralihan termasuk hilangnya status MLP dengan ordernya yang terjamin, informasi yang dibagikan, dan meningkatnya tanggung jawab. Lagi pula peralihan Nike ke patnersip kolaboratif dan meningkatnya tekanan CSR, leveransir yang beralih tidak akan mendapat order. Dapat diprediksi bahwa respon kontraktor merupakan kerja sama CSR (lihat, umumnya, Note, 2004, 1962-1965).
Kerja sama dibuktikan dengan tersebarluasnya kepuasan pekerja yang tampak dalam wawancara kami dengan wakil serikat di MLP. Di pabrik Feng Thay Dona Pacific yang berlokasi di Ho Chi Minh City, keluhan para pekerja terpusat pada kualitas makanan (pabrik ‘meningkatkannya’) dan kebijakan cuti tahunan (serikat kerja mengatur sebuah system rotasi) (Interview, VF3). Isu tenaga kerja terakhir pada operasi pabrik Changshin HCM City berkaitan dengan hubungan general supervisor – pekerja (perusahaan meresponnya dengan program training supervisor) dan cuti pekerja (perusahaan menyetujui permintaan pekerja) (Interview, VC4). Perselisihan tentang cuti tahunan telah menjadi keluhan utama di pabrik Tae Kwang HCM City (subkontraktor menyetujui proposal perserikatan) (Interview, VT3). Para pekerja di Pou Chen keberatan dengan beberapa bahan kimia di tempat kerja (mereka kemudian diganti). Wakil perserikatan menambahkan “sedikit” keluhan lain yang ia terima

berupa keterasingan pekerja dengan kehidupan pabrik (Interview, VP2). Sebuah laporan investigasi surat kabar Lao Dong terhadap HCM City mengatakan bahwa tidak ada lagi kasus pekerja di bawah umur, pekerja tawanan dan keluhan terakhir telah dimasukkan sebagai program cuti tahunan (Interview, SS2).
Tidak ada diskusi kami yang menutupi perhatian tradisional CSR menyangkut pekerja anak dan tawanan atau kerja lembur yang dipaksa dan illegal, gaji illegal, siksaan fisik dan kondisi kerja yang tidak aman. Keinginan pekerja untuk menyuarakan beberapa keluhan kepada kami membuktikan bahwa kami akan mendengarkan jika ada masalah yang lebih serius. Lebih sedikit masalah yang kami kemukakan dengan jelas secukupnya disampaikan oleh para kontraktor.
CSR yang lebih baik tidak akan member Anda order lebih. Yang menentukan daya saing pabrik adalah harga, kualitas dan pengiriman. CSR dapat memutuskan relasi dengan Nike. Jika Anda ketahuan menipu dalam CSR, masalahnya akan lebih serius dari pada harga dan kualitas sepatu yang Anda produksi. Kami harus berinvestasi dalam CSR. (Interview, VC1).
Pembayaran lembur adalah salah satu contoh keluhan awal leveransir tentang pelaksanaan CSR. Menurut hasil wawancara rothenburg-Aalami dengan Feng Tay (kontraktor Nike Taiwan di Vietnam), manajer pabrik berpendapat bahwa banyak pekerja menginginkan lembur karena dengan waktu tersebut dan pembayaran setengah, mereka dapat meningkatkan kompensasi take-home dengan cepat pada masa sibuk. Meski demikian, Nike, di bawah tekanan kelompok masyarakat sipil menerapkan larangan wajib lembur selama 200 jam per tahun (Rothenberg-Aalami, 2002, 208). Supervisor Korea menjelaskan “karena kami menjalankan kebijakan lembur yang keras, banyak pekerja ambisius meninggalkan perusahaan kami” (Interview, VT2). Wawancara kami di Cina, di mana jam lembur dibatasi sampai 36 jam per bulan menunjukkan fenomena yang sama.
Meskipun relasi dengan pekerja bermasalah, subkontraktor memaksakan batas jam lembur untuk menghindari pemutusan hubungan dengan Nike, suatu resiko yang lansung dipelajari seorang kontraktor pemberontak dari Korea. Meski dengan kesalahan manufacturing berulang-ulang, kontraktor berusaha melanjutkan asosiasi dengan Nike, meski ordernya menurun. Ancaman pemberhentian diberikan ketika pabrikan diketahui melanggar CSR dengan tidak membayar gaji lembur sehingga jam ‘ilegal’ tidak muncul dalam neraca seimbang (Interview, N1, CT2).
Dinamika ekonomi lainnya – perekrutan dan penyewaan tenaga kerja – sebenarnya memotivasi prilaku subkontraktor. Seorang petugas CSR di Changshin, yang terletak di zona ekonomis di mana gaji minimum cukup rendah, menjelaskan:
Kami mulai merasakan tekanan pasar tenaga kerja. Rekrutmen dan penyewaan tenaga kerja menjadi lebih sulit di Vietnam. Untuk merekrut pekerja, kami menawarkan gaji yang sama sampai daerah zona 2; upaya CR membantu kami menyewa pekerja (Interview VC2).
Pada tingkat hubungan pembeli, activitas CSR subkontraktor dapat dijelaskan dari perspektif instrumental. Aktivitas itu berupa alat procedural untuk mengamankan dan menjaga status MLP dan mendapatkan pekerja. Sementara kalkulus ekonomi, pada awalnya mengontrol,

penelitian lapangan kami membuktikan bahwa leveransir telah berkembang ke arah pendekatan normatif, menginternalisasi komitmen CSR dan menggapainya demi CSR itu sendiri. Kesimpulan ini didukung kontraktor yang mengejar aturan tambahan (extra-code), program CSR lainnya. Jika para kontraktor semata-mata didorong urusan ekonomi, kami mengharapkanpemenuhan minimal dan sama dengan standar CSR Nike yang telah dibuat detailnya. Tabel 1 menggambarkanberbagai contoh aturan-ekstra awal para kontraktor.
Pabrikan Korea di Vietnam, Changshin dan Taekwang, bekerja sama dengan sukarelawan medis Korea, melayani operasi katarak bagi pekerja dan anggota masyarakat. Changshin mempekerjakan lebih dari 200 pekerja dengan fisik meyakinkan, suatu program CSR yang tidak lazim bagi Vietnam karena aturan pekerja membatasi jam kerja orang cacat hingga 7 jam per hari. Kontraktor harus menegosiasikan suatu amandemen untuk mengakomodasi 8 jam kerja per hari dari perusahaannya. Changshin mempersiapkan bagi pekerja (1) subsidi rumah, (2) pinjaman bebas bunga, (3) perawatan medis gratis bagi keluarga, (4) orang dewasa melanjutkan pendidikan, termasuk sastra, pendidikan computer, dan program ‘life skills’, dan (5) lingkungan pabrik bebas racun. Perusahaan yang lebih besar diuntungkan dari kursus dan pelatihan teknis, pengolahan kembali dan reduksi limbah. Sebagai pekerja special, tenaga kerja Vietnam ditawari biaya perjalanan ke Korea yang memang menarik karena “Demam Korea” (Hallyu) di Vietnam (Interview, VC1, VC2, VC3).
Pou Chen, perusahaan Taiwan dan subkontraktor Nike terbesar membiayai pekrja: (1) dengan dokter dan klinik dalam, (2) pinjaman, dan (3) kelas pendidikan malam. Komunitas menerima bantuan yang ditargetkan (misalnya bantuan bencana alam) dan konstruksi pabrik daur ulang air limbah (Interview, VP1). Grup Feng Tay juga menyediakan kurikulum pendidikan malam sehingga para pekerja dapat menyelesaikan sekolah menengah mereka (Interview, VF1, VF2).s
Peralihan ke aturan tambahn CSR ini menunjukkan bahwa meskipun leveransir mula-mula mempraktikan CSR untuk memperoleh dan mempertahankan status MLP serta bersaing mendapatkan pekerja, goodwill (kehendak baik) yang diulang-ulang menjadi suatu kebiasaan dan mengubah sikap organisasi mereka. Model penguasaan baru Nike membentuk basis kontraktor, yang tidak hanya lebih menerima CSR, dank arena itu lebih mudah dimonitor, tetapi termotivasi secara independen untuk memajukan CSR.
Pegawai CSR Cahngshin mengatakan bahwa perubahan filosofis ini: “CSR menerangi perusahaan kami. Tanpanya kami tidak akan pernah mengetahui nilai CSR” (Interview, VC2). Penulis merekam sebuah transformasi etis pada pabrik sepatu Nike di Cina di mana manajer personalia Korea berkata:
Saya bangga bahwa kami melakukan pekerjaan bagus dalam kaitan dengan tanggung jawab badan hokum. Mereka diberi makan layak dan berada dalam lingkungan yang baik. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa kami tidak memikirkn hal ini juga penting di Korea. Saya menyesal dengan rekan kerja perempuan kami (Interview, CT3).
Mungkin contoh dukungan empiris terhadap peralihan nilai yang paling jelas adalah bahwa Nike mengakhiri program MLP beberapa tahun lalu, tetapi leveransir dengan hak istimewa melanjutkan aturan penyesuaian dan aturan ekstra CSR (Interview, N4). Dapat dibuktikan bahwa para kontraktor telah berubah dari ‘moralitas bersyarat’ di mana mereka menerapkan CSR semata-mata untuk mengamankan order dan ketersediaan tenaga kerja ke penanaman ‘moralitas komunitas’ di mana CSR dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam dirinya

sendiri (lihat, umumnya Lipton, 2001).Pemahaman kami terhadap evolusi filosofis ini dinformasikan oleh teori institusional,
yang mengeksplorasi pemahaman yang tersebar dan norma yang membingkai tindakan, membentuk identitas, mempengaruhi daya tarik, dan mempengaruhi apa yang dianggap sebagai masalah dan apa yang diterima sebagai solusi (Schmidt, 2005). Norma produksi Nike yang berorientasi pasar telah membentuk perpanjangan tangan GVC, tetapi mengubah norma dalam perubahan persepsi Amerika dan Eropa mengenai prilaku TNC yang tepat dan memperluas dugaan masalah produksi Nike termasuk kegagaln CSR. Karena tindakan Nike benar (Future Vision) norma pada basis kontraktor telah berkembang kea rah komitmen CSR yang lebih besar. Ekstensi kerja dalam teori etika dapat menopang kekuatan norma moral memastikan bahwa pemenuhan prilaku dapat melalui pujian dan rasa malu (Mackenzie, 2004, 54-60). Contoh paling jelas dalam produksi ekonomi adalah moral menentang perbudakan. Apapun keuntungan ekonomisnya, sangat jarang TNC dari sebuah negara maju sengaja mengasosiasikan diri dengan jaringan penyedia pekerja yang menggunakan perbudakan manusia.
Cukup beralasan untuk mempertimbangkan apakah perkembangan CSR yang diamati merupakan hasil dari monitoring dan sangsi terhadap leveransir yang diberikan Nike. Meski monitoring eksternal (Nike), pihak ketiga (FLA) (www.nikebiz.com), dan internal (leveransir) terjadi, hal itu tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh perubahan pelaksanaan CSR pada leveransir atau semua laporan peraturan tambahan CSR kontraktor.
Nike memulai monitoring pada 1997, termasuk audit Erns & Young dan inspeksi Andrew Young; tetapi kegagalan CSR signifikan dibiarkan. Bahkan sekarang, audit jarang dilakukan untuk menjelaskan perubahan. Berdasarkan rata-rata pemenuhan CSR anggota staf untuk lebih dari 10 pabrik, Nike ‘ditantang’ melakukan dua inspeksi setiap tahun untuk semua pabrikan yang aktif, dan ia mengakui bahwa monitoring, tracking dan remediasi membantu pabrik berada dalam ‘kerangka kerja yang yang menakutkan dan tidak beres.’ Target tahunan Nike pada basis pabrikan aktif adalah 25-33%, dan inspeksi FLA dibatasi hanya 5% dari leveransir (www.nikebiz.com). Di Chang Shin, misalnya, direktur CSR mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai audit pihak ke tiga dalam dua tahun terakhir (Interview, CC4).
Kesimpulan
Perubahan dalam jaringan persediaan Nike memberikan pemahaman terhadap evolusi GVC hingga meningkatnya CSR. Denan meningkatnya aktivitas konsumen dan pekerja, dan penelitian NGO, Nike memperluas perhatian leveransirnya terhadap kondisi kerja, proteksi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Meski ia mengadopsi code of conduct CSR, implementasinya terhambat karena nike menerapkan system produksi berorientasi pasar. Nike merespon dengan beralih dari kontrak perpanjangan tangan ke partnersip kolaboratif, suatu keputusan yang menunjukkan legitimasi sosial, tidak hanya ekonomi, mengarah pada perubahan jejaringan nilai global.
Di dalam partnersip ini, leveransir dibebaskan dari tekanan harga yang berat dan ketakutan berkepanjangan akan hilangnya bisnis dan pesaing yang lebih murah yang telah menghambat implementasi CSR. Kontraktor juga didorong untuk menjalankan aturan Nike untuk memenangkan dan merangkul status MLP serta menarik pekerja berkualitas. Perluasan dan peraturan tambahan CSR leveransir, sejalan dengan kelanjutan penerapan dan inovai setelah penghentian order aman minimum Future Vision, menunjukkan bahwa pabrikan telah

beralih dari ‘moralitas bersyarat’ ke ‘moralitas masyarakat’ yang mendukung CSR. Moralitas masyarakat yang tertanam ini tidak hanya merepresentasikan komitmen lebih tinggi terhadap CSR, tetapi juga harus stabil.
Sementara penelitian tambahan diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap evolusi ini, kami memberikan beberapa kesimpulan. Model penguasaan GVC dan penjelasan transisi harus mempertimbangkan peran CSR. Pendekatan terakhir cenderung terfokus pada proses manufaktur, jenis produk, perbedaan teknologi, perubahan biaya dan kelompok-kelompok kecil (Gereffi et al., 2005) atau terlampau melenceng dalam menjelaskan partnersip CSR yang dapat muncul dala relasi TNC-kontraktor (misalnya ‘quasi hirarki’, Humphrey dan Schmitz, 2004). Pendukung CSR harus melihat aturan perusahaan dan keteraturan global demi mempertimbangkan halangan dan dukungan terhadap pelaksanaan GVC. Program pelaksanaan harus terstruktur untuk mengubah CSR kontraktir agar menjadi kebiasaan dan melahirkan suatu komitmen penguatan etis pribadi untuk memajukan standar pekerja, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.