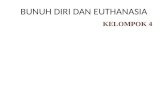Bunuh-Diri
-
Upload
doan-atrya -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of Bunuh-Diri
BAB I
PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangBunuh diri merupakan salah satu masalah utama dalam kesehatan masyarakat dimana 0,9% dari seluruh penyebab kematian adalah akibat bunuh diri. Sekitar 1000 orang mencoba untuk melakukan bunuh diri setiap harinya di seluruh dunia.Hampir sering kita dengar dan lihat di berbagai media massa maupun elektronik akan banyaknya yang melakukan bunuh diri. Mengapa orang memilih bunuh diri? Secara umum, stres muncul karena kegagalan beradaptasi. Ini dapat terjadi di lingkungan pekerjaan, keluarga, sekolah, pergaulan dalam masyarakat dan sebagainya. Demikian pula bila seseorang merasa terisolasi, kehilangan hubungan atau terputusnya hubungan dengan orang yang disayangi. Padahal hubungan interpersonal merupakan sifat alami manusia. Bahkan keputusan bunuh diri juga bisa dilakukan karena perasaan bersalah. Suami membunuh isteri, kemudian dilanjutkan membunuh dirinya sendiri, bisa dijadikan contoh kasus, depresi berat menjadi penyebab utama. Depresi timbul, karena pelaku tidak kuat menanggung beban permasalahan yang menimpa. Karena terus menerus mendapat tekanan, masalah yang menumpuk dan pada puncaknya memicu keinginan bunuh diri.Bunuh diri merupakan masalah yang cukup banyak ditemukan di negara maju tetapi belakangan ini juga marak ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan pada tahun 2005, sedikitnya 50.000 orang Indonesia melakukan tindak bunuh diri tiap tahunnya. Dengan demikian, diperkirakan 1.500 orang Indonesia melakukan bunuh diri per harinya, data ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu penting bagi kita mengetahui mengenai bunuh diri, hal-hal yang berkaitan untuk pencegahan bagi kita dan orang-orang disekitar.1.2. Batasan Masalah
Dalam MTE ini dibahas mengenai definisi, epidemiologi, etiologi dan faktor risiko, jenis-jenis bunuh diri, diagnosis dan gambaran klinis serta terapi dan pencegahan bunuh diri.
1.3. Tujuan Penulisan
Penulisan MTE ini bertujuan untuk memahami serta menambah pengetahuan tentang bunuh diri dan pencegahannya
1.4. Metode Penulisan
Penulisan MTE ini menggunakan berbagai literatur sebagai sumber kepustakaan.BAB II
TINJAUAN PUSTAKA2.1 DefinisiSecara umum, bunuh diri berasal dari bahasa Latin suicidium, dengan sui yang berarti sendiri dan cidium yang berarti pembunuhan. Schneidman mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan pada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah isu. Dia mendeskripsikan bahwa keadaan mental individu yang cenderung melakukan bunuh diri telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustasi yang bertahan lama sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk masalah yang dihadapi yang bisa menghentikan rasa sakit yang dirasakan (Maris dkk., 2000). Beberapa definisi lain dari bunuh diri adalah sebagai berikut :
Sigmund Freud (1856-1939) seorang psikoanalisis mengatakan bahwa bunuh diri merupakan agresi yang membalik kepada dirinya terhadap suatu obyek cinta.
Karl Menninger (1893-1990) seorang psikiater Amerika mengatakan bahwa bunuh diri sebagai pembunuhan terbalik karena kemarahan terhadap orang lain diarahkan kepada dirinya.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bunuh diri secara umum adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan intensi mati sebagai penyelesaian atas suatu masalah.
Sedangkan percobaan bunuh diri adalah upaya untuk membunuh diri sendiri dengan intensi mati tetapi belum berakibat pada kematian.2.2. EpidemiologiDi Amerika Serikat, setiap tahun didapati sekitar 30.000 kematian yang disebabkan oleh bunuh diri yang berhasil. Sedangkan untuk percobaan bunuh diri sekitar 8-10 kali dari angka kejadian bunuh diri yang berhasil. Saat ini ada 12,5 kematian bunuh diri per 100.000 populasi di Amerika Serikat. Selain itu, di Amerika Serikat bunuh diri menduduki peringkat ke-8 sebagai penyebab kematian setelah penyakit jantung, kanker, cardio vascular disease, kecelakaan, pneumonia, diabetes melitus, dan sirosis hepatis. Dan merupakan peringkat kedua pada usia populasi 25-34 tahun. Terjadi sekitar 75 bunuh diri setiap harinya, atau 1 kali tiap 20 menit.Bunuh diri langka pada anak sebelum pubertas dan sebagian besar masalah pada remaja, terutama diantara usia 15 dan 19, dan masa dewasa. Meskipun begitu, anak bunuh diri telah terjadi dan seharusnya tidak diabaikan pada sebelum remaja. Ide bunuh diri terjadi dengan frekuensi terbesar jika gangguan depresif berat. Bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 3 yang terbanyak di Amerika Serikat pada orang yang berusia 15 sampai 24 tahun dan nomor 2 di antara laki-laki kulit putih pada kelompok usia tersebut.Angka bunuh diri adalah tergantung pada usia, dan angka meningkat secara bermakna setelah pubertas. Bilamana kurang dari 1% bunuh diri yang berhasil per 100.000 untuk usia di bawah 14 tahun, kira-kira 10 per 100.000 bunuh diri yang berhasil terjadi pada remaja yang berusia antara 15 dan 19 tahun. Di bawah usia 14 tahun, usaha bunuh diri sekurangnya adalah 50 kali lebih sering dibandingkan succesfull bunuh diri. Tetapi, antara usia 15 dan 19 tahun, angka usaha bunuh diri adalah kira-kira 15 kali lebih besar dibandingkan succesfull bunuh diri. Jumlah bunuh diri remaja pada beberapa dekade yang lalu telah meningkat sebesar 3 sampai 4 kali.Di Indonesia, prevalensi bunuh diri pada anak dan remaja dalam satu tahun antara 1,7 - 5,9% dan untuk selama hidup antara 3,0 - 7,1%. Diperkirakan 12% dari kematian pada kelompok anak dan remaja disebabkan karena bunuh diri. Keberhasilan bunuh diri pada remaja laki-laki 5 kali lebih besar dibandingkan wanita, meskipun untuk percobaan bunuh diri pada remaja wanita 3 kali lebih banyak dibandingkan remaja laki-laki.
Di Jepang, orang kebanyakan melakukan bunuh diri untuk memperlihatkan kesetiaanya ataupun sebagai cara untuk mempertahankan harga dirinya. Banyak kita mendengar pejabat/menteri yang melakukan bunuh diri bila ia merasa telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Di Swedia pelaku bunuh diri biasanya di latar belakangi oleh penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Usia pelaku bunuh diri di negara tersebut rata-rata berkisar antara 16 34 tahun. Sedangkan di Indonesia, pelaku bunuh diri biasanya di latar belakangi oleh kesulitan ekonomi, putus asa, masalah percintaan dan sisanya disebabkan oleh masalah-masalah lain.2.3Faktor Risiko Bunuh DiriBunuh diri merupakan masalah yang kompleks karena tidak diakibatkan oleh penyebab atau alasan tunggal. Tindakan bunuh diri merupakan interaksi yang kompleks dari faktor biologik, genetik, psikologik, sosial, budaya dan lingkungan. Sulit untuk menjelaskan mengenai penyebab mengapa orang memutuskan untuk melakukan bunuh diri, sedangkan yang lain dalam kondisi yang sama bahkan lebih buruk tetapi tidak melakukannya.
Schneidman menyebut bunuh diri sebagai hasil dari psychache. Psychache merupakan rasa sakit dan derita yang tidak tertahankan dalam jiwa dan pikiran. Rasa sakit tersebut pada dasarnya berasal dari jiwa seseorang ketika merasakan secara berlebih rasa malu, rasa bersalah, penghinaan, kesepian, ketakutan, kemarahan, kesedihan karena menua, atau berada dalam keadaan sekarat (dalam Maris dkk., 2000). Di samping itu, Mann dari bidang psikiatri mengatakan penyebab bunuh diri berada di otak, akibat kurangnya tingkat 5-HIAA, reseptor post-sinapsis, dan pertanda biologis lainnya (dalam Maris dkk., 2000).
Tidak ada faktor tunggal pada kasus bunuh diri, setiap faktor yang ada saling berinteraksi. Faktor genetik
Faktor ini didasarkan pada penelitian risiko bunuh diri keluarga dan tingginya angka kesesuaian untuk bunuh diri di antara kembar monozigot dibandingkan kembar dizigotik. Walaupun risiko bunuh diri tinggi pada orang dengan gangguan mentaltermasuk skizofrenia, gangguan depresif berat, dan gangguan bipolar Irisiko untuk bunuh diri jauh lebih tinggi pada orang dengan riwayat keluarga dengan gangguan mood dibandingkan dengan riwayat keluarga dengan skizofenia.
Faktor biologis lain
Kadar serotonin (5-HT) dan metabolit utamanya, 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) yang rendah, ditemukan postmortem pada orang yang bunuh diri. Kadar 5-HIAA yang rendah ditemukan dalam cairan serebrospinal orang depresi yang berusaha bunuh diri dengan cara kekerasan; kadar 5-HIAA dapat turun akibat alcohol dan zat psikoaktif lain. Hal ini kemungkinan meningkatkan kerentanan perilaku bunuh diri pada orang yang sebelumnya telah terpredisposisi. Mekanisme hubungan antara penurunan fungsi serotonergik dengan perilaku agresif atau bunuh diri tidak diketahui, dan serotonin yang rendah mungkin hanya petanda kecenderungan agresi dan bunuh diri, bukan suatu penyebab. Beberapa penelitian pada anak-anak dan remaja menyatakan adanya suatu hubungan nonsupresi pada tes supresi deksametason dan usaha bunuh diri yang potensial mematikan
Faktor sosial
Remaja rentan terhadap lingkungan yang kacau, penyiksaan, dan penelantaran. Berbagai macam gejala psikopatologis daoat terjadi sekunder karena situasi rumah yang penuh kekerasan dan penyiksaan. Perilaku agresif, menghancurkan diri sendiri, dan bunuh diri tampaknya terjadi dengan frekuensi terbesar pada orang yang mengalami kehidupan keluarga yang penuh dengan stress secara kronis.
Sangat banyak faktor yang berperan dalam munculnya keinginan untuk bunuh diri, sedikit diantaranya : Kehilangan status pekerjaan dan mata pencaharian.
Kehilangan sumber pendapatan secara mendadak karena migrasi, gagal panen, krisis moneter, kehilangan pekerjaan, bencana alam.
Kehilangan keyakinan diri dan harga diri.
Merasa bersalah, malu, tak berharga, tak berdaya, dan putus asa.
Mendengar suara-suara gaib dari Tuhan untuk bergabung menuju surga.
Mengikuti kegiatan sekte keagamaan tertentu.
Menunjukkan penurunan minat dalam hobi, seks dan kegiatan lain yang sebelumnya dia senangi.
Mempunyai riwayat usaha bunuh diri sebelumnya.
Sering mengeluh adanya rasa bosan, tak bertenaga, lemah, dan tidak tahu harus berbuat apa.
Mengalami kehilangan anggota keluarga akibat kematian, tindak kekerasan, berpisah, putus hubungan.
Pengangguran dan tidak mampu mencari pekerjaan khususnya pada orang muda.
Menjadi korban kekerasan rumah tangga atau bentuk lainnya khususnya pada perempuan.
Mempunyai konflik yang berkepanjangan dengan diri sendiri, atau anggota keluarga.
Baru saja keluar dari RS khususnya mereka dengan gangguan jiwa (depresi, skizofrenia) atau penyakit terminal lainnya (seperti kanker, HIV/AIDS, TBC, dan cacat).
Tinggal sendirian di rumah dan menderita penyakit terminal tanpa adanya dukungan keluarga ataupun dukungan ekonomi.
Mendapat tekanan dari keluarga untuk mencari nafkah atau mencapai prestasi tinggi di sekolah.
Mendapat tekanan/bujukan dari organisasi/ kelompoknya.2.4 Jenis Jenis Bunuh DiriEmile Durkheim (1858-1917) seorang sosiolog modern, membagi bunuh diri menjadi empat kategori sosial yaitu bunuh diri egoistik, altruistik, anomik dan fatalistik. 1. Bunuh diri egoistik terjadi pada orang yang kurang kuat integrasinya dalam suatu kelompok sosial. Misalnya orang yang hidup sendiri lebih rentan untuk bunuh diri daripada yang hidup di tengah keluarga, dan pasangan yang mempunyai anak merupakan proteksi yang kuat dibandingkan yang tidak memiliki anak. Masyarakat di pedesaan lebih mempunyai integritas sosial daripada di perkotaan. Pada bunuh diri jenis ini, penderita kurang mampu beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Bunuh diri altruistik terjadi pada orang-orang yang mempunyai integritas berlebihan terhadap kelompoknya, contohnya adalah tentara Jepang dalam peperangan dan pelaku bom bunuh diri, bunuh diri bersama pada suatu sekte.
3. Bunuh diri anomik terjadi pada orang-orang yang tinggal di masyarakat yang tidak mempunyai aturan dan norma dalam kehidupan sosialnya. Pada bunuh diri jenis anomik, penderita merasa masyarakat tempatnya tinggal tidak mampu untuk membantunya dalam menghadapi permasalahan. Misalnya, pada korban bencana yang tidak kunjung mendapat bantuan.
4. Bunuh diri fatalistik terjadi pada individu yang hidup di masyarakat yang terlalu ketat peraturannya.Mitos dan Fakta Bunuh DiriNo.MitosNo.Fakta
1.Orang yang bicara mengenai bunuh diri, tidak akan melakukannya.1.Kebanyakan orang yang bunuh diri telah memberikan peringatan yang pasti dari keinginannya.
2.Orang dengan kecenderungan bunuh diri (suicidal people) berkeinginan mutlak untuk mati.2.Mayoritas dari mereka ambivalen (mendua, antara keinginan untuk bunuh diri tetapi takut mati)
3.Bunuh diri terjadi tanpa peringatan.3.Orang dengan kecenderungan bunuh diri seringkali memberikan banyak indikasi.
4.Perbaikan setelah suatu krisis berarti risiko bunuh diri telah berakhir.4.Banyak bunuh diri terjadi dalam periode perbaikan saat pasien telah mempunyai energi dan kembali ke pikiran putus asa untuk melakukan tindakan destruktif.
5.Tidak semua bunuh diri dapat dicegah.5.Sebagian besar bunuh diri dapat dicegah.
6.Sekali seseorang cenderung bunuh diri, ia selalu cenderung bunuh diri.6.Pikiran bunuh diri tidak permanen dan untuk beberapa orang tidak akan melakukannya kembali.
7.Hanya orang miskin yang bunuh diri7.Bunuh diri dapat terjadi pada semua orang tergantung pada keadaan sosial, lingkungan, ekonomi dan kesehatan jiwa
8.Bunuh diri selalu terjadi pada pasien gangguan jiwa8.Pasien gangguan jiwa mempunyai risiko lebih tinggi untuk bunuh diri, tapi bunuh diri dapat juga terjadi pada orang yang sehat fisik dan jiwanya
9.Menanyakan tentang pikiran bunuh diri dapat memicu orang untuk bunuh diri9.Bertanya tentang bunuh diri tak akan memicu bunuh diri. Bila tak menanyakan pikiran bunuh diri, tak akan dapat mengiden-tifikasi orang yang berisiko tinggi untuk bunuh diri
2.5Diagnosis dan Gambaran KlinisPikiran bunuh diri (berbicara tentang menyakiti diri sendiri) dan ancaman bunuh diri (pernyataan misalnya,ingin melompat dari mobil) lebih sering daripada pelaksanaan bunuh diri. Sepertiga dari mereka yang berusaha bunuh diri sebelumnya pernah berusaha bunuh diri. Karakteristik orang yang rentan terhadap bunuh diri adalah:
Gangguan mood dengan kombinasi penyalahgunaan zat & riwayat perilaku agresif
Tanpa gangguan mood, dengan sifat keras, agresif, dan impulsive serta memiliki konflik
Keputusasaan yang berat, kemampuan yang buruk dalam memecahkan masalah, riwayat perilaku agresif
Depresi (psikopatologi pada pria lebih berat)
Seseorang yang bercita-cita tinggi dan perfeksionistik, dan sedang kecewa karena kegagalan
Adanya stressor, seperti konflik dengan teman, putus cinta, kesulitan sekolah, pengangguran, kehilangan, perpisahan, dan penolakan.
Orang yang melakukan percobaan bunuh diri juga harus diklasifikasikan, apakah masuk kelompok risiko tinggi atau tidak. Penentuan ini penting untuk pengambilan keputusan terapi, apakah harus rawat inap atau cukup dengan rawat jalan saja. Yang masuk ke dalam kelompok risiko tinggi adalah :
Pernah mencoba bunuh diri sebelumnya
Laki-laki berusia > 12 tahun dengan riwayat perilaku agresif atau penyalahgunaan zat
Percobaan bunuh diri dengan cara mematikan, misalnya sengaja menelan racun atau dengan senjata
Memiliki gangguan depresif berat (menarik diri dari lingkungan sosial, putus asa, tidak bergairah)
Anak perempuan yang melakukan percobaan bunuh diri selain dari menelan zat toksik
Menunjukkan ide bunuh diri yang menetapTanda atau Gejala Awal Seseorang yang Ingin Bunuh DiriTerdapat gejala umum yang ditemukan pada orang yang cenderung bunuh diri:
Merasa sedih
Sering menangis
Kecemasan dan gelisah
Perubahan mood (senang berlebihan sampai sedih berlebihan)
Perokok dan peminum alkohol berat
Gangguan tidur yang menetap atau berulang
Mudah tersinggung, bingung
Menurunnya minat dalam kegiatan sehari-hari
Sulit mengambil keputusan
Perilaku menyakiti diri
Mengalami kesulitan hubungan dengan pasangan hidup atau anggota keluarga lain
Menjadi sangat fanatik terhadap agama atau jadi atheis
Membagikan uang atau barangnya dengan cara yang khusus
Dengan mengetahui seseorang yang akan berusaha atau kemungkinan berpikir tentang bunuh diri, maka kita dapat membantu melakukan pencegahan agar mereka tidak bunuh diri. Beberapa karakteristik kepribasian yang mungkin ditemukan pada orang memiliki kecenderungan bunuh diri :1. AmbivalensiKeinginan untuk tetap hidup dan keinginan untuk mati berkecamuk pada pelaku bunuh diri. Terdapat dorongan untuk lari dari pedihnya kehidupan, sekaligus terdapat pula keinginan untuk bertahan hidup. Banyak pelaku bunuh diri sesungguhnya tidak ingin mati, hanya saja mereka tidak merasa bahagia dengan kehidupannya. Bila diberikan dukungan dan keinginan untuk hidup ditingkatkan, maka risiko bunuh diri akan berkurang.
2. ImpulsivitasBunuh diri juga merupakan tindakan impulsif. Sebagaimana juga impuls lain, impuls bunuh diri juga bersifat sementara dan berlangsung hanya beberapa menit atau beberapa jam. Biasanya dicetuskan oleh peristiwa sehari-hari yang negatif. Dengan mengatasi keadaan krisisnya serta mengulur waktu, maka petugas kesehatan dapat menolong mengurangi keinginan bunuh diri.
3. RigiditasPada saat melakukan tindakan bunuh diri, pikiran, perasaan dan perilakunya terbatas. Mereka terus memikirkan bunuh diri saja dan tidak dapat menemukan jalan ke luar lain dari masalahnya. Mereka berpikir secara kaku.
2.6Terapi Gangguan Bunuh Diri dan PencegahannyaApakah seorang pasien dengan bunuh diri perlu dihospitalisasi adalah bergantung pada diagnosis gangguan jiwa yang mendasarinya, keparahan depresinya, keparahan ide-ide bunuh dirinya, kesanggupan pasien dan keluarganya untuk melawan dan menghambat ide bunuh diri tersebut, situasi kehidupan pasien, adanya sokongan sosial dan apakah ada faktor resiko untuk bunuh diri.Tindakan terapi yang dapat dilakukan bisa berupa psikoterapi individual dan psikoterapi keluarga serta farmakoterapi dan E.C.T. Khusus untuk farmakoterapi, hal ini bergantung pada diagnosis penyakit yang mendasarinya, misalnya bila oleh karena gangguan depresi maka diberikan anti depresan. Sedangkan untuk E.C.T., hal ini diberikan pada bunuh diri dengan gangguan depresi berat. Selain itu bisa juga dilakukan manipulasi lingkungan yaitu bisa berupa manipulasi lingkungan keluarga, misalnya dengan dimintakan pada keluarga pasien untuk memberikan sokongan terhadap masalah yang dihadapi pasien.Pencegahan
Upaya preventif dapat dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat, psikolog, sosiolog, pendidik, tenaga kesehatan masyarakat dan lain-lain. Selain pencegahan oleh individu, upaya pencegahan bunuh diri selayaknya juga dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat dan jaringan yang lebih luas, media massa, sektor kesehatan, guru, dan pemuka agama. Masyarakat juga harus mewaspadai tempat-tempat yang berisiko menjadi lokasi tindakan bunuh diri seperti rumah sakit, panti werda, lembaga pemasyarakatan, penginapan, mal dan lain-lain. Oleh karena itu perlu mengembangkan mekanisme pencegahan tindakan bunuh diri pada tempat-tempat tersebut dengan upaya khusus.Menurut Schneidman, patokan pencegahan praktis yang dapat dilaksanakan pada bunuh diri dengan mengurangi perasaan sakit psikologik dengan memodifikasi lingkungan stress pasien, misalnya dengan meminta pengertian dari pasangannya, temannya atau lingkungan pekerjaannya. Memberikan sokongan realistik dengan mengatakan bahwa pasien mungkin memiliki suatu keluhan yang dapat dipahami oleh orang lain serta mengusahakan tindakan alternatif terhadap bunuh diri tersebut. Teori ini dapat dijelaskan dalam lima langkah, yaitu; 1. Orang terdekat yang berperan penting dalam pencegahan bunuh diri harus peka terhadap perubahan perilaku dari teman atau anggota keluarga. Mereka yang semula ceria tetapi kini lebih sering mengurung diri di kamar, atau bahkan mulai memberi sinyal-sinyal secara eksplisit maupun tersamar, memiliki resiko untuk melakukan bunuh diri. Bisa jadi mereka sekadar mengatakan bahwa hidup ini sudah tidak menyenangkan atau lebih baik mati daripada hidup.2. Tawarkan bantuan kepada mereka. Jika mereka tampak ragu, buatlah mereka yakin. 3. Jika mereka mau berbagi masalahnya kepada Anda, arahkan mereka untuk melihat pilihan-pilihan selain bunuh diri. Menurut Schneidman, dengan memberikan opsi-opsi ini saja, biasanya sudah memberikan efek tenang. Yakinkan bahwa meskipun pilihan-pilihan itu bukan pilihan yang terbaik, tetapi masih lebih baik dari bunuh diri. 4. Dalam menayangkan berita bunuh diri, media hendaknya memberikan edukasi bagi masyarakat dengan memaparkan cara-cara pencegahannya, bukan hanya berfokus pada upaya menjelaskan penyebab mereka melakukannya.5. Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dengan mendirikan semacam pusat krisis bunuh diri. Bersama-sama, kita dapat membantu menyelamatkan jiwa sesama dengan mencegah mereka melakukan bunuh diri dan mengajarkan keterampilan menyelesaikan masalah yang efektif.BAB III
PENUTUP
Bunuh diri merupakan masalah yang cukup banyak ditemukan di negara maju tetapi belakangan ini juga marak ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia.
Bunuh diri secara umum adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan intensi mati sebagai penyelesaian atas suatu masalah. Tidak ada faktor tunggal pada kasus bunuh diri, setiap faktor yang ada saling berinteraksi. Dalam upaya pencegahan tindakan bunuh diri, kita harus mengenali gejala-gejala yang umum ditampakkan oleh seseorang yang berniat untuk bunuh diri. Tindakan pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga keluarga, masyarakat dan instansi terkait, media massa, tenaga kesehatan, guru, dan sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA1. Sadock, BJ. Kaplan and Sadocks Comprehensive Textbook of Psychiatri. 7th Ed. Volume 2. Lippincott Williams and Wilkins Publisher: USA. 2000. p. 4400-22.2. Viora E. Bunuh diri dan upaya pencegahan. Diakses tanggal 21 Desember 2011 dari http://www.novariyantiyusuf.net/konsultasi-online/187-bunuh-diri-dan-upaya-pencegahan.html.3. Psychological Etiology of Suicide. Diakses tanggal 20 Desember 2011 dari http://www.sparknotes.com/psychology/abnormal/bunuh diri/section1.html. 4. Utama H, Elvira SD, Hadisukanto G, editor. Buku ajar psikiatri. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2010.5. Greydanus DE, Bacopoulou F, Tsalamanios E. Suicide in adolescents: a worldwide preventable tragedy [review]. Keio J Med 2009; 58 (2): 95-102
6. Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Sinopsis psikiatri. Jilid 2. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher; 2010
7. Hartanto H, Koesoemawati H, Salim IN, Setiawan L, dkk., editor. Kamus kedokteran Dorland. Edisi 29. Jakarta: EGC; 2002: 3914