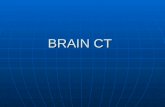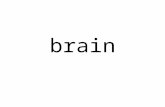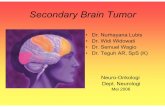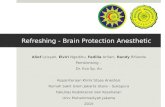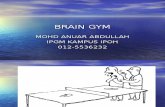Brain
-
Upload
hafidh-wahyu-purnomo -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Brain
FIQH MUAMALAHPENDAHULUAN Dalam menetapan hukum suatu permasalahan dalam Islam ,harus dilandasi dengan pijakan atau alasan berdasarkan sumber hukum agama Islam (al Quran dan as Sunnah). Namun adakalanya timbul permasalahan baru akibat dari perkembangan zaman, oleh karena itu dibutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum perkara melalui ijtihad. A. Al Quran Al Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman seperti yang tertera dalam QS 34: 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (Saba QS 34: 28) Sumber ajaran Islam juga disebut sumber pertama atau Asas Pertama Syara' (merupakan rujukan yang utama dan pertama jika ingin memutuskan persoalan). B. Hadist Hadits adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadits antara lain: Mempertegas hukum dalam Al-Qur'an Memperjelas hukum dalam Al-Qur'an Menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an C. Ijtihad Ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Macam ijtihad antara lain :
Ijma' (kesepakatan para ulama) Qiyas (diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya) Maslahah Mursalah (untuk kemaslahatan umat) 'Urf (kebiasaan)
FIQH A. Pengertian Fiqh Fiqh muamalah berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan Muamalah. Fiqh secara etimologis berarti paham. Fiqh secara terminologis berarti bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil terperinci. Muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Fiqh Muamalah berarti aturan-aturan Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dari definisi diatas terlihat bahwa Fiqh Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan Maal . Ada dua kaidah hukum asal dalam syariah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalat, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
B. Sejarah Fiqh Islam 1. Pada Masa Rasulullah SAW Sejak ayat Al Quran yang diwahyukan pertama kalinya, arah risalah Rasulullah SAW adalah membawa manusia menuju Allah SWT. Oleh karena itu, sumber hukum pada masa Rasulullah Muhammad SAW hanya satu, yaitu wahyu dari Allah SWT kepada rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al Quran dan Sunnah (hadis). Masyarakat Islam ketika itu mengetahui hukum-hukum dari Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Pada masa ini Rasulullah menjelaskan metode Ijtihad untuk menentukan hukum atas suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Masa Khulafaurrasyidin Pada masa ini banyak terjadi peristiwa baru yang memerlukan kepastian hukum, apalagi Islam tersebar luas melampaui batas semenanjung Arabia. Kenyataan ini mengharuskan para sahabat mengkaji hukumnya melalui ijtihad, seperti yang ditegaskan Rasulullah kepada para sahabatnya: Saya mewariskan kepada kamu dua hal. Selama kamu berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka tidak akan sesat. Kedua hal tersebut adalah Kitab Allah (Al Quran) dan sunnah Rasulullah SAW. 3. Akhir Masa Khulafaurrasyidin hingga Awal Abad ke-2 H Rujukan penetapan hukum pada masa ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Rayu. Namun prinsip musyawarah antara para ahli hukum Islam mulai mengalami kendala karena beberapa faktor, antara lain: semakin tersebar luas mereka di wilayah-wilayah Islam karena semakin luasnya wilayah Islam, perpecahan masyarakat Islam mengenai khalifah menjadi tiga golongan yaitu khawarij, Syiah, dan mayoritas yang moderat (kendala yang serius dalam sejarah fiqh Islam secara khusus). Dalam kelompok mayoritas yang moderat tumbuh dua macam metode penetapan hukum fiqh, yaitu ahlu al hadis (cenderung berpegang pada teks hadis) dan ahlu Ar rayu (berpegang pada hadis juga,tetapi disamping itu banyak menggunakan qiyas). 4. Awal Abad ke-2 hingga Pertengahan Abad ke-4 H Puncak pengkajian fiqh terjadi di masa ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu perhatian pemerintah terhadap fiqh dan para ahli fiqh, kebebasan berpendapat, kegiatan diskusi, banyaknya kejadian baru, luasnya pengetahuan tentang bangsa lain, dan kodifikasi ilmu pengetahuan. Mujtahid yang menonjol pada masa ini tidak kurang dari 13 orang, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik,Imam SyafiI dan Imam Ahmad bin Hambali. C. Pembagian Fiqh dan Ruang Lingkup Ditinjau dari segi pembahasan-pembahasan fiqh yang luas, dapat disimpulkan bahwa fiqh mencakup dua bidang pembahasan pokok. a. Bagian ibadat mencakup kitab-kitab tentang : Thaharah (hukum dan cara bersuci), Shalat, Jenazah, Zakat, (Puasa dan Itikaf), Haji, Jihad, Sumpah dan nadzar, (Makanan, minuman, berburu dan hewan yang dipotong), (Kurban, aqiqah dan khitan). b. Bagian Muamalat mencakup kitab-kitab tentang : Nikah, Thalaq dan hal-hal yang berhubungan dengan thalaq, Jual beli, Perjanjian (persetujuan) yang menyerupai jual beli, Peradilan, kesaksian dan hal-hal yang berhubungan dengan peradilan dan kesaksian, hal-hal yang berhubungan dengan peradilan, kejahatan dan sanksi, Hibah, wakaf dan yang semacamnya, Pembebasan dan yang berhubungan dengan pembebasan, (Faraidl dan waris).
Fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian yaitu 1. Al- Muamalah Al- Madiyah
Muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Dengan kata lain Al-Muamalah Al Madiyah adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara dari segi objek benda. Oleh karena itu maka setiap aktivitas muslim yang berkenaan dengan benda tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih dari itu untuk memperoleh ridho Allah SWT. 2. Al- Muamalah Al- Adabiyah Muamalah yang mengkaji cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari alat indra manusia sedangkan unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri dan lain-lain. Jadi Al- Muamalah Al- Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subjeknya yaitu manusia sebagai pelakunya. Akan tetapi dalam prakteknya Al- Muamalah Al- Adabiyah dan Al- Muamalah Al- Madiyah tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian pembagian itu hanya secara teoritis semata. Pembagian Ruang lingkup
FIQH MUAMALAH
Al-Muamalah Al-Mariah
Al-Muamalah Al-Adabiyah
Ruang Lingkup Ijab Qobul Saling meridhoi Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak Hak dan kewajiban Kejujuran Penipuan Dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta AKAD
Ruang Lingkup Jual beli Gadai Jaminan Sewa-menyewa tanah Upah Gugatan Sayembara Pembagian harta bersama Hibah Pembebasan dan damai
dan tanggungan Pemindahan utang Jatuh bangkit Batas bertindak Perseroan Mudharabah
NORMA AKAD (KONTRAK) DALAM FIQH ISLAM Sekilas tentang sejarah akad Aqad adalah bagian dari tasharruf (segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan beberapa haknya. Tasharruf dibagi 2 yaitu, tasharruf fili dan tasharruf qauli. Tasharruf fili adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Tasharruf Qauli adalah Tasharruf yang keluar dari lidah manusia.
Rukun akad meliputi:
1. Orang yang akad (aqid)Aqid ini disyaratkan orang yang ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu melakukan akad jika menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
2. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih)Untuk objek akad ini fuqaha menetapkan empat syarat yaitu Barang harus ada ketika akad Maqud alaih harus sesuai ketentuan syara( masyru) Dapat diberikan waktu akad Maqud alaih harus diketahui oleh pihak yang akad Maudhual-Aqd Maudhual-Aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Shighat ( ijab qobul) Ijab qobul ini dapat berupa lafadz, perbuatan, isyarat (jika mengalami cacat), ataupun dengan tulisan. Ijab qobul sendiri memiliki syarat yaitu harus jelas maksudnya, terjadi kesesuaian antara ijab dengan qobul, dan antara ijab dan qobul harus tersambung dan berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang sudah diketahui keberadaannya oleh kedua belah pihak. Syarat akad terdiri dari : syarat terjadinya akad ( segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad), syarat sah akad ( segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak), syarat pelaksanaan akad meliputi kepemilikan dan kekuasaan, syarat kepastian hukum yaitu terhindar dari khiyar. A. Alat Aqad Aqad dengan lafadz (ucapan), aqad dengan lafadz yang dipakai untuk ijab dan Qabul harus jelas dan tidak ambigu, harus bersesuaian antar ijab dan qabul, dan shighat ijab dan qabul harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Dengan cara tulisan (kitab) Jika dua aqid yang berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dilakukan dengan cara kitab, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas,tampak, dan dapat dipahami oleh 2 belah pihak. Isyarat, bagi orang-orang tertentu aqad atau ijab dan qabul tidak dapat dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Maka dibuatlah kaedah isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah Dengan perbuatan, yaitu biasanya aqad yang tidak diucapkan dapat ditunjukkan melalui perbuatan saling meridlai. B. Syarat akad 1) Syarat terjadinya akad: segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad. 2) Syarat sah akad: segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin dampak kebsahan akad, jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak. 3) Syarat pelaksanaan akad meliputi kepemilikan dan kekuasaan. 4) Syarat kepastian hukum yaitu terhindar dari khiyar. C. Pengertian aqad : Secara bahasa, akad atau perjanjian didefinisikan dalam banyak arti, yang keseluruhannya kembali kembali pada bentuk ikatan atau penghubungannya terhadap dua hal. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan sebagai: Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak. Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. D. Macam hak pilih dalam perjanjian usaha. Definisi khiyar (hak pilih)
Secara etimologi, khiyar artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Macam Hak pilih: 1. Hak pilih di lokasi perjanjian (Khiyar Majlis). Yakni hak masing masing pihak untuk membatalkan perjanjiannya atau melanjutkannya selama masih di lokasi perjanjian. 2. Hak pilih persyaratan (Khiyar Asy-Syarath). Yakni hak masing masing pihak bagi dirinya sendiri atau bagi pihak lain untuk membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. 3. Hak pilih melihat (Khiyar Ar-Ruyah). Yakni hak pilih bagi pihak pihak yang melakukan perjanjian pada objek tertentu yang belum ia lihat untuk membatalkannya bila ia telah melihat objek tersebut. 4. Hak pilih bila terdapat cacat pada objek perjanjian (Khiyar Aib). Yakni hak pilih untuk membatalkan perjanjian bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian. Cacat dalam perjanjian usaha. Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. Diantara cacat cacat itu adalah : 1. Intimidasi. Yakni memaksa pihak lain terhadap ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya, melalui gertakan dan ancaman. Intimidasi ini ada dua macam : a. Intimiasi fungsional, yakni yang dapat merusak keridhaan dan hak pilih. b. Intimidasi non fungsional, yakni intimidasi yang tidak menghilangkan keridhaan, dan tidak merusak hak pilih. 2. Kekeliruan. Yakni kekeliruan yang berkaitan dengan objek perjanjian misalkan, seseorang membeli perhiasan berlian, akan tetapi yang didapatinya perhiasan yang terbuat dari kaca. Kekeliruan terbagi menjadi dua : a. Kekeliruan yang membatalkan perjanjian, yakni bila terjadi perbedaan jenis atau fasilitas objek perjanjian secara signifikan. b. Kekeliruan yang tidak sampai membatlkan perjanjian, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap diberi hak untuk membatalkan perjanjian. 3. Penyamaran harga. Yakni terjadinya kekurangan pada salah satu barang barter atau kompensasi, atau terjadinya tukar menukar yang tidak adail (dan diketahui salah satu pihak). Penyamaran harga sendiri ada dua macam : a. Penyamaran ringan, yakni yang tidak menyebabkan objek perjanjian keluar dari harga pasaran dengan perkiraan harga para pakar perniagaan. b. Penyamaran berat, yakni yang sampai mengeluarkan barang perjanjian dari harga pasaran. E. JENIS-JENIS AKAD TRANSAKSI a. Menurut Jatuh tempo 1.Aqad Munjiz yaitu aqad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya aqad. Pernyataan aqad yang langsung diikuti dengan pelaksanaan aqad. Pernyataan ini tidak disertai syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah aqad. 2. Aqad Mualaq ialah aqad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam aqad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran. 3. Aqad Mudhaf ialah aqad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan aqad, pernyataan yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang
ditentukan,perkataan ini syah dilakukan pada waktu aqad,tetapi belum mempunyai akibat hokum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan b.Akad pertukaran 1. Jual beli Berdasarkan perbandingan harga jual dan harga beli akad a) Al musawwamah (transaksi jual beli dengan harga yang bisa di tawar, dimana si penjual tidak memberi tahu kan si pembeli harga pokok/pasar dari barang tersebut dan berapa keuntungan yang diperolehnya. Si pembeli pun bebas menawar harga barang yang akan di belinya. Terjadinya jual beli ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan cara negoisasi) b) Al Tauliah (transaksi jual beli dengan harga pokok/pasar di mana penjual tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barangnya). c) Al Muwadhaah d) Al Murabahah (perjanjian jual-beli dengan harga pasar di tambah dengan laba atau untung buat si penjual, dimana pembeli mengetahui dengan pasti nilai dari harga pasar dari barang tersebut dan nilai tambahan dari si penjual). Berdasarkan jenis barang pengganti a) Al Mughayadah (pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. b) Al Mutlaq (pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.) c) As Sharf (transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya). Berdasarkan waktu penyerahan a) Bithaman Ajil (Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit). b) Bai As Salam (Perjanjian jual beli, dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan dimuka) c) Baiu Al Istisna (Suatu perjanjian jual beli dengan cara memesan barang yang bukan komoditi atau barang pertanian tapi barang yang dibuat dengan mesin dan keahlian khusus, seperti perlengkapan kitchen set, kursi dan meja makan atau konstruksi bangunan, dimana barang tersebut dipesan dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh pembeli dengan sepsifikasi yang khusus, di bayar sebagian di muka dan bisa dengan cicilan atau langsung di bayar sekaligus apabila barang pesanan tersebut sudah selesai dan siap untuk di gunakan oleh pembelinya). d) Baiu Istijrar c. Akad Titipan/ Wadiah Wadiah adalah aqad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Jenis Wadiah: a. b. Wadiah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali. Wadiah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. d. Akad Bersyarikat 1) Al Musyarakah (terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan)
2) Al Mudharabah (Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagai antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya). 3) Muzaraah e. Akad memberi kepercayaan 1) Al Kafalah (bertujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua / yang ditanggung). 2) Al Hiwalah (alih utang piutang), bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang 3) Al Jialah (tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan pekerjaan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan). f. Akad memberi ijin/ Al Wakalah Al Wakalah terjadi apabila nasabah melakukan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Misalnya ketika pembukuan L/C, inkaso dan transfer. HARTA Harta secara Etimologis berarti sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-timbuhan dan ( tidak tampak) yakni manfaat seperti kendaraaan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan menurut ulama Hanafiayah harta itu memeiliki dua unsur penting yaitu dapat dikuasai dan dipelihara serta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama harta adalah sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasahinya. Kedudukan harta dalam Al-Quran diatur dengan: Q.S At-Taghabun :15 ( harta sebagai fitnah) Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dan disisi Allah-lah pahala yang besar. Q.S. Al-Kahfi: 46 ( harta sebagai perhiasan hidup) Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia Q.S. Ali Imron: 14 (harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan ) Dijadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dadi sisi Allahlah tempat kembali yang baik ( surga). Fungsi harta menurut Islam adalah: Kesempurnaan ibadah mahzhah; Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT ; Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah; Menyelaraskan kehidupan dunia dan akherat; Bekal mencari dan mengembangkan ilmu; Keharmonisan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. TRANSAKSI Dalam Ushul Fiqh dikenal dua kaedah hukum asal dalam syariat. yaitu dalam Ibadah itu semua tidak boleh kecuali yang ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan dalam muamalah semua itu boleh kecuali ada larangannya. Jadi dalam muamalat, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan oleh: 1. Haram zatnya / haram li-dzatihi Transaksi terlarang karena obyek yang ditransaksikan itu juga dilarang walaupun jual belinya sah, misalnya minuman keras, NARKOBA, bangkai, daging babi.
2. Haram selain zatnya/ haram li- ghairihi, terdiri dari a. Melanggar prinsip An taraddin minkum ( Tadlis). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada yang merasa dicurangi/ ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party. Unknown to one party ini dalam fiqh disebut tadlis yang dapat terjadi dalam empat hal dalam hal yaitu KUANTITAS, KUALITAS, HARGA, WAKTU PENYERAHAN. b. Melanggar prinsip La tazhlimuna Wa La tuzhlamun meliputi 1. Rekayasa pasar dalam Supply ( Ikhtikar) Terjadi apabila seorang produsen mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply sehingga harga akan naik. 2. Rekayasa pasar dalam Demand ( Bai Najasy) Terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual akan naik. 3. Taghrir (Gharar) Hal ini akan terjadi ketika terjadi incomplete information karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi ketika kita merubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam 4 hal yaitu: Kuantitas, Kualitas, Harga, dan Waktu penyerahan 4. Riba Riba Fadl Adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar yaitu ketidak jelasan bagi kedua pihak akan nilai maing-masing barang yang dipertukarkan. Tindakan ini akan menimbulkan kezaliman bagi salh satu pihak. Riba Nasiah Adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko dan hasil muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba Jahiliyah Adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditentukan. Riba jahiliyah dilarang karena melanggar kaidah Kullu Qardin jarra manfaah fatuwa Riba ( setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman dalah transaksi kebajikan ( tabarru) sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi tijarah. jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi ibadah tidak boleh dirubah menjadi transaksi bermotif bisnis, tanpa ada persetujuan lebih dahulu. ZAKAT 1. Pengertian Zakat Zakat menurut etimologi berarti berkembang dan bertambah, mensucikan dari kotoran, dan kebaikan. Sedangkan zakat menurut terminologi berarti hak (kadar tertentu) yang diwajibkan (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu pula. Kata golongan yang tertentu maksudanya adalah delapan golongan yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya pada QS At Taubah :60. Sedangkan kata waktu yang tertentu maksudnya ialah kepemilikan itu sudah sempurna penuh dalam satu tahun. Zakat merupakan salah satu pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Pembentukan keshalihan pribadi dan keshalihan dalam sistem masyarakat inilah salah satu tujuan diturunkannya Risalah Islam sebagai rahmatallil lilalamin
oleh allah SWT kepada manusia.Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. zakat (juga infaq dan shadaqah) adalah salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat. Allah SWT berfirman; Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS At Taubah : 71) 2. Syarat dan Harta Wajib Zakat a. Syarat Wajib Zakat Para ahli fiqih bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka, beragama Islam, baligh dan berakal, mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya, lelaki atau perempuan. Dalam hal ini banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama mengenai harta anak kecil dan orang gila, apakah wajib zakat atau tidak atas mereka. Namun sebagian besar ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya b. Harta Wajib Zakat Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek wajib zakat pun harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Harta milik penuh (al-milku at-tam), yakni bahwa pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat harta itu secara penuh. 2. Berkembang (an namaa), maksudnya harta tersebut dapat bertambah bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. 3. Cukup nisbah, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara. 4. Lebih dari kebutuhan pokok, yakni lebih dari kebutuhan minimal yang harus dipenuhi setiap hari seperti sandang, pangan dan papan. 5. Bebas dari hutang. Orang yang memiliki hutang yang besar dan mengurangi nilai nisbah kena zakat, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat. 6. Sudah satu tahun. Maksudnya kepemilikan harta tersebut sudah lewat dari 12 bulan Qomariyah. Masa satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan. 3. Macam-Macam Zakat 1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa, yang bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberik makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri. 2. Zakat Harta (al-maal), yakni zakat yang dikeluarkan karena telah diperolehnya suatu harta kekayaan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut lazimnya. Sesuatu dapat disebut harta (al-maal) jika memenuhi dua syarat, yaitu: 1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnyasesuai dengan lazimnya. Serta harta yang wajib dikeluarkan hartanya yaitu: 1. Hasil pertanian, 2. Harta terpendam, barang tambana dan kekayaan laut, 3. Emas dan perak, 4. Perniagaan dan perusahaan, 5. Binatang ternak, 6. Saham dan surat berharga, 7. Hadiah atau harta tidak terduga, dan 8. profesi4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang berhak menerima zakat mengatakan, Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At Taubah: 60) Dari surat diatas dapat kita jelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu: 1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sumber pendapatan yang jelas dan tidak mencukupi kebutuhan hidup minimalnya. 2. Miskin, ialah orang yang mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang jelas tetapi belum bias memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. 3. Rikab, yaitu orang yang keadaannya dapat dikategorikan sebagai budak, yakni orang yang secara ekonomis tertekan oleh lingkungannya seperti pembantu rumah tangga atau orang yang hidupnya menggantungkan diri kepada orang lain. 4. Gharimin, adalah orang yang tidak mampun melunasi hutangnya (pailit), atau kewajiban hutangnya lebih besar dari pada kekayaannya. 5. Sabilillah, ialah orang yang sedang melakukan kegiataan atau usaha dalam rangka menegakkan hukum Allah SWT, seperti penyelenggaraan pendidikan dan dakwah Islam. 6. Ibnu Sabil, adalah segala macam kegiatan atau usaha dalam rangka mendukung lancarnya suatu perjalanan, pembangunan fasilitas transportasi, pembangunan sarana jalan, jembatan, atau komunikasi untuk membuka daerah terpencil. 7. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, atau usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam terutama bagi orang muslim yang pengetahuan agamay masih kurang. 8. Amil, yakni orang atau organisasi berikut system administrasinya untuk mendukung lancarnya kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. 6. Hikmah Zakat Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kewajiban menunaikan zakat demikian tegas dan murlak, oleh karena di dalamnya terkandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Diantara hikmahnya adalah sebagai berikut: 1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, 2. Menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, 3. Pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kesejangan antara orang yang mempunyai limpahan harta dengan orang yang kekurangan hartanya. 7. Pengertian Pajak
Pajak adalah beban kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat didalam suatu negara, baik hal itu bersifat personal maupun kelompok. Yang kegunaannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara didalam pembangunannya. Peranan pajak dapat mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pajak adalah merupakan salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara. Pengeluaran pemerintah di dalam membiayai setiap kegiatannya yang digunakan untuk membengun bangsa didalamnya kontribusi yang didapat dari pajak. Batasan atau definisi dari pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri banyak macamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. P.J.A Andrian, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Berdasarkan definisi pajak di atas, unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1. 2. 3. 4. Pajak merupakan pungutan pemerintah Secara paksa berdasarkan Undang-Undang Sebagai penutup pengeluaran-pengeluaran umum Tanpa ada jasa (prestasi) timbal balik secara khusus.
Dari pengertian pajak diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan zakat, dan perbedaan itu adalah: 1. Unsur Paksaan Bagi seorang muslim yang hartanya telah memenuhi syarat zakat maka ia harus menunaikan kewajibannya yang diwakili oleh petugas zakat yaitu amil. Demikian halnya dengan orang yang sudah masuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Unsur Pengelola Asas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan olah sebuah lembaga yang menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. 3. Dari Sisi Tujuan Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Demikian pula dengan pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. 1. Sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam (muallaf). 2. Menambah pendapatan negara untuk proyek proyek yang berguna bagi umat.
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAMDalam pengertian secara natural, ekonomi membahas hubungan antara manusia dengan tanah dalam proses mempertahankan dan melanjutkan serta menikmati kehidupannya. Dalam pengertiaan secara modern, ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang langka dalam meemproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya kepada individu dan kelompok masyarakat. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Mengapa saat ini perkembangan pemikiran Ekonomi Islam, yang mana 6 abad yang lalu pernah menjadi kiblat pengetahuan dunia, kurang dikenal dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? Hal ini dikarenakan kajian pemikiran Ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi ilmu pengetahuan konvensional (Barat) sejak runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki. Akibatnya, perkembangan Ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600M kurang begitu dikenal masyarakat. 1. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai Rasul. Masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Al-Quran dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh khalifah dan pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran pada masa tersebut adalah sebagai berikut : 1.1.Perekonomian di Masa Rasulullah SAW (571-632 M) Pada masa Rosululloh SAW, tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh jadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Situasi berubah setelah turunnya Surat Al-Anfal (8) ayat 41 : Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Alloh, Rosul, Kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Alloh dan kepada yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rosululloh SAW biasanya membagi seperlima (khums) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk beliau dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang sedang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi diantara prajurit yang ikut perang, dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapat dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara shodaqoh fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul hasa berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. 1.1.1. Sumber Pendapatan Primer Pendapatan utama bagi negara pada masa Rosululloh SAW adalah zakat (memiliki karakteristik yang sama dengan pajak, tetapi secara dasar berorientasi pada agama ) dan ushr ( iuran untuk tanah produksi ). Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan Ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara jelas dalam Surat At-Taubah (9) ayat 60 : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orag fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Alloh dan orangorang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Alloh dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 1.1.2. Sumber Pendapatan Sekunder Diantara sumber-sumber pendapat sekunder yang memberikan hasil adalah : 1. Uang tebusan untuk para tawanan perang, hanya tidak disebutkan jumlah uang tebusannya 2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Mekkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham ( 20.000
dirham menurut Bukhari ) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah. 3. Khusmus atau Rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam 4. Amwal fadhla, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang orang muslim yang meninggalkan negerinya 5. Wakaf, harta benda yang diindikasikan kepada umat Islam yang disebabkan Alloh dan pendapatannya akan didepositokan ke Baitul Maal, 6. Nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk, 7. Zakat fitrah, zakat yang ditarik di bulan suci Ramadhan, dan dibagi sebelum sholat Ied, 8. Bentuk dan shodaqoh lainnya seperti kurban dan Kuffarat adalah dende atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, seperti berburu pada musim haji. Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rosululloh SAW tidak ada, karena beberapa alasan : 1. Jumlah orang Islam yang bisa membaca, menulis dan mengenal aritmatika sedikit 2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana baik yang didistribusikan maupun yang diterima 3. Sebagian besar dari zakat hanya didistribusikan secara lokal 4. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan 5. Pada kebanyakan kasus, ghanimah (harta yang didapatkan dari kemenangan perang) digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu 2. Perekonomian Di Masa Khulafaurrasyidin 2.1.Abu Bakar As-Sidiq (51 SH 13 H / 537 634 M) Setelah Abu Bakar pindah ke Madinah, dibangun baitul mal. Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah yang tegas untuk mengumpulkan zakat dari umat Islam. 2.2.Umar bin Khattab (40SH 23H / 584 644 M) Pada masa kekhalifahan Umar banyak dibangun saluran irigasi, waduk, tangki kanal, dan pintu air seba guna untuk mendistribusikan air di ladang pertanian. Hukum perdagangan juga mengalami penyempurnaan untuk menciptakan perekonomi secara sehat. Umar mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syiria sebesar 50% untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota. Pada saat yang sama juga dibangun pasar agar tercipta peradangan dengan persaingan yang bebas. Serta adanya pengawasan terhadap penekanan harga. Beliau juga sangat tegas dalam menangani masalah zakat. Umar menetapkan zakat atas harta dan bagi yang membangkang didenda sebesar 50% dari kekayaannya. Pada masa beliau dibangun Institusi Administrasi dan Baitul Mal yang reguler dan permanen di Ibu Kota dan mendirikan Baitul Mal cabang di ibu kota propinsi. Baitul Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan Diwan Islam yang disebut Al-Divan (kantor yang mengurusi pembayaran tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tujangan lainnya secara reguler dan tepat). Khalifah Umar juga membentuk komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. 2.3. Ustman bin Affan ( 47 SH 35H / 577 656 M ) Ustman membuat kebijakan di bidang keamanan perdagangan dengan membentukan organisasi kepolisian tetap dan mengurangi jumlah zakat dari pensiun. Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, ushr, kharaj, fay, dan ghanimah. Zakat ditetapkan 2,5% dari modal aset. Ushr ditetapkan 10% iuran tanah pertanian. Kharaj (iuran pajak pada daerah-daerah yang ditaklukan). Prosentase dari kharaj lebih tinggi dari ushr. Ghanimah yang didapatkan dibagi 4/5 kepada para prajurit yang ikut andil dalam perang sedangkan 1/5-nya disimpan sebagai kas negara. 2.4. Ali bin Abi Thalib ( 23H 40H / 600 661 M ) Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah , Busra, dan Kuffah. Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi umum dan masalah yang berkaitan dengannnya seperti mendiskripsikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab
penguasa, menyusun dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim dan abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administratif dan pengadaan bendahara. 3. Perkembangan Ekonomi Pasca Khulafaurrasyidin 3.1.Pendapatan Pemerintah Pendapatan pada masa pasca khulafaurrasyidun masih menggunakan sistem perpajakan yang dikenal dengan kharaj. Pajak ini ditetapkan atas tanah pertanian yang dibayar dalam bentuk uang. Besar kecilnya ditentukan oleh kesuburan dan luas lahan. 3.2.Mata Uang Pada masa permulaannya Muslim menggunakan emas dan perak dengan beratnya. Mata uang Islam dibuat pada masa Khalifah Abdullah Malik bin Marwan. Saat itu beliau memerintahkan untuk pembuatan dirham yang dicap dengan Allah adalah Satu, Allah adalah Abadi . Mata uang yang lain pada waktu itu berfungsi sebagai sarana pengumuman keabsahan pemerintahan pada waktu itu yang namanya terpatri di mata uang disebut sikkah. Dalam Islam dikenal dua jenis mata uang utama, yaitu dinar emas dan dirham perak. Selain kedua mata uang tersebut terdapat mata uang pecahan yang disebut maksur seperti qitha dan miqtal. Pada keempat hijrah dunia Islam mengalami krisis mata uang emas dan perak, maka kemudian dibuatlah mata uang dari tembaga yang dikenal dengan fulus. Nilai mata uang ditetapkan sendiri oleh Khalifah. Penetapan itu sendiri tidak lepas dari pertimbangan nilai riil masyarakat dan naik turunya nilai uang dari waktu ke waktu. 4. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pasca Khulafaurrasyidin Perkembangan pemikiran ekonomi pasca Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin dibagi menjadi 3 periode yang didasarkan atas nama tokoh ekonomi Islam tersebut hidup. 1. Ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M Tokohnya: Zaid bin Ali (738), Abu Hanifa (798), Ibnu Farabi (950), Ibnu Sina (1037), dll. 2. Ekonomi Islam periode kedua (1058-1446M) Tokoh: Al-Ghazali (1111), Ibnu Taimiyah (1328), Ibnu Khaldun (1040), Ibnu Rusyd (1198), dll 3. Ekonomi Islam periode ketiga (1446-1931 M) Tokoh: Jamaluddin Al-Afghani (1897), Muhammad Iqbal (1938), Syekh Ahmaad Sirhindi (1524), dll Berikut adalah beberapa kontribusi pemikiran Ekonom Islam diatas, terutama untuk periode awal yang menjadi tonggak ekonomi Islam, dan periode tengah yang merupakan periode puncak pemikiran ekonomi : 1. Zayd bin Ali (699 738) Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Beliau tidak memperbolehkan harga yang ditangguhkan pembayannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, sebagaimana halnya penambahan pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman. Setiap penambahan terhadap penundaan pembayaran adalah riba Prinsipnya jenis transakai barang atau jasa yang halal kalau didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan. Sebagaiman firman Alloh dalam surat An-Nisaa( 4) ayat 29 : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dia ntara kamu . 2. Abu Hanifa (80-150 H /699 767 M) Abu Hanifa mencetuskan salam (suatu bentuk transaksi diman antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati). Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan dengan jual beli. Abu Hanifah sangat memperhatikan pada orang-orang lemah. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen (muzaraah) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah tidak menghasilkan apapun. Hal ini untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. 3. Abu Yusuf (113 182H/731 798M) Kitab Al-Kharaj ditulis atas permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya yaitu produsen dan konsumen. Jika karena suatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi
karena kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penetuan harga sepenuhnya harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. 4. Al-Ghazali (450 505H/ 1058 1111M) Al-Ghazali mengatakan bahwa kebutuhan hidup manusia terdiri dari 3, yaitu kebutuhan dasar (darruriyah), kebutuhan sekunder (hajiat), dan kebutuhan mewah (takhsiniyyat). Teori hierarki kebutuhan ini kemudian diambil oleh William Nassau Senior yang menyatkan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar (necessity), sekunder (decency), dan kebutuhan tersier (luxury). Beliau juga menyatakan tentang tujuan utama dan penerapan syariah adalah masalah religi atau agama, kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi. Beliau juga memperkenalkan mengenai peranan uang dalam ekonomi (ditulis dalam kitab Ihya Ulum Din). Menurut beliau , manusia memerlukan uang sebagai alat perantara / pertukaran (medium exchange) untuk membeli barang. Fungsi ini kemudian dijabarkan kembali oleh Ibnu Taimiyah dengan menambahkan 1 fungsi tambahan, yakni bahwa uang juga berfungsi sebagai alat untuk menetukan nilai (measurement of value ) 5. Ibnu Rusyd (1198) Sebelumnya filsuf Yunani, Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, alat mengukur nilai dan sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Ibnu Rusyd menambahkan fungsi keempat dari uang, yakni sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen, yang menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli keperluan hidupnya. Ibnu Rusyd juga membantah Aristoteles tentang teori nilai uang dimana nilainya boleh berubahubah. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa uang itu tidak boleh berubah-ubah karena 2 alasan, yakni pertama uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka seperti Allah SWT Yang Maha Pengukur, Allah Tidak Berubah-Ubah, maka uangpun sebagai pengukur keadaan tidak boleh berubah. Kedua uang berfungsi sebagai cadangan untuk konsumsi masa depan, maka perubahan padanya sangatlah tidak adil. Dari kedua alasan tersebut maka sesungguhnya nilai nominal uang itu harus sama dengan nilai intrinsiknya. 6. Ibnu Taimiyah ( 661 728H / 1263 1328M) Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang lain : Sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi (khalq) suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik, sebaliknya jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun. Teori dikenal dengan price volality atau turun naiknya harga di pasar. Teori ini jika dikaji lebih mendalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran (supply dan demand) di pasar, yang kini justru secara ironi diakui sebagi teori yang bersal dari Barat. 7. Ibnu Khaldun (732 807H / 1332 1383M) Ibnu Khaldun adalah Bapak Ekonomi Dunia. Sumbangan terbesar dalam bidang Ekonomi banyak dimuat dalam karya besarnya, Al-Muqadimmah. Beberapa prinsip dan falsafah ekonomi telah difikirkannya, seperti keadilan (al-adl), hardworking, kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation), dan fairness. Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah tulang punggung dan asas kekuatan sebuah ekonomi. lain sehingga pada akhirnya menyebabkan disintegrasi dan kemunduran masyarakat. Manusia dan Ekonomi Teori ekonomi dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang manusia adalah berdasarkan pada prinsipprinsip dan falsafah Islam, tidak hanya melihat fungsi manusia dalam aktifitas perekonomian sebagai hewan ekonomi (economic animal), sebaliknyanya beliau mengungkapkan bahwa manusia yang sebenarnya adalah manusia Islam (Islamic Man / homoislamicus) yang memerlukan Ilmu pengetahuan (sumber yang didapatkan dari Alloh SWT melalui pengamatan dan observasi) ekonomi untuk memenuhi misinya di muka bumi. Teori Produksi Ibnu Khaldun mengemukakan suatu teori bahwa kehidupan ekonomi selalu mengarah pada pelaksanaan keseimbangan (equilibrium) antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau produksi berdasarkan pada faktor tenaga kerja (buruh) dan kerjasama dari masyarakat. Beliau menganggap tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi walaupun faktor lain seperti bahan baku diperlukan, tenaga buruh diperlukan untuk menghasilkan produksi akhir.
Teori Nilai, Uang, dan Harga Meskipun Ibnu Khaldun tidak secara jelas membedakan antara teori nilai guna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value), tetapi secara tegas beliau mengatakan bahwa nilai suatu barang tergantung pada nilai tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Beliau mengatakan, Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh. Mengenai Uang beliau berpendapat bahwa banyaknya uang tidaklah menetukan kekayaan suatu negara, tetapi ditentukan oleh banyaknya produksi negara tersebut dan neraca pembayarn yang positif. Pada bagian lain, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik turunya penawaran terhadap harga. Beliau mengatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila arak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, mak akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang melimpah dan harga-harga akan turun. 5. Perkembangan Pemikiran Islam ke Barat Mulai abad 9 muncul banyak tokoh Islam yang mempengaruhi pemikiran dan kehidupan mayarakat Barat, seperti Biruni, Firdawsi, Ibnu Sina, Nasisirn, Khuswraw, Nizamul Mulk, Al-Ghazali, Omar Khayyam, dan lin sebagainya. Pengaruh pemikiran Islam terhadap masyarakat barat dipengaruhi du fakta yang menonjol : 1. Para cendikiawan tersebut menerima dorongan terbesar dari warisan ilmu pengetahuan dan filsafat Greco-Helenistik 2. Islam menerima warisan tersebut dan mengajarkan di dalam sekolah-sekolah perguruan tinggi, pusat penelitian, dan perpustakaan-perpustakaan Sedangkan beberapa bentuk pengelola ekonomi barat yang sama digunakan Islam adalah : 1. Syirkat ( partnership ) 2. Suftaja ( bill of exchange ) 3. Hawal ( letters of credit ) 4. Funduq ( specialized large scale commercial institutions and market which development developed in to virtual stock exchange ) 5. Dur-ul tiraz ( pabrik yang dijalankan oleh negara ) 6. Mauna ( private bank ) 7. Wilatil hisba( polisi ekonomi )
PENGANTAR EKONOMI ISLAMRANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak dapat dikompromikan karena dasar keduanya sangat berbeda (ekonomi Islam berorientasi dimensi akherat dan dimensi dunia sedangkan ekonomi konvensional berorientasi sekuler atau tidak memasukkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya). Dalam paradigmanya ekonomi Islam sampai saat ini pemikiran ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi:a. Mazhab Baqir as-sadr Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as sadr dalam bukunya Iqtishoduna yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah berjalan bersandingan dengan islam, ekonomi tetap ekonomi dan islam tetap islam. Hal itu dikarenakan keduanya berasal dari filosofi yang berbeda. b. Mazhab mainstream Mazhab ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang terbatas dan dihadapkan keinginan yang tak terbatas. Tokoh mazhab ini adalah Umer Chapra, M Nejatullah Siddiqi, dan MA Mannan. c. Mazhab alternatif kritis Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Untuk mazhab baqir dikritik sebaai mazhab yang berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ada sebelumnya dengan menghancurkan teori lama kemudian mengantikannya dengan teori baru. Untuk mazhab mainstream
dikritik sebagai penjiplak ekonomi neoklasik dengan meninggalkan variabelriba dan memasukkan variable niat dan zakat.
Kerangka ekonomi islam
akhlaq
Multiple ownershi p
Freedo m to act
Social justice Prinsip sistem ekonomi islam
tauhid
ad l
nubuwwah
khilafah
Maad
Teori ekonomi islam
Bangunan ekonomi islam didasarkan atas 5 nilai universal yakni tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan maad (hasil).
Prinsip Ekonomi Syariah 1. Keadilan, persamaan, dan solidaritas Usaha yang bertentangan dengan keadilan, persamaan dan solidaritas adalah bukan berdasarkan syariah 2. Berdasarkan halal dan haram Transaksi yang jelas halal dan haramnya baik dari segi objek, cara mendapatkan, dan jasa yang ditawarkan. 3. Menghargai kepemilikan (property right) Kepemilikan dalam Islam dapat dipindahtangankan melalui: a. Kombinasi kemampuan seseorang (human capital) dengan sumberdaya lain (natural capital, man made capital) b. Pada transaksi barang ribawi dan non ribawi diperbolehkan c. Kepemilikan juga bisa dipindahkan karena hadiah (voluntary gift) 4. Kekayaan harus digunakan dalam pilihan yang rasional dan jalan yang adil Islam menolak pilihan penggunaan kekayaan yang kontra produktif dan menimbulkan kemubaziran (inefficient) pada alokasi sumber daya (Karim, Adiwarman Azwar.2001). dalam Islam kekayaan merupakan titipan Allah dan tidak dibenarkan menggunaakannya untuk menggangu ketertiban social (kepentingan public). 5. Tidak ada keuntungan tanpa usaha (effort) dan kewajiban (liability) Menerima keuntungan secara financial (bunga)tanpa memberikan imbalan balik dilarang. Islam tidak melarang untuk mendaapatkan laba (profit) selama:
a. Ada usaha yang dikerjakan atau kewajiban yang diterima sebagai hasil kerjasama. b. Usaha atau kewajiban adalah sesuatu yang produktif dabn bertujuan meningkatkan nilai. c. Keuntungan yang dibuat dari sikap jujur dan sesuai garis syariah. 6. Kondisi umum dari pembiayaan Debitor dalam pembiayaan syariah tidak diperkenankan diperlakukan secara kaku. Jika ia tidak dapat membayar kepada principal (LKS) maka ia diberi penangguhan tanpa ada hukuman (dalam konvensional = bunga). 7. Konsep dual dari resiko Dalam pandangan Islam konsepsi risiko memiliki 2 makna (Van Scaik, Diedriek.2001). a. Sebagian kewajiban diterima sebagai konsekuensi dari kerjasama untuk mendapatkan laba. b. Risiko harus diperlakukan secara hati-hati.
MIKRO SYARIAH Perilaku Konsumen Dibangun atas dasar syariat Islam. Tujuan konsumsi adalah sukses dunia akhirat ( falah ) sedangkan motifnya adalah maslahat( public interest or general human good )kebutuhan dan kewajiban. Maslahat secara bahasa berarti ketergunaan ( utility ) atau kesejahteraan (welfare ) yang oleh Abu Hamid Al Ghazali (505H/1111M) dan Abu Ishaq Al Shatibi ( 790H/1388M) masalih (plural of mashlahah dibagi menjdai 3 kategori : esensial, pelengkap, dan keinginan. Dan negaralah yang memastikan kemaslahatan kategori pertama dari masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Prinsip-prinsip konsumsi ( Mannan, 1993, bab 4) 1. Keadilan 2. kebersihan 3. kesederhanaan 4. Kemurahan hati 5. Moralitas Asumsi asumsi menurut Monzef Kahf : 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat 2. Zakat hukumnya wajib 3. Tidak ada riba dalam perekonomian 4. Mudharabah merupakan wujud perekonomian 5. Perilaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan utilitas Monzer Kahf (1992) memperkenalkan FS ( final spending ). Formulanya : FS = ( Y- S ) + ( S SZ ) FS = Final spending FS = ( Y sY ) + ( sY zsY Y = Pendapatan ) S = Total tabungan FS = Y ( 1-zs ) s = presentase Y yang hilang Sehingga didapat memaksimumkan kepuasan : z = presentase zakat Max U = U ( FS, s ) Karena seorang muslim percaya adanya hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat maka akan berdampak terhadap perilaku konsumsi : 1. Hasil pilihan dari setiap tidakan terdiri dari 2 bagian, yaitu dampak langsung terhdapa kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu utilitas yang diturukan dari pilihan ini adalah total nilai sekarang ( persent valuie ) dari kedua dampak tadi 2. Jumlah alternative penggunaan pendapatan akan meningkat dengan dimasukkannya manfaat yang akan diperoleh di akhirat. Jadi jelas banya alternative penggunaan pandapatan yang mungkin mempunyai utilitas positif dalam Islam, meskipun dalam perspektif kapitalis maupun sosilais bisa nol atau negative
Dalam perspektif Islam anatar utilitas dan manfaat mempunyai perbedaan. Konsep utilitas bersifat subjektif karena bertolak dari pemenuhan want ( keinginan ), sedangkan konsep manfaat relative lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan need ( kebutuhan ) Dalam perspektif Islam antara benda satu dengan yang lain bukan merupakan subsitusi sempurna, terdapat benda ekonomi yang lebih berharga sehingga akan diutamakan disbanding dengan pilihan konsumsi yang lain, sebaliknya ada benda ekonomi yang kurang berharga bahkan terlarang sehingga perlu dijauhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar menurut pandangan Islam ( pandapat Al-Ghazali ) ,yaitu : 1. Kebenaran 2. kehidupan 3. Harta material 4. Ilmu pengetahuan 5. Kelangsungan keturunan Dengan demikian preferensi konsumsi dan pemenuhannnya akan memiliki pola sebagai berikut : 1. Mengutamakan akhirat daripada dunia Pada tataran paling dasar seorang muslim akan dihadapkan pada pilihan antara mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka ( worldly consumption, Cw ) dan yang bersifat ibadah ( ibadah consumption, Ci ). Konsumsi untuk ibadah bernilai tinggi daripada konsumsi untuk duniawai sehingga keduanya bukan subtitusi sempurna. Hubungan antara falah dengan kedua jenis konsumsi dapat digambarkan dalam grafik : a) Hubungan antara falah dengan konsumsi untuk kebutuhan ibadah F
C1 Terdapat hubungan positif antara pencapaian tujuan falah dengan kebutuhan konsumsi ibadah Semakin tinggi tujuan falah yang ingin dicapai, semakin dituntut untuk memperbesar konsumsi kebutuhan ibadah b) Hubungan antara falah dengan Konsumsi untuk kebutuhan duniawi F
Terdapat hubungan negative antara pencapaian tujuan falah dengan kebutuhan konsumsi duniawi Semakin tinggi tuijuan falah yang ingin dicapai, semakin dituntut untuk mengurangi konsumsi kebutuhan duniawi. C1 Seorang muslim yang rasional akan mengalokasikan anggaran lebih banyak dalam konsumsi untuk ibadah untuk memaksinalisasi falah, sebaliknya semakin tidak rasional ( semakin kufur )
akan semakin besar anggaran untuk duniawi. Meskipun demikian, konsumsi dalam ukuran wajar boleh dilakukan. Pola alokasi anggara ini dapat disajikan dalam grafik : C1 C1 (a) Semakin rasional (beriman) seorang muslim maka budget linenya akan semakin condong vertical (inelastic ) (b) Semakin tidak rasional (kufur ) seorang muslim maka budged line akan semakin condong horizontal Cw Cw
2. Konsistensi dalam prioritas pemenuhannya Kebutuhan manusia dalam konsumsi memiliki tingkat urgensi yang berbeda. Para ulama membagi prioritas konsumsi menjadi 3 ( Mannan, 1993 ; p. 48 ) : a. Kebutuhan darurat ( al hajat adh dharuriyah ) Kebutuhan yang harus dipenuhi segera, jika diabaikan akan menimbulkan resiko yang membahayakan eksistensi manusia b. Kebutuhan pelengkap ( al haajat al hajjiyah ) Kebutuhan yang ada jika dipenuhi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah ( added value ) misalnya makan dengan cukup dengan kualitas gizi yang lengkap c. kebutuhan kemewahan ( al haajat al tahsiniyyah ) Kebutuhan yang jika dipenuhi akan meningkatkan kepuasan atau kenikmatan, meskipun tidak menambah efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah, misal : makan dengan selera/cita rasa/merk sesuai dengan keinginan. 3. Memperhatikan etika dan norma Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dipegang seseorang yang melakukan konsusmi. Norma dan etika Islam dalam konsumsi dirangkum dalam berbagai hal pokok (Qhardawi, 1997: bab 2, Thahir, et.al, 1992: bab 2 - 8 ) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menajuhi sifat kikir Bersifat sederhana Perbedaan yang cukup jelas antara antara perilaku konsumsi Islam dan konvensional adalah terlatak pada motif konsumsi dan batasan-batasan hukum yang ada dalam sistem ekonomi.Teori Produksi Islami Produksi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) suatu barang.
Motif produksi dalam Islam yaitu kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Perilaku produksi pada dasarnya merupakan usaha seseorang atau beberapa orang untuk lepas dari kefakiran. Disamping itu, menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan membangun kemandirian ummat. Menurut Kahf (1992;p. 114) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai usaha manusi untuk memperbaii tidak hanya kondisi fisik material, tetapi juga moralitas, sebagiai saran untuk mencapai tujuan hidup sebagaiman digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian seperti diatas akan membawa implikasi bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa implikasi mendasar adalah : 1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan niali moral dan teknikal yang Islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi 2. Kegiatan produksi harus mempehatikan aspek social kemasyarakatan
3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (scarcity) saja, tetapi lebih komplek Asumsi-asumsi (M.M Metwally,1992) 1. Produksi untuk barang halal 2. Proses manajemen halal 3. Tidal melakukan strategi pemasaran atau distribusi yang memberi kemudaratan kepada umat Secara lebih spesifik Siddiqi (1972, hal 11-34) telah menyebutkan beberapa tujuan produksi adalah 1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat 2. Menemukan kebutuhan masyarakat 3. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan dating 4. Persediaan bagi generasi mendatang 5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan ibadah kepada AllohTujuan Produksi: Maksimisasi maslahah dengan mengenakan cara berproduksi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam
Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altrustik sehingga produsen tidak hanya dapat mngejar keuntungan maksimal saja. Produsen harus mengejar tujuan akhirat. Konsekuensi altruistic maka konsep pareto optimality dan given demand hypothesis tidak hanya diterima begitu saja. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (altrustic consideration) perilaku produsen tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar ( given demand condisition) karena kurva permintaan pasar tidak cukup memberikan data untuk sebuah perusahan untuk mengambil keputusan. Sifat altruistic bukanlah sifat yang ekstrim tetapi terikat oleh nilai-nilai AlQuran dan AlHadist. Konsekuensi altruistic dalam produksi ini maka terdapat 2 konsep ekonomi konvensioanl yang perlu mendapat perhatian : 1. Pareto Optimally Kriteria pareto adalah efisiensi alokasi akan terjadi bila tidak mungkin bagi dilkukan reorganisasi produksi sedemikian rupa rupa sehingga masing-masing pihak (konsumen dan produsen) merasa lebih sejahtera (better off). Oleh karena itu pada keadaan efisiensi alokatif utility orang lain. Secara teorirtis criteria efisiensi pareto mengabaikan masalah distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam kondisi ini pareto optimally hanya menujukkan bahwa kesejahteraan yang dimiliki orang yang kaya lebih tinggi daripada orang miskin, padahal ajaran Islam memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
A
Batas kemungkinan utilitas
B C
Efisiensi Alokatif Vs Keadlian Alokatif Hasil perekonomian disebut efisien jika tidak ada orang yang bisa lebih sejahtera tanpa merugikan orang lain. Hal ini biasa digambarkan dedengan garis kemungkinan utilitas disamping menggambarkan kemungkinan efisiensi tertinggi. Yang dapat dicapai, sementara titik B bukan posisi efisiensi yang tertinggi. Bergerak dari titik A ke C akan mempengaruhi kenaikan kepuasan orang kedua (U2), tetapi mengurangi kepuasan orang pertama (U1). 2. Given Demand Hypothesis
Karena keterikatannya pada nilai-nilai keislaman dan sifat altrustiknya maka produsen tidak harus merespon segala permintaan konsumen (given demand condition ) Karena belum tentu demand condition sejalan dengan tujuan produksio yang islami. Secara lebih spesifik Siddiqi (1992) menyebut 3 prinsip pokok produsen, yaitu : 1. Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan 2. Memliki mdorangan untuk melayani masyarakat 3. Optimasi keuntungan diperkenankan batasan kedua prinsip di atasIbnu Khaldun mengemukakan suatu teori bahwa kehidupan ekonomi selalu mengarah pada pelaksanaan keseimbangan (equilibrium) antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau produksi berdasarkan pada faktor tenaga kerja (buruh) dan kerjasama dari masyarakat. Beliau menganggap tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi walaupun faktor lain seperti bahan baku diperlukan, tenaga buruh diperlukan untuk menghasilkan produksi akhir. Pada ekonomi konvensional modal mendapat perhatian dalam analisa perilaku produksi dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Karena pada ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga. Sedangkan dalam Islam tidak menerapkan sistem bunga. Persamaan fungsi produksi dalam ekonomi Islam dapat diformulasikan sebagai berikut: Y = (Q.R)v.W
Q:Nisbah bagi hasil R : Rate of return dari bisnis V : Rate of saving utilitation W: Wealth Aktivitas produksi Islam menekankan pentingnya sikap produktif yaitu berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin semua potensi yang dimiliki sebagaimana firman Allah SWT Demi masa(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian(2), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran(3). (QS al-Ashr, 103: 13) MAKRO SYARIAH
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dalam negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok agama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kegiatan yang menambah pengeluaran dan menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah SAW adalah zakat dan ushr. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Seperti tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Rasulullah SAW berkata pada Muadz ketika beliau mengirim nya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka. Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang
KEBIJAKAN FISKAL
tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibukota negara. Dalam negara Islam, dasar anggaran bukan semata-mata penerimaan yang akan menentukan pengeluaran. Pengeluaranlah yang harus menjadi dasar utama untuk mengerahkan penghasilan. Hal ini berdasarkan persyaratan Islam bahwa suatu negara harus menyediakan kebutuhan minimum pokok bagi semua warganya. Karena itu bila penghasilan zakat memenuhi persediaan pokok bagi si miskin, selalu terdapat kemungkinan lain untuk perpajakan tambahan di luar zakat, asal saja digunakan dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, dalam suatu ekonomi Islam pembiayaaan defisit dapat dilakukan. Hal ini dapat diatur melalui perjanjian mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Di samping itu, suatu pemerintahan Islam juga dapat menghimpun dana dengan mengeluarkan obligasi dan sertifikat investasi kepada umum atas dasar pembagian laba dan rugi. KONSEP DAN FUNGSI UANG 1. KONSEP UANG Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan capital. Sementara itu, dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak jelas. Misalnya, dalam buku Money, Interest, and Capital (1989) oleh Colin Rogers, uang diartikan bertukaran (interchangeability), sebagai uang atau sebagai capital. Ketidak jelasan dalam konsep ini bisa menimbulkan kekacauan. Perbedaan lainnya, menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept, sedangkan capital bersifat stock concept. Dalam ekonomi konvensional, terdapat beberapa pengertian. Frederick Mishkin dalam bukunya Economics of Money, Banking, and Financial Institution, mengungkapkan konsep Irving Fisher: MV = PT, dimana M adalah jumlah uang, V adalah tingkat perputaran uang, P adalah tingkat harga barang, dan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Persamaan tersebut menunjukkan semakin cepat perputaran uang, semakin besar pendapatan. Menegaskan pula bahwa uang adalah flow concept. Fisher mengatakan bahwa, sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (demand for holding money) dengan tingkat suku bunga. Menurut konsep ekonomi Islam, capital is private goods, sedangkan money is public goods. Uang yang mengalir adalah public goods (flow concept), sedangkan yang mengendap sebagai milik seseorang (stock concept) adalah milik pribadi (private goods). Dengan demikian, jika dan hanya jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, kita akan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional, mereka tetap menginginkan keuntungan tanpa memperdulikan apakah uang itu diinvestasikan pada proses produksi atau tidak. 2. FUNGSI UANG Fungsi uang berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, dikenal 3 fungsi uang, yaitu: alat pertukaran (medium of exchange), satuan nilai (unit of account), dan penyimpan nilai (store of value). Dalam ekonomi Islam hanya mengenal uang dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (medium of exchange), yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsi lainnya adalah sebagai satuan nilai (unit of account). Teori konvensional juga memasukkan alat penyimpan nilai (store of value) sebagai salah satu fungsi uang, termasuk motif money demand for speculation. Tapi, hal ini tidak boleh dalam Islam, Islam hanya memperbolehakan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Sama sekali menolak untuk spekulasi. TIME VALUE OF MONEY Vs ECONOMIC VALUE OF TIME Teori keuangan konvensional mendasarkan argumen bunganya dengan konsep time value of money. Teori ini merupakan kekeliruan, karena diambil dari ilmu teori pertumbuhan penduduk (populasi), bukan dari ilmu keuangan. Hal ini keliru, karena uang bukan makhluk
hidup yang dapat berkembang dengan sendirinya. Validitas teori ini akan dibantah dengan konsep yang lebih tepat, yaitu economic value of time. Kuantitas waktu sama bagi semua orang. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Faktor yang menentukan nilai dari waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi waktunya. Efektif dan akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya, secara sunnatullah akan mendapat keuntungan di dunia. Dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, tapi juga harus didasari dengan keimanan. Dalam ekonomi konvensional time value of money didefinisikan sebagai berikut: a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat positive, negative, atau no return. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu disebut risk-return relationship. Menurut ekonom konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yakni: presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. Alasan pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, maka deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Tapi, hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh konsep time value of money, yaitu pada kondisi inflasi dan mengabaikan kondisi deflasi. Ekonomi syariah menolak keadaan yang disebut al ghunmu bi la ghurmi (gaining return without responsible for any risk) dan al-kharaj bi la dhaman (gaining income without responsible for any expenses). Keadaan yang juga ditolak oleh teori ilmu keuangan berdasarkan prinsip return goes along with risk. KEBIJAKAN MONETER Sistem moneter, sepanjang zaman, mengalami banyak perkembangan. Pada zaman Rasulullah sistem ini menggunakan bimetallic standard, dengan emas dan perak (dalam bentuk dinar dan dirham) sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak, pada masa ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar-dirham 1:10. namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah terganggu karena disekuilibrium antara persediaan dan penawaran. Instabilitas dalam nilai tukar uang ini mengakibatkan terjadinya bad coins to drive good coins out of circulations atau uang buruk menggantikan uang berkualitas baik. Dalam literature konvensional, peristiwa yang disebut hukum Gresham ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Bani Mamluk (1263-1328 M). Saat itu, uang logam dari jenis fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Oleh Ibnu Taimiyah, kondisi ini digambarkan sebagai uang berkualitas rendah menendang keluar uang berkualitas baik. Perkembangan emas sebagai standar peredaran uang mengalami tiga kali evolusi, yaitu: the gold coin standard, the gold bullion standard, dan the gold exchange standard. Pada dasarnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelu serta mendesak dan tidak perlu serta kurang bermanfaat. Komponen pertama dapat dimasukkan sebagai permintaan akan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif, sedang jenis kedua meliputi konsumsi yang berlebihan (conspicuous consumption), investasi yang tidak produktif, dan investasi untuk spekulasi. Para ekonom muslim mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yaitu: nilai-nilai moral, lembaga-lembaga sosialekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga, dan tingkat keuntungan riil sebagai pengganti keberadaan suku bunga. Dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan akan uang dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Dengan demikian, setiap instrumen yang mengarah kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana secara tidak produktif akan ditinggalkan. Penghapusan suku
bunga, penetapan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, serta penghilangan insentif bagi pemegang uang idle mendorong orang melakukan: qard (meminjamkan harta kepada orang lain), penjualan muajjal, dan mudharabah.
AKUNTANSI SYARIAH Pendahuluan Akuntansi merupakan bahasa atau alat komunikasi yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan. Menurut AICPA (American Institute of Certified Accounting), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Pengertian akuntansi menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan (tanya jawab) berdasar syarat-syarat yang telah disepakati, dan selanjutnya penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindak tanduk dan pekerjaan, baik yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Oleh karena itu, muhasabah dalam Islam mempunyai dua arti, perhitungan dan pembukuan keuangan. A. SEJARAH AKUNTANSI SYARIAHBangsa arab telah lama menaruh perhatian yang besar terhadap praktek akuntansi. Hal ini bisa terlihat dari usaha tiap pedagang arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam hal keuangan seperti keuntungan dan kerugian. Seperti dalam firman Allah SWT : karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan pans. Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Kabah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. (QS. Al Quraisy : ) Setelah Islam muncul di semenanjung arab dibawah kepeminpinan Rasulullah, serta berdirinya Daulah Islamiyah di Madinahh, dimulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan monopoli, dan segala bentuk usaha pengambialihan harta orang lain dengan jalan batil. Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan fungsi pencatatan transaksi, dasar, dan manfaat pencatatan: Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya Istilah Akuntansi Syariah sendiri sebenarnya baru diwacanakan pada tahun 1995, berawal dari sebuah disertasi di University of Wollongong, Australia yang berjudul Shariate Organization and Accounting: The Reflection of Selfs Faith and Knowledge. B. PERBEDAAN AKUNTANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL Akuntansi Konvensional dikembangkan oleh ideologi barat, yang berasaskan kapitalisme dan liberalisme. Sedang Akuntansi Syariah tumbuh berkembang berdasarkan ideologi timur, yang tentunya berdasar sayariah Islam. Menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut: a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.
c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagi sumber harga atau nilai. d. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. C. STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DAN PENYUSUNANNYA Sejauh ini dunia internasional terdapat Lembaga yang menyusun standar akuntansi (dalam hal ini lebih pada perbankan), AAOIFI (Accounting for Islamic Financial Institution) yang terpusat di Manama. Di Indonesia sendiri terdapat IAI yang saat ini telah menebitkan Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam SAK terdapat Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No 56 yang mengatur tentang Akuntansi perbankan Syariah serta : a. PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah b. PSAK No 102 tentang Akuntansi Murabahah c. PSAK No 103 tentang Akuntansi Salam d. PSAK No 104 tentang Akuntansi Istishna e. PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudharabah f. PSAK No 106 tentang Akuntansi Musyarakah D. PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah AsySyuara ayat 181-184 yang berbunyi: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut tabayyun sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah AlHujuraat ayat 6 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa ayat 35 yang berbunyi: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kespakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut. Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada halhal sebagai berikut: 1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi; 2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; 3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal; 4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang; 5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya); 6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan; 7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan E. HARTA DAN MODAL 1. Harta Akuntansi umumnya menyangkut masalah kekayaan atau harta. Menurut Al Quran, harta itu pada hakikatnya milik Allah SWT. Seperti pada firman-Nya ; sesunggungnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi.. (QS. Yusuf : 55) Harta adalah milik Allah dan berilah kepada mereka yang membutuhkan harta yang diberikan kepadamu (QS. An Nur : 33) 2. Modal dalam Perspektif Islam Modal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut capital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital dan circulating capital. Fixed capital seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik,; yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang eksistensi substansinya. Adapun circulating capital seperti: bahan baku dan uang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Perbedaan keduanya dalam syariah dapat kita lihat sebagai berikut. - Modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh). - Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik, substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Return on Capital Dari uraian di atas nyatalah bahwa barang modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan, atau kapal akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah sewa jika transaksi yang dipergunakan adalah ijarah. Di samping itu barang-barang modal ini dapat juga mendapatkan return on capital dalam bentuk bagian dari laba (profit) jika transaksi yang dipergunakan adalah musyarakah atas dasar kaidah suatu barang yang dapat disewakan, maka barang tersebut dapat dilakukan musyarakah atasnya. Ini telah dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman dulu misalnya dalam transaksi muzara. Dalam akad ini si empunya tanah menyediakan tanah untuk digarap oleh penggarap. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, misalnya 50:50. F. LABA Dalam bahasa arab laba (ribh) dikaitkan dengan aktivitas perdagangan sehingga ia sering diartikan sebagai pertumbuhan dalam dagang, seperti terdapat dalam kitab Lisanul Arab karangan Abu Mandzur. Laba juga merupakan bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa maupun Al-Quran, yaitu pertumbuhan (kelebihan) dari modal pokok. Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya di kalangan mitra usaha. Konsep Laba/Rugi
1. Arti Laba Secara Bahasa Dalam bahasa Arab, laba berrti pertumbuhan dalm dagang, seperti terdapat dalam kitab Lisanul-Arab karangna Ibnu manzur: yaitu pertumbuhan dalam dagang. 2. Arti Laba dalam Islam
Di dalam surah al-Baqarah, Allah ber