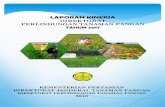bahan wereng
-
Upload
mohammad-iqbal -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of bahan wereng

Pendahuluan
Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal)adalah salah satu hama utama tanaman padi di
Indonesia. Berdasarkan catatan yang ada wereng coklat diketahui sudah menyerang tanaman
padi sejak tahun 1931 pada lahan sawah di daerah Dramaga Bogor. Serangan wereng coklat
secara luas terjadi pada tahun 1976/1977, dimana hampir seluruh wilayah Indonesia
dilaporkan terjadi serangan hama ini. Selanjutnya dilaporkan pada tahun 1982/1983 terjadi
lagi ledakan wereng coklat disertai dengan munculnya wereng coklat biotipe 3 dan biotipe
Sumatra Utara.
Di Jawa Barat ledakan serangan wereng coklat terjadi di Jalur Pantura pada tahun 1998 dan
pada tahun 2005, kemudian menyerang pertanaman padi di Kabupaten Cirebon pada awal
bulan Juli 2005, sedangkan serangan terkini terjadi pada musim hujan 2009/2010. Demikian
pula para petani dan petugas pertanian tanaman pangan di kabupaten Subang, Karawang dan
Indramayu kembali dikejutkan oleh eksplosi serangan hama wereng coklat pada pertanaman
padi sawah musim hujan 2009/2010. Serangan wereng coklat yang terjadi di Kabupaten
Subang, Karawang dan Indramayu menyerang pada semua varietas padi yang ditanam
termasuk Varietas Ciherang, dengan tingkat kerusakan berkisar dari ringan sampai dengan
berat, bahkan puso.
Serangan wereng coklat sangat berpotensi mengganggu kestabilan produksi padi. Provinsi
Jawa Barat merupakan salah satu pemasok padi terbesar secara nasional. Dengan demikian
serangan wereng coklat dikhawatirkan dapat mengganggu program ketahanan pangan
utamanya dalam hal ketersediaan beras di Jawa Barat. Olehckarena itu perlu dilakukan
tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya serangan wereng coklat yang lebih luas.
Wereng coklat merupakan hama tanaman padi yang paling berbahaya dibandingkan dengan
hama lainnya. Hal itu disebabkan wereng coklat mempunyai sifat plastis, yaitu mudah
beradaptasi pada keadaan atau kondisi lingkungan baru. Disamping itu wereng coklat juga
merupakan vektor (penular) virus penyakit kerdil rumput (grassy stunt) dan kerdil hampa
(ragged stunt). Di Indonesia Wereng Coklat tersebar luas hampir di seluruh kepulauan,
kecuali di daerah Maluku dan Papua.

Lingkungan tumbuh dan morfologi padi
Padi membutuhkan curah hujan pertahun + 200 mm/bulan, dengan distribusi selama empat
bulan atau 1.500–2.000 mm. Padi dapat tumbuh baik pada suhu di atas 23oC. Pada ketinggian
0– 65 m dpl, dengan suhu 26,5–22,5 oC. Tanaman padi memerlukan sinar matahari untuk
proses fotosintesis, terutama pada saat berbunga sampai proses pemasakan. Pada tekstur
tanah membutuhkan adanya lumpur, tumbuh baik pada tanah dengan ketebalan atasnya antara
18–22 cm, terutama tanah muda pH 4–7 (Prihatman, 2000).
Padi dapat tumbuh dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Di Indonesia kebanyakan
padi padi sawah (85–90%), sedangkan sebagian kecil lainnya (10–15%) diusahakan sebagai
padi gogo (Taslim dkk, 1988). Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 fase yaitu fase vegetatif,
fase reproduktif dan fase pemasakan. Fase vegetatif meliputi pertumbuhan tanaman mulai
saat berkecambah sampai inisiasi primordial malai. Pada fase reproduktif dimulai dari inisiasi
primordia malai sampai tanaman berbunga dan fase pemasakan dimulai dari masa berbunga
sampai masak panen. (Yoshida, 1981).
Perkembangan Populasi Wereng Coklat
Pada tahap permulaan wereng datang pada pertanaman padi yang sudah mulai tumbuh yaitu
pada umur 15 hari setelah tanam atau pada umur 10-20 hari setelah tanam. Di daerah beriklim
sedang, pada awalnya populasi wereng coklat rendah, kemudian berkembang dengan cepat.
Perkembangan populasi wereng juga tergantung pada inangnya (varietas) padi yang cocok
untuk
perkembangannya. Dilapangan wereng coklat bergerak dari tanaman satu ke tanaman
lainnya. Pergerakan dilakukan oleh wereng makroptera. Gerakan penyebaran ini
menunjukkan adanya wereng coklat yang meninggalkan tanaman tua atau menyebar pada
akhir generasi ke-3 menuju tanaman muda. Sebenarnya wereng coklat sudah mulai menyebar
pada generasi ke-2 dan mencapai puncaknya padagenerasi ke-3.
Vektor Penyakit Kerdil Rumput dan Kerdil Hampa
Wereng coklat juga berperan sebagai vektor (penular) penyakit kerdil rumput (grassy stunt)
dan kerdil hampa (ragged stunt). Oleh karena itu serangan wereng coklat biasanya diikuti
dengan serangan penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa yang dapat menimbulkan kerugian
pada tanaman padi. Kerdil Rumput Tanaman yang terinfeksi berat pada penyakit kerdil
rumput akan menjadi kerdil dengan anakan yang berlebihan, sehingga tampak seperti rumput.
Daun tanaman padi menjadi sempit, pendek, kaku, berwarna hijau kekuningan dan penuh

dengan bercak coklat seperti karat. Stadia pertumbuhan tanaman yang paling rentan (peka)
adalah pada saat tanaman muda berumur sekitar 2 minggu setelah tanam sampai 17 fase
primordia umur 40-50 hst). Penyakit kerdil rumput disebabkan oleh virus (rice grassy stunt
virus/RGSV) berbentuk seperti benang lentur, berdiameter 6 - 20 nm dan panjangnya 900-
1350 nm. Hubungan virus dengan vektornya adalah secara persisten. Periode makan akuisisi
terpendek 30 menit dan periode laten dalam serangga 5 sampai 28 hari, rata-rata 10,6 hari.
Periode inkubasi dalam tanaman 10 sampai 19 hari. Kebanyakan serangga yang infektif tetap
infektif sampai mati, beberapa dapat mempertahankan infektivitasnya hanya untuk
beberapa hari atau menjadi tidak infektif dalam sisa hidupnya. Periode retensi yang
terpanjang adalah 40 hari. Virus ini masih dapat ditularkan setelah serangga ganti kulit
(transtadial), tetapi tidak dapat ditularkan melalui telurnya (tidak transovarial). Lama hidup
rata-rata wereng coklat yang mengandung virus (16,1 hari), lebih pendek bila dibandingkan
dengan serangga yang bebas virus (20,4 hari).
Gambar 10. Gejala serangan kerdil rumput
Kerdil Hampa
Tanaman yang sakit kerdil hampa akan tumbuh menjadi kerdil. Gejala lain bervariasi
tergantung pada fase pertumbuhan tanaman. Pada awalnya, tanaman sehat dan sakit
mempunyai anakan yang sama. Akan tetapi pada fase menjelang panen tanaman sakit
mempunyai lebih banyak anakan dibandingkan dengan tanaman sehat. Daundaun bergerigi
merupakan gejala awal yang cukup jelas pada fase awal tanaman muda. Pinggir daun yang
tidak rata atau pecah-pecah dapat terlihat sebelum daun menggulung. Bagian helai daun yang
rusak menunjukkan gejala khlorotik, menjadi kuning atau kuning kecoklatan dan terpecah-
pecah. Infeksi pada daun bendera menyebabkan daun melintir, berubah bentuk dan
memendek pada fase primordia (bunting). Penyakit kerdil hampa disebabkan oleh virus (rice

ragged stunt virus/RRSV) berbentuk polihedral berdiameter 50 - 70 nm dan banyak
ditemukan dalam sel-sel floem dan sel-sel puru. Hubungan virus dengan vektornya adalah
secara persisten. Periode makan akuisisi terpendek lebih kurang delapan jam dan periode
latennya 2 - 33 hari (rata-rata sembila hari). Periode makan inokulasi minimum lebih kurang
satu jam dan bila periode makan inokulasinya diperpanjang sampai satu hari, maka tanaman
yang terinfeksi akan bertambah banyak.
Pengendalian Kerdil Rumput dan Kerdil Hampa
Sampai saat ini belum ada varietas padi tahan terhadap penyakit kerdil rumput dan kerdil
hampa.
Pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara:
1. Memutus hubungan antara wereng coklat
dengan virus kerdil rumput dan kerdil hampa dan
tanaman padi dengan cara pengaturan pola
tanam.
2. Eradikasi tanaman padi atau ratun yang tertular
virus dan tidak menanam padi untuk beberapa
saat (1-2 bulan).
Periode retensinya berkisar antara 3 sampai 35 hari (rata-rata 15 hari) atau 13% sarnpai 35%
dari lama hidupnya. Penularan virus ini adalah transtadial tetapi tidak transovarial. Periode
inkubasinya dalam tanaman 2-3 minggu. Tanaman yang terserang kerdil hampa menunjukkan
suatu penyembuhan sementara, karena gejala dapat hilang tetapi akhirnya akan timbul
kembali.

Gulma yang Berperan sebagai Inang Predator, Hama dan Patogen
Secara umum, gulma merupakan tumbuhan yang di pada suatu sistem budidaya tanaman keberadaannya lebih bersifat merugikan daripada bersifat menguntungkan. Salah satu sifat merugikan yang ditimbulkan gulma secara tidak langsung adalah gulma dapat berperan sebagai inang untuk berbagai macam hama dan patogen penyebab penyakit. Walaupun demikian, keberadaan gulma sebagai inang organisme lain tidak selalu merugikan, ada beberapa gulma yang digunakan sebagai inang hewan predator sehingga hama dapat dikendalikan oleh predator dengan sendirinya. Keberadaan gulma sebagai inang bagi hama dan patogen terkadang juga memberikan keuntungan misalnya pengendalian hama dan patogen menjadi lebih mudah ketika hama dan patogen yang menyerang hanya berkumpul pada tumbuhan gulma.
Berikut adalah beberapa contoh gulma yang menjadi inang predator, hama, dan patogen tumbuhan:
1. Gulma sebagai inang predator
a. Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell sebagai inang Coccinella arquata yang merupakan pemangsa wereng coklat b. Vernonia cinerea (L.) Less. adalah inang Diadegma eucerophaga yang merupakan parasitoid pada Plutella xylostella (serangga pemakan kubis) c. Ageratum conyzoides L adalah inang Platigaster oryzae yang merupakan parasitoid hama ganjur yang menyerang padi.
Gulma yang menjadi inang
Gulma yang dapat menjadi inang alternatif bagi serangga hama dan patogen, secara tidak
langsung menjadi faktor pembatas produksi padi. Gulma dapat menyediakan makanan serta
menjadi tempat berlindung (shelter) dan berkembangbiak bagi serangga, nematoda, patogen,
dan tikus (Ampong-Nyarko and de Datta 1991, Norris and Kogan 2005). Beberapa serangga
hama padi, seperti pelipat daun, wereng daun, dan kumbang daun dapat berkembangbiak

pada beberapa gulma yang umum ditemukan pada pertanaman padi, umumnya jenis rumput
(grasses), yang terdapat pada saat sawah bera, di pematang, dan dalam petakan sawah (Norris
and Kogan 2005), seperti Cyperus rotundus, Fimbristylis miliaceae, Oryza longistaminata,
dan O. barthii (Ampong-Nyarko and de Datta 1991).
Uji Gulma Inang Alternatif Virus Tungro
Sampel tanaman gulma yang banyak ditemukan pada areal persawahan di Lolit Tungro,
dikoleksi pada bulan Maret 2010. Masing-masing sampel gulma ditanam dan dipelihara di
rumah kaca dengan menanam masingmasing secara terpisah pada ember diameter 15 cm
yang berisi tanah sawah, satu tanaman per ember.
Wereng hijau Nephotettix virescens yang digunakan sebagai vektor virus tungro dan sumber
inokulum pada pengujian ini berasal dari koleksi di rumah kaca Lolit Tungro. Perbanyakan
wereng yang viruliferous dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah wereng hijau ke
dalam kurungan yang berisi tanaman padi bergejala tungro (sumber inokulum) selama 24 jam
untuk proses acquisition feeding. Selanjutnya, masing-masing spesies gulma dalam ember
disungkup dengan sungkup plastik dan diinokulasi dengan wereng hijau yang viruliferous
(10 ekor/ember) selama 48 jam untuk proses inoculation feeding. Tanaman gulma yang telah
diinokulasi dengan virus tungro dipindahkan ke sungkup yang lain yang berisi wereng hijau
non-viruliferous (10 ekor/ember) agar menjadi viruliferous.
Uji gulma sebagai inang alternatif virus tungro dilakukan dengan metode tabung reaksi ( test
tube) menggunakan varietas padi Taichung Native 1 (TN1). Benih TN1 disemai dan
dipelihara dalam baki plastik berisi tanah sampai berumur 14 hari setelah semai (HSS). Setiap
bibit TN1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi
yang telah diisi 2 ekor wereng hijau viruliferous, kemudian direinokulasikan ke tanaman padi
umur 14 HSS. Percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 10 ulangan.
Parameter yang diamati adalah persentase tanaman padi yang terinfeksi tungro berdasarkan
gejala visual penyakit. Pengamatan dilakukan setiap hari sejak tanaman berumur 7 HSI
hingga 28 HSI. Selanjutnya, tanaman padi dan gulma yang terinfeksi virus tungro dan dapat
menginfeksi tanaman padi diperbanyak di rumah kaca dan dijadikan sebagai sumber
inokulum untuk percobaan di lapangan.

jenis yang mampu menularkan virus tungro, yaitu Cyperus rotundus Phyllanthus niruri,
Fimbristylis miliaceae, dan Eulisine indica, dengan persentase penularan yang cukup rendah
(15-25%). Selain sebagai inang alternatif RTV, gulma tersebut juga menjadi inang alternatif
bagi serangga vektor (wereng hijau). Tiga dari empat gulma yang terindikasi sebagai inang
alternatif virus tungro termasuk dalam golongan sedges (teki-tekian), yaitu C. rotundus, F.
miliaceae, dan E. indica. Jenis teki-tekian ini sulit dimusnahkan karena memproduksi umbi
yang memiliki masa dormansi, sehingga dapat bertahan pada kondisi stres lingkungan
(Ampong-Nyarko and de Datta 1991).
Oleh sebab itu, untuk menekan perkembangan penyebaran virus tungro oleh wereng hijau
secara dini, maka harus dilakukan eradikasi sumber inokulum virus tungro, termasuk gulma
sebagai inang alternatifnya. Dengan mengendalikan gulma, berarti juga mengendalikan
serangga vektor sekaligus virus tungro yang terbawa oleh wereng hijau.
Ampong-Nyarko, W. and S.K. De Datta. 1991. A Handbook for Weed Control in Rice. IRRI,
Manila, Philippines. 113 pp.
Herlinda, Siti. 2004. Jenis Tumbuhan Inang, serta Populasi dan Kerusakan oleh Pengorok Daun, Liriomyza huidobrensis (Blanchard) pada Tanaman Kubis (Brassica oleracea L.). Jurnal Tanaman Tropika 7:59-68
Sitompul, Y. F. 2003. Nematoda Parasit pada Gulma Padi Sawah di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Skripsi. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Institut Pertanian Bogor.
Soejono, A.T. 2006. Gulma dalam Agroekosistem: Peranan, Masalah, dan Pengelolaanya. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
pangan.litbang.deptan.go.id/files/Fauziah-PP32-03.pdf