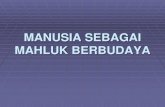BAB II PANDANGAN TENTANG YANG SKARAL DAN YANG PROFAN · 2017. 10. 5. · 11 BAB II PANDANGAN...
Transcript of BAB II PANDANGAN TENTANG YANG SKARAL DAN YANG PROFAN · 2017. 10. 5. · 11 BAB II PANDANGAN...
11
BAB II
PANDANGAN TENTANG YANG SKARAL DAN
YANG PROFAN
Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan hampir semua hal yang
menyangkut tingkah laku manusia ditentukan oleh budaya. Tidak dapat dipungkiri
bahwa antara manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Dalam berbudaya itu
manusia tidak sendiri tetapi bersama-sama dengan orang lain, tidak ada
masyarakat tanpa kebudayaan begitu pula tidak ada kebudayaan tanpa
masyarakat. Kebudayaan merupakan seluruh hasil kreativitas manusia yang sangat
kompleks.
A. Kebudayaan
Secara etimologis istilah kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta
budddhayah merupakan bentuk jamak dari kata budhi (akal) artinya bahwa
kebudayaan berarti hasil karya akal budi manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.1
Menurut E.B. Tylorkebudayaan adalah kompleks yang mencakup
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan
kemampuan-kemampuan serta kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia
sebagai anggota komunitas. Kemudian Herskovits memandang kebudayaan
sebagai sesuatu yang superorganic, karena kebudayaan yang berturun temurun
1 Tri Widiarto, Pengantar Antropologi Budaya.(Salatiga: Widya Sari Press, 2005), 10
12
dari generasi ke generasi tetap hidup meskipun orang-orang yang menjadi anggota
masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan karena kematian dan kelahiran.2
Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan adalah budi
daya manusia dalam hidup bermasyarakat.3
Dalam Kebudayaan terdapat unsur-unsur kebudayaan seperti yang
dikatakan oleh Tri Widiarto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar
Antropologi Budaya”4 dalam hal ini memiliki setiap unsur memiliki hubungan
satu dengan yang lain. Di situ dijelaskan tiga unsur : 1) Cipta, yakni kemampuan
akal pikiran yang menimbulkan pengetahuan dan teknologi. Manusia selalu
memiliki kenginginan untuk mengetahui rahasia-rahasia alam dan kehidupan.
Dengan akal, pikiran dan nalar (ratio) manusia selalu mencari, menyelidiki dan
menemukan sesuatu yang baru, serta mampu menciptakan karya-karya besar; 2)
Rasa, dengan panca inderanya menusia mengembangkan rasa keindahan atau
seketika dan melahirkan karya-karya kesenian; 3) Karsa atau kehendak, dengan
ini manusia selalu menghendaki untuk menyempurnakan hidupnya, merindukan
kemuliaan hidup, mencari kesusilaan, budi pekerti luhur dan selalu mencari
perlindungan dari sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian
kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang
dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya
dengan belajar.
2 Di kutip oleh Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar,. (Jakarta PT. Raja
Gravindo persada, cet 23, 1996), 187-888.
3 Tri Widiarto, Pengantar Antropologi Budaya. (Salatiga: Wisdya Sari Press, 2005), 12
4Ibid., 12
13
B. Mayarakat
Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa
Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa
Inggris disebut society yang artinya sekelompok orang yang membentuk
sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi
adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Mereka
mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.5
Dengan mendasarkan pada pandangan Comte yang melihat masyarakat
sebagai suatu keseluruan organik yang kenyataannya lebih dari sekedar jumlah
bagian-bagian yang saling bergantung maka Durkheim memfokuskan pada
solidaritas dan integrasi masyarakat sebagai permasalahan substansial karyanya.
Tentunya hal ini sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh kondisi pada masa itu,
saat terjadinya revolusi khususnya di Perancis yang menimbulkan perubahan
tatanan sosial dan munculnya efek-efek negatif industrialisasi terhadap
masyarakat. Pada masa itu pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara individu
dengan masyarakat masih menjadi bahan pemikiran. Namun Durkheim memiliki
perspektif yang berbeda dengan pemikir-pemikir lain seperti Hobbes dan Spencer.
Para pemikir sebelumnya melihat bahwa masyarakat dibentuk oleh individu-
individu yang kemudian dengan berbagai alasan tertentu membentuk jalinan
masyarakat. Durkheim memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan
5 Indah F, Pengertian Dan Defenisis Masyarakat Menurut Para Ahli. Cara pedia.
carapedia.com/pengertian_definisi_masyarakat_menurut_para_ahli_info488.html. Di akses
tanggal 4 agustus 2014.
14
pandangan ini.Ia melihat bahwa individu dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat
juga memiliki sejumlah aturan yang membuat kita bergantung padanya. Hal-hal
itu adalah fakta sosial yang ada dalam masyarakat seperti hukum-hukkum,
norma-norma, nilai-nilai, dan sanksi-sanksi yang diterima apabila anggota
masyarakat tidak menjalankan hukum-hukum atau norma-norma yang ada.6
Dasar pemikiran Durkheim ini dijelaskan dengan apa yang dia sebut dengan fakta
sosial. Fakta sosial adalah perbuatan-perbuatan yang ada diluar individu secara
terpisah, umum, dan memaksa karena fakta itu tidak dapat terlepas dari individu-
individu secara bersama-sama serta memaksakan individu berbuat sesuai dengan
keadaan masyarakatnya. Sesungguhnya individu-individu memiliki hasrat sendiri-
sendiri namun lingkungan sosialnya mempengaruhi sehingga hasrat individu tidak
muncul. Proses ini sepenuhnya terjadi melalui sosialisasi yang memungkinkan
proses “pemaksaan” itu terjadi tanpa disadari. Jadi fakta sosial tidak menyatu
dengan individu-individu secara utuh tetapi juga tidak bisa lepas dari individu-
individu tersebut. Inti dari fakta sosial ini yaitu adanya tindakan yang dilakukan
disebabkkan karena adanya pola dalam hubungan sosial itu sendiri. Sehingga
Menurut Emile Durkheim, fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta
individu, karena ia memiliki eksistensi yang independen ditengah-tengah
masyarakat. Fakta sosial sesungguhnya suatu kumpulan dari fakta-fakta individu
akan tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu realitas yang riil. Masyarakat
merupakan realitas sui generis.Durkheim menyebut fakta sosial dengan sui
6 Bernard Raho SVD. Agama Dalam Perspektif Sosiologi. (Jakarta: OBOR, cet-1. 2013),
42
15
generis, yang berarti “unik”, artinya bahwa masyarakat memiliki karakteristiknya
sendiri yang tidak bisa dijumpai dalam realitas lain dalam alam semesta atau tidak
dapat dijumpai dalam bentuk yang sama.7Dengan demikian fakta sosial akan
berlaku umum bagi masyarakat dan bukan mencerminkan satu keinginan
individu.
Lebih lanjut Durkheim menjelaskan tentang fakta sosial sebagai kesadaran
kolektif dan gambaran kolektif. Gambaran kolektif adalah simbol-simbol yang
mempunyai makna yang sama bagi semua anggota sebuah kelompok dan
memungkinkan mereka untuk merasa satu sama lain sebagai anggota kelompok.
Sedangkan kesadaran kolektif merupakan semua gagasan yang dimiliki bersama
oleh para anggota masyarakat dan menjadi tujuan-tujuan dan maksud-maksud
kolektif sebagai bentuk consensus normative yang mencakup kepercayaan-
kepercayaan keagamaan.8
Masyarakat secara paling sederhana dipandang oleh Durkheim sebagai
kesatuan intregral dari fakta-fakta sosial itu. Durkheim mendefinisikan kesadaran
kolektif sebagai berikut; “seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang
kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap
yang punya kehidupan sendiri atau dapat juga disebut dengan kesadaran kolektif
atau kesadaran umum. Masyarakat memiliki “kesadaran kolektif” yang
7Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta: Ircisod,
2003), 38
8Daniel Pals, Seven Theories Of Religion(Terj.). (Jogjakarta: IRCiSoD, Edisi baru Cet-2
2012), 140
16
membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang
ideal bagi individu. Durkheim pun menjadikan fakta solidaritas sosial sebagai
unsur dasar dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu kekuatan yang lebih
besar daripada kita. Ia melampaui kita, menuntut pengorbanan kita, menindas
kecendrungan egois kita, dan memenuhi kita dengan energi. Masyarakat, menurut
Durkheim, melaksanakan kekuatan-kekuatan tersebut melalui representasi-
representasi. Misalnya didalam Tuhan, Durkheim melihat “hanya masyarakat
yang diubah rupanya dan diungkapkan secara simbolis”. Oleh karena itu
masyarakat adalah sumber dari yang sakral.
Menurut Durkheim definisi kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan
bersama orang banyak dalam masyarakat yang akan menimbulkan sebuah sistem
yang tetap dan memiliki kehidupan sendiri bersifat umum. Durkheim memandang
kesadaran kolektif tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat secara
keseluruhan melalui kepercayaan dan sistem bersama. Durkheim menilai bahwa
kesadaran kolektif tidak dapat telepas dari fakta sosial dan Durkheim pun tidak
memungkiri kalau kesadaran kolektif dapat terwujud melalui kesadaran-kesadaran
individu.
Sementara itu, adanya representatif kolektif dikarena, kesadaran
kolektif memiliki sesuatu yang luas dan tidak memiliki bentuk yang tetap dan
hanya bisa dipelajari dengan melalui fakta sosial material, maka Durkeim pun
memilih sesuatu yang lebih spesifik dalam karya-karyanya. Contoh dari
representatif kolektif adalah simbol agama, mitos serta cerita-cerita populer.
Semua itu adalah cara-cara masyarakat merefleksikan dirinya dan
17
mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif dan mendorong kita
untuk menyesuaikan diri dengan pengakuan kolektif. Representasi kolektif tidak
dapat ditimbulkan oleh kesadaran-kesadran individu, karena reperesentatif
kolektif berhubungan langsung dengan simbol material.
C. Agama Menurut Emile Durkheim
Kata “agama” merupakan kata atau istilah yang menjadi sangat penting di
dalam kehidupan manusia. Agama diperlukan oleh manusia baik perorangan
maupun kelompok dari generasi ke generasi.9 Seringkali pengertian agama itu
dipahami secara abstrak dan tidak riil karena merupakan keyakinan terhadap
sesuatu yang misterius. Pengertian agama seperti ini merupakan pengertian
umum, dimana agama sebagai sesuatu yang berhubungan dengan yang misterius
dan tidak bisa dipahami manusia karena keterbatasan intelektual.
Emile Durkheim dalam penelitian terhadap kehidupan kepercayaan
masyarakat Aboriginyang ada di pedalaman Australia, melihat bahwa
pemahaman ide-ide tentang agama sebagai suatu yang misteri tidak didapat dalam
masyarakat primitif, karena bagi mereka ide-ide tersebut adalah sesuatu yang
bersifat sederhana, tidak rumit dan bukanlah suatu yang irasional. Ide-ide yang
dianggap misteri tersebut justru merupakan cara terbaik untuk mengetahui dan
memahami apa yang ada disekitar.10
Dengan demikian dapat disimpulkan secara
9 K. Sukardi, Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya. (Bandung:
Angkasa Bandung, 1993), 17
10 Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta:
Ircisod, 2003), 251-255
18
keseluruhan bahwa masyarakat adalah sosok yang membentuk agama itu sendiri,
dimana setiap individu yang memilki kebiasan yang sama akan disatukan melalui
kepercayaan dan ritus. Masyarakat merupakan sesuatu yang mengikat setiap
individu dalam aturan yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai Tuhan
yang juga harus disembah dan dihormati oleh setiap individu sebagaimana setiap
individu menghormati prinsip-prinsip totem.
Menurut Durkheim, ide yang muncul dalam benak manusia tentang hal
yang misterius akan melahirkan konsep tentang yang supernatural. Namun
pemahaman tentang ide yang supernatural tidak hanya didapat melalui fenomena-
fenomena alam yang terlihat tidak natural. Menurutnya, ide mengenai yang
misteruis merupakan ide yang diciptakan atau diolah oleh manusia itu sendiri
sebagaimana yang misterius mempengaruhi manusia. Sesuatu yang supernatural
seringkali dipahami oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang agung atau
sebagai Tuhan, tetapi Durkheim sendiri lebih suka menggunakan istilah “sesuatu
yang spiritual” (spiritual being). Sesuatu yang spiritual itu mesti dipahami sebagai
subjek yang berkesadaran yang memiliki kemampuan melebihi manusia. Sebab
Durkheim sendiri mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat
menghubungkan kita dengan yang spiritual itu hanyalah apa yang dilekatkan
manusia padanya. Sesuatu yang spiritual tadi adalah sesuatu yang berkesadaran
dan kita dapat mempengaruhinya sebagaimana kita dapat mempengaruhi
kesadaran secara umum dengan menggunkan sarana-sarana psikologi, dengan
berusaha meyakinkan dan membangkitkan kata-kata (matra dan doa) atau dengan
sesaji dan kurban-kurban. Dan karena objek agama mengatur hubungan-hubungan
19
kita dengan sesuatu yang khas ini, maka agama hanya bisa ada jika doa, kurban,
ritus-ritus tolak bala dan sejenisnya.11
Lebih lanjut, Durkheim melihat bahwa agama juga tidak bisa dipisahkan
dari ide tentang komunitas agama karena komunitas agama membentuk satu
komunitas moral yang memiliki keyakinan yang sama dan yang terdiri dari para
pengikut, baik orang awam, pemimpin agama atau pemuka agama.12
Lebih
jelasnya Durkheim mendefenisikan agama sebagai kesatuan sistem kepercayaan
dan praktek-praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral yakni hal-hal
yang terpisah dan dilarang yang menyatu dalam suatu komunitas moral yang
disebut komunitas agama. Untuk menunjukan bahwa ide agama tidak dapat
dipisahkan dari ide gereja, mau tidak mau agama harus dikonsepsikan sebagai hal
yang benar-benar kolektif.13
Dasar dari pendapat Durkheim adalah agama merupakan perwujudan dari
collective consciousness (kesadaran kolektif) sekalipun selalu ada perwujudaan-
perwujudan lainnya.Ia menyatakan bahwa Tuhan dianggap sebagai simbol dari
masyarakat itu sendiri yang sebagai collective consciouness kemudian menjelma
ke dalam collective representation. Tuhan itu hanyalah idealisme dari masyarakat
itu sendiri yang menganggapnya sebagai makhluk yang paling sempurna (Tuhan
adalah personifikasi masyarakat) dan melebihi apa yang dimiliki oleh manusia.
11
Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta:
Ircisod, 2003), 56-57
12DhavamonyMariasusai. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: Kanisius), 79
13 Emil durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.) (Jogjakarta: Ircisod,
2003), 80
20
Sehingga ia berkesimpulan bahwa agama merupakan lambang kolektif atau
collective representation daripada masyarakat dalam bentuknya yang ideal.
Dalam hal ini Durkheim mengemukakan dua hal pokok dalam agama yaitu
kepercayaan dan ritus atau upacara-upacara.Keyakinan adalah pikiran dan ritus
adalah tindakan.14
Pandangan inipula yang nampak dalam pemikiran Durkheim bahwa agama
berasal dari masyarakat itu sendiri.Masyarakatlah yang secara kolektif
mengkonstruksikan hal-hal yang mereka anggap suci (sakral) dan yang mereka
anggap duniawiah. Anggapannya tersebut didukung dari hasil penelitian yang ia
lakukan terhadap masyarakat Aborijin di pedalaman Australia. Masyarakat
tersebut secara kolektif menganggap bahwa sebuah benda yang dinamakan
“Totem” itu sebagai benda yang suci dan diangap sebagai Tuhan sehingga mereka
tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku karena mereka merasa
diawasi oleh Totem tersebut. Totem yang mereka anggap suci tersebut tidak lain
adalah sebuah simbol belaka yaitu simbol dari Tuhan yang mereka konstruksikan
sendiri.
Durkheim mengatakan ada dua hal paling pokok dalam agama, yaitu apa
yang disebut sebagai kepercayaan dan apa yang disebut sebagai ritus atau
upacara-upacara, dan kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Kepercayaan
agama merupakan kepercayaan kepada hal-hal yang dianggap sakral, sehingga
14
Hotman M. Siahaan. Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi.(Jakarta: Penerbit
Erlangga. 1986), 156
21
orang bertingkah laku tertentu terhadap hal-hal yang dilakukan dalam
hubungannya dengan hal-hal tersebut.
Agama dianggap sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif
diantara masyarakat yang diwujudkan melalui upacara-upacara atau ritus-ritusnya.
Upacara-upacara keagamann tersebut dianggap dapat memperkuat kesadaran
kolektif diantara para pemeluknya dan setelah selesai melakukan upacara
keagamann tersebut, kesadaran kolektif itu dibawa dalam kehidupannya sehari-
hari dan lama kelamaan akan luntur dan akan diperkuat lagi dengan mengikuti
upacara keagamaan lagi.
Dalam defenisi Durkeim tentang agama jelas menunjukan bahwa perhatian
agama adalah tentang hal-hal yang sakral.Dan disebutkan komunitas agama
karena agama merupakan suatu komunitas yang melibatkan kepentingan-
kepentingan besar dan kesejahteraan seluruh kelompok umat.Defenisi ini juga
mengingatkan bahwa yang profan itu tidak selalu jahat atau buruk, melainkan
menunjukan ruang lingkup yang lebih kecil dan pribadi.
Bertolak dari pemikiran Durkheim mengenai agama, maka dapat dilihat
bahwa agama memiliki hubungan dengan komunitasnya. Agama tidak lain
daripada kekuatan kolektif masyarakat yang berada di atas individu-individu.
Kekuatan ini sungguh ada dan kekuatan-kekuatan itu adalah
masyarakat.Meskipun demikian agama bukan hanya merupakan sistem
kepercayaan atau konsep-konsep, melainkan juga sistem tindakan karena agama
melibatkan ritus-ritus. Dengan demikian hubungan agama dengan masyarakatnya
nampak di dalam ritual.
22
D. Ritual
Emile Durkehim dalam bukunya yang berjudul The Elemetary Forms The
Religius Life menjelaskan bahwa ritual merupakan aturan tentang perilaku yang
menentukan bagaimana manusia harus mengatur hubungan dirinya dengan hal-hal
yang sakral.15
Tingkah laku manusia dan sistem upacara dalam kehidupan sehari-
hari dapat saja mempengaruhi perkembangan keyakinan dan ajaran, karena apa
yang telah dilakukan berulang-ulang dan terus menerus dan itu akan
menyebabkan manusia yang melaksanakannya sebagai sesuatu yang memang
sebaliknya demikian.
Dalam kehidupan keagamaan terdapat simbol-simbol sakral.Simbol sakral
tersebut membawa manusia pada pelaksanaan ritus, karena di dalam ritus itulah
tingkah laku manusia dijadikan sakral. Melalui ritus-ritus tertentu yang
didalamnya terdapat suasana hati dan motivasi yang apabila dipertemukan akan
membentuk kesadaran spiritual dalam suatu masyarakat. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa ritualdilakukan untuk mempersatukan individu dalam kegiatan
bersama dan satu tujuan bersama dengan memperkuat kepercayaan, perasaan dan
komitmen moral terhadap kehidupan kelompok.
Durkheim menghubungkan ritus dengan kesadaran kolektif, bahwa
kesadaran kolektif itu merupakan kebutuhan asasi dalam diri setiap manusia
15
Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta:
Ircisod, 2003), 72
23
sehingga perlu diaktifkan kembali dengan upacara-uparaca religius yang dianggap
sakral.
Perlu dikemukakan bahwa, sistem ritual keagamaan biasanya relatif tetap,
tetapi latar belakang, keyakinan, maksud atau doktrinnya bisa berubah. Kalau
diamati dalam pelaksanaanya, ternyata biasanya melibatkan banyak warga
masyarakat yang menganut agama yang sama, sehingga mereka bersama-sama
mempunyai fungsi sosial yang sama pula yaitu untuk mengintensifkan solidaritas
masyarakat. Para pemeluk agama itu dituntut untuk menjalankan kewajiban
mereka melakukan upacara agamanya dengan sungguh-sungguh, namun demikian
ada saja anggota yang melakukan tuntutan itu dengan tidak serius.
Ritual memang tidak dapat dilepas pisahkan dari agama.Agama
merupakan lambang representasi kolektif dalam bentuknya yang ideal. Agama
adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif seperti ritus-ritus agama.
Orang yang terlibat dalam upacara keagamaan maka kesadaran mereka tentang
collective consciouness semakin bertambah kuat. Sesudah upacara keagamaan
suasana keagamaaan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian lambat laun
collective consciousness tersebut semakin lemah kembali. Jadi ritual-ritual
keagamaan merupakan sarana yang dianggap berperan dalam menciptakan
kesadaran kolektif di antara masyarakat, atau dengan kata lain ritual agama
merupakan perintah atau tuntunanbagi manusia untuk mendekatkan diri kembali
kepada Tuhannya.
24
Dari sini, terjawab sudah arti penting ritual-ritual keagamaan dari agama-
agama yang pada saat ini masih ada. Mereka dapat memberikan arti penting suatu
masyarakat dalam diri kita sekaligus memberikan kepada kita perasaan yang
transenden, yang tidak terjamah, yang tidak tercapai dalam kehidupan sehari-hari
yang bersifat individual. Ini juga menjelaskan mengapa pemuka-pemuka agama
dan kalangan-kalangan beragama yang taat sangatlah dijunjung tinggi oleh
masyarakat. Karena mereka sudah mengorbankan diri mereka untuk kepentingan
masyarakat. Ia menjadi contoh bagi masyarakat untuk meninggalkan Yang Profan
karena Yang sakral berada di kepentingan masyarakat.
Pandangan mengenai ritus juga dikemukakan oleh Mircea Eliade.Eliade
mendefenisikan ritus sebagai sarana bagi manusia religius untuk bisa beralih dari
waktu profan ke waktu kudus (sakral) yang transenden terhadap kondisi manusia,
dimana manusia meniru tindakan kudus yang mengatasi kondisi manusiawinya
dengan keluar dari waktu kronologis dan masuk ke dalam waktu awal mula yang
kudus yang menjadi pusat dunia.16
Pada dasarnya dalam makna religiusnya ritual
merupakan gambaran prototype yang suci, model-model teladan, arketipe
primordial; sebagaimana dikatakan ritual merupakan pergulatan tingkah laku dan
tindakan makhluk ilahi atau leluhur mistis.17
Pendefenisian yang senada juga
dikemukakan oleh J. Goody dalam fenomenologi Agama mendefenisikan ritual
sebagai suatu kategori adat perilaku yang dibakukan, dimana hubungan antara
16
Hary Susanto, Mitos : Menurut Pemikiran Mircea Eliade. (Jogjakarta: Kanisius, 1987),
56
17Mariasuasi Dhavamony. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: kanisius, 1995), 183
25
sarana-sarana dengan tujuan yang bersifat “intrinsik”, dengan kata lainsifatnya
entah rasional atau nonrasional.18
Dalam pendefenisian yang berbeda, Susana Langer dalam Dhavamony
mengemukakan bahwa ritual merupakan ungkapan dari yang lebih bersifat logis
daripada hanya bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-
simbol yang diobjekan. Simbol-simbol tersebut mengungkapkan perilaku dan
perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari pada pemuja mengikuti
modelnya masing-masing.19
Melalui pengobjekan terhadap simbol-simbol tersebut
terdapat kepentingan untuk melanjutkan eksistensi individu dan kolektifitas dalam
keagamaan.
Berbicara mengenai eksistensi ritus dalam realitas keagamaan suatu
masyarakat, Geertz mengemukakan bahwa dalam ritus, tingkahlaku yang
dikeramatkan, kepercayaan bahwa konsep-konsep religius dibenarkan dan
kepercayaan bahwa tujuan-tujuan religius terbukti agak berhasil. Di dalam
semacam bentuk seremonial tertentulah-sekalipun bentuk itu hampir tidak lebih
daripada resitasi sebuah mitos, konsultasi sebuah ramalan, atau dekorasi sebuah
makam, suasana-suasana sebuah hati atau motivasi-motivasi yang timbul oleh
simbol-simbol sakral dalam diri manusia dan konsep-konsep umum tentang tata
18
Ibid ., 175
19Mariasuasi Dhavamony. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: kanisius, 1995), 174
26
eksistensi yang di rumuskan simbol-simbol itu bagi manusia bertemu dan saling
memperkuat satu sama lain.20
Bertolak dari pemikiran tokoh-tokoh di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa; 1), ritus merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi dengan
hakekat yang tertinggi dalam penggunaan simbol-simbol. 2), ritus mengikat klan-
klan menjadi satu. 3), ritus dalam pelaksanaannya secara kolektif memperbaharui
rasa solidaritas pada mereka. Tetapi ketika anggota-anggota klan terpisah, rasa
solidaritas mulai menurun dan sewaktu-waktu harus dirangsang lagi dengan
berkumpul dan mengulangi upacara dimana kelompok tersebut saling
memperkuat.
Selain itu, ritual dapat dibedakan menjadi empat macam; Pertama,
tindakan magi. tindakan magi dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang
bekerja karena daya-daya mistis. Kedua, tindakan religius, kultus para leluhur,
juga bekerja dengan cara ini. ketiga, ritual konstituti yang mengungkapkan atau
mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis,
dengan cara ini upacara-upacara kehidupan menjadi khas. Keempat, ritual faktatif
yang meningkatkan kekuatan atau pemurnian dan perlindungan, juga
meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.21
Sejalan dengan itu Van
Gennep melihat bahwa ritual ini juga di perlukan untuk menetapkan
20
Clifford Geertz, The Interpretation Of Cultures (Terj.). (Jogjakarta: Kanisius, 1992),
32-33
21Mariasuasi Dhavamony. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: kanisius, 1995) 175
27
keseimbangan baru di dalamhubungan-hubungan yang berubah atau dengan
istilahnya yaitu memperoleh penyatuan kembali. 22
Ritual juga memiliki suatu lingkaran dan kalender tersendiri.23
Lingkaran
ritual (ritual circle) mengandung didalamnya tindakan manusia, kemudian
bagaimana tindakana itu mengarah dan menunjuk kepada makhluk-makhluk ilahi
yang disembah atau yang menjadi alasan dan dasar dari suatu perbuatan ritual.
Lingkaran itu adalah lingkaran kosmis yang secara langsung membawa manusia
(pelaku ritual) masuk dalam suatu pola hubungan kosmis dengan dunia transenden
dimana makhluk ilahi itu berada.24
Tindakan ritus selalu melibatkan partisipasi
manusia baik sebagai individu maupun komunitas.
Adapun tujuan dari ritual-ritual (upacara-upacara) itu, adalah : tujuan
penerimaan, perlindungan, pemurnian, pemulihan, kesuburan (produktifitas),
penjaminan, melestarikan kehendak leluhur (penghormatan), mengontrol pelikau
komunitas menurut situasi kehidupan sosial, yang semuanya diarahkan kepada
transformasi keadaan dalam manusia atau alam. Kadang-kadang tujuannya untuk
menjamin perubahan amat cepat dan menyeluruh pada keadaan akhir yang
diinginkan oleh pelaku upacara. Kadangkala juga targetnya adalah suatu aspek
hakikat bukan manusia; kadang manusiawi, individu; atau juga suatu kelompok.
Perubahan yang dimaksud kadang merupakan suatu perubahan kecil, suatu
22
Ibid ., 176
23 Lorrieane V. Aragon, Fields Of The Lord: Animism, Christian Ministiries, And State
Develompment In Indonesia. (Honolulu: Hawai University Press, 2002), 202-207
24 Bnd. Dhavamony.,175
28
koreksi yang akan memulihkan keseimbangan dan status qou, melestarikan
gerakan sistema dalam ikatan-ikatana; kadang menyangkut suatu sistem yang
rasikal, tercapainya level keseimbangan baru, atau bahkan kualitas baru dalam
organisasi.25
Secara global ritus dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu : ritual
(upacara-upacara) yang bersifat musiman dan bukan musiman. Ritual-ritual
musiman terjadi pada acara-acara yang sudah ditentukan, dan kesempatan untuk
melaksanakannya selalu merupakan peristiwa dalam siklus lingkaran alam-siang
dan malam gerhana, letak planet-planet dan bintang-bintang. Sedangkan ritual-
ritual bukan musiman, dilaksanakan pada saat-saat kritis, mengikuti kalender
lingkaran hidup. Sebagaimana dipaparkan Tiev, bahwa ritual-ritual musiaman
hampir selalu bercorak komunal dan menyelesaikan secara teratur kebutuhan-
kebutuhan yang berulang dari masyarakat sosial, sementara ritual-ritual (upacara-
upacara) bukan musiman mungkin atau bisa jadi tidak bercorak komunal.26
Pemahaman mengenai ritus sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
dapat dikatakan bahwa ritus sangat penting untuk mempertahankan solidaritas dan
hubungan masyarakat. Dengan demikian menurut Durkheim, melalui ritus-ritus
atau upacara-upacara tersebut masyarakat memperkuat dan memperbaharui
sentimen-sentimen keagamaan mereka serta perasaan ketergantungan mereka
pada kekuatan moral dan spiritual yang bersifat eksternal yang sebetulnya tidak
25
Mariasuasi Dhavamony. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: kanisius, 1995) 180
26Mariasuasi Dhavamony. Fenomenologi Agama. (Jokjakarta: kanisius, 1995), 178-179
29
lain dari masyarakt itu sendiri.27
Ritus-ritus atau upacara-upacara seperti itu akan
menciptakan suasana kegembiraan serta berusaha meyakinkan setiap anggota
masyarakat akan pentingnya kelompok dan masyarakat lewat nasihat-nasihat
keagamaan. Namun, sering kali ritus juga dilakukan untuk memperoleh sesuatu
atau menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
E. Yang sakral dan Yang Profan
Menurut Emile Durkheim dasar dari kepercayaan terhadap agama
bukanlah terletak pada kepercayaan terhadap hal-hal yang supernatural seperti
Tuhan, karena pada banyak agama tidak ditemukan kepercayaan terhadap Tuhan.
Dasar dari agama bukanlah kepercayaan terhadap kekuatan supernatural
(pembedaan atas apa yang natural dan supernatural), melainkan konsep yang
sakral. Pada masyarakat beragama, terdapat dua konsep yang terpisah, yaitu yang
sakral dan yang profan. Hal-hal yang sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang
superior, berkuasa, dalam kondisi profan ia tidak tersentuh dan terjamah dan
dihormati. Sementara, yang profan adalahkehidupan sehari-hari yang bersifat
biasa saja.28
Dalam penjelasan Durkheim mengenai agama, ia menjelaskan bahwa
agama adalah suatu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang utuh dan
selalu dikaitkan dengan yang sakral yaitu sesuatu yang terpisah dan terlarang.
27
Bernard Raho SVD. Agama Dalam Perspektif Sosiologi. (Jakarta: OBOR, cet-1. 2013),
45
28Daniel Pals, Seven Theories Of Religion(Terj.). (Jogjakarta: IRCiSoD, Edisi baru Cet-2
2012), 144-145
30
Perilaku-perilaku tersebut kemudian disatukan kedalam komunitas
masyarakat.yang sakral memiliki pengaruh luas, menentukan kesejahteraan dan
kepentingan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian yang sakral menurut
Durkheim berada dalam masyarakat. Sementara yang profan tidak memiliki
pengaruh yang kuat, dan hanya merefleksikan kehidupan setiap hari yang
dilakukan oleh individu-individu.
Untuk menjelaskan yang sakral, Durkheim menganalisis agama
totemisme yang dianut oleh suku Aborijin bangsa penduduk asli Australia. Dalam
totemisme, kelompok manusia itu mengasosiasikan dirinya dengan salah satu
binatang atau tumbuhan sebagai totem. Mereka menganggap semua simbol totem
itu sakral, sehingga tidak boleh disentuh atau dimakan. Dari pandangan seperti
itulah muncul pandangan mengenai yang sakral dan profan.29
Berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan profan, maka ide
tentang pembagian dunia menjadi dua ranah tersebut pada akhirnya akan
melahirkan antagonitas. Manusia menciptakan dua hal ini dengancara
menciptakan larangan-larangan agar keduanya tidak saling bersentuhan. Berkaitan
erat dengan yang sakral atau suci, maka keadaaan tertentu yang tidak suci
dianggap dapat mencemarkan yang suci tersebut. Oleh karena itu untuk
29
Daniel Pals ., 157-158
31
menghindari kemungkinan timbulnya pencemaran suatu yang profan terhadap
yang sakral, maka manusia memagari keduanya dengan larangan atau tabu-tabu.30
Untuk menjauhi sentuhan antara keduanya, maka hal-hal yang sakral di
isolasikan oleh larangan-larangan, sedangkan hal-hal yang profan adalah tempat
larangan itu diterapkan. Untuk mengatur hubungan dengan hal-hal yang sakral,
maka manusia menggunakan ritus sebagai sebuah aturan atau tindakan. Hal-hal
yang sakral akan menjadi pusat organisasi yang dikelilingi oleh kepercayaan,
larangan-larangan, dan tata cara ritus-ritus yang dilakukan oleh masyarakat.31
Bagi Durkheim yang sakral berada dalam masyarakat, sementara yang
profan ada dalam konteks individu. Ia mengemukan konsepiniatas dasar
penelitiannya mengenai masyarakat dengan agama totemisme; agama yang
dianggap sebagai agama paling tua yang pernah ada dalam sejarah manusia. Pada
agama totemisme, simbol-simbol hewan dan tumbuhan dipuja sebagai sesuatu
yang dihormati. Simbol hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tertentu
merupakan lambang dari klan-klan tertentu pada suku-suku. Hewan-hewan dan
tumbuhan-tumbuhan itu suci dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai atau
bahkan didekati kecuali dalam perayaan-perayaan tertentu. Kesucian totem adalah
mutlak dalam masyarakat itu. Kesuciannya dapat dirasakan oleh tiap-tiap
individu, terutama dalam perayaan dan ritual-ritual keagamaan. Pada ritual-ritual
dan perayaan-perayaan itu, totem-totem menyusup dan mengatur kesadaran diri
30
Elizabeth K Nottingham, Religion And Society (Terj.). (Jakarta: Rajawali, cet-1, 1985),
12
31 Emil Durkheim ., 71
32
manusia. Saat pemujaan berlangsung dimana tarian-tarian, lagu-lagu, mantera-
mantera dan perasaan tenteram dan tenang merasuk ke dalam tiap individu, maka
detik itu juga individu kehilangan pribadinya dan masuk ke dalam kerumunan
masa yang sakral. Sebuah perasaan melayang-layang yang tidak biasa, yang tidak
bisa diungkapkan, tetapi nyata dan bersifat transendental.32
Menurut Durkheim pemujaan sebagai bagian dari fenomena religius dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu pemujaan negatif dan pemujaan positif. Pemujaan
negatif sangat erat hubungannya dengan larangan-larangan atau tabu, karena ia
yang akan menentukan jenis-jenis larangan religius tersebut. Larangan religius
termuat dalam ide tentang hal yang sakral dan dia muncul dari respek yang di
tuntut oleh objek-objek yang sakral.33
Ia selanjutnya memperlihatkan bahwa
kepercayaan terhadap roh-roh dan dewa-dewi berasal dari kepercayaan akan roh
nenek moyang yang sebetulnya merupakan jiwa-jiwa dari nenek moyang. Karena
itu, jiwa-jiwa dari nenek moyang tersebut sebetulnya merupakan prinsip-prinsip
sosial yang diekspresikan pada individu-individu tertentu.Sementara itu, larangan-
larangan atau tabu berasal dari rasa hormat terhadap objek-objek yang sakral.
Sehingga tujuan dari larangan-larangan atau tabu tersebut adalah untuk
mempertahankan rasa hormat tersebut.34
Dengan demikian dari hal-hal tersebut
muncul larangan-larangan dan penyangkalan diri yang di dalamnya juga
32
Ibid ., 154-166
33 Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta:
Ircisod, 2003), 434-436
34Raho Bernard SVD. Agama Dalam Perspektif Sosiologi. (Jakarta: OBOR, cet-1. 2013),
46
33
mengandung pengertian bahwa keteraturan sosial menjadi mungkin apabila
individu-individu dalam tingkatan tertentu menyangkal dirinya dan meninggalkan
kepentingan-kepentingan dirinya.
Fungsi dari larangan religius dalam pemahaman Durkheim adalah untuk
memisahkan antara yang sakral dan profan.Larangan-larangan tersebut
mengusahakan agar keduanya tidak melakukan kontak. Kontak yang dimaksud di
sini, misalnya dengan tatapan atau memandang terhadap yang sakral dan suara
atau bahasa-bahasa yang digunakan ketika melakukan upacara tidak boleh sampai
ke telinga orang-orang yang profan, perlengkapan-perlengkapan untuk ritus juga
menjadi suatu yang sacral dan terpisah dari profan. Lebih jauh lagi, tindakan dan
perilaku dalam kehidupan sehari-hari dilarang dilakukan selama kehidupan
religius berjalan.35
Jadi pemujaan negatif dalam hal ini merupkan sesuatu yang
terbatas pada sistem larangan dan bersifat menghalangi aktivitas profan.
Pemujaan negatif merupakan sarana yang diciptakan oleh masyarakat
untuk menandakan dan memisahkan sesuatu yang sakral dan profan, sehingga
setiap individu dengan sendirinya mampu membedakan kedua dunia
tersebut.Dengan adanya pemisahan antara yang sakral dan profan maka setiap
individu dapat menjalankan kehidupan religius mereka.Pemujaan negatif juga
merupakan langkah untuk tiba pada pemujaan positif seperti yang diistilahkan
35
Emil Durkheim. The Elementary Forms Of The Religius Life (Terj.). (Jogjakarta:
Ircisod, 2003), 437-444
34
oleh Durkheim.36
Dengan demikian maka setiap individu yang terikat dalam satu
keyakinan akan memahami sesuatu sebagai yang sakral ketika ada suatu larangan
yang mendorong setiap individu untuk patuh dan tunduk terhadapnya.
Implikasi dari keyakinan terhadap totem itu selanjutnya mampu
menjelaskan bagaimana masyarakat membangun sistem-sistem kepercayaan
tertentu melalui metode asosiasi hubungan-hubungan antar konsep yang berpusat
pada Yang sakral. Termasuk didalamnya adalah sistem kepercayaan terhadap roh
atau jiwa (yang menjadi dasar dari banyak agama). Roh yang ada dalam diri
seseorang merupakan representasi ketergantungan mereka terhadap masyarakat.
Roh bertugas untuk memberitahukan kepada individu untuk mematuhi kewajiban-
kewajiban moral terhadap masyarakat. Roh yang menjadi representasi
masyarakat dalam diri individu merupakan yang sakral sementara badan yang
bertugas memenuhi kebutuhan individu saja adalah yang profan. Selanjutnya
hubungan asosiatif dikembangkan lebih lanjut mengenai konsep roh yang bersifat
abadi. Dari sinilah penyembahan terhadap Dewa-Dewi dan Tuhan berasal. Roh-
roh yang mampu mengatur alam pada akhirnya dituntut oleh masyarakat sebagai
representasi kepribadian tertentu, yang superior, yang disebut Dewa dan Tuhan.37
Kepercayaan terhadap totem-totem yang pada akhirnya menjadi Dewa dan
Tuhan itu bukanlah hal yang paling penting dalam agama menurut Durkheim.
36
Seno P Harbangan. Antara Yang Saktal dan Yang Profane: Suatu Analisi Sosiologi-
Antropologis Tentang Upacara Rambu Solo’ Dikalangan Masyarakat Toraja (Tesis Magister
Sosiologi Agama, Universitas Kristes Satya Wacan ), 32
37Daniel Pals ., 153-156
35
Yang paling penting, adalah perasaan sakral yang dihasilkan dari ritual-ritual
keagamaan. Pemujaan-pemujaan yang ada dalam ritual-ritual atau perayaan-
perayaan dalam setiap agama bertujuan bukan untuk totem atau Dewa, melainkan
untuk menjaga individu-individu agar tidak melupakan arti penting klan dan
memberikan perasan bahwa yang sakral adalah sesuatu yang berbeda dan
memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Yang Profan.38
Dengan
demikianmenurut Durkeim,yang sakral beradadalam masyarakat artinya bahwa
ikatan paling mendasar yang mempersatukan masyarakat itulah yang disebut
sakral.
Menurut Mircea Eliade yang sakral adalah sesuatu yang supernatural, luar
biasa, amat penting, dan tidak mudah dilupakan. Sementara,yang profan adalah
sesuatu yang biasa, bersifat keseharian, hal-hal yang dilakukan sehari-hari secara
teratur dan acak, dan sebenarnya tidak terlalu penting. Yang sakral bersifat abadi,
mengandung substansi, dan nyata. Di dalam yang sakral mengandung
kesempurnaan dan keteraturan, yang di dalamnya bersemayam roh, nenek
moyang, tempat tinggal Dewa-Dewi dan Tuhan. Sementara yang profan bersifat
mudah hilang, terlupakan, dan tidak nyata. Di dalamnya, manusia selalu berbuat
salah, manusia selalu berubah, dan mengalami kekacauan.39
Menurut Eliade, yang sakral diketahui oleh manusia karena ia
memanifestasikan dirinya secara berbeda dari dunia profan. Manifestasi dari yang
38
Ibid ., 156-164
39Ibid ., 233-234
36
sakral ini disebut Eliade sebagai “Hierofani”.40
Eliade memperkenalkan konsep
hierofani sebagai sebuah konsep di mana yang sakral memanifestasikan dirinya
pada diri manusia, pengalaman dari orde realitas lain yang merasuki pengalaman
manusia. Ia juga memaparkan ide tentang ruang yang sakral, yang
mengambarkan bagaimana satu-satunya ruang yang “nyata” adalah ruang sakral,
yang dikelilingi oleh satu medan tanpa bentuk. Ruang sakral menjadi arah bagi
ruang yang lainnya. Ia mendapatkan bahwa manusia mendiami sebuah dunia
tengah, antara dunia-luar yang kacau dan dunia-dalam yang sakral, yang
diperbaharui lagi oleh praktik dan ritual sakral. Dengan menyucikan satu tempat
dalam dunia profan, kosmologi direkapitulasi dan yang sakral menjadi mungkin
diakses. Ini menjadi pusat dari dunia primitif. Ritual mengambil tempat dalam
ruang sakral ini, dan menjadi satu-satunya cara partisipasi dalam kosmos yang
sakral ketika berupaya menghidupkan dan menyegarkan kembali dunia profan.
Selanjutnya, Eliade mengaitkan waktu sakral dengan mitologi. Ketika
“waktu profan” adalah linear, waktu sakral kembali pada permulaan manakala
segalanya nampak lebih “nyata” daripada keadaannya sekarang. Lagi-lagi ritual
memainkan peran penting. Waktu digerakkan kembali dengan menjadikannya
baru kembali sementara ritual-ritual mengikat kembali para penganut kepada
keaslian kosmos yang sakral.
Dalam buku The sacred and the profane, Eliade mengatakan dengan
hadirnya yang sakral, maka setiap benda yang dipakai dapat menjadi sesuatu yang
40
Hierofani berasal dari bahasa yunani, yaitu hieros dan phainein yang berarti
“penampakan yang sakral”
37
lain, walaupun benda-benda tersebut tetap nampak seperti benda-benda biasa dan
berada di alamnya. Sementara dalam pandangan profan, sebuah batu yang
dianggap sakral kelihatannya tidak lebih dari batu biasa, tidak istimewah. Tetapi
bagi mereka yang melihat kehadiran yang sakral didalamnya, maka dengan
seketika batu akan berubah menjadi suatu kenyataan yang supernatural.41
Demikian juga halnya dengan tindakan religius, dimana setiap tindakan
religius bisa hanya oleh karena fakta sederhana maka tindakan itu bersifat
religius.Dengan diberi status makna simbolis maka tindakan itu menunjuk kepada
makhluk atau nilai-nilai yang supernatural.Yang sakral bisa disamakan dengan
kekuatan atau suatu realitas.42
Tetapi bisa terjadi pada waktu yang tertentu sesuatu
yang mejadi sarana sakral itu pada waktu yang lain tidak lagi menjadi symbol-
simbol sakral dan tempatnya diganti dengan objek yang lain, sekalipun yang
sakral sendiri tetap dan tidak pernah berubah. Karena yang sakral itu ialah yang
ilahi, abadi dan tidak pernah mati. Yang sakral merupakan suatu realitas yang
bukan dari dunia, sehingga sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan yang
profan.43
Bagi Eliade, otoritas yang sakral mengatur semua kehidupan. Misalnya
dalam pembangunan perkampungan baru.Masyarakat arkhais tidak dengan
41
Seno P Harbangan. Antara Yang Saktal dan Yang Profane: Suatu Analisis Sosiologi-
Antropologis Tentang Upacara Rambu Solo’ Dikalangan Masyarakat Toraja (Tesis Magister
Sosiologi Agama, Universitas Kristes Satya Wacan ), 31-32
42Mircea Eliade, The Sacred And The Profane: The Nature Of Religion. (London: A
Harvest/HBJ Book, 1959), 12
43Ibid ., 14-18
38
sembarangan memilih tempat.Satu perkampungan haruslah didirikan pada tempat
yang memiliki “Hierofani”.Sehingga rencana tersebut dapat diwujudkan apabila di
tempat yang dipilih tersebut pernah “dikunjungi” oleh yang sakral, baik itu dalam
bentuk dewa atau arwah nenek moyang.Dengan demikian suatu ruang atau tempat
menjadi sakral karena peristiwa “Hierofani”.
Lebih lanjut Eliade mengatakan bahwa di dalam masyarakat arkhais,
realitas yang paling utama adalah yang sakral. Dalam melakukan hal-hal yang
sifatnya mendasar, seperti menetukan waktu dan tempat menetap, mereka akan
selalu menyerahkan pilihannya kepada yang sakral.44
Keinginan manusia untuk
selalu dekat dengan yang sakral itulah menyebabkan Eliade, menyebutkan
manusia seperti itu sebagai manusia religius. Eliade juga mengatakan bahwa
manusia nonreligius sebetulnya juga berasal dari manusia religius. Ia merupakan
karya manusia religius dan dibentuk mulai dari sejak para leluhur yang merupakan
hasil proses desakralisasi. Manusia profan merupakan hasil dari desakralisai
eksistensi manusia.45
Dari sini terlihat sebenarnya perbedaan konsep yang sakral antara
Durkheim dan Eliade. Sementara Durkheim selalu mengunakan pendekatan sosial
kemasyarakatan yang non-supernatural dalam menentukan apa yang sakral itu,
Eliade berpendapat sebaliknya. Baginya, kekuatan supernatural adalah inti dari
yang sakral itu. Pemikiran Eliade ini bukanlah bersumber sepenuhnya dari
pemikiran Durkheim meski menggunakan istilah-istilah yang sama, melainkan
44
Daniel Pals ., 236
45Seno P Harbangan ., 44
39
bersumber dari seorang teolog yang pernah menjadi pembimbingnya, yaitu Rudolf
Otto yang mengartikan perjumpaan dengan yang sakral (The Holy) sebagai
mysterium (hal yang misterius). Baik itu mysterium fascinosum (misterius yang
mengagumkan) atau mysterium tremendum (misterius yang menakutkan),
keduanya merupakan perjumpaan dengan yang sakral.46
Perjumpaan yang sakral
ini memberikan perasaan yang nyata, agung, tinggi, dan menakjubkan. Perasaan
ini tidak sama dengan perasaan-perasaan lainnya yang bersifat duniawi.
Pengalaman tentang yang sakral terjadi apabila orang menjumpai sesuatu yang
benar-benar luar biasa dan dasyat, terpikat oleh suatu yang sama sekali lain,
sesuatu yang misterius, menawan, berkuasa dan indah, sesuatu yang menakutkan
tetapi sekaligus menawan. Ketika manusia mengalami pengalaman yang sakral
itu, manusia selalu menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa.Dalam pengalaman
yang mengesankan dan menggetarkan ini, terletak emosional dari semua manusia
yang kita sebut agama.Perhatian agama adalah terhadap yang supernatural, yang
jelas dan sederhana yang berpusat pada yang sakral. Dengan demikian agama
menurut Eliade (lebih dekat dengan Tylor dan Frazer) pertama-tama dan terutama
sebagai kepercayaan pada wilayah dari wujud yang supernatural.47
Kesakralan adalah keseluruhan realitas yang dahsyat dan abadi, sehingga
manusia ingin berada dekat dengan kekuatan itu. Eliade mengatakan bahwa dalam
perjumpaan dengan yang sakral, seseorang merasa disentuh oleh sesuatu yang nir-
46
Daniel Pals ., 235
47Ibid ., 235-238
40
duniawi.48
Segala konsep-konsep yang berada dalam ruang lingkup perjumpaan
dengan yang nir-duniawi dapat dikatakan sebagai yang sakral, dan ini tidak berarti
harus selalu dengan Tuhan yang bersifat personal. Dengan kepercayaan terhadap
kekuatan yang agung dan nir-duniawi yang nyata itu,adalah mudah menjelaskan
bagaimana kepercayaan yang begitu kuatnya pada akhirnya membentuk sistem-
sistem tertentu. Yang sakral mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia.
Sehingga bagi Eliade yang sakral itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan
supernatural, yang tertinggi, ada pada diri sendiri dan bukan produk masyarakat.
Pandangan di atas tentu tidak terlepas dari pandangan terhadap leluhur.
Fenomena kepercayaan terhadap roh leluhur merupakan gelaja umum yang
ditemukan pada kalangan masyarakat primitif dan juga ada pada berbagai kelas
masyarakat dan tingkat pendidikan. Peran leluhur sanngat penting dalm
mempengaruhi mereka yang masih hidup, misalnya supaya leluhur itu tidak marah
dan mendatangkan malapetaka maka setiap ketentuan harus di ikuti.
Kepercayaan terhadap leluhur biasanya termasuk suatu rasa kebutuhan
akan sesuatu bentuk komunikasi yang baik. Oleh karena itu pemahaman
masyarakat yang mengakui bahwa kedudukan leluhur dalam upacara adat
merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam menangkal kejahatan dan
menjamin kesejahteraan.Dengan demikian masyarakat mengalami secara
langsung impresi-impresi keagamaan yang menghubungkan mereka dengan
leluhur. Dalam pengalaman itu, leluhur diyakini memiliki kuasa tertentu dan
48
Ibid ., 235
41
fungsi menjaga dan memelihara komunitas masyarakat itu dan bahkan mereka
merasakan bahwa leluhur itu begitu dekat.
Berkaitan dengan penyembahan terhadap para lelulur, Dhavamony49
melihat ada dua bentuk kepercayaan dan praktek yang berkenan dengan para
leluhur yakni berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah meninggal
dalam suatu komunitas dan orang-orang yang sudah meninggal dianggap sebagai
makhluk-makhluk berkuasa yang kebutuhannya harus dipenuhi. Sementara itu
Paul Radin menggunakan istilah antropologis untuk menjelaskan pemujaan
terhadap para leluhur adalah penyamaan leluhur, baik secara langsung ataupun
tidak langsung, atau dari orang-orang yang menggantikan kedudukan leluhur
dengan roh dan dewa, serta pemindahan kepada mereka khususnya tindakan dan
sikap religius yang biasanya diasosiasikan dengan pemujaan roh dan dewa.50
Sedangkan menurut Richard, leluhur lebih superior dari manusia yang hidup, akan
tetapi kedudukan mereka tidak sederajat dengan Allah, peran mereka adalah
sebagai perantara yakni menolong Allah menyampaikan kehendak manusia
sekaligus menolong manusia menyampaikan masalah-masalah kepada Allah.51
Sementara itu Durkheim dalam teorinya tentang pemujaan dengan mendasarkan
pada kehidupan atau dunia yang sakral karena pemujaan itu sendiri tidak akan
lepas dari segala sesuatu yang dianggap sakral.
49
Davamnony ., 79
50Paul radin dalam MariasuasiDhavamony. Fenomenologi Agama. (Jogjakarta: kanisius,
1995), 79
51Suh Sung Min, Injil Dan Penyembahan Nenek Moyang. (Jogyakarta:Media Pressindo
2001), 24
42
Hal ini juga terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat Mepa yang
mengandaikan bahwa walaupun leluhur itu sudah meninggal namun, jiwanya
masih tetap hidup. Oleh karena itu maka leluhur patut diberi penghormatan.
Leluhur diyakni oleh masyarakat adat desa Mepa sebagai sosok yang dapat
menjaga dan melindungi mereka ketika mereka melakukan upacara-upacar adat.
Fenomena ini memberikan gambaran bahwa pola karakteristik masyarakat adat
merupakan cerminan menarik untuk dipelajari. Durkheim dan Eliade dalam
penelitiannya memberikan gambaran hampir sama dengan masyarakat adat desa
Mepa.