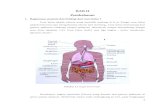BAB II
-
Upload
andrikeisha -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of BAB II

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Stroke
Stroke adalah suatu gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh
karena gangguan peredaran darah otak, dimana secara mendadak (dalam beberapa
detik atau menit) dapat menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah
fokal di otak yang mengalami kerusakan. Menurut WHO, stroke adalah
manifestasi klinik dari gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh
(global) yang berlangsung dengan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam, atau
berakhir dengan maut, tanpa ditemukan penyebab selain dari gangguan
vaskular.1Berdasarkan penyebabnya stroke dibagi manjadi dua jenis yaitu stroke
iskemik dan stroke hemoragik.
Stroke adalah sindrom yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah
otak (GPDO) dengan awitan akut, disertai manifestasi klinis berupa defisit
neurologis dan bukan sebagai akibat tumor, trauma ataupun infeksi susunan saraf
pusat.
2.2 Epidemiologi Stroke
Pada tahun 2009 secara keseluruhan tingkat kematian disebabkan CVD
adalah 236,1 per 100.000. Rasio 281,4 per 100.000 untuk laki-laki kulit putih,
387,0 per 100.000 untuk laki-laki hitam, 190,4 per 100.000 untuk perempuan kulit
putih, dan 267,9 per 100.000 untuk wanita hitam. Dari tahun 1999 sampai 2009,
tingkat kematian relatif disebabkan CVD mengalami penurunan sebesar 32,7%.
Namun di Amerika Serikat pada tahun 2009, CVD masih menyebabkan 32,3%
(787.931) dari semua 2.437.163 kematian, atau 1 dari setiap 3 kematian.9
Pada tahun 2010 di Inggris, stroke terbesar keempat penyebab kematian
setelah kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan menyebabkan hampir
50.000 kematian. Kejadian stroke adalah sekitar25% lebih tinggi pada pria

dibandingkan pada wanita. Sekitar 85% stroke disebabkan oleh sumbatan (stroke
iskemik), 15% stroke disebabkan oleh perdarahan diotak (stroke hemoragik)
dengan 10% disebabkan oleh perdarahan intraserebral dan 5% disebabkan oleh
perdarahan subarakhnoid.10
Di Indonesia data nasional stroke menunjukkan angka kematian stroke
mencapai 15,4% (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2007). Sementara itu terdapat
juga data stroke di Indonesia berdasarkan penelitian cross sectional multi-senter
di 28 rumah sakit dengan jumlah subjek sebanyak 2065 orang pada bulan Oktober
1996 sampai bulan Maret 1997. Selama pengamatan tersebut didapatkan stroke
dan transient ischemic attack (TIA) sebanyak 693 orang.Usia rata-rata stroke dari
data 28 rumah sakit di Indonesia adalah 58,8 tahun ± 13 tahun, dengan kisaran 18-
95 tahun. Usia rata-rata wanita lebih tua dari pria (60,4 ± 13,8 tahun versus 57,5 ±
12,7 tahun). Usia kurang dari 45 tahun sebanyak 12,9% dan lebih dari 65 tahun
sebanyak 35,8%. Dari data ini terlihat peningkatan kejadian stroke yang
berkorelasi dengan bertambahnya usia. Pada studi Framingham, kejadian stroke
pada pria rata-rata 2,5 kali lebih sering daripada wanita, hal ini agak berbeda
ditemukan pada studi di Indonesia, dimana kejadian stroke pada wanita lebih
banyak daripada pria (53,8% versus 46,2%).2
Pada tahun 2007 hingga 2011 jumlah penderita stroke di RSUP dr. Moh
Hoesin Palembang sebesar 3259 orang, dengan kecenderungan terjadi
peningkatan angka kejadian stroke setiap tahunnya. Penelitian Junaidi dkk di
RSUP dr.Moh. Hoesin Palembang pada periode Oktober hingga November 2014
mendata jumlah penderita stroke yang dirawat sebanyak 118 penderita stroke,
dimana61,9%adalahstroke non-hemoragik/stroke iskemik dan 38,1% stroke
hemoragik. Usia penderita stroke terbanyak pada kelompok usia 31-60(56,8%),
diikuti kelompok usia> 60 tahun(41,5%), dan kelompokusia 0-30
tahun(1,7%).Stroke hemoragik (100%) sering terjadi lebih sering dibandingkan
stroke non-hemoragik (0%) pada kelompok usia 0-30 tahun, sedangkan stroke
non-hemoragik lebih sering terjadi pada kelompok usia 31-60 (65,7%) dan >60
tahun (59,2%) dibandingkan stroke hemoragik. Pada seluruh kasus stroke, laki-
laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, laki-laki lebih sering

mengalami stroke non-hemoragik (66,7%) daripada stroke hemoragik(33,3%) dan
perempuan lebih sering mengalami stroke non-hemoragik (56,9%) daripada stroke
hemoragik (43,1%).
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Mencari
Pertolongan
Tujuan penatalaksanaan stroke secara umum yaitu menurunkan morbiditas
dan menurunkan tingkat kematian serta penurunan angka kecacatan. Salah satu
upaya yang mempunyai peran penting dengan pengenalan gejala stroke dan
penanganan yang cepat dan tepat. Terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi perilaku seseorang untuk mendapatkan pertolongan yaitu
a. Geografis dan demografi.
Faktor geografi seperti jarak antara rumah penderita dengan petugas
kesehatan terdekat dapat mempengaruhi perilaku mencari pertolongan
kesehatan.
b. Faktor klinis
Faktor klinis juga berpengaruh terhadap perilaku mencari pertolongan.
Adanya riwayat diabetes, hipertensi dan jantung koroner akan membuat
penderita lebih berhati-hati.5,6,7
c. Sosial-budaya
Faktor sosial budaya dimana penderita hidup sendiri, kemudian adanya
kebiasaan mengobati diri sendiri kemudian baru mencari pertolongan
kesehatan baik ke pengobatan tradisional atau ke tenaga kesehatan
profesional.
d. Faktor tingkat pengetahuan.
Tingkat pengetahuan tentang penyakit stroke yang rendah akan
mempengaruhi kesadaran untuk mencari pertolongan kesehatan.
e. Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
keterlambatan seseorang untuk mencari pertolongan. Dimana saat ini
masih banyak penduduk yang belum menggunakan jaminan kesehatan.
Dan masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.4 Klasifikasi Stroke
Klasifikasi stroke telah banyak dikemukakan oleh beberapa institusi.
Pasa dasarnya klasifikasi tersebut dikelompokkan atas dasar manifestasi
klinik, proses patologi yang terjadi di otak dan area lesinya. Menurut
modifikasi Marshall, stroke dapat diklasifikasikan menjadi:
1. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :
A. Stroke Iskemik
a. Trancient Ischemic Attack (TIA)
b. Trombosis serebri
c. Emboli serebri
B. Stroke Hemoragik
a. Perdarahan intraserebral
b. Perdarahan subarakhnoid
2. Berdasarkan stadium atau pertimbangan waktu:
A. Transcient Ischemic Attack (TIA)
B. Reversible Ischemic Neurologic Deficit(RIND)
C. Stroke in evolution atau progressingstroke
D. Completed stroke
3. Berdasarkan sistem pembuluh darah:
A. Sistem karotis
B. Sistem vertebro-basilar
4. Berdasarkan sindroma klinis yang berhubungan dengan lokasi lesi otak,
Bamford dkk mengemukakan klasifikasi stroke menjadi 4 sub tipe :
A. Total Anterior Circulation Infarct (TACI)
B. Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)
C. Posterior Circulation Infarct (POCI)
D. Lacunar Infarct (LACI)
2.4 Patofisiologi Stroke
2.4.1 Patofisiologi Stroke Iskemik

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stroke iskemik, salah
satunya adalah aterosklerosis, dengan mekanisme trombosis yang
menyumbat arteri besar dan arteri kecil, dan juga melalui mekanisme
emboli. Pada stroke iskemik, berkurangnya aliran darah ke otak
menyebabkan hipoksemia daerah regional otak dan menimbulkan reaksi
reaksi berantai yang berakhir dengan kematian sel- sel otak dan unsur-unsur
pendukungnya.
Secara umum daerah regional otak yang iskemik terdiri dari bagian
inti (core) dengan tingkat iskemia terberat dan berlokasi di sentral. Daerah
ini akan menjadi nekrotik dalam waktu singkat jika tidak ada reperfusi. Di
luar daerah core iskemik terdapat daerah penumbra iskemik. Sel- sel otak
dan jaringan pendukungnya belum mati akan tetapi sangat berkurang fungsi-
fungsinya dan menyebabkan juga defisit neurologis. Tingkat iskemiknya
makin ke perifer makin ringan. Daerah penumbra iskemik, di luarnya dapat
dikelilingi oleh suatu daerah hiperemik akibat adanya aliran darah kolateral
(luxury perfusion area). Daerah penumbra iskemik inilah yang menjadi
sasaran terapi stroke iskemik akut supaya dapat direperfusi dan sel-sel otak
berfungsi kembali. Reversibilitas tergantung pada faktor waktu dan jika
tidak terjadi reperfusi, daerah penumbra dapat berangsur-angsur mengalami
kematian.
Pada proses iskemia fokal terjadi juga perubahan penting di daerah
penumbra pada sel-sel neuron tergantung dari luas dan lama iskemia, yaitu:
a. Kerusakan membran sel
b. Aliran masuk Ca++ ke dalam sel melalui kerusakan reseptor Ca++
c. Meningkatnya asam arakidonat dalam jaringan, diikuti oleh naiknya
kadar prostaglandin yang menyebabkan vasokonstriksi dan
meningkatnya agregasi trombosit.
d. Lepasnya neurotransmiter asam amino eksitatorik di daerah otak
tertentu yang mempunyai kepekaan selektif terhadap iskemia (selective

vulnerability) yaitu daerah-daerah thalamus, area CA di hipothalamus,
sel-sel granuler dan Purkinye di serebelum, serta lapisan 3,5,6 korteks
piramidalis.
e. Lepasnya radikal bebas, yaitu unsur yang mempunyai elektron pada
lingkar paling luarnya tidak berpasangan, karena itu zat ini sangat labil
dan sangat reaktif. Dalam keadaan normal, proses kimia yang
menghasilkan radikal bebas terjadi di dalam mitokondria sehingga tidak
mengganggu struktur sel lainnya. Pada kerusakan mitokondria, zat ini
bebas dan merusak struktur protein dalam sel serta menghasilkan zat-
zat toksik. Besarnya peran radikal bebas dalam kerusakan sel saraf dan
jaringan iskemik masih dalam penelitian.
Gambar 1. Patofisiologi stroke iskemik
2.5 Penatalaksanaan Stroke

A. Penatalaksanaan di ruang gawat darurat
1. Evaluasi Cepat dan Diagnosis
Oleh karena jendela terapi dalam pengobatan stroke akut sangat pendek,
maka evaluasi dan diagnosis klinik harus dilakukan dengan cepat,
sistematik, dan cermat. Evaluasi gejala dan tanda klinik stroke akut
meliputi:
a. Anamnesis
b. Pemeriksaan fisik
c. Pemeriksaan neurologis dan skala stroke
2. Terapi umum
a. Stabilisasi Jalan Nafas dan Pernapasan
Pemantauan secara khusus terhadap status neurologis, nadi, tekanan
darah, suhu, dan saturasi oksigen dianjurkan dalam 72 jam, pada
penderita dengan defisit neurologis yang nyata.
Pemberian oksigen dianjurkan pada keadaan dengan saturasi oksigen
<95%.
Terapi oksigen diberikan padapenderita hipoksia.
Instubasi ETT (Endo Tracheal Tube) atau LMA (Laryngeal Mask
Airway) diperlukan pada penderita dengan hipoksia (pO2<60 mmHg
atau pCO2>50 mmHg), atau syok atau pada penderita yang beresiko
untuk terjadi aspirasi.
b. Stabilisasi Hemodinamik
Berikan cairan kristaloid atau koloid intravena.
Anjurkan pemasangan CVC (Central Venous Catheter).
Usahakan CVC 5-12 mmHg.
Optimalisasi tekanan darah.
Bila tekanan darah sistolik <120 mmHg dan cairan sudah
mencukupi, maka obat-obat vasopressor dapat diberikan secara
titrasi seperti dopamin dosis sedang/tinggi, norepinefrin atau
epinefrin dengan target tekanan darah sistolik berkisar 140 mmHg.

c. Pemeriksaan Awal Fisik Umum
Tekanan darah
Pemeriksaan jantung
Pemeriksaan neurologi umum awal:
i. Derajat kesadaran
ii. Pemeriksaan pupil dan okulomotor
iii. Keparahan hemiparesis
d. Pengendalian Peninggian Tekanan Intrakranial (TIK)
Penatalaksanaan penderita dengan peningkatan tekanan intrakranial
meliputi:
i. Tinggikan posisi kepala 200- 300
ii. Posisi penderita hendaklah menghindari penekanan vena
jugularis
iii. Hindari pemberian cairan glukosa atau cairan hipotonik
iv. Hindari hipertermia
v. Jaga normovolemia
vi. Osmoterapi atas indikasi:
o Manitol 0,25-0,50 gr/kgBB, selama >20 menit,diulangi 4-6 jam
dengan target <310 mOsm/L.
o Kalau perlu, berikan furosemide dengan dosis inisial 1 mg/kgBB
i.v.
vii. Intubasi untuk menjaga normoventilasi (pCO2 35-40).
viii. Kortikosteroid tidak direkomendasi untuk mengatasi edema otak
dan tekanan tinggi intrakranial pada stroke iskemik.
e. Penanganan Transformasi Hemoragik

Tidak ada anjuran khusus tentang terapi transformasi perdarahan
asimtomatik. Terapi transformasi perdarahan simptomatik sama
dengan terapi stroke perdarahan.
f. Pengendalian Kejang
Bila kejang berikan diazepam bolus lambat intravena 5-20 mg dan
diikuti oleh fenitoin loading dose 15-20 mg/kg bolus dengan
kecepatan maksimum 50 mg/menit.
Bila kejang belum teratasi, maka perlu dirawat di ICU.
Pemberian fenitoin memiliki kelebihan yaitu tidak terdapatnya efek
samping menurunnya kesadaran seperti yang terjadi pada pemberian
diazepam, sehingga penilaian derajat kesadaran penderita lebih
akurat.
g. Pengendalian Suhu Tubuh
Setiap penderitaan stroke yang disertai demam harus diobati dengan
antipiretika dan diatasi penyebabnya
Berikan Asetaminofen 650 mg bila suhu lebih dari 38,50C atau
37,50C
Pada penderita febris atau beresiko terjadi infeksi, harus dilakukan
kultur dan hapusan dan diberikan antibiotik
h. Pemeriksaan Penunjang
EKG
Laboratorium (kimia darah, fungsi ginjal, hematologi, faal
hemostasis, kadar gula darah, analisis urin, analisa gas darah, dan
elektrolit)
Bila perlu pada kekurangan perdarahan subaraknoid, lakukan pungsi
lumbal.
i. Pemeriksaan radiologi Foto rontgen dada
ii. CT scankepala

B. Penatalaksanaan umum di ruang rawat
1. Cairan
a. Berikan cairan isotonis
b. Pada umumnya, kebutuhan cairan 30 ml/kgBB/hari
c. Balans cairan diperhitungkan dengan mengukur produksi urin sehari
di tambah dengan pengeluaran cairan yang tidak tampak dan di
tambah lagi 300 ml per derajat celcius pada penderita panas)
d. Elektrolit (natrium, kalium, kalsium, dan magnesium) harus
dikoreksi sesuai dengan hasil analisa gas darah.
2. Nutrisi
a. Nutrisi enteral paling lambat sudah harus diberikan dalam 48 jam
b. Pada keadaan akut, kebutuhan kalori 25-30kkal/kg/hari dengan
komposisi:
Karbohidrat 30-40% dari total kalori
Lemak 20-35% (pada gangguan nafas dapat lebih tinggi 35-55%);
Protein 20-30% (pada keadaan stres kebutuhan protein 1,4-2,0
g/kgBB/hari (pada gangguan fungsi ginjal <0,8 g/kgBB/hari).
3. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi
a. Mobilisasi dan penilaian dini untuk mencegah komplikasi subakut
b. Berikan antibiotik atas indikasi dan usahakan sesuai dengan tes
kultur dan sensitivitas kuman atau minimal terapi empiris sesuai
dengan pola kuman.
c. Pencegahan dekubitus dengan mobilisasi dan/atau memakai kasur
anti-dekubitus.
d. Pencegahan trombosis vena dalam dan emboli paru.
C. Penatalaksanaan tekanan darah pada stroke akut
1. Penatalaksanaan Hipertensi
a. Pada penderita stroke iskemik akut, tekanan darah diturunkan sekitar
15% (sistolik maupun diastolik) dalam 24 jam pertama setelah
awitan apabila tekanan darah sistolik (TDS) >220 mmHg atau
tekanan darah diastolik (TDD) >120 mmHg. Pada penderita stroke

iskemik akut yang akan diberi terapi trombolitik (rtPA), tekanan
darah diturunkan hingga TDS <185 mmHg dan TDD <110 mmHg.
Obat antihipertensi yang digunakan adalah labetalol, nitropaste
nitroprusid, nikardipin, atau ditiazem intravena.
b. Pada penderita stroke perdarahan intraserebral akut apabila TDS
>200 mmHg atau Mean Arterial Pressure (MAP) >150 mmHg,
tekanan darah diturunkan dengan menggunakan obat antihipertensi
intravena secara kontinu dengan pemantauan tekanan darah setiap 5
menit.
c. Apabila TDS >180 mmHg atau MAP >130 mmHg disertai dengan
gejala dan tanda peningkatan tekanan intrakranial, dilakukan
pemantauan tekanan intrakranial. Tekanan darah diturunkan dengan
menggunakan obat antihipertensi intravena secara kontinu atau
intermiten dengan pemantauan tekanan perfusi serebral ≥60 mmHg.
d. Apabila TDS >180 mmHg atau MAP >130 mmHg tanpa disertai
gejala dan tanda peningkatan tekanan intrakranial, tekanan darah
diturunkan secara hati-hati dengan menggunakan obat antihipertensi
intravena kontinu atau intermiten dengan pemantauan tekanan darah
tiap 15 menit, MAP 110 mmHg atau tekanan darah 160/90 mmHg.
e. Pada penderita stroke pendarahan intraserebral dengan TDS 150-220
mmHg, penurunan tekanan darah dengan cepat hingga TDS 140
mmHg cukup aman.
f. Calcium Channel Blocker (nimodipin) telah dilakukan dalam
berbagai panduan penatalaksanaan PSA (perdarahan subarakhnoid)
karena dapat memperbaiki keluaran fungsional penderita apabila
vasospasme serebral telah terjadi.
g. Penurunan tekanan darah pada stroke akut dapat dipertimbangkan
hingga lebih rendah dari target diatas pada kondisi tertentu yang
mengancam target organ lainnya, misalnya diseksi aorta, infark
miokard akut, edema paru, gagal ginjal akut, dan ensefalopati

hipertensif. Target penurunan tersebut adalah 15-25% pada jam
pertama, dan TDS 160/90 mmHg dalam 6 jam pertama.
2. Penatalaksanan Hipotensi Stroke Akut
Hipotensi arterial pada stroke akut berhubungan dengan buruknya
keluaran neurologis terutama bila TDS<100 mmHg atau TDD<70
mmHg. Obat-obat vasopressor yang dapat digunakan antara lain
fenilephrin, dopamin, dan norepinefrin, pemberian obat-obat tersebut
diawasi dengan dosis kecil dan dipertahankan pada tekanan darah
optimal, yaitu TDS berkisar 140 mmHg pada kondisi akut stroke
D. Penatalaksanaan gula darah pada stroke akut
a. Kadar gula darah >150 mg/dL harus dikoreksi sampai batas gula darah
sewaktu 150 mg/dL dengan insulin drip intravena kontinu selama 2-3
hari pertama.
b. Hipoglikemia (kadar gula darah <60 mg/dL atau <80 mg/dL dengan
gejala) diatasi segera dengan dekstrosa 40% iv sampai kembali normal
dan harus dicari penyebabnya.
2.6 Kerangka Teori
Penderita stroke
RS kurang dari 3 jam
Geografi dan demografiFaktor klinisSosial budayaPengetahuan Ekonomi
RS lebih dari 3 jam