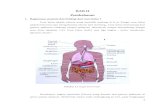BAB II
-
Upload
wahyu-cahyani -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of BAB II

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hemoglobin
1. Definisi dan Pengukuran Hemoglobin
Menurut kamus Kedokteran Dorland, hemoglobin didefinisikan
sebagai pigmen pembawa oksigen sel darah merah (eritrosit), dibentuk
oleh eritrosit yang berkembang dalam sumsum tulang, merupakan
empat rantai polipeptida globin yang berbeda, masing-masing terdiri
dari beberapa ratus asam amino (Kumala, P et al, 1998). Hemoglobin
ini berperan penting dalam pengangkutan oksigen sekaligus ikut serta
dalam pengangkutan karbondioksida dan menentukan kapasitas
penyangga dari darah (Sherwood, 2001).
Hemoglobin adalah pigmen pengangkut oksigen utama dan
terdapat di eritrosit. Merupakan pigmen merah dan menyerap cahaya
maksimum pada panjang gelombang 540 nm. Jika eritrosit dalam
konsentrasi tertentu lisis, terjadi pembebasan hemoglobin yang dapat
diukur secara spektrofotometris pada panjang gelombang ini, yang
konsentrasinya setara dengan densitas optis. Semua bentuk
hemoglobin, termasuk oksihemoglobin, deoksihemoglobin,
methemoglobin adalah metode yang paling luas digunakan karena
reagen dan instrumen dapat dengan mudah dikontrol terhadap standar
yang stabil dan handal (Sacher, 2004).
Hemoglobin dapat diukur dengan menggunakan
spektrofotometer yang tersedia di kamar praktik dokter atau di
sebagian besar laboratorium umum, namun metode yang paling
banyak digunakan adalah penghitung sel otomatis yang secara
langsung mengukur hemoglobin di dalam saluran sel darah merah
(Sacher, 2004).
5

6
2. Kadar Hemoglobin
Pemeriksaan kadar hemoglobin bertujuan untuk menetapkan
atau mengetahui kadar hemoglobin dalam darah (Asmadi, 2008).
Kisaran cut off point untuk kadar hemoglobin menurut WHO adalah
sebagai berikut :
Tabel 1 : Cut Off Point Kadar Hemoglobin Menurut WHO
Populasi Non-anemia*Anemia*
Ringan* Sedang* Berat*Anak 6-59 bulan ≥110 100-109 70-99 <70Anak 5-11 tahun ≥115 110-114 80-109 <80Anak 12-14 tahun ≥120 110-119 80-109 <80Wanita tidak hamil (≥15 tahun)
≥120 110-119 80-109 <80
Wanita hamil ≥110 100-109 70-99 <70Laki-laki (≥15 tahun)
≥130 110-129 80-109 <80
*Hemoglobin dalam gram per liter (WHO, 2011).
3. Anemia pada Kehamilan
Pada wanita normal, volume darah rata-rata pada atau
menjelang aterm adalah 50% lebih tinggi daripada volume pada
keadaan tidak hamil. Volume darah ibu mulai meningkat selama
trimester pertama, meningkat paling pesat pada trimester kedua dan
mulai meningkat dengan kecepatan jauh lebih lambat pada trimester
ketiga hingga mendatar pada beberapa minggu terakhir kehamilan
(Cunningham et al, 2009).
Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga
memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma
bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun, peningkatan
volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika
dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan
konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi (Prawirohardjo, 2008).

7
Puncak peningkatan volume plasma ini terjadi pada kehamilan 32
minggu (Cunningham et al, 2009).
Ekspansi volume plasma merupakan penyebab anemia
fisiologik pada kehamilan. Volume plasma yang terekspansi
menurunkan hematokrit (Ht), konsentrasi hemoglobin darah (Hb) dan
hitung eritrosit, tetapi tidak menurunkan jumlah absolut Hb atau
eritrosit dalam sirkulasi. Mekanisme yang mendasari perubahan ini
belum jelas. Ada spekulasi bahwa anemia fisiologik dalam kehamilan
bertujuan menurunkan viskositas darah maternal sehingga
meningkatkan perfusi plasenta dan membantu penghantaran oksigen
serta nutrisi ke janin (Prawirohardjo, 2008).
Tabel 2 : Nilai Batas untuk Anemia pada Perempuan
Status Kehamilan Hemoglobin (g/dl) Hematokrit (%)Tidak hamil 12,0 36Hamil
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
11,010,511,0
333233
(Prawirohardjo, 2008)
4. Penyebab Anemia pada Kehamilan
Penyebab anemia tersering adalah defisiensi zat-zat nutrisi.
Seringkali defisiensinya bersifat multipel dengan manifestasi klinik
yang disertai infeksi, gizi buruk, atau kelainan herediter seperti
hemoglobinopati. Namun, penyebab mendasar anemia nutrisional
meliputi asupan yang tidak cukup, absorbsi yang tidak adekuat,
bertambahnya zat gizi yang hilang, kebutuhan yang berlebihan dan
kurangnya utilisasi nutrisi hemopoetik (Prawirohardjo, 2008).
Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh
defisiensi besi yang memperlihatkan gambaran eritrositik hipokrom
pada apusan darah tepi. Penyebab tersering kedua adalah anemia

8
megaloblastik yang dapat disebabkan oleh defisiensi asam folat dan
defisiensi vitamin B12. Penyebab anemia lainnya yang jarang ditemui
antara lain adalah hemoglobinopati, proses inflamasi, toksisitas zat
kimia dan keganasan (Prawirohardjo, 2008).
B. Prematuritas
1. Definisi
Persalinan prematur (preterm) adalah dimulainya proses
persalinan sebelum usia gestasi 37 minggu (Norwitch & Schorge,
2007). Persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada
umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari pertama haid
terakhir. Menurut WHO, menyatakan bahwa bayi prematur adalah
bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang.
Sedangkan menurut Himpunan Kedokteran Fetomaternal (POGI) di
Semarang tahun 2005 menetapkan bahwa persalinan preterm adalah
persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu
(Prawirohardjo, 2008).
Insidensi kelahiran bayi prematur ini antar 7-10 % dari seluruh
kelahiran. Kelahiran ini bertanggungjawab terhadap 85% dari semua
morbiditas dan mortalitas perinatal. Persalinan bayi prematur ini
menunjukkan kegagalan mekanisme yang bertanggungjawab untuk
mempertahankan kondisi tenang uterus selama kehamilan atau adanya
gangguan yang menyebabkan menjadi singkatnya kehamilan atau
membebani jalur persalinan normal sehingga memicu dimulainya
proses persalinan secara dini (Norwitch & Schorge, 2007).
2. Penyebab Prematuritas
Meiss et al. dalam Cunningham (2006) menganalisa kausa
kelahiran sebelum usia gestasi 37 minggu pada sebuah studi populasi
kehamilan tunggal yang dilakukan di Maternal Fetal Medicine Units

9
Network. Sekitar 28 persen kelahiran preterm diindikasikan disebabkan
oleh preeklamsia (43%), gawat janin (27%), pertumbuhan janin
terhambat (10%), ablasio plasenta (7%), dan kematian janin (7%).
Tujuh puluh dua persen sisanya disebabkan oleh persalinan preterm
spontan dengan atau tanpa pecah ketuban. Ibu dengan plasenta previa
dan kehamilan multipel, yang keduanya sering disertai dengan
kelahiran preterm, disingkirkan dari analisis ini (Cunningham et al,
2006).
Perilaku merokok, gizi buruk dan penambahan berat badan yang
kurang baik selama kehamilan serta penggunaan obat seperti kokain
atau alkohol telah dilaporkan memainkan peranan penting pada
kejadian dan hasil akhir bayi dengan berat lahir rendah. Telah diamati
pula selama bertahun-tahun kelahiran preterm merupakan suatu
kondisi yang terjadi secara familial. Selain itu, infeksi cairan amnion
dan korioamnion yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme telah
memunculkan penjelasan berbagai kasus pecah ketuban dan persalinan
preterm yang tidak dapat dijelaskan hingga kini (Cunningham et al,
2006).
C. Berat Badan Lahir Rendah
1. Definisi
Berat badan lahir rendah (BBLR) telah didefinisikan oleh
WHO sebagai berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram.
Prevalensi BBLR adalah 15,5 %, yang berarti bahwa sekitar 20,6 juta
bayi yang lahir setiap tahun, 96,5% diantaranya di Negara
berkembang. Terdapat variasi yang signifikan insiden BBLR tiap
wilayah, insidensi tertinggi di Asia Selatan dan Tengah (27,1%) dan
terendah di Eropa (6,4%) (WHO, 2011).
BBLR menjadi konsekuensi dari kelahiran bayi prematur
(didefinisikan sebagai kelahiran sebelum 37 minggu) atau karena

10
ukuran yang kecil untuk usia kehamilan atau Short Gestational Age
(SGA), yang didefinikan sebagai berat badan lahir untuk usia
kehamilan <10 persentil) atau keduanya. Selain itu , tergantung pada
berat badan lahir referensi yang digunakan, proporsi varibel tapi kecil.
Pertumbuhan intrauterin yang terhambat didefinisikan sebagai
pertumbuhan janin yang lebih lambat dibandingkan normalnya,
biasanya bertanggungjawab atas SGA (WHO, 2011).
Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram)
merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap
kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan atas 2 kategori
yaitu BBLR karena premature dan BBLR karena intrauterine growth
retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat
badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR karena IUGR
karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita
penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau saat
kehamilan. (Depkes, 2005)
2. Faktor yang Mempengaruhi Berat Bayi Lahir Rendah
Faktor penyebab kejadian BBLR sering tidak diketahui
ataupun kalau diketahui faktor penyebabnya tidaklah berdiri sendiri,
antara lain yaitu faktor genetik atau kromosom, infeksi, bahan toksik,
radiasi, insufisiensi atau disfungsi plasenta, faktor nutrisi serta faktor-
faktor lain meliputi merokok, peminum alkohol, bekerja berat masa
hamil, plasenta previa, kehamilan ganda, obat-obatan dan sebagainya
(Mochtar, 1998).
Menurut Hobel dalam Chairunita (2006) menyatakan bahwa
peristiwa-peristiwa tertentu yang timbul selama masa prenatal
(kehamilan) dan intrapartum (persalinan) dapat memberi pengaruh
kurang baik terhadap bayi dalam perkembangan selanjutnya.

11
Tabel 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin
dalam kandungan
Unsur Ibu Interaksi Ibu-Janin Unsur JaninUnsur GenetikStatus Gizi Saat iniStatus gizi sebelumnyaTinggi badanKenaikan berat badan selama hamilUmurParitasJarak kehamilan terakhirKeadaan kesehatanAdaptasi terhadap Lingkungan
PerokokPolusiKetinggianSuhuInfeksiDiabetesToksemiaAktivitas Fisik IbuStruktur Plasenta
Jenis KelaminRasUmur KehamilanKembarKetidakcocokan ibu-janin
(Chairunita, 2006)
D. Nilai APGAR
1. Definisi
Nilai APGAR adalah sebuah pemeriksaan cepat yang
memperlihatkan keadaan bayi pada menit ke-1 dan menit ke-5 setelah
kelahiran. Skor pada menit ke-1 menentukan seberapa baik toleransi
bayi dalam proses bernafasnya. Skor pada menit ke-5 menjelaskan
pada dokter seberapa baik kemampuan bayi hidup di luar rahim ibu.
Pemeriksaan ini dilakukan bertahap selama 10 menit setelah
kelahiran. Pemeriksaan APGAR ini dilakukan oleh dokter, perawat
atau bidan untuk memeriksa kemampuan bernafas bayi, denyut
jantung, tonus otot, refleks dan warna kulit (Zieve, D. & Kaneshiro,
N. K., 2011).
Nilai APGAR digunakan untuk menggambarkan kondisi bayi
selama beberapa menit pertama kehidupan. Skor ini dinilai pada menit
pertama dan kelima kehidupan. Jika skor masih dibawah 7 atau bayi

12
memerlukan resusitasi maka penilaian ini diteruskan setiap 5 menit
sampai normal atau sampai 20 menit (Lissauer & Fanaroff, 2008).
Tabel 4 : Nilai APGAR
Aspek yang dinilai
Nilai APGAR0 1 2
Denyut jantung Tidak ada Lambat (<100 kali/menit)
>100 kali/menit
Pernafasan Tidak ada Lambat, irregular
Bagus, menangis
Tonus Otot Lemah Sedikit fleksi pada ekstrimitas
Gerakan aktif
Kepekaan reflex Tidak ada Meringis Batuk, bersin,menangis
Warna Biru atau pucat
Badan merah muda, ekstremitas biru
Merah muda
(Lissauer & Fanaroff, 2008)
Nilai APGAR berkisar antara 1-10. Nilai tertinggi merupakan
indikasi bayi yang terbaik setelah kelahiran. Nilai antara 7, 8, 9 adalah
nilai normal dan menandakan bahwa bayi yang baru lahir tersebut
memiliki kesehatan yang baik. Nilai di bawah 7 menandakan bayi
tersebut memerlukan perhatian medis (Zieve, D. & Kaneshiro, N. K.,
2011).
2. Faktor yang Mempengaruhi Nilai APGAR
Nilai rendah pada APGAR biasanya disebabkan karena bayi
kesulitan bernafas, persalinan seksio sesaria, dan adanya cairan pada
saluaran respirasi bayi (Zieve, D. & Kaneshiro, N. K., 2011).

13
Tabel 5: Kondisi yang berhubungan dengan adaptasi neonatal terhadap
kehidupan ekstrauterin
Fetal Maternal PlasentalPreterm Anestesi umum KorioamnionitisKelahiran multiple Terapi obat-obatan
maternalPlasenta previa
Persalian dibantu dengan forsep atau vakum
Hipertensi diinduksi oleh kehamilan
Abrupsio plasenta
Presentasi sungsang atau abnormal
Hipertensi kronik Prolaps tali pusat
Seksio sesaria darurat Infeksi maternal Prolaps tali pusatPertumbuhan janin terhambat
Diabetes melitus maternal
Cairan amnion terwarnai mekonium
Polihidramnion
Denyut jantung janin abnormal
Oligohidramnion
Malformasi congenitalAnemiaInfeksi
(Lissauer & Fanaroff, 2008)
E. Hubungan Kadar Hemoglobin Maternal dengan Luaran Perinatal
Hemoglobin merupakan pemasok utama oksigen yang terdapat di
dalam eritrosit. Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga
memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma
bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun, peningkatan volume
plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan
peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin
akibat hemodilusi. Batas kadar hemoglobin yang masih dapat ditolerir
untuk ibu hamil adalah 11 gr/dl. Jika kurang dari nilai tersebut ibu hamil
mengalami anemia (Prawirohardjo, 2008).
Penurunan konsentrasi hemoglobin menyebabkan fungsinya
sebagai pemasok oksigen ke seluruh tubuh termasuk plasenta akan
berkurang. Janin yang terganggu asupan oksigennya yang berhubungan

14
dengan insufisiensi uteroplasenta akan mengalami hipoksia, hal ini
menyebabkan stress janin (Norwitz & Schorge, 2008).
Terdapat bukti klinis dan laboratorium yang meningkat bahwa
banyak persalinan premature disebabkan karena stress ibu dan janin, yang
mengaktifkan sel-sel dalam plasenta, desidua, dan membran janin untuk
memproduksi corticotropin releasing hormone yang pada gilirannya
dapat meningkatkan produksi prostaglandin dalam jaringan untuk
menginduksi proses persalinan (Lockwood, 1999).
Mekanisme bayi prematur menunjukkan adanya kegagalan
mekanisme yang bertanggungjawab untuk mempertahankan kondisi
tenang uterus selama kehamilan atau adanya gangguan yang menyebabkan
menjadi singkatnya kehamilan atau membebani jalur persalinan normal
sehingga memicu dimulainya proses persalinan secara dini (Norwitz &
Schorge, 2008).
Persalinan prematur memiliki konsekuensi kelahiran bayi dengan
berat badan rendah. Selain itu BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) juga
dapat disebabkan karena intrauterine growth retardation (IUGR) (Depkes,
2005). Pertumbuhan janin yang mulai berkurang ini disebabkan karena
penurunan suplai nutrien (glukosa, oksigen, asam amino dan faktor
pertumbuhan lain). Gangguan pertumbuhan ini terjadi dengan urutan tetap
(jaringan subkutan, rangka aksial, organ vital) (Norwitz & Schorge, 2008).
Gangguan pertumbuhan jaringan sub kutan, rangka aksial serta
organ vital dapat menurunkan fungsi dari ketiganya. Sehingga penilaian
APGAR pada bayi baru lahir dengan cara mengobservasi denyut jantung,
pernafasan, tonus otot, kepekaan refleks dan warna kulit akan didapatkan
nilai APGAR yang rendah.

15
Dengan demikian berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan
bahwa kadar hemoglobin maternal berhubungan dengan luaran perinatal
yang merugikan. Antara lain kelahiran bayi prematur, BBLR, IUGR dan
nilai APGAR yang rendah sehingga membutuhkan perhatian khusus.
.

16

17
F. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan
prematuritas
2. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan luaran
berat badan lahir rendah
3. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan luaran
Intra Uterine Growth Retardation (IUGR)
4. Ada hubungan antara kadar hemoglobin maternal dengan nilai
APGAR pada bayi