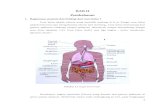BAB II
-
Upload
shazhan828 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
1
Transcript of BAB II
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Rumah Sakit
Menurut World Health Organisation (WHO) rumah sakit merupakan
pusat kegiatan dari sebuah organisasi masyarakat dan kesehatan yang berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan yang sempurna kepada seluruh masyarakat
dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakit, baik untuk pasien rawat
jalan maupun rawat inap, juga sebagai tempat untuk penelitian dan pelatihan
tenaga kesehatan.
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan dengan inti
kegiatannya berupa pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non
medis, pelayanan dan asuhan keperawata, pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan, pelayanan rujukan uapaya kesehatan, administarasi umum
dan keuangan. Pelayanan rumah sakit pada hakekatnya merupakan sistem
proses yang aktivitasnya saling tergantung satu dengan lainnya. Unsur-unsur
yang saling berinteraksi dalam mendukung terciptanya pelayanan prima adalah
sumber daya manusia (medis, paramedis dan non medis), sarana dan prasarana,
peralatan, obat-obatan, bahan pendukung dan lingkungan.
Fungsi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.983/Menkes/Sk/XI/1992, tentang pedoman organisasi rumah sakit
umum yaitu menyelenggarakan pelayanan medis, menyelenggarakan pelayanan
penunjang medis dan non medis, menyelenggarakan pelayanan dan asuhan
keperawatan, menyelenggarakan pelayanan dan rujukan, menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
serta menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
B. Limbah Rumah Sakit
1. Definisi Limbah Rumah Sakit
1
Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari
kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang
dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia
beracun, dan sebagian bersifat radioaktif ( Depkes, 2006).
Limbah rumah sakit yaitu buangan dari kegiatan pelayanan yang tidak
dipakai ataupun tidak berguna termasuk dari limbah pertamanan. Limbah
rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat
mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan
hidup apabila tidak di kelola dengan baik. Limbah rumah sakit adalah semua
limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat dan
cair ( KepMenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004).
Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik dan
anorganik yang umumnya diukur dengan parameter BOD, COD, TSS, dan
lain-lain. Sedangkan limbah padat rumah sakit terdiri atas sampah mudah
membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain-lain.
Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya
pengelolaan yang baik meliputi alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana
pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah
sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
Limbah rumah sakit yang mengandung mikroorganisme patogen atau
bahan kimia beracun berbahaya dapat menyebabkan penyakit infeksi dan
tersebar ke lingkungan rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan
kesehatan yang kurang memadai, kesalahan penanganan bahan-bahan
terkontaminasi dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana
sanitasi yang masib buruk. Pembuangan limbah yang berjumlah cukup besar
ini paling baik jika dilakukan dengan memilah-milah limbah ke dalam
pelbagai kategori. Untuk masing-masing jenis kategori diterapkan cara
pembuangan limbah yang berbeda. Prinsip umum pembuangan limbah rumah
2
sakit adalah sejauh mungkin menghindari risiko kontaminsai dan trauma
(injury).
2. Sumber dan Karakteristik Limbah Rumah Sakit
Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah
yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.
Apabila dibanding dengan kegiatan instansi lain, maka dapat dikatakan
bahwa jenis sampah dan limbah rumah sakit dapat dikategorikan kompleks.
Dalam melakukan fungsinya rumah sakit menimbulkan berbagai
buangan dan sebagian dari limbah tersebut merupakan limbah berbahaya.
Sumber limbah cair rumah sakit dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
a. Limbah cair infeksius : air limbah yang berhubungan dengan tindakan
medis seperti pemeriksaan mikrobioogis dari poliklinik, perawatan,
penyakit menular dan lain-lain.
b. Limbah cair domestik : air limbah yang tidak berhubungan dengan
tindakan medis yaitu berupa air limbah kamar mandi, toilet, dapur dan
laundry.
c. Limbah cair kimia : air limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan
kimia dalam tindakan medis, laboratorium dan sterilisasi, riset dan
lain-lain (Chandra, 2007).
Pada dasarnya sumber limbah padat di rumah sakit dapat
diklasifikasikan menjadi limbah medis dan limbah non medis.
1. Limbah medis
Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin,
pembedahan dan di unit-unit resiko tinggi. Limbah ini mungkin
berbahaya dan mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi
umum dan staf rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas
sebagai resiko tinggi. contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau
3
pembungkus yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi,
jarum-jarum dan semprit bekas, kantung urin dan produk darah
Limbah medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari
tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien. Termasuk dalam
kegiatan tersebut juga kegiatan medis di ruang poliklinik, perawatan,
bedah, kebidanan, otopsi dan ruang laboratorium. Limbah padat medis
sering juga disebut sampah biologis. Sampah biologis terdiri dari :
a. Limbah medis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, ruang
peralatan, ruang bedah, atau botol bekas injeksi, kateter, plester,
masker.
b. Limbah patologis yang dihasilkan dari ruang poliklinik, bedah,
kebidanan, atau ruang otopsi, misalnya plasenta, jaringan tubuh,
potongan anggota badan. Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi
dan sebaiknya di autoklaf sebelum keluar dari unit patologi.
Limbah tersebut harus diberi label biohazard.
c. Limbah laboratorium yang dihasilkan dari pemeriksaan
laboratorium diagnostik atau penelitian, misalnya sediaan atau
media sampel dan bangkai binatang percobaan.
d. Limbah radioaktif mencakup benda padat,cair dan gas yang
terkontaminasi radionuklida. Walaupun limbah ini tidak
menimbulkan persoalan pengendalian infeksi di rumah sakit,
pembuangannya secara aman perlu diatur dengan baik.
2. Limbah Nonmedis
Limbah padat non medis adalah semua sampah padat diluar limbah
padat medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan, seperti
kantor/administrasi, unit perlengkapan, ruang tunggu, ruang inap, unit
gizi atau dapur, halaman parkir dan taman, serta unit pelayanan.
4
Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus atau kantong dan
plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan. Meskipun tidak
menimbulkan resiko sakit, limbah tersebut cukup merepotkan karena
memerlukan tempat yang besar untuk mengangkut dan membuangnya.
Selain di bedakan menurut jenis unit penghasil, limbah rumah sakit
dapat dibedakan berdasarkan karakteristik limbah yaitu :
a. Limbah Infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme
patogen yang yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan
organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk
menularkan penyakit pada manusia rentan.
b. Limbah gas adalah semua limbah yng berbentuk gas yang berasal
dari hasil kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator,
dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat
sitotoksis.
c. Limbah sangat infeksius adalah limbah berasal dari pembiakan
dan stock bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang
percobaan, dan bahan lain yang telah diinokulasi, terinfeksi atau
kontak dengan bahan yang sangat infeksius.
d. Limbah sitotoksis adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi
dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi
kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau
menghambat pertumbuhan sel hidup (Asmadi, 2013).
C. Kualitas Limbah Padat dan Cair
1. Kualitas Limbah Padat
Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah di mulai dari
sumber, mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang
berbahaya dan beracun, pengelolaan stok kimia dan farmasi, dan peralatan
di mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan.
5
Pemilahan harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan
limbah. Limbah padat yang akan/dapat di manfaatkan lagi harus melalui
proses sterilisasi. Pengolahan dan pemusnahan limbah medis tidak
diperbolehkan membuang langsung ke tempat pembuangan akhir sebelum di
anggap aman bagi kesehatan (Depkes RI, 2004).
2. Parameter Kualitas Limbah Cair
Menurut pendapat Okun dan Ponghis yang dikutip Soeparman dan
Soeparmin (2002) berbagai kualitas limbah cair yang penting untuk
diketahui adalah bahan padat terlarut (dissolved solid), kebutuhan oksigen
biokimia (Biochemical Oxygen Demand), kebutuhan oksigen kimiawi
(Chemical Oxygen Demand) dan pH (power Hidrogen).
a. Bahan padat terlarut
Bahan padat terlarut penting diketahui terutama apabila limbah cair
akan dipergunakan setelah pengolahan.
b. Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Merupakan ukuran kandungan bahan organik dalam limbah cair dan
ditentukan dengan mengukur jumlah oksigen yang diserap oleh akibat
adanya mikroorganisme selama satu periode waktu tertentu. Juga
merupakan petunjuk dari pengaruh yang diperkirakan terjadi pada
badan air penerima berkaitan dengan pengurangan kandungan
oksigennya.
c. Chemical Oxygen Demand (COD)
Merupakan ukuran persyaratan kebutuhan oksigen limbah cair yang
berada dalam kondisi tertentu, yang ditentukan dengan menggunakan
suatu oksigen kimiawi.
d. pH (Keasaman)
6
pH merupakan ukuran keasaman atau kebasaan limbah cair. pH
menunjukkan perlu atau tidaknya pengolahan pendahuluan untuk
mencegah terjadinya gangguan pada proses pengolahan limbah cair.
D. Pengelolaan Limbah Padat dan Cair Rumah Sakit
1. Pengelolaan Limbah Padat
Pengolaan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi
volume, konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau
kegiatan, melalui proses fisika, kimia atau hayati. Dalam pelaksanaan
pengelolaan limbah, upaya pertama yang harus dilakukan adalah upaya
preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang dikeluarkan ke
lingkungan yang meliputi upaya mengurangi limbah pada sumbernya, serta
upaya pemanfaatan limbah.
Program minimisasi limbah yang baru mulai digalakkan di Indonesia,
bagi rumah sakit masih merupakan hal baru. Tujuannya untuk mengurangi
jumlah limbah dan pengolahan limbah yang masih mempunyai nilai
ekonomis. Berbagai upaya telah dipergunakan untuk mengungkapkan
pilihan teknologi mana yang terbaik untuk pengolahan limbah, khususnya
limbah berbahaya antara lain reduksi limbah (waste reduction), minimisasi
limbah (waste minimization), pemberantasan limbah (waste abatement),
pencegahan pencemaran (waste prevention), dan reduksi pada sumbemya
(source reduction).
Reduksi limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus
dilaksanakan pertama kali karena upaya ini bersifat preventif yaitu
mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang keluar dan proses
produksi. Reduksi limbah pada sumbernya adalah upaya mengurangi
volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang akan keluar
ke lingkungan secara preventif langsung pada sumber pencemar, hal ini
banyak memberikan keuntungan yakni meningkatkan efisiensi kegiatan
7
serta mengurangi biaya pengolahan limbah dan pelaksanaannya relatif
murah.
Berbagai cara yang digunakan untuk reduksi limbah pada sumbernya
adalah:
a. House keeping yang baik, usaha ini dilakukan oleh runah sakit dalam
menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah terjadinya ceceran,
tumpahan atau kebocoran bahan serta menangani limbah yang terjadi
dengan sebaik mungkin.
b. Segregasi aliran limbah, yakni memisahkan berbagai jenis aliran
limbahmenurut jenis komponen, konsentrasi atau keadaanya, sehingga
dapat mempermudah, mengurangi volume, atau mengurangi biaya
pengolahan limbah.
c. Pelaksanaan preventive maintenance, yakni pemeliharaan/penggantian
alat atau bagian alat menurut waktu yang telah dijadwalkan.
d. Pengelolaan bahan (material inventory), adalah suatu upaya agar
persediaan bahan selalu cukup untuk menjamin kelancaran proses
kegiatan, tetapi tidak berlebihan sehiugga tidak menimbulkan
gangguan lingkungan, sedangkan penyimpanan agar tetap rapi dan
terkontrol.
e. Pengaturan kondisi proses dan operasi yang baik, sesuai dengan
petunjuk pengoperasian/penggunaan alat dapat meningkatkan
efisiensi.
f. Penggunaan teknologi bersih yakni pemilikan teknologi proses
kegiatan yang kurang potensi untuk mengeluarkan limbah B3 dengan
efisiensi yang cukup tinggi, sebaiknya dilakukan pada saat
pengembangan rumah sakit baru atau penggantian sebagian unitnya.
Kebijakan kodifikasi penggunaan warna untuk memilah-milah limbah
di seluruh rumah sakit harus memiliki warna yang sesuai, sehingga limbah
8
dapat dipisah-pisahkan di tempat sumbernya, perlu memperhatikan halhal
berikut:
1. Bangsal harus memiliki dua macam tempat limbah dengan dua warna,
satu untuk limbah klinik dan yang lain untuk bukan klinik.
2. Semua limbah dari kamar operasi dianggap sebagai limbah klinik.
3. Limbah dari kantor, biasanya berupa alat-alat tulis, dianggap sebagai
limbah bukan klinik.
4. Semua limbah yang keluar dari unit patologi harus dianggap sebagai
limbah klinik dan perlu dinyatakan aman sebelum dibuang.
Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan
kodifikasi dengan warna yang menyangkut pemisahan limbah adalah hal-hal
hal-hal berikut:
1. Limbah harus dipisahkan dari sumbernya.
2. Semua limbah berisiko tinggi hendaknya diberi label jelas.
3. Perlu digunakan kantung plastik dengan warna-warna yang berbeda,
yang menunjukkan ke mana plastik harus diangkut untuk insinerasi
atau dibuang.
Di beberapa negara, kantung plastik cukup mahal sehingga sebagai
ganti dapat digunakan kantung kertas yang tahan bocor (dibuat secara lokal
sehingga dapat diperoleh dengan mudah). Kantung kertas ini dapat
ditempeli dengan strip berwarna, kemudian ditempatkan di tong dengan
kode warna di bangsal dan unit-unit lain.
a. Penyimpanan limbah
Cara penyimpanan limbah adalah sebagai berikut :
1. Kantung-kantung dengan warna harus dibuang jika telah berisi 2/3
bagian. Kemudian diikat bagian atasnya dan diberi label yang
jelas.
9
2. Kantung harus diangkut dengan memegang lehernya, sehingga
kalau dibawa mengayun menjauhi badan, dan diletakkan di
tempat-tempat tertentu untuk dikumpulkan.
3. Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung
dengan warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirim ke
tempat yang sesuai.
4. Kantung harus disimpan di kotak-kotak yang kedap terhadap kutu
dan hewan perusak sebelum diangkut ke tempat pembuangannya.
b. Penanganan Limbah
Petugas pengangkut limbah memperlakukan limbah sebagai
berikut:
1. Kantung-kantung dengan kode warna hanya boleh diangkut bila
telah ditutup.
2. Kantung dipegang pada lehernya.
3. Petugas harus mengenakan pakaian pelindung, misalnya dengan
memakai sarung tangan yang kuat dan pakaian terusan (overal),
pada waktu mengangkut kantong tersebut.
4. Jika terjadi kontaminasi diluar kantung diperlukan kantung baru
yang bersih untuk membungkus kantung baru yang kotor tersebut
seisinya (double bagging).
5. Petugas diharuskan melapor jika menemukan benda-benda tajam
yang dapat mencederainya di dalam kantung yang salah.
6. Tidak ada seorang pun yang boleh memasukkan tangannya kedalam
kantung limbah.
c. Pengangkutan limbah
Kantung limbah dikumpulkan dan sekaligus dipisahkan
menurut kode warnanya. Limbah bagian bukan klinik misalnya dibawa
10
ke kompaktor, limbah bagian klinik dibawa ke insinerator.
Pengangkutan dengan kendaran khusus (mungkin ada kerjasama
dengan Dinas Pekerjaan Umum) kendaraan yang digunakan untuk
mengankut limbah tersebut sebaiknya dikosongkan dan dibersihkan
tiap hari, kalau perlu (misalnya bila ada kebocoran kantung limbah)
dibersihkan dengan menggunakan larutan klorin.
d. Pembuangan Limbah
Setelah dimanfaatkan dengan kompaktor, limbah bukan klinik
dapat dibuang ditempat penimbunan sampah (land-fill site), limbah
klinik harus dibakar (insinerasi), jika tidak mungkin harus ditimbun
dengan kapur dan ditanam limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari
yang sama sehingga tidak sampai membusuk.
Kemudian mengenai limbah gas, upaya pengelolaannya lebih
sederhana dibanding dengan limbah cair, pengelolaan limbah gas tidak
dapat terlepas dari upaya penyehatan ruangan dan bangunan
khususnya dalam memelihara kualitas udara ruangan (indoor) yang
antara lain disyaratkan agar:
a. Tidak berbau (terutania oleh gas H2S dan Amoniak).
b. Kadar debu tidak melampaui 150 Ug/m3 dalam pengukuran rata-
rata selama 24 jam.
c. Angka kuman. Ruang operasi: kurang dan 350 kalori/m3 udara
dan bebas kuman pada gen (khususnya alpha streptococus
haemoliticus) dan spora gas gangrer. Ruang perawatan dan
isolasi: kurang dan 700 kalori/m3 udara dan bebas kuman
patogen. Kadar gas dan bahan berbahaya dalam udara tidak
melebihi konsentrasi maksimum yang telah ditentukan. Rumah
sakit yang besar mungkin mampu membeli insinerator sendiri.
Insinerator berukuran kecil atau menengah dapat membakar pada
11
suhu 1300-1500oC atau lebih tinggi dan mungkin dapat mendaur
ulang sampai 60% panas yang dihasilkan untuk kebutuhan energi
rumah sakit. Suatu rumah sakit dapat pula memperoleh
penghasilan tambahan dengan melayani insinerasi limbah rumah
sakit yang berasal dari rumah sakit lain. Insinerator modern yang
baik tentu saja memiliki beberapa keuntungan antara lain
kemampuannya menampung limbah klinik maupun bukan klinik,
termasuk benda tajam dan produk farmasi yang tidak terpakai.
Jika fasilitas insinerasi tidak tersedia, limbah klinik dapat
ditimbun dengan kapur dan ditanam. Langkah-langkah pengapuran
(liming) tersebut meliputi hal-hal berikut:
a. Menggali lubang, dengan kedalaman sekitar 2,5 meter.
b. Tebarkan limbah klinik di dasar lubang sampai setinggi 75 cm.
c. Tambahkan lapisan kapur.
d. Lapisan limbah yang ditimbun lapisan kapur masih bisa
ditambahkan sampai ketinggian 0,5 meter di bawah permukaan
tanah.
e. Akhirnya lubang tersebut harus ditutup dengan tanah.
2. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit
Prinsip dasar pengolahan air limbah adalah menghilangkan atau
mengurangi kontaminan yang terdapat didalamair limbah tersebut sehingga
hasil olahan limbah dapat dimanfaatkan kembali atau tidak mengganggu
lingkungan apabila dibuang ke tanah atau ke badan air.
Secara spesifik pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi
jumalah padatan tersuspensi, mengurangi jumlah padatan terapung,
mengurangi jumlah bahan organik, membunuh bakteri patogen, mengurangi
jumlah bahan kimia, serta mengurangi unsur lain yang dapat menimbulkan
dampak negative terhadap ekosistem.
12
Guna meningkatkan mutu lingkungan dan sanitasi di rumah sakit
maka perlu dibuatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baik
dan teruji prosesnya. Dengan proses yang baik diharapkan kualitas effluent
yang dikeluarkan rumah sakit dapat mencapai baku mutu yang ditetapkan.
Limbah rumah sakit mengandung bermacam-macam mikroorganisme,
bahan-bahan organik dan an-organik. Beberapa contoh fasilitas atau Unit
Pengelolaan Limbah (UPL) di rumah sakit antara lain sebagai berikut:
a. Kolam Stabilisasi Air Limbah (Waste Stabilization Pond System)
Sistem pengelolaan ini cukup efektif dan efisien kecuali masalah
lahan, karena kolam stabilisasi memerlukan lahan yang cukup luas;
maka biasanya dianjurkan untuk rumah sakit di luar kota (pedalaman)
yang biasanya masih mempunyai lahan yang cukup. Sistem ini terdiri
dari bagian-bagian yang cukup sederhana yakni :
1. Pump Swap (pompa air kotor).
2. Stabilization Pond (kolam stabilisasi) 2 buah.
3. Bak Klorinasi
4. Control room (ruang kontrol)
5. Inlet
6. Incinerator antara 2 kolam stabilisasi
7. Outlet dari kolam stabilisasi menuju sistem klorinasi.
b. Kolam oksidasi air limbah (Waste Oxidation Ditch Treatment
System)
Sistem ini terpilih untuk pengolahan air limbah rumah sakit di
kota, karena tidak memerlukan lahan yang luas. Kolam oksidasi dibuat
bulat atau elips, dan air limbah dialirkan secara berputar agar ada
kesempatan lebih lama berkontak dengan oksigen dari udara (aerasi).
Kemudian air limbah dialirkan ke bak sedimentasi untuk
13
mengendapkan benda padat dan lumpur. Selanjutnya air yang sudah
jernih masuk ke bak klorinasi sebelum dibuang ke selokan umum atau
sungai. Sedangkan lumpur yang mengendap diambil dan dikeringkan
pada Sludge drying bed (tempat pengeringan Lumpur). Sistem kolam
oksidasi ini terdiri dari :
1. Pump Swap (pompa air kotor)
2. Oxidation Ditch (pompa air kotor)
3. Sedimentation Tank (bak pengendapan)
4. Chlorination Tank (bak klorinasi)
5. Sludge Drying Bed ( tempat pengeringan lumpur, biasanya 1-2
petak).
6. Control Room (ruang kontrol)
c. Anaerobic Filter Treatment System
Sistem pengolahan melalui proses pembusukan anaerobik
melalui filter/saringan, air limbah tersebut sebelumnya telah
mengalami pretreatment dengan septic tank (inchaff tank). Proses
anaerobic filter treatment biasanya akan menghasilkan effluent yang
mengandung zat-zat asam organik dan senyawa anorganik yang
memerlukan klor lebih banyak untuk proses oksidasinya. Oleh sebab
itu sebelum effluent dialirkan ke bak klorida ditampung dulu di bak
stabilisasi untuk memberikan kesempatan oksidasi zat-zat tersebut di
atas, sehingga akan menurunkan jumlah klorin yang dibutuhkan pada
proses klorinasi nanti. Sistem Anaerobic Treatment terdiri dari
komponen-komponen antara lain sebagai berikut :
1. Pump Swap (pompa air kotor)
2. Septic Tank (inhaff tank)
3. Anaerobic filter.
4. Stabilization tank (bak stabilisasi)
14
5. Chlorination tank (bak klorinasi)
6. Sludge drying bed (tempat pengeringan lumpur)
7. Control room (ruang kontrol)
Sesuai dengan debit air buangan dari rumah sakit yang juga
tergantung dari besar kecilnya rumah sakit, atau jumlah tempat tidur,
maka kontruksi Anaerobic Filter Treatment System dapat disesuaikan
dengan kebutuhan tersebut, misalnya :
a. Volume septic tank
b. Jumlah anaerobic filter
c. Volume stabilization tank
d. Jumlah chlorination tank
e. Jumlah sludge drying bed
f. Perkiraan luas lahan yang diperlukan
2. Keterpaparan Dan Parameter Limbah Cair Rumah Sakit
Keterpaparan limbah cair rumah sakit hampir sama dengan limbah
cair domestik, hanya yang membedakannya adalah adanya kandungan
limbah infeksius dan kimia/toksik/antibiotik. Limbah rumah sakit bisa
mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung jenis rumah
sakit, tingkat pengolahan sebelum di buang. Pengukuran baku mutu kimia
limbah rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
nomor 58 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah
sakit adalah sebagai berikut :
a. Biological Oxygen Demand (BOD)
Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi oksidasi zat-
zat organik dengan oksigen dalam air dimana proses tersebut dapat
berlangsung karena ada sejumlah bakteri. Diperhitungkan selama dua hari
reaksi lebih dari sebagian reaksi telah tercapai. BOD adalah kebutuhan
oksigen bagi sejumlah bakteri untuk menguraikan semua zat-zat organik
15
yang terlarut maupun sebagian tersuspensi dalam air menjadi bahan
organik yang lebih sederhana. Nilai ini hanya merupakan jumlah bahan
organik yang dikonsumsi bakteri. Penguraian zat-zat organik ini terjadi
secara alami. Dengan habisnya oksigen terkonsumsi membuat biota
lainnya yang membutuhkan oksigen menjadi kekurangan dan akibatnya
biota yang memerlukan oksigen ini tidak dapat hidup. Semakin tinggi
angka BOD semakin sulit bagi makhluk air yang membutuhkan oksigen
untuk bertahan hidup.
b. Chemical Oxygen Demand (COD)
Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain
pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah. Metode ini lebih singkat
waktuya dibandingkan dengan analisis BOD. Pengukuran ini menekankan
kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur
adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia. Adanya racun
atau logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri akan terhalang dan
pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk mengatasinya lebih tepat
meggunakan analisis COD. COD adalah sejumlah oksigen yang
dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat anorganik dan organik
sebagaimana pada BOD. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran
air oleh zat anorganik. Semakin dekat nilai BOD terhadap COD
menunjukkan bahwa semakin sedikit bahan anorganik yang dapat
dioksidasi dengan bahan kima. Pada limbah yang mengandung logam-
logam pemeriksaan terhadap BOD tidak memberi manfaat karena tidak
ada bahan organik dioksida.Hal ini bisa jadi karena logam merupakan
racun bagi bakteri. Pemeriksaan COD lebih cepat dan sesatannya lebih
mudah mengantisipasinya. Perbandingan BOD dengan COD pada
umumnya bervariasi untuk berbagai jenis limbah.
c. Metan
16
Gas metan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik dalam
kondisi anaerob pada air limbah. Gas ini dihasilkan oleh lumpur yang
membusuk pada dasar kolam, tidak berdebu, tidak berwarna dan mudah
terbakar. Metan juga dapat ditemukan pada rawa-rawa dan sawah. Suatu
kolam limbah yang menghasilkan gas metan akan sedikit sekali
menghasilkan lumpur, sebab lumpur telah habis terolah menjadi gas metan
dan air serta CO2.
d. Keasaman Air
Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan
berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Air
buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril dan
sebagai akibatnya membunuh mikroorganisme air yang diperlukan untuk
keperluan biota tertentu. Demikian juga makhluk-makhluk lain tidak dapat
hidup seperti ikan. Air yang mempunyai pH rendah membuat air korosif
terhadap bahan-bahan konstruksi besi dengan kontak air.
e. Alkalinitas
Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan air senyawa karbonat,
garam-garam hidroksida, kalsium, magnesium, dan natrium dalam air.
Tingginya kandungan zat-zat tersebut mengakibatkan kesadahan dalam
air. Semakin tinggi kesadahan suatu air semakin sulit air berbuih. Untuk
menurunkan kesadahan air dilakukan pelunakan air. Pengukuran
alkalinitas air adalah pegukuran kandunganion CaCO3, ion Mg bikarbonat
dan lain-lain.
f. Lemak dan minyak
Kandungan lemak dan minyak yang terkandung dalam limbah
bersumber dari instalasi yang mengolah bahan baku mengandung minyak.
Lemak dan minyak merupakan bahan organis bersifat tetap dan sukar
diuraikan bakteri. Limbah ini membuat lapisan pada permukaan air
sehingga membentuk selaput.
17
g. Oksigen terlarut
Keadaan oksigen terlarut berlawanan dengan keadaan BOD.
Semakin tiggi BOD semakin rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen
terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan
biota dalam perairan. Kemampuan air untuk mengadakan pemulihan
secara alami banyak tergantung pada tersedianya oksigen terlarut. Angka
oksigen yang tinggi menunjukkan keadaan air semakin baik. Pada
temperatur dan tekanan udara alami kandungan oksigen dalam air alami
bisa mencapai 8 mg/liter. Aerator salah satu alat yang berfungsi
meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Lumut dan sejenis ganggang
menjadi sumber oksigen karena proses fotosintesis melalui bantuan sinar
matahari. Semakin banyak ganggang semakin basar kandungan
oksigennya.
h. Klorida
Klorida merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Sebagai klor
bebas berfungsi desinfektan tetapi dalam bentuk ion yang bersenyawa
dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan dapat merusak
pipa-pipa instalasi.
i. Phospat
Kandungan phospat yang tinggi menyebabkan suburnya algae dan
organisme lainnya yang dikenal dengan eutrophikasi. Ini terdapat pada
ketel uap yang berfungsi untuk mencegah kesadahan. Pengukuran
kandungan phospat dalam air limbah berfungsi untuk mencegah tingginya
kadar phospat sehingga tumbuh-tumbuhan dalam air berkurang jenisnya
dan pada gilirannya tidak merangsang pertumbuhan tanaman air.
Kesuburan tanaman ini akan menghalangi kelancaran arus air. Pada danau
suburnya tumbuh-tumbuhan air akan mengakibatkan berkurangnya
oksigen terlarut.
18