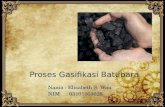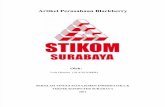BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang...
Transcript of BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang...
1
BAB I
PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Masalah
Di dalam cerita-cerita Melayu, tema-tema seperti penghormatan terhadap orang
tua, cinta sejati, harga sumpah, kekuatan akal, karma, kepentingan masyarakat, dan
toleransi tampil sangat menonjol. Di dalam cerita dengan tema penghormatan terhadap
orang tua, terutama ibu, digambarkan tokoh ini memiliki kekuatan yang luar biasa, baik
kekuatan cinta, maupun murkanya (Sutarto, melalui Djamaris, 2004:209). Cerita dengan
tema kemurkaan tokoh ibu inilah yang tampaknya kemudian berkembang menjadi cerita
yang lebih dikenal dengan cerita anak durhaka.
Cerita mengenai anak durhaka ini banyak ditemukan di Indonesia. Di Provinsi
Riau saja, ditemui cerita “Si Lancang” dari Kabupaten Kampar, “Batang Tuake” dari
Kabupaten Indragiri Hilir, “Rawang Tekuluk” dari Kabupaten Kuantan Singingi, “Si
Alang” atau “Legenda Pulau Halang Besar dan Pulau Halang Kecil” dari Kabupaten
Rokan Hilir, “Manggis Keramat” dari Rokan Hulu, “Si Umbut Muda” dari Kabupaten
Siak, dan ”Si Bujang: Asal Mula Burung Punai” dari Kabupaten Pelalawan. Di Sumatera
Barat, dikenal cerita “Malin Kundang”. Menurut Djamaris (2004: 206), cerita anak
durhaka menjadi topik yang mewarnai legenda-legenda pewarisnya yang memiliki latar
belakang keagamaan yang kuat.
2
Salah satu cerita yang berkaitan dengan tema ini adalah cerita “Batu Belah”1.
Cerita ”Batu Belah” ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri.
Selain terdapat di Provinsi Riau, cerita ini juga ada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Aceh, Sumatera Selatan, Sambas (Kalimantan Barat), dan Ambon. Di luar negeri, cerita
ini dapat ditemui di Malaysia, Brunei, dan Singapura.
Di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Brunei, dan
Malaysia, cerita ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti cerita “Batu Belah”, cerita
“Batu Batangkup”, atau cerita “Batu Belah Batu Bertangkup”. Sementara di Gayo,
Aceh, cerita ini disebut “Atu Belah”, sedangkan menurut Danandjaja (1984), di Ambon
cerita ini dikenal dengan nama “Batu Badaung”.
Cerita “Batu Belah” (selanjutnya ”BB”) yang dikategorikan sebagai legenda
(Djamaris, 2004:198; Fitra: 2007) ini dianggap oleh masyarakat pemilik cerita tersebut,
benar-benar pernah terjadi pada masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh Danandjaja
(1984:66), legenda adalah prosa rakyat yang dianggap benar-benar pernah terjadi.
Sebagai upaya untuk memperkuat argumen kebenaran cerita tersebut, masyarakat
pemilik cerita menunjukkan sebuah batu yang dipercaya sebagai batu belah yang ada di
daerah mereka. Selain itu, di daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Malaysia,
Batu Belah dijadikan nama desa.
“Kepercayaan” bahwa cerita ini benar-benar terjadi terlihat pula dari penyebutan
cerita ini sebagai sejarah. Di dalam kuesioner penelitian berjudul Apresiasi Sastra Murid
SMTA Kabupaten Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh (1992:46), Surya Noleh dkk.
1 Istilah “Batu Belah” merujuk kepada cerita “Batu Belah” secara umum, sedangkan secara khusus, di
setiap daerah, cerita ini dapat dikenal dengan istilah “Batu Belah Batu Bertangkup”, “Batu Batangkup”,
“Atu Belah”, atau “Atu Badaung”.
3
mengategorikan cerita ini sebagai cerita bertema sejarah. Hal senada disebutkan pula
oleh penulis cerita “BB” versi Gayo yang mengawali ceritanya dengan perkataan
sebagai berikut.
Menurut sejarah, cerita Batu Belah benar-benar terjadi karena sampai saat ini
masih ada buktinya. Batu Belah tempatnya di Isaq, Kecamatan Linge,
Kabupaten Aceh Tengah (1981:113).
Cerita ”BB” yang terdapat di berbagai tempat ini merupakan sebuah cerita
rakyat yang menarik untuk dikaji. Sebagai cerita yang dikategorikan bertema anak
durhaka, cerita ini berbeda dengan sebagian besar cerita bertema sama, seperti Malin
Kundang (Sumatera Barat), Si Lancang, dan Batang Tuake (Riau). Seperti yang
disampaikan Djamaris, tokoh-tokoh anak di dalam cerita-cerita bertema anak durhaka
tersebut dapat berubah menjadi batu, air, tumbuhan, atau binatang (2004: 206). Hal
tersebut dapat dilihat pada cerita ”Malin Kundang” dan ”Si Lancang” yang berubah
menjadi batu dan tokoh anak durhaka pada ”Batang Tuake” menjadi elang. Sementara
itu, pada sebagian besar cerita ”BB”, hukuman terhadap si anak, seperti yang pada
cerita-cerita di atas, tidak ditemukan. Bahkan, pada sebagian besar cerita ”BB” yang
dijumpai, anak-anak yang dianggap durhaka tersebut hidup berbahagia di akhir cerita
walaupun sebelumnya mereka juga mengalami kesusahan dan penderitaan.
Di Indonesia, setelah cerita ”Malin Kundang”, cerita rakyat yang bertema anak
durhaka yang terkenal adalah cerita ”BB”. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya
resepsi terhadap cerita ini ke dalam berbagai genre. Setakat ini, bentuk transformasi
awal cerita rakyat “BB” yang diketahui adalah dalam bentuk naskah berbahasa Gayo,
Aceh. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai naskah ini karena seperti yang
disebutkan di dalam buku Direktori Edisi Naskah Nusantara (2000:6) yang dieditori
4
Edi S. Ekadjati, dinyatakan bahwa penyalin, waktu penyalinan, dan tempat penyimpanan
naskah ini tidak diketahui. Hal tersebut menyebabkan upaya pelacakan terhadap naskah
tersebut menjadi lebih sulit. Setelah itu, cerita ”BB” ini ditransformasikan pula ke dalam
bentuk syair dengan judul Shaer Batu Belah Batu Bertangkup oleh Alias Rasulun pada
tahun 1962.
Selain bentuk sastra lama di atas, cerita ”BB” ini juga ditransformasikan ke
dalam genre sastra modern, yaitu berbentuk puisi, prosa, dan drama. Karya berbentuk
puisi yang didasari cerita ”BB” adalah sajak “Batu Belah” (1937) yang ditulis oleh Amir
Hamzah. Cerita rakyat ini juga bertransformasi ke dalam bentuk prosa, yaitu cerita Batu
Belah Batu Bertangkup (Abd. Samad Ahmad, 1971), cerita ”Batu Belah” (Proyek
Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1981), cerita anak Batu Belah Batu
Bertangkup: Cerita Rakyat di Kepulauan Siantan (Syamsuddin, 1983), “Batu Belah
Batu Bertangkup” (Tim Penulis, 1991), Batu Belah Batu Bertangkup (Rejab F.I., 1994),
Batu Belah Batu Bertangkup: Cerita Rakyat Indonesia (Suparlan, 1998), “Batu Belah
Batu Bertangkup” (Burhanuddin dkk.:1998), “Batu Belah Batu Bertangkup” dalam
Berguru kepada Anak dan Sejumlah cerita Rakyat yang Lain (Muda dan Merie, 2003),
dan “Batu Batangkup” (Alwi, 2006). Sebuah cerpen yang berjudul ”Ibu, Anaknya, dan
Sebongkah Batu” (Fitra, 2007) diakui pengarangnya juga merupakan resepsi terhadap
cerita ”BB”. Sementara cerita “Batu Belah Batu Bertangkup” dalam Riau Negeri
Tercinta (Ali, 2005) merupakan cerita “BB” yang ditulis dengan menggunakan huruf
Arab-Melayu yang digunakan sebagai materi pelajaran muatan lokal Arab-Melayu di
Provinsi Riau.
5
Cerita ini ditemui pula dalam genre drama televisi, yaitu legenda “Cinta Batu
Belah” (2008). Cerita ‘BB” ini pernah pula menjadi cerita dalam salah satu episode
cerita Unyil yang ditayangkan di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (Wenni, 2005).
Tahun 2008, cerita “Batu Belah” ini menjadi sebuah sinetron yang juga ditayangkan di
TPI (2008). Sebuah film animasi “Batu Belah Batu Bertangkup” (2008) dan sebuah
pementasan drama juga dibuat berdasarkan cerita “BB” ini. Jauh sebelumnya, pada
tahun 1959 cerita ini pernah pula ditransformasikan ke dalam film “Batu Belah Batu
Bertangkup”.
Di berbagai daerah, cerita “BB” ini tidak muncul dengan bentuk yang sama
persis. Padahal, dengan nama yang sama atau mirip di daerah satu dengan daerah lain,
ada kemungkinan cerita “BB” berasal dari satu daerah dan kemudian menyebar (difusi)
ke daerah lain. Walaupun penelitian mengenai hal ini belum ditemukan, penyebaran ini
memungkinkan terjadi karena secara geografis letak daerah-daerah tersebut tidak
berjauhan. Perhubungan antara daerah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat, Ambon, Malaysia, Singapura, dan Brunei pun sudah lama terjadi.
Daerah-daerah tersebut mempunyai hubungan historis dan kultural yang sudah berabad-
abad terjalin.
Secara umum, cerita “BB” ini berkenaan dengan anak yang tidak patuh kepada
ibunya atau membuat susah ibunya. Karena sedih dan kecewa, si ibu memutuskan untuk
masuk ke dalam sebuah batu yang berbelah. Akan tetapi, pada kenyataannya, cerita
”BB” muncul dalam bentuk yang bervariasi pada setiap daerahnya. Setiap tempat,
mempunyai versi atau varian tersendiri. Cerita “BB” di Aceh dan Sumatera Selatan
6
sangat berbeda dengan cerita “BB” yang ada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau,
Malaysia, Brunei, dan Singapura.
Di dalam cerita “BB” yang terdapat di Aceh, tidak terdapat motif memakan
telur tembakul, seperti yang ada di dalam cerita “BB” di Provinsi Riau (Kabupaten
Indragiri Hilir), Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kemarahan orang
tua si anak, dalam hal ini ayah, terjadi karena si anak atau pada varian lain, si istri,
secara tidak sengaja melepaskan belalang yang disimpan di kandang. Sementara itu, di
dalam cerita “BB” yang berasal dari Sumatera Selatan, motif memakan telur tembakul
juga tidak dijumpai. Perbedaan lain, tokoh yang masuk ke dalam batu belah adalah si
anak perempuan, bukan ibunya, seperti pada sebagian besar cerita “BB”. Pada cerita ini,
anak yang masuk ke dalam batu tersebut dapat kembali dengan selamat kepada
keluarganya.
Adapun, cerita “BB” yang terdapat pada kelima tempat yang disebutkan
terakhir, mempunyai persamaan yang cukup besar. Walaupun demikian, tidak berarti
cerita “BB” pada daerah-daerah tersebut benar-benar sama. Asumsi tersebut perlu
dibuktikan melalui sebuah penelitian. Pada penelitian ini, dilihat cerita ”BB” yang
berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yang dibandingkan dengan cerita ”BB” yang ada
di Malaysia.
Walaupun berbeda negara, secara geografis Provinsi Kepulauan Riau dan
Malaysia terletak pada daerah yang berdekatan. Dahulunya, kedua daerah ini termasuk
ke dalam satu Kerajaan Melayu2 yang kemudian terpecah akibat Perjanjian London
2 Perjanjian London tahun 1824 yang disepakati pemerintah kolonial Inggris dan Belanda secara politik
telah membelah Kerajaan Melayu ke dalam dua wilayah politik yang berbeda, yaitu Singapura (Temasek)
7
tahun 1824. Dengan demikian, masyarakat kedua daerah ini secara sosial budaya
mempunyai kaitan erat, bahkan setelah perjanjian London tersebut dibuat (Mahayana,
2007:1).
Situasi yang demikian, membuat cerita “BB” menjadi semakin menarik untuk
diteliti. Bagaimana bentuk cerita ”BB” yang hidup di dalam masyarakat Melayu di
Provinsi Kepulauan Riau dan Malaysia setelah keduanya berada pada dua negara yang
berbeda.
Pada penelitian ini, untuk cerita “BB” yang ada di Indonesia, dipilih cerita “BB”
yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang dibandingkan dengan cerita “BB” yang ada
di Malaysia. Kedua cerita itulah yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini.
Penelitian dengan ruang lingkup sastra banding dimungkinkan pada kedua cerita
tersebut. Hal itu disebabkan oleh kedua cerita tersebut berada pada dua negara yang
berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Selain itu, bahasa yang dipergunakan pada kedua
cerita itu berbeda. Cerita Batu Belah Batu Bertangkup Bertangkup (1983) karya BM
Syamsuddin (selanjutnya BBBB BMSy) menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan
cerita Batu Belah Batu Bertangkup (1971) yang ditulis oleh Abd. Samad Ahmad
(selanjutnya BBBB ASA) menggunakan bahasa Melayu Malaysia.
Penelitian terhadap kedua cerita “BB” penting dilakukan karena beragamnya
versi dan varian di setiap daerah dan juga berbagai transformasi terhadap cerita ini
belum diimbangi dengan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Sampai saat ini,
hanya sedikit pembicaraan mengenai cerita “BB” (lihat daftar pustaka), apalagi
dan Johor berada di bawah kekuasaan Inggris, sedangkan Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan
Belanda (Maman S. Mahayana. 2007. ”Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia-Malaysia”,
Makara, Sosial Humaniora, Vol. 11, No. 2, Desember 2007: 48-57)
8
pembicaraan yang berkenaan dengan kajian sastra banding. Setakat ini, satu-satunya
tulisan yang berkenaan dengan penelitian sastra banding terhadap cerita “BB” adalah
tulisan Ismail Nasution (2008), yaitu “”Batu Belah” dan Puisi “Batu Belah” Amir
Hamzah: Kajian Perbandingan“. Di dalam tulisan tersebut diperbandingkan cerita Batu
yang Belah yang berasal dari Kayu Agung, Sumatra Selatan dengan puisi “Batu Belah”
yang ditulis oleh Amir Hamzah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas
cerita-cerita “BB” di berbagai daerah di Indonesia belum ditemukan, demikian pula
dengan penelitian mengenai cerita “BB” di Indonesia yang dibandingkan dengan cerita
“BB” di luar Indonesia. Oleh karena itu, penelitian “Cerita Batu Belah Batu Bertangkup
di Indonesia dan Malaysia: Kajian Perbandingan Sastra” perlu dilakukan. Penelitian ini
tidak hanya sekadar mengetahui persamaan dan perbedaan pada kedua cerita yang
berasal dari dua negara yang berbeda tersebut, tetapi juga dapat mengetahui mengapa
perbedaan tersebut terjadi.
1.2 Perumusan Masalah
Seperti yang dijelaskan pada latar belakang masalah, masyarakat Melayu di Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia, dan Malaysia mempunyai kedekatan secara historis dan
kultural. Setelah terpisah dan berada pada dua negara berbeda, yaitu Indonesia dan
Malaysia, perlu diketahui bagaimana bentuk cerita BBBB yang ada dan berkembang
pada kedua masyarakat tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, pada penelitian ini
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
9
1. sejarah berdiri dan runtuhnya Kesultanan Melaka dan berbagai versi cerita
”BB” di Indonesia, sinopsis cerita BBBB yang dijadikan objek, serta
penulisnya;
2. struktur cerita, yaitu: tema, alur (plot); tokoh dan penokohan (character);
latar (setting) cerita BBBB (1983) yang ditulis oleh BM Syamsuddin sebagai
sampel cerita ”BB” yang terdapat di Indonesia dan cerita BBBB (1971) Abd.
Samad Ahmad sebagai sampel dari cerita ”BB” di Malaysia;
3. persamaan dan perbedaan yang muncul pada cerita BBBB yang ditulis oleh
BM Syamsuddin dan cerita BBBB Abd. Samad Ahmad dan penyebabnya.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejarah berdiri dan runtuhnya Kesultanan
Malaka dan berbagai versi cerita ”BB” di Indonesia, sinopsis cerita BBBB yang
dijadikan objek, serta penulisnya, (2) struktur cerita BBBB BM Syamsuddin dan cerita
BBBB Abd. Samad Ahmad, yang terdiri atas tema, alur (plot); tokoh dan penokohan
(character); latar (setting), dan (3) persamaan dan perbedaan yang muncul pada cerita
BBBB yang ditulis oleh BM Syamsuddin dan cerita BBBB Abd. Samad Ahmad dan
penyebabnya.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dibagi atas tujuan teoretis dan tujuan praktis. Secara teoretis,
penelitian ini bertujuan untuk ikut mengembangkan teori sastra banding. Pengembangan
10
tersebut didapat melalui pengetahuan mengenai bentuk-bentuk yang sama dan berbeda
yang terdapat pada karya-karya sastra yang dibandingkan, yang ada di beberapa negara
yang mempunyai hubungan historis dan kultural yang erat.
Adapun tujuan praktis penelitian ini adalah (1) memberikan alternatif penafsiran
kepada masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi berbagai cerita ”BB”, (2)
memperlihatkan berbagai macam versi cerita ”BB”, dan (3) membantu
menginventarisasi cerita-cerita “BB” dari beberapa daerah di Indonesia dan Malaysia.
1.5 Tinjauan Pustaka
Beberapa pembicaraan mengenai cerita rakyat “BB” sudah dilakukan oleh para
peneliti atau pengamat sastra. Beberapa penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut.
Di dalam tulisan “”Batu Belah” dan Puisi “Batu Belah” Amir Hamzah: Kajian
Perbandingan“, Nasution (2008) memperbandingkan cerita Batu Belah yang berasal
dari Kayu Agung, Sumatra Selatan dengan puisi “Batu Belah” yang ditulis oleh Amir
Hamzah. Pembicaraan difokuskan pada aspek latar dan penokohan, serta motif si ibu
melakukan bunuh diri dengan cara masuk ke dalam batu belah. Dari penelitian tersebut,
diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada kedua bentuk karya tersebut.
Berdasarkan konsep Jost, persamaan-persamaan yang ditemukan menunjukkan bahwa
antara cerita Batu Belah dari Kayu Agung dengan puisi Amir Hamzah terdapat organic
affinities, yaitu adanya relevansi pada bagian-bagian tertentu dari sastra lisan dengan
puisi Amir Hamzah. Berdasarkan konsep giver-receiver (pemberi-penerima) Jost, puisi
Amir Hamzah yang terbit pertamakali 1937 dianggap sebagai receiver cerita lisan “Batu
11
Belah” yang sudah ada terlebih dahulu di dalam masyarakat. Walaupun demikian,
Nasution tidak dapat memastikan bahwa cerita “Batu Belah” yang berasal dari Kayu
Agunglah yang menjadi rujukan Amir Hamzah menulis sajaknya. Hal tersebut
mengingat cerita ini ada dan berkembang di berbagai daerah dengan versi yang beragam.
Dari tulisan di atas, diketahui bahwa penelitian terhadap cerita “BB” sudah pernah
dilakukan dengan kajian sastra banding, yaitu antara cerita “BB” versi Kayu Agung,
Sumatera Selatan, dengan sajak “Batu Belah” oleh Amir Hamzah. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak sama dengan yang dilakukan
Nasution. Namun, melalui penelitian Nasution ini diketahui beberapa hal, yaitu (1) ada
cerita “BB” versi Kayu Agung, Sumatera Selatan dan (2) sajak “Batu Belah” Amir
Hamzah yang merupakan penerima (receiver, istilah Jost) cerita “BB” adalah salah satu
bentuk karya transformasi dari cerita “BB” .
Di dalam tulisan “Iktibar Batu Belah Batu Bertangkup: Ibu Tidak Boleh
Merajuk” (©Fitrah Sdn. Bhd), penulis menitikberatkan pembicaraannya mengenai cerita
rakyat “BB” pada dua hal, yaitu subjek pendidikan dan subjek komunikasi.
Menurutnya, dalam masalah pendidikan terdapat kepincangan yang besar pada karakter
ibu dalam kisah ini. Sebagai ibu, perbuatan merajuk atas perbuatan anak (dalam kasus
ini sampai sanggup membunuh diri) adalah salah. Penulis mengaitkan ketidaksabaran
tokoh ibu dengan kesabaran para nabi dalam menghadapi umatnya. Dia menyatakan
bahwa tidak ada komunikasi berdasarkan simpati dan empati antara kedua belah pihak,
yaitu pihak si ibu dengan pihak si anak. Dalam komunikasi yang baik, sikap ‘seek to
understand then to be understood’ –sikap memahami orang lain terlebih dahulu, barulah
12
orang memahami diri sendiri, sangat perlu-. Dalam cerita ini, si ibu dianggap gagal
menyelami perasaan si kakak yang bersimpati pada adiknya yang lapar. Ibu juga
dianggap gagal memahami perasaan si adik yang sangat menyukai telur ikan. Dengan
demikian, di dalam tulisan ini, penulis mengkritik tokoh si ibu dalam cerita “BB” ini;
“kebaikan” tokoh ibu tersebut digugat.
Dalam tulisan “Muara Seluruh Arus Budaya Ibu, Kasih, dan Strategi Budaya...”,
Putra (2007) mengaitkan sosok ibu di dalam cerita “BB” dan juga dalam sajak “Batu
Belah” Amir Hamzah dengan sebuah pergulatan pemikiran dalam budaya lisan. Dia
membandingkan sosok ibu di dalam cerita “BB” dengan cerita “Malin Kundang”. Di
dalam cerita “Malin Kundang”, ibu tidak dapat sama sekali menerima perubahan sikap
anak sehingga dia meminta anaknya dihukum. “Malin Kundang” dianggap sebagai
sebuah produk dari sebuah moralitas budaya yang mengharamkan kedurhakaan sebagai
landasan perubahan. Di dalam moralitas budaya yang demikian, perubahan hanya
mungkin melalui negosiasi. Sementara di dalam cerita “BB”, sosok ibu merupakan
martir. Ibu lebih memilih berkorban ditelan batu bertangkup daripada mengutuk anaknya
yang sudah berbuat salah pada dirinya. Namun, penulis mengakui sikap ibu dapat saja
dianggap tidak dapat menjalankan perannya sebagai negosiator terhadap perubahan.
Dalam banyak hal, seorang ibu kerap merupakan subjek yang paling dikorbankan dari
setiap transisi kebudayaan. Tulisan ini bermanfaat karena mengungkapkan adanya
perubahan pemikiran dan budaya yang terkandung dalam cerita “BB”.
Di dalam buku Analisis Tema, Amanat, dan Nilai Budaya Sastra Nusantara di
Sumatera Selatan yang ditulis Zainul Arifin Aliana dkk. (1994) ditemukan bahwa tema
13
cerita ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa pikir panjang akan mengakibatkan
kerugian. Sementara amanat yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut adalah
hendaknya orang berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan penyesalan di
kemudian hari. Sementara nilai budaya yang terdapat di dalam cerita “Batu Belah Batu
Bertangkup” adalah nilai (1) kepatuhan terhadap ibu dan (2) cinta kasih. Dengan
demikian, terlihat bahwa penelitian ini lebih mengarah pada upaya untuk melihat nilai-
nilai moral yang ada di dalam cerita ”BB”.
Dalam pembicaraannya mengenai legenda pada buku Folklor Indonesia: Ilmu
Gosip, Dongeng, dan Lain-lain, Danandjaja mengemukakan cerita “Atu Belah” yang
berasal dari Gayo, Aceh. Menurutnya, cerita ini merupakan salah satu contoh yang
memperkuat bahwa mite atau legenda (cerita rakyat) berasal dari mimpi seseorang,
seperti yang dikemukakan dalam teori poligenesis psikonalisisnya Sigmund Freud.
Berdasarkan teori ini, cerita “Atu Belah” merupakan proyeksi seorang perempuan yang
mengalami kesukaran dan kekecewaan hidup sehingga berangan-angan untuk kembali
ke rahim ibunya, tempat yang dianggap aman. Berdasarkan pendapat aliran Freudian ini,
cerita “Atu Belah” menjadi terkenal di Gayo karena perempuan di daerah itu banyak
mengalami kesukaran dan kekecewaan (Danandjaja, 1984:64—66). Tulisan Danandjaja
ini menganalisis cerita “Atu Belah” dengan teori poligenesis psikonalisis Sigmund Freud
yang berbeda dengan teori perbandingan yang digunakan di dalam penelitian ini. Akan
tetapi, tulisan Danandjaja ini memberikan pengetahuan mengenai cerita “BB” versi
Gayo, Aceh, yang berbeda dengan cerita “BB” yang ada di daerah-daerah lain.
14
Penelitian Bunga Rampai Cerita Rakyat Gayo yang ditulis Kadir dkk. (1982)
berisi transliterasi dan ringkasan isi dari 12 naskah berbahasa Gayo. Salah satu naskah
tersebut berisi cerita “Atu Belah” yang terdapat di dalam masyarakat Gayo (Ekadjati
(ed.), 2000). Kadir dkk. menggubah cerita tersebut dari pantun yang terdiri atas 47 bait.
Tiap-tiap bait terdiri atas empat bait dengan berbagai variasi persajakan, yaitu abab,
aaab, dan sebait bersajak abcd (Kadir dkk. 1982). Tulisan Kadir dkk. ini sangat
bermanfaat karena mengandung informasi mengenai cerita “BB” yang berbentuk
pantun. Setakat ini, bentuk ini merupakan bentuk tertulis yang tertua dari cerita “BB”.
Selain pembicaraan mengenai cerita ”BB” di atas, ditemukan pula tulisan
mengenai cerpen ”Ibu, Anak, dan Sebongkah Batu” yang merupakan transformasi dari
cerita ”BB” yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Esai itu berjudul
“Jenazah “Keranda Jenazah …” (Telaah Buku Kumpulan Cerpen “Keranda Jenazah
Ayah”) yang ditulis Gde Agung Lontar dan diterbitkan di Riau Pos, Ahad, 27 Januari
2008. Esai ini memuat pembicaraan mengenai kumpulan cerpen pilihan Riau Pos tahun
2007, yaitu Keranda Jenazah Ayah: Cerpen Pilihan Riau Pos 2007. Pada esai tersebut,
dibahas juga cerpen “Ibu, Anaknya, dan Sebongkah Batu” yang ditulis oleh Iggoy el
Fitra. Lontar memuji teknik penceritaan yang ada di dalam cerpen ini. Selain itu, dia
menyebut cerpen ini merupakan perkawinan dari dua mitos, yaitu ”Batu Belah Batu
Bertangkup” dan ”Malin Kundang”.
Selain tulisan-tulisan di atas, beberapa penelitian di bawah ini dianggap dapat
memberi konstribusi terhadap penelitian yang dilakukan karena meneliti beberapa cerita
rakyat dengan menggunakan teori sastra banding.
15
Di dalam buku Antologi Esai Sastra Banding dalam Sastra Indonesia Modern
(2003), Suripan Sadi Hutomo menulis “Cerita Kentrung Djaka Tarub dan Teori
Astronout”. Di dalam tulisan tersebut diperbandingkan cerita-cerita yang bermotif
“pemuda beristrikan bidadari setelah baju bidadari tersebut diambil oleh si pemuda
ketika pemiliknya sedang mandi di telaga” yang terdapat pada cerita Jaka Tarub (Jawa),
Malem Diwa (Aceh), Lahilote (Gorontalo), Cerita Telaga Bidadari atau Datu Unjun
(Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan), Fefo Kakar Ritu atau Tujuh Orang Puri
Bersaudara (Tetun, Nusa Tenggara Timur). Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa
cerita Fefo Kakar Ritu memiliki lebih banyak persamaan dengan cerita Lahilote
dibandingkan dengan cerita Jaka Tarub. Hal itu disebabkan (1) Laku Lekik menyusul
istrinya ke langit dan (2) Laku Lekik diuji di kerajaan langit. Hutomo sampai pada
kesimpulan bahwa di masa lampau terdapat hubungan yang erat antarsuku di Indonesia
sehingga terdapat persamaan pada cerita-cerita tersebut. Akan tetapi, dia menemukan
bahwa detil cerita berbeda pada setiap daerah. Selain memperbandingkan cerita-cerita
bermotif astronout yang ada di Indonesia, Hutomo juga membandingkannya dengan
cerita sejenis yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, yaitu cerita Dato Umar dan cerita
Ha-Goromo di Jepang. Dia menyimpulkan bahwa cerita yang terdapat di Mindanao
tersebut mempunyai keterkaitan dengan cerita-cerita yang ada di Indonesia. Hutomo
menduga cerita tersebut masuk ke Mindanao melalui Sulawesi Utara (sekarang
Gorontalo) atau Halmahera. Akan tetapi, seperti yang disebutkan oleh Roosman
(Hutomo, 2003:29), di Mindanao cerita itu sudah diganti dengan nama-nama Islam.
Dengan merujuk pada kesamaan rumpun bahasa yang dipergunakan, yaitu bahasa
Austronesia yang mempunyai kaitan erat dengan bahasa Jepang, seperti yang
16
disampaikan Matsumoto Nobuhiro (melalui Hutomo, 2003: 30), cerita-cerita seperti ini
diperkirakan terdapat di daratan Asia yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Lebih
lanjut, Hutomo menemukan cerita yang mirip di Thailand Lambantulang. Hutomo
tidak hanya membandingkan cerita-cerita tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan
teori astronout yang diajukan Eric von Daniken dalam bukunya Erinnerungen und die
Zukunft (1968) dan Zuruck zu den Sterken (1969). Teori ini menganggap sastra lisan
sebagai ”saksi zaman” atau ”pencatat sejarah”. Dengan demikian, cerita-cerita semotif
dengan Jaka Tarub dianggap sebagai sistem proyeksi perkawinan campuran antara
manusia bumi dengan wanita dari planet lain yang lebih tinggi kebudayaan dan
peradabannya. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa cerita-cerita rakyat dengan motif
tertentu pada masing-masing daerah memiliki persamaan secara garis besar, tetapi detil
dari cerita tersebut berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh geografis dan juga
budaya yang masuk pada daerah tersebut.
Di dalam tulisan “Cerita Ciung Wanara dalam Perbandingan”3 Titik Pudjiastuti
memperbandingkan tiga versi cerita Ciung Wanara, yaitu cerita versi Pleyte (1910),
Sajarah Banten (tt), dan Kiai Djaka Mangoe (tt). Untuk melihat persamaan dan
perbedaan yang terdapat pada ketiga cerita tersebut, Pudjiastuti menggunakan teori
strukturalisme. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa secara garis besar ketiga cerita
tersebut mempunyai kesamaan. Akan tetapi, detil cerita tersebut berbeda, seperti terlihat
pada penamaan tokoh-tokoh, cara Ciung Wanara membalas dendam, dan akhir cerita.
3 http://staff.ui.ac.id/internal/131635535/publikasi/CeritaCiungWanaradalamPerbandingan.pdf
17
”Analisis Perbandingan Struktur dan Nilai Budaya Dongeng Issunbooshi
dengan Dongeng Jaka Kendil” (2007) ditulis oleh Ni Luh Putu Sulastri. Pada skripsinya,
Sulastri membandingkan dongeng Issunbooshi yang ada di Jepang dengan dongeng Jaka
Kendil yang ada di Jawa. Dia mendapati bahwa kedua dongeng ini mempunyai
perbedaan pada latar, tetapi sama dari segi tema, yaitu mengenai kegigihan yang
membawa keberhasilan. Adapun nilai budaya yang terdapat pada kedua dongeng
tersebut adalah kepercayaan dan rasa bersyukur terhadap Tuhan, nilai kebijaksanaan,
kasih sayang orang tua terhadap anak, rasa hormat pada orang tua, suka menolong, dan
balas budi. Adapun nilai budaya berani meminta maaf terdapat pada dongeng Jaka
Kendil, tetapi tidak ada pada dongeng Issunbooshi.
Suharyanto meneliti ”Perbandingan Cerita Rakyat Indonesia-Korea Jaka Tarub
dan Bidadari dengan Seonyeo Wa Namukaun” (2010). Dia menyimpulkan bahwa kedua
cerita ini mempunyai kesamaan karena tokohnya memperistri bidadari. Tidak hanya itu,
persamaan lainnya adalah pesan moral kedua cerita tersebut, yaitu ”sesuatu yang diawali
dengan kebohongan tidak akan berakhir dengan baik”. Akan tetapi, terdapat pula
perbedaan pada kedua cerita ini, yaitu penokohannya, alur, dan juga latarnya.
Pemaparan beberapa penelitian di atas menunjukkan dua hal. Pertama,
menunjukkan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Artinya, setakat ini belum ada yang
meneliti “Cerita Batu Belah Batu Bertangkup di Indonesia dan Malaysia: Kajian
Perbandingan”. Kedua, penelitian-penelitian yang disebutkan di atas dapat dijadikan
masukan (input) bagi penelitian ini. Penelitian mengenai cerita rakyat dari beberapa
daerah atau negara di atas, misalnya, bermanfaat untuk melihat cara memperbandingkan
struktur cerita yang dilakukan antara satu cerita dengan cerita lainnya.
18
1.6 Kerangka Teori
Penelitian ini berada dalam ruang lingkup perbandingan sastra yang dibantu teori
struktural semiotik.
Perbandingan sastra dipergunakan karena ingin mengetahui persamaan dan
perbedaan yang ada pada cerita “BB” yang ada di Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut
dilakukan karena kedua karya sastra ini berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu
Indonesia dan Malaysia serta menggunakan bahasa yang berbeda pula, yaitu bahasa
Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sementara itu, teori strukturalisme semiotik
dipergunakan untuk meneliti struktur dan makna tanda-tanda yang terdapat pada kedua
karya sastra. Dengan teori ini, dapat diungkapkan struktur dan tanda-tanda yang terdapat
di dalam cerita BBBB di Indonesia dan Malaysia. Melalui penganalisisan dengan
penggunaan teori struktural semiotik, unsur-unsur pada kedua cerita dapat diketahui
untuk kemudian dibandingkan.
1.6.1 Sastra Banding
Istilah sastra banding muncul pertama kali di Perancis pada tahun 1816. Istilah
ini berasal dari sebuah antologi pengajaran sastra yang berjudul Cours de Litterature
Comparee. Di Jerman, sastra banding disebut dengan istilah vergleichende
literaturgesichte yang muncul di dalam buku Moriz Carriere (1854). Sementara di
Inggris istilah comparative literature diperkenalkan oleh Matthew Arnold pada tahun
1848 (Bassnett, 1995:12).
Berbagai pendapat dikemukakan para ahli berkenaan dengan ruang lingkup
penelitian yang disebut sastra banding ini. Remak (1990:1) menyatakan bahwa sastra
19
banding merupakan kajian yang membahas karya sastra dengan karya sastra lain di luar
batas negara. Dia juga memperbolehkan penelitian sastra yang dikaitkan dengan ilmu di
luar sastra, seperti seni, filsafat, sejarah, politik, ekonomi, dan agama. Sementara itu,
Nada (1999:9 melalui Damono, 2005: 4) menganggap penelitian sastra banding hanya
diperbolehkan antarkarya sastra saja dengan penekanan adanya unsur kesejarahan dan
perbedaan bahasa yang ada di antara karya-karya yang dibandingkan.
Dalam perkembangannya, terdapat dua mazhab sastra banding yang terkenal,
yaitu mazhab Eropa dan Amerika. Mazhab Eropa menekankan pada penelitian
antarkarya sastra saja. Adapun mazhab Amerika berpendapat bahwa di dalam sastra
banding diperbolehkan memperbandingkan sastra dengan disiplin bidang lain, seperti
seni, filsafat, dan bidang-bidang lain (Damono, 2005: 10).
Berkaitan dengan ruang lingkup penelitian sastra banding ini, berdasarkan
pendapat François Guyard4, Owen Aldrige5, lebih rinci, Clements (melalui Damono,
2005: 8), mengajukan lima pendekatan yang dapat dipergunakan dalam sastra banding,
yaitu (1) tema/mitos, (2) genre/bentuk, (3) gerakan/zaman, (4) hubungan-hubungan
sastra dengan bidang seni dan disiplin ilmu lain, dan (5) pelibatan sastra sebagai bahan
perkembangan teori yang terus-menerus bergulir.
Sementara, Francois Jost (1974: viii—ix) mengajukan empat bidang dalam
kajian sastra banding, yaitu (1) relasi analogi dan pengaruh, (2) gerakan dan trend (3)
4 Francois Guyard menyatakan bahwa pendekatan dalam sastra banding adalah sejarah hubungan-
hubungan sastra antarbangsa. Di dalamnya, terdapat survei mengenai pertukaran gagasan, tema, buku,
atau perasaan di antara bangsa-bangsa, di antara dua atau beberapa sastra (melalui Damono, 2005:7) 5 Owen Aldridge beranggapan bahwa sastra sebagai studi mengenai gejala sastra dari perspektif lebih dari
satu sastra suatu bangsa atau hubungannya dengan satu atau lebih disiplin intelektual (melalui Damono,
2005:7)
20
genre dan bentuk, dan (4) motif, tipe, dan tema. Kategori yang pertama, relasi analogi
dan pengaruh, merujuk pada penunjukan adanya pertalian atau jalinan organik satu
karya dengan karya lain. Penelitian diarahkan pada pengaruh satu karya terhadap karya
yang lain, yang berkaitan dengan analogi antara beberapa karya, baik sebagai penerima-
pemberi (giver-receiver) atau pertalian hubungan sebab-akibat. Pada kategori ini,
termasuk pula aspek sastra interdisipliner, yaitu sejumlah koneksi antara sastra dengan
domain budaya lain, seperti filsafat, psikologi, sosiologi, linguistik, musik, dan seni
lukis. Pada kategori kedua, yaitu gerakan dan trend, meneliti studi mengenai gerakan
dan trend -seperti Renaissans, Baroque, Klasisme, Romantisme, Realisme- yang
mencirikan peradaban Barat dalam frase perkembangan. Gerakan dan trend ini terutama
akan terlacak pada karya-karya penulis yang dominan (andal) yang karya-karyanya
selalu mencerminkan semangat zaman (Zeitgeist). Kategori ketiga adalah genre dan
bentuk. Pada kategori ini analisis karya sastra dilihat dari sudut pandang bentuk (form)
lahir dan batin, genre karya. Kategori terakhir ini menggabungkan studi tentang tema
dan motif. Akan tetapi, tema dan motif juga bisa berbentuk abstrak dan konseptual
murni. Tema dan motif dapat terkait dengan topik seperti patriotisme, pemberontakan,
persahabatan, dan kematian.
Sastra banding muncul disebabkan kekhawatiran adanya pandangan sempit
mengenai sastra nasional. Oleh karena itu, sastra bandingan bertujuan untuk menghapus
pandangan sempit sastra nasional dan untuk menghilangkan anggapan bahwa satu sastra
nasional lebih baik dari satu sastra nasional lainnya (Wellek dan Warren, 1990: 51). Di
sisi lain, sebelumnya, penelitian sastra bersifat monodisipliner, yaitu terpusat pada karya
sastra saja. Penelitian yang seperti ini cenderung sebatas meningkatkan keterampilan
21
berbahasa, mengembangkan kosakata, atau mencari tema-tema kemanusiaan yang
universal. Hal tersebut dapat mengalienasi karya sastra terhadap ilmu-ilmu lain. Sastra
banding dianggap sebagai solusi terhadap kelemahan tersebut. Melalui penelitian sastra
banding diharapkan sastra akan lebih dekat dengan disiplin ilmu sosial lainnya dan dapat
mengembangkan cara pandang yang utuh dan luas terhadap realitas (Rokhman, 2003: 4-
-6).
1.6.2 Teori Struktural Semiotik
Seperti yang sudah disampaikan di atas, penelitian teori sastra banding ini
didukung teori lain, yaitu teori struktural-semiotik. Seperti yang disampaikan Damono
(2005:2) bahwa teori sastra banding tidak menghasilkan teori sendiri. Oleh karena itu,
teori apa pun dapat dipergunakan sesuai dengan objek dan tujuan penelitian. Di dalam
penelitian ini, teori pendukung tersebut adalah teori struktural semiotik.
Teori strukturalisme menganggap sebuah karya sastra terdiri atas unsur-unsur
yang terjalin erat yang membentuk sebuah struktur (Pradopo, 2001:97). Makna sebuah
karya sastra didapat melalui totalitas unsur-unsurnya tersebut (Hawkes, 1978: 17—18).
Senada dengan pendapat di atas, Teeuw (1988:135) menyatakan bahwa pendekatan
strukturalisme berupaya memahami karya sastra dengan memperhitungkan struktur-
struktur atau unsur-unsur pembentuk karya sastra sebagai suatu jalinan yang utuh.
Menurutnya, penggunaan pendekatan struktural dalam analisis dimaksudkan untuk
membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterjalinan dan keterkaitan semua
unsur karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh.
22
Stanton (1965:12-34) mengemukakan bahwa yang disebut struktur cerita itu
terdiri atas unsur-unsur tema (theme), fakta cerita (fact of story), yang mencakup alur
(plot); tokoh dan penokohan (character); latar (setting), dan sarana-sarana sastra
(literary devices) yang terdiri atas pusat pengisahan (point of view), gaya bahasa dan
nada (style and tone), simbol (symbol), ironi (irony), dan sebagainya. Untuk keperluan
penelitian ini, unsur yang dibahas adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, serta latar.
Stanton (1965:4) menyebut tema sebagai arti pusat, ide pusat, atau ide pokok.
Lebih lanjut, dia mengartikan tema sebagai makna sebuah cerita yang secara khusus
menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana.
Alur adalah cerita yang berisi urutan peristiwa dan tiap peristiwa itu
dihubungkan berdasarkan hubungan sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau
menyebabkan terjadinya peristiwa lain dan apabila dihilangkan dapat merusak jalan
cerita (Stanton, 1965: 14). Hal senada diungkapkan Forster (1970: 93) yang menyatakan
alur sebagai peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya
hubungan kausalitas. Untuk melihat alur, Stanton (1965:14) melakukannya melalui
pembabakan peristiwa yang disebut episode.
Abrams (1981:20) menyatakan bahwa tokoh cerita dimaksudkan untuk orang
yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan
memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam
ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Adapun latar (1981:175) adalah landas
tumpu yang menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial
tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
23
Seperti yang dinyatakan oleh Teeuw (1991:61), pendekatan struktural ini
memang bukan tugas utama atau tujuan akhir sebuah penelitian karya sastra, tetapi
analisis ini merupakan prioritas pekerjaan pendahuluan (Teeuw, 1983:61) apabila
hendak menganalisis sebuah karya sastra dari sudut apapun. Oleh karena itu, penelitian
terhadap struktur ini dilanjutkan dengan penelitian semiotik yang sebenarnya merupakan
kelanjutan dari teori struktural. Hal tersebut disebabkan, karya sastra dianggap sebagai
struktur tanda yang memiliki makna (Junus, 1981:17).
Semiotik berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti ‘tanda’. Semiotik
adalah ilmu yang mempelajari tanda, sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi yang
memungkinkan tanda itu mempunyai arti (Pradopo, 1995:119). Menurut Saussure
(melalui Nöth, 1990: 60) tanda memiliki dua aspek, yaitu penanda (signifié; signifier)
dan petanda (signifiant; signified). Penanda (signifier, expression) adalah apa yang
digunakan untuk merepresentasikan tanda, sedangkan petanda (signified/concept,
content) adalah makna yang direpresentasikan oleh tanda itu.
Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda ini, dikenal istilah ikon,
indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang mempunyai hubungan yang alamiah berupa
persamaan antara penanda dan petandanya. Indeks merupakan tanda yang hubungannya
bersifat kausalitas antara penanda dan petandanya, sedangkan pada simbol, hubungan
antara penanda dan petandanya bersifat arbitrer (Pradopo, 1995:120).
Pemberian makna pada tanda tersebut, tergantung pada sistem, aturan, dan
konvensi yang berlaku pada masyarakat. Oleh karena itu, pemberian makna pada tanda
yang ada di dalam karya sastra hendaknya memperhatikan konvensi bahasa, konvensi
24
sastra, kerangka kesejarahan, dan relevansinya dengan sosial budaya masyarakat
(Pradopo, 2000: 47).
(a) Konvensi Bahasa
Karya sastra bermedium bahasa. Sebelum menjadi bagian dari karya sastra,
bahasa ini sudah memiliki arti (meaning) yang ditentukan oleh konvensi masyarakatnya
(Teeuw, 1988: 96). Pada tataran ini, bahasa berada pada sistem semiotik tingkat pertama
(ein primäres modellbildendes system; primary order semiotics) (Lotman melalui
Teeuw, 1988: 99).
Bahasa yang sudah mempunyai arti inilah yang dieksplorasi oleh sastrawan di
dalam karyanya. Walaupun kemudian dijumpai penggunaan bahasa yang menyimpang
dari arti yang umum, pemaknaan terhadap kata tersebut masih dapat dirunut ke dalam
konvensi bahasa yang disepakati masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan Teeuw
(1988: 97) bahwa sistem kemaknaan bahasa itu bersifat lincah, luwes, dan penuh
dinamika sehingga memberi peluang bagi pemanfaatannya secara kreatif. Namun,
diingatkan oleh Pradopo (2000: 47) bahwa penggunaan kata yang terlalu jauh dari arti
yang diketahui oleh masyarakat membuat karya tersebut menjadi kurang komunikatif.
(b) Konvensi Sastra
Ketika berada dalam sebuah karya sastra, arti bahasa (meaning) tersebut akan
memperoleh makna tambahan yang disesuaikan dengan sistem dan konvensi sastra
sebagai sistem semiotika tingkat kedua (ein sekundäres modellbildendes system;
secondary order semiotics) (Lotman melalui Teeuw, 1988: 99). Pada tataran ini, yang
dicari adalah makna (significance) bahasa yang didapatkan melalui tempat dan fungsi
bahasa tersebut di dalam struktur karya sastra (Pradopo, 2000: 48). Makna tambahan ini,
25
seperti istilah yang diajukan Preminger (1974; 980--981), biasanya juga bersumber dari
arti kata tersebut (Pradopo, 1995:121).
Dalam perwujudannya di dalam karya sastra, terlihat penyimpangan penggunaan
bahasa dari konvensinya yang dikenal dengan istilah defamiliarisasi atau deotomatisasi
(Teeuw, 1983: 4). Pembaca, termasuk peneliti, bertugas untuk mengungkapkan makna
yang tersembunyi di dalam karya sastra tersebut sehingga dapat dipahami dengan baik.
Selain konvensi sastra yang diungkapkan di atas, perlu pula diperhatikan genre
karya sastra yang diteliti. Secara garis besar, karya sastra dibagi atas beberapa jenis-jenis
sastra (genre), seperti puisi, prosa, dan drama. Genre puisi terdiri atas ragam puisi lirik,
pantun, syair, soneta, balada, dan sebagainya. Sementara genre prosa terdiri atas cerpen,
novel, dan roman sebagai ragam utama (Pradopo, 2001: 73).
Untuk puisi, konvensi yang harus diperhatikan adalah yang berkenaan dengan
bahasa kiasan, sarana retorika, gaya bahasa, ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense.
Konvensi lain yang terdapat pada puisi adalah konvensi visual yang terdiri atas bait,
baris sajak, enjambement, sajak (rima), tipografi, dan homologue. Sementara pada prosa,
yang kerap disebut juga dengan cerita rekaan, konvensi yang harus diperhatikan adalah
plot, penokohan, latar, dan pusat pengisahan (Pradopo, 2001, 74). Adapun untuk drama
konvensinya adalah plot, karakter, dan tema yang disebut sebagai struktur dan dialog,
suasana hati (mood), dan spektakel (spactacle) yang merupakan bagian dari tekstur
drama (Kernodles melalui Soemanto, 2002:15).
(c) Kerangka Sejarah; Hubungan Intertekstual
Sebuah karya sastra haruslah dipandang sebagai respon atau jawaban terhadap
karya sastra sebelumnya (Riffaterre via Teeuw, 1983: 65). Oleh karena itu, sebuah karya
26
sastra dapat dipahami secara lebih baik apabila dihubungkan atau dibandingkan dengan
karya sastra lain yang ditanggapi tersebut.
Pernyataan ini sesuai pula dengan pendapat Julia Kristeva, (melalui Teeuw,
1988:145) yang menyatakan bahwa setiap teks sastra harus dibaca dengan latar belakang
teks lain; tidak ada sebuah teks pun yang benar-benar mandiri. Kristeva (melalui Culler,
1977:139) mengemukakan bahwa setiap karya sastra merupakan mosaik kutipan-
kutipan, penyerapan, dan transformasi dari teks lain.
Memahami sebuah karya sastra dengan menghubungkannya dengan karya
sastra lain, seperti yang diterangkan di atas, menggunakan prinsip intertekstual. Sebuah
karya dipahami sebagai bagian dari konteks rangkaian sejarah sastra (Pradopo, 1995:
167). Pada intertekstual, karya yang lebih awal ada atau yang menjadi latar karya lain
disebut sebagai hipogram (Riffaterre, 1978: 11), sedangkan karya yang lahir sesudahnya
disebut karya transformasi.
Sebuah karya sastra yang dianggap mempunyai hubungan intertekstual tidak
selalu harus mempunyai kesamaan karena seperti yang disampaikan Julia Kristeva via
Teeuw (1988:145—146) hubungan ini dapat pula dalam arti penyimpangan dan
transformasi model teks; pemberontakan atau penyimpangan mengandaikan adanya
sesuatu yang dapat diberontaki ataupun disimpangi.
Lotman menyatakan bahwa ada kecenderungan pengarang tradisional
mengikuti konvensi dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sementara pengarang
modern berusaha menyimpanginya. Sistem artistik yang dilakukan oleh pengarang
tradisional disebut estetika identitas dan estetika yang diikuti pengarang modern disebut
estetika pertentangan (dalam Teeuw, 1988:26—27; Abdullah, 1991:100). Oleh karena
27
itu, sebuah hubungan intertekstual dapat berupa afirmasi, negasi, atau inovasi (Abdullah,
1991:105) terhadap apa yang direspon pengarang. Dengan menyandingkan karya-karya
yang berhipogram, makna dari karya-karya tersebut dapat diketahui secara lebih baik
(Pradopo, 2000: 55).
Menurut Pradopo (1983:32) dalam perbandingan secara intertekstual ini, dapat
diperbandingkan baik masalah yang ditampilkan struktur penceritaan maupun gaya
ataupun teknik pengekspresiannya.
(d) Relevansi Sosial Budaya
Untuk memahami sebuah karya sastra, perlu diperhatikan latar sosial budaya
ketika karya tersebut muncul. Hal tersebut disebabkan, seperti yang diungkapkan Teeuw
(1983: 4, 8), karya sastra tidak terlahir dari kekosongan budaya. Dengan demikian,
diperlukan pengetahuan mengenai latar sosial budaya dari karya tersebut yang secara
tidak langsung terungkap dalam sistem bahasanya (1988: 100).
Pradopo (2000: 59) menyatakan bahwa latar sosial budaya tersebut dapat dilihat
di dalam karya sastra tersebut. Latar tersebut akan tercermin dari tokoh, sistem
kemasyarakatan, kebiasaan, adat-istiadat, pergaulan, kesenian, dan benda-benda budaya
yang ada di dalam karya tersebut.
Pengetahuan mengenai latar sosial budaya ini sangat membantu pembaca untuk
memahami karya sastra. Karya yang mempunyai latar sosial budaya yang berbeda akan
memperlihatkan tindakan-tindakan yang berbeda dari tokoh-tokohnya. Pemahaman
terhadap latar inilah yang memungkinkan pembaca “mengerti” tindakan tokoh Pariyem
seperti yang terdapat dalam novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi. Selain itu,
28
latar sosial yang berbeda ini akan memunculkan cerita yang yang dianggap mempunyai
kesamaan, tetapi tetap mempunyai perbedaan. Hal tersebut terlihat pada contoh cerita
bertema inces, Oedipus yang berasal dari Yunani dan Sangkuriang dari Sunda yang
dibahas oleh Damono (2005: 54--60) ketika menulis mengenai “Membandingkan
Dongeng”. Pada cerita Oedipus, tokoh tersebut berhasil menikahi ibunya sendiri, tetapi
di dalam cerita Sangkuriang hal itu tidak terjadi. Hal tersebut tidak terlepas dari latar
sosial budaya yang berbeda dari kedua cerita tersebut.
1.7 Metodologi Penelitian
1.7.1 Metode Penelitian
Secara umum, metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati (Moleong, 1998:3). Penelitian
dengan metode ini bertujuan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data yang
sedalam-dalamnya. Penelitian dengan metode ini tidak mengutamakan besarnya
populasi sehingga dengan data yang sedikit atau terbatas pun, penelitian ini dapat
dilakukan (Denzin dan Lincoln melalui Hariwijaya, 2007:71).
Secara khusus, penelitian ini akan menggunakan metode perbandingan sastra
yang dibantu oleh teori struktural- semiotik. Hal tersebut disebabkan sastra merupakan
fenomena yang universal, sekaligus individual (Chamamah-Soeratno, 2001:10). Sebagai
fenomena yang universal, sastra dapat diteliti dengan menggunakan metode umum.
Akan tetapi, sebagai fenomena individual, sastra juga harus diperlakukan secara khusus.
Oleh karena itu, penelitian sastra membutuhkan sebuah metode yang khusus pula.
29
Chamamah-Soeratno (1994:14--16) mengemukakan bahwa karya sastra memiliki sifat
khusus dilihat dari sisi bahannya, yaitu bahasa yang berbeda dengan pemakaian bahasa
sehari-hari. Pemakaian bahasa yang berbeda tersebut pada hakikatnya dalam rangka
fungsi sastra sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi yang
bermacam-macam kepada pembaca yang bermacam-macam pula.
Penelitian “Cerita Batu Belah Batu Bertangkup di Indonesia dan Malaysia:
Kajian Perbandingan Sastra” ini menggunakan metode perbandingan. Seperti yang
dikemukakan Damono (2005:2), dalam penelitian yang menggunakan sastra banding,
metode ini merupakan langkah utama. Azas yang dipergunakan adalah banding-
membandingkan. Hal yang dibandingkan tersebut adalah struktur dari dua karya sastra
yang dipilih, yaitu cerita BBBB BMSy dengan BBBB ASA. Adapun unsur yang
dibandingkan tersebut adalah plot, tokoh, latar, dan tema.
Unsur yang dibandingkan disesuaikan dengan teori pendukung yang
dipergunakan. Di dalam penelitian ini, teori pendukung yang dipergunakan adalah teori
struktural-semiotik. Berdasarkan teori ini, karya sastra adalah sebuah struktur yang
bermakna (Pradopo, 1995: 141). Makna didapat melalui totalitas unsur-unsur karya
tersebut (Hawkes, 1978: 17--18).
Berkenaan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan di dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
Pertama, mendeskripsikan sejarah berdiri dan runtuhnya Kesultanan Malaka
dan berbagai versi cerita ”BB” di Indonesia, sinopsis cerita BBBB yang dijadikan objek,
serta penulisnya. Sejarah Melaka diungkap untuk mengetahui sejarah pemisahan daerah
Melayu yang menjadi tempat hidup dan berkembangnya kedua cerita BBBB. Penyebutan
30
beberapa versi cerita BBBB dimaksudkan untuk menempatkan kedua cerita ini sebagai
bagian dari berbagai cerita BBBB yang ada.
Kedua, menganalisis struktur cerita-cerita BBBB, baik ditulis BM Syamsuddin
maupun yang ditulis oleh Abd. Samad Ahmad. Analisis difokuskan untuk menemukan
plot, tokoh, latar, dan tema yang membentuk cerita-cerita tersebut. Langkah ini perlu
dilakukan untuk mengetahui struktur kedua cerita BBBB sehingga kemudian dapat
dibandingkan.
Metode yang dipergunakan untuk menemukan hal di atas adalah pembacaan
heuristik dan hermeneutik yang diajukan Riffaterre (1978: 5—6). Pada pembacaan
heuristik karya dibaca berdasarkan struktur bahasanya. Sementara pada pembacaan
hermeneutik, karya dibaca berdasarkan konvensi sastranya (Pradopo, 1995:135).
Pada cerita rekaan (cerkan), seperti yang menjadi objek kajian pada penelitian
ini, pembacaan heuristik yang dilakukan adalah pembacaan ”tatabahasa” ceritanya,
yaitu pembacaan cerita dari awal sampai akhir cerita. Pembacaan dengan cara ini dapat
dipermudah dengan membuat sinopsis cerita. Dalam hal ini, cerita yang berplot sorot
balik dapat dibaca berplot lurus. Dengan demikian, bagian-bagian yang berurutan dari
cerita tersebut dapat diterangkan (Pradopo, 2001: 84).
Setelah pembacaan secara heuristik, pembacaan dilanjutkan dengan pembacaan
hermeneutik atau disebut juga retroaktif. Pada pembacaan ini, karya dibaca kembali
secara bolak-balik (retroaktif) dan kemudian diberi penafsiran (hermeneutik). Pada tahap
ini, karya sastra dibaca sebagai bagian dari sistem semiotik tingkat kedua sehingga yang
didapatkan adalah makna (significance) dari karya tersebut.
31
Ketiga, menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan unsur-
unsur yang terdapat pada cerita-cerita tersebut. Setelah struktur kedua karya sastra itu
dapat diungkap, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada
cerita BBBB BM Syam dan BBBB ASA dideskripsikan satu per satu, terutama yang
berkaitan dengan struktur plot, tokoh, latar, dan tema. Pada bagian ini, dijelaskan pula
penyebab terjadinya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada
cerita-cerita BBBB tersebut.
Keempat, membuat kesimpulan dari penelitian ini. Setelah mengetahui beberapa
persamaan dan perbedaan pada cerita BBBB yang berasal dari Indonesia dan Malaysia di
atas, dibuat simpulan terhadap makna yang didapat melalui analisis kedua cerita
tersebut.
1.7.2 Populasi dan Sampel
Di dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh cerita rakyat
“BB” dalam berbagai genre dan versi yang ada selama ini, baik yang terjangkau oleh
penulis ataupun tidak. Populasi cerita rakyat “BB” dikumpulkan sebanyak mungkin
melalui studi kepustakaan dan internet.
Dari populasi tersebut, teridentifikasi beberapa cerita ”BB” dari berbagai genre
dan versi sebagai berikut.
a. satu puisi, yaitu sajak ”Batu Belah” yang ditulis Amir Hamzah dalam kumpulan
sajaknya Nyanyi Sunyi;
b. sebelas teks cerita ”BB” bergenre prosa. Dua dari cerita tersebut menggunakan
tulisan Arab-Melayu;
32
c. satu cerita drama “Bangsawan Batu Belah Batu Bertangkup” ditulis oleh Lenny
Erwan;
d. dua lagu yang berkisah tentang cerita “BB”, yaitu lagu ciptaan Mohd. Syed bin
Ahmad dan lagu yang dinyanyikan oleh grup band Malaysia Poetical Kingdom
dari Malaysia;
e. satu film “Batu Belah Batu Bertangkup” yang disutradarai oleh Jamil Sulong dari
Malaysia;
f. sinetron dengan judul “Batu Belah”. Sinetron ini ditayangkan di Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI); dan
g. sebuah cerita animasi “Batu Belah Batu Bertangkup” versi (tokoh) burung
berasal dari Malaysia yang dibuat oleh Adi Lukman bin Saad.
Dari cerita-cerita ”BB” dan transformasinya tersebut di atas, dipilih dua cerita
sebagai sampel, yaitu:
1. Cerita Batu Belah Batu Bertangkup: Cerita Rakyat di Kepulauan Siantan Karya
BM Syamsuddin (1983)
Cerita BBBB yang ditulis BM Syamsuddin ini diperuntukkan bagi anak-anak.
Hal tersebut terlihat dari tulisan “bacaan anak” yang tertera di bagian sudut
kanan atas pada lembar halaman judul buku (cover). Buku ini diterbitkan oleh
Balai Pustaka pada tahun 1983.
2. Cerita Batu Belah Batu Bertangkup Karya Abd. Samad Ahmad (1971)
Cerita BBBB karya Abd. Samad Ahmad ini pertama kali dicetak pada tahun 1963
oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. Setelah itu, dengan penerbit yang
sama, pada tahun 1969, terbit cetakan kedua, disusul cetakan ketiga pada tahun
33
1971. Terakhir diketahui bahwa cerita ini kembali dicetak oleh Dewan Bahasa
dan Pustaka Malaysia pada tahun 1999. Akan tetapi, pada penelitian ini, cerita
BBBB yang digunakan sebagai sampel adalah cerita BBBB yang terbit pada tahun
1971. Di dalam sekapur sirih (Se-kapor Sireh) dan pendahuluan yang terdapat
pada buku tersebut, tidak disebutkan kalau terdapat perubahan pada buku-buku
terbitan 1963, 1969, dan 1971 tersebut.
Kedua sampel ini yang menjadi sumber data bagi penelitian ini. Kedua karya ini
dipilih sebagai sampel disebabkan hal-hal sebagai berikut.
1. Kedua cerita BBBB ini dianggap memiliki unsur cerita yang lebih lengkap
dibandingkan dengan cerita-cerita ”BB” lainnya. Cerita dimulai ketika keluarga ini
masih memiliki ayah sampai kedua tokoh anak ini mulai memperoleh kesenangan
hidup.
2. Cerita-cerita BBBB yang dipilih sebagai sampel ini termasuk cerita ”BB” yang sudah
lama dicetak, yaitu tahun 1983 untuk cerita BBBB BMSy dan 1971 untuk cerita
BBBB ASA.
3. Cerita-cerita BBBB ini ditulis oleh pengarang-pengarang yang diakui
kepengarangannya di negara masing-masing. Oleh karena itu, karya-karya mereka
dianggap bermutu dan dapat mewakili cerita-cerita ”BB” lainnya.
1.8 Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi atas lima bab. Bab I Pengantar berisi latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
34
Di dalam bab II dideskripsikan latar belakang sejarah Kesultanan Melaka, cerita-
cerita Batu Belah Batu Bertangkup yang ada di Nusantara, dan pengarang BBBB.
Pada bab III dikemukakan struktur cerita BBBB karya BM Syamsuddin
(Indonesia) dan Abd. Samad Ahmad (Malaysia).
Bab IV berisi penjelasan mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan yang terdapat pada cerita-cerita BBBB yang berasal dari negara yang berbeda
tersebut.
Di dalam bab V ini, dimuat simpulan terhadap penelitian berjudul “Cerita Batu
Belah Batu Bertangkup di Indonesia dan Malaysia: Kajian Perbandingan Sastra”. Pada
bagian ini disampaikan pula saran-saran yang dirasa perlu untuk penelitian selanjutnya.