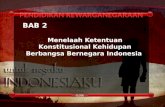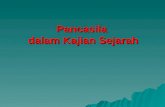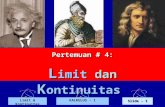Bab 2
description
Transcript of Bab 2

5
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kolon
2.1.1 Anatomi
Kolon merupakan tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 5
kaki yang terbentang dari sekum sampai canalis ani. Kolon dibagi menjadi
caecum, appendix vermiformis, colon (ascendens, tranversum, descendens,
dan sigmoid) dan rectum. Pada caecum terdapat katup illeocaecal dan
appendix yang melekat pada ujung caecum. Caecum menempati 2/3 atau 3
inci pertama dari kolon. Katup illeocaecal mengontrol aliran kimus dari ileum
ke caecum (Gambar 2.1) (Snell, 2006).
(Sobotta, 2003)
Gambar 2.1
Anatomi Colon ascendens, Colon descendens, Colon transversum, Colon sigmoid, dan
Rectum

6
2.1.1.1 Caecum
a. Lokasi dan Deskripsi
Caecum (Gambar 2.2) adalah bagian yang terletak di
perbatasan ileum dan intestinum crassum. Caecum merupakan
kantong buntu yang terletak pada fossa iliaca dextra. Panjang
caecum sekitar 2 ½ inci (6 cm) dan seluruhnya diliputi oleh
peritoneum. Seperti pada colon, stratum longitudinale tunica
muscularis terbatas pada tiga pita tipis yaitu taenia coli yang
bersatu pada dasar appendix vermiformis dan membentuk
stratum longitudinale tunica muscularis yang sempurna pada
appendix vermiformis. Caecum sering teregang oleh gas dan
dapat diraba melalui dinding anterior abdomen pada orang
hidup (Snell, 2006).
(Sobotta, 2003)
Gambar 2.2
Caecum tampak ventral, Appendix vermiformis di titik pertemuan
taenia omentalis, taenia libera, dan taenia mesocolica

7
Terdapat hubungan antara caecum dengan jaringan
sekitarnya, yaitu:
Ke anterior: lengkung-lengkung intestinum tenue, kadang-
kadang sebagian omentum majus, dan dinding anterior abdomen
pada regio iliaca dextra. Ke posterior: musculus psoas major
dan musculus iliacus, nervus femoralis, dan nervus cutaneus
femoris lateralis. Appendix vermiformis sering ditemukan di
belakang caecum (Snell, 2006).
b. Pendarahan
Arteriae caecalis anterior dan arteriae caecalis posterior
merupakan percabangan dari arteriae ileocolica, dimana
arteriae ileocolica adalah cabang dari arteria mesenterica
superior. Venae mengikuti arteriae yang sesuai dan
mengalirkan darahnya ke vena mesenterica superior (Snell,
2006).
c. Persarafan
Saraf–saraf berasal dari cabang–cabang saraf simpatis dan
parasimpatis (nervus vagus) membentuk plexus mesentericus
superior (Snell, 2006).
2.1.1.2 Appendix vermiformis
a. Lokasi dan Deskripsi
Appendix vermiformis adalah organ sempit, berbentuk
tabung yang mempunyai otot dan mengandung banyak jaringan
limfoid. Panjang appendix vermiformis bervariasi dari 3-5 inci

8
(8-13 cm). Dasarnya melekat pada permukaan posteromedial
caecum, sekitar 1 inci (2,5 cm) di bawah junctura ileocaecalis.
Bagian appendix vermiformis lainnya bebas. Appendix
vermiformis diliputi seluruhnya oleh peritoneum, yang melekat
pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenue melalui
mesenteriumnya sendiri yang pendek, mesoappendix (Snell,
2006).
Appendix vermiformis terletak di regio iliaca dextra, dan
pangkal diproyeksikan ke dinding anterior abdomen pada titik
sepertiga bawah garis yang menghubungkan spina iliaca
anterior superior dan umbilicus (titik McBurney) (Snell,
2006).
b. Posisi Ujung Appendix Vermiformis yang Umum
Ujung appendix vermiformis mudah bergerak dan mungkin
ditemukan pada tempat-tempat berikut ini:
1. Menggantung ke arah bawah masuk ke dalam pelvis
berhadapan dengan dinding pelvis dextra,
2. Melengkung di belakang caecum,
3. Menonjol ke atas sepanjang pinggir lateral caecum, dan
4. Di depan atau di belakang pars terminalis ileum.
Posisi pertama dan kedua merupakan posisi yang sering
ditemukan (Snell, 2006).
c. Pendarahan

9
Arteriae appendicularis merupakan cabang arteria
caecalis posterior. Arteria ini berjalan menuju ujung appendix
vermiformis di dalam meso-appendix. Vena appendicularis
mengalirkan darahnya ke vena caecalis posterior (Snell, 2006).
d. Persarafan
Saraf-saraf bearasal dari cabang-cabang saraf simpatis dan
saraf parasimpatis (nervus vagus) dari plexus mesentericus
superior. Serabut saraf aferen yang menghantarkan rasa nyeri
visceral dari appendix vermiformis berjalan bersama saraf
simpatis dan masuk ke medulla spinalis setinggi vertebra
thoracica X (Snell, 2006).
2.1.1.3 Colon ascendens
a. Lokasi dan Deskripsi
Panjang colon ascendens sekitar 5 inci (13 cm) dan terletak
di kuadran kanan bawah. Colon ascendens (Gambar 2.3)
membentang ke atas dari caecum sampai permukaan inferior
lobus hepatis dextra, lalu colon ascendens membelok ke kiri,
membentuk flexura coli dextra, dan melanjutkan diri sebagai
colon transversum. Di dalam colon ascendens terdapat plicae
semilunares coli. Colon ascendens diliputi oleh tiga pita seperti
pada caecum. Peritoneum meliputi bagian depan dan samping
colon ascendens serta menghubungkan colon ascendens dengan
dinding posterior abdomen (Snell, 2006).

10
(Sobotta, 2003)
Gambar 2.3
Colon ascendens, Ileum, Caecum, dan Appendix vermiformis
Terdapat hubungan antara colon ascendens dengan jaringan
sekitarnya, yaitu:
Ke anterior: lengkung-lengkung intestinum, omentum majus,
dan dinding anterior abdomen. Ke posterior: musculus iliacus,
crista iliaca, musculus quadrates lumborum, origo musculus
transverses abdominis, dan polus inferior ren dextra. Nervus
iliohypogastricus dan nervus ilioinguinalis berjalan di
belakangnya (Snell, 2006).
b. Pendarahan
Arteria ileocolica dan arteria colica dextra yang merupakan
cabang arteria mesenterica superior. Venae mengikuti arteriae
yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior (Snell,
2006).
c. Persarafan
Saraf berasal dari cabang saraf simpatis dan saraf
parasimpatis (nervus vagus) dari plexus mesentericus superior
(Snell, 2006).

11
2.1.1.4 Colon transversum
a. Lokasi dan Deskripsi
Panjang colon transversum (Gambar 2.4) sekitar 15 inci (38
cm) dan berjalan menyilang abdomen, menempati regio
abdominalis. Colon transversum mulai dari flexura coli dextra
di bawah lobus hepatis dextra dan tergantung ke bawah oleh
mesocolon transversum dari pancreas. Di dalam colon
transversum terdapat plicae semilunares coli. Colon
transversum diliputi oleh tiga pita seperti pada caecum (Snell,
2006).
Kemudian colon transversum berjalan ke atas sampai
flexura coli sinistra di bawah lien. Flexura coli sinistra lebih
tinggi daripada flexura coli dextra dan digantung ke diaphragma
oleh ligamentum phrenicocolicum (Snell, 2006).
(Sobotta, 2003)
Gambar 2.4
Colon transversum; Omentum majus dilipat ke atas untuk
memperlihatkan Taenia libera; lipatan selaput lendir di dalam bagian
usus yang tampak terbuka; tampak ventral kaudal
Terdapat hubungan antara colon transversum dengan
jaringan sekitarnya, yaitu:

12
Ke anterior: omentum majus, dan dinding anterior abdomen
(regio umbilicalis dan hypogastrium). Ke posterior: pars
descendens duodenum, caput pancreatic, dan lengkung-
lengkung jejunum dan ileum (Snell, 2006).
b. Pendarahan
Dua pertiga bagian proksimal colon transversum
diperdarahi oleh arteria colica media, cabang arteria
mesenterica superior. Sepertiga bagian distal diperdarahi oleh
arteria colica sinistra, cabang arteria mesenterica inferior.
Venae mengikuti arteriae yang sesuai dan bermuara ke vena
mesenterica superior dan vena mesenterica inferior (Snell,
2006).
c. Persarafan
Dua pertiga proksimal colon transversum dipersarafi oleh
saraf simpatis dan saraf parasimpatis (nervus vagus) melalui
plexus mesentericus superior, sepertiga distal dipersarafi oleh
saraf simpatis dan parasimpatis nervi splanchnici pelvic melalui
plexus mesentericus inferior (Snell, 2006).
2.1.1.5 Colon descendens
a. Lokasi dan Deskripsi
Panjang colon descendens sekitar 10 inci (25 cm) dan
terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Kolon ini berjalan ke
bawah dari flexura coli sinistra sampai pinggir pelvis, disini
colon transversum melanjutkan diri menjadi colon sigmoid.

13
Peritoneum meliputi permukaan depan dan sisi-sisinya serta
menghubungkannya dengan dinding posterior abdomen (Snell,
2006).
Terdapat hubungan antara colon descendens dengan
jaringan sekitarnya, yaitu:
Ke anterior: lengkung-lengkung intestinum tenue, omentum
majus, dan dinding anterior abdomen. Ke posterior: margo
lateralis ren sinistra, origo musculus transversum abdominis,
musculus quadratus lumborum, crista iliaca, musculus iliacus,
dan musculus psoas major sinistra. Nervus iliohypogastricus
dan nervus ilioinguinalis, nervus cutaneus femoris lateralis,
serta nervus femoralis juga terletak di belakangnya (Snell,
2006).
b. Pendarahan
Arteria colica sinistra dan arteriae sigmoideae merupakan
cabang arteria mesenterica inferior. Venae mengikuti arteriae
yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica inferior (Snell,
2006).
c. Persarafan
Saraf simpatis dan parasimpatis nervi splanchnici pelvic
melalui plexus mesentericus inferior (Snell, 2006).

14
2.1.1.6 Colon sigmoid
a. Lokasi dan Deskripsi
Colon sigmoid panjangnya sekitar 25-38 cm dan dimulai
sebagai kelanjutan dari colon descendens. Batas anterior dari
colon sigmoid pada pria berbeda dengan wanita. Pada pria,
anteriornya berbatasan dengan vesica urinaria, sedangkan pada
wanita berbatasan dengan permukaan posterior uterus dan bagian
atas vagina (Snell, 2006).
b. Pendarahan
Pendarahan colon sigmoid berasal dari rami sigmoideum a.
mesenterica inferior. Vena colon sigmoid sesuai dengan
arterinya dan dipercabangkan dari sistem vena porta (Snell,
2006).
c. Persarafan
Persarafan berasal dari plexus hypogastricus inferior (Snell,
2006).
2.1.1.7 Rectum
a. Lokasi dan Deskripsi
Rectum panjangnya sekitar 13 cm dan dilai dari depan
vertebrae sacralis 3 sebagai lanjutan colon sigmoid. Rectum
berjalan ke bawah mengikuti lengkungan sacrum dan coccygis
dan berakhir 2,5 cm di depan ujung coccygis dengan menembus
diaphragma pelvis dan melanjutkan diri sebagai canalis ani,
bagian bawah rectum yang terletak tepat di atas diaphragma

15
pelvis melebar membentuk ampulla recti. Lapisan muskular
rectum tersusun atas lapisan otot polos longitudinal (luar) dan
sirkular (dalam) (Snell, 2006).
b. Pendarahan
Perdarahan rectum berasal dari a. rectalis superior, a.
rectalis media, dan a. rectalis inferior (Snell, 2006).
c. Persarafan
Persarafan rectum berasal dari plexus hypogastricus inferior
(Snell, 2006).
2.1.2 Fisiologi
Kolon terdiri dari caecum, colon ascendens, colon transversum, colon
descendens, colon sigmoid, dan rectum. Panjang kolon sekitar 1,2 meter dan
diameternya antara 6 sampai 9 cm. Kira-kira 1,5 L kimus memasuki kolon
setiap harinya melalui sfingter yang disebut sfingter ileocaecal. Distensi
bagian akhir ileum menyebabkan menutupnya sfingter, sehingga
mempertahankan laju masuknya kimus tetap optimum untuk memaksimalkan
fungsi utama kolon, yaitu untuk mengabsorbsi sebagian besar air dan
elektrolit. Dari 1,5 L kimus yang memasuki kolon, akan berkurang sampai
sekitar 150 g feses yang terdiri dari 100 mL air dan 50 g solid (Ward, Clarke,
Linden, 2009).
Pergerakan kimus melalui kolon mencakup pergerakan mencampur dan
propulsi. Akan tetapi, karena fungsi utama kolon adalah menyimpan sisa-sisa
makanan dan mengabsobrsi air dan elektrolit, maka pergerakannya pelan dan
lambat (sekitar 5-10 cm/jam). Kimus biasanya tetap berada di kolon sampai 20

16
jam. Pergerakan mencampur disebut juga haustrasi dan akibat pergerakan ini
terbentuk kompartemen-kompartemen dengan bentuk seperti kantung, disebut
haustra. Isi haustra seringkali didorong bolak-balik ke haustra lainnya, proses
ini disebut haustral shuttling. Proses ini membantu pemajanan kimus ke
permukaan mukosa dan membantu reabsorbsi air dan elektrolit. Pada bagian
distal kolon, kontraksi lebih pelan dan kurang propulsif, dan akhirnya feses
akan terkumpul di colon descendens (Ward, Clarke, Linden, 2009).
Beberapa kali dalam sehari, terjadi peningkatan aktivitas dalam kolon,
dimana terjadi pergerakan propulsif yang kuat, disebut pergerakan massal
(mass movement). Hal ini menyebabkan pengosongan sebagian besar isi kolon
proksimal ke bagian yang lebih distal. Pergerakan massal ini diinisiasi oleh
serangkaian reflek intrinsik yang kompleks yang dimulai dengan distensi
lambung dan duodenum segera setelah mengkonsumsi makanan (Ward,
Clarke, Linden, 2009).
Jika massa feses yang kritis (yang cukup banyak) didorong ke dalam
rectum, maka akan dirasakan dorongan defekasi. Distensi mendadak dinding
rectum oleh pergerakan massal akhir ini akan menyebabkan reflek defekasi.
Reflek ini terdiri dari kontraksi rectum, relaksasi sfingter analis interna, dan
pada awalnya kontraksi sfingter analis eksterna. Kontraksi awal ini kemudian
segera diikuti oleh reflek relaksasi sfingter yang diinisiasi oleh peningkatan
aktivitas peristaltis pada colon sigmoid dan peningkatan tekanan rectum.
Akhirnya feses dikeluarkan. Relaksasi reflek ini dapat dikalahkan oleh
aktivitas pusat yang lebih tinggi, menyebabkan kontrol volunter pada sfingter
yang bisa menunda pengeluaran feses. Distensi rectum yang terlalu lama bisa

17
menyebabkan peristalsis tebalik, dimana isi rectum dikembalikan ke kolon
sehingga dorongan defekasi hilang sampai terjadi pergerakan massal
berikutnya dan/ atau sampai waktu yang lebih sesuai (Ward, Clarke, Linden,
2009).
Kimus yang memasuki kolon bersifat isotonik, namun demikian pada
kolon, air ternyata lebih banyak diabsorbsi daripada elektrolit, sehingga air
diabsorbsi melawan gradien konsentrasinya. Proses ini dikontrol oleh Na+-K
+-
ATPase yang terletak di membran basolateral dan membran lateral sel epitel
yang melapisi dinding kolon. Permukaan mukosa kolon besar relatif lebih
halus dengan tanpa vili (hanya ada mikrovili); namun demikian, terdapat
kripta dan sebagian besar sel-sel adalah sel absorb kolumnar dengan banyak
sel goblet penyekresi mukus. Na+ dikeluarkan oleh pompa membran ke rongga
ekstraseluler. Tight junction (persambungan erat) pada sisi lumen sel akan
mencegah difusi Na+ dan Cl
- dari ruang ektraseluler ke dalam lumen; hal ini
menyebabkan larutan yang dekat lumen bersifat hipertonik, sehingga air
berdifusi dari isi lumen. Pada dasarnya, terdapat pergerakan netto ion K+ dan
ion bikarbonat dari darah ke kolon yang terjadi karena perbedaan potensial
yang muncul akibat absorbsi asimetris Na+ dan Cl
- yang melintasi dinding sel
(Ward, Clarke, Linden, 2009).
Mayoritas bakteri yang terdapat di saluran pencernaan ditemukan di
kolon, karena lingkungan yang asam pada bagian lain saluran pencernaan akan
menghancurkan sebagian mikroflora ini. Sembilan puluh sembilan persen
bakteri ini bersifat anaerob dan mengandung 1011
bakteri. Bakteri ini terlibat
dalam sintesis vitamin K, B12, tiamin, dan riboflavin, pemecahan asam

18
empedu primer menjadi sekunder, dan konversi bilirubin menjadi metabolit
tidak berpigmen, dimana semuanya menjadi mudah diabsorbsi oleh saluran
pencernaan. Bakteri ini juga memecah kolesterol, sejumlah zat aditif dalam
makanan dan obat-obatan (Ward, Clarke, Linden, 2009).
2.2 Kanker Kolorektal
2.2.1 Definisi
Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian
dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak
normal, cepat, dan tidak terkendali. Sel-sel kanker akan terus membelah diri.
Kanker bisa terjadi dari berbagai jaringan dalam berbagai organ, seperti sel
kulit, sel hati, sel darah, sel otak, sel lambung, sel usus, sel paru, sel saluran
kencing, dan berbagai macam sel tubuh lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan
dan perkembangbiakannya, sel-sel kanker membentuk suatu massa dari
jaringan ganas yang menyusup ke jaringan di dekatnya (invasif) dan bisa
menyebar (metastasis) ke seluruh tubuh. Sel-sel kanker dibentuk dari sel-sel
normal dalam suatu proses rumit yang disebut transformasi, yang terdiri dari
tahap inisiasi dan promosi (Dinkes Gorontalo, 2007).
Colorectal cancer atau dikenal sebagai kanker usus besar adalah suatu
bentuk keganasan yang terjadi pada kolon, rektum, dan appendix (usus buntu).
Di negara maju, kanker ini menduduki peringkat ke tiga yang paling sering
terjadi, dan menjadi penyebab kematian yang utama di dunia barat. Untuk
menemukannya diperlukan suatu tindakan yang disebut sebagai kolonoskopi,
sedangkan untuk terapinya adalah melalui pembedahan diikuti kemoterapi
(Arief, 2008).

19
2.2.2 Etiologi
Walaupun penyebab kanker kolorektal (seperti kanker lainnya) belum
diketahui, namun telah dikenali beberapa faktor predisposisi. Salah satu faktor
predisposisi yang penting yaitu berkaitan dengan kebiasaan makan (Price,
Lorraine, 2005).
Burkitt (1971) mengemukakan bahwa diet rendah serat dan tinggi
karbohidrat murni mengakibatkan perubahan flora feses dan degradasi garam
empedu atau hasil pemecahan protein dan lemak, sebagian zat ini bersifat
karsinogenik. Diet rendah serat juga menyebabkan pemekatan zat berpotensi
karsinogenik ini menjadi feses yang bervolume lebih kecil. Selain itu, masa
transit feses meningkat. Akibatnya kontak zat berpotensi karsinogenik dengan
mukosa usus bertambah lama (Price, Lorraine, 2005).
Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi
meningkatnya terjadinya kanker usus, antara lain:
1. usia: golongan orang tua (berusia diatas 50 tahun) lebih beresiko
terkena kanker usus,
2. obesitas atau penderita diabetes,
3. merokok,
4. riwayat kanker usus dalam keluarga,
5. kontak dengan zat-zat kimia tertentu seperti logam berat, toksin, dan
ototoksin (Sorra, 2008).

20
2.2.3 Patofisiologi
2.2.3.1 Kelainan genetik
Banyak kelainan genetik yang dikaitkan dengan keganasan
kolorektal diantaranya sindroma poliposis dan sindroma Lynch. Kanker
kolorektal terjadi sebagai akibat dari kerusakan genetik pada lokus yang
mengontrol pertumbuhan sel. Terdapat dua mekanisme yang
menimbulkan instabilitas genom dan berujung pada kanker kolorektal,
yaitu instabilitas kromosom dan instabilitas mikrosatelit (Abdullah,
2006).
Instabilitas kromosom merupakan hasil perubahan besar pada
kromosom seperti translokasi, amplifikasi, delesi, dan berbagai bentuk
kehilangan alel lainnya disertai dengan hilangnya heterozigositas pada
DNA (Deoxyribonucleic Acid) yang berdekatan dengan lokasi kelainan-
kelainan tersebut (Abdullah, 2006).
Awal dari proses kejadian kanker kolorektal yang melibatkan
mutasi somatik terjadi pada gen APC (Agent Presenting Cell ) baik
sporadik maupun familial. Gen APC mengatur kematian sel dan mutasi
yang terjadi menyebabkan proliferasi selanjutnya berkembang menjadi
adenoma. Mutasi pada proto onkogen seluler K-ras yang biasanya terjadi
pada adenoma kolon yang berukuran besar akan menyebabkan gangguan
pertumbuhan sel yang tidak normal (Abdullah, 2006).
Transisi dari adenoma menjadi karsinoma merupakan akibat dari
mutasi gen supresor p53. Mutasi gen p53 menyebabkan sel dengan
kerusakan DNA tetap dapat bereplikasi yang menghasilkan sel-sel DNA

21
dengan kerusakan yang lebih parah. Hal ini menyebabkan kehilangan
gen supresor tumor yang lain yang merupakan tahap akhir dari
transformasi ke arah keganasan (Abdullah, 2006).
Pada instabilitas mikrosatelit, terjadi peningkatan resiko mutasi-
mutasi noktah yang mempengaruhi satu atau lebih pasangan basa DNA
secara acak sepanjang genom. Gen yang mempengaruhi mutasi tersebut
adalah MMR(Mismatch Repair) (Abdullah, 2006).
2.2.3.2 Faktor Lingkungan
Sejumlah bukti menunjukkan bahwa lingkungan berperan penting
pada kejadian kanker kolorektal. Risiko mendapat kanker kolorektal
meningkat pada masyarakat yang bermigrasi dari wilayah dengan
insiden yang rendah ke wilayah insiden yang tinggi. Kandungan dari
mikronutrien dan makronutrien juga berhubungan dengan kanker
kolorektal. Transformasi sel melalui peningkatan konsentrasi empedu
dalam kolon telah diketahui sebagai promotor kanker pada masyarakat
yang disertai dengan konsumsi rendah serat dan insiden kanker
kolorektal yang tinggi (Dinkes Gorontalo, 2007).
Secara umum berdasarkan Dinkes Gorontalo, terdapat 3 tahapan
karsinogenesis, yaitu:
1. Tahap inisiasi
Pada tahap inisiasi terjadi suatu perubahan dalam bahan genetik
sel yang memancing sel menjadi ganas. Perubahan dalam bahan
genetik sel ini disebabkan oleh suatu agen yang disebut
karsinogen, yang dapat berupa bahan kimia, virus, radiasi, atau

22
sinar matahari. Tetapi tidak semua sel memiliki kepekaan yang
sama terhadap suatu karsinogen (Dinkes Gorontalo, 2007).
2. Tahap promosi
Pada tahap promosi, suatu sel telah mengalami inisiasi akan
berubah menjadi sel ganas. Sel yang belum melewati tahap
inisiasi tidak akan terpengaruh oleh promosi. Karena itu
diperlukan beberapa faktor untuk terjadinya keganasan
(gabungan dari sel yang peka dan karsinogen) (Dinkes
Gorontalo, 2007).
3. Tahap keganasan
Pada saat sel menjadi ganas, sistem kekebalan tubuh sering
merusaknya sebelum sel ganas tersebut berlipat ganda dan
menjadi suatu kanker. Namun apabila sistem kekebalan tubuh
tidak berfungsi secara normal, maka tubuh cenderung rentan
terhadap resiko kanker, seperti yang terjadi pada penderita AIDS
(Acquired Immunodeficiency Syndrome), orang-orang yang
menggunakan obat penekan kekebalan, dan pada penyakit
autoimun tertentu. Tetapi sistem kekebalan tubuh pun tidak
selalu efektif, sehingga kanker kadangkala masih dapat
menembus perlindungan ini meskipun sistem kekebalan
berfungsi secara normal. Pada hampir semua jenis kanker, angka
keberhasilan terapi sangat berkaitan dengan stadium saat
diagnosis dan pengobatan. Semakin tinggi stadium saat
diagnosis, maka keberhasilan terapi akan semakin menurun

23
dengan modalitas pengobatan yang semakin agresif (Dinkes
Gorontalo, 2007).
Kanker kolorektal sporadik salah satunya disebabkan oleh kontak
sel-sel mukosa usus besar dengan zat-zat karsinogen, terutama jika
kontak tersebut terjadi dalam waktu yang lama dengan konsentrasi
senyawa karsinogen yang tinggi. Senyawa karsinogen berasal dari
makanan yang mengandung senyawa prekursor (Koswara, 2008).
Di dalam sistem pencernaan, senyawa prekursor dapat dirubah
menjadi senyawa-senyawa karsinogen oleh enzim pencernaan dan
aktivitas flora usus. Kontak senyawa karsinogen dengan sel usus akan
merusak keutuhan sel dan intinya sehingga bersifat mutagenik,
menyebabkan perubahan sel DNA yaitu sel-sel normal setelah dicemari
zat tersebut menjadi sel yang ganas dan berkembangbiak tak terkendali
(Koswara, 2008; LP POM MUI, 2008).
Pertumbuhan tumor secara tipikal tidak terdeteksi, sehingga
menimbulkan beberapa gejala. Saat timbul gejala, penyakit mungkin
sudah menyebar ke dalam lapisan lebih dalam dari jaringan usus dan
organ-organ yang berdekatan. Kanker kolorektal menyebar dengan
perluasan langsung ke sekeliling permukaan usus, submukosa, dan
dinding luar usus. Struktur yang berdekatan seperti hepar, curvatura
mayor gaster, duodenum, intestinum, pancreas, lien, genitourinary tract,
dan dinding abdominal juga dapat dikenai perluasan (Harahap, 2004).
Metastasis ke kelenjar getah bening regional sering berasal dari
penyebaran tumor. Tanda ini tidak selalu terjadi, bisa saja kelenjar yang

24
jauh sudah dikenai namun kelenjar regional masih normal (Harahap,
2004).
Sel-sel kanker dari tumor primer dapat juga menyebar melalui
sistem limfatik atau sistem sirkulasi ke area sekunder seperti hati, paru-
paru, otak, tulang, dan ginjal. Penyebaran tumor ke area lain dari rongga
peritoneal dapat terjadi bila tumor meluas melalui serosa (Gambar 2.5)
(Harahap, 2004).
(Adams, 2006)
Gambar 2.5
Stadium I, II, dan III Kanker Kolorektal
2.2.4 Gejala Klinis
Kebanyakan kasus kanker kolorektal didiagnosis pada usia 50 tahun dan
umumnya sudah memasuki stadium lanjut sehingga prognosisnya juga buruk.
Keluhan yang paling sering dirasakan pasien di antaranya: perubahan pola
buang air besar, perdarahan per anus (hematosezia dan konstipasi) (Abdullah,
2006).
Gejala dan tanda penyakit kanker kolorektal bervariasi sesuai dengan
letak kanker dan sering dibagi menjadi kanker yang mengenai bagian kanan
dan kiri usus besar (Price, Lorraine, 2005).

25
Kanker kolon kiri dan rektum mempunyai gejala dan tanda sebagai
berikut:
1. obstruksi
2. nyeri mirip kejang
3. kembung
4. feses kecil dan berbentuk pita
5. terdapat darah segar dan mukus pada feses
6. anemia
7. hemoroid, nyeri pinggang bagian bawah, keinginan defekasi dan
berkemih dapat timbul karena tekanan pada kolon (Price, Lorraine,
2005).
Kanker kolon kanan (isi kolon berupa cairan) mempunyai gejala dan
tanda sebagai berikut:
1. diare
2. anemia akibat perdarahan
3. darah bersifat samar dan hanya dapat diuji dengan uji guaiak
4. mukus jarang terlihat karena bercampur feses
5. pada orang kurus, tumor kolon kanan dapat teraba tetapi tidak khas
pada stadium awal
6. perasaan tidak enak pada abdomen dan epigastrium (Price, Lorraine,
2005).

26
2.2.5 Stadium Kanker Kolorektal
Terdapat beberapa macam stadium, dibawah ini merupakan stadium
kanker kolorektal menurut TNM (Gambar 2.6) (Kelompok Kerja
Adenokarsinoma Kolorektal Indonesia, 2006).
Tabel 2.1 Stadium Kanker Kolorektal Berdasarkan Kriteria TNM
Stadium
Derajat T N M
0 Tis N0 M0
IA T1 N0 M0
IB T2 N0 M0
IIA T3 N0 M0
IIB T4 N0 M0
IIIA Semua T N1 M0
IIIB Semua T N2 M0
IV Semua T Semua N M1
(Sumber: Kelompok Kerja Adenokarsinoma Kolorektal Indonesia, 2006)
Keterangan:
T- Tumor primer
Tx : tumor primer tidak dapat dinilai
T0 : tumor primer tidak ditemukan
Tis : karsinoma insitu, intaephitelial atau ditemukan sebatas lapisan mukosa saja
T1 : tumor menginvasi submukosa
T2 : tumor menginvasi lapisan muskularis propria
T3 : tumor menembus muskularis propria hingga lapisan serosa atau jaringan perikolika/ perirektal
belum mencapai peritoneum
T4 : tumor menginvasi organ atau struktur disekitarnya atau menginvasi sampai peritoneum visceral
N- Kelenjar getah bening regional
Nx : kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai
N0 : tidak ditemukan metastasis pada kelenjar getah bening regional
N1 : ditemukan anak sebar pada 1-3 kelenjar getah bening regional
N2 : ditemukan anak sebar pada 4 atau lebih kelenjar getah bening
M- Metastasis jauh
Mx : metastasis jauh tidak dapat dinilai
M0 : tidak ditemukan metastasis jauh
M1 : ditemukan metastasis jauh
Dan dibawah ini merupakan stadium kanker kolorektal berdasarkan
kriteria Dukes modifikasi Astler Coller (Kelompok Kerja Adenokarsinoma
Kolorektal Indonesia, 2006).

27
Tabel 2.2 Stadium Kanker Kolorektal Berdasarkan Kriteria Dukes Modifikasi Astler
Coller
Dukes Penyebaran Histopatologi
A Tumor terbatas pada lapisan mukosa
B1 Tumor menginvasi sampai lapisan muskularis propria
B2 Tumor menginvasi menembus lapisan muskularis propria
C1 Tumor B1 dan ditemukan anak sebar pada kelenjar getah bening
C2 Tumor B2 dan ditemukan anak sebar pada kelenjar getah bening
D Tumor bermetastasis jauh
(Sumber: Kelompok Kerja Adenokarsinoma Kolorektal Indonesia, 2006)
(Adams, 2006)
Gambar 2.6
Stadium Kanker Kolorektal
2.2.6 Pendekatan Diagnosis
2.2.6.1 Prosedur Diagnosis pada Pasien dengan Gejala
Keberadaan kanker kolorektal dapat dikenali dari beberapa tanda
seperti: anemia mikrositik, hematosezia, nyeri perut, berat badan turun
atau perubahan defekasi. Temuan darah samar di feses memperkuat
dugaan neoplasia namun bila tidak ada darah samar tidak dapat
menyingkirkan lesi neoplasma (Abdullah, 2006).
2.2.6.2 Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium meliputi:
1. Tes darah: pengukuran darah pasien untuk peningkatan kadar
protein tertentu dapat memberikan indikasi beban tumor. Secara

28
khusus, tingkat tinggi CEA (Carcinoembryonic Antigen) dalam
darah dapat menunjukkan metastasis adenokarsinoma. Tes ini
sering negatif palsu atau positif palsu, dan tidak
direkomendasikan untuk skrining, dapat berguna untuk menilai
kekambuhan penyakit (Marin, 2010).
2. FOBT (Fecal Occult Blood Test): tes darah pada tinja. Dua jenis
tes dapat digunakan untuk mendeteksi darah yang tersembunyi
pada kotoran manusia, tes ini menggunakan uji kimia tertentu
dan immunochemical. Sensitivitas pengujian immunochemical
adalah lebih tinggi dari pengujian kimia (nilai spesifisitas-nya
dapat diterima) (Marin, 2010).
2.2.6.3 Pemeriksaan Radiologi
Enema barium kontras (hanya mendeteksi 50% polip kolon dengan
spesifisitas 85%) untuk memeriksa bagian kolon di balik striktur yang
tak terjangkau dengan pemeriksaan kolonoskopi (Abdullah, 2006).
2.2.6.4 Kolonoskopi
Kolonoskopi merupakan cara pemeriksaan mukosa kolon yang
sangat akurat dan dapat sekaligus melakukan biopsi pada lesi yang
mencurigakan. Pemeriksaan kolon yang lengkap dapat mencapai 95%.
Kolonoskopi mempunyai sensitivitas 95% dan spesifisitas 99%
(Abdullah, 2006).
2.2.6.5 Evaluasi Histologi
Adenoma diklasifikasikan sesuai dengan gambaran histologi yang
dominan. Yang paling sering adalah adenoma tubular (85%), adenoma

29
tubulovilosum (10%), dan adenoma serrata (1%). Temuan sel atipik pada
adenoma dikelompokkan menjadi ringan, sedang, dan berat. Gambaran
atipik berat menunjukkan adanya fokus karsinomatosus namun belum
menyentuh membran basalis. Bilamana sel ganas menembusi membran
basalis tapi tidak melewati muskularis mukosa disebut karsinoma intra
mukosa (Abdullah, 2006).
2.2.6.6 Macam Skrining Lainnya
Selain pemeriksaan tersebut diatas, diagnosis dapat ditegakkan
dengan pemeriksaan lain, yaitu:
1. DRE (Digital Rectal Examination): dokter memasukkan jari-
yang sebelumnya diberi sarung tangan dan dilumasi dengan
pelicin-ke dalam rektum untuk mengecek daerah yang
abnormal. Cara ini hanya mendeteksi tumor yang sudah tumbuh
cukup besar dan dirasakan di bagian distal rektum. Namun cara
ini berguna sebagai tes skrining awal.
2. Genetik konseling dan tes genetik untuk keluarga yang mungkin
memiliki bentuk turun-temurun kanker usus besar, seperti
HNPCC (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) dan FAP
(Familial Adenomatous Polyposis).
3. PET (Positron Emission Tomography) adalah teknologi
pemindaian 3-dimensi di mana gula radioaktif disuntikkan ke
pasien, gula terkumpul dalam jaringan dengan aktivitas
metabolik tinggi, dan gambar dibentuk dengan mengukur emisi
radiasi dari gula. Karena sel-sel kanker sering memiliki tingkat

30
metabolisme yang sangat tinggi, ini dapat digunakan untuk
membedakan tumor jinak dan ganas. PET tidak digunakan untuk
skrining dan tidak (belum) memiliki tempat dalam hasil
pemeriksaan rutin kasus kanker kolorektal (Marin, 2010).
2.2.7 Penatalaksanaan
Empat jenis utama pengobatan untuk kanker kolorektal yaitu
pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan target terapi molekuler (Sorra,
2008).
2.2.7.1 Pembedahan
Pembedahan biasanya merupakan pengobatan utama untuk kanker
usus stadium awal. Suatu polipektomi adalah suatu metode yang biasa
digunakan oleh dokter (ahli endoskopi) untuk mengangkat polip usus
yang dianggap berbahaya (mengarah ke pra-kanker) pada saat
dilakukannya kolonoskopi. Bila sudah menjadi kanker, maka perlu
dilakukan tindakan operasi yang disebut kolektomi atau reseksi
segmental. Biasanya dokter akan mengangkat bagian usus yang terkena
kanker (termasuk getah bening didekatnya), dan kemudian
menyambungkan kembali bagian usus yang tersisa. Pada operasi ini,
dokter mungkin menganggap perlu untuk membuat lumbang
pembuangan tinja sementara (ostomi) di pinggang pasien untuk
memberikan waktu ususnya sembuh (Sorra, 2008).
Suatu bedah laparoskopi kolostomi (gambar 2.7) menggunakan
teknik yang lebih canggih yang tidak memerlukan sayatan panjang
seperti pada operasi pembedahan biasa (open surgery). Beberapa

31
manfaat dari metode ini adalah rasa sakit sesudah operasi jauh lebih
berkurang dan pasien tidak perlu rawat inap terlalu lama di RS (Sorra,
2008).
Pada kasus kanker usus dan kanker rektum stadium II dan III,
mungkin memerlukan penanganan/pembedahan yang lebih serius,
dengan salah satu metode ini:
1. Reseksi Anterior: metode ini dilakukan bila posisi kanker
terletak diatas rektum dekat dengan perbatasan usus besar.
Dokter bedah perlu membuat sayatan terbuka pada perut untuk
mengangkat bagian yang terkena kanker (beserta kelenjar getah
bening terinfiltrasi), tanpa mempengaruhi anus. Pada metode ini,
pasien masih dapat BAB (buang air besar) seperti biasa (melalui
anus).
2. LAR (Low Anterior Resection): bila letak kanker 1/3 tengah
rektum, dengan mengangkat rectum 1/3 tengah dan proksimal
serta sebagian distal colon sigmoid yang dianggap bebas massa
tumor. Ini adalah operasi yang sulit untuk dilakukan. Untuk itu
dokter akan membuat kantong pembuangan tinja sementara
(ostomi) hingga ususnya sembuh. Operasi kedua diperlukan
untuk menutup pembukaan ostomi.
3. APR (Abdomino Perineal Resection): bila kankernya berada
pada bagian bawah rektum dekat dengan anus, maka ahli bedah
perlu mengangkat juga anusnya. Akibatnya sebuah lubang

32
pembuangan tinja (ostomi) permanen perlu dibuat untuk
mengeluarkan tinja/kotoran dari tubuh pasien selanjutnya.
4. Eksenterasi panggul: jika kanker rektum sudah menyebar ke
organ terdekat, maka diperlukan suatu pembedahan radikal,
yang mungkin melibatkan pengangkatan usus besar, anus
ataupun kandung kemih/prostat/rahim yang terinfiltrasi. Suatu
ostomi diperlukan untuk pembuangan tinja permanen. Jika
kandung kemih diangkat, sebuah urostomi (pembuka untuk
buangan air seni) juga diperlukan (Sorra, 2008).
Efek samping dari operasi tergantung pada banyak hal, seperti
tingkat operasi dan kesehatan umum seseorang sebelum operasi. Rasa
sakit sesudah operasi, umum dirasakan. Efek lain yang mungkin timbul
antara lain: pendarahan, pembekuan darah di kaki, dan kerusakan organ
terdekat selama operasi (Sorra, 2008).
Pembedahan juga bisa berdampak pada kehidupan seksual.
Beberapa efek samping yang mungkin timbul antara lain, tidak
keluarnya air mani saat orgasme, gangguan ereksi pada pria, serta rasa
sakit dan menurunnya gairah seksual pada wanita (Sorra, 2008).
2.2.7.2 Radioterapi
Radioterapi dalam mengobati kanker usus terutama digunakan
ketika sel-sel kankernya sudah menempel ke organ dalam atau ke lapisan
dalam perut. Dalam hal ini radioterapi digunakan setelah operasi
pengangkatan untuk memastikan seluruh sel-sel kanker yang tersisa
mati. Radiasi jarang digunakan untuk mengobati kanker usus besar yang

33
telah menyebar (metastasis). Untuk kanker rektum, radiasi sering
diberikan baik sebelum atau setelah operasi untuk membantu mencegah
kankernya kambuh (Sorra, 2008).
Brachytherapy adalah terapi radiasi internal dimana pelet kecil atau
biji bahan radioaktif ditempatkan langsung ke kankernya dalam jangka
pendek dengan tujuan mematikan kankernya tanpa merusak jaringan
sehat disekitarnya. Metode ini dilakukan untuk orang-orang yang karena
satu dan lain hal tidak dapat menjalani operasi (Sorra, 2008).
2.2.7.3 Kemoterapi
Kemoterapi melibatkan penggunaan obat-obatan melalui infus ke
dalam aliran darah ataupun tablet minum untuk mematikan sel-sel
kankernya. Kemoterapi kadang digunakan sebelum operasi untuk
mengecilkan kankernya, atau pada kasus kanker usus yang telah
bermetastasis ke hati. Kemoterapi sendiri dapat digolongkan menjadi 2,
yaitu:
1. Terapi Adjuvan
Kemoterapi ajuvan dimaksudkan untuk menurunkan tingkat
rekurensi kanker kolorektal setelah operasi. Pasien dengan
stadium Dukes A jarang mengalami rekurensi sehingga tidak
perlu terapi ajuvan. Pasien stadium Dukes C mendapat levamisol
dan 5-FU (5-flurourasil) secara signifikan meningkatkan
harapan hidup dan masa interval bebas tumor. Irinotectan (CPT
11) inhibitor topoisomer dapat memperpanjang masa harapan

34
hidup. Oxaliplatin analog platinum juga memperbaiki respon
setelah diberikan 5-FU dan leucovorin.
2. Terapi Neoadjuvan
Merupakan terapi kombinasi terbaru yang menjadi prioritas
untuk menghindari terjadinya tumor. Terapi neoajuvan ini
diberikan sebelum dan sesudah operasi. Terdapat dua macam
kombinasi, yaitu FOLFOX dan FOLFIRI. FOLFOX sendiri
berisi 5-FU, leucovorin, dan oxaliplatin. Sedangkan FOLFIRI
berisi 5-FU, leucovorin, dan irinotectan (Sorra, 2008; Schofield,
Jones, 1996).
2.2.7.4 Molecular Target Therapy
Target terapi, kadang disebut sebagai smart drugs, yaitu hanya
memfokuskan diri untuk mematikan sel-sel kankernya, sehingga tidak
mengganggu sel-sel normal lainnya. Contoh obat-obatan target terapi
untuk kanker usus, adalah: bevacizumab (Avastin ®), panitumumab
(Vectibix), dan cetuximab (Erbitux). Obat ini merupakan antibodi
monoclonal buatan (versi manusia) untuk menyerang kanker pada akar
molekulnya. Molecular target therapy biasanya dilakukan bersamaan
dengan kemoterapi untuk meningkatkan peluang keberhasilan
pengobatan (Sorra, 2008).
2.2.8 Prognosis
Harapan hidup pasien kanker kolorektal tergantung pada derajat
penyebaran saat pasien datang. Faktor yang mempengaruhi prognosis adalah
metastasis jauh, penyebaran lokal yang menyebabkan perlekatan dengan

35
struktur yang tak dapat diangkat, derajat keganasan histologi yang tinggi, dan
penyebaran ke kelenjar limfe regional (Schofield, Jones, 1996).
Untuk semua pasien, hasil kelangsungan hidup adalah sekitar 25%, tetapi
pada pasien yang tampaknya dapat diobati dengan reseksi pada saat operasi,
lebih baik 50%, dan jika tumor tidak menembus seluruh ketebalan dinding
kolon, maka harapan hidupnya hampir normal (Schofield, Jones, 1996).
2.2.9 Pencegahan
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjangkit penyakit
kanker kolorektal adalah:
1. hindari makanan tinggi lemak, protein, kalori, serta daging merah.
Jangan lupakan konsumsi kalsium dan asam folat. Setelah menjalani
polipektomi adenoma disarankan pemberian suplemen kalsium,
2. disarankan pula suplementasi vitamin E dan D,
3. makan buah dan sayuran setiap hari,
4. pertahankan IMT (indeks massa tubuh) antara 18,5- 25,0 kg/m2
sepanjang hidup,
5. lakukan aktivitas fisik, semisal jalan cepat paling tidak 30 menit dalam
sehari,
6. hindari kebiasaan merokok,
7. lakukan deteksi dini dengan tes darah samar sejak usia 40 tahun
(Pasaribu, 2009).

36
2.3 Anemia
2.3.1 Definisi
Anemia adalah berkurangnya volume sel darah merah atau konsentrasi
Hb di bawah nilai normal. Anemia sendiri sebenarnya bukan suatu penyakit
tetapi merupakan gejala dari suatu kelainan yang sebab-sebabnya harus
ditentukan (Digilib-USU, 2005).
Anemia yang disebabkan oleh kanker bisa terjadi akibat efek langsung
dari keganasan, dapat sebagai produksi zat-zat tertentu yang dihasilkan
kanker, atau dapat juga sebagai akibat dari hasil pengobatan (Kar, 2005).
2.3.2 Derajat Anemia
Menurut WHO (2001), anemia dalam individu ditentukan sebagai
konsentrasi Hb dalam darah dibawah nilai yang diharapkan. Hemoglobin
sendiri berfungsi untuk membantu sel darah merah membawa oksigen dari
paru-paru ke semua bagian tubuh. Berikut merupakan derajat anemia menurut
kriteria WHO dan NCI (Syafei, 2009).
Tabel 2.3 Derajat Anemia Menurut WHO dan NCI
Derajat WHO NCI
Normal ≥11 gr/dl Pr 12.0-16.0 gr/dl
Lk 14.0-18.0 gr/dl
Derajat 1 (ringan) Pr < 10 gr/dl
Lk <11 gr/dl
10.0 gr/dl-nilai normal
Derajat 2 (sedang) 8.0-9.4 gr/dl 8.0-10.0 gr/dl
Derajat 3 (berat) ≤8.0 gr/dl ≤8.0 gr/dl
(Sumber: Cermin Dunia Kedokteran, 2009)
2.3.3 Etiologi dan Klasifikasi Anemia
Anemia hanyalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh
bermacam-macam penyebab. Pada dasarnya anemia disebabkan oleh karena:

37
1) Gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang; 2) Kehilangan darah
keluar tubuh (perdarahan); 3) Proses penghancuran eritrosit dalam tubuh
sebelum waktunya (hemolisis). Gambaran lebih rinci tentang etiologi anemia
dapat dilihat pada tabel 2.4 (Bakta, 2006).
Tabel 2.4 Klasifikasi Anemia Menurut Etiopatogenesis
Klasifikasi Anemia Menurut Etiopatogenesis
A. Anemia karena gangguan pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang
1. Kekurangan bahan esensial pembentuk eritrosit
i. Anemia defisiensi besi
ii. Anemia defisiensi asam folat
iii. Anemia defisiensi vitamin B12
2. Gangguan penggunaan besi
i. Anemia akibat penyakit kronik
ii. Anemia sideroblastik
3. Kerusakan sumsum tulang
i. Anemia aplastik
ii. Anemia mieloplastik
iii. Anemia pada keganasan hematologi
iv. Anemia diseritropoietik
v. Anemia pada sindrom mielodiplastik
B. Anemia akibat hemoragi
1. Anemia pasca perdarahan akut
2. Anemia akibat perdarahan kronik
C. Anemia hemolitik
1. Anemia hemolitik intrakorpuskular
i. Gangguan membran eritrosit (membranopati)
ii. Gangguan ensim eritrosit (enzinomati): anemia akibat defisiensi G6PD
iii. Gangguan hemoglobin (hemoglobinopati)
Thalassemia
Hemoglobinopati struktural: HbS, HbE,dll
2. Anemia hemolitik ekstrakorpuskuler
i. Anemia hemolitik autoimun
ii. Anemia hemolitik mikroangiopatik
D. Anemia dengan penyebab tidak diketahui atau dengan patogenesis yang kompleks
(Sumber: Bakta, 2006)

38
Klasifikasi lain untuk anemia dapat dibuat berdasarkan gambaran
morfologik dengan melihat indeks eritrosit atau hapusan darah tepi. Dalam
klasifikasi ini, anemia dibagi menjadi 3 golongan: 1) Anemia hipokromik
mikrositer, bila MCV <80 fl dan MCH <27 pg; 2) Anemia normokromik
normositer, bila MCV 80-95 fl dan MCH 27-34 pg; 3) Anemia makrositer,
bila MCV >95 fl. Klasifikasi etiologi dan morfologi bila digabungkan (Tabel
2.5) akan sangat menolong dalam mengetahui penyebab suatu anemia
berdasarkan jenis morfologi anemianya (Bakta, 2006).
Tabel 2.5 Klasifikasi Anemia Berdasarkan Morfologi dan Etiologi
Klasifikasi Anemia Berdasarkan Morfologi dan Etiologi
A. Anemia hipokromik mikrositer
a. Anemia defisiensi besi
b. Thalassemia major
c. Anemia akibat penyakit kronik
d. Anemia sideroblastik
B. Anemia normokromik normositer
a. Anemia pasca perdarahan akut
b. Anemia aplastik
c. Anemia hemolitik didapat
d. Anemia akibat penyakit kronik
e. Anemia pada gagal ginjal kronik
f. Anemia pada sindrom mielodiplastik
g. Anemia pada keganasan hematologic
C. Anemia makrositer
a. Bentuk megaloblastik
i. Anemia defisiensi asam folat
ii. Anemia defisiensi B12, termasuk anemia pernisiosa
b. Bentuk non-megaloblastik
i. Anemia pada penyakit hati kronik
ii. Anemia pada hipotiroidisme
iii. Anemia pada sindrom mielodiplastik
(Sumber: Bakta, 2006)

39
2.3.4 Gejala Klinis Anemia
Kira-kira 75% dari semua pasien kanker melaporkan adanya rasa lelah
(fatigue) yang dapat dimanifestasikan sebagai rasa lemah, kurang energi, sulit
memulai dan mengurangi pekerjaan, serta rasa ingin tidur saja seharian. Rasa
lelah merupakan gejala utama pada pasien kanker. Anemia juga menyebabkan
berbagai keluhan seperti palpitasi (rasa berdebar), gangguan fungsi kognitif,
mual, gangguan fungsi imun, sakit kepala, nyeri dada, nafas pendek, dan
depresi (Kar, 2005).
2.3.5 Pemeriksaan Untuk Diagnosis Anemia
Terdapat beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk
menegakkan anemia, antara lain:
1. Pemeriksaan Penyaring
Pemeriksaan penyaring untuk kasus anemia terdiri dari pengukuran
kadar Hb, indeks eritrosit dan hapusan darah tepi. Dari sini dapat
dipastikan adanya anemia serta jenis morfologik anemia tersebut, yang
sangat berguna untuk pengarahan diagnosis lebih lanjut.
2. Pemeriksaan Darah Seri Anemia
Pemeriksaan darah seri anemia meliputi hitung leukosit, trombosit,
hitung retikulosit dan LED (Laju Endap Darah). Sekarang sudah banyak
dipakai automatic hematology analyzer yang dapat memberikan presisi
hasil yang lebih baik.

40
3. Pemeriksaan Sumsum Tulang
Pemeriksaan sumsum tulang memberikan informasi yang sangat
berharga mengenai keadaan sistem hematopoesis. Pemeriksaan ini
dibutuhkan untuk diagnosis definitive pada beberapa jenis anemia.
4. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan ini hanya dikerjakan atas indikasi khusus, misalnya pada:
a. Anemia defisiensi besi: serum iron, TIBC (Total Iron Binding
Capacity), saturasi transferin, protoporfirin eritrosit, feritin serum,
reseptor transferin dan pengecatan besi pada tulang (Perl’s stain)
b. Anemia megaloblastik: folat serum, vitamin B12 serum, tes supresi
deoksiuridin dan tes Schiling
c. Anemia hemolitik: bilirubin serum, tes Coomb, elektroforesis Hb
d. Anemia aplastik: biopsi tulang (Bakta, 2006).
2.3.6 Terapi Anemia
Pada penderita anemia karena kanker, tata laksana yang baik adalah
mengatasi penyebab yang merupakan tindakan paling optimal. Beberapa
penyebab seperti defisiensi nutrisional, mudah untuk diidentifikasi dan
diobati. Keadaan seperti adanya perdarahan samar, infeksi, dan hemolisis
eritrosit memerlukan evaluasi yang mendalam (Kar, 2005).
2.3.6.1 Defisiensi Nutrisional
Bila kehilangan darah sedikit-sedikit yang terus-menerus tidak
merupakan problem utama, tetapi gejala anemia tidak juga teratasi, maka
harus dicari/diperiksa kemungkinan adanya defisiensi besi, asam folat,
atau vitamin B12, dan terapi suplemen harus diberikan kalau ditemukan

41
tanda-tanda defisiensi. Kalau anemia tidak berat, terapi suplemen cukup
untuk menghilangkan gejalanya dan mengembalikan Hb ke batas normal
(Kar, 2005).
2.3.6.2 Defisiensi Zat Besi
Pemberian zat besi diperlukan sebagai terapi kombinasi yang
menstimulasi eritropoesis seperti rHuEPO, untuk mengobati anemia
secara efektif. Defisiensi besi fungsional karena adanya gangguan
transportasi besi untuk eritropoesis merupakan faktor penting pada
anemia kronik pada kanker. Besi dapat diberikan secara oral dan
intravena (Kar, 2005).
2.3.6.3 Transfusi Eritrosit
Transfusi eritrosit hanya diberikan pada kasus anemia akut setelah
terjadi perdarahan akut, pada kasus anemia kronik yang bergejala tetapi
tidak berhasil dengan terapi besi, dan pada anemia berat yang tidak
cukup waktu untuk menerima rHuEPO (Kar, 2005).
2.4 Patofisiologi Anemia Pada Kanker
Terjadinya anemia pada penderita kanker (tumor ganas), dapat disebabkan
karena aktivasi sistem imun tubuh dan sistem inflamasi yang ditandai dengan
peningkatan beberapa petanda sistem imun seperti INF (Interferon), TNF (Tumor
Necrosis Factor), dan IL (Interleukin)yang semuanya disebut sitokin (Gambar
2.7) (Kar, 2005).
Konsentrasi INF - meningkat pada penyakit kronik. Sedangkan kadar TNF
tergantung pada keganasan dan aktivitasnya. Sesuai dengan penemuan dari
beberapa studi klinis maupun eksperimental, paparan kronik pada TNF dapat

42
TNF Erythrophagocytosis
Dyserythropoesis
menyebabkan anemia. IL-1 adalah sitokin yang mempunyai peranan luas dalam
proses respon imun dan inflamasi. Konsentrasi IL-1 meningkat pada anemia
karena penyakit kronik (Kar, 2005).
Massa eritrosit secara normal ditentukan oleh umur dari eritrosit tersebut dan
dari kecepatan produksinya. Anemia terjadi karena ketidakseimbangan kedua
faktor tersebut. Pada anemia karena kanker, kedua faktor tersebut sangat
menentukan (Kar, 2005).
(Kar, 2005)
Gambar 2.7
Pathophysiology of Anemia in Cancer
Berikut mekanisme patogenik yang bertanggung jawab terhadap anemia
akibat kanker yang diperantarai oleh INF, TNF, dan IL-1, yaitu (Kar, 2005):
1. Gangguan pemakaian besi
2. Produksi Epo tidak memadai
3. Pemendekan umur eritrosit
Tumor Cells
Erythrocytes Activated immune
system
Macrophages
Shortened survival
Anemia Reduced
Eriythropoetin
Production
Suppressed
BFU-E,
CFU-E
Impaired
iron
utilization

43
2.4.1 Gangguan Pemakaian Besi
Mekanisme yang bertanggung jawab pada proses ini adalah gangguan
pada TFR (Transferin-receptor) pada eritrosit. Eritroblas pada pasien anemia
karena penyakit kronik jumlahnya berkurang, dan TFR pada sel-sel tersebut
afinitasnya terhadap transferin menurun. Pada keadaan infeksi, keganasan,
dan kelainan imunologis, IL-1, IL-6, dan TNF meningkatkan konsentrasi
protein fase akut α1-antitripsin yang mampu menahan eritropoesis dengan
cara mengganggu pengikatan transferin ke TFR dan internalisasi kompleks
TFR-transferin (Kar, 2005).
2.4.2 Produksi Eritropoetin Tidak Memadai
Pada penderita anemia karena kanker, sel progenitor eritrosit
memberikan respon yang baik terhadap Epo (Eritropoetin), tetapi respon Epo
terhadap anemia mengalami gangguan. Pada pasien kanker, produksi Epo
terganggu oleh tumor (Kar, 2005).
Gangguan respon Epo yang terlihat pada anemia karena kanker mungkin
sebagai hasil adanya efek supresi dari IL-1 atau TNF terhadap sel-sel yang
memproduksi Epo. Sitokin ini dapat menginhibisi produksi Epo (Kar, 2005).
2.4.3 Pemendekan Umur Eritrosit
Pada penderita anemia karena penyakit kronik, umur eritrosit biasanya
60-90 hari, lebih pendek dari umur eritrosit pada orang normal (120 hari).
Secara klinis maupun eksperimental data ini menunjukkan bahwa efek ini
diperantarai oleh IL-1 dan TNF. Efek TNF tersebut dapat menurunkan
eritropoesis dan memendekkan eritrosit pada pasien anemia karena kanker
(Kar, 2005).

44
Saat ini ditemukan bahwa suatu protein yang disebut substansi penyebab
anemia (AIS) telah dapat diidentifikasi di dalam plasma penderita kanker.
Substansi ini menurunkan resistensi osmotik dari eritrosit, yang juga
didapatkan di dalam sitosol dan fraksi dari inti sel kanker. Mekanisme yang
mendasari terjadinya peningkatan fragilitas osmotik di dalam eritrosit
bergantung pada inhibisi metabolisme (influks glukosa, aktivitas piruvat
kinase, dan konsentrasi ATP (Adenosine Tri Phosphate)) dari sel tersebut.
AIS spesifik untuk penyakit keganasan (Kar, 2005).
Adapun faktor terjadinya anemia selain akibat sitokin yaitu akibat dari
keganasan itu sendiri (Tabel 2.6). Kebanyakan adalah tumor ganas solid yang
terabaikan sebagai faktor penyebab anemia. Keganasan ini menyebabkan
reaksi fibrosis, yaitu terjadinya peningkatan proses fibrosis di dalam sumsum
tulang yang akan mengurangi volume rongga sumsum tulang dan matrix
sinusoid. Proses ini dapat menyebabkan gangguan pelepasan sel darah yang
matang dari tulang (Kar, 2005).

45
Tabel 2.6 Anemia pada Kanker: Efek Langsung Dari Keganasan
Kehilangan darah akut ataupun kronik Keganasan dari saluran cerna
Kanker kepala dan leher
Kanker urogenital
Kanker pada cervix dan vagina
Perdarahan dalam tumor sendiri (intratumor) Sakoma
Melanoma yang sangat besar
Hepatoma
Kanker ovarium
Tumor cortex adrenal
Anemia karena fagositosis dari eritrosit Retikulositosis histiocytic medular
Limfoma histiositik
Neoplasma histiositik yang lain
Penggantian sumsum tulang Leukemia
Limoma
Myeloma
Carcinoma (prostat, payudara)
(Sumber: Kar, 2005)