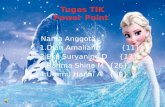BAB 1
-
Upload
nazula-mufarihah -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
Transcript of BAB 1

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rinitis alergi merupakan inflamasi kronis mukosa saluran hidung dan sinus
yang disebabkan berbagai macam alergen. Rinitis alergi juga merupakan masalah
kesehatan global dan angka kejadiannya mengalami peningkatan dibanyak negara.
Angka kejadian rhinitis alergi secara umum berkisar 25% terutama pada remaja
dan dewasa. Prevalensi rinitis alergi di Indonesia bervariasi antara 1,5-12,3 % dan
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagian besar penderita ternyata
mengalami penurunan kualitas hidup, kualitas pendidikan dan produktivitas kerja.
Meskipun bukan penyakit yang berbahaya, rinitis alergi harus dianggap sebagai
penyakit serius agar tidak memperparah kondisi dan mempersulit penanganannya
(DeGuzman DA, 2007;Nurcahyo H, 2009).
Bakteri potensial patogen merupakan flora normal yang hidup pada kulit dan
mukosa yang bersifat sementara mengkolonisasi nasofaring orang sehat.
Keberadaannya selalu ditemukan pada setiap individu walaupun sedang dalam
keadaan tidak sakit. Kolonisasi nasofaring oleh bakteri potensial pathogen
respiratori seperti gram negative, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus
aureus, Haemophillus influenza umumnya tanpa menimbulkan manifestasi klinis,
tetapi keberadaan bakteri-bakteri potensial patogen respiratori ini tetap menjadi
sebuah masalah karena dapat menjadi sumber penularan dan penyebaran pada
orang lain (Hikmawati,2010).
Bakteri gram negatif pada saluran pernafasan di antaranya Haemophillus
Influenzae, Enterobacteriacea, Neisseria meningitidis. Haemophillus influenza
ditemukan pada selaput mukosa saluran napas bagian atas pada manusia. Neisseria
Meningitidis (meningokokus) dalam tubuh manusia bersifat pathogen. Nasofaring
merupakan pintu masuknya, disana organism ini melekat pada sel-sel epitel
dengan bantuan pili, bakteri ini dapat merupakan bagian flora sementara tanpa
menimbulkan gejala. Dari nasofaring, bakteri ini dapat mencapai aliran darah dan
mengakibatkan bakteremia, gejalanya seperti infeksi saluran pernapasan (Jawetz et
al,2007).
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu :
1. Apa anatomi fisiologi dari rhinitis ?
2. Bagaimana epidemiologi dari rhinitis ?
3. Apa definisi dari rhinitis ?
1

4. Bagaimana etiologi dari rhinitis ?
5. Bagaimana patofisiologi dan WOC dari rhinitis ?
6. Apa tanda dan gejala dari rhinitis ?
7. Bagaimana pemeriksaan penunjang dari rhinitis ?
8. Bagaimana penatalaksanaan dari rhinitis ?
9. Bagaimana asuhan keperawatan dari rhinitis ?
C. Tujuan
Adapun tujuan dalam makalah ini, yaitu :
1. Mengetahui anatomi fisiologi dari rhinitis.
2. Mengetahui epidemiologi dari rhinitis.
3. Mengetahui definisi dari rhinitis.
4. Mengetahui etiologi dari rhinitis.
5. Mengetahui patofisiologi dan WOC dari rhinitis.
6. Mengetahui tanda dan gejala dari rhinitis.
7. Mengetahui pemeriksaan penunjang dari rhinitis.
8. Mengetahui penatalaksanaan dari rhinitis.
9. Mengetahui asuhan keperawatan dari rhinitis.
2

BAB 2
TINJAUAN TEORI
A. Anatomi dan Fisiologi
Dari luar, hidung berbentuk piramida dengan puncak hidung sebagai apeks.
Sepertiga bagian kerangka hidung terdiri dari tulang dan dua pertiga bagian
terdiri dari tulang rawan (Gambar 3.1).
Di dalam, hidung dibagi menjadi dua rongga hidung (kavum nasi) yang
dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Bagian tulang posterior terdiri dari
vomer dan lamina perpendikularis etmoid (Gambar 3.2). Bagian depan (kartilago
kuadrangularis) ialah tulang rawan dan membrane. Maksila, palatum dan
premaksila merupakan dasar pyramid hidung. Atapnya terdiri dari tulang hidung,
lamina kribriformis tulang etmoid dan tulang sphenoid. Bagian lateral rongga
hidung terutama terdiri dari tulang. Rongga hidung oleh kerang hidung (konka)
dibagi menjadi tiga celah (meatus) (Gambar 3.3).
Rongga hidung bermuara di nasofaring melalui koana. Bagian paling depan
(vestibulum) berlapis epitel kulit, sebagian besar dengan epitel berambut getar
(silia). Panjang silia kurang lebih 6-7µ, bergetar dalam irama dan arah yang sama
dengan frekuensi 10-25 Hz dan dengan demikian dapat memindahkan palut
lender (mucous blanket) 6-12 mm/menit yang terjadi dari lapisan viskosa di
permukaan dan lapisan bawah yang agak serosa. Tahap pengembalian gerak silia
berada di lapisan bawah, pada saat gerak propulsi ujung silia menyentuh lapisan
atas yang viskos.
3
Gambar 3.1 Rangka Luar Hidung

Pada diskinesis siliaris primer, terdapat kerusakan congenital ultrastruktur
pada silia yang menyebabkan gerakan silia dan transportasi lender tidak ada dan
pada laki-laki terjadi infertilitas karena silia pada spermatozoa tidak bergerak.
Pasien menderita sinusitis kronis, bronchitis kronis dan lama-lama terjadi
bronkiektasis. Setengah dari pasien, selain dari itu menderita situs inversus dan
kombinasinya yang dikenal sebagai sindrom Kartagener.
Selaput lendir pada region olfaktoria atau celah penghidu tampak sebagai
lokus luteus. Epitel penghidu, kira-kira 1 cm2 pada setiap rongga hidung terletak
di lamina kribosa, dibagian atas dari septum dan dipermukaan atas konka
superior. Epitel penghidu terdiri dari sel basal, sel penunjang, kelenjar Bowman
dan kurang lebih 2.106 sel indera. Sel epitel penghidu bipolar mempunyai cabang
sentrypetal yang membentuk ikatan yaitu fila olfaktoria. Ikatan ini menjadi n.
olfaktorius yang mempunyai bulbus olfaktorius dan traktus olfaktorius berjalan
ke girus hipokampi. Letaknya kira-kira 2,5 cm dibelakang lubang hidung,
beberapa sentimeter diatas dasar hidung diantara selaput lender dan perikondrium
4
Gambar 3.2 Sekat Hidung (septum nasi)
Gambar 3.3 Dinding Lateral Hidung

septum nasi pasangan organ vomer nasi atau organ Jacobson. Struktur yang
berbentuk pipa ini mempunyai diameter 1 mm dan panjang 2-12 mm.
Organ ini peka terhadap feromon, zat penghidu mudah menguap yang lebih
kuat pada binatang daripada manusia yang berpengaruh untuk melaksanakan
kehidupan yang ganas. Pada sub mukosa, apalagi di konka, terdapat jaringan
pembuluh darah dengan badan menggelembung.
Pendarahan hidung sebagian besar berasal dari daerah aliran a. karotis eksterna
dan 30% melalui a. karotis interna. Inervasi sensoris terutama berjalan melalui
percabangan n. trigeminus.
Fungsi Hidung
Hidung merupakan bagian dari traktus respiratorius, alat penghidu dan rongga
suara untu berbicara.
Fungsi pernafasan adalah mengatur kondisi udara yang dihirup dan mengatur
tahanan pernapasan. Fungsi mengatur kondisi udara meliputi pemanasan,
kelembaban dan pembersihan. Pemanasan tercapai melalui kontak udara yang
dihirup dengan permukaan dalam yang luas dan pleksus pembuluh darah didalam
submukosa hidung. Palut lender diatas selaput lender menjenuhkan udara yang
dihirup dengan uap air. Pembersihan terjadi karena rambut didalam vestibulum
menahan debu dan karena percikan debu (partikel) tertahan dalam lender, oleh
gerakan rambut getar selaput lender, lender dialirkan ke faring.
Hidung sebagai alat penghidu pada manusia memiliki peran yang lebih kecil
disbanding dengan fungsi hidung pada hewan pada umumnya, namun masih
sangat penting untuk memilih jenis makanan dan minuman, sebagai perlindungan
terhadap pengaruh yang merusak dan berbahaya (misalnya mencium bau
pembakaran) dan untuk hubungan dengan lingkungan.
Pada waktu berbicara, hidung berperan sebai rongga suara yaitu rongga
resonansi, apabila nasofaring tidak tertutup dan sebagian dikeluarkan melalui
hidung. Hidung merupakan alat reflex yang penting. Kebanyakan reflex melibat
dalam pengaturan dalamnya pernapasan, lama bernapas dan tertahan hidung.
Hidunng mempunyai fungsi estetis dan emotif. Hidung secara tak wajar dipakai
dalam kata mutiara dan gambar komik. Bentuk hidung yang menyimpang sering
merupakan beban psikis dan social. Kelainan bentuk bisa didapat sejak lahir atau
akibat trauma, infeksi atau tumor.
5

B. Epidemiologi
Rinitis tersebar di seluruh dunia, baik bersifat endemis maupun muncul
sebagai KLB. Di daerah beriklim sedang, insidensi penyakit ini meningkat di
musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di daerah tropis, insidensi
penyakit tinggi pada musim hujan. Sebagian besar orang, kecuali mereka yang
tinggal di daerah dengan jumlah penduduk sedikit dan terisolasi, bisa terserang
satu hingga 6 kali setiap tahunnya. Insidensi penyakit tinggi pada anak-anak di
bawah 5 tahun dan akan menurun secara bertahap sesuai dengan bertambahnya
umur.
Rinitis merupakan salah satu penyakit paling umum yang terdapat di amerika
Serikat, mempengaruhi lebih dari 50 juta orang. Keadaan ini sering berhubungan
dengan kelainan pernapasan lainnya, seperti asma. Rhinitis memberikan
pengaruh yang signifikan pada kualitas hidup. Pada beberapa kasus, dapat
menyebabkan kondisi lainnya seperti masalah pada sinus, masalah pada telinga,
gangguan tidur, dan gangguan untuk belajar. Pada pasien dengan asma, rinitis yg
tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi asmanya.
Angka kejadian rhinitis alergi secara umum berkisar 25% terutama pada
remaja dan dewasa. Prevalensi rinitis alergi di Indonesia bervariasi antara 1,5-
12,3 % dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagian besar penderita
ternyata mengalami penurunan kualitas hidup, kualitas pendidikan dan
produktivitas kerja. Meskipun bukan penyakit yang berbahaya, rinitis alergi
harus dianggap sebagai penyakit serius agar tidak memperparah kondisi dan
mempersulit penanganannya (DeGuzman DA, 2007, Nurcahyo H, 2009).
C. Definisi Rhinitis
Rhinitis berasal dari dua kata bahasa Greek “rhin/rhino” (hidung) dan “itis”
(radang). Dengan demikian rhinitis berarti radang hidung atau tepatnya radang
selaput lendir (membran mukosa) hidung.
Rhinitis adalah suatu inflamasi ( peradangan ) pada membran mukosa di
hidung. (Dipiro, 2005 ). Rhinitis adalah peradangan selaput lendir hidung.
( Dorland, 2002 ). Rinitis atau hidung tersumbat adalah suatu bejala yang paling
sering ditemukan dan etiologinya dapat alergi ataupun non alergi (Swartz, Mark
H,1995).
Rinitis adalah suatu inflamasi membran mukosa hidung dan mungkin di
kelompokkan sebagai rinitis alergik maupun non alergik (Brunner&Suddart,
2001). Sedangkan menurut WHO ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma) 2001 adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rhinore,
6

rasa gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang
diperantari oleh IgE.
Klasifikasi rinitis alergi berdasarkan rekomendasi dari WHO Iniative ARIA
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) tahun 2000, yaitu berdasarkan sifat
berlangsungnya dibagi menjadi :
1. Intermiten (kadang-kadang) : bila gejala kurang dari 4 hari/minggu atau
kurang dari 4 minggu
2. Persisten atau menetap bila gejala lebih dari 4 hari/minggu dan atau lebih dari
4 minggu.
Sedangkan untuk tingkat berat ringannya penyakit, rinitis alergi dibagi
menjadi :
1. Ringan, bila tidak ditemukan gangguan tidur, gangguan aktifitas harian,
bersantai, berolahraga, belajar, bekerja dan hal-hal lain yang mengganggu.
2. Sedang atau berat bila terdapat satu atau lebih dari gangguan tersebut.
Klasifikasi rhinitis yaitu :
1. Rhinitis Akut
Rhinitis akut adalah radang akut pada mukosa hidung yang disebabkan
oleh infeksi virus atau bakteri. Selain itu, rhinitis akut dapat juga timbul
sebagai reaksi sekunder akibat iritasi lokal atau trauma. Penyakit ini seringkali
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk ke dalam rhinitis akut
seperti rhinitis influenza.
7

2. Rhinitis Kronis
Suatu peradangan kronis pada membran mukosa yang disebabkan oleh
infeksi yang berulang, karena alergi, atau karena rinitis vasomotor. Rhinitis
disebut kronik bila radang berlangsung lebih dari 1 bulan.
Rinitis kronis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Rhinitis Alergi
Rhinitis alergi adalah istilah umum yang digunakan untuk
menunjukkan setiap reaksi alergi mukosa hidung, dapat terjadi bertahun-
tahun atau musiman. (Dorland,2002 ). Rhinitis alergi adalah penyakit
inflamasi yang disebabkan oleh reaksi pasien atopi yang sebelumnya sudah
tersensitasi dengan alergen spesifik atau pada partikel seperti debu, asap ,
serbuk atau tepung sari yang ada pada udara. (Efianty Arsyad,Soepardi,
2010). Gejala klinis yang muncul pada fase akut (dalam 5 menit setelah
terpajan alergen), manifestasi rinitis alergi berupa bersin, gatal di hidung,
dan rinorea cairan. Selama fase lanjut (4-8 jam setelah pajanan), gejala
utama rinitis alergi adalah kongesti nasal. (Greenberg,2008).
Macam-macam rhinitis alergi yaitu :
a. Rinitis alergi musiman (Hay Fever), biasanya terjadi pada musim semi.
Umumnya disebabkan kontak dengan allergen dari luar rumah, seperti
benang sari dari tumbuhan yang menggunakan angin untuk
penyerbukannya, debu dan polusi udara atau asap.
b. Rinitis alergi yang terjadi terus menerus (perennial), disebabkan bukan
karena musim tertentu ( serangan yang terjadi sepanjang masa
(tahunan)) diakibatkan karena kontak dengan allergen yang sering
berada di rumah misalnya kutu debu rumah, bulu binatang peliharaan
serta bau-bauan yang menyengat.
8

b) Rhinitis Non Alergi
Rhinitis Non Alergi disebabkan oleh infeksi saluran napas (rhinitis
viral dan rhinitis bakterial, masuknya benda asing kedalam hidung,
deformitas struktural, neoplasma, dan massa, penggunaan kronik
dekongestan nasal, penggunaan kontrasepsi oral, kokain dan anti
hipertensif.
Rhinitis non alergi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Rhinitis vasomotor adalah hiperaktivitas aspesifik selaput lendir hidung.
Keluhan utamanya ialah hidung tersumbat, terutama waktu merebahkan
diri dan tidur dan dalam lingkungan yang berasap.
Keseimbangan vasomotor ini dipengaruhi berbagai hal :
a) Obat-obatan yang menekan dan menghambat kerja saraf simpatis,
seperti: ergotamin, klorpromazin, obat antihipertensi, dan obat
vasokontriktor lokal.
b) Faktor fisik, seperti iritasi asap rokok, udara dingin, kelembapan
udara yang tinggi, dan bau yang merangsang.
c) Faktor endokrin, seperti : kehamilan, pubertas, dan hipotiroidisme.
d) Faktor psikis, seperti : cemas dan tegang.
b. Rhinitis Atrofi adalah di tandai dengan adanya atrofi selaput lendir
hidung, rongga hidung yang luas, keluhan tersumbatnya hidung (karena
luasnya rongga hidung terjadi peningkatan tahanan akibat lebih banyak
aliran turbulen dibanding aliran laminar) dan biasanya banyak terdapat
krusta yang bau.
c. Rhinitis Hipertrofi biasanya terjadi akibat gangguan kronis di hidung
sehingga timbul hipertrofi selaput lendir dan konka. Keluhan pasien
adalah hidung tersumbat.
D. Etiologi
1. Penyebab
Rinitis alergi secara umum disebabkan oleh interaksi dari pasien yang secara
genetik memiliki potensi alergi dengan lingkungan. Peran lingkungan dalam
dalam rinitis alergi yaitu alergen, yang terdapat di seluruh lingkungan,
terpapar dan merangsang respon imun yang secara genetik telah memiliki
kecenderungan alergi. Adapun alergen yang biasa dijumpai berupa alergen
9

inhalan yang masuk bersama udara pernapasan yaitu debu rumah, tungau,
kotoran serangga, kutu binatang, jamur, serbuk sari, dan lain-lain
2. Faktor Risiko
Seseorang akan mudah atau mungkin lebih mudah mengalami rinitis alergi
ketika memiliki riwayat alergi seperti asma atau gatal-gatal pada kulit,
riwayat keluarga dengan rinitis alergi atau asma dan alergi jenis lain dan
tinggal di tempat yang sering terpapar alergen seperti bulu binatang.
3. Faktor Predisposisi
A. Faktor luar :
a) Pengaruh atmofer : angin, suhu, udara, humiditas, hujan.
b) Common cold virus hidup lebih baik pada humiditas tinggi.
c) Ventilasi ruangan yang kurang : ruangan kecil, tertutup, penuh
orang.
d) Debu, gas
Dingin menimbulkan refleksi vasokonstriksi yang kemudian
menyebabkan iskemi jaringan sehingga daya tahan terhadap infeksi
menurun.
B. Faktor dalam :
a) Daya tahan tubuh yang menurun.
a. Kelelahan.
b. Kurang makanan bergizi.
c. Defisiensi vitamin A, C dan D
b) Daya tahan local kavum nasi.
a. Alergi hidung.
b. Obstruksio nasi kronis, misalnya adenoid hipertrofi, septum
deviasi.
c) Penyakit exanthema
Rhinitis akuta dapat merupakan gejala prodomal dari morbilli,
varicella, variola.
Rhinitis alergi adalah penyakit peradangan yang diawali oleh dua tahap
sensitisasi yang diikuti oleh reaksi alergi. Reaksi alergi terdiri dari dua fase
yaitu :
1. Immediate Phase Allergic Reaction, berlangsung sejak kontak dengan
allergen hingga 1 jam setelahnya.
2. Late Phase Allergic Reaction, reaksi yang berlangsung pada dua hingga
empat jam dengan puncak 6-8 jam setelah pemaparan dan dapat berlangsung
hingga 24 jam.
10

Berdasarkan cara masuknya allergen dibagi atas :
1. Alergen Inhalan, yang masuk bersama dengan udara pernafasan, misalnya
debu rumah, tungau, serpihan epitel dari bulu binatang serta jamur.
2. Alergen Ingestan, yang masuk ke saluran cerna, berupa makanan, misalnya
susu, telur, coklat, ikan dan udang.
3. Alergen Injektan, yang masuk melalui suntikan atau tusukan, misalnya
penisilin atau sengatan lebah.
4. Alergen Kontaktan, yang masuk melalui kontak dengan kulit atau jaringan
mukosa, misalnya bahan kosmetik atau perhiasan
Dengan masuknya allergen ke dalam tubuh, reaksi alergi dibagi menjadi
tiga tahap besar :
1. Respon Primer, terjadi eliminasi dan pemakanan antigen, reaksi non spesifik.
2. Respon Sekunder, reaksi yang terjadi spesifik, yang membangkitkan system
humoral, system selular saja atau bisa membangkitkan kedua system terebut,
jika antigen berhasil dihilangkan maka berhenti pada tahap ini, jika antigen
masih ada, karena defek dari ketiga mekanisme system tersebut maka
berlanjut ke respon tersier.
3. Respon Tersier , reaksi imunologik yang tidak meguntungkan.
Sedangkan klasifikasi yang lebih baru menurut guideline dari
ARIA, 2001 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) disdasarkan
pada waktu terjadinya gejala dan keparahannya adalah:
Berdasarkan lamanya terjadi gejala
Klasifikasi Gejala dialami selama
Intermitten Kurang dari 4 hari seminggu, atau
kurang dari 4 minggu setiap saat
kambuh.
Persisten Lebih dari 4 hari seminggu, atau
lebih dari 4 minggu setiap saat
kambuh.
Berdasarkan keparahan dan kualitas hidup
Ringan Tidak mengganggu tidur, aktivitas
harian, olahraga, sekolah atau
pekerjaan. Tidak ada gejala yang
mengganggu.
Sedang sampai berat Terjadi satu atau lebih kejadian di bawah
ini:
11

1. Gangguan tidur, gangguan aktivitas
harian, kesenangan, atau olah raga
3. gangguan pada sekolah atau pekerjaan
4. gejala yang mengganggu
E. Patofisiologi
1) Rinitis Alergi
Rinitis alergi merupakan suatu penyakit inflamasi yang diawali dengan
tahap sensitisasi dan diikuti tahap provokasi atau reaksi alergi. Pada kontak
pertama dengan alergen, makrofag dan monosit sebagai penyaji akan
menangkap allergen yang menempel dimukosa hidung. Setelah diproses,
antigen akan membentuk fragmen pendek peptida dan bergabung dengan
molekul HLA (Human Leukosit Antigen) dan akan membentuk komplek
peptida MHC (Major Histocompatibility Complex) yang kemudian akan
bertemu oleh sel T helper.
Kemudian sel penyaji akan melepaskan sitokin seperti interleukin dan
sel T helper akan berproliferasi (memperbanyak diri) yang menghasilkan
berbagai sitokin dan sel limfosit B dalam darah akan mengikat sitokin
tersebut. Mengakibatkan sel limfosit B akan menjadi aktif dan akan
menghasilkan Ig E. Ig E di aliran darah akan masuk ke jaringan dan diikat
oleh mastoid atau basofil (sel mediator) sehingga kedua sel ini menjadi aktif.
Proses ini disebut sensitisasi yang menghasilkan sel mediator yang
tersensitisasi. Bila mukosa ini terpapar allergen yang sama, Ig E akan
mengikat allergen spesifik dan terjadi degranulasi (pecahnya dinding sel
mastoid dan basofil) yang mengakibatkan mediator kimia terlepas
(histamin).
Histamin ini akan merangsang H1 pada ujung syaraf vidianus
sehingga menimbulkan rasa gatal pada hidung dan bersin-bersin. Dan
histamine juga akan menyebabkan kelenjar mukosa dan sel goblet
mengalami hipersekresi dan pemeabilitas kapiler meningkat sehingga terjadi
rinore yang akan terjadi hidung tersumbat sehingga akan mengakibatkan
obstruksi saluran pernafasan. (Efianty Arsyad Soepardi 2010).
2) Rinitis non alergi
12

Pemakaian topikan vasokonstriktor berulang dan dalam waktu lama
akan menyebabkan terjadinya fase dilatasi berulang setelah vasokonstriksi
sehingga timbul gejala obstruksi. Hal ini menyebabkan pasien lebih sering
dan lebih lama lagi memakai obat tersebut. Pada keadaan ini ditemukan
kadar agonis alfa adrenergic yang tinggi di mukosa hidung. dan akan diikuti
penurunan sensitivitas reseptor alfa adrenergic di pembuluh darah sehingga
terjadi suatu toleransi. Aktivitas dari tonus simpatis yang menyebabkan
vasokonstriksi (dekongesti mukosa hidung) menghilang. Akan terjadi
dilatasi dan kongesti jaringan mukosa hidung.
Kerusakan yang terjadi pada mukosa hidung pada pemakaian obat
tetes hidung dalam waktu lama ialah silia akan rusak, sel goblet berubah
ukurannya, membran basal menebal, pembuluh darah melebar, stroma
tampak edema, hipersekresi kelenjar mucus dan perubahan pH secret hidung,
lapisan sub mukosa menebal dan lapisan periostium menebal. Oleh karena
itu pemakaian obat vasokonstriktor sebaiknya tidak lebih dari satu minggu,
dan sebaiknya yang bersifat isotonik dengan sekret hidung normal (pH
antara 6,3 dan 6,5). (Efianty Arsyad Soepardi 2010).
WOC
13

F. Tanda dan Gejala
14

1. Rhinitis akut
a. Stadium Prodromal Kering (stadium awal), di mana penderita merasakan
gejala umum seperti menggigil dengan rasa panas dingin berselingan
(meriang), nyeri kepala, pucat, kurang nafsu makan, kadang suhu
subfebril atau tidak terlalu panas, tapi sering juga terjadi suhu yang tinggi
apalagi pada anak-anak yang disertai rasa gatal, panas, rasa kering pada
hidung dan tenggorokan, iritasi hidung. Mukosa hidung biasanya pucat
dan kering.
b. Stadium Kataralis (stadium lanjutan), pada saat ini biasanya dimulai
beberapa jam setelah sekret mencair, obstruksi atau penyumbatan hidung,
kehilangan penciuman sementara, lakrimalisasi atau airmata terus-
menerus meleleh, dan keadaan bisa berangsur-angsur menjadi lebih
buruk. Mukosa hidung memerah, bengkak, dan terdapat sekret atau ingus
yang banyak.
2. Rhinitis Kronis
a. Rhinitis Alergi
Gejala rinitis alergi yang khas ialah terdapatnya serangan bersin
berulang. Sebetulnya bersin merupakan gejala yang normal, terutama
pada pagi hari atau bila terdapat kontak dengan sejumlah besar debu. Hal
ini merupakan mekanisme fisiologik, yaitu proses membersihkan sendiri
(self cleaning process). Bersin dianggap patologik, bila terjadinya lebih
dari 5 kali setiap serangan, sebagai akibat dilepaskannya histamin.
Disebut juga sebagai bersin patologis (Soepardi, Iskandar, 2004). Gejala
lain ialah keluar ingus (rinore) yang encer dan banyak, hidung tersumbat,
hidung dan mata gatal, yang kadang-kadang disertai dengan banyak air
mata keluar (lakrimasi). Tanda-tanda alergi juga terlihat di hidung, mata,
telinga, faring atau laring. Tanda hidung termasuk lipatan hidung
melintang – garis hitam melintang pada tengah punggung hidung akibat
sering menggosok hidung ke atas menirukan pemberian hormat (allergic
salute), pucat dan edema.
b. Rhinitis Non Alergi
a) Rhinitis Vasomotor
Hidung tersumbat, bergantian kiri dan kanan, tergantung pada posisi
pasien. Terdapat rinorea yang mukus atau serosa, kadang agak
banyak. Jarang disertai bersin, dan tidak disertai gatal di mata. Gejala
15

memburuk pada pagi hari waktu bangun tidur karena perubahan suhu
yang ekstrim, udara lembab, juga karena asap rokok dan sebagainya.
b) Rhinitis Atrofi
Bersin berulang-ulang, terutama setelah bangun tidur pada pagi
hari (umumnya bersin lebih dari 6 kali). Hidung tersumbat dan hidung
meler. Cairan yang keluar dari hidung meler yang disebabkan alergi
biasanya bening dan encer, tetapi dapat menjadi kental dan putih
keruh atau kekuning-kuningan jika berkembang menjadi infeksi
hidung atau infeksi sinus. Hidung gatal dan juga sering disertai gatal
pada mata, telinga dan tenggorok. Badan menjadi lemah dan tak
bersemangat.
c) Rhinitis Hipertrofi
Penderita mengeluh hidungnya tersumbat terus menerus dan berair.
Pada pemeriksaan konka dengan secret hidung yang berlebihan.
G. Pemeriksaan Diagnostik
1. In vitro
Hitung eosinofil dalam darah tepi dapat normal atau meningkat.
Demikian pula pemeriksaan IgE total (prist-paper radio imunosorbent test)
sering kali menunjukkan nilai normal, kecuali bila tanda alergi pada pasien
lebih dari satu macam penyakit, misalnya selain rinitis alergi juga menderita
asma bronkial atau urtikaria. Pemeriksaan ini berguna untuk prediksi
kemungkinan alergi pada bayi atau anak kecil dari suatu keluarga dengan
derajat alergi yang tinggi. Lebih bermakna adalah dengan RAST (Radio
Immuno Sorbent Test) atau ELISA (Enzyme Linked Immuno SorbentAssay
Test).
Pemeriksaan sitologi hidung, walaupun tidak dapat memastikan
diagnosis, tetap berguna sebagai pemeriksaan pelengkap. Ditemukannya
eosinofil dalam jumlah banyak menunjukkan kemungkinan alergi inhalan.
Jika basofil (5 sel/lap) mungkin disebabkan alergi makanan, sedangkan jika
ditemukan sel PMN menunjukkan adanya infeksi bakteri.
2. In vivo
Alergen penyebab dapat dicari dengan cara pemeriksaan tes cukit
kulit, uji intrakutan atau intradermal yang tunggal atau berseri (Skin End-
point Titration/SET). SET dilakukan untuk alergen inhalan dengan
menyuntikkan alergen dalam berbagai konsentrasi yang bertingkat
16

kepekatannya. Keuntungan SET, selain alergen penyebab juga derajat alergi
serta dosis inisial untuk desensitisasi dapat diketahui.
Untuk alergi makanan, uji kulit seperti tersebut diatas kurang dapat
diandalkan. Diagnosis biasanya ditegakkan dengan diet eliminasi dan
provokasi (Challenge Test). Alergen ingestan secara tuntas lenyap dari tubuh
dalam waktu lima hari. Karena itu pada Challenge Test, makanan yang
dicurigai diberikan pada pasien setelah berpantang selama 5 hari, selanjutnya
diamati reaksinya.
Pada diet eliminasi, jenis makanan setiap kali dihilangkan dari menu
makanan sampai suatu ketika gejala menghilang dengan meniadakan suatu
jenis makanan.
3. Pemeriksaan Rinoskopi Anterior dan Posterior
Rinoskopi anterior adalah pemeriksaan rongga hidung dari depan dengan
memakai spekulum hidung. Di belakang vestibulum dapat dilihat bagian
dalam hidung. Saluran udara harus bebasdan kurang lebih sama pada kedua
sisi. Pada kedua dinding lateral dapat dilihat konka inferior. Hal-hal yang
harus diperhatikan pada rinoskopi anterior ialah :
a) Mukosa. Dalam keadaan normal, mukosa berwarna merah muda. Pada
radang berwarna merah, sedangkan pada alergi akan tampak pucat atau
kebiru-biruan (livid).
b) Septum. Biasanya terletak di tengah dan lurus. Diperhatikan apakah ada
deviasi, krista, spina, perforasi, hematoma, abses dan lain-lain.
c) Konka. Diperhatikan apakah konka besarnya normal (eutrofi, hipertrofi,
hipotrofi atau atrofi).
d) Sekret. Bila ditemukan sekret pada rongga hidung, harus diperhatikan
banyaknya, sifatnya (serous, mukoid, mukopurulen, purulen atau
17

bercampur darah) dan lokalisasinya (meatus inferior medius, atau superior).
Lokasi sekret ini penting artinya, sehubungan dengan letak ostium sinus-
sinus paranasal dan dengan demikian dapat menunjukkan dari mana sekret
tersebut berasal. Krusta yang banyak ditemukan pada rhinitis atrofi.
e) Massa. Massa yang sering ditemukan di dalam rongga hidung adalah polip
dan tumor. Pada anak dapat ditemukan benda asing.
Rhinoskopi posterior adalah pemeriksaan ronnga hidung dari
belakang, dengan menggunakan kaca nasofaring. Dengan mengubah-ubah
posisi kaca, kita dapat melihat koana, ujung posterior septum, ujung
posterior konka, sekret yang mengalir dari hidung ke nasofaring (post nasal
drip), torus tubarius, dan ostium tuba.
Akhir-akhir ini dikembangkan cara pemeriksaan dengan endoskop,
disebut nasoendoskopi. Dengan cara ini bagian-bagian rongga hidung yang
tersembunyi yang sulit dilihat dengan rinoskopi anterior, maupun rinoskopi
posterior akan tampak lebih jelas.
H. Penatalaksanaan Medis
Terapi medikamentosa yaitu anti histamin, dekongestan dan kortikosteroid.
a. Antihistamin
Antihistamin yang sering digunakan adalah antihistamin oral.
Antihistamin oral dibagi menjadi dua yaitu generasi pertama (nonselektif)
dikenal juga sebagai antihistamin sedatif serta generasi kedua (selektif)
dikenal juga sebagai antihistamin nonsedatif.
Efek sedative antihistamin sangat cocok digunakan untuk pasien yang
mengalami gangguan tidur karena rhinitis alergi yang dideritanya. Selain itu
efek samping yang biasa ditimbulkan oleh obat golongan antihistamin adalah
efek antikolinergik seperti mulut kering, susah buang air kecil dan konstipasi.
Penggunaan obat ini perlu diperhatikan untuk pasien yang mengalami
kenaikan tekanan intraokuler, hipertiroidisme, dan penyakit kardiovaskular.
Antihistamin sangat efektif bila digunakan 1 sampai 2 jam sebelum
terpapar allergen. Penggunaan antihistamin harus selalu diperhatikan
terutama mengenai efek sampingnya. Antihistamin generasi kedua memang
memberikan efek sedative yang sangat kecil namun secara ekonomi lebih
mahal.
b. Dekongestan
18

Dekongestan topical dan sistemik merupakan simpatomimetik agen
yang beraksi pada reseptor adrenergic pada mukosa nasal, memproduksi
vasokonstriksi. Topikal dekongestan biasanya digunakan melalui sediaan
tetes atau spray. Penggunaan dekongestan jenis ini hanya sedikit atau sama
sekali tidak diabsorbsi secara sistemik (Dipiro, 2005).
Penggunaan obat ini dalam jangka waktu yang lama dapat
menimbulkan rhinitis medikamentosa (rhinitis karena penggunaan obat-
obatan). Selain itu efek samping yang dapat ditimbulkan topical dekongestan
antara lain rasa terbakar, bersin, dan kering pada mukosa hidung. Untuk itu
penggunaan obat ini memerlukan konseling bagi pasien.
Sistemik dekongestan onsetnya tidak secepat dekongestan topical.
Namun durasinya biasanya bisa lebih panjang. Agen yang biasa digunakan
adalah pseudoefedrin. Pseudoefedrin dapat menyebabkan stimulasi sistem
saraf pusat walaupun digunakan pada dosis terapinya (Dipiro, 2005).
Obat ini harus hati-hati digunakan untuk pasien-pasien tertentu seperti
penderita hipertensi. Saat ini telah ada produk kombinasi antara antihistamin
dan dekongestan. Kombinasi ini rasional karena mekanismenya berbeda.
c. Nasal Steroid
Merupakan obat pilihan untuk rhinitis tipe perennial, dan dapat
digunakan untuk rhinitis seasonal. Nasal steroid diketahui memiliki efek
samping yang sedikit. Obat yang biasa digunakan lainnya antara lain sodium
kromolin, dan ipatropium bromida.
Operatif : Konkotomi merupakan tindakan memotong konka nasi inferior
yang mengalami hipertrofi berat. Lakukan setelah kita gagal mengecilkan
konka nasi inferior menggunakan kauterisasi yang memakai AgNO3 25%
atau triklor asetat.
Imunoterapi : Jenisnya desensitasi, hiposensitasi dan netralisasi. Desensitasi
dan hiposensitasi membentuk blocking antibody. Keduanya untuk alergi
inhalan yang gejalanya berat, berlangsung lama dan hasil pengobatan lain
belum memuaskan. Netralisasi tidak membentuk blocking antibody dan
untuk alergi ingestan.
I. Asuhan Keperawatan
19

1. Teori Asuhan Keperawatan Pada Klien Rhinitis Akut
a) Pengkajian
Pengkajian adalah langkah awal dari proses keperawatan yang meliputi
aspek bio, psiko, sosio dan spiritual secara komprehensif. Maksud dari
pengkajian adalah untuk mendapatkan informasi atau data tentang pasien.
Data tersebut berasal dari pasien (data primer), dari keluarga (data
sekunder) dan data dari catatan yang ada (data tersier). Pengkajian
dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan melalui wawancara,
observasi langsung, dan melihat catatan medis, adapun data yang
diperlukan pada klien Rhinitis Akut adalah sebagai berikut :
a. Data dasar
Adapun data dasar yang dikumpulkan meliputi :
1. Identitas klien
Identitas klien meliputi nama, umur (Rhinitis akut menyerang pada
semua usia tidak terkecuali), jenis kelamin (Rhinitis akut menyerang
pada semua orang tidak terkecuali), suku bangsa, agama, pendidikan,
pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit dan diagnose medis.
2. Riwayat kesehatan sekarang
Meliputi keluhan utama pasien dengan Rhinitis Akut biasanya
datang dengan keluhan flu (influenza).
3. Riwayat kesehatan masa lalu
Klien mengatakan tidak punya penyakit yang lain.
4. Riwayat kesehatan keluarga
Klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang alergi terhadap
apapun.
b. Pemeriksaan fisik yaitu Review of system (ROS)
Keadaan umum : Tampak kesakitan pada pemeriksaan fisik terdapat nyeri
tekan di kuadran epigastrik
1. B1 (breath) : Takhipnea.
2. B2 (blood) : Warna kulit pucat.
3. B3 (brain) : Sakit kepala, kelemahan, kesadaran composmentis.
4. B4 (bladder) : Pola eliminasi normal.
5. B5 (bowel) : Anorexia.
6. B6 (bone) : Kelemahan.
c. Pemeriksaan Diagnostik
Pemeriksaan diagnostik yang dianjurkan untuk pasien Rhinitis
Akut adalah :
20

1. Pemeriksaan darah (eosinofil).
2. Pemeriksaan rinoskopi anterior posterior.
b) Diagnosa Keperawatan
Sebelum membuat diagnosa keperawatan maka data yang terkumpul
diidentifikasi untuk menentukan masalah melalui analisa data,
pengelompokkan data dan menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa
keperawatan adalah keputusan atau kesimpulan yang terjadi akibat dari
hasil pengkajian keperawatan.
Diagnosa keperawatan pada klien dengan Rhinitis Akut adalah :
1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan
obstruksi saluran nafas.
2. Gangguan persepsi sensori yang berhubungan dengan berkurangnya
sensasi penciuman.
3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang
berhubungan dengan anoreksia.
4. Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan penyumbatan pada
hidung.
c) Intervensi
a. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
Tujuan : Untuk melaporkan jalan napas menjadi efektif.
a) Kaji status pernapasan sekurangnya setiap 4 jam.
b) Gunakan posisi fowler dan sangga lengan pasien.
c) Bantu pasien untuk mengubah posisi, batuk dan bernapas
dalam setiap 2 sampai 4 jam.
d) Isap sekresi sesuai keperluan.
b. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
Tujuan : Untuk melaporkan peningkatan persepsi penciuman.
a) Kaji kemampuan pasien untuk mencium bau dan
dokumentasikan temuan.
b) Yakinkan pasien bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan
sensasi penciumannya akan pulih.
c) Berikan obat yang diprogamkan sesuai antihistamin.
21

d) Catat karakteristik drainase hidung meliputi jumlah, warna,
konsistensi dan bau.
c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan anoreksia.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien mengkonsumsi minimal 3000 kalori.
a) Observasi dan catat asupan pasien (cair dan padat).
b) Tentukan makanan kesukaan pasien.
c) Ciptakan lingkungan yang menyenangkan pada waktu makan.
d) Hindari bertanya apakah pasien lapar atau ingin makan.
d. Gangguan pola tidur berhubungan dengan penyumbatan pada hidung.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien tidak menunjukkan gejala perilaku
yang berkaitan dengan tidur seperti kegelisahan.
a) Segera buat perubahan apapun yang mungkin untuk
mengakomodasi pasien.
b) Rencanakan jadwal pemberian pengobatan disekitar jadwal
tidur pasien.
c) Buat rencana detail untuk member pasien kesempatan tidur 7
jam tanpa gangguan.
d) Implementasi
Menurut Doengoes, 2000 implementasi adalah tindakan pemberian
keperawatan yang dilaksanakan untuk membantu mencapai tujuan pada
rencana tindakan keperawatan yang telah disusun. Setiap tindakan
keperawatan yang dilaksanakan dicatat dalam catatan keperawatan yaitu
cara pendekatan pada klien efektif, teknik komunikasi terapeutik serta
penjelasan untuk setiap tindakan yang diberikan kepada pasien.
Dalam melakukan tindakan keperawatan menggunakan 3 tahap
pendekatan, yaitu independen, dependen, interdependen. Tindakan
keperawatan secara independen adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau
tenaga kesehatan lainnya. Interdependen adalah tindakan keperawatan
yang menjelaskan suatu kegiatan dan memerlukan kerja sama dengan
tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, dan dokter.
Sedangkan dependen adalah tindakan yang berhubungan dengan
pelaksanaan rencana tindakan medis. Keterampilan yang harus dipunyai
22

perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan yaitu kognitif, sikap
dan psikomotor.
Dalam melakukan tindakan khususnya pada klien dengan rhinitis
akut yang harus diperhatikan adalah pola nutrisi, pernafasan klien serta
melakukan pendidikan kesehatan pada klien.
e) Evaluasi Keperawatan
Menurut Doengoes, 2000 evaluasi adalah tingkatan intelektual
untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa
jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaannya
sudah berhasil dicapai. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap
evaluasi adalah masalah dapat diatasi, masalah teratasi sebagian,
masalah belum teratasi atau timbul masalah baru. Evaluasi yang
dilakukan adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil.
Evaluasi proses adalah evaluasi yang harus dilaksanakan segera
setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan untuk membantu
keefektifitasan terhadap tindakan. Sedangkan evaluasi hasil adalah
evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan secara
keseluruhan sesuai dengan waktu yang ada pada tujuan.
Adapun evaluasi dari diagnosa keperawatan rhinitis akut secara
teoritis adalah apakah klien dapat mengkonsumsi makanan dengan
baik, apakah klien dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri,
apakah klien mampu mengungkapkan pemahaman tentang penyakit
rhinitis akut.
2. Teori Asuhan Keperawatan Pada Klien Rhinitis Alergi
a) Pengkajian
Pengkajian adalah langkah awal dari proses keperawatan yang meliputi
aspek bio, psiko, sosio dan spiritual secara komprehensif. Maksud dari
pengkajian adalah untuk mendapatkan informasi atau data tentang pasien.
Data tersebut berasal dari pasien (data primer), dari keluarga (data
sekunder) dan data dari catatan yang ada (data tersier). Pengkajian
dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan melalui wawancara,
observasi langsung, dan melihat catatan medis, adapun data yang
diperlukan pada klien Rhinitis Alergi adalah sebagai berikut :
a. Data dasar
Adapun data dasar yang dikumpulkan meliputi :
23

1. Identitas klien
Identitas klien meliputi nama, umur (Rhinitis alergi menyerang
pada semua usia tidak terkecuali), jenis kelamin (Rhinitis alergi
menyerang pada semua orang tidak terkecuali), suku bangsa,
agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit
dan diagnose medis.
2. Riwayat kesehatan sekarang
Meliputi keluhan utama pasien dengan Rhinitis Alergi
biasanya datang dengan keluhan hidung tersumbat dan hidung
terasa gatal.
3. Riwayat kesehatan masa lalu
Klien mengatakan tidak punya penyakit yang lain.
4. Riwayat kesehatan keluarga
Klien biasanya mempunyai riwayat keturunan alergi.
b. Pemeriksaan fisik yaitu Review of system (ROS)
Keadaan umum : Tampak kesakitan pada pemeriksaan fisik terdapat
nyeri tekan di kuadran epigastrik
1. B1 (breath) : Bradipnea.
2. B2 (blood) : Warna kulit pucat.
3. B3 (brain) : Sakit kepala, kelemahan, kesadaran
composmentis.
4. B4 (bladder) : Pola eliminasi normal.
5. B5 (bowel) : Anorexia.
6. B6 (bone) : Kelemahan.
c. Pemeriksaan Diagnostik
Pemeriksaan diagnostik yang dianjurkan untuk pasien Rhinitis Alergi
adalah :
1. Pemeriksaan darah (eosinofil).
2. Pemeriksaan rinoskopi anterior posterior.
b) Diagnosa Keperawatan
Sebelum membuat diagnosa keperawatan maka data yang terkumpul
diidentifikasi untuk menentukan masalah melalui analisa data,
pengelompokkan data dan menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa
24

keperawatan adalah keputusan atau kesimpulan yang terjadi akibat dari
hasil pengkajian keperawatan.
Diagnosa keperawatan pada klien dengan Rhinitis Alergi adalah :
1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan
obstruksi saluran nafas.
2. Gangguan persepsi sensori yang berhubungan dengan berkurangnya
sensasi penciuman..
3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang
berhubungan dengan anoreksia.
4. Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan penyumbatan pada
hidung.
c) Intervensi
a. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
Tujuan : Untuk melaporkan jalan napas menjadi efektif.
a) Kaji status pernapasan sekurangnya setiap 4 jam.
b) Gunakan posisi fowler dan sangga lengan pasien.
c) Bantu pasien untuk mengubah posisi, batuk dan bernapas
dalam setiap 2 sampai 4 jam.
d) Isap sekresi sesuai keperluan.
b. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
Tujuan : Untuk melaporkan peningkatan persepsi penciuman.
a) Kaji kemampuan pasien untuk mencium bau dan
dokumentasikan temuan.
b) Yakinkan pasien bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan
sensasi penciumannya akan pulih.
c) Berikan obat yang diprogamkan sesuai antihistamin.
d) Catat karakteristik drainase hidung meliputi jumlah, warna,
konsistensi dan bau.
c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan anoreksia.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien mengkonsumsi minimal 3000 kalori.
a) Observasi dan catat asupan pasien (cair dan padat).
25

b) Tentukan makanan kesukaan pasien.
c) Ciptakan lingkungan yang menyenangkan pada waktu makan.
d) Hindari bertanya apakah pasien lapar atau ingin makan.
d. Gangguan pola tidur berhubungan dengan penyumbatan pada hidung.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien tidak menunjukkan gejala perilaku
yang berkaitan dengan tidur seperti kegelisahan.
a) Segera buat perubahan apapun yang mungkin untuk
mengakomodasi pasien.
b) Rencanakan jadwal pemberian pengobatan disekitar jadwal
tidur pasien.
c) Buat rencana detail untuk member pasien kesempatan tidur 7
jam tanpa gangguan.
d) Implementasi
Menurut Doengoes, 2000 implementasi adalah tindakan pemberian
keperawatan yang dilaksanakan untuk membantu mencapai tujuan pada
rencana tindakan keperawatan yang telah disusun. Setiap tindakan
keperawatan yang dilaksanakan dicatat dalam catatan keperawatan yaitu
cara pendekatan pada klien efektif, teknik komunikasi terapeutik serta
penjelasan untuk setiap tindakan yang diberikan kepada pasien.
Dalam melakukan tindakan keperawatan menggunakan 3 tahap
pendekatan, yaitu independen, dependen, interdependen. Tindakan
keperawatan secara independen adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau
tenaga kesehatan lainnya. Interdependen adalah tindakan keperawatan
yang menjelaskan suatu kegiatan dan memerlukan kerja sama dengan
tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, dan dokter.
Sedangkan dependen adalah tindakan yang berhubungan dengan
pelaksanaan rencana tindakan medis. Keterampilan yang harus dipunyai
perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan yaitu kognitif, sikap
dan psikomotor.
Dalam melakukan tindakan khususnya pada klien dengan rhinitis
alergi yang harus diperhatikan adalah pola nutrisi, pernafasan klien serta
melakukan pendidikan kesehatan pada klien.
e) Evaluasi Keperawatan
26

Menurut Doengoes, 2000 evaluasi adalah tingkatan intelektual
untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa
jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaannya
sudah berhasil dicapai. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap
evaluasi adalah masalah dapat diatasi, masalah teratasi sebagian,
masalah belum teratasi atau timbul masalah baru. Evaluasi yang
dilakukan adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil.
Evaluasi proses adalah evaluasi yang harus dilaksanakan segera
setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan untuk membantu
keefektifitasan terhadap tindakan. Sedangkan evaluasi hasil adalah
evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan secara
keseluruhan sesuai dengan waktu yang ada pada tujuan.
Adapun evaluasi dari diagnosa keperawatan rhinitis alergi secara
teoritis adalah apakah klien dapat mengkonsumsi makanan dengan
baik, apakah klien dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri,
apakah klien mampu mengungkapkan pemahaman tentang penyakit
rhinitis alergi.
3. Teori Asuhan Keperawatan Pada Klien Rhinitis Vasomotor
a) Pengkajian
Pengkajian adalah langkah awal dari proses keperawatan yang meliputi
aspek bio, psiko, sosio dan spiritual secara komprehensif. Maksud dari
pengkajian adalah untuk mendapatkan informasi atau data tentang pasien.
Data tersebut berasal dari pasien (data primer), dari keluarga (data
sekunder) dan data dari catatan yang ada (data tersier). Pengkajian
dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan melalui wawancara,
observasi langsung, dan melihat catatan medis, adapun data yang
diperlukan pada klien Rhinitis Vasomotor adalah sebagai berikut :
a. Data dasar
Adapun data dasar yang dikumpulkan meliputi :
1. Identitas klien
Identitas klien meliputi nama, umur (Rhinitis vasomotor
menyerang pada semua usia tidak terkecuali), jenis kelamin (
Rhinitis vasomotor menyerang pada semua orang tidak terkecuali),
suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk
rumah sakit dan diagnose medis.
2. Riwayat kesehatan sekarang
27

Meliputi keluhan utama pasien dengan Rhinitis Vasomotor
biasanya datang dengan keluhan hidung tersumbat secara
bergantian kanan dan kiri tetapi tidak gatal pada daerah mata
hidung dan tenggorokan.
3. Riwayat kesehatan masa lalu
Klien mengatakan tidak punya penyakit yang lain.
4. Riwayat kesehatan keluarga
Klien biasanya tidak mempunyai riwayat keturunan alergi.
b. Pemeriksaan fisik yaitu Review of system (ROS)
Keadaan umum : Tampak kesakitan pada pemeriksaan fisik terdapat
nyeri tekan di kuadran epigastrik
1. B1 (breath) : Bradipnea.
2. B2 (blood) : Warna kulit pucat.
3. B3 (brain) : Sakit kepala, kelemahan, kesadaran
composmentis.
4. B4 (bladder) : Pola eliminasi normal.
5. B5 (bowel) : Anorexia.
6. B6 (bone) : Kelemahan.
c. Pemeriksaan Diagnostik
Pemeriksaan diagnostik yang dianjurkan untuk pasien Rhinitis Akut
adalah :
1. Pemeriksaan darah (eosinofil).
2. Pemeriksaan rinoskopi anterior posterior.
b) Diagnosa Keperawatan
Sebelum membuat diagnosa keperawatan maka data yang terkumpul
diidentifikasi untuk menentukan masalah melalui analisa data,
pengelompokkan data dan menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa
keperawatan adalah keputusan atau kesimpulan yang terjadi akibat dari
hasil pengkajian keperawatan.
Diagnosa keperawatan pada klien dengan Rhinitis Alergi adalah :
1. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan
obstruksi saluran nafas.
2. Gangguan persepsi sensori yang berhubungan dengan berkurangnya
sensasi penciuman.
28

3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang
berhubungan dengan anoreksia.
4. Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan penyumbatan pada
hidung.
c) Intervensi
a. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
Tujuan : Untuk melaporkan jalan napas menjadi efektif.
a) Kaji status pernapasan sekurangnya setiap 4 jam.
b) Gunakan posisi fowler dan sangga lengan pasien.
c) Bantu pasien untuk mengubah posisi, batuk dan bernapas
dalam setiap 2 sampai 4 jam.
d) Isap sekresi sesuai keperluan.
b. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
Tujuan : Untuk melaporkan peningkatan persepsi penciuman.
a) Kaji kemampuan pasien untuk mencium bau dan
dokumentasikan temuan.
b) Yakinkan pasien bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan
sensasi penciumannya akan pulih.
c) Berikan obat yang diprogamkan sesuai antihistamin.
d) Catat karakteristik drainase hidung meliputi jumlah, warna,
konsistensi dan bau.
c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan anoreksia.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien mengkonsumsi minimal 3000 kalori.
a) Observasi dan catat asupan pasien (cair dan padat).
b) Tentukan makanan kesukaan pasien.
c) Ciptakan lingkungan yang menyenangkan pada waktu makan.
d) Hindari bertanya apakah pasien lapar atau ingin makan.
d. Gangguan pola tidur berhubungan dengan penyumbatan pada hidung.
Tujuan : Untuk melaporkan pasien tidak menunjukkan gejala perilaku
yang berkaitan dengan tidur seperti kegelisahan.
29

a) Segera buat perubahan apapun yang mungkin untuk
mengakomodasi pasien.
b) Rencanakan jadwal pemberian pengobatan disekitar jadwal
tidur pasien.
c) Buat rencana detail untuk member pasien kesempatan tidur 7
jam tanpa gangguan.
d) Implementasi
Menurut Doengoes, 2000 implementasi adalah tindakan pemberian
keperawatan yang dilaksanakan untuk membantu mencapai tujuan pada
rencana tindakan keperawatan yang telah disusun. Setiap tindakan
keperawatan yang dilaksanakan dicatat dalam catatan keperawatan yaitu
cara pendekatan pada klien efektif, teknik komunikasi terapeutik serta
penjelasan untuk setiap tindakan yang diberikan kepada pasien.
Dalam melakukan tindakan keperawatan menggunakan 3 tahap
pendekatan, yaitu independen, dependen, interdependen. Tindakan
keperawatan secara independen adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau
tenaga kesehatan lainnya. Interdependen adalah tindakan keperawatan
yang menjelaskan suatu kegiatan dan memerlukan kerja sama dengan
tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, dan dokter.
Sedangkan dependen adalah tindakan yang berhubungan dengan
pelaksanaan rencana tindakan medis. Keterampilan yang harus dipunyai
perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan yaitu kognitif, sikap
dan psikomotor.
Dalam melakukan tindakan khususnya pada klien dengan rhinitis
vasomotor yang harus diperhatikan adalah pola nutrisi, pernafasan klien
serta melakukan pendidikan kesehatan pada klien.
e) Evaluasi Keperawatan
Menurut Doengoes, 2000 evaluasi adalah tingkatan intelektual
untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa
jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaannya
sudah berhasil dicapai. Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap
evaluasi adalah masalah dapat diatasi, masalah teratasi sebagian,
masalah belum teratasi atau timbul masalah baru. Evaluasi yang
dilakukan adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil.
30

Evaluasi proses adalah evaluasi yang harus dilaksanakan segera
setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan untuk membantu
keefektifitasan terhadap tindakan. Sedangkan evaluasi hasil adalah
evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan secara
keseluruhan sesuai dengan waktu yang ada pada tujuan.
Adapun evaluasi dari diagnosa keperawatan rhinitis vasomotor
secara teoritis adalah apakah klien dapat mengkonsumsi makanan
dengan baik, apakah klien dapat melakukan aktivitasnya secara
mandiri, apakah klien mampu mengungkapkan pemahaman tentang
penyakit rhinitis vasomotor.
BAB III
APLIKASI TEORI
Kasus 1
An. N usia 7 tahun. Datang ke rumah sakit, dengan keluhan bersin-
bersin, hidung tersumbat dan hidung terasa gatal. Awalnya pasien mengira hal
tersebut merupakan pilek biasa, tapi ternyata pileknya tidak sembuh-sembuh.
31

Ibunya mengatakan bahwa anaknya juga sering mengalami sulit tidur karena
sulit bernapas, dan tak jarang menganga ketika kesulitan bernapas. Dari
pemeriksaan fisik ketika di inspeksi kulit tampak berwarna kehitaman
dibawah kelopak mata bawah dan ada cairan menetes dari hidung. Ketika
dipalpasi An.N merasa nyeri karena ada inflamasi. Setelah dilakukan
pemeriksaan rongga hidung dengan spekulum didapatkan sekret hidung
jernih, membran mukosa edema, basah dan kebiru-biruan (boggy and bluish).
Dan dari hasil tes laboratorium (pemeriksaan sekret) terdapat sel eusinofil
meningkat > 3 %.
PENGKAJIAN
A. Identitas Anak
Nama : An. N
Umur : 7 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
BB : 25 kg
TB : 100 cm
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Alamat : -
Tanggal MRS : 1 Februari 2015 Jam : 08.00 WIB
Tanggal Pengkajian : 1 Februari 2015 Jam : 11.00 WIB
Nomor Register : 1234
Diagnosa Medik : Rhinitis Alergi
B. Identitas Penanggung Jawab
Nama : Ny. W
Umur : 25 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Alamat : -
Hubungan dengan klien : Ibu klien
C. Riwayat Kesehatan Klien
1. Keluhan Utama
32

Bersin-bersin, hidung tersumbat dan hidung terasa gatal.
2. Riwayat Kesehatan Sekarang
Klien datang ke rumah sakit dengan keluhan bersin-bersin, hidung
tersumbat dan hidung terasa gatal. Awalnya pasien mengira hal tersebut
merupakan pilek biasa, tapi ternyata pileknya tidak sembuh-sembuh.
Ibunya mengatakan bahwa anaknya juga sering mengalami sulit tidur
karena sulit bernapas, dan tak jarang menganga ketika kesulitan bernapas.
3. Riwayat Kesehatan Dahulu
Sebelumnya klien tidak pernah masuk RS, dan klien hanya mengalami flu
biasa.
4. Riwayat Kesehatan Keluarga
Dalam keluarga klien tidak ada yang mengalami penyakit keturunan dan
penyakit menular.
D. Riwayat Anak
1. Masa Pre – Natal
Selama kehamilan ibu 4 kali memeriksakan kandungannya ke Puskesmas
dan Dokter, mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali. Selama kehamilan
ibu tidak pernah mengalami penyakit yang menular atau penyakit lainnya.
2. Masa Intra – Natal
Proses persalinan klien secara normal (spontan) dengan bantuan bidan,
dengan umur kehamilan 37 minggu.
3. Masa Post – Natal
Klien lahir dalam keadaan normal, dengan BB ± 3200 gram dalam
keadaan sehat. Waktu lahir klien langsung menangis.
E. Pengetahuan Orang Tua
1. Tentang Makanan Sehat
Orang tua klien cukup mengetahui tentang makanan sehat dan gizi klien
baik dan berat badannya 25 kg, klien diberikan ASI sampai umur 2 bulan
saja dan dilanjutkan dengan PASI.
2. Tentang Personal Hygiene
33

Orang tua klien mengetahui tentang kebersihan, dilihat dari kebersihan
klien dan orang tuanya sendiri. Badan klien terlihat bersih, rambut klien
hitam lurus dan kelihatan bersih, kuku klien bersih dan tidak ada kotoran,
mulut klien tampak kelihatan bersih.
3. Imunisasi
Klien mendapat imunisasi, yaitu :
a. BCG : 1 kali
b. DPT : 3 kali
c. Campak : 1 kali
d. Polio : 3 kali
e. Hepatitis B : 2 kali
F. Pertumbuhan dan Perkembangan
Usia Pertumbuhan Perkembangan
7 tahun BB : 100 kg
PB : 25 cm
Sudah memiliki proporsi tubuh
seperti orang dewasa. Imajinasi
anak merupakan bagian yang
penting bagi perkembangannya
saat ini.
G. Pemeriksaan Fisik
1. Keadaan Umum
Penampilan : Klien tampak agak lemah.
Kesadaran : Composmentis
Vital Sign : TD : - RR : 27 kali / menit
Suhu : 37,4 º C Nadi : 95 kali / menit
BB : 25 kg TB : 100 cm
2. Kebersihan Anak
Klien kelihatan bersih, klien tidak dimandikan tetapi hanya diseka oleh
ibuya dan pakaian diganti oleh ibunya sehingga klien kelihatan bersih.
3. Suara Anak Waktu Menangis
Ketika klien mengangis terdengar suara yang kuat.
4. Keadaan Gizi Anak
Keadaan gizi anak baik ditandai dengan BB: 25 kg.
34

5. Aktivitas
Di rumah sakit klien berbaring ditempat tidur dan sesekali berpindah
posisi agar klien merasa nyaman, dan kadang klien digendong orang
tuanya.
6. Kepala dan Leher
Keadaan kepala tampak bersih, dan tidak ada luka atau lecet. Klien dapat
menggerakkan kepalanya kekiri dan kekanan. Tidak ada pembengkakan
kelenjar tyroid dan limfe.
7. Mata (Penglihatan)
Bentuk simetris, tidak ada kotoran mata, konjungtiva tidak anemis, fungsi
penglihatan baik karena klien tidak menggunakan alat bantu, tidak ada
peradangan dan pendarahan.
8. Telinga (Pendengaran)
Tidak terdapat serumen, fungsi pendengaran baik karena klien jika
dipanggil langsung memberi respon. Tidak ada peradangan dan
pendarahan.
9. Hidung (Penciuman)
Bentuk simetris namun sulit mencium karena hidung tersumbat.
10. Mulut (Pengecapan)
Tidak terlihat peradangan dan pendarahan pada mulut, fungsi pengecapan
baik, mukosa bibir edema, basah dan kebiru-biruan.
11. Dada (Pernafasan)
Bentuk dada simetris, tetapi ada gangguan dalam bernafas dan terdapat
secret cair dalam hidungnya dengan frekuensi nafas 27 x/menit.
12. Kulit
Terlihat bersih, tidak terdapat lesi maupun luka, turgor kulit baik (dapat
kembali dalam 2 detik), kulit klien teraba panas dengan temperatur 37,4 º
C.
13. Abdomen
Bentuk simetris, tidak ada luka dan peradangan, tidak ada kotoran yang
melekat pada kulit.
14. Ekstremitas Atas dan Bawah
Bentuk simetris, tidak ada luka maupun fraktur pada ekstremitas atas dan
bawah, terdapat keterbatasan gerak pada ekstremitas atas bagian dekstra
karena terpasang infuse RL 20 tetes/menit.
35

15. Genetalia
Klien berjenis kelamin perempuan dan tidak terpasang kateter.
H. Pola Makan dan Minum
Di rumah : Klien makan 3x sehari dengan menu nasi ayam dan klien suka
minum air putih dan susu.
Di RS : Klien makan bubur 3x sehari dan tidak bisa menghabiskannya,
klien minum hanya ½ gelas dari 1 gelas.
I. Pola Eliminasi
Di rumah : Klien BAB 1x/hari dengan konsistensi padat dan bau khas feses,
BAK klien 4-5x/hari berwarna kuning jernih dan berbau
amoniak.
Di RS : Klien BAB 1x dalam 2 hari dengan konsistensi padat dan berbau
khas feses. Dan klien BAK 2-3x/hari berwarna kuning jernih
dan berbau amoniak.
J. Terapi Yang Didapatkan di RS
Terapi medikamentosa yaitu anti histamine, dekongestan dan
kortikosteroid.
K. ANALISA DATA
No Data Subjektif & Objektif Etiologi Masalah
36

1 DS:
DO:
- Ibu klien mengatakan
bahwa anaknya sulit
bernafas dan hidungnya
tersumbat.
- Klien terlihat kesulitan
bernapas.
- Tanda – tanda vital :
N : 95 x/menit
RR : 27 x/menit
S : 37,4 °C
BB : 25 kg
TB : 100 cm
TD : -
Obstruksi saluran
napas
Ketidakefektifan
bersihan jalan
napas.
2 DS:
DO:
- Ibu klien mengatakan jika
anaknya hidungnya
tersumbat.
- Terdapat cairan menetes
dari hidung.
Berkurangnya
sensasi
penciuman.
Gangguan persepsi
sensori.
3 DS:
DO:
-Ibu klien mengatakan
anaknya juga sering
mengalami sulit tidur
karena sulit bernapas, dan
tak jarang menganga
ketika kesulitan bernapas.
- Kelopak mata bawah klien
berwarna kehitaman.
Penyumbatan
pada hidung
Gangguan pola
tidur
PRIORITAS DIAGNOSA
37

a. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
b. Gangguan persepsi sensori yang berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
c. Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan penyumbatan pada hidung.
INTERVENSI
NoTujuan/
Kriteria HasilIntervensi Rasional
1 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan jalan
napas menjadi
efektif.
Kriteria hasil:
jalan nafas
kembali
normal
terutama
hidung.
1. Kaji status
pernapasan
sekurangnya
setiap 4 jam.
2. Gunakan posisi
semi fowler dan
sangga lengan
pasien.
3. Bantu pasien
untuk
mengubah
posisi, batuk,
dan bernapas
dalam setiap 2
sampai 4 jam.
4. Isap sekresi
sesuai
keperluan.
1. Untuk mendeteksi
tanda awal bahaya.
2. Untuk membantu
bernapas.
3. Untuk membantu
mengeluarkan
sekresi dan
mempertahankan
patensi jalan napas.
4. Untuk menstimulasi
batuk dan
membersihkan jalan
napas.
2 Setelah
dilakukan
tindakan
1. Kaji
kemampuan
pasien untuk
1. Untuk menentukan
kondisi normal.
38

keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
peningkatan
persepsi
penciuman.
Kriteria hasil:
Sensasi
penciuman
klien kembali
normal.
mencium baud
an
dokumentasika
n temuan.
2. Yakinkan
pasien bahwa
kondisi tersebut
bersifat
sementara dan
sensasi
penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat
yang
diprogamkan
seperti anti
histamine.
4. Catat
karakteristik
drainase hidung
meliputi
jumlah, warna,
konsistensi dan
bau.
2. Untuk mengurangi
ansietas pasien.
3. Untuk meringankan
kongesti hidung.
4. Untuk mengkaji
perubahan kondisi
olfaktorius.
3 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
pasien tidak
menunjukkan
1. Segera buat
perubahan
apapun yang
mungkin untuk
mengakomodas
i pasien.
2. Rencanakan
jadwal
pemberian
pengobatan
1. Tindakan ini
mendorong istirahat
dan tidur.
2. Untuk
mmungkinkan
istirahat yang
39

gejala perilaku
yang berkaitan
dengan tidur
seperti
kegelisahan
Kriteria Hasil :
Klien dapat
tidur 9-10 jam
per hari.
disekitar jadwal
tidur pasien.
3. Buat rencana
detail untuk
member pasien
kesempatan
tidur 9 jam
tanpa
gangguan.
maksimal.
3. Tindakan ini
memberikan waktu
tidur tanpa
gangguan kepada
pasien.
IMPLEMENTASI
NoTanggal
dan jamPelaksanaan
Evaluasi
tindakan/respon klienParaf
1 02 February
2015, pukul
08.00 WIB
02 February
2015, pukul
08.10 WIB
02 February
2015, pukul
08.20 WIB
02 February
2015, pukul
08.30 WIB
1. Mengkaji status
pernapasan
sekurangnya
setiap 4 jam.
2. Menggunakan
posisi fowler dan
sangga lengan
pasien.
3. Membantu pasien
untuk mengubah
posisi, batuk dan
bernapas dalam
setiap 2 sampai 4
jam.
4. Mengisap sekresi
sesuai keperluan.
1. Status
pernapasan
klien berangsur
normal.
2. Klien lebih
nyaman
bernapas.
3. Klien lebih
stabil.
4. Jalan napas
klien hamper
normal.
2 02 February
2015, pukul
1. Mengkaji
kemampuan
1. Secara perlahan
klien mampu
40

13.00 WIB
02 February
2015, pukul
13.10 WIB
02 February
2015, pukul
13.20 WIB
02 February
2015, pukul
13.30WIB
pasien untuk
mencium bau dan
dokumentasikan
temuan.
2. Yakinkan pasien
bahwa kondisi
tersebut bersifat
sementara dan
sensasi
penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat
yang
diprogamkan
sesuai
antihistamin.
4. Catat
karakteristik
drainase hidung
meliputi jumlah,
warna,
konsistensi dan
bau.
mencium
kembali secara
normal.
2. Klien yakin
jika
penciumannya
bisa pulih.
3. Kongesti pada
hidung klien
berkurang.
4. Kondisi
penciuman
klien hampir
kembali
normal.
3 03 February
2015, pukul
08.00 WIB
03 February
2015, pukul
08.10 WIB
03 February
2015, pukul
1. Segera buat
perubahan
apapun yang
mungkin untuk
mengakomodasi
pasien.
2. Rencanakan
jadwal pemberian
pengobatan
disekitar jadwal
tidur pasien.
3. Buat rencana
detail untuk
1. Klien dapat
tidur dengan
nyaman jika
jauh dari
kegaduhan.
2. Klien lebih
nyenyak tidur.
3. Klien bisa tidur
dengan
41

08.20 WIB member pasien
kesempatan tidur
9 jam tanpa
gangguan.
nyaman.
EVALUASI
No Tanggal dan Jam Catatan Perkembangan Paraf
`1 03 February 2015,
pukul 16.00 WIB
S = Pasien mengatakan hidungnya
sudah tidak begitu tersumbat
setelah diberi obat.
O = Pasien terlihat tidak kesulitan
bernafas.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang
dan diberikan Health
Education.
2 03 February 2015,
pukul 16.05 WIB
S=Pasien mengatakan penciumannya
hampir normal.
O = Pasien sudah nampak ceria.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
3 03 February 2015,
pukul 16.10 WIB
S = Pasien mengatakan sudah bisa
tidur dengan nyaman.
O= Kelopak mata bawah pasien
sudah tidak kehitaman.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
42

Kasus 2
Ny. S berusia 30 tahun MRS tanggal 14 Februari 2015 dengan keluhan
hidung tersumbat kadang bergantian kanan dan kiri juga pilek sejak tahun yang
lalu serta berlangsung secara hilang timbul. Ny S juga mengatakan bahwa ia
bersin-bersin tapi tidak sering. Pileknya dirasakan agak kental dan bewarna
43

bening. Tidak ada rasa gatal di mata, hidung dan tenggorokan saat serangan. Ny
S juga mengatakan nafsu makan menurun saat serangan terjadi. Ia juga berkata
tidak bisa mencium jika serangan terjadi. Pada palpasi tidak ditemukan nyeri
tekan didaerah sinus. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan eosinofil tetapi
dalam jumlah sedikit dan tes kulit negative. Tanda- tanda vital = TD : 120/80,
Nadi : 86x/menit, RR : 22x/menit, suhu : 37 OC.
Pengkajian
a. Anamnesa
No.Reg : 2530
Ruang : Ratu
Tanggal MRS : 14-02-2015
Tanggal pengkajian: 14-02-2015 Jam : 08.00 WIB
Diagnosa medis : Rhinitis Vasomotor
IDENTITAS KLIEN
Nama : Ny. S
Umur : 30 tahun
Alamat : Suku minang.
Pendidikan : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
a) RIWAYAT KEPERAWATAN
Riwayat Sebelum Sakit :
Riwayat berat yang pernah di derita : Pernah pilek sejak tahun lalu.
Obat-obat yang biasa dikonsumsi : Obat-obat yang beli di warung.
Kebiasaan berobat :Bila sakit dibawa ke
puskesmas.
Alergi : Tidak ada alergi.
Kebiasaan merokok/alcohol : Tidak pernah.
Riwayat Penyakit Sekarang :
Keluhan utama : Klien mengatakan hidung
tersumbat kadang bergantian kanan
dan kiri juga pilek sejak tahun yang
lalu serta berlangsung secara hilang
44

timbul. Ny S juga mengatakan
bahwa ia bersin-bersin tapi tidak
sering.
Upaya yang telah dilakukan : Tanggal 13 Februari 2015 pukul
20.30 memberi minyak kayu putih
disekitar hidungnya.
Terapi/operasi yang dilakukan : Belum pernah melakukan operasi
apapun.
Riwayat penyakit keluarga : Klien mengatakan bahwa tidak
ada keluarga yang mempunyai
penyakit yang sama.
Riwayat Kesehatan Lingkungan : Ny. T mengatakan lingkungan
disekitar rumahnya berasap.
Riwayat Kesehatan Lainnya : Ny. T mengatakan tidak
mempunyai alergi baik makanan,
obat maupun udara.
Alat bantu yang dipakai : Tidak ada alat bantu yang
digunakan.
b) OBSERVASI DAN PEMERIKSAAN FISIK
Keadaan umum : Ny. T cemas dan composmentris.
Tanda-tanda vital, TB dan BB : Suhu : 37,5oC, Nadi= 86x/menit,
TD=120/80, RR= 22x/menit,
TB=155 cm, BB=50 kg.
Body Systems :
- Pernafasan (B1: Breathing)
Hidung : Hidung simetris, terdapat
sumbatan dan secret.
Trakea : Tidak ada pembesaran kelenjar
tyroid.
Suara nafas tambahan : Tidak ada wheezing, ronchi,
rales dan crackles.
Bentuk dada : Simetris, suara nafas sonor dan
tidak ada kelainan dada.
- Cardiovaskuler (B2: Bleeding)
45

Suara jantung :Normal, tidak ada kelainan
cardiovaskuler.
Edema : Tidak ada oedema.
- Persyarafan (B3 : Brain)
Composmentris.
Kepala dan wajah :
Mata : Sklera putih, conjungtiva pucat.
Leher : Tidak ada pembesaran tyroid.
Persepsi sensori :
Pendengaran :Kiri dan kanan tidak ada
kelainan (normal).
Penciuman : Penciuman menurun karena
hidung tersumbat.
Pengecapan : Tidak ada kelainan, bisa
merasakan semua rasa manis,
asin dan pahit.
Penglihatan : Kiri dan kanan tidak ada
kelainan (normal).
Perabaan : Tidak ada kelainan.
- Perkemihan-Eliminasi Urin (B4: Bladder)
Produksi urine : 600 ml.
Frekuensi : 5x/hari.
Warna : Lebih pekat..
- Pencernaan-Eliminasi Alvi (B5: Bowel)
Mulut dan tenggorokan : Mukosa bibir kering.
Abdomen
I = Pernafasan dangkal, klien gelisah, dada simetris.
P= Tympani.
P= Tidak adanya pembengkakan di abdomen atas atau
quadran kanan atas, tidak ada nyeri tekan epigastrum.
A= Peristaltik 5-12x/menit
BAB : 1x/1 hari dengan konsistensi
normal.
46

- Tulang-Otot-Integumen (B6: Bone)
Kemampuan pergerakan sendi : Bebas dan tidak ada kelainan
sendi.
Extremitas : Bagian atas dan bawah tidak
ada kelainan.
Kulit : Warna kulit kepucatan, turgor
cukup, akral hangat.
- Sistem Endokrin
Terapi hormone : Tidak ada terapi hormone.
Riwayat perkembangan fisik :Kekeringan kulit, kelemahan
- Sistem Reproduksi
Perempuan : Bentuk kelamin normal,
payudara simetris.
c) POLA AKTIVITAS ( Di Rumah dan RS )
- Makan :
Rumah Rumah Sakit
Frekuensi 3x 3x
Jenis menu Semua makananRendah lemak dan
serat
Porsi 1 porsi habis ½ porsi
Yang disukai Semua disukai Disukai
Yang tidak disukai Tidak ada Tidak ada
Pantangan Tidak ada pantangan Tidak ada pantangan
Alergi Tidak ada alergi Tidak ada alergi
Lain-lain - -
- Minum :
Rumah Rumah Sakit
Frekuensi 10x 5x
Jenis minuman Air putih biasa, es Air putih biasa
Jumlah (Lt/gelas) 1 liter ½ liter
Yang disukai Semua disukai Disukai
Yang tidak disukai Tidak ada Tidak ada
Pantangan Tidak ada pantangan Tidak ada pantangan
47

Alergi Tidak ada alergi Tidak ada alergi
Lain-lain - -
- Kebersihan diri :
Rumah Rumah Sakit
Mandi 2x -
Keramas Setiap hari -
Sikat gigi 2x setiap mandi -
Memotong kuku 1 minggu sekali -
Ganti pakaian Sehari 2x -
Lain-lain - -
- Istirahat dan Aktivitas :
Istirahat Tidur
Rumah Rumah Sakit
Tidur SiangLama : -
Jam : -
Lama : 2 jam
Jam : 13.00-15.00
Tidur MalamLama : 6 jam
Jam: 22.00-04.00
Lama : 8 jam
Jam : 21.00-05.00
Gangguan tidur -
Sering terbangun
karena nyeri pada
perut bagian kanan
atas
Aktivitas
Rumah Rumah Sakit
Aktivitas sehari-hariLama : 8 jam
Jam : 06.00-14.00
Lama : -
Jam : -
Jenis aktivitas
Memasak,
membersihkan rumah
dan mengasuh cucu
Pasien hanya
berbaring tidur
Tingkat
ketergantungan
Semua aktivitas
dilakukan sendiriDi bantu
d) PSIKOSOSIAL SPIRITUAL
48

Sosial/Interaksi :
- Hubungan dengan klien : Tidak kenal.
- Dukungan keluarga : Aktif.
- Dukungan kelompok/masyarakat : Aktif.
- Reaksi saat interaksi : Kooperatif.
- Konflik yang terjadi terhadap : Tidak ada.
Spritual :
- Konsep tentang penguasaan kehidupan : Allah SWT.
- Sumber kekuatan saat sakit : Allah SWT.
- Ritual agama yang diharapkan saat ini : Baca kitab suci.
- Sarana ritual agama : Lewat ibadah.
- Upaya kesehatan yang bertentangan agama : Tidak ada.
- Keyakinan bahwa Tuhan akan menolong : Ya.
- Keyakinan penyakit dapat disembuhkan : Ya.
- Persepsi terhadap penyebab penyakit : Cobaan/peringatan
e) PEMERIKSAAN PENUNJANG.
- Laboratorium :
Ditemukan eosinofil dalam jumlah yang sedikit dan tes kulit
negative.
f) TERAPI
Tidak ada.
ANALISA DATA
No Data Subjektif & Objektif Etiologi Masalah
49

1 DS:
DO:
- Klien mengatakan bahwa
hidungnya tersumbat
kadang bergantian kanan
dan kiri juga pilek sejak
tahun yang lalu serta
berlangsung secara hilang
timbul
- Klien terlihat kesulitan
bernapas.
- Tanda – tanda vital :
N : 86 x/menit
RR : 22 x/menit
S : 37,5 °C
Obstruksi saluran
napas
Ketidakefektifan
bersihan jalan
napas.
2 DS:
DO:
- Klien mengatakan sulit
mencium jika terjadi
serangan.
- Ada cairan keluar dari
hidung..
Berkurangnya
sensasi
penciuman.
3 DS:
DO:
- Klien mengatakan nafsu
makan menurun jika terjadi
serangan.
- Klien lemah.
Anoreksia Ketidakseimbangan
nutrisi kurang dari
kebutuhan tubuh.
Prioritas Diagnosa
a. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
b. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
c. Ketidakseimbangan nutria kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan
dengan anoreksia.
50

INTERVENSI
NoTujuan/
Kriteria HasilIntervensi Rasional
1 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan jalan
napas menjadi
efektif.
Kriteria hasil:
jalan nafas
kembali
normal
terutama
hidung.
1. Kaji status
pernapasan
sekurangnya
setiap 4 jam.
2. Gunakan posisi
semi fowler
dan sangga
lengan pasien.
3. Bantu pasien
untuk
mengubah
posisi, batuk,
dan bernapas
dalam setiap 2
sampai 4 jam.
4. Isap sekresi
sesuai
keperluan.
1. Untuk mendeteksi
tanda awal bahaya.
2. Untuk membantu
bernapas.
3. Untuk membantu
mengeluarkan
sekresi dan
mempertahankan
patensi jalan napas.
4. Untuk menstimulasi
batuk dan
membersihkan jalan
napas.
2 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
peningkatan
persepsi
1. Kaji
kemampuan
pasien untuk
mencium baud
an
dokumentasika
n temuan.
2. Yakinkan
pasien bahwa
kondisi tersebut
1. Untuk menentukan
kondisi normal.
2. Untuk mengurangi
ansietas pasien.
51

penciuman.
Kriteria hasil:
Sensasi
penciuman
klien kembali
normal.
bersifat
sementara dan
sensasi
penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat
yang
diprogamkan
seperti anti
histamine.
4. Catat
karakteristik
drainase hidung
meliputi
jumlah, warna,
konsistensi dan
bau.
3. Untuk meringankan
kongesti hidung.
4. Untuk mengkaji
perubahan kondisi
olfaktorius.
3 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
pasien
mengkonsums
i minimal
3000 kalori.
Kriteria Hasil:
Nafsu makan
klien
bertambah.
1. Observasi dan
catat asupan
pasien (cair
dan padat).
2. Tentukan
makanan
kesukaan
pasien.
3. Ciptakan
lingkungan
yang
menyenangkan
pada waktu
makan.
1. Untuk mengkaji
zat gizi yang
dikonsumsi dan
suplemen yang
diperlukan.
2. Untuk
meningkatkan
nafsu makan klien.
3. Untuk
meningkatkan
nafsu makan klien.
52

4. Hindari
bertanya
apakah pasien
lapar atau ingin
makan.
4. Sikap positif dan
tidak
membebankan
dapt menghindari
konfrontasi
dengan pasien.
IMPLEMENTASI
NoTanggal
dan jamPelaksanaan
Evaluasi
tindakan/respon
klien
Paraf
1 15
February
2015,
pukul
08.00
WIB
15
February
2015,
pukul
08.10
WIB
15
February
2015,
pukul
08.20
WIB
15
February
1. Mengkaji status
pernapasan
sekurangnya setiap 4
jam.
2. Menggunakan posisi
fowler dan sangga
lengan pasien.
3. Membantu pasien
untuk mengubah
posisi, batuk dan
bernapas dalam setiap
2 sampai 4 jam.
4. Mengisap sekresi
1. Status
pernapasan
klien
berangsur
normal.
2. Klien lebih
nyaman
bernapas.
3. Klien lebih
stabil.
4. Jalan napas
klien hamper
53

2015,
pukul
08.30
WIB
sesuai keperluan. normal.
2 15
February
2015,
pukul
13.00
WIB
15
February
2015,
pukul
13.10
WIB
15
February
2015,
pukul
13.20
WIB
15
February
2015,
pukul
13.30
WIB
1. Mengkaji kemampuan
pasien untuk mencium
bau dan
dokumentasikan
temuan.
2. Yakinkan pasien
bahwa kondisi tersebut
bersifat sementara dan
sensasi penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat yang
diprogamkan sesuai
antihistamin.
4. Catat karakteristik
drainase hidung
meliputi jumlah,
warna, konsistensi dan
bau.
1. Secara
perlahan klien
mampu
mencium
kembali
secara normal.
2. Klien yakin
jika
penciumannya
bisa pulih.
3. Kongesti pada
hidung klien
berkurang.
4. Kondisi
penciuman
klien hampir
kembali
normal.
3 16
February
2015,
pukul
08.00
1. Mengobservasi dan
catat asupan pasien (cair
dan padat).
1. Asupan
makan dan
minum klien
hampir stabil.
54

WIB
16
February
2015,
pukul
08.10
WIB
16
February
2015,
pukul
08.20
WIB
16
February
2015,
pukul
08.30
WIB
2. Menentukan makanan
kesukaan pasien.
3. Menciptakan
lingkungan yang
menyenangkan pada
waktu makan.
4. Menghindari bertanya
apakah pasien lapar atau
ingin makan.
2. Klien lebih
nafsu makan.
3. Klien nyaman
saat makan
dengan
lingkungan
yang indah.
4. Klien makan
dengan baik.
EVALUASI
No Tanggal dan Jam Catatan Perkembangan Paraf
`1 16 February 2015,
pukul 16.00 WIB
S = Pasien mengatakan hidungnya
sudah tidak begitu tersumbat
setelah diberi obat.
O = Pasien terlihat tidak kesulitan
bernafas.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang
dan diberikan Health
Education.
55

2 16 February 2015,
pukul 16.05 WIB
S=Pasien mengatakan penciumannya
hampir kembali normal.
O = Pasien sudah nampak ceria.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
3 16 February 2015,
pukul 16.10 WIB
S = Pasien mengatakan sudah ada
nafsu makan kembali.
O= Pasien lebih tenang.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
Kasus 3
56

An. E berumur 5 tahun datang MRS bersama ibunya tanggal 18 Februari
2015 dengan keluhan bersin bersin secara tiba tiba, hidung tersumbat yang tidak
sembuh sembuh selama 1 minggu. Ayahnya berkata semenjak itu klien sulit
mencium bau dan sulit tidur karena hidungnya tersumbat. Setelah diperiksa,
dibawah kelopak mata kehitaman dan pada pemeriksaan darah tepi tidak
terdapat eosinofil yang tidak meningkat. Tanda-tanda vital = Suhu : 36oC, Nadi :
90x/menit, RR: 22x/menit, BB=25 kg, TB=100 cm.
PENGKAJIAN
A. Identitas Anak
Nama : An. E
Umur : 5 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
BB : 25 kg
TB : 100 cm
Pendidikan : Taman kanak-Kanak (TK)
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Alamat : -
Tanggal MRS : 18 Februari 2015 Jam : 08.00 WIB
Tanggal Pengkajian : 18 Februari 2015 Jam : 11.00 WIB
Nomor Register : 1234
Diagnosa Medik : Rhinitis Akut
B. Identitas Penanggung Jawab
Nama : Ny. W
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia
Alamat : -
Hubungan dengan klien : Ibu klien
C. Riwayat Kesehatan Klien
57

1. Keluhan Utama
Bersin-bersin, hidung tersumbat yang datang tiba-tiba.
2. Riwayat Kesehatan Sekarang
Klien datang ke rumah sakit dengan keluhan bersin-bersin, hidung
tersumbat yang datang tiba-tiba. Ibunya mengatakan bahwa anaknya juga
sering mengalami sulit tidur karena sulit bernapas.
3. Riwayat Kesehatan Dahulu
Sebelumnya klien tidak pernah masuk RS.
5. Riwayat Kesehatan Keluarga
Dalam keluarga klien tidak ada yang mengalami penyakit keturunan dan
penyakit menular.
D. Riwayat Anak
1. Masa Pre – Natal
Selama kehamilan ibu 4 kali memeriksakan kandungannya ke Puskesmas
dan Dokter, mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali. Selama kehamilan
ibu tidak pernah mengalami penyakit yang menular atau penyakit lainnya.
2. Masa Intra – Natal
Proses persalinan klien secara normal (spontan) dengan bantuan bidan,
dengan umur kehamilan 37 minggu.
3. Masa Post – Natal
Klien lahir dalam keadaan normal, dengan BB ± 3200 gram dalam
keadaan sehat. Waktu lahir klien langsung menangis.
E. Pengetahuan Orang Tua
1. Tentang Makanan Sehat
Orang tua klien cukup mengetahui tentang makanan sehat dan gizi klien
baik dan berat badannya 25 kg, klien diberikan ASI sampai umur 2 bulan
saja dan dilanjutkan dengan PASI.
2. Tentang Personal Hygiene
58

Orang tua klien mengetahui tentang kebersihan, dilihat dari kebersihan
klien dan orang tuanya sendiri. Badan klien terlihat bersih, rambut klien
hitam lurus dan kelihatan bersih, kuku klien bersih dan tidak ada kotoran,
mulut klien tampak kelihatan bersih.
3. Imunisasi
Klien mendapat imunisasi, yaitu :
f. BCG : 1 kali
g. DPT : 3 kali
h. Campak : 1 kali
i. Polio : 3 kali
j. Hepatitis B : 2 kali
F. Pertumbuhan dan Perkembangan
Usia Pertumbuhan Perkembangan
7 tahun BB : 100 kg
PB : 25 cm
Sudah memiliki proporsi tubuh
seperti orang dewasa. Imajinasi
anak merupakan bagian yang
penting bagi perkembangannya
saat ini.
G. Pemeriksaan Fisik
1. Keadaan Umum
Penampilan : Klien tampak agak lemah.
Kesadaran : Composmentis
Vital Sign : TD : - RR : 22 kali / menit
Suhu : 36 º C Nadi : 90 kali / menit
BB : 25 kg TB : 100 cm
2. Kebersihan Anak
Klien kelihatan bersih, klien tidak dimandikan tetapi hanya diseka oleh
ibuya dan pakaian diganti oleh ibu dan ayahnya sehingga klien kelihatan
bersih.
3. Suara Anak Waktu Menangis
Ketika klien menangis terdengar suara yang kuat.
4. Keadaan Gizi Anak
59

Keadaan gizi anak baik ditandai dengan BB: 25 kg.
5. Aktivitas
Di rumah sakit klien berbaring ditempat tidur dan sesekali berpindah
posisi agar klien merasa nyaman, dan kadang klien digendong orang
tuanya.
6. Kepala dan Leher
Keadaan kepala tampak bersih, dan tidak ada luka atau lecet. Klien dapat
menggerakkan kepalanya kekiri dan kekanan. Tidak ada pembengkakan
kelenjar tyroid dan limfe.
7. Mata (Penglihatan)
Bentuk simetris, tidak ada kotoran mata, konjungtiva tidak anemis, fungsi
penglihatan baik karena klien tidak menggunakan alat bantu, tidak ada
peradangan dan pendarahan.
8. Telinga (Pendengaran)
Tidak terdapat serumen, fungsi pendengaran baik karena klien jika
dipanggil langsung memberi respon. Tidak ada peradangan dan
pendarahan.
9. Hidung (Penciuman)
Bentuk simetris namun sulit mencium karena hidung tersumbat.
10. Mulut (Pengecapan)
Tidak terlihat peradangan dan pendarahan pada mulut, fungsi pengecapan
baik, mukosa bibir edema, basah dan kebiru-biruan.
11. Dada (Pernafasan)
Bentuk dada simetris, tetapi ada gangguan dalam bernafas dan terdapat
secret cair dalam hidungnya dengan frekuensi nafas 27 x/menit.
12. Kulit
Terlihat bersih, tidak terdapat lesi maupun luka, turgor kulit baik (dapat
kembali dalam 2 detik).
13. Abdomen
Bentuk simetris, tidak ada luka dan peradangan, tidak ada kotoran yang
melekat pada kulit.
14. Ekstremitas Atas dan Bawah
Bentuk simetris, tidak ada luka maupun fraktur pada ekstremitas atas dan
bawah, terdapat keterbatasan gerak pada ekstremitas atas bagian dekstra
karena terpasang infuse RL 20 tetes/menit.
15. Genetalia
60

Klien berjenis kelamin perempuan dan tidak terpasang kateter.
H. Pola Makan dan Minum
Di rumah : Klien makan 3x sehari dengan menu nasi ayam dan klien suka
minum air putih dan susu.
Di RS : Klien makan bubur 3x sehari dan tidak bisa menghabiskannya,
klien minum hanya ½ gelas dari 1 gelas.
I. Pola Eliminasi
Di rumah : Klien BAB 1x/hari dengan konsistensi padat dan bau khas feses,
BAK klien 4-5x/hari berwarna kuning jernih dan berbau
amoniak.
Di RS : Klien BAB 1x dalam 2 hari dengan konsistensi padat dan berbau
khas feses. Dan klien BAK 2-3x/hari berwarna kuning jernih
dan berbau amoniak.
J. Terapi Yang Didapatkan di RS
Terapi medikamentosa yaitu anti histamine, dekongestan dan
kortikosteroid.
K. ANALISA DATA
No Data Subjektif & Objektif Etiologi Masalah
1 DS:
DO:
- Ibu klien mengatakan
bahwa anaknya sulit
bernafas dan hidungnya
tersumbat.
- Klien terlihat kesulitan
bernapas.
- Tanda – tanda vital :
N : 90 x/menit
RR : 22 x/menit
S : 36 °C
BB : 25 kg
TB : 100 cm
Obstruksi saluran
napas
Ketidakefektifan
bersihan jalan
napas.
61

TD : -
2 DS:
DO:
- Ibu klien mengatakan jika
anakya sulit mencium bau
sejak hidungnya tersumbat.
- Ada cairan keluar dari
hidung
Berkurangnya
sensasi
penciuman
Gangguan persepsi
sensori
3 DS:
DO:
-Ibu klien mengatakan
anaknya juga sering
mengalami sulit tidur
karena sulit bernapas.
- Kelopak mata bawah klien
berwarna kehitaman.
Penyumbatan
pada hidung
Gangguan pola
tidur
PRIORITAS DIAGNOSA
a. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan obstruksi
saluran napas.
b. Gangguan persepsi sensori yang berhubungan dengan berkurangnya sensasi
penciuman.
c. Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan penyumbatan pada hidung.
INTERVENSI
NoTujuan/
Kriteria HasilIntervensi Rasional
62

1 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan jalan
napas menjadi
efektif.
Kriteria hasil:
jalan nafas
kembali
normal
terutama
hidung.
1. Kaji status
pernapasan
sekurangnya
setiap 4 jam.
2. Gunakan posisi
semi fowler
dan sangga
lengan pasien.
3. Bantu pasien
untuk
mengubah
posisi, batuk,
dan bernapas
dalam setiap 2
sampai 4 jam.
4. Isap sekresi
sesuai
keperluan.
1. Untuk mendeteksi
tanda awal bahaya.
2. Untuk membantu
bernapas.
3. Untuk membantu
mengeluarkan
sekresi dan
mempertahankan
patensi jalan napas.
4. Untuk menstimulasi
batuk dan
membersihkan jalan
napas.
2 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 3x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
peningkatan
persepsi
penciuman.
Kriteria hasil:
Sensasi
penciuman
klien kembali
1. Kaji
kemampuan
pasien untuk
mencium baud
an
dokumentasika
n temuan.
2. Yakinkan
pasien bahwa
kondisi
tersebut
bersifat
sementara dan
sensasi
1. Untuk menentukan
kondisi normal.
2. Untuk mengurangi
ansietas pasien.
63

normal. penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat
yang
diprogamkan
seperti anti
histamine.
4. Catat
karakteristik
drainase
hidung
meliputi
jumlah, warna,
konsistensi dan
bau.
3. Untuk meringankan
kongesti hidung.
4. Untuk mengkaji
perubahan kondisi
olfaktorius.
3 Setelah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2x24
jam dengan
tujuan untuk
melaporkan
pasien tidak
menunjukkan
gejala perilaku
yang berkaitan
dengan tidur
seperti
kegelisahan
Kriteria Hasil :
Klien dapat
tidur 9-10 jam
per hari.
1. Segera buat
perubahan
apapun yang
mungkin untuk
mengakomodas
i pasien.
2. Rencanakan
jadwal
pemberian
pengobatan
disekitar
jadwal tidur
pasien.
3. Buat rencana
detail untuk
member pasien
kesempatan
tidur 9 jam
tanpa
1. Tindakan ini
mendorong istirahat
dan tidur.
2. Untuk
mmungkinkan
istirahat yang
maksimal.
3. Tindakan ini
memberikan waktu
tidur tanpa
gangguan kepada
pasien.
64

gangguan.
IMPLEMENTASI
NoTanggal
dan jamPelaksanaan
Evaluasi
tindakan/respon
klien
Paraf
1 19 February
2015, pukul
08.00 WIB
19 February
2015, pukul
08.10 WIB
19 February
2015, pukul
08.20 WIB
19 February
2015, pukul
08.30 WIB
1. Mengkaji status
pernapasan
sekurangnya
setiap 4 jam.
2. Menggunakan
posisi fowler dan
sangga lengan
pasien.
3. Membantu pasien
untuk mengubah
posisi, batuk dan
bernapas dalam
setiap 2 sampai 4
jam.
4. Mengisap sekresi
sesuai keperluan.
1. Status
pernapasan
klien berangsur
normal.
2. Klien lebih
nyaman
bernapas.
3. Klien lebih
stabil.
4. Jalan napas
klien hamper
normal.
2 19 February
2015, pukul
13.00 WIB
19 February
2015, pukul
13.10 WIB
1. Mengkaji
kemampuan
pasien untuk
mencium bau dan
dokumentasikan
temuan.
2. Yakinkan pasien
bahwa kondisi
tersebut bersifat
sementara dan
1. Secara
perlahan klien
mampu
mencium
kembali secara
normal.
2. Klien yakin
jika
penciumannya
65

19 February
2015, pukul
13.20 WIB
19 February
2015, pukul
13.30WIB
sensasi
penciumannya
akan pulih.
3. Berikan obat yang
diprogamkan
sesuai
antihistamin.
4. Catat karakteristik
drainase hidung
meliputi jumlah,
warna, konsistensi
dan bau.
bisa pulih.
3. Kongesti pada
hidung klien
berkurang.
4. Kondisi
penciuman
klien hampir
kembali
normal.
3 20 February
2015, pukul
08.00 WIB
20 February
2015, pukul
08.10 WIB
20 February
2015, pukul
08.20 WIB
1. Segera buat
perubahan apapun
yang mungkin
untuk
mengakomodasi
pasien.
2. Rencanakan
jadwal pemberian
pengobatan
disekitar jadwal
tidur pasien.
3. Buat rencana detail
untuk member
pasien kesempatan
tidur 9 jam tanpa
gangguan.
1. Klien dapat
tidur dengan
nyaman jika
jauh dari
kegaduhan.
2. Klien lebih
nyenyak tidur.
3. Klien bisa tidur
dengan
nyaman.
EVALUASI
No Tanggal dan Jam Catatan Perkembangan Paraf
`1 20 February 2015,
pukul 16.00 WIB
S = Pasien mengatakan hidungnya
sudah tidak begitu tersumbat
66

setelah diberi obat.
O = Pasien terlihat tidak kesulitan
bernafas.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang
dan diberikan Health
Education.
2 20 February 2015,
pukul 16.05 WIB
S=Pasien mengatakan penciumannya
hampir kembali normal.
O = Pasien sudah nampak ceria.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
3 20 February 2015,
pukul 16.10 WIB
S = Pasien mengatakan sudah bisa
tidur dengan nyaman.
O= Kelopak mata bawah pasien
sudah tidak kehitaman.
A = Masalah teratasi.
P = Pasien diperbolehkan pulang dan
diberikan Health Education.
BAB IV
PEMBAHASAN
Rhinitis alergi adalah penyakit peradangan yang disebabkan oleh reaksi alergi
pada pasien-pasien yang memiliki atopi, yang sebelumnya sudah tersensitisasi
atau terpapar dengan allergen (zat/materi yang menyebabkan timbulnya alergi)
67

yang sama serta meliputi mekanisme pelepasan mediator kimia ketika terjadi
paparan ulangan dengan allergen yang serupa. Menurut WHO ARIA tahun 2001
rhinitis alergi adalah kelainan pada hidung degan gejala bersin-bersin, rinore,
rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar allergen yang
diperantarai oleh IgE.
Stimulasi pada reseptor H1 di ujung saraf sensoris menyebabkan gejala
bersin-bersin dan gatal pada hidung. Gejala-gejala tersebut timbul beberapa saat
setelah terpapar allergen. Fase ini disebut respon fase cepat dengan histamine
sebagai mediator utama sehingga preparat anti histamine efektif untuk mengatasi
gejala. Gejala dapat berlanjut sampai 6 – 8 jam kemudian yang timbul akibat
aktivitas berbagai mediator, tetapi histamine bukan pemegang peran utama. Fase
ini disebut respon fase lambat dengan gejala yang menonjol terutama adalah
obstruksi hidung. Pada fase ini selain factor spesifik (allergen), iritasi oleh factor
non spesifik dapat memperberat gejala seperti asap rokok, bau yang merangsang,
perubahan cuaca dan kelembapan yang tinggi.
Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang,
pasien didiagnosis menderita rhinitis alergi. Berdasarkan anamnesa, pasien
mengeluhkan keluhan pilek tidak sembuh-sembuh dan memberat sudah 1 bulan
ini. Pasien sering bersin-bersin dan hidung dirasakan tersumbat, dan keluar ingus
cair. Pasien juga mengeluh hidung terasa gatal dan kesulitan tidur karena hidung
tersumbat. Setelah dilakukan pemeriksaan rongga hidung dengan spekulum
didapatkan sekret hidung jernih, membran mukosa edema, basah dan kebiru-
biruan (boggy and bluish). Dan dari hasil tes laboratorium (pemeriksaan sekret)
terdapat sel eusinofil meningkat > 3 %.
Pada pasien ini ditemukan gejala allergic shiner yaitu adanya bayangan gelap
di daerah bawah mata yang terjadi karena stasis vena sekunder akibat obstruksi
hidung. Terapi yang paling ideal adalah dengan menghindari kontak dengan
allergen penyebabnya (avoidance) dan eliminasi. Pengobatan imunoterapi
diberikan pada alergi inhalan dengan gejala yang berat dan sudah berlangsung
lama serta pengobatan lain tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan dari
imunoterapi adalah pembentukan IgG blocking antibody dan penurunan IgE.
Pada kasus 2, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta
pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis menderita rhinitis vasomotor.
Berdasarkan anamnesa, pasien mengeluhkan dengan keluhan hidung tersumbat
kadang bergantian kanan dan kiri juga pilek sejak tahun yang lalu serta
berlangsung secara hilang timbul. Ny S juga mengatakan bahwa ia bersin-bersin
tapi tidak sering. Pileknya dirasakan agak kental dan bewarna bening. Tidak ada
68

rasa gatal di mata, hidung dan tenggorokan saat serangan. Ny S juga mengatakan
sulit tidur saat serangan terjadi. Ia juga berkata cemas akan penyakitnya tidak
tahu akan penanganannya selain memberi minyak kayu putih disekitar
hidungnya. Pada palpasi tidak ditemukan nyeri tekan didaerah sinus. Pada
pemeriksaan laboratorium ditemukan eosinofil tetapi dalam jumlah sedikit.
Pada kasus 3, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta
pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis menderita rhinitis akut. Berdasarkan
anamnesa, pasien mengeluhkan dengan keluhan bersin bersin secara tiba tiba,
hidung tersumbat yang tidak sembuh sembuh selama 1 minggu. Ayahnya berkata
semenjak itu klien tidak nafsu makan dan sulit tidur karena hidungnya tersumbat.
Setelah diperiksa, dibawah kelopak mata kehitaman dan pada pemeriksaan darah
tepi tidak terdapat eosinofil yang tidak meningkat.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rhinitis adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin,
rhinore, rasa gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen
yang diperantari oleh IgE.
69

Rinitis alergi secara umum disebabkan oleh interaksi dari pasien yang
secara genetik memiliki potensi alergi dengan lingkungan. Peran lingkungan
dalam dalam rinitis alergi yaitu alergen, yang terdapat di seluruh lingkungan,
terpapar dan merangsang respon imun yang secara genetik telah memiliki
kecenderungan alergi.
Tanda dan gejala rinitis adalah bersin-bersin, kongesti nasal, mengeluarkan
sekresi hidung yang berlebih (rinore), timbulnya rasa gatal pada: hidung,
palatum, faring, serta telinga, mata yang gatal dan kemerahan, serta
keluarnya air mata dapat juga terjadi. Sehingga menyebabkan rasa yang tidak
enak. Pada penderita rinitis yang khas datang dengan penyumbatan hidung
bilateral akibat dari edema basah membran mukosa. Seringkali, mukosa yang
berlebih ditumpuk pada dasar hidung, membran mukosa berwarna kebiruan
dan agak pucat. Dan menyebabkan gejala sistemik seperti malaise, gelisah,
dan selera makan berkurang, nyeri kepala, suara hidung.
Pemeriksaan diagnostic dapat dilakukan dengan cara in vitro dan in
vivo. Terapi medikamentosa yaitu anti histamin, dekongestan dan
kortikosteroid.
B. Saran
Sebaiknya kita perlu mengetahui tentang penyakit rhinitis agar kita
dapat mencegah hal itu timbul dalam lingkungan kita. Penulis juga menyadari
bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu
penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca
untuk menyempurnakan penulisan makalah berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Price, Sylvia. 2005. Patofisiologis : Konsep Klinis Proses-proses Penyakit. Jakarta :
EGC
Brunner & Suddart. 2001. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta: EGC
70

Soepardi, Efianty Arsyad,dkk. 2010. Buku Ajar Ilmu Kesehatan THT, Kepala &
Leher edisi 6. Jakarta : FKUI
Wilkinson, Judith M. 2012. Buku Saku Diagnosis Keperawatan. Jakarta : EGC.
Van den Broek, Dr. 2007. Buku Saku Ilmu Kesehatan Tenggorok, Hidung dan
Telinga. Jakarta : EGC
Mangunkusumo. E, Rifki. N. 2002. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung
Tenggorok Kepala Leher, Edisi ke-5. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
71