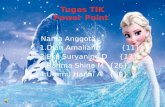Bab 1
-
Upload
choirun-nisa -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
description
Transcript of Bab 1
TUGAS TERSTRUKTUR
MATA KULIAH : MANAJEMEN DAS
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAS DAN
MANAJEMEN DAS TERINTEGRASI
Oleh:
Nama : Choirun Nisa’
Nim : 125040200111015
Kelas : C
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
MINAT SUMBER DAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015
BAB 1
Potensi dan Manfaat Sumberdaya Alam bagi Masyarakat
Faktor alam adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumberdaya alam merupakan semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam adalah seluruh bentang lahan (termasuk ruang publik dalam skala luas maupun semua daya-daya alam di dalamnya, beserta seluruh komoditi yang dihasilkan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
Berbagai sumber daya alam telah tersedia di Indonesia dengan umlah yang sangat melimpah. Dari mulai sumberdaya hutan, tanah/lahan, air, laut, dan mineral. Sumber daya alam memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Tanpa sumberdaya alam tentu manusia tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan aktiviasnya. Gambaran tentang fungsi dari sumberdaya alam tersebut antara lain:
1. Sumberdaya HutanHutan memiliki fungsi yang beragam, misalnya sebagai penyedia kayu, sumber
pangan, dan obat-obatan untuk kini dan masa depan. Melindungi tanah dari erosi; habitat berbagai satwa; pengatur tata air; pengatur keadaan iklim;fungsi ilmiah dan edukatif serta berfungsi sebagai rekreasi dalam hal wisata alam.
2. Sumberdaya AirAir memiliki manfaat yang besar dalamkehidupan manusia maupun makhluk lainnya.
Manfaat secara langsung air adalah sebagai air minum, mandi dan mencuci; sebagai sumber energi; tempat hidup berbagai biota air; prasarana transportasi; salah satu komponen pengontrol suhu udara; bahan pendingin mesin, dan lain sebagainya.
3. Sumberdaya TanahTanah antara lain berfungsi sebagai tempat pemukiman; lahan pertanian dan
kehutanan; tempat kegiatan industri dan berbaagai sarana prasarana pendukung kegiatan manusia; sebagai bahan mentah industri; sebagai sumber energi alternaatif dan sebagainya.
4. Sumberdaya LautLaut merupakan sumberdaya yang sangat melimpah di Indonesia sebagai negara
maritim. Fungsi dan manfaat laut antar alain sebagai tempat hidup makhluk-makhluk laut; sumber mineral utamanya garam; sarana trasportasi; sumber energi; fungsi rekreatif, edukatif dan riset serta banyak lagi lainnya.
5. Sumberdaya MineralSumberdaya ini tergolong pada sumbersaya yang tidak dapat diperbaharui, meski
demikian cadangan mineral di negara kita ini masih cukup tinggi sehingga menjadi tumpuan devisa negara dari hasil penambangan mineral alam. Manfaat sumber daya ini antara lain sebagai sumber enrgi danbaahn bakar; bahan dari berbaagai jenis industri; bahan konstruksi; bahan pembuatan perhiasan dari logam mulia; dan lain sebgainya.
Kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Alam menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Dengan potensi yang besar dari alam semakin lama pemanfaatan alam oleh manusia tidak terkendali dan justru menimbulkan kerusakan hingga bencana alam. Pemanfaatan alam haruslah terintegrasi dengan kondisi sumberdaya alam tersebut. Sehingga diaharapkan tetap ada keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan
usaha pemulihan atau pelestarian. Salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yanng unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam, air, dan vegetasinya dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam tersebut.
Sumber daya alam pada daerah aliran sungai merupakan seluruh unsur lingkungan yang menyusun sistem daerah aliran sungai, baik hayati maupun nonhayati, termasuk produk yang dihasilkan oleh sistem DAS tersebut. Termasuk sumber daya alam DAS adalah tanah, air, hutan, kebun, hewan, dan komoditi lain dari suatu sistem DAS. Di DAS, sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dan rentan adalah berkaitan dengan sumber daya tanah, hutan dan terutama air.
Keberadaan DAS memberikan kehidupan, menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat salah satunya di bidang pertanian dan secara alamiah merupakan tempat berbagai jenis ekosistem. DAS yang ditumbuhi berbagai tanaman dapat melindungi tanah dan air. Keberadaan tanaman dan pohon-pohon memperlambat jalannya air hujan, membantu menyebar dan merembeskan air di dalam tanah, dan mencegah hanyutnya tanah terlalu banyak. Sungai dan mata air yang mengalir memberi kehidupan pada manusia, ikan-ikan, dan hewan. Ketika air masuk ke sungai-sungai dengan perlahan, tentu akan tersedia lebih banyak air di antara dua musim hujan dan lebih sedikit banjir ketika kemarau. Sehingga kebutuhan air tetap tersedia bagi masyarakat di sepanjang musim. Sementara otu, rawa-rawa, yang biasanya berada di kawasan DAS paling rendah, menyaring dan membersihkan ketika air mengalir.
DAS Brantas merupakan DAS yang sangat strategis dan penting di Jawa Timur karena DAS Brantas mencakup kurang lebih 25% wilayah Jawa Timur. Wilayah cakupannya sangat luas dan diperkirakan jumlah penduduk yang bergantung terhadap sumber daya alam DAS Brantas mencapai 50% total penduduk Jawa Timur. Bukan hal yang mengeherankan karena DAS Brantas melintasi 15 Kab/Kota yang ada di Jawa Timur. Pemanfaatan dari DAS Brantas sangat luas, mulai dari hulu sampai dengan hilir. DAS Brantas terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Aliran airnya bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) di lereng Gunung Anjasmara dan juga dari lereng barat Gunung Semeru, lalu aliran airnya bertemu di Malang. Dari hilir barat melalui Blitar, Tulungagung dan berbelok ke utara menuju Kediri melalui Nganjuk, berbelok ke timur melewati Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua manjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Banyaknya cakupan luasan dari DAS Brantas ini juga mengindikasikan adanya pemanfaatan yang luas dari DAS Brantas dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang ada di DAS Brantas sangat luas dan sangat banyak mendukung kehidupan masyarakat dan petani di daerah DAS Brantas. Banyak kehidupan yang bergantung dari DAS Brantas ini. Sumber daya alam yang sangat umum dimanfaatkan di DAS Brantas adalah dalam 2 hal utama yaitu sumber daya tanah (lahan) dan air.
DAS Brantas mempunyai potensi jumlah curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm/th. Potensi air permukaannya per tahun rata-rata 12,3 milyar m3 (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, 2009). Dengan potensi yang sangat besar ini, maka sumber daya air mempunyai peran strategi dan vital dalam kehidupan masyarakat, ketahanan pangan dan energi. Aliran-aliran sungai yang terdapat dalam DAS dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga pada PLTA, PDAM, irigasi, industri dan lain sebagainya. Kondisi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang berasal dari aliran sungai. Jika kondisi DAS menurun (debit air sungai), musim kemarau akan sangat menyulitkan para petani dan mempengaruhi hasil panen petani.
BAB 2
Permasalahan gangguan fungsi DAS
2.1. Fakta Lapangan gangguan ekosistem DAS
Saat ini kondisi DAS di sebagian besar daerah di Indonesia cenderung menurun. DAS memikul beban yang sangat berat dengan meningkatnya kepadatan penduduk di sekitar DAS dan meningkatnya pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam secara intensif sehingga kondisi DAS mengalami degradasi. Hasil pemantauan kualitas air melalui pengukuran Indeks Kualitas Airpada 13 sungai dan 40 situ yang ada di wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa 83% sungai dan 79% situ berada dalam kategori buruk (Hendrawan, 2005). Hasil penelitian yang mengacu pada studi Departemen PU ini perlu dicermati mengingat sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber daya alam pendukung kehidupan manusia.
Pertambahan populasi penduudk di sekitar DAS sangat memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi DAS secara lebih besar demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dikelola oleh manusia tanpa memperhatikan daya dukungnya sehingga membuat permasalahan-permasalahan yang serius yang menyebabkan fungsi-fungsi DAS tidak terlaksana dengan semestinya tau teradi penurunan fungsi DAS.
Banyak permasalah yang timbul salah satunya gangguan fungsi DAS dalam sedimen yang banyak terdapat di DAS. Kondisi derah tangkapan hujan banyak beralih fungsi menjadi pemukiman dan lahan pertanian tanpa mengindahkan aspek konservasi tanah dan air. Pohon di hutan ditebang dengan semena-mena. Hal ini tentu saja meningkakan erosi lahan yang menyebabkan adanya sedimentasi di sungai dan waduk. Selain penurunan kualitas air, terjadi pula kecenderungan peningkatan bencana di sekitar DAS, seperti tanah longsor, erosi dan sedimentasi. Hal ini terjadi baik di kawasan hulu berupa penebangan hutan, maupun di kawasan hilir berupa perubahan lahan irigasi dan persawahan untuk kepentingan ekonomi.
Fakta di lapangan ditemukan beberapa bukti adanya penurunan fungsi DAS Brantas. Pengamatan dilakukan di dua titik pengamatan yakni Desa Sengkaling dan Desa Pakisaji, Malang. Dua titik ini dipilih agar dapat mereeprentasikan kondisi DAS pada lokasi yang berbeda, Daerah Sengkaling yang tergolong lereng tengah sedangkan Pakisaji tergolong daerah hilir.
Gambar 1. Kondisi salah satu sungai di Sengkaling
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kualitas air sungai, warna aliran air yang tidak jernih menandakan bahwa air yang ada telah terkontaminasi bahan-bahan lain. Sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran dari limbah rumah tangga, sebab di bagian tepi atas sungai terdapat saluran pembuangan dari rumah warga sekitar sungai. Sampah-sampah plastik juga banyak ditemukan pada area ini, yang mana sampah-sampah ini menumpuk di badan sungai sehingga akan menghambat laju aliran air. Sampah yang banyak ditemukan adlah jenis sampah plastik yang tidak semestinya dibuang di daerah sungai karena sulit terurai dan akan memperparah terjadinya pendangkalan. Di tepi lain, ditemukan aktivitas manusia yaitu penambangan batu koral. Aktivitas ini berdampak buruk bagi kesehatan sungai ini sebab batu yang diambil dari bagian bawah membuat kondisi dasar sungai menjadi lemah, akibatnya tidak mampu menopang tanah yang berda di bagian tepinya. Jika hal ini diteruskan akan sangat mungkin terjadi longsoran.
Area sekitar sungai merupakan area pertanaman apel dengan kondisi lokasi yang cukup miring tetapi tutupan lahan terlihat kurang. Pada saat musim hujan besar kemungkinan terjadi erosi pada lahan apel tersebut yang akibatnya sedimen-sedimen hasil erosi akan masuk ke areal sungai dan menambah pendangkalan sungai yang terjadi. Pengelolaan pertanian intensif dengan berbaagai input kimia (pupuk dan pestisida) tentu akan mempengaruhi kualitas air yang keluar (drainase) lahan ke sungai. Hal ini semakin memperparah kondisi pencemaran sungai yang terjadi.
Gambar 2. Kondisi salah satu sungai di Pakisaji
Pengamatan lain dilakukan di daerah Pakisaji, Malang. Berbeda dengan yang ada di Sengkaling, pengamatan kedua ini menunjukkan kondisi yang lebih buruk dimana aliran air yang ada berwarna snagat keruh (coklat) yang mengindikasikan angkutan sedimen yang tinggi. Permaslahn sampahpun tak luput di daerah ini, banyak ditemukan sampah-sampah rumah tangga yang terangkut aliran. Sedimentasi yang terjadi juga menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga jika terjadi peningkatan volume air (misal: hujan) daerah ini sering meluap hingga menggenangi are ajaln di sekitarnya.
Kedua pengamatan menunjukkan kondisi yang sejalan, indikasinya bahwa telah terjadi penurunan fungsi DAS Brantas di Daearh Malang akibat sedimentasi, pencemaran dan pembuangan limbah yang kurang tepat.
2.2. Dampak masalah terhadap masyarakat dan petani di daerah hulu
Sebagian besar permasalahan yang terjadi di sungai/aliran air pada di daearah hilir suatu DAS banyak dipengaruhi kondisi pengelolaan di daerah hulu. Permsalahan
yang ditemukan selain karena kondisi in-situ (kondisi di sekitar aliran) dan eks situ (daerah lain yang memperngaruhi).
Kondisi daerah hulu akan jelas tercermin pada daerah hilir. Seperti yang ditemukan pada pengamatan, dengan adanya sedimentasi maka dapat digali lebih dalam penyebab terjadinya sedimentasi tersebut baik pada daerah kejadian dan daerah hulu sebagai sumbernya. Besarnya sedimentasi menandakan bahwa intensitas limpasan permukaan tinggi sehingga aliran air membawa partikel-partikel tanah yang mudah larut dalam air. Penyebab dari tingginya limpasan permukaan adalah menurunnya kapasitas infiltrasi tanah. Lebih jauh kapasitas infiltrasi ini diperngaruhi oelh berat isi tanah yang semakin padat sehingga kondisi pori-porinya tergolong rendah dan tidka mampu meloloskan apalagi menampung banyak air. Kapasitas tanah menahan air menjadi berkurang dan tanah menajdi cepat jenuh dengan air. Jika tanah telah jenuh maka air dari hujan misalnya akan terlimpasa ke permukaan dan mengakibatkan erosi di bagian hulu dan sedimentas di bagian hilir.
Analisa kondisi daerah hulu tidak bisa semata-mata karena kondisi tanah melainkan apa yang menyebabkan tanah mengalami penurunana fungsi. Jawabannya sudah barang pasti adalah aktivitas manusia. Perilaku-perilaku manusia yang mengekploitasi sumberdaya tanpa memperhatikan keberlanjutan sumberdaya tersebut menimbulkan banyak permasalahan bagi alam maupun manusia itu sendiri. Hal yang sangat mungkin dilakukan pada daerah hulu adalah penebangan hutan untuk diambil hasil kayu dan pembukaan lahan hutan menjadi area pertanian.
Pertaian daerah hulu yang dikembangakan oleh masyarakat lokal lebih condong kepada praktek pertanian semusim. Nampaknya masyarakat belum memahami kondisi atau karakteristik daerah mereka dimana daerah hulu merupakan daerah dengan kemiringan yang lebih besar sehingga tanahnya akan mudah terkikis oleh air hujan jika tidak ada penutup lahan yang optimal. Tanah yang terekspose secara langsung tanpa ada tutupan di atasnya akan mudah sekali menagalami erosi terutama oleh air. Ditambah lagi dengan kondisi umum daerah hulu yang identik dengan curah hujan yang cukup tinggi, tentu akan memperhebat erosi yang mungkin terjadi. Akibatnya lapisan tanah yang subur (di permukaan tanah) menjadi hilang terbawa aliran air, munculllah masalah baru yaitu penurunan kesuburan tanah. Penurunan kesuburan tanah berdampak panjang pada hasil produksi pertanain dan pendapatan masyarakat, yang artinya dari satu masalah erosi akan berakibat buruk pada tanah, lahan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pada awal pembukaan lahan hutan, petani tentu mendapakan tanah yang paling subur karena bekas hutan. Kondisi tersebut akan bertahan untuk beberapa tahun kedepan. namun, semakin lama kesuburan tanah ini akan menurun karena jenis pertanian yang diusahakan adalah tanaman semusim yang memerlukan banyak unsur hara sehingga hara yang berada dalam tanah cepat habis dan terkuras. Oleh karena itu, input tinggi menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Hal ini pun akan berdampak buruk bagi lingkungan tanah dan air karena adanya bahan pencemar dari residu pertanian. Residu yang dihasilkan dari pupuk dan pestisida kimia akan mencemari tanah, jika terjadi hujan residu tersebut akan terlarut dalam air sehingga terbawa oleh aliran air ke dalam sungai maupun saluran lainnya. Akibatnya, aliran air yang ada merupakan aliran air yang telah tercemar dengan bahan-bahan kimia belum lagi ditambah limbah-limbah rumah tangga yang terikut didalamnya. Akhirnya kualitas air sungai menjadi menurun.
Penurunan kualitas air menimbulkan maslaah lain lagi. Masyarakat di daerah hulu mayoritas menggunakan air dari sumber air DAS. Sehingga adanya sedimentasi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di DAS Brantas Hulu. Air yang digunakan oleh masyarakat keruh dan mengandung partikel-partikel sedimen tanah yang banyak
sehingga menjadi kurang layak. Hal ini tentu saja akan menyulitkan masyarakat yang ada di DAS hulu Brantas.
Masalah lain yang juga dihadapi oleh masyarakat hulu DAS Brantas adalah berkurangnya mata air akibat dari penggunaan lahan yang salah tidak sesuai peruntukkan sehingga tanah yang ada tidak mampu menahan air atau infiltarsinya berkurang sehingga limpasan permukaan meningkat dan terjadilah seidmentasi. Permasalahan ini sangat serius karena bisa menyebabkan kekurangan air di daerah hulu. Berkurangnya kapasitas infiltrasi tanah juga akan menyebabkan berkurangnya air yang dapat disimpan oleh tanah sehingga petani mengalami kendala dalam hal budidaya. Selain itu, kendala yang juga dihadapi petani adalah tercucinya unsur hara sehingga menyebabkan kesuburan tanah menurun dan menyebabkan gangguan produksi tanaman yaitu menurunnya produksi tanaman.
2.3. Dampak masalah terhadap masyarakat daerah hilir DAS
Daerah hilir dicirikan sebagai daerah pengguna air. Biasanya terletak pada daerah-daerah yang datar. Pola perubahan penggunaan lahan menjadi akar maslah yang terjadi baik daerah hulu maupun daerah hilir. Berdasarkan permasalahan yang dipaparan diatas berupa erosi, sedimentasi, dan penurunan kualitas air daerah hulu tentu akan berdampak pada daerah hilir. Tempat akhir penumpukan sedimen adalah daerah hilir, dengan demikian maka daerah ini akan banyak menerima kiriman sedimen akibat erosi di hulu. Sedimen yang masuk ke dalam area tubuh air seperti sungai dan waduk akan menyebabkan pendengkalan sehingga kapasitas tampung dan simpan air berkurang. Akibatnya terjadi kekurangan air pada saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Kemarau, air yang tertahan oleh tubuh air tidak adapat mencukupi kebutuhan masyarakat secara luas sementara saat musim penghujan tubuh air tidka mampu menampung banyak air sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan tampungan dengan jumlah air yang masuk dan akhirnya meluber menyebabkan banjir.
Sedimen hasil erosi tanah lapisan atas yang mengandung banyak unsur hara menyebabkan dampak negatif terhdap kondisi hidrologi dan biota air lainnya. Unsur hara yang masuk dalam tubuh air akan menyebabkan peningkatan aktivitas bakteri unutk merombak bahan organik yang terbawa sehingga kandungan oksigen dalam air berkurang. Oleh karenanya banyak biota-biota air yang kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Selain itu juga ditandai dengan terjadinya eutrofikasi.
Masalah lain yang harus dihadapi adalah adanya timbunan sampah yang terbawa oleh aliran air. Sampah baik dari hulu maupun daerah tengah DAS Brantas akan terbawa aliran air yang deras ketika turun hujan. Sampah-sampah tersebut kemudian akan terbawa terus hingga ke daerah DAS hilir. Akibatnya terjadi penumpukan sampah setelah hujan. Sampah ini juga akan menjadi masalah baru bagi daerah hilir, yang jika dibiarkan berada pada aliran air maka akan menyebabkan penyumbatan dan pengdangkalan sedangkan jika dipindahkan maka perlu menyediakan tempat dan pengelolaan yang tepat guna.
2.4. Analisis akar masalah secara komprehensif
Permasalahan utama berdasarkan hasil observasi adalah sedimentasi, sampah dan penurunan kualitas air. Ketiganya berasal dari permasalahan pokok yaitu peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan kemudian masyarakat membuka daerah hutan (hulu DAS) dan mengupayakan pertanian semusim. Perubahan fungsi hutan menjadi pertanaman semusim ini kemudian membawa dampak buruk bagi lingkungan, seperti erosi dan sedimentasi.
Masyarakat hulu yang belum memahami arti penting DAS bagi kehidupan memperlakukan hutan hanya demi tujuan ekonomis dan pemenuhan kebutuhan hidup. Paradigma tentang hutan juga msih bersifat pada hutan sebagai lahan yang kurang produktif karena tidak menghasilkan secara ekonomis, sehingga harus dibuka guna lahan pertanian yang dirasa lebih menguntungkan bagi perekonomian mereka.
Pola hidup masyarakat juga menimbulkan masalah lain yaitu sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik terutama pada area DAS Brantas ini, telah terbukti berpengaruh pada pendangkalan akibat tumpukan sampah dan penurunan kualitas air sungai yang dijadikan sumber air bagi masyarakat. Terlebih banyak daerah sempadan sungai yang dijaikan perumahan, tentu masyarakat sempadan sungai ini tidak akan berpikir panjang untuk membuang sampah langsung di sungai.
Pandangan lain yang perlu diperhatikan adalah segi sosial ekonomi masyarakat daerah sekitar DAS Brantas. Perilaku apapun terbentuk di lingkungan masyarakat, sehingga permasalahan dapat ditemukan disana sekaliguspun dengan penyelesaian yang ditawarkan nantinya.Pembahasan permasalahan DAS termasuk degradasi lingkungan sangat terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Permukiman padat di sepanjang sungai cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai. Kebiasaan membuang kotoran, sampah, lebih disebabkan pandangan yang keliru dari masyarakat terkait dengan fungsi sungai, yang dianggap sebagai halaman belakang rumah. Kebiasaan masyarakat semacam ini ditemui di kedua wilayah wilayah baik tengah-hilir, yang mengindikasikan ketidakpedulian masyarakat terhadappentingnya memelihara sungai. Keterbatasan yang dimiliki masyarakat kelas bawah yang tinggal disepanjang DAS, menambah permasalahan ini.
Kebiasaan masyarakat di kawasan hilir sungai merefleksikan ketidakpedulian masyarakat, meskipun di lain pihak sungai juga memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bencana banjir yang terjadi pun merupakan akibat bencana yang mereka harus alami sebagai penduduk permukiman di wilayah hilir, yang bisa jadi merupakan akibat kebiasaan serupa di wilayah hulu.
Diagram alur permasalahan DAS Brantas
Peningkatan Penduduk
Pembukaan lahan hutan
Pertanian tanaman semusim Erosi dan
sedimentasi
Pemukiman
Pola hidup tidak bersih
Sampah Sungai Sedimen
pendangkalanSampah pencemaranKemarau :
kekeringanHujan :Banjir
BAB 3
Tinjauan Pustaka
3.1 Pengertian Daerah Aliran Sungai
Sungai adalah salah satu sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang mempunyai komponen badan sungai dan kawasannya. Pengertian lain, sungai adalah tempat tempat dan wadah wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan di batasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Dalam rangka memanfaatkan sungai, perlu adanya pembinaan yang berorientasi pada kelestarian kawasan dan badan sungai tersebut, agar pemanfaatan air sungai dapat berjalan lama dan dapat mencapai manfaat sebesar besarnya dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Sungai mempunyai kawasan tampungan air yang akan masuk ke badan sungai tersebut, dan secara umum dinamakan Daerah Aliran Sungai (Bisri, 2009). Berbagai definisi tentang DAS di kemukakan oleh berbagai kalangan.
Menurut UU Republik Indonesia No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Adapun Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
3.2 Kerusakan dan Pengelolaan DAS TerpaduKerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) salah satunya disebabkan praktik
penebangan liar dan konversi lahan yang menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Kerusakan DAS tersebut juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga (Bappenas, 2012). Sebab-sebab kerusakan DAS antara lain timbul akibat (Gautama, 2008) :
a. Perencanaan bentuk penggunaan lahan dan praktek pengelolaan yang tidak sesuai,b. Pertambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun buatan,c. Kemiskinan dan kemerosotan ekonomi akibat keterbatasan sumber daya manusia,
sumber alam dan mata pencaharian,d. Kelembagaan yang ada kurang mendukung pelayanan kepada para petani di hulu/
hutan,e. Kebijakan perlindungan dan peraturan legislatif, tidak membatasi kepemilikan
penggunaan lahan,f. Ketidakpastian penggunaan hak atas tanah secara defakto pada lahan hutan.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan menata kembali kerusakan lahan yang terjadi dan dilain pihak perlu melakukan pencegahan kerusakan dimasa mendatang. Semua tujuan ini untuk membuat penggunaan lahan menjadi lebih baik akibat keterbatasan lahan dan sumber air yang ada. Ada sejumlah pelaksanaan pengelolaan DAS yang dapat digunakan dan dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Ada tiga sasaran umum kegiatan pengelolaan DAS yaitu (Gautama, 2008).
1. Rehabilitasi
Memperbaiki lahan pertanian/kehutanan akibat erosi dan sedimen yang berlebihan dan bahan-bahan yang mudah larut yang tidak diperlukan akibat run-off dan lain-lain. Metoda rehabilitasi yang digunakan adalah metoda: tanah hutan, rangeland, tanah pertanian dan saluran aliran. Rehabilitasi sering dibatasi untuk DAS kecil; pengertian rehabilitasi sering digunakan untuk membatasi fungsi DAS yang memerlukan penataan kembali.
2. ProteksiPerlindungan tanah pertanian/kehutanan akibat pengaruh yang membahayakan produksi dan kelestarian menggunakan metoda: tanah hutan, rangeland, pencegahan kebakaran, pencegahan terhadap gangguan serangga/hama serta penyakit.
3. PeningkatanPeningkatan sifat sumber air dilakukan dengan manipulasi ciri-ciri suatu DAS akibat pengaruh hidrologi atau fungsi kualitas air. Tujuan peningkatan pengelolaan DAS didasarkan pada pengakuan bahwa sistem tanah-tanaman yang alami tidak memerlukan produksi air yang optimum. Ketergantungan pada tujuan pengelolaan tanah tertentu, neraca air, cara hidup atau kualitas air dapat dirubah. Semua praktek dan program peningkatan yang sekarang dilakukan (kuantitas air dan cara hidup) dan program perlindungan serta perbaikan, bertujuan untuk mengontrol atau menata kualitas air.
Upaya pengelolaan DAS terpadu pertama kali dilaksanakan di DAS Citanduy (1981) dengan kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas disiplin. Kemudian dikembangkan di DAS Brantas, Jratun Seluna. Proyek-proyek pengelolaan DAS pada saat itu lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik kegiatan konservasi lahan untuk mencegah banjir dan erosi yang hampir seluruhnya dibiayai oleh pemerintah dan bantuan asing. Namun walau upaya pengelolaan DAS yang sudah cukup lama dilakukan, ternyata karena kompleksitas masalah, hasilnya belum memadai, terutama yang berkaitan dengan pembangunan SDM dan kelembagaan masyarakat.
Pengelolaan DAS selama ini masih banyak bersifat sektoral dan administratif, kerap menjadikan adanya benturan kepentingan antar instansi terkait. Batas pengelolaan DAS yang mestinya menggunakan batas-batas alami justru terbentur dengan batas administrasi yang tidak sesuai untuk dijadikan batas pengelolaan karena semua komponennya saling berkaitan. Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan.
Prinsip pengelolaan DAS terpadu adalah sebagai berikut :
1. DAS harus dipahami sebagai suatu ekosistem alami, satu rencana, satu sistem pengelolaan terpadu.
2. Pengelolaan DAS dilakukan secara terencana, melibatkan multipihak, terkoordinasi, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
3. Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pendekatan adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis dan sesuai dengan karakteristik DAS.
4. Pembagian beban biaya dan manfaat antar multipihak.
Pelaksanaan prinsip pengelolaan DAS terpadu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, ada beberapa contoh keberhasilan pengelolaan ini di wilayah seperti Das Cidanau. Pengelolaan DAS mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat pemanfaat aliran sungai. Manfaat besar telah didapatkan dengan mengelola DAS dengan benar, misalnya untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik dan
ketersediaan air bersih untuk konsumsi. Pengolaan DAS akan lebih efektif dengan kerjasama yang sinergis, integratif, sinkronisasi dan sinergis antar semua lembaga baik dari pihak pemerintahan, swasta, NGO dan masyarakat pada umumnya.
3.3 Upaya Perbaikan DASPemecahan masalah DAS dapat menggunakan alternatif pengelolaan lahan secara
mekanis dan vegetatif yang dapat dilakukan dengan beberapa usaha konservasi secara terpadu yaitu sebagai berikut (Fatturachman, 2008) :
1) Wanatani (agroforestry),tanaman pangan pada perkebunan tanaman keras kopi. Kuantitas tanaman pangan disesuaikan dengan kemiringan lereng pada lahan tersebut dan acuan umum proporsi tanaman pada kemiringan lahan yang berbeda, yaitu pada kelerengan < 15% dilakukan proporsi penanaman 25% tanaman tahunan dan 75% tanaman semusim; pada kelerengan 15-30% proporsi penanaman tanaman tahunan dan semusim adalah sama, yaitu 50 %; pada kemiringan lereng 30-40% proporsi penanaman tanaman tahunan adalah 75% dan tanaman semusim 25%; serta untuk kelerengan > 40% penerapan tanaman adalah tanaman tahunan saja, sebab pada kemiringan ini merupakan kriteria fungsi kawasan lindung.
2) Pemilihan tanaman keras kopi didasarkan pada pola budidaya masyarakat sekitar yang menanam kopi sebagai tanaman keras perkebunan, sehingga kopi merupakan tanaman keras yang sudah diberdayakan oleh masyarakat walaupun kuantitasnya sedikit dibandingkan dengan penanaman tanaman semusim.
3) Pemilihan tanaman semusim disesuaikan dengan kondisi kebiasaan masyarakat dalam mengusahakan tanaman pertanian, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan penanaman jenis tanaman baru. Penanaman tanaman semusim dilakukan diantara tanaman keras sehingga kegiatan pertanian berlangsung sebagai kegiatan budidaya tanaman pangan diantara perkebunan yang telah direkomendasikan. Kegiatan pertanian terbatas diusahakan sebagai jalan peningkatan perekonomian masyarakat tanpa harus mengurangi fungsi kawasan yang ada dan sebagai bentuk penyokong usaha perkebunan sebagai tanaman pokok lahan menggantikan tanaman semusim tanpa tanaman keras.
4) Pemilihan pengelolaan lahan (P) dipilih dengan mempertimbangkan kondisi pengelolaan awal, besar erosi (A) dan erosi yang diperbolehkan (T). Pengelolaan lahan alternatif disusun dengan menekan seminimal mungkin perubahan yang terjadi pada relief mikro lahan, akan tetapi dapat menciptakan CP alternatif yang nilai A alternatifnya ≤ besar erosi (A). Pemilihan pengelolaan lahan, baik dengan teras guludan, teras kridit, dan bangku serta perlakukan penanaman tanaman pagar dan pertanaman lorong disesuaikan dengan tingkat kebutuhan berdasarkan syarat dan karakteristik fisik lahan di daerah penelitian. Seta (1991) menyatakan bahwa tanaman yang baik digunakan untuk tanaman pagar pada perkebunan kopi dan karet di Indonesia adalah lamtoro (Leucaena glauca). Tanaman ini memiliki keunggulan sebagai tanaman pagar di daerah lereng yang memiliki ketinggian hingga 1.500 dpal, memiliki sistem perakaran yang dalam, tahan pangkas, dan memberikan unsur nitrogen pada tanah dalam jumlah yang besar sebagai sumber bahan organic serta mulsa. Pangkasan dari tanaman pagar yang digunakan sebagai mulsa diharapkan dapat menyumbangkan hara terutama nitrogen. Tanaman penutup tanah rendah, dapat ditanam bersama tanaman pokok maupun menjelang tanaman pokok ditanam. Tanaman penutup tanah sedang dan tinggi pada dasarnya seperti tanaman sela dimana tanaman pokok ditanam di sela-sela tanaman penutup tanah. Dapat juga tanaman pokok ditanam setelah tanaman penutup tanah dipanen. Untuk perbaikan teras bangku, selain menanam tanaman pagar pada bibir teras, sebaiknya ditanam rumput pada tampingan teras. Rumput yang baik digunakan pada tampingan dan bersifat tebang pangkas menguntungkan bagi petani sebagai pakan ternak adalah rumput bede.
5) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam keterkaitan konservasi lahan sangat diperlukan guna menanamkan sikap yang ramah lingkungan demi keberlangsungan usaha pertanian di kemudian hari dan menekan seminimal mungkin dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya pengolahan lahan oleh masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat di daerah konservasi dapat berupa.a. Program penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan perdesaan,
sehingga pendapatan petani meningkat. b. Program pengembangan pertanian konservasi, sehingga dapat berfungsi produksi
dan pelestarian sumber daya tanah dan air. c. Penyuluhan dan transfer teknologi untuk menunjang program pertanian konservasi
dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi lahan.
d. Pengembangan berbagai bentuk bantuan, baik berupa bantuan langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk bantuan teknis, pinjaman, yang dapat memacu peningkatan produksi pertanian dan usaha konservasi tanah dan air.
e. Upaya mengembangkan kemandirian dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah, sehingga mampu memperluas keberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi rakyat.
f. Memonitor dan evaluasi terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut berperan serta dalam pengelolaan dan konservasi lahan.
6) Penegasan Aturan Hukum yang Berlaku Penegasan aturan hukum yang berlaku dimaksudkan sebagai bentuk monitoring pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan tata ruang wilayah berdasarkan pada tingkat kemampuan dan kesesuaian lahannya. Suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung harus semestinya tetap dilindungi dengan aturan hukum, tidak semestinya terjadi alih fungsi lahan yang berdasarkan keputusan sesaat yang hanya mementingkan kepentingan politik dan ekonomi saja. Pengawasan dan evaluasi harus terus diterapkan guna menuju suatu pengelolaan lahan yang berkelanjutan (sustainable development).
BAB 4
Rencana Aksi Manajemen DAS
Manajemen DAS atau pengelolaan DAS berati mengelola DAS sebagaimana mestinya guna mempertahankan fungsi maupun meningkatkan kondisi DAS menjadi lebih baik. Pengeloaan DAS terpadu adalah dengan memahami DAS sebagai suatu sistem yang kompleks dengan semua komponen didalamnya yang saling berinteraksi satu sma lain termasuk dialmnya manusia. Komponen manusialah yang menjadi masalah sekaligus solusi bagi pengelolaan DAS. Rencana aksi yang dilakukan hendaknya bersifat integratif dari berbagai disiplin ilmu, multi kepentingan dan komprehensif untuk perbaikan menyeluruh.
1. Permasalahan Erosi dan SedimentasiSebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa terjadi permasalahan erosi dan
sedimentasi dari hulu ke hilir DAS Brantas, maka upaya-uapaya yang dapat dilakukan antara lain :a. perencanaan tata ruang dan wilayah daerah (RTRW)
Rencana tata ruang dan wilayah di DAS Brantas seluruhnya yang mencakup ? kabupaten lebih ditujukan pad aperbaikan kondisi DAS yang semakin parah. Proporsi ruang terbuka hijau juga harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Pemanfaatan sumberdaya air pun diatur dalam kebijakan ini. Selain itu, pemerintah juga wajib bertindak tegas pada warganya yang melanggar aturan terkait pengeloaan DAS. Pengawasan dan monitoring harus dilakukan sehingga penyelewengan dari aparatur maupun masyarakat umum dapat dihindari.
b. penegakan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap pembukaan lahan hutan sebagai daerah konservasi;Terutama di daerah hulu dengan topografi wilayah yang miring, kebijakan pembukaan lahan huta untuk pertanian harus ditegakkan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pertanian jauh lebih besar manfaatnya terhadap pendapatan masyarakat. Namun akan lebih baik jika msyarkat mengetahui kelebihan hutan seara jangka panjang. Pembukaan hutan sebagai area pertanian harus sangat dibatasi, oleh sebab itu instansi terkait seperti Perhutani dapat tegas memberikan
Erosi & sedimentasi
Sampah
Usaha tani konservasi
Kebijakan(RTRW)
Penegakan kebijakan
pembukaan lahan hutan
Penggalakan kembali
program kali bersih
Pemberdayaan LSM
pengawasan dan tindakan tegas bila diketemukan adanaya pembukaan hutan tanpa ijin.
c. peningkatan fungsi LMDH dan LSM terkait guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan;Masyarakat berinteraksi dalam lingkungannya melahirkan suatu budaya yang khas di setiap daerah.Peningktan lembaga swadaya masyarakat yang telah mengenal baik lingkunganmsyarakat tertentu akan jauh lebih efektif dalam angka pendekatan kkesadaran ekologis terhadap masyarakt ketimbang harus mendatangkan ahli yang jauh dari luar tetapi tidak sesuai dengan kebudayaan setempat. Lembaga-lembaga ini harus bersinergi dengan pemerintah terkait usaha bersama dalam rangka pengelolaan DAS yang lebih baik.
d. penerapan usahatani konservasi;Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memrlukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak dapat pula pemerinta langsung dan secara diktatif mengganti mata pencaharian petani utamanya daerah hulu dengan hutan sebagai konservasi. Diperlukan adanya integrasi antar berbagai kepentingan. Usahatani konservatif seperti sistem wanatani dapat dikembangkan dalam hal ini. Sistem ini memadukan antara tanaman pohon dengan tanaman semusim atau tanaman produksi sehingga msyarakat tetap dapat mendapatkan penghasilan sedangkan konservasi juga dapat berjalan. Usahatani ini menemui banyak kendala ketika hasil usaha tani ni tidak sebesar jika suatu lahan diusahakan dengan tanaman hortikultur misalnya. Untuk itu, diperlukan banyak pertimbangan dalam pemilihan komoditas usaha yang akan ikembangkan sehingga pendapatan yang diterima tidak terlalu jauh berbeda.
e. penerapan sistem imbal jasa lingkungan (hidrologi)Imbal jasa lingkungan diartikan sebagai bentuk interaksi antara masyarkat hulu sebagai penyedia, masyarakat hilir sebagai pengguna dan phak ketiga sebagai perantara. Inbal jasa ini akan mendorong petani daerah hulu mau untuk mengusahakan konservasi karena mendapatkan insentif dari masyarakat hilir sebagai pengguna dan tidak merasa harus bekerja sendiri dalam upaya perlindungan lingkungan. Sementara msyarakat hilir sebaagi pengguna sanagt diuntungkan dengan hasil konservasi yang dilakukan seperti ketersediaan air bersih. Namun tidak semata hanya dengan membayarkan insentif sebagai imbal jasa, warga dearah hilir wajib pula menjaga lingkungannya agar tetap bersih terutama dari maslah samapah yang selalu ada.
2. Permasalahan SampahMasalah sampah ini sangat terkait dengan pandangan masyarakat yang menilai
bahwa sungai sebagai halaman belakang rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga. pandangan ini yang kemudian membuat masyarakat tanpa pikir panjang membuang samaph sembarangan disempadan sungai. Apalagi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sempadan sungai. Daerah sempadan sebenarnya bukanlah daerah yang dpat ditinggali sebagai pemukiman, tetapi karena kebutuhan papan yang terus meningkat seiring dengan peningktan umlah penduduk maka hal inipun tidak dapat dihindarkan. Peran pemerintah yang melarang warga tinggla di area ini tidak diperhatikan sama sekali. Di sisi lain, pemerintah juga tidak berani bersikap tegas karena belum memiliki solusi yang pas untuk kasus ini. Jika ngin dipindahkan maka pemerintah setidaknya harus menyediakan tempat bagi warga sempadan sungai sebagai gantinya, tentunya keputusan ini tidak memerlukan dana yang sedikit.
Oleh sebab itu, sebagai upaya pengurangan sampah domestik yang masuk ke aliran perlu digalakkan kembali program yang sebelumnya sudah pernah ada yaitu ‘kali
bersih’. Program ini telah terlaksana tetapi belum optimal dimana limbah yang dijadikan fokus barulah limbah industri sementara limbah domestik belum tersentuh. Program ini dapat dijalankan melalui upaya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga pemahaman tentang lingkungan yang bersih dapat dipahami dengan baik. Tindakan nyata yang dapat diberikan adalah dengan pengadaan tempat sampah di setiap rumah beserta dengan pemilahan jenisnya agar dapat dimanfaatkan kembali untuk memperoleh keuntungan ekonomis. lebih baiklagi jika masyarakat juga diberi penyuluhan untuk mengolah sampah secara mandiri. Tentunya tidak ada masyarakat yang menolak untuk alasan ekonomis. Dengan demikian maka sampah domestik tidak akan masuk ke dalam aliran sungai.
BAB 5
Kesimpulan dan Saran
5.1 KesimpulanWilayah DAS Brantas merupakan wilayah utama bagi masyrakat sekitar DAS
tersebut. Potensi sumberdaya air yang ada dapat diamnfaatkan dalm pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Namun, ditemukan berbagai permaslah yang cukup kompleks baik daerah hulu maupun daerah hilir DAS Brantas. Masalah utamanya adalah erosi, sedimentasi, sampah, dan penurunan kualitas air akibat pencemaran. Sedangkan akar dari permasalahan ini adalah peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidupnya sehingga aktivitas-aktivitas yang idak sejalan dengan lingkungan terus terjadi salah satunya dengan pembukaan lahan hutan untuk pertanian. Perilaku hidup masyarakat di daerah DAS yang kurang baik juga memicu permasalahan lain yaitu sampah yang pada dasarnya akan berdampak buruk baik bagi lingkungan maupun kehidupan msyarakat itu sendiri.
Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan upaya penegakan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap pembukaan lahan hutan sebagai daerah konservasi; peningkatan fungsi LMDH dan LSM terkait guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan; penerapan usahatani konservasi; penerapan sistem imbal jasa lingkungan; dan penggealakna kembaliporgrma kali bersih.
5.2 SaranPengelolaan DAS Brantas tidak dapat dilakukan salah satu atau beberapa pihak
saja. Semua komponen harus terlibat dan saling bersinergis dalam upaya menjada fungsi DAS sebagaimana mestinya. Kondisi masyarkat yang belum tahu dan belum sadar akan pentingnya DAS harus dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting karena ujung tombak pengelolaan adalah masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi pihak-pihak seperti akedemisi, peneliti dan pemerintah yang lebih memahami aspek lingkungan-ekonomi wajiblah memberikan pendekatan kepada masyarakat guna peningkatan pengelolaan DAS secara integratif.
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas. 2012. Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Di Ekosistem Das Dalam Menunjang Ketahanan Air Dan Ketahanan Pangan : Studi Kasus Das Brantas. Jakarta: Direktorat Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas.
Fathurrohman, Deden. 2008. Masalah Pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS) Brantas di Jawa Timur : Solusi dan Model Kolaborasi. Agritek Volume 16 Nomor 5 Mei 2008 Halaman 678-952.
Gautama, Iswara. 2008. Daerah Aliran Sungai (Das), Ekosistem Dan Pengelolalan. Lembaga Swadaya Pemerhati Sungai Jakarta.
Hendrawan, D. (2005). Kualitas air sungai dan situ di Jakarta. Jurnal Makara, Seri Teknologi, 9 (1), 13-19.
Harini, Sri dan Elok Mutiara. 2012. Manajemen Pengelolaan Lahan Kritis Pada Das Brantas Hulu Berbasis Masyarakat (Pilot Project Desa Bulukerto, Kota Batu). Sainstis. Volume 1, Nomor 1, April – September 2012.