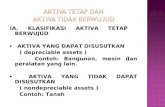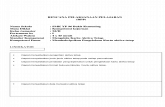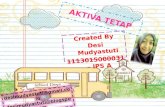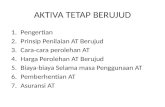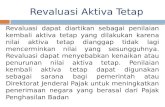AKTIVA TETAP
Transcript of AKTIVA TETAP
BAB II PEMBAHASANAset tetap adalah aset berujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap sebagai berikut: 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan (bukan barang dagangan) 2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama (bukan investasi jangka panjang) 3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan (bukan perlengkapan) 4. Memiliki nilai yang relatif tinggi Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap (Capital Budgeting) harus diperhitungkan dengan matang.
KLASIFIKASI ASET TETAP Umumnya aset tetap dibagi dalam empat kelompok, yaitu: 1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan Tanah, seperti jalan diseputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. 3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. 4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan meubel.
PENENTUAN HARGA PEROLEHAN ASET TETAP Dari beragam aset tetap berujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokkan sbb: 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. 2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, seperti sumber-sumber alam misalnya tambang dan hutan
Penyusutan atas 3 kelompok aset tetap berwujud tsb adalah: 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas tidak dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya 2. Aset tetap yang terbatas umurnya dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya Aset tetap yang dapat diganti dengan aset sejenis, penyusutannya disebut depresiasi. Penyusutan sumber alam disebut deplesi, sedangkan penyusutan aset tidak berwujud disebut amortisasi. PENGELUARAN-PENGELUARAN MODAL DAN PENDAPATAN Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Capital expenditure (pengeluaran modal) Merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset (dikapitalisasi). 2. Revenue expenditure (pengeluaran pendapatan) Merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Namun dengan alasan kepraktisan, dilakukan penyimpangan antara lain: 1. Sebagai revenue expenditure apabila: a. jumlah pengeluaran relatif kecil b. manfaat di masa yang akan datang tidak begitu berarti c. sulit mengukur manfaat di masa yang akan datang 2. Sebagai capital expenditure apabila pengeluaran di atas jumlah tertentu dan jelas-jelas memberikan manfaat untuk periode-periode yang akan datang. PRINSIP PENILAIAN ASET TETAP BERWUJUD Aset Tetap Dinyatakan Sebesar Nilai Buku Yaitu Harga Perolehan Aset Tetap Tersebut Dikurangi Dengan Akumulasi Penyusutannya Sesudah aset tetap diperoleh dan dalam masa penggunaan, maka: 1. Aset yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehannya 2. Aset yang umurnya terbatas dicantumkankan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
Harga perolehan (acquisition cost) aset tetap meliputi jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset tetap tersebut. Nilai buku aset tetap adalah harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi depresiasi/deplesi aset tetap tersebut CARA-CARA PEROLEHAN ASET TETAP Pembelian Tunai Pembelian Angsuran Ditukar dengan Surat-surat Berharga Ditukar dengan Aset Tetap yang Lain 1. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis 2. Pertukaran aset tetap yang sejenis 5. Diperoleh dari Hadiah/Donasi 6. Aset yang Dibuat Sendiri MASALAH KHUSUS DLM PENENTUAN HARGA PEROLEHAN 1. Pembelian dengan Menggunakan Wesel Berbunga 2. Pembelian dalam Satu Paket (lump-sum) 3. Perolehan dengan Membangun Sendiri 4. ASET YANG DIPEROLEH DARI PERTUKARAN DENGAN SURAT BERHARGA Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar: 1. 2. 3. Harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar Jika harga pasar surat berharga tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aset tetap yang ditukar keduanya tak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan 1. 2. 3. 4.
Harga pasar surat berharga adalah harga yang terjadi dalam bursa surat-surat berharga atau dalam transaksi dengan pihak lain yang bebas. Pertukaran aset tetap dengan surat berharga akan: 1. dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya 2. selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio/disagio
Ilustrasi PT XYZ menukar sebuah gedung dengan 10.000 lembar saham biasa, nominal @ Rp10.000. Pada saat pertukaran harga pasar saham per lembar adalah Rp11.000 Pertukaran ini dicatat dengan jurnal: Gedung Modal Saham Biasa Agio Saham Rp 110.000.000 Rp 100.000.000 Rp 10.000.00
ASET YANG DIPEROLEH DARI HADIAH/DONASI Pencatatannya dapat menyimpang dari harga perolehan karena harga perolehannya relatif kecil. Ilustrasi PT ALIT menerima hadiah berupa tanah dan gedung yang masing-masing dinilai Rp60.000.000 dan Rp40.000.000. Pencatatannya adalah: Tanah Gedung Modal Hadiah Rp 60.000.000 Rp 40.000.000 Rp 100.000.000
Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut, PT ALIT mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000,00. Maka pencatatan penerimaan hadiah tersebut: Tanah Gedung Modal Hadiah Kas Rp 60.000.000 Rp 40.000.000 Rp 95.000.000 Rp 5.000.000
Apabila donasi yang diterima itu belum pasti akan menjadi milik perusahaan (karena tergantung pada terlaksananya perjanjian) maka aset dan modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti (contingent). Apabila hak atas aset tersebut sudah diterima, maka barulah contingent assets tersebut dicatat sebagai aset. Ilustrasi Jika pada kasus PT ALIT di atas, hak atas tanah baru akan diserahkan 2 tahun kemudian maka jurnal yang dibuat adalah Aset yang Belum Pasti Tanah Aset yang Belum Pasti Gedung Modal yang Belum Pasti - Hadiah Rp 60.000.000 Rp 40.000.000 Rp 100.000.000
Ketika hak atas sudah diterima, dikeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000. Jurnal: Tanah Gedung Modal yang Belum Pasti - Hadiah Aset yang Belum Pasti Tanah Rp 60.000.000 Rp 40.000.000 Rp 100.000.000 Rp 60.000.000
Aset yang Belum Pasti - Gedung Modal Hadiah Kas
Rp 40.000.000 Rp 95.000.000 Rp 5.000.000
Apabila hadiah yang belum pasti tersebut berupa aset yang didepresiasi, maka perhitungan depresiasi dimulai sejak aset tersebut diterima sebagai hadiah yang belum pasti. ASET YANG DIBUAT SENDIRI Pembuatan aset (seperti gedung, alat, dan perabotan) oleh perusahaan sendiri biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas Permasalahan pada aset yang dibuat sendiri adalah alokasi BOP tidak langsung. Dua cara alokasi BOP-TL yaitu: 1. kenaikan BOP yang dibebankan pada aset yang dibuat 2. BOP dialokasikan dengan tarif pada pembuatan aset maupun produksi Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Bila pembuatan aset berasal dari dana pinjaman, maka: a. bunga pinjaman selama masa pembuatan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset. b. Sesudah aset selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. c. Biaya-biaya lain yang timbul dalam masa pembuatan aset, dibebankan sebagai harga perolehan aset tetap. 2. Dalam hal harga pokok aset yang dibuat lebih rendah daripada harga beli di luar, selisihnya merupakan penghematan biaya dan tidak diakui sebagai laba. 3. Dalam hal harga pokok aset yang dibuat lebih tinggi daripada harga beli di luar, selisihnya diperlakukan sebagai kerugian dan aset dicatat sebesar harganya yang normal. ASET TETAP YANIG DIHIBAHKAN Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan maka hibah pun dapat dikelompokkan ke dalam 1. Memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) Bentuk aset yang dihibahkan berupa kendaraafl dengan rincian: Harga perolehan Rp 100.000.000 Akumulasi penyusutan Rp 60.000.000 + Harga sisa buku Rp 40.000.000 Harga pasar Rp 55.000.000 1.
Ayat jurnal yang disusun dari pokok pemberi adalah sebagai berikut: Biaya tidak dapat dibebankan/saldo laba Rp 40.000.000 Akumulasi penyusutan kendaraan Rp 60.000.000 Kendaraan Rp 100.000.000 Sedangkan ayat jurnal bagi penerima hibah adalah: Kendaraan Rp 40.000.000 Modal Hibahan Rp 40.000.000 2. Tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) Dalam hal tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) pemberian hibah tersebut dimaksudkan menjadi penghasilan bagi yang menerimanya karena ternyata pemberian hibah ini mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak penerima hibah. Transaksi hibah ini dipandang sebagai transaksi pertukaran, sehingga dasar pengukurannya harga pasar.
Contoh : yang lalu, ayat jurnal yang disusun dan pemberi adalah sebagai berikut: Biaya hibah Rp 55.000.000 Akumulasi penyusutan kendaan Rp 60.000.000 Kendaraan Rp 100.000.000 Keuntungan dari hibah kendaraan Rp 15.000.000 Sedangkan ayat jurnal bagi penerima hibah adalah: Kendaraan Rp 55.000.000 Penghasilan hibah Rp 55.000.000 HARGA PEROLEHAN ASET TETAP BERWUJUD Aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset tersebut sampai aset siap untuk digunakan Aset tetap berwujud, termasuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tanah Bangunan/Gedung Mesin dan Alat-alat Alat-alat Kerja Pattern dan Dies/Cetakan Perabot/Mebelair dan Alat-alat Kantor Kendaraan Tempat Barang yang Dapat Dikembalikan/Returnable Container
BIAYA-BIAYA SELAMA MASA PENGGUNAAN ASET TETAP 1. 2. 3. 4. 5. Reparasi dan Pemeliharaan Penggantian Perbaikan/betterment/improvement Penambahan Penyusunan Kembali Aset Tetap/Rearrangement
PEMBERHENTIAN ASET TETAP Aset tetap bisa dihentikan penggunaannya dengan cara: 1. Dijual, 2. Ditukarkan, atau 3. Rusak Pada saat aset tetap diberhentikan dari pemakaian 1. semua rekening yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dihapuskan 2. apabila aset tetap tersebut dijual, maka selisih harga jual dengan nilai buku atau residu dicatat sebagai laba atau rugi.
Ilustrasi Mesin yang dibeli pada tanggal 1 Februari 2002 dengan harga Rp5.700.000,00; pada tanggal 1 Juli 2006 dijual dengan harga Rp1.200.000. Mesin tersebut ditaksir berumur 5 tahun, didepresiasi menggunakan metoda garis lurus, dan taksiran nilai residu Rp450.000,00. Penjualan pada tanggal 1 Juli 2006 dicatat: Depresiasi Mesin Akumulasi Depresiasi Mesin Rp 525.000 Rp 525.000
Depresiasi 6 bulan: 6/12 x 1/5 x (Rp5.700.000 Rp450.000) = Rp525.000 Kas Akumulasi Depresiasi Mesin Mesin Laba Penjualan Mesin Rp 1.200.000 Rp 4.637.500 Rp 5.700.000 Rp 137.500,00
Perhitungan Harga jual Nilai buku mesin: Harga perolehan Akumulasi depresiasi: 2002: 11 bulan = Rp962.500 2003: 12 bulan = 2004: 12 bulan = 2005: 12 bulan = 2006: 6 bulan = Laba penjualan aset tetap 1.050.000 1.050.000 1.050.000 525.000 (4.637.500) (1.062.500) Rp137.500 Rp5.700.000 Rp1.200.000
ASURANSI KEBAKARAN Asuransi diperlukan untuk melindungi kekayaan dari kemungkinan kerugian kebakaran, asuransi akan mengganti kerugian maksimum sebesar jumlah pertanggungan yang dinyatakan dalam polis. Perjanjian asuransi yang sudah berjalan dapat dibatalkan 1. pembatalan dilakukan oleh perusahaan asuransi, maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar jumlah premi untuk periode mulainya pembatalan sampai selesainya perjanjian (dengan dasar pro rata) pembataalan dilakukan oleh pihak yang mempertanggungkan, maka premi yang dikembalikan dihitung dengan tarif yang lebih rendah (short rate)
2.
ASURANSI BERSAMA Dengan syarat yang menyatakan bahwa apabila harta benda diasuransikan (dipertanggungkan) dengan jumlah yang lebih rendah dg persentase tertentu dari harga pasar benda tersebut saat terjadi kebakaran, maka perusahaan yg mengasuransikan akan menderita kerugian krn kebakaran sebanding dg selisih jumlah yg dipertanggungkan dg persentase tertentu dari harga pasar harta tersebut.
Jumlah kerugian yang akan diganti oleh perusahaan asuransi adalah nilai yang paling rendah dari jumlah berikut: 1. jumlah yang dibebankan kepada perusahaan asuransi yang dihitung dengan cara asuransi bersama 2. jumlah pertanggungan dalam polis, atau 3. jumlah kerugian yang sebenarnya
Ilustrasi Mesin diasuransikan sebesar Rp15.000.00. Suatu ketika mesin terbakar dengan kerugian Rp12.000.000. Pada saat kebakaran harga pasar mesin tersebut sebesar Rp30.000.000. Polis asuransi menyebutkan syarat asuransi bersama 80%. Perhitungan sbb: Coinsurance requirement: 80% x Rp30.000.000 = Jumlah pertanggungan Selisih Rp24.000.000 Rp15.000.000 Rp9.000.000
Kerugian sebesar Rp12.000.000,00 ditanggung oleh kedua belah pihak, masing-masing sebesar:
1. Perusahaan asuransi menanggung kerugian sebesar: Rp15.000.000 x Rp12.000.000 80% x Rp30.000.000 = Rp7.500.000
2. Pihak yang mengasuransikan menanggung kerugian sebesar: Rp9.000.000 x Rp12.000.000 80% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000
Apabila kerugian yang timbul lebih besar dari jumlah pertanggungan (Rp15.000.000), maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang timbul maksimum sebesar jumlah pertanggungan. Jika harta dipertanggungkan ke beberapa perusahaan asuransi, maka pertanggungan kerugian masing-masing perusahaan asuransi sebanding dengan jumlah pertanggungan total seluruh polis.
lustrasi Harta diasuransikan pada perusahaan asuransi sbb: Perusahaan asuransi A sebesar Rp12.000.000 Perusahaan asuransi B sebesar Rp3.000.000 Kerugian kebakaran sebesar Rp20.000.000,00. Perhitungan: Rp4.000.000,00 dan nilai harta pada saat kebakaran
a. apabila polis tanpa syarat asuransi bersama Ganti rugi dari perusahaan A Rp12.000.000 x Rp4.000.000 = (Rp12.000.000 + Rp3.000.000) Rp 3.200.000
Ganti rugi dari perusahaan B Rp3.000.000 x Rp4.000.000 = (Rp12.000.000 + Rp3.000.000) Rp 4.000.000, Rp 800.000,
b. apabila masing-masing polis dengan syarat asuransi bersama 80% Ganti rugi dari perusahaan A Rp12.000.000 x Rp4.000.000 = 80% x Rp20.000.000 Rp3.000.000
Ganti rugi dari perusahaan B Rp3.000.000 x Rp4.000.000 = 80% x Rp20.000.000 Rp3.750.000 Rp750.000
c. apabila polis dengan syarat asuransi bersama, perusahaan A 90% dan perusahaan B 80%
Ganti rugi dari perusahaan A Rp12.000.000 x Rp4.000.000 90% x Rp20.000.000 = Rp2.666.666,67
Ganti rugi dari perusahaan B Rp3.000.000 x Rp4.000.000 80% x Rp20.000.000 Rp3.416.666,67 = Rp750.000
POLIS GABUNGAN Bila perusahaan mengasuransikan beberapa aset dalam satu polis, maka polis tersebut akan menunjukkan syarat alokasi yang dasarnya adalah harga pasar aset-aset tersebut pada saat terjadinya kebakaran. Misalnya polis asuransi dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp30.000.000 untuk mesin dan bangunan, dengan syarat asuransi bersama 80%. Pada saat kebakaran yang melanda bangunan, harga pasar mesin Rp20.000.000 dan bangunan Rp40.000.000. Perhitungan ganti rugi bangunan adalah Alokasi pertanggungan Rp30.000.000 sebagai berikut: Mesin: (Rp20.000.000 /Rp60.000.000) x Rp30.000.000= Rp10.000.000 Bangunan: (Rp40.000.000/Rp60.000.000) x Rp30.000.000= Rp20.000.000 Coinsurance requirement: 80% x Rp40.000.000= Rp32.000.000 PerhitunganCoinsurance:(Rp20.000.000/Rp32.000.000)xRp40.000.000=Rp25.000.000 Karena jumlah pertanggungan yang dialokasikan untuk bangunan (Rp20.000.000) lebih rendah dari kerugian akibat terbakarnya bangunan (Rp40.000.000) dan hasil perhitungan coinsurance Rp25.000.000,00, maka ganti rugi sebesar Rp20.000.000
PENCATATAN ASURANSI KEBAKARAN Apabila terjadi kebakaran atas aset yng diasuransikan, maka langkah yang harus dilakukan untuk mengadakan pencatatan akuntansinya adalah 1. menyusun kembali catatan-catatan yang terbakar (jika ada) 2. menyesuaikan buku-buku agar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada saat terjadinya kebakaran 3. menentukan nilai buku aset yang terbakar 4. membebankan nilai buku aset yang terbakar dan biaya-biaya yang timbul pada saat kebakaran, ke rekening kerugian kebakaran 5. menentukan jumlah yang akan diterima dari perusahaan asuransi 6. rekening kerugian kebaakaran dikredit dengan jumlah ini dan jumlah yang diterima dari penjualan aset yang terbakar 7. menutup saldo rekening kerugian kebakaran ke rekening rugi laba. Saldo ini menunjukkan rugi atau laba dari kebakaran. 8. AKUNTANSI ASET TETAP TIDAK BERWUJUD Aset tidak berwujud dapat dikatagorikan sebagai aset tetap perusahaan, namun secara fisik aset tetap tsb tidak tampak. Oleh karean itu, disebut istilah tidak berwujud. Contoh hak paten. Penggolongan aset tidak berwujud, dibedakan sesuai sifat kekhususannya, masa manfaat, hubungan dengan kegiatan usaha dan penghapusannya. Sebagai dasar penggolongan aset tidak berwujud: 1. Kemampuan untuk diidentifikasi: dapat/tidak dapat diidentifikasi secara khusus 2. Cara perolehan: diperoleh secara individual, secara kelompok, melalui penggabungam badan usaha, atau dikembangkan sendiri 3. Masa manfaat yang diharapkan: tergantung pada pembatasan yang diatur oleh hukum atau perjanjian. 4. Kemampuan untuk dipisahkan dari keseluruhan perusahaan hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya.
PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yan dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva dibebankan secara bertahap. Kebijakan pajak (Tax Policy) untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal yaitu: Keadilan Pajak (Tax Equity) Kebijakan Ekonomi (Economic Policy) Administrasi (Admnistration)
Aktiva yang dapat disusustkan : Penggunaan dalam kegiatan usaha Nilainya menurun secara perlahan/bertahap Aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud Pihak yang berhak melakukan penyusutan Saat dilakukan penyusutan Dasar untuk melakukan penyusutan
PENYUSUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN Sebagimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antar pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial).
Persamaan Dan Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Persamaannya : Aktiva/harta tetap yang memberika manfaat lebih dari satu perode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Aktiva/harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap baik bangunan maupun bukan bangunan. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali tanah tersebut memeliki masa manfaat terbatas.
Perbedaannya:
Akuntansi Komersial
Akuntansi Fiskal
Masa Manfaat: 1. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis 2. Ditelaah ulang secara periodik 3. Nilai residu bisa diperhitungkan Harga Perolehan: 1. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya 2. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis memggunakan harga wajar 3. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas 4. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar
Masa Manfaat: 1. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 2. Nilai residu tidak diperhitungkan
Harga Perolehan: 1. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesuangguhnya 2. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar 3. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar 4. Dalam rangka lukidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau
penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan 5. Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi
Metode Penyusutan: 1. Garis lurus By. Penyu.= tarif penyu. X dasar perhitungan penyu. 2. Jumlah angka tahun By. Penyu.= tarif penyu. X dasar penghitungan penyu. Dsar penghitungan penyu.= hrga perolehan / nilai residu 3. Saldo menurun/menurun ganda By. Penyu. = tarif penyu. X dasar perhitungan penyu. Dsr penghitungan penyu. = harga sisa buku awal periode 4. Metode jam jasa Tarif penyu. per jam= hrg perolehan- nilai residu Estimade Service Life 5. Unit produksi Tarif penyu. = produksi sebenarnya kapasitas produksi By. Penyu. = tarif penyu. x dsr penyusutan Dsr penyu. = harga perolehan nilai residu 6. Anuitas 7. Sistem persediaan 8. Wajib pajak dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodik
Metode Penyusutan: 1. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus 2. Untukaktiva tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas
Sistem Penyusutan: 1. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan Saat dimulainya penyusutan: 1. Saat perolehan 2. Saat penyelesaian
Sistem Penyusutan: 1. Penyusutan individual 2. Penyusutan gabungan/group
Saat dimulainya penyusutan: 1. Saat perolehan 2. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan
HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN DALAM HAL TERJADI JUAL BELl HARTA Harta perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta ditentukan sebagai berikut: 1. Yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa: a. Bagi pihak pembeli, harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar; Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. b. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya diterima. 2. Yang dipengaruhi hubungan istimewa: a. Bagi pihak pembeli, harga perolehan harta adalah harga jumlah yang seharusnya dikeluarkan; b. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima. HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN DALAM HAL TERJADI TUKARMENUKAR HARTA Dalam hal terjadi transaksi tukar menukar harta dengan harta lain, maka nilai perolehan atau nilai penjualan harta tersebut adalah: 1. Bagi pihak pembeli, harga perolehan harta adalah harga yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar; 2. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang berdasarkan harga pasar (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PPh)
HARGA PEROLEHAN ATAU HARGA PENJUALAN DALAM HAL TERJADJ PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA LIKUIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN ATAU PENGAMBILAN USAHA Apabila terjadi pengalihan harta, penhlaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Di samping itu, pengalihan tersebut dapat pula dilakukaiuk dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya. Untuk memudahkan pembahasan perlu diketahui istilah: 1. Penggabungan usaha adalah penggabungan dan dua badan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. 2. Peleburan adalah penggabungan dan dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. 3. Pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian asset dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah: 1. Jumlah yang seharusnya dikeluarka atau diterima berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Contoh: PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dan kedua badan tersebut adalah sebagai berikut: PT A PTB Nilai sisa buku Rp 200.000.000 Rp 300.000.000 Harga pasar Rp 300.000.000 Rp 450.000.000 Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dan harta. Dengan demikian, PT A mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (Rp 300.000.000 - Rp 200.000.000) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000.000 (Rp 450.000.000 - Rp 300.000.000). Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp 750.000.000 (Rp 300.000.000+ Rp 450.000.000). Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (dengan menggunakan metode pooling of interest). Dalam hal demikian PT C membukukan penerimaan harta dan PT A dan PT B tersebut sebesar: Rp 200.000.000 + Rp 300.000.000 = Rp 500.000.000.
2. Penggunaan Nilai Buku Secara umum, penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha akan melibatkan pihak yang mengalihkan harta dan pihak yang memperoleh harta. Sesuai Akuntansi Komersial, metode yang digunakan dalam konsolidasi adalah : a. Penyatuan kepentingan (pooling of interest) b. Pembelian (purchase) Dalam akuntansi perpajakan digunakan metode pembelian (purchase method) atau berdasarkan harga pasar, sedang metode penyatuan kepentingan dapat digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan yang diacu yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK 04/1998 Tanggal 9 September 1998 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK 04/1998 Tanggal 30 Oktober 1998 dan terakhir diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999. Pengaturan tersebut meliputi: 1. Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta menurut keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah: a. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. b. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha, yang akan Go Public dengan melakukan penawaran umum perdana (initial public offeringIPO) di bursa efek. 2. Wajib Pajak yang menggunakan nilai buku dalam pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha diatas wajib memenuhi syarat: a. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan izin diajukan kepada Kanwil DJP yang membawahi KKP wajib pajak terdaftar selambatlambatnya 6 bulan sesudah proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dilakukan, yaitu dalam hal : 1.) Penggabungan atau peleburan, diajukan oleh Wajib Pajak menerima pengalihan harta. 2.) Pemekaran usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta. Jika Wajib Pajak terlambat mengajukan permohonan, maka tidak akan dipertimbangkan. Sebaliknya bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonannya telah memenuhi syarat (setelah penelitian dari konfirmasi) akan menerima surat keputusan persetujuan selambatlambatnya satu bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Sebaliknya bila terdapat penolakan, maka akan disertai pula alasan penolakan. Pihak yang memberikan persetujuan adalah kepala Kanwil atas nama Direktur Jenderal Pajak. b. Telah melunasi seluruh utang pajak dari setiap badan usaha yang terkait termasuk cabang/perwakilan yang terdaftar di KPP-KPP lokasi. c. Laporan keuangan Wajib Pajak khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta harus diaudit oleh Akuntan Publik.
3.
Sisa Kerugian Fiskal a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dapat mengalihkan kerugian/sisa kerugian fiskal, termasuk kerugian selisih kurs badan usaha lama yang belum dikompensasikan dengan syarat: 1.) Wajib Pajak badan usaha lama harus melakukan revaluasi aset tetap terlebih dahulu, menurut ketentuan yang berlaku; dan 2.) Wajib Pajak badan usaha yang lama dalam kondisi aktifmenjalankan kegiatan usahanya; dan 3.) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta harus tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha. b. Revaluasi aset tetap yang dimaksud tersebut meliputi sebagian atau seluruh aset tetap sesuai dengan keperluan untuk mengompensasikan kerugian fiskal semaksimal mungkin dengan selisih lebih revaluasi aset tetap yang dihasilkan. c. Kemungkinan terjadi kompensasi timbal balik (offset) utang piutang di antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha, maka: 1.) Penghapusan utang bagi pihak debitor bukan merupakan penghasilan. 2.) Penghapusan piutang bagi pihak kreditor bukan merupakan biaya. 4. Persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Jika pengalihan harta menggunakan nilai buku ternyata tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, maka pengalihan harta harus dinilai dengan harga pasar dan atas keuntungan yang diperolehnya dikenakan PPh. Demikian sebaliknya, jika pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak yang meneiima pengalihan harus mencatat nilai perolehannya sesuai dengan nilai buku yang tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan buku. Bagi Wajib Pajak yang sebelum penggabungan, peleburan, atau pemekaran telah melakukan revaluasi aset tetap, maka nilai buku yang dicatat adalah nilai buku setelah dilakukan revaluasi. 5. Penyusutan dan Amortisasi. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku di mana pengalihan harta terjadi, dilakukan secara prorata (perhitungan bulanan) yang didasarkan pada masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta. Penyusutan dan amortisasi tersebut dihitung secara prorata sampai dengan bulan dilakukannya pengalihan harta. Sedang dan pihak yang menerima pengalihan perhitungan prorata sebanyak sisa bulan setelah bulan pengalihan dengan menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang dianut Wajib Pajak yang bersangkutan. 6. Pajak Penghasilan Pasal 25. Kemungkinan penggabungan atau peleburan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima pengalihan, setelah penggabungan atau
peleburan usaha tidak boleh lebih dari penjumlahan PPh Pasal 25 dan seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan atau peleburan usaha. Apabila Wajib Pajak yang menerima pengalihan yaitu setelah penggabungan atau peleburan mengalami penurunan usaha, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan pengurangan PPh Pasal 25. 7. Kewajiban Menyampaikan SPT Kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan PPh bagi W ajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dalam tahun berjalan diatur : a. Kewajiban formal menyampaikan SPT Masa atau Tahunan PPh bagi wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha berakhir sampai dengan masa pajak/bagian tahun pajak dilakukannya penggabungan atau peleburan usaha. b. Kewajiban formal menyampaikan SPT Masa atau Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka manerima pengalihan harta dalam rangka peleburan dan pemekaran usaha, dimulai sejak Wajib Pajak terdaftar di KPP segera setelah pendirian badan usaha baru. 8. Surat Ketetapan Pajak Pemeriksaan pajak yang dilakukan setelah penggabungan atau peleburan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta yang menyangkaut tahun pajak sebelum tahun terjadinya penggabungan atau peleburan, maka surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan serta tindakan penagihan dan atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP badan usaha lama yang melakukan pengalihan harta qq nama dan NPWP badan usaha baru yang menerima pengalihan harta. 9. Penjualan Saham di Bursa Efek Jakarta Ketentuan Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di bursa efek dalam rangka pemekaran usaha: a. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku, harus sudah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang paling lama 2 (dua) tahun. c. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dan Direktur Jenderal Pajak. d. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut, maka nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
Sedangkan ketentuan bagi pemegang saham dan badan usaha lama yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha: a. Apabila pemegang saham dan badan usaha lama yang melakukan pengalihan harta menerima sejumlah saham baru dan badan usaha yang menerima pengalihan harta sebagai pengganti saham lama, maka atas penerimaan saham baru tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan dan nilai perolehan saham baru dicatat sebesar nilai saham lama. b. Apabila pemegang saham dan badan usaha lama yang melakukan pengalihan harta menerima sejumlah saham baru dan sejumlah uang dan badan usaha yang menerima pengalihan harta sebagai pengganti saham lama, maka penerimaan sejumlah uang tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan Paj ak Penghasilan dengan tarif umum. c. Apabila pemegang saham daribadan usaha lama yang melakukan pengalihan harta tidak setuju dengan rencana pengalihan harta tersebut dan pemegang saham dimaksud memilih menjual sahamnya, maka: 1.) atas selisih lebih antara harga perolehan dengan harga jual merupakan capital gain yang diterima pemegang saham tersebut dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.) atas selisih kurang antara harga perolehan dengan harga jual yang diterima pemegang saham tersebut dapat dibebankan sebagai biaya, dengan syarat sepanjang pemegang saham yang bersangkutan menyelenggarakan pembukuan. 10. Pengecualian Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 di atas dikecualikan dan pengenaan PPh apabila pengalihan hartanya berupa tanah dan atau bangunan. AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Karena Hibah, Bantuan atau Sumbangan, dan Warisan Apabila terjadi pengalihan harta karena hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, dengan syarat hibah, bantuan atau sumbangan tersebut tidak dalarn rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan, maka dasar penilaian atau nilai perolehan bagi pihak yang menerima pengalihan harta adalah: 1. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan Nilai perolehan adalah sama dengan nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak. Dengan demikian, yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan haurf b Undang-Undang PPh. Apabila tidak
memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar. 2. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan Dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan sebagai berikut : a. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak dapat diketahui, namun tahun perolehannya diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah : 1.) Apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, adalah sama besarnya dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 1986 atau 2.) Apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan; atau 3.) Apabila SPPT PBB tidak ada, adalah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) b. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pa)ak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) c. Untuk harta selain tanah dan atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama besarnya dengan 60% (enam puluh persen) dan harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan. Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan Sebagai Pengganti Penyertaan Modal Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta. Apabila terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan adalah sama dengan nilai pasar dan harta yang dialihkan tersebut. PEROLEHAN ASET MEMBANGUN SENDIRI Harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan pembangunan hingga siap pakai. Kemungkinan masalah yang timbul meliputi pembebanan biaya tidak langsung dengan alokasi secara proporsional, dan bunga selama masa
konstruksi dan penghematan biaya. IJntuk kepentingan perpajakan perlakuan akuntansi tetap dapat diikuti, tetapi bunga selama masa kontruksi (pembangunan) akan dikapitalisasi yang nantinya secara bertahap dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan. Masalah penghematan biaya misalnya dengan membangun sendiri menjadi lebih murah, selisihnya tidak diakui sebagai penghasilan. Sedangkan kerugian akibat nilai bangunan menjadi lebih tinggi diakui sebagai beban kerugian. METODE PENYUSUTAN SESUAI KETENTUAN PERPAJAKAN Aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten/taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyedikan daya banding hasil afiliasi perusahaan dan periode ke periode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu. Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 1. Metode garis lurus (straight line method), atau metode saldo menunrun (declining balance method) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan. 2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Aktiva Tetap merupakan aset suatu perusahaan yang berwujud, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Di dalam menilai kembali suatu aktiva tetap, nilai buku dan umur aktiva tetap harus disesuaikan. Aktiva tetap yang mau dijual harus diperhitungkan laba atau rugi nya yang berdasarkan perbandingan antara nilai buku aktiva tetap dengan harga jualnya.
Saran Setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan atas penyusutan aktiva tetap. Perlu adanya penialaian kembali untuk setiap aktiva tetap yang masih dapat dipakai walaupun nilai penyusutannya sudah habis. Perlu adanya pengetahuan tentang mengetahui akuntansi pajak dalam aset tetap.
BAB I PENDAHULUANAktiva tetap (fixed assets ) disebut juga Property, Plant and Equipment. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 14, hal 16.2 & 16.) Aktiva tetap adalah harta milik perusahaan yang digunakan secara terus menerus dan aktiva berwujud yang diperoleh dalam siap pakai atau d engan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan utnuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Keberadaan aktiva tetap disuatu perusahaaan benar-benar milik perusahaan dan bukan pinjam atau list. Apabila aktiva tetap dan penyusutan disajikan dalam laporan keuangan secara tidak wajar maka akan memberikan informasi yang menyesatkan bagi laporan keuang tersebut, untuk mengecek kebenarannya informasi laporan keuangan perlu dilakukan pemeriksaan akuntansi. Pemeriksaan terhadap aktiva tetap memerlukan waktu yang relative singkat dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan memeriksa pos lainnya. Hal ini dikarenakan pemeriksaan aktiva tetap hanya berputar di suatu tempat dalam arti tidak perlu konfirmasi pihak ketiga. S u a t u b e n d a b e r w u j u d h a r u s d i a k u i s e b a g a i s u a t u a k t i v a d a n d i k e l o m p o k a n s e b a g a i aktiva tetap bila: a. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitandengan aktiva tersebut akan mengalir kedalam perusahaan. b. Biaya perolehan aktiva dapat di ukur dari satu tahun. Aktiva tetap dalam perusahaan sangat penting, karena berpengaruh laporan keukang y a n g d i s a j i k a n p a d a s u a t u perusaahan tertentu. S e p e r t i a k u m u l a s i p e n yu s u t berpengaruh terhadap nilai buku yang disajikan dalam neraca dan beban penyusutan terhadap laporan penyusunan laporan rugi laba. Pemerikasaan terhadap aktiva tetap merupakan waktu yang relative singkat dan biaya yang murah dibandingkan jika memerlukan pos lainnya dimana a k t i v a t e t a p m e r u p a k a n s a l a h s a t u h a r t a p e r u s a h a a n ya n g d i p a k a i d a l a m k e g i a t a n operasional dan nilanya material yang harus dipertanggung jawabkan.
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo.2010. Akuntansi Pajak.Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT. bahwa penulis telah menyelesaikan tugas mata pelajaran Akutansi Pajak dengan membahas aktiva tetap dalam bentuk makalah. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak dosen mata kuliah akuntansi pajak yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini. 2. Orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga tugas ini selesai. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.