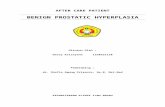Acp
description
Transcript of Acp
BAB I PENDAHULUAN
Angka kejadian penyakit alergi akhir-akhir ini meningkat sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat modern, polusi baik lingkungan maupun zat-zat yang ada di dalam makanan. Salah satu penyakit alergi yang banyak terjadi di masyarakat adalah penyakit asma. Asma merupakan penyakit inflamasi kronis saluran napas yang ditandai dengan mengi episodik, batuk, dan sesak di dada akibat penyumbatan saluran napas. Dalam 30 tahun terakhir prevalensi asma terus meningkat terutama di negara maju. Peningkatan terjadi juga di negara-negara Asia Pasifik seperti Indonesia. Studi di Asia Pasifik baru-baru ini menunjukkan bahwa tingkat tidak masuk kerja akibat asma jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat dan Eropa. Hampir separuh dari seluruh pasien asma pernah dirawat di rumah sakit dan melakukan kunjungan ke bagian gawat darurat setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan manajemen dan pengobatan asma yang masih jauh dari pedoman yang direkomendasikan Global Initiative for Asthma (GINA).Kasus asma meningkat insidennya secara dramatis selama lebih dari lima belas tahun, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Beban global untuk penyakit ini semakin meningkat. Dampak buruk asma meliputi penurunan kualitas hidup, produktivitas yang menurun, ketidakhadiran di sekolah, peningkatan biaya kesehatan, risiko perawatan di rumah sakit dan bahkan kematian. Asma merupakan sepuluh besar penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia, hal ini tergambar dari data Studi Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di berbagai propinsi di Indonesia. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1986 menunjukkan asma menduduki urutan ke-5 dari 10 penyebab kesakitan (morbiditas) bersama-sama dengan bronkitis kronik dan emfisema. Pada SKRT 1992, asma, bronkitis kronik dan emfisema sebagai penyebab kematian ke- 4 di Indonesia atau sebesar 5,6 %. Tahun 1995, prevalensi asma di seluruh Indonesia sebesar 13/1000, dibandingkan bronkitis kronik 11/1000 dan obstruksi paru 2/1000.Peran dokter dalam mengatasi penyakit asma sangatlah penting. Dokter sebagai pintu pertama yang akan diketuk oleh penderita dalam menolong penderita asma, harus selalu meningkatkan pelayanan, salah satunya yang sering diabaikan adalah memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kepada penderita dan keluarganya akan sangat berarti bagi penderita, terutama bagaimana sikap dan tindakan yang bisa dikerjakan pada waktu menghadapi serangan, dan bagaimana caranya mencegah terjadinya serangan asma.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
II.1. DefinisiAsma adalah keadaan saluran napas yang mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, yang menyebabkan peradangan; penyempitan ini bersifat sementara/reversible. Asma bronchial merupakan suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan jalan nafas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah baik secara spontan maupun hasil dari pengobatan.Asma didefinisikan menurut ciri-ciri klinis, fisiologis dan patologis. Ciri-ciri klinis yang dominan adalah riwayat episode sesak, terutama pada malam hari yang sering disertai batuk. Pada pemeriksaan fisik, tanda yang sering ditemukan adalah mengi. Ciri-ciri utama fisiologis adalah episode obstruksi saluran napas, yang ditandai oleh keterbatasan arus udara pada ekspirasi. Sedangkan ciri-ciri patologis yang dominan adalah inflamasi saluran napas yang kadang disertai dengan perubahan struktur saluran napas. Status asmatikus adalah keadaan darurat medik paru berupa serangan asma yang berat atau bertambah berat yang bersifat refrakter sementara terhadap pengobatan yang lazim diberikan. Refrakter adalah tidak adanya perbaikan atau perbaikan yang sifatnya hanya singkat, dengan pengamatan 1-2 jam.
Gambar 1. Anatomi dan Obstruksi Saluran Nafas Pada AsmaII.2. Patogenesis Pandangan tentang patogenesis asma telah mengalami perubahan pada beberapa dekade terakhir. Dahulu dikatakan bahwa asma terjadi karena degranulasi sel mast yang terinduksi bahan alergen, menyebabkan pelepasan beberapa mediator seperti histamin dan leukotrien sehingga terjadi kontraksi otot polos bronkus. Saat ini telah dibuktikan bahwa asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran napas yang melibatkan beberapa sel, menyebabkan pelepasan mediator yang dapat mengaktivasi sel target saluran napas sehingga terjadi bronkokonstriksi, kebocoran mikrovaskular, edema, hipersekresi mukus dan stimulasi refleks saraf.81. Inflamasi Saluran Napas Inflamasi saluran napas pada asma merupakan proses yang sangat kompleks, melibatkan faktor genetik, antigen, berbagai sel inflamasi, interaksi antar sel dan mediator yang membentuk proses inflamasi kronik dan remodelling.8 a. Mekanisme imunologi inflamasi saluran napas Sistem imun dibagi menjadi dua yaitu imunitas humoral dan selular. Imunitas humoral ditandai oleh produksi dan sekresi antibodi spesifik oleh sel limfosit B sedangkan selular diperankan oleh sel limfosit T. Sel limfosit T mengontrol fungsi limfosit B dan meningkatkan proses inflamasi melalui aktivitas sitotoksik cluster differentiation 8 (CD8) dan mensekresi berbagai sitokin. Sel limfosit T helper (CD4) dibedakan menjadi Th1dan Th2. Sel Th1 mensekresi interleukin-2 (IL-2), IL-3, Granulocytet Monocyte Colony Stimulating Factor (GMCSF), interferon- (IFN-) dan Tumor Necrosis Factor-(TNF-) sedangkan Th2 mensekresi IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-16 dan GMCSF. Respons imun dimulai dengan aktivasi sel T oleh antigen melalui sel dendrit yang merupakan sel pengenal antigen primer ( primary antigen presenting cells/ APC). b. Mekanisme limfosit T IgE Setelah APC mempresentasikan alergen/antigen kepada sel limfosit T dengan bantuan Major Histocompatibility (MHC) klas II, limfosit T akan membawa ciri antigen spesifik, teraktivasi kemudian berdiferensiasi dan berproliferasi. Limfosit T spesifik (Th2) dan produknya akan mempengaruhi dan me-ngontrol limfosit B dalam memproduksi imunoglobulin. Interaksi alergen pada limfosit B dengan limfosit T spesifik alergen akan menyebabkan limfosit B memproduksi IgE spesifik alergen. Pajanan ulang oleh alergen yang sama akan meningkatkan produksi IgE spesifik. Imunoglobulin E spesifik akan berikatan dengan sel-sel yang mempunyai reseptor IgE seperti sel mast, basofil, eosinofil, makrofag dan platelet. Bila alergen berikatan dengan sel tersebut maka sel akan teraktivasi dan berdegranulasi mengeluarkan mediator yang berperan pada reaksi inflamasi. c. Mekanisme limfosit T non IgE Setelah limfosit T teraktivasi akan mengeluarkan sitokin IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 dan GMCSF. Sitokin bersama sel inflamasi yang lain akan saling berinteraksi sehingga terjadi proses inflamasi yang kompleks, degranulasi eosinofil, mengeluarkan berbagai protein toksik yang merusak epitel saluran napas dan merupakan salah satu penyebab hiperesponsivitas saluran napas (Airway Hyperresponsiveness/AHR).
Gambar 2. Respon Imun Pada Asma
2. Hiperesponsivitas Saluran Napas Hiperesponsivitas saluran napas adalah respons bronkus berlebihan yaitu berupa penyempitan bronkus akibat berbagai rangsangan spesifik maupun nonspesifik. Respons inflamasi dapat secara langsung meningkatkan gejala asma seperti batuk dan rasa berat di dada karena sensitisasi dan aktivasi saraf sensorik saluran napas. Hubungan antara AHR dengan proses inflamasi saluran napas melalui beberapa mekanisme; antara lain peningkatan permeabilitas epitel saluran napas, penurunan diameter saluran napas akibat edema mukosa sekresi kelenjar, kontraksi otot polos akibat pengaruh kontrol saraf otonom dan perubahan sel otot polos saluran napas. Reaksi imunologi berperan penting dalam patofisiologi hiperesponsivitas saluran napas melalui pelepasan mediator seperti histamin, prostaglandin (PG), leukotrien (LT), IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 dan protease sel mast sedangkan eosinofil akan melepaskan platelet activating factor (PAF), major basic protein (MBP) dan eosinophyl chemotactic factor (ECF).8
Gambar 3. Penyempitan Saluran Napas Pada Asma
3. Sel Inflamasi Banyak sel inflamasi terlibat dalam patogenesis asma meskipun peran tiap sel yang tepat belum pasti. Sel inflamasi yang berperan antara lain adalah sel mast, makrofag, eosinofil, neutrofil, limfosit T, basofil, sel dendrit, dan sel-sel struktural.4. Mediator Inflamasi Banyak mediator yang berperan pada asma dan mem-punyai pengaruh pada saluran napas. Mediator tersebut antara lain histamin, prostaglandin, PAF, leukotrien dan sitokin yang dapat menyebabkan kontraksi otot polos bronkus, peningkatan kebocoran mikrovaskular, peningkatan sekresi mukus dan penarikan sel inflamasi. Interaksi berbagai mediator akan mempengaruhi AHR karena tiap mediator memiliki beberapa pengaruh. Histamin Prostaglandin Platelet activating factor (PAF) Leukotrien Sitokin Endotelin Nitric oxide (NO) Radikal bebas oksigen Bradikinin Neuropeptida Adenosin 5. Mekanisme Saraf Berbagai proses yang terjadi pada asma dapat disebabkan melalui mekanisme saraf yaitu mekanisme kolinergik, adrenergik dan non adrenergik non kolinergik. Kontrol saraf pada saluran napas sangat kompleks. a. Mekanisme kolinergik Saraf kolinergik merupakan bronkokonstriktor saluran napas dominan pada binatang dan manusia. Peningkatan refleks bronkokonstriksi oleh kolinergik dapat melalui neurotransmiter atau stimulasi reseptor sensorik saluran napas oleh modulator inflamasi seperti prostaglandin, histamin dan bradikinin.b. Mekanisme adrenergik Saraf adrenergik melakukan kontrol terhadap otot polos saluran napas secara tidak langsung yaitu melalui katekolamin/epinefrin dalam tubuh. Mekanisme adrenergik meliputi saraf simpatis, katekolamin dalam darah, reseptor adrenergik dan reseptor adrenergik. Perangsangan pada reseptor adrenergik menyebabkan bronkokonstriksi dan perangsangan reseptor adrenergik akan menyebabkan bronkodilatasi.c. Mekanisme nonadrenergik nonkolinergik (NANC) Terdiri atas inhibitory NANC (i-NANC) dan excitatory NANC (e-NANC) yang menyebabkan bronkodilatasi dan bronkokonstriksi. Peran NANC pada asma belum jelas, diduga neuropeptida yang bersifat sebagai neurotransmiter seperti substansi P dan neurokinin A menyebabkan peningkatan aktivitas saraf NANC sehingga terjadi bronkokonstriksi. Kemungkinan lain karena gangguan reseptor penghambat saraf NANC menyebabkan pemecahan bahan neurotransmiter yang disebut vasoactive intestinal peptide (VIP).8
II.3. Patofisiologi Pencetus serangan asma dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain alegen, virus, dan iritan yang dapat menginduksi respon inflamasi akut. Asma dapat terjadi melalui 2 jalur, yaitu jalur imunologis dan syaraf otonom. Jalur imunologis didominasi oleh antibodi IgE, merupakan reaksi hipersensitivitas tipe I (tipe alergi), terdiri dari fase cepat dan fase lambat. Reaksi alergi timbul pada orang dengan kecenderungan untuk membentuk sejumlah antibodi IgE abnormal dalam jumlah besar, golongan ini disebut atopi. Pada asma alergi, antibodi IgE terutama melekat pada permukaan sel mast pada interstisial paru, yang berhubungan erat dengan bronkiolus dan bronkus kecil. Bila sesorang menghirup alergen, terjadi fase sensitisasi, antibodi IgE orang tersebut meningkat. Alergen kemudian berikatan dengan antibodi IgE yang melekat pada sel mast dan menyebabkan sel ini berdegranulasi mengeluarkan berbagai macam mediator. Beberapa mediator yang dikeluarkan adalah histamin, leukotrien, faktor kemotaktik, eosinofil dan bradikinin. Hal itu akan menimbulkan efek edema lokal pada dinding bronkiolus kecil, sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus, dan spasme otot polos bronkiolus, sehingga menyebabkan inflamasi saluran nafas.1Pada reaksi alergi fase cepat, obstruksi saluran nafas terjadi segera yaitu 10-15 menit setelah pajanan alergen. Spasme bronkus yang terjadi merupakan respons terhadap mediator sel mast terutama histamin yang bekerja langsung pada otot polos bronkus. Pada fase lambat, reaksi terjadi setelah 6-8 jam, bahkan kadang-kadang sampai beberapa minggu. Sel-sel inflamasi seperti eosinofil, sel T, sel mast dan antigen precenting cell (APC) merupakan sel-sel kunci fdalam patogenesis asma.1Pada jalur syaraf otonom, inhalasi alergen akan mengaktifkan sel mast intralumen, makrofag alveolar, nervus vagus, dan mungkin juga epitel saluran napas. Peregangan vagal menyebabkan reflek bronkus, sedangkan mediator inflamasi yang dilepaskan oleh sel mast dan makrofag akan menbuat epitel saluran napas lebih permeabel dan memudahkan alergen masuk ke dalam submukosa, sehingga meningkatkan reaksi yang terjadi. Kerusakan epitel bronkus oleh mediator yang dilepaskan pada beberapa keadaan reaksi asma dapat terjadi tanpa melibatkan sel mast, misalnya pada hiperventilasi, inhalasi udara dingin, asap, kabut, dan SO2. Pada keadaan tersebut, reaksi asma terjadi melalui reflek syaraf. Ujung syaraf eferen vagal mukosa yang terangsang menyebabkan dilepasnya neuropeptid sensorik senyawa P, neurokinin A, dan Calcitonin Gen-Related Peptid (CGRP). Neuropeptida itulah yang menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi, edema bronkus, eksudasi plasma, hipersekresi lendir, dan aktifasi sel-sel inflamasi.1Hipereaktivitas bronkus merupakan ciri khas asma, besarnya hipereaktivitas bronkus tersebut dapat diukur secara tidak langsung, yang merupakan parameter objektif beratnya hipereaktivitas bronkus. Berbagai cara digunakan untuk mengukur hipereaktivitas bronkus tersebut antara lain dengan uji provokasi beban kerja, inhalasi udara dingin, inhalasi antigen, dan inhalasi zat nonspesifik.1
II.4. Faktor Resiko Secara umum faktor resiko asma dipengaruhi atas faktor genetik dan faktor lingkungan.11. Faktor genetik a. Atopi/alergiHal yang diturunkan adalah bakat alerginya, meskipun belum diketahui bagaimana cara penurunannya. Penderita dengan penyakit alergi biasanya mempunyai keluarga dekat yang juga alergi. Dengan adanya bakat alergi ini, penderita sangat mudah terkena penyakit asma bronkial jika terpajan dengan faktor pencetus.b. Hipereaktivitas bronkusSaluran napas sensitif terhadap berbagai rangsangan alergen maupun iritan. c. Jenis kelaminPria merupakan resiko untuk asma pada anak. Sebelum usia 14 tahun, prevalensi asma pada anak laki-laki adalah 1,5-2 kali dibanding anak perempuan. Tetapi menjelang dewasa perbandingan tersebut lebih kurang sama dan pada masa menopause perempuan lebih banyak.d. Ras/etnike. ObesitasObesitas atau peningkatan body mass index (BMI), merupakan faktor resiko asma. Mediator tertentu seperti leptin dapat mempengaruhi fungsi saluran napas dan meningkatkan kemungkinan terjadinya asma. Meskipun mekanismenya belum jelas, penurunan berat badan penderita obesitas dengan asma, dapat memperbaiki gejala fungsi paru, morbiditas dan status kesehatan.2. Faktor lingkungan a. Alergen dalam rumah (tungau, debu rumah, spora jamur, kecoa, serpihan kulit binatang seperti anjing, kucing, dan lain-lain).b. Alergen luar rumah (serbuk sari, dan spora jamur)3. Faktor laina. Alergen makanan Contoh: susu, telur, udang, kepiting, ikan laut, kacang tanah, coklat, kiwi, jeruk, bahan penyedap, pengawet dan pewarna makanan.b. Alergen obat-obatan tertentuContoh: penisilin, sefalosporin, golongan beta laktam lainnya, eritosin, tetrasiklin, analgesik, antipiretik, dan lain-lain.c. Bahan yang mengiritasiContoh:parfum, household spray, dan lain-lain.d. Ekspresi emosi berlebihStress/gangguan emosi dapat menjadi pencetus serangan asma, selain itu dapat memperberat serangan asma yang sudah ada. Disamping gejala asma yang timbul harus segera diobati, penderita asma yang mengalami stress/gangguan emosi perlu diberi nasihat untuk menyelsaikan masalah pribadinya. Karena jika stressnya belum diobati maka gejala asmanya lebih sulit diobati.e. Asap rokok bagi perokok aktif maupun pasifAsap rokok berhubungan dengan penurunan fungsi paru. Pajanan asap rokok, sebelum dan sesudah kelahiran berhubungan dengan efek berbahaya yang dapat diukur seperti meningkatkan resiko terjadinya gejala serupa asma pada usia dini.f. Polusi udara dari luar dan dalam ruangan g. Exercise-induced asthmaPada penderita yang kambuh asmanya ketika melakukan aktivitas/olahraga tertentu. Sebagaian besar penderita asma akan mendapat serangan jika melakukan aktiviatas jasmani atau olahraga yang berat. Lari cepat paling mudah menimbulkan serangan asma. Serangan asma karena aktivitas biasanya terjadi segera setelah selesai aktivitas tersebut.h. Perubahan cuacaCuaca lembab dan hawa pegunungan yang dingin sering mempengaruhi asma. Atmosfer yang mendadak dingin merupakan faktor pemicu terjadinya serangan asma. Serangan kadang-kadang berhubungan dengan musim, seperti: musim hujan, musin kemarau, musim bunga (serbuk sari beterbangan)i. Status ekonomi
II.5. Gambaran Klinis Gambaran klinis asma klasik adalah serangan episodik batuk, mengi, dan sesak napas. Pada awal serangan sering gejala tidak jelas seperti rasa berat di dada, dan pada asma alergik mungkin disertai pilek atau bersin. Meskipun pada mulanya batuk tanpa disertai sekret, tetapi pada perkembangan selanjutnya pasien akan mengeluarkan sekret baik yang mukoid, putih kadang-kadang purulen. Ada sebagian kecil pasien asma yang gejalanya hanya batuk tanpa disertai mengi, dikenal dengan istilah cough variant asthma. Bila hal yang terakhir ini dicurigai, perlu dilakukan pemeriksaan spirometri sebelum dan sesudah bronkodilator atau uji provokasi bronkus dengan metakolin.9Pada asma alergik, sering hubungan antara pemajanan alergen dengan gejala asma tidak jelas. Terlebih lagi pasien asma alergik juga memberikan gejala terhadap faktor pencetus non alergik seperti asap rokok, asap yang merangsang, infeksi saluran napas maupun perubahan cuaca.9 Lain halnya dengan asma akibat pekerjaan. Gejala biasanya memburuk pada awal minggu dan membaik menjelang akhir minggu. Pada pasien yang gejalanya tetap memburuk sepanjang minggu, gejalanya mungkin akan membaik bila pasien dijauhkan dari lingkungan kerjanya, seperti sewaktu cuti misalnya. Pemantauan dengan alat peak flow meter atau uji provokasi dengan bahan tersangka yang ada di lingkungan kerja mungkin diperlukan untuk menegakkan diagnosis.9
II.6. KlasifikasiSebenarnya derajat asma adalah suatu kontinum, yang berarti bahwa derajat asma persisten dapat berkurang atau bertambah. derajat gejala eksaserbasi atau serangan asma dapat bervariasi yang tidak tergantung dari derajat sebelumnya.1. Klasifikasi menurut etiologiBanyak usaha telah dilakukan untuk membagi asma menurut etilogi, terutama dengan bahan lingkungan yang mensensitisasi. Namun hal itu sulit dilakukan antara lain oleh karena bahan tersebut sering tidak diketahui.2. Klasifikasi menurut derajat berat asmaKlasifikasi asma menurut derajat berat berguna untuk menetukan obat yang diperlukan pada awal penanganan asma. Menurut derajat besar asma diklasifikasikan sebagai intermiten, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat.3. Klasifikasi menurut kontrol asmaKontrol asma dapat didefinisikan menurut berbagai cara. Pada umumnya, istilah kontrol menunjukkan penyakit yang tercegah atau sembuh. Namun pada asma, hal itu tidak realistis. Maksud kontrol adalah kontrol manifestasi penyakit. Kontrol yang lengkap biasanya diperoleh dengan pengobatan. Tujuan pengobatan adalah memperoleh dan mempertahankan kontrol untuk waktu lama dengan pemberian obat yang aman, dan tanpa efek samping. 4. Klasifikasi menurut gejalaAsma dapat diklasifikasikan pada saat tanpa serangan dan pada saat serangan. Tidak ada satu pemeriksaan tunggal yang dapat menentukan berat ringannya suatu penyakit. Pemeriksaan gejala-gejala dan uji faal paru berguna untuk mengklasifikasikan penyakit menurut berat ringannya. Klasifikasi itu sangat penting untuk penatalaksanaan asma. Berat ringan asma ditentukan oleh berbagai faktor seperti gambaran klinis sebelum pengobatan (gejala, eksaserbasi, gejala malam hari, pemberian obat inhalasi -2 agonis, dan uji faal paru) serta obat-obat yang digunakan untukmengontrol asma (jenis obat, kombinasi obat, dan frekuensi pemakaian obat). Asma dapat diklasifikasikan menjadi intermitten, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat (Tabel 1).Selain klasifikasi derajat asma berdasarkan frekuensi serangan danobat yang digunakan sehari-hari, asma juga dapat dinilai berdasarkan berat ringannya serangan. Global initiative for asthma (GINA) melakukan pembagian derajat serangan asma berdasarkan gejala dan tanda klinis, uji fungsi paru, dan pemeriksaan laboratorium. Derajat serangan menetukan terapi yang akan diterapkan. Klasifikasi tersebut adalah asma serangan ringan, asma serangan sedang, dan asma serangan berat (tabel 2). Dalam hal ini perlu adanya pembedaan antara asma kronik dengan serangan asma akut. Dalam melakukan penilaian berat ringannya serangan asma, tidak harus lengkap untuk setiap pasien. Penggolongannya harus diartikan sebagai prediksi dalam menangani pasien asma yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keterbatasan yang ada.1
Tabel 1. Klasifikasi derajat asma berdasarkan gejala pada orang dewasa1Derajat AsmaGejalaGejala MalamFaal Paru
intermittenBulanan Gejala 80%VEP1 80% nilai prediksi APE 80% nilai terbaikVariabilitas APE 20-30%
Persisten sedangHarian Gejala setiap hariSerangan menggangu aktivitas dan tidurBronkodilator setiap hari>2 kali sebulanAPE 60-80%-VEP1 60-80% nilai prediksi APE 60-80% nilai terbaik-Variabilitas APE >30%
Persisten beratKontinyu Gejala terus menerus Sering kambuhaktivitas fisik terbatasSering APE 60%VEP1 60% nilai prediksi APE 60% nilai terbaikVariabilitas APE >30%
Tabel 2. Klasifikasi Derajat Beratnya Serangan Asma9RinganSedangBerat
AktivitasDapat berjalanDapat berbaringJalan terbatasLebih suka dudukSukar berjalanDuduk membungkuk ke depan
BicaraBeberapa kalimatKalimat terbatasKata demi kata
KesadaranMungkin tergangguBiasanya terganggu Biasanya terganggu
Frekuensi napasMeningkatmeningkatSering >30 kali/menit
Retraksi otot-otot bantu napasUmumnya tidak adaKadang kala adaada
MengiLemah sampai sedangKeras Keras
Frekuensi nadi120
Pulsus paradoksusTidak ada (25 mmHg)
APE sesudah bronkodilator (% prediksi)>80%60-80%1000 g BDP atau ekuivalen) + LABA satu atau lebih obat berikut bila diperlukan Teofilin lepas lambat Anti leukotrin LABA oral Kortikosteroid oral Anti IgE
Pengobatan Asma Berdasarkan Sistem Wilayah Bagi PasienSistem pengobatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pasien mengetahui perjalanan dan kronisitas asma, memantau kondisi penyakitnya, mengenal tanda-tanda dini serangan asma, dan dapat bertindak segera mengatasi kondisi tersebut. Dengan mengunakan peak flow meter pasien diminta mengukur secara teratur setiap hari, dan membandingkan nilai APE yang didapat pada waktu itu dengan nilai terbaik APE pasien atau nilai prediksi normal.9Seperti halnya lampu pengatur lalu lintas, berdasarkan nilai APE akan terletak pada wilayah:9Hijau Berarti AmanNilai APE luasnya 80-100% nilai prediksi, variabilitas kurang dari 20%. Tidur dan aktivitas tidak terganggu. Obat-obat yang dipakai sesuai dengan tingkat anak tangga saat itu. Bila 3 bulan tetap hijau, pengobatan ini diturunkan ke tahap yang lebih ringan. Kuning Berarti Hati-HatiNilai APE luasnya 60-80% nilai prediksi, variabilitas 20-30%. Gejala asma masih normal, terbangun malam karena asma, aktivitas terganggu. Daerah ini menunjukkan bahwa pasien sedang mendapat serangan asma.sehingga obat-obat anti asma perlu ditingkatkan atau ditambah antara lain agonis beta 2 hirup dan bila perlu kortikosteroid oral. Mungkin pula tahap pengobatan yang sedang dipakai belum memadai, sehingga perlu dikaji ulang bersama dokternya. Merah Berarti BahayaNilai APE di bawah 60% nilai prediksi. Bila agonis beta 2 hirup tidak memberikan respon, segera mencari pertolongan dokter. Bila dengan agonis beta 2 hirup membaik, masuk ke daerah kuning, obat diteruskan sesuai dengan wilayah masing-masing. Pada wilyah merah, kortikosteroid oral diberikan lebih awal dan diberikan oksigen.9
BAB IIIBERKAS KELUARGA
III.1. Identitas Keluarga 1. Nama kepala keluarga: Tn.S2. Alamat rumah: Getaskumbang 3. Daftar Anggota Keluarga yang Tinggal dalam Satu Rumah :NoNamaKedudukan L/PUmurPendidikanPekerjaan
1.SutiminSuamiL64 thSDPedagang
2.NgatminiIstriP60 thSDPedagang
4. Family map :SuamiIstri
5. Bentuk keluarga :Keluarga inti6. Siklus kehidupan keluarga : Keluarga lanjut usia7. Deskripsi identitas keluarga :Keluarga ini adalah keluarga inti yang terdiri dari 2 orang dalam satu rumah, yang terdiri atas suami selaku kepala keluarga, serta istrinya. Rata-rata pendidikan di keluarga kurang, yaitu pendidikan terakhir lulusan SD. Kedua anak bapak tersebut tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, melainkan tinggal di luar kota.
III.2 Identifikasi Fungsi-Fungsi Keluarga1. Fungsi BiologisPasien adalah seorang perempuan berusia 64 tahun mengalami penyakit asma bronkial dengan keluhan sesak napas akibat kedinginan2. Fungsi PsikologiPasien tinggal bersama istrinya. Pasien sangat dekat dengan istrinya3. Fungsi EkonomiPasien adalah seorang pedagang4. Fungsi PendidikanPasien sudah tidak menjalani pendidikan5. Fungsi ReligiusPasien dan keluarganya adalah seorang muslim yang taat beragama, selalu menjalankan ibadah sholat lima waktu6. Fungsi Sosial BudayaPasien aktif terjun ke masyarakat, seperti bersilaturahmi dengan penduduk sekitar, tidak sombong dalam bersikap, dan bekerja keras. Kedudukan keluarga di tengah lingkungan sosial adalah warga biasa, namun keluarga pasien cukup dikenal bersosialisasi dengan kalangan di rumahnya.
III.3. Pola Konsumsi PasienFrekuensi makan pasien ratarata setiap harinya 3x/hari dengan variasi makanan sebagai berikut: nasi, lauk (tempe, tahu, telur, ayam), sayur (bayam, kangkung, kacang panjang, sayur labu, dan sayuran lainnya).
III.4 Identifikasi Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan 1. Faktor PerilakuPerilaku pasien terhadap kesehatan adalah apabila pasien sakit, pasien akan langsung berobat ke dokter, dan untuk dana kesehatan pasien dengan pembiayaan sendiri. 2. Faktor Non-PerilakuSarana pelayanan kesehatan di sekitar rumah cukup dekat yaitu RSUD Ambarawa. Jarak rumah ke RSUD Ambarawa kurang lebih 5 km. Jika ingin berobat pasien terbiasa untuk naik motor pribadi dari rumahnya.
III.5 Keadaan Rumah 1. Jenis lantai : Tanah2. Jenis atap : Asbes3. Jenis dinding : Tembok dilapisi cat4. Perbandingan luas jendela/lantai di ruang tidur < 20%5. Perbandingan luas jendela/lantai di ruang keluarga < 20%
III.6 Identifikasi Lingkungan RumahPasien tinggal di perumahan kavling bersama keluarganya. Kawasan perumahan pasien merupakan kawasan layak huni. Rumah berada di dalam gang yang cukup besar yaitu kurang lebih 3 meter dan terbuat dari tanah dengan kebersihan lingkungan pemukiman yang kurang baik karena banyak debu. Rumah tidak bertingkat, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi. Lantai rumah pasien berupa semen yang diplester dan keramik. Dinding rumah pasien berupa tembok dilapisi cat dan atap rumah pasien ditutupi oleh asbes dengan langit-langit.Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah dengan jumlah cukup. Rumah mempunyai ventilasi dan setiap kamar mempunyai jendela. Kebersihan dan kerapian rumah kurang. Di dalam kamar mandi terdapat sebuah jamban jongkok dan sebuah kran air serta bak mandi. Air minum, air untuk mencuci dan masak didapat dari air pam. Saluran air dialirkan ke got depan rumah yang mengalir dan tidak mengambang. Keluarga pasien memiliki sebuah TV 14 inch, kompor gas, setrika dan radio.
BAB IVLAPORAN HASIL KUNJUNGAN
IV.1. Identitas Nama: Tn. SUsia: 64 tahunTanggal Lahir: 31 Desember 1950Jenis Kelamin: Laki-lakiAgama: IslamStatus : MenikahPendidikan: SDPekerjaan: SwastaAlamat: Getaskumbang 1/5 Jatirunggo Pringapus, SemarangNo. RM: 074937Bangsal/Kelas: Teratai/IIITanggal Masuk: 21 Februari 2015 Tanggal Keluar: 23 Februari 2015
IV.2. AnamnesaIV.2.1. Keluhan Utama Pasien datang dengan keluhan sesak napas 1 hari SMRS
IV.2.2. Riwayat Penyakit SekarangPasien datang ke IGD RSUD Ambarawa dengan keluhan sesak nafas sejak 1 hari SMRS. Sesak timbul bertahap setelah pasien kehujanan, terdengar . Sebelumnya pasien sering sesak nafas jika suasana dingin atau kelelahan. Pasien menyangkal sering sesak napas sejak kecil. Pasien mulai sering sesak napas pada usia 40 tahun. Awalnya sesak napas hanya timbul satu bulan sekali tapi lama-lama frekuensi sesak semakin sering terutama dua tahun terakhir ini. Pasien juga mengeluh batuk tidak berdahak bersamaan dengan sesaknya. Dahak diakui sulit untuk dikeluarkan. Pasien mengaku sudah pernah mengobati keluhannya ke Polikinik Penyakit Dalam RSUD Ambarawa, namun pasien lupa nama obatnya. Adanya demam, kaki bengkak, ataupun sesak saat beraktivitas disangkal oleh pasien. IV.2.3. Riwayat Penyakit DahuluPasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Penyakit jantung, penyakit paru, DM disangkal oleh pasien. Pasien memiliki terhadap debu.
IV.2.4. Riwayat Penyakit Keluarga :Pasien tidak mengetahui apakah terdapat anggota keluarga yang pernah mengalami keluhan serupa. Riwayat hipertensi, DM, penyakit jantung dalam keluarga disangkal.
IV.2.5. Riwayat Pengobatan :Pasien mencoba mengobati keluhannya dengan memeriksakan diri ke poliklinik RSUD Ambarawa. Pasien telah diberikan obat namun lupa nama obatnya.
IV.2.6. Riwayat Kebiasaan :Pasien tidak mengkonsumsi alkohol, memiliki kebiasaan merokok, dan memiliki pola makan teratur 3 kali sehari.
IV.2.7. Riwayat Sosial Ekonomi :Pasien saat bekerja lepas dan tinggal di lingkungan rumah yang padat penduduk dan cukup bersih.
IV.3. Pemeriksaan FisikKeadaan Umum : Tampak sakit sedangKesadaran: Compos mentisTanda Vital:Tekanan darah: 130/80 mmHgNadi: 102 kali/menitResprasi: 28 kali/menitSuhu: 36,8oCStatus Gizi: Cukup baikKepala: Normocephal, rambut hitam tidak rontok, distribusi merataMata: Alis mata madarosis (-/-), bulu mata rontok (-/-), konjungtiva anemis (+/+), sklera ikterik (-/-), refleks pupil (+/+) isokor kanan dan kiri.Hidung: Sekret (-/-), epistaksis (-/-), napas cuping hidung (-/-)Telinga: Bentuk normal, nyeri tekan tragus (-/-), otore (-/-), darah (-/-)Mulut: Bibir kering (-), lidah kotor (-), tremor (-), tepi lidah hiperemis (+), tonsil (-), gigi geligi lengkap (+), mouth breathing (+)Leher: Pembesaran KGB (-), pembesaran tiroid (-), tidak ada peningkatan JVPParu Inspeksi: Dada simetris, tidak ada bagian dada yang tertinggal, retraksi suprasternal (+) Palpasi: Vokal fremitus kanan = kiri, tidak ada nyeri tekan Perkusi: Sonor di kedua lapang paru, batas paru-hepar setinggi ICS 5 Auskultasi: Suara dasar vesikuler +/+, Rhonki -/-, Wheezing +/+Jantung Inspeksi: Ictus cordis tidak tampak Palpasi: Ictus cordis tidak teraba Perkusi: Batas atas jantung pada ICS II linea sternalis sinistra, batas pinggang jantung pada ICS III linea para sternalis sinistra, batas kanan bawah jantung pada ICS V linea sternalis dextra, dan batas kiri jantung ICS V 2 cm medial linea midclavicularis sinistra Auskultasi: S1 > S2 murni reguler, tidak ada suara tambahanAbdomen Inspeksi: Perut cembung, tidak nampak benjolan, tidak nampak striae, tidak nampak caput medusa Palpasi: Nyeri tekan (-), tidak teraba hepatosplenomegali, ballotement ginjal (-) Perkusi: Bunyi timpani di seluruh lapang abdomen, shifting dullness (-) Auskultasi: Bising usus (+) normal 12 kaliAnggota gerak : Edema -/-, refleks fisiologis +/+, refleks patologis -/-, Pulsasi a.dorsalis pedis: kanan dan kiri dalam batas normal a. poplitea: kanan dan kiri dalam batas normal a. tibialis posterior: kanan dan kiri dalam batas normalSensibilitas : Dalam batas normal
IV.4. ResumePasien datang ke IGD RSUD Ambarawa dengan keluhan sesak nafas sejak 1 hari SMRS. Sesak timbul bertahap setelah pasien kehujanan, terdengar . Sebelumnya pasien sering sesak nafas jika suasana dingin atau kelelahan. Pasien menyangkal sering sesak napas sejak kecil. Pasien mulai sering sesak napas pada usia 40 tahun. Awalnya sesak napas hanya timbul satu bulan sekali tapi lama-lama frekuensi sesak semakin sering terutama dua tahun terakhir ini. Pasien juga mengeluh batuk tidak berdahak bersamaan dengan sesaknya. Dahak diakui sulit untuk dikeluarkan. Pasien mengaku sudah pernah mengobati keluhannya ke Polikinik Penyakit Dalam RSUD Ambarawa, namun pasien lupa nama obatnya. Adanya demam, kaki bengkak, ataupun sesak saat beraktivitas disangkal oleh pasien. Pasien pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Penyakit jantung, penyakit paru, DM disangkal oleh pasien. Pasien memiliki terhadap debu.
IV.5. Diagnosa KerjaAsma bronkiale intermitten derajat serangan sedang
IV.6. Penatalaksanaan Oksigen 3 liter/menit (nasal canule) Nebulizer agonis B2 kerja cepat (salbutamol) per 20 menit dalam 1 jam evaluasi setelah 1 jam Salbutamol 2 x 2 mg Glukokortikoid sistemik injeksi dexamethason 1 amp / 8 jam Infus D5 20 tpm + aminofilin drip 2 amp
IV.7. Hasil Kunjungan Pasca PerawatanDalam kunjungan ke rumah pasien pasca perawatan, pasien mengaku sudah tidak mengalami serangan sesak napas seperti yang dialami sebelumnya. Kami datang dan memberikan edukasi tambahan mengenai penyakit yang diderita pasien serta bagaimana cara menghindari serangan berikutnya, yaitu dengan menghindari faktor-faktor risiko maupun pencetus. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan serangan asma adalah genetik (atopi/alergi), obesitas, alergen di dalam rumah yaitu tungau, debu rumah, spora jamur, atau serpihan kulit/bulu binatang, alergen di luar rumah seperti serbuk sari atau jamur, alergen makanan, alergen obat-obatan tertentu, bahan-bahan iritan seperti parfum dan household spray, ekspresi emosi berlebih, asap rokok, polusi udara, exercise berlebihan, serta cuaca dingin dan lembab. Kami juga memberikan edukasi mengenai pengobatan yang dapat dilakukan jika sewaktu-waktu dapat terjadi serangan, yaitu misalnya dengan penggunaan inhaler bronkodilator untuk melegakan bronkus apabila mengalami hiperesponsivitas dan menganjurkan agar pasien memeriksakan diri ke dokter. Pasien mengaku telah mengerti penjelasan yang diberikan oleh kami dan akan memperhatikan pola hidup serta menghindari faktor pencetus serangan asma.
BAB VPEMBAHASAN
Asma adalah keadaan saluran napas yang mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, yang menyebabkan peradangan; penyempitan ini bersifat sementara/reversible. Asma bronchial adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan jalan nafas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah baik secara spontan maupun hasil dari pengobatan.Asma didefinisikan menurut ciri-ciri klinis, fisiologis dan patologis. Ciri-ciri klinis yang dominan adalah riwayat episode sesak, terutama pada malam hari yang sering disertai batuk. Pada pemeriksaan fisik, tanda yang sering ditemukan adalah mengi. Ciri-ciri utama fisiologis adalah episode obstruksi saluran napas, yang ditandai oleh keterbatasan arus udara pada ekspirasi. Sedangkan ciri-ciri patologis yang dominan adalah inflamasi saluran napas yang kadang disertai dengan perubahan struktur saluran napas.Dalam kasus ini, pasien datang dengan keluhan sesak nafas sejak 1 hari SMRS. Sesak timbul bertahap setelah pasien kehujanan, terdengar . Sebelumnya pasien sering sesak nafas jika suasana dingin atau kelelahan. Pasien menyangkal sering sesak napas sejak kecil. Pasien mulai sering sesak napas pada usia 40 tahun. Awalnya sesak napas hanya timbul satu bulan sekali tapi lama-lama frekuensi sesak semakin sering terutama dua tahun terakhir ini. Pasien juga mengeluh batuk tidak berdahak bersamaan dengan sesaknya. Dahak diakui sulit untuk dikeluarkan. Pasien hanya dapat berbcara kalimat sepenggal-sepenggal dan pasien lebih nyaman dalam posisi duduk. Pasien mengaku pernah mengalami keluhan serupa, dimulai beberapa tahun lalu saat pasien sudah tua. Pada pemeriksaan fisik ditemukan peningkatan nadi sebanyak 102 kali, adanya retraksi otot bantuan napas, dan pada palpasi ditemukan adanya bunyi wheezing pada kedua lapang paru di bagian tengah. Hal-hal yang telah disebutkan diatas membantu mendukung penegakan diagnosa asma bronkiale. Pasien diberikan pengobatan berupa salbutamol sebagai reliever, dan dexamethason sebagai controller.Hasil dari penanganan pasien ini selama tiga hari sangat memuaskan. Outcome yang bagus timbul karena penanganan yang tepat cepat dan dukungan dari pasien dan keluarga pasien yang banyak berperan dalam kesembuhan pasien. Pasien disarankan untuk kontrol rawat jalan di Poli Penyakit Dalam, tiga hari setelah diperbolehkan pulang dari ruang rawat inap.
DAFTAR PUSTAKA
1. Rengganis, I. 2008. Diagnosis Dan Tatalaksana Asma Bronkhiale. Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UI: Jakarta, Majalah Kedokteran Indonesia, Volume: 58; No.11;Nopember 2008.2. Baratawidjaja KG, Soebaryo RW, Kartasasmita CB, Suprihati, Sundaru H, Siregar SP, et al. Allergy And Asthma, The Scenario In Indonesia. In: Shaikh WA. Editor. Principles And Practice Of Tropical Allergy And Asthma. Mumbai: Vicas Medical Publisher; 2006.707-363. Anonim. 2009. Patofisiologi asma.http://ayosz.wordpress.com/2009/01/07/patofisiologi-asma/4. Ohrui T, Yasuda H, Yamaya M, Matsui T, Sasaki H. Transient Relief Of Asthma Symptoms During Jaundice: A Possible Beneficial Role Of Bilirubin. Department of Geriatric and Respiratory Medicine, Tohoku University School of Medicine5. Tanjung, D. 2008. Asma bronhkiale. http://forbetterhealth.wordpress.com/author/forbetterhealthy/asma-bronkhiale diakses tanggal 20 Februari 20156. Healthzone. 2008. Asma bronkhiale. http://puskesmas-oke.blogspot.com/2008/12/asma-bronkial.html di akses tanggal 20 Februari 20157. Alsagaff, H., Mukty, A. 2009. Anatomi dan Faal Pernapasan dalam Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Paru, Edisi 6. Airlangga University Press: Surabaya8. Rahmawati, I., Yunus, F., Wiyono, WH. 2003. Artikel: Tinjauan Kepustakaan Patogenesis dan Patofisiologi Asma. Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Persahabatan: Jakarta, Cermin Dunia Kedokteran No. 141, 2003 9. Sukamto, Sundaru, H. 2006. Asma Bronkhiale Dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta
1