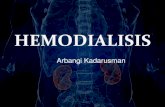9. BAB II - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2008-2-00005-AK Bab 2.pdf11 yang berlaku....
Transcript of 9. BAB II - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2008-2-00005-AK Bab 2.pdf11 yang berlaku....
8
BAB II
LANDASAN TEORI
Pendahuluan
Pembahasan Pengendalian Internal berkaitan erat dengan proses pemeriksaan
akuntansi, sebab untuk dapat memahami secara sepenuhnya dan sekaligus memberi
masukan yang bermanfaat, seorang Auditor dituntut untuk memahami pengendalian
internal. Hal ini disinggung oleh James A. Hall (2007), yaitu bahwa komponen
pengendalian internal – lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan
komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian (selanjutnya dibahas pada hal.
23) – menyediakan informasi yang penting mengenai resiko penyalahsajian yang
penting dalam laporan keuangan dan penipuan. Para auditor karenanya diharuskan
untuk mendapat pengetahuan yang memadai atas pengendalian internal untuk
merencanakan audit mereka. Contohnya, pengendalian internal di perusahaan
mempengaruhi cara auditor akan menilai apakah perusahaan telah melaporkan semua
kewajibannya. Auditor harus memahami bagaimana penjualan dilakukan, diproses,
dicatat. Struktur pengendalian internal menyediakan informasi ini dan membimbing
auditor dalam perencanaan berbagai pengujian tertentu untuk menetapkan
kecendrungan dan keluasaan penyalahsajian laporan keuangan.
Oleh karena hal tersebut diatas, maka penulis terlebih dahulu akan mengupas
mengenai pengertian pemeriksaan akuntansi. Selanjutnya penulis akan membahas
mengenai pengendalian internal.
9
II.1 Pengertian Audit Secara Umum
II.1.1 Definisi Audit
Beberapa definisi audit yang penulis kutip dari beberapa sumber menuliskan
bahwa, antara lain:
1. Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf (2003):
“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilaksanakan
oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan
melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah
ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan seorang yang independen dan
kompeten” (h. 1).
2. Sedangkan menurut Agoes S. (1999):
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis
oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun
oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut”.
3. Menurut Arens, Elden, dan Beasley (2006):
“Auditing is an the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on degree of correspondence between the information,
and established criteria. Auditing should be done by a component, independent
person“ (p. 4).
10
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah
suatu proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi
mengenai kejadian ekonomi, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan
independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi
tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dimana hasilnya akan
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
II.1.2 Tujuan Audit
Tujuan audit laporan keuangan oleh auditor independen secara umum meliputi:
a. Menyatakan pendapat dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan;
yang dalam segala hal yang material, atas posisi laporan keuangan, hasil
operasi, perubahan modal dan arus kas perusahaan, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku.
b. Menambah kredibilitas laporan keuangan.
c. Memberikan keyakinan pada direksi dan para pemegang saham bahwa
harta perusahaan telah dikelola dengan baik dan aman.
d. Mengidentifikasikan area dimana efisiensi dapat diperbaiki dan
penghematan biaya dapat dilakukan.
Audit laporan keuangan juga dapat memiliki manfaat lainnya, yaitu :
a. Menyediakan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dalam
informasi akuntansi yang disusun berdasarkan kriteria yang diinginkan
oleh para pihak pemakai laporan keuangan.
b. Memberikan motivasi kepada para penyusun laporan keuangan untuk
mencatat proses akuntansi dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi
11
yang berlaku. Jika disajikan secara tidak benar, maka akan dapat diketahui
saat dilakukan audit.
Proses Audit bertujuan untuk menilai asersi manajemen, yaitu:
1. Keberadaan atau Keterjadian (Existence or Occurrence)
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence)
berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas memang benar-
benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat benar-
benar telah terjadi selama periode tersebut.
2. Kelengkapan (Completeness)
Asersi mengenai kelengkapan (completeness) berkaitan dengan apakah
semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan
benar-benar telah dicantumkan.
3. Hak dan Kewajiban (Right and Obligation)
Asersi mengenai hak dan kewajiban (right and obligation) berkaitan
dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah
menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu.
4. Penilaian atau Alokasi (Valuation or Allocation)
Asersi mengenai penilaian atau alokasi (valuation or allocation) berkaitan
dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah
dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.
5. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure)
Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan (presentation and
disclosure) berkaitan dengan apakah komponen tertentu dalam laporan
12
keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapkan sebagaimana
mestinya.
II.1.3 Konsep Audit
Akuntansi merupakan cara pengumpulan data dan pengolahan data keuangan
yang penting untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan, laporan manajemen
atau ikhtisar-ikhtisar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan. Dengan demikian akuntansi mempunyai bentuk konstruktif, yaitu
melakukan pengolahan data yang belum seberapa berguna menjadi data yang cukup
berguna bagi para pemakainya.
Laporan keuangan di Indonesia yang disajikan berdasarkan data yang ada,
harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia,
sehingga laporan keuangan tersebut dapat mencerminkan keadaan atau posisi
keuangan yang wajar. SAK Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI), yang harus terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan akuntansi saat ini.
Di lain pihak, audit merupakan suatu proses yang sistematis dengan tujuan
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti sehubungan dengan tindakan dan
kejadian ekonomi yang dilakukan, untuk mendukung pendapat akuntan mengenai
kewajaran penyajian laporan keuangan atau manajemen yang dibuat oleh
perusahaan. Hal ini tentunya berbeda dengan proses yang terjadi pada penyusunan
laporan keuangan dan atau laporan manajemen.
Perbedaan proses ini terjadi karena pada saat proses, proses audit dimulai dari
laporan keuangan dan atau laporan manajemen yang tersedia, sehingga pada proses
yang dilakukan dalam audit dilakukan berlawanan dengan proses yang dilakukan
dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya perbedaan proses diatas dapat
disimpulkan bahwa audit hanya dapat dilakukan apabila :
13
1. Terdapat laporan keuangan dan atau laporan manajemen perusahaan yang
disusun sesuai dengan siklus yang memadai.
2. Terdapat tenaga pemeriksa yang memahami standar akuntansi maupun standar
audit yang memadai.
Di indonesia, audit atas laporan keuangan harus dilakukan sesuai dengan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang disusun oleh IAI.
II.1.4 Jenis-jenis Audit
Menurut Mulyadi (2002), dari jenis pemeriksaannya jenis-jenis audit dibagi
menjadi tiga yaitu:
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar
kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Hasil
auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis
berupa laporan audit.
2. Audit kepatuhan (Compliance Audit)
Audit bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan
kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit biasanya tidak dilaporkan kepada
pihak luar, tetapi kepada pihak-pihak tertentu dalam organisasi. Pimpinan
organisasi adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur
dan aturan yang telah ditetapkan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan merupakan review secara sistematik
kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan
tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja,
14
mengindentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi
untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit
operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional
diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut.
Menurut Agoes (2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
1. Pemeriksaan umum (General Audit)
Suatu pekerjaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan Kode Etik
Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh IAI serta
Standar Pengendalian Mutu (SPM).
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan auditee) yang dilakukan oleh
KAP yang independen, pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu
memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu
yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
15
II.1.5 Standar Audit
Karena akuntan publik memainkan peranan sosial yang sangat penting,
Manajemen KAP dan staf operasional mereka dituntut untuk berperilaku secara
pantas dan melaksanakan audit dan jasa lainnya dengan kualitas tinggi. IAI dan
organisasi terkait lainnya telah mengembangkan beberapa mekanisme untuk
meningkatkan kualitas audit dan perilaku profesional.
Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung
jawab profesinya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas
profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan
bahan bukti.
Pedoman utama adalah sepuluh standar auditing atau 10 generally auditing
standart – GAAS. Sejak disusun oleh AICPA ditahun 1947 dan diadaptasi oleh IAI
di Indonesia sejak 1973 yang sekarang disebut Standar Auditing Yang Ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI).
Kesepuluh standart auditing dibagi menjadi tiga kelompok standar. Standar
umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Kesepuluh standar ini
terdiri dari:
A. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi
dalam sikap harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
16
B. Standar Pekerjaan Lapangan
4. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan sebaik-baiknya.
5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang harus dilakukan.
6. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
C. Standar Pelaporan
7. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
8. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip
akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
9. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
10. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasan harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana
auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada,
dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.
17
II.2 Penjualan dan Penerimaan Kas
II.2.1 Pengertian penjualan Tunai
Menurut Mulyadi (2001), penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan
dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih
dahulu sebelum barang tersebut diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah
uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan
transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan (h. 255).
II.2.2 Pengertian penjualan Kredit
Menurut Mulyadi (2001), Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan
dengan cara mengirimkan barang sesuai order yang diterima dari pembelian dan
untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut
untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama
kepada pembeli selalu dengan evaluasi terhadap atau tidaknya pembeli tersebut
diberi kredit (h. 212).
II.2.3 Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas
Pemahaman atas fungsi yang terdapat dalam organisasi klien atas siklus
penjualan dan penerimaan kas, menurut Arens dan Loebbecke bermanfaat untuk
memahami bagaimana pelaksanaan audit dalam siklus ini, fungsi penjualan dan
penerimaan kas adalah sebagai berikut:
a. Pemrosesan pesanan pelanggan
Permintaan barang oleh pelanggan merupakan permintaan untuk membeli
barang dengan ketentuan tertentu. Permintaan pesanan pelanggan
menghasilkan pesanan penjualan.
18
b. Persetujuan penjualan secara kredit
Sebelum barang dikirim, seorang yang berwenang dalam perusahaan harus
menyetujui penjualan secara kredit ke pelanggan atas penjualan kredit tersebut.
Seleksi yang tidak ketat dalam persetujuan penjualan kredit seringkali
menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih.
c. Pengiriman barang
Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan saat barang dikirimkan. Nota
pengiriman disiapkan pada saat pengiriman dan dokumen pengiriman
diperlukan untuk kepastian penagihan atas barang yang dikirim ke pelanggan.
d. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan
Aspek terpenting dalam penagihan adalah untuk meyakini bahwa seluruh
pengiriman barang diperlukan sebagai dasar untuk mayakini penagihan atas
pengiriman ke pelanggan mencakup pembuatan faktur penjualan rangkap dan
copyan berkas transaksi penjualan dan berkas induk piutang usaha.
e. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas
Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, perhatian utama adalah
memungkinkan dicuri sebelum penerimaan kas dicatat. Pertimbangan utama
dalam penerapan penerimaan kas adalah seluruh kas disetor ke bank dalam
jumlah yang benar dengan tepat waktu dan dicatat di berkas termasuk berkas
penerimaan kas, yang digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas
memperbaharui berkas induk piutang usaha.
f. Pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan penjualan
Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterimanya, bagian
penjualan sering kali menerima pengambilan barang dan kemudian diberikan
pengurangan harga penjualan dan berkas induk piutang usaha.
19
g. Penghapusan piutang tak tertagih
Penghapusan piutang tak tertagih terjadi ketika perusahaan berkesimpulan
bahwa suatu jumlah akan tidak tertagih lagi, maka jumlah tersebut harus
dihapuskan dan biasa ini terjadi setelah pelanggan pailit dan piutang dialihkan
ke agen penagihan.
h. Penyisihan piutang tak tertagih
Penyisihan piutang tak tertagih merupakan gambaran dari penjualan sekarang
yang diperkirakan tidak dapat ditagih dimasa depan.
II.3 Sistem Pengendalian Internal
II.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian Internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk
menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.
Disamping itu, sistem pengendalian internal dapat mengendalikan ketelitian dan
akurasi pencatatan data akuntansi.
Definisi sistem pengendalian internal yang penulis kutip dari sumber
menuliskan bahwa :
1. Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway
Commission report, seperti dikutip oleh Bagnaroff, Moscove, Simkin (2001)
yaitu:
“A process, effected by a board of directors, management, and other
personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the
achievement of objectives in the following categories-effectiveness and
efficiency of operations,. Reliability of financial reporting, and compliance
laws and regulations”
20
Or Internal controls are the tools that managers use (but are often not
taught) to help achieve their business objective in the following categories:
• Effectiveness and efficiency of operations
• Reliability of financial reporting
• Complience with external laws and regulations” (p.211).
Definisi diatas dapat diartikan bahwa Pengendalian Internal adalah alat
yang digunakan oleh para manajer (tetapi jarang diajarkan) untuk
membantu dalam pencapaian tujuan usaha mereka dalam kategori berikut
ini :
• Efektivitas dan efisiensi operasional
• Keandalan dari laporan keuangan
• Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
2. Menurut Mulyadi (2002) yaitu:
“Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi” (h. 180).
Dari kedua definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar
Pengendalian Internal sebagai berikut :
a. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan
tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu
21
rangkaian tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi bagian tidak
terpisahkan.
b. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari
formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang
mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan
memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris
entitas. Kerterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian
internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian
tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat
memberikan keyakinan mutlak.
d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling
berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.
3. Menurut SPAP (2001) yaitu:
“Pengendalian internal adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini: (a)keandalan pelaporan keuangan, (b)efektifitas dan efisiensi
operasi, dan (c)kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku” (h.
319.2).
22
II.3.2 Unsur dan Tujuan Pengendalian Internal
Menurut Mulyadi (2001), unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan
yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (h.162).
Menurut tujuannya, pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua bagian,
yaitu:
1. Pengendalian internal akuntansi (internal accounting control)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa ketelitian dan
keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan
menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam
perusahaan serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
2. Pengendalian internal administrative (internal administrative control)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Gambar II.3 berikut ini menyajikan tujuan pokok dari pengendalian internal
23
Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Intern
Mengecek ketelitian danKeandalan data akuntansi
Mendorong dipatuhinyaKebijakan manajemn
Menjaga kekayaanorganisasi
Mendorong efisiensi
TujuanPengendalianInternAkuntansi
TujuanPengandalianInternAkuntansi
Gambar II.1 Tujuan pokok pengendalian internal
II.3.3 Struktur Pengendalian Internal
Unsur-unsur sistem pengendalian internal setiap perusahaan pada umumnya
adalah sama. Tetapi perbedaannya terletak pada dinamika interaksi unsur-unsur
tersebut untuk setiap perusahaan akan berbeda. Hal ini disesuaikan dengan industri
besar kecilnya perusahaan, dan falsafah manajemen.
Unsur-unsur pokok pengendalian internal perusahaan terdiri atas :
1. Lingkungan pengendalian (control environment)
Menurut Mulyadi (2002)
“Merupakan pengaruh gabungan dari faktor-faktor yang membentuk,
memperkuat atau memperlemah efektifitas kebijakan dan prosedur
tertentu” (h.183). Misalnya :
24
a. Falsafah manajemen dan gaya operasinya
b. Struktur organisasi perusahaan
c. Berfungsinya dewan komisaris dan komite yang dibentuk
d. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
e. Pengendalian manajemen dalam memantau kinerja kerja
f. Kebijakan dan praktek personalia
g. Faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan praktek perusahaan
Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran,
dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak lain
mengenai pentingnya pengendalian dan tekanan pada perusahaan yang
bersangkutan.
2. Penaksiran resiko (risk assessment)
Merupakan metode untuk mengidentifikasikan, menganalisa, dan
mengelola resiko yang relevan dalam penyusunan laporan. Resiko dapat
berubah atau timbul karena terjadinya perubahan dalam personel, lingkungan
bisnis, peraturan, tren pasar dan lain-lain.
3. Aktivitas pengendalian (control activities)
Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu menyakinkan
bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko
dalam mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas ini mencangkup :
a. Review atas kinerja
b. Pengendalian pengolahan informasi
c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
d. Pemisahan fungsi yang memandai
25
4. Informasi dan komunikasi (information processing and communication)
Merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang
dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi
perusahaan.
5. Pemantauan (monitoring)
Merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal
sepanjang waktu. Hal ini mencangkup penentuan desain dan operasi
pengendalian yang tepat waktu serta perbaikan terus menerus.
II.3.4 Keterbatasan Pengendalian Internal
A. Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002) mengidentifikasikan keterbatasan
yang melekat (inherent limitations) pada Pengendalian Internal (h. 376). Yaitu:
1. Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement)
Kadang-kadang, manajemen dan personnel lainnya dapat melakukan
pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam
melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi,
keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.
2. Gangguan (Breakdown)
Gangguan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personal
salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan,
kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam
personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada
terjadinya gangguan.
26
3. Kolusi (Collusion)
Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan
suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan yang lain,
konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan
sehingga tidak dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi
antara tiga karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan
penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau
jadwal pembayaran kembali kepada seorang karyawan dalam departemen
pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen
penjualan dengan pelanggan.
4. Pengabaian oleh manajemen (Management Override)
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk
tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai
kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan
(misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran
bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan
pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan hukum dan
peraturan). Praktik pengabaian (override) termasuk membuat penyajian
yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan
dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.
5. Biaya lawan manfaat (Cost Versus Benefit)
Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi
manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari
biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus
27
membuat sendiri estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam
mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.
B. Menurut SPAP (2001) yaitu:
16 Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya,
pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi
manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan
pengendalian internal entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi
oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini
mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan
keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena
kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan
yang sifatnya sederhana. Disamping itu, pengendalian dapat tidak efektif
karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen
mengesampingkan pengendalian internal.
17 Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya
pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan
dari pengendalian tersebut meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan
kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian
internal, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin
dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan
kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.
18 Adat-istiadat, kultur, dan corporate governance system dapat
mencegah terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun
tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. Lingkungan pengendalian
28
yang efektif juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakberesan
semacam itu. Sebagai contoh, dewan komisaris, komite audit, dan fungsi audit
internal yang efektif dapat mengurangi perbuatan yang tidak semestinya oleh
manajemen. Sebagai alternatif, lingkungan pengendalian dapat mengurangi
efektivitas komponen yang lain. Sebagai contoh, jika adanya insentif
manajemen menciptakan lingkungan yang dapat menghasilkan salah saji
material dalam laporan keuangan, efektifitas aktivitas pengendalian dapat
dikurangi. Efektivitas pengendalian internal entitas dapat juga dipengaruhi
secara negatif oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam kepemilikan dan
pengendalian perubahan manajemen atau personel lain, atau pengembangan
pasar atau industri entitas (h. 319.6).
II.4 Aktivitas Pengendalian Transaksi Penjualan
Pesanan penjualan dapat dilakukan secara over-the-counter, atau melalui
telepon, surat, representative penjualan traveling (traveling sales representative),
Fax, atau pertukaran data elektronik (electronic data interchange). Barang-barang
dapat diambil sendiri oleh pelanggan atau dikirimkan oleh penjual. Transaksi
penjualan ini biasanya dicatat dengan menggunakan sistem komputer yang dapat
memproses transaksi secara berurut atau dengan model pemrosesan batch. Aktivitas
pengendalian selama transaksi penjualan berlangsung disesuaikan dengan perubahan
situasi.
Dimulai dengan menjelaskan setiap fungsi yang terkait dalam pemrosesan
transaksi ini, dan bagaimana aktifitas pengendalian saling berhubungan satu sama
lain untuk mengurangi resiko salah saji dalam asersi laporan keuangan yang di
29
pengaruhi oleh transaksi penjualan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi sejumlah
dokumen dan catatan yang umumnya digunakan dalam pemrosesan transaksi ini.
II.4.1 Fungsi-fungsi
Fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan:
1. Fungsi Penjualan
Bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengedit order dari
pelanggan sehingga menjadi pesanan penjualan (sales order) dan meminta
otorisasi kredit.
2. Fungsi Kredit
Bertugas untuk memverifikasi kelayakan pemberian kredit.
3. Fungsi Gudang
Bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang dipesan oleh pelanggan,
serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.
4. Fungsi Pengiriman
Bertugas menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang
diterimanya dari fungsi penjualan, dan bertanggung jawab untuk menjamin
bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari
yang berwenang.
5. Fungsi Penagihan
Bertugas untuk memuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan,
serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan
oleh fungsi akuntansi.
30
6. Fungsi Akuntansi
Bertugas untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan baik
tunai maupun kredit, membuat dan mengirimkan pernyataan piutang kepada
para debitur serta membuat laporan penjualan dan untuk mencatat harga pokok
persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan.
II.4.2 Pengendalian Internal atas Fungsi Penjualan
Penjualan merupakan aktivitas yang penting didalam suatu perusahaan karena
dari penjualan diperoleh sumber pendapatan berupa laba untuk membiayai
kelangsungan hidup perusahaan. Siklus penjualan dimulai dari permintaan barang
oleh pelanggan sampai berpindahnya kepemilikan barang dari penjual ke pelanggan
dengan sistem pembayaran tunai ataupun dengan pembayaran kredit.
Menurut Mulyadi (2001):
“Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik
secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order
dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa,
untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada
pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan
melalui sistem penjualan kredit.”
Unsur pokok pengendalian terdiri dari:
A. Organisasi
1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit.
2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit.
3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.
31
4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan,
fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi.
Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap
hanya oleh satu fungsi tersebut.
B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan
menggunakan formulir surat pengiriman.
2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan
membubuhkan tanda tangan pada credit copy.
3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman
dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada
copy surat order pengiriman.
4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan
potongan penjualan berada ditangan Direktur Pemasaran dengan
penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut.
5. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan
membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan.
6. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal
penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan
cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber.
7. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang
didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat.
C. Praktik yang Sehat
1. Surat order pengiriman bernomor urut cetak dan pemakaiannya
dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
32
2. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya
dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan.
3. Secara periodik fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang
(account receivable statement) kepada setiap debitur untuk mengkaji
ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut.
4. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening
kontrol piutang dalam buku besar (h.221).
Menurut James (2007)
Aktivitas Pengendalian Pemrosesan Penjualan
Otorisasi Transaksi
Pemisahan Tugas
Catatan Akuntansi
Akses
Verifikasi independent
Pemeriksaan Kredit
Kebijakan Retur Barang
Kredit dipisahkan dari pemrosesan
Pengendalian persediaan dipisah dari gudang
Buku besar pembantu piutang dagang dipisah dari
buku besar umum
Pesanan penjualan, Jurnal penjualan, Buku besar
pembantu piutang dagang (buku besar umum),
Buku besar pembantu persediaan, Pengendalian
persediaan, Akun penjualan (buku besar umum)
Akses fisik ke persediaan
Akses ke catatan akuntansi diatas
Departemen pengiriman; departemen penagihan,
buku besar umum
(p.244)
33
II.4.3 Dokumen dan Catatan Umum
Sejumlah dokumen dan catatan yang digunakan oleh perusahaan besar dalam
pemrosesan transaksi penjualan kredit seringkali mencakup kal-hal berikut:
1. Pesanan pelanggan
Permintaan barang dagang oleh pelanggan yang diterima langsung dari
pelanggan atau melalui wiraniaga (sales person). Pesanan ini dapat berupa
formulir yang disiapkan oleh penjual atau formulir pesanan pembelian yang
dibuat oleh pembeli.
2. Pesanan penjual
Formulir yang menunjukkan deskriptif, kuantitas, dan data lainnya yang
berkaitan dengan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan ini berfungsi sebagai
dasar dimulainya transaksi dan pemrosesan internal atas pesanan pelanggan
oleh penjual.
3. Dokumen pengiriman
Formulir yang digunakan untuk menunjukkan rincian dan tanggal setiap
pengiriman. Dokumen ini dapat berupa bill of leading, yang berfungsi sebagai
pemberitahuan formal atas penerimaan barang yang dikirimkan oleh kurir.
Dokumen pengiriman lainnya termasuk slip pengepakan yang merinci item-
item yang dikirimkan.
4. Faktur penjualan
Faktur yang menyatakan penjualan tertentu, termasuk jumlah terutang, syarat,
dan tanggal penjualan. Formulir ini digunakan untuk menagih pelanggan dan
memberikan dasar untuk mencatat penjualan.
34
5. Daftar harga yang diotorisasi
Daftar atau file induk komputer yang berisi harga barang-barang yang
diotorisasi yang ditawarkan untuk dijual.
6. File transaksi komputer
File komputer yang berisi transaksi penjualan yang diselesaikan. File ini
digunakan untuk mencetak faktur penjualan serta jurnal penjualan, dan
memperbaharui file induk piutang usaha, persediaan, serta buku besar.
7. Jurnal penjualan
Daftar jurnal dari transaksi penjualan yang telah diselesaikan.
8. File induk pelanggan
File yang berisi informasi tentang pengiriman dan penagihan pelanggan serta
batas kredit pelanggan.
9. File induk piutang usaha
File yang berisi informasi tentang transaksi dan saldo dari setiap pelanggan.
File ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun buku pembantu piutang
usaha.
10. Laporan bulanan pelanggan
Laporan yang dikirimkan ke setiap pelanggan yang menunjukkan saldo awal,
transaksi selama periode berjalan, dan saldo akhir.
II.4.4 Perolehan Pemahaman dan Penilaian Resiko Pengendalian
Auditor harus memperoleh pemahaman atas siklus penjualan yang mencukupi
untuk merencanakan pemeriksaan. Yaitu auditor perlu mempunyai pemahaman yang
cukup untuk dapat:
35
1. Mengidentifikasi jenis salah saji potensial.
2. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko salah saji yang
material.
3. Merancang pengujian substantive.
Jika auditor berencana menilai resiko pengendalian yang rendah atas sebuah
asersi, maka sangat penting bagi dia untuk memperoleh pemahaman mengenai
prosedur pengendalian untuk asersi tersebut. Pengujian pengendalian merupakan
sarana untuk menentukan keefektifan pengendalian.
II.5 Aktivitas Pengendalian Transaksi Penerimaan Kas
Penerimaan kas merupakan hasil dari beberapa aktivitas. Sebagai contoh, kas
diterima dari hasil transaksi pendapatan, pinjaman jangka pendek atau jangka
panjang, serta aktiva lainnya. Lingkup bagian ini dibatasi pada penerimaan kas dari
penjualan tunai dan penagihan dari pelanggan atas penjualan kredit.
Fungsi penerimaan kas yang meliputi pemrosesan penerimaan kas dari
penjualan tunai dan kredit, termasuk sub fungsi sebagai berikut:
1. Menerima penerimaan kas
2. Menyetorkan kas ke bank
3. Mencatat penerimaan kas
Sebagaimana dalam kasus transaksi penjualan kredit, pemisahan tugas untuk
melakukan fungsi-fungsi ini merupakan aktivitas pengendalian internal yang penting.
Fungsi-fungsi, aktivitas pengendalian yang berlaku, dan asersi yang relevan serta
tujuan audit spesifik akan dijelaskan dalam bagian tersebut. Banyak dari
pengendalian tersebut berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas yang
36
melibatkan cek dan saldo secara manual daripada dengan komputer. Pengendalian
komputer paling efektif dalam mengendalikan pencatatan subfungsi.
Resiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas adalah kemungkinan
pencurian kas sebelum atau sesudah pencatatan penerimaan kas dibuat. Dengan
demikian, prosedur pengendalian harus memberikan kepastian yang layak bahwa
dokumentasi penetapan tanggung jawab telah dibuat pada saat kas diterima dan
bahwa kas telah disimpan ditempat yang aman. Resiko kedua adalah kemungkinan
terjadinya kesalahan dalam pemrosesan penerimaan kas berikutnya.
II.5.1 Fungsi-fungsi
II.5.1.1 Fungsi-fungsi Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai
1. Fungsi Penjualan
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung
jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan
menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran
harga barang ke fungsi kas. Fungsi ini berada pada Bagian Penjualan.
2. Fungsi Kas
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung
jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Fungsi ini berada pada Kasir.
3. Fungsi Gudang
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung
jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta
menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada pada
Bagian Gudang.
37
4. Fungsi Pengiriman
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung
jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar
harganya kepada pembeli. Fungsi ini berada pada Bagian Pengiriman.
5. Fungsi Akuntansi
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung
jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat
laporan penjualan. Fungsi ini berada pada Bagian Jurnal.
II.5.1.2 Fungsi-fungsi Sistem Penerimaan Kas dari Piutang
1. Fungsi Sekretariat
Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat bertanggung
jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para
debitur perusahaan. Fungsi sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat
pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Fungsi ini berada
pada Bagian Sekretariat.
2. Fungsi Penagihan
Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui
penagih perusahaan, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan
penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih
yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada pada Bagian Penagihan.
3. Fungsi Kas
Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat (jika
pelaksanaan penagihan piutang melalui pos) atau dari fungsi penagihan (jika
pelaksanaan penagihan piutang melalui penagih perusahaan). Fungsi kas
38
bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi
tersebut kepada bank dengan segera. Fungsi ini berada pada Kasir.
4. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari
piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam
kartu piutang. Fungsi ini berada pada Bagian Piutang.
5. Fungsi Pemeriksa Internal
Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksaan internal
bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada ditangan
fungsi kas secara periodik. Disamping itu, fungsi pemeriksa internal
bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek
ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Fungsi
pemeriksa internal berada pada Bagian Pemeriksa Internal.
II.5.2 Pengendalian Internal atas Fungsi Penerimaan Kas
II.5.2.1 Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Penerimaan Kas dari
Penjualan Tunai
A. Organisasi
1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.
2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi
kas, fungsi pengiriman dan akuntansi.
B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan
menggunakan formulir faktur penjualan tunai.
39
5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap
“lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada
faktur tersebut.
6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi
dari bank penerbit kartu kredit.
7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara
membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.
8. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan
cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai.
C. Praktik yang Sehat
9. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya
dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank
pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja
berikutnya.
11. Penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan
secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal.
II.5.2.2 Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Penerimaan Kas dari
Piutang
A. Organisasi
1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi
penerimaan kas.
2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
40
3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas
nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet).
4. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang
yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
5. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian
piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari
debitur.
C. Praktik yang Sehat
6. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas
dan disetor ke bank dengan segera.
7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan.
8. Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan Kasir maupun ditangan
penagih perusahaan) harus diasuransikan.
Menurut James A.Hall (2007)
Aktivitas Pengendalian Penerimaan Kas
Otorisasi Transaksi
Pemisahan Tugas
Supervisi
Catatan Akuntansi
Daftar permintaan pembayaran (pradaftar kas)
Penerima kas dipisah dari piutang dagang dan
akun kas.
Buku besar pembantu piutang dagang dipisahkan
dari buku besar.
Ruang penerimaan dokumen
Permintaan pembayaran, cek, daftar permintaan
pembayaran, jurnal penerimaan kas, buku besar
pembantu piurang dagang, akun pengendali
41
Akses
Verifikasi independent
piutang dagang, akun kas.
Akses fisik ke kas.
Akses ke catatan akuntansi.
Penerimaan kas, buku besar umum, rekonsiliasi
bank
II.5.3 Dokumen dan Catatan Umum
Dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan penerimaan
kas adalah sebagai berikut:
1. Bukti penerimaan uang (remittance advice)
Dokumen yang dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan, yang
kemudian akan dikembalikan bersama pembayaran yang menunjukkan nama
pelanggan serta nomor akun, nomor faktur, dan jumlah yang dibayarkan
(misalnya, bagian tagihan telepon yang dikembalikan bersama dengan
pembayaran).
2. Lembar perhitungan kas
Daftar kas dan cek dalam register kas. Daftar ini digunakan dalam rekonsiliasi
total penerimaan kas dengan total yang dicetak oleh register kas.
3. Ikhtisar kas harian
Laporan yang menunjukkan total penerimaan kas melalui kasir (over-the-
counter) atau pos yang diterima oleh kasir sebagai setoran.
42
4. Slip deposit yang disahkan
Daftar yang dibuat oleh penyetor dan distempel oleh bank yang menunjukkan
tanggal serta total setoran yang diterima bank dan rincian penerimaan kas
dalam setoran tersebut.
5. File transaksi penerimaan kas
File komputer atas transaksi penerimaan kas yang telah disahkan yang diterima
untuk pemrosesan, file ini digunakan untuk memperbaharui file induk piutang.
6. Jurnal penerimaan kas
Jurnal yang berisi daftar penerimaan kas dari penjualan tunai dan penagihan
piutang usaha.
II.5.4 Perolehan Pemahaman dan Penilaian Resiko Pengandalian
Tanggung jawab dan metodologi auditor untuk memenuhi persyaratan dari
standart pekerjaan lapangan kedua pada transaksi penerimaan kas, banyak prosedur
pengendalian yang terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas merupakan
pengendalian manual, bukan prosedur pengendalian yang terprogram. Auditor
biasanya akan menggunakan kombinasi dari pengajuan pertanyaan (Internal Control
Questionnaires), observasi, dan inspeksi dokumen untuk mengumpulkan bukti
bahwa prosedur pengendalian manual sudah efektif.