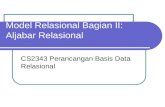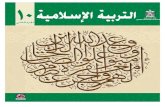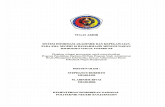.._2
-
Upload
meriam-gita-maulia-suhaidi -
Category
Documents
-
view
161 -
download
0
description
Transcript of .._2

PENAPISAN AWAL KOMPONEN BIOAKTIF DARI KERANG DARAH (Anadara granosa)
SEBAGAI SENYAWA ANTIBAKTERI
Oleh:
Ika Pranata Wahyu Daluningrum C34104010
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Penapisan Awal Komponen Bioaktif dari Kerang Darah (Anadara granosa) sebagai Senyawa Antibakteri adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Januari 2009
Ika Pranata W.D. NRP C34104010

RINGKASAN
IKA PRANATA WAHYU DALUNINGRUM. C34104010. Penapisan Awal Komponen Bioaktif dari Kerang Darah (Anadara granosa) sebagai Senyawa Antibakteri. Dibawah bimbingan: ELLA SALAMAH dan KOMARIAH TAMPUBOLON.
Produksi kerang darah Indonesia tahun 2003 sebesar 47.505 ton dan tahun 2004 mencapai 64.498 ton. Masyarakat pesisir Malaysia dan Thailand telah memanfaatkan kerang darah sebagai obat tradisional untuk mengatasi penyakit kolera, hepatitis A dan disenteri. Pemanfaatan kerang darah sebagai obat tradisional menunjukkan adanya dugaan kerang darah memiliki komponen aktif.
Tujuan penelitian ini adalah mengekstrak komponen aktif pada kerang darah dengan tiga jenis pelarut yaitu heksana, etil asetat dan metanol, menguji ekstrak sebagai senyawa antibakteri, mengamati zona hambat yang dihasilkan pada penyimpanan suhu 10oC dan 30oC selama tujuh hari serta analisis fitokimia terhadap ekstrak yang menunjukkan aktivitas antibakteri paling baik.
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis proksimat kerang darah, ekstraksi senyawa aktif dari kerang darah, uji aktivitas antibakteri dari ekstrak yang dihasilkan terhadap bakteri E. coli dan S. aureus dengan konsentrasi ekstrak 2%, 3,5%, 5% dan 6,5% serta analisis fitokimia terhadap ekstrak yang memiliki aktivitas antibakteri paling baik.
Penelitian ini menunjukkan hasil analisis proksimat kerang darah mempunyai kadar air 81,82%, kadar abu 2%, kadar protein 11,84%, kadar lemak 0,6% dan kadar karbohidrat 3,75%. Ekstrak kerang darah dengan pelarut heksana adalah 3,00±1,40 mg, dengan pelarut etil asetat adalah 107,50±3,50 mg dan dengan pelarut metanol adalah 995,50±0,70 mg. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat mampu menghasilkan zona hambat pada S. aureus untuk konsentrasi 2%, 3,5%, 5% dan 6,5% masing-masing 3 mm, 4 mm, 6 mm dan 7 mm, serta menghambat E. coli dengan zona hambat masing-masing konsentrasi 1 mm, 2 mm, 3 mm dan 4 mm. Ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol tidak menunjukkan penghambatan pada konsentrasi 2% dan 3,5%, tetapi pada konsentrasi 5% dan 6,5% menghasilkan zona hambat sebesar 0,5 mm dan 1 mm pada E. coli dan S. aureus. Kemampuan penghambatan ekstrak kerang darah dari pelarut etil asetat yang lebih baik daripada pelarut metanol berarti senyawa antibakteri yang terdapat pada kerang darah bersifat semi polar karena larut dalam pelarut etil asetat.
Hasil pengamatan diameter zona hambat selama tujuh hari pada suhu 10oC dan suhu 30oC menunjukkan bahwa pada suhu 10oC E. coli mulai tumbuh pada hari keempat pengamatan dan S. aureus mulai tumbuh pada hari ketiga pengamatan. Pada suhu 30oC E. coli mulai tumbuh kembali pada hari ketiga pengamatan dan S. aureus mulai tumbuh pada hari kedua pengamatan. Kemampuan E. coli dan S. aureus untuk tumbuh kembali selama pengamatan berarti ekstrak kerang dari pelarut etil asetat mengalami penurunan aktivitas penghambatan dengan semakin lamanya kontak ekstrak dengan bakteri uji. Analisis fitokimia terhadap ekstrak etil asetat kerang darah menunjukkan hasil bahwa ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat mengandung senyawa alkaloid dan steroid tetapi tidak mengandung senyawa flavonoid.

PENAPISAN AWAL KOMPONEN BIOAKTIF DARI KERANG DARAH (Anadara granosa)
SEBAGAI SENYAWA ANTIBAKTERI
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor
Oleh:
Ika Pranata Wahyu Daluningrum C34104010
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

Judul Skripsi : PENAPISAN AWAL KOMPONEN BIOAKTIF DARI KERANG DARAH (Anadara granosa) SEBAGAI SENYAWA ANTIBAKTERI
Nama : Ika Pranata Wahyu Daluningrum NRP : C34104010
Menyetujui,
Pembimbing I
Dra. Ella Salamah, M.Si NIP. 131 788 597
Pembimbing II
Ir. Komariah Tampubolon, MS NIP. 130 355 555
Mengetahui, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP. 131 578 799
Tanggal lulus :

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segenap
limpahan karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah
kepada Rasulullah SAW.
Penyusunan skripsi yang berjudul “Penapisan Awal Komponen Bioaktif
dari Kerang Darah (Anadara granosa) sebagai Senyawa Antibakteri”
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu baik moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini,
diantaranya kepada:
1. Ibu Dra. Ella Salamah, MSi dan Ibu Ir. Komariah Tampubolon, MS
selaku komisi pembimbing atas segala saran, kritik, arahan dan motivasi.
2. Ibu Dr. Ir. Sri Purwaningsih, MS dan Ibu Ir. Iriani Setyaningsih, MS
selaku dosen penguji atas segala saran dan arahan.
3. Ibu Ir. Winarti Zahiruddin, MS selaku pembimbing akademik atas segala
bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
4. Seluruh staf dan dosen pengajar Departemen Teknologi Hasil Perairan
atas segala arahan dan bimbingan.
5. Bu Ema, Mbak Ica, Mas Zacky dan Mas Ipul atas bantuan dan
bimbingannya selama ini.
6. Kedua orang tua, Bapak Soekadi dan Ibu Sri Nastiti atas segala cinta,
kasih sayang, pengorbanan, doa dan jerih payah yang tidak terbalas.
7. Adikku, Dhimas Harianto, atas segala cinta, doa dan perhatiannya.
Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari segala kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.
Bogor, Januari 2009
Ika Pranata W.D.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu baik moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini,
diantaranya kepada:
1. Pak Man, Bulek Lolo, Umar, Ibrahim, Ismail, Ahmad, Atika, Afifah,
Aqrom, Aiman dan Sarah di Kalimalang atas cinta, kasih sayang dan
perhatiannya.
2. Mas Andik dan istri di Sukabumi atas perhatiannya.
3. Mas Nur dan Mbak Aulia di Jakarta atas kasih sayangnya.
4. Oom Wiwid, Mbak Yuni dan Kiki atas kasih sayang dan perhatiannya.
5. Rekan-rekan THP angkatan 39, 40, 41, 42 dan 43 atas kerjasama dan
persahabatan yang indah.
6. Kerabat-kerabat Blitarian_Soekarnoensis di Kawah Kelud, Bek La, Ali,
Farikha, Bek Fah, Mas Alfa, Mas Aris, Mas Tyo, Dedi, Fa’i, To’o, Iin,
Nelly, Mbak Niken, Dody, Dicky, Jo, Azzam, Sapek, Dan, Ulie, Tyas
dan Ikka atas kasih sayang, nasehat dan dukungannya.
7. Eka, Nia, Dilla dan Sereli atas kasih sayang, perhatian serta persahabatan
yang indah dan tak terlupakan .
8. Andi Patria atas kasih sayang, semangat dan kenangan yang telah terukir.
9. Saukya Singgih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang diberikan.
10. Anang, An’im, Windhyka, Nuzul, Laler, Alim, Nicolas, Sait, Glory,
Estrid, Amel, Yudha dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu per
satu, terima kasih atas persahabatan yang sangat indah selama ini.
11. Yerry Rozaq dan Teguh Dwi Cahyanto atas semangatnya.
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal
29 April 1986 dari ayah Soekadi dan ibu Sri Nastiti. Penulis
merupakan putri pertama dari dua bersaudara. Tahun 2004
penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menegah Atas
Negeri I Srengat, Jawa Timur dan pada tahun yang sama lulus
seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB
(USMI) dengan memilih Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi FORCES
(Forum For Scientific Students) tahun 2004/2005 dan Badan Eksekutif Mahasiswa
divisi Kewirausahaan tahun 2005/2006. Penulis juga menjadi asisten mata kuliah
Penanganan Hasil Perairan tahun ajaran 2006/2007, mata kuliah Transportasi
Biota Perairan tahun ajaran 2007/2008, mata kuliah Diversifikasi Produk Hasil
Perairan tahun ajaran 2007/2008, mata kuliah Hasil Samping Perairan tahun
ajaran 2007/2008 dan mata kuliah Biotoksikologi Hasil Perairan tahun ajaran
2008/2009. Pada tahun 2008 penulis menjuarai Kompetisi Pemikiran Kritis
Mahasiswa (KPKM) tingkat nasional bidang perekomomian sebagai juara II,
dengan judul karya tulis Tantangan dalam Meningkatkan Standar Kualitas Udang
Ekspor Indonesia melalui Traceability System.
Penulis menyelesaikan studi di Institut Pertanian Bogor dengan menyusun
skripsi yang berjudul Penapisan Awal Komponen Bioaktif dari Kerang Darah
(Anadara granosa) sebagai Senyawa Antibakteri.

DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ............................................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xii
1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Tujuan .................................................................................................. 2
2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 3
2.1 Kerang Darah (Anadara granosa)........................................................ 3
2.2 Senyawa Bioaktif ................................................................................ 5
2.3 Ekstraksi ............................................................................................... 6
2.4 Bakteri .................................................................................................. 10 2.4.1 Escherichia coli .......................................................................... 10 2.4.2 Staphylococcus aureus ............................................................... 11
2.5 Uji Aktivitas Antibakteri ...................................................................... 12
2.6 Kloramfenikol ...................................................................................... 14
3. METODOLOGI ........................................................................................... 16
3.1 Waktu dan Tempat ................................................................................ 16
3.2 Alat dan Bahan ...................................................................................... 16
3.3 Metode Kerja ......................................................................................... 16 3.3.1 Analisis proksimat ....................................................................... 17 3.3.2 Ekstraksi senyawa bioaktif (Darusman et al. 1994).................... 19 3.3.3 Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak kasar kerang darah (Anadara granosa) (Noer & Nurhayati 2006) ............................ 20 3.3.4 Analisis fitokimia ........................................................................ 26
4. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 27
4.1 Analisis Proksimat ................................................................................ 27
4.2 Ekstraksi Komponen Bioaktif ................................................................ 28
4.3 Uji Aktivitas Antibakteri ........................................................................ 32 4.3.1 Uji pendahuluan aktivitas antibakteri ......................................... 32 4.3.2 Uji aktivitas antibakteri dengan berbagai konsentrasi ................ 33 4.3.3 Pengamatan zona hambat pada penyimpanan suhu 10oC
dan 30oC ...................................................................................... 37
4.4 Analisis Fitokimia .................................................................................. 46

5. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 50
5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 50
5.2 Saran ........................................................................................................ 50
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 51
LAMPIRAN ....................................................................................................... 55

DAFTAR TABEL
Halaman
1 Produksi kerang darah tahun 2001-2005 ..................................................... 4
2 Kandungan gizi kerang per 100 gram bahan ............................................... 4
3 Sifat fisik dari beberapa pelarut ................................................................... 7
4 Data proksimat kerang darah (A. granosa) .................................................. 27
5 Kadar proksimat kerang ............................................................................... 27
6 Berat ekstrak kasar kerang darah (A. granosa) ............................................ 29
7 Aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah pada konsentrasi 2% ................ 32
8 Aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah pada berbagai konsentrasi ........ 34
9 Pengamatan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada penyimpanan suhu 10oC ...................................................................... 38
10 Pengamatan zona hambat kloramfenikol pada penyimpanan suhu 10oC ..... 41
11 Pengamatan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada penyimpanan suhu 30oC ...................................................................... 43
12 Pengamatan zona hambat kloramfenikol pada penyimpanan suhu 30oC ..... 45
13 Analisis fitokimia ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat .............. 47

DAFTAR GAMBAR
Halaman
1 Anatomi kerang ............................................................................................ 3
2 Rumus umum heksana ................................................................................. 8
3 Sintesis etil asetat ......................................................................................... 9
4 Reaksi pembentukan metanol ...................................................................... 10
5 Bakteri Escherichia coli ............................................................................... 11
6 Bakteri Staphylococcus aureus .................................................................... 12
7 Tahapan uji aktivitas antibakteri (Noer dan Nurhayati 2006) ...................... 13
8 Struktur kloramfenikol ................................................................................. 14
9 Tahapan proses ekstraksi (Darusman et al. 1994) ...................................... 21
10 Tahapan uji pendahuluan aktivitas antibakteri ( modifikasi
Noer & Nurhayati 2006) ............................................................................. 24
11 Tahapan uji aktivitas antibakteri pada berbagai konsentrasi ekstrak (modifikasi Darusman et al 1994) ................................................................ 25
12 Ekstrak kerang darah .................................................................................... 30
13 Rendemen ekstrak kerang darah dengan tiga jenis pelarut ......................... 31
14 Hasil analisis fitokimia ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat ..... 48

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Perhitungan rendemen daging kerang darah (A. granosa) ........................... 56
2 Kerang darah (A. granosa) yang digunakan untuk penelitian...................... 56
3 Ekstraksi kerang darah (A. granosa) ............................................................ 57
4 Perhitungan rendemen ekstrak kerang darah (A. granosa) .......................... 58
5 Uji pendahuluan aktivitas antibakteri pada bakteri E. coli ......................... 59
6 Uji pendahuluan aktivitas antibakteri pada bakteri S. aureus ...................... 60
7 Contoh perhitungan konsentrasi ekstrak ...................................................... 60
8 Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat dan metanol kerang darah pada bakteri E. coli ............................................................................................... 61
9 Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat dan metanol kerang darah pada bakteri S. aureus ............................................................................................ .62
10 Uji aktivitas antibakteri kontrol (kloramfenikol) pada bakteri E. coli ......... 63
11 Uji aktivitas antibakteri kontrol (kloramfenikol) pada bakteri S. aureus ..... 64
12 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-1 ................................................. 65
13 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-2 ................................................. 66
14 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-3 ................................................. 67
15 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-4 ................................................. 68
16 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-5 ................................................. 69
17 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-6 ................................................. 70
18 Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-7 ................................................. 71
19 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-1 ................................................. 72
20 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-2 ................................................. 73
21 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-3 ................................................. 74
22 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-4 ................................................. 75
23 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-5 ................................................. 76
24 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-6 ................................................. 77
25 Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-7 ................................................. 78

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Wilayah nusantara sebagian besar merupakan perairan yang terdiri atas
perairan tawar dan perairan laut dengan kandungan kekayaan alam yang berupa
sumber bahan pangan dan non pangan. Perairan Indonesia kaya akan moluska,
salah satunya adalah kerang darah (Anadara granosa), yang merupakan hasil laut
dengan nilai ekonomis penting dan menjadi salah satu sumber bahan pangan.
Produksi kerang darah Indonesia tahun 2003 adalah 47.505 ton dan meningkat
pada tahun 2004 menjadi 64.498 ton (DKP 2006).
Bivalvia (kerang) merupakan salah satu kelas dari tujuh kelas pada filum
Moluska. Di daerah tropis terdapat bermacam-macam Bivalvia seperti tiram,
remis dan kerang, terutama di daerah pantai yang berhutan bakau. Ciri utama dari
kelas ini adalah tubuhnya yang tertutup oleh dua cangkang dengan satu atau dua
pasang otot adduktor. Berbentuk pipih ke arah lateral dan bagian kepala
mengalami reduksi.
Kerang darah banyak ditemukan di sepanjang pantai di daerah tropis
dengan substrat lumpur halus atau kadang-kadang pasir berlumpur dan dilindungi
atau berasosiasi dengan pohon-pohon bakau. Pathansali (1966) diacu dalam
Erianto (2005) menyebutkan bahwa habitat ideal untuk kerang darah adalah
lumpur halus berukuran kurang dari 0,124 mm, terlindung dari ombak dan dengan
salinitas antara 18-30‰.
Inswiasri et al. (1995) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kerang
darah memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (±20%) sehingga banyak
dibudidayakan untuk mencukupi kebutuhan protein yang berasal dari hewan,
selain itu kerang darah memiliki kemampuan menyerap Cd dari perairan lebih
tinggi daripada jenis kerang yang lain, sehingga biasa digunakan sebagai
bioindikator pencemaran logam berat pada perairan dibandingkan jenis kerang
lainnya. Trilaksani dan Nurjanah (2004) diacu dalam Erianto (2005)
menyebutkan bahwa bagian yang dapat dimakan dari kerang terdiri dari mantel
3-5%, kaki 5-7%, otot adduktor 2,5-3%, sedangkan siphon, insang dan organ
pencernaan merupakan bagian yang tidak dapat dimakan sebesar 4-7%.

Ninda (2008) dalam artikelnya menyatakan bahwa kerang mampu
membantu melawan bakteri dan beberapa jenis penyakit. Tan dan Ng (2008) juga
menyebutkan bahwa beberapa daerah berpantai di Malaysia dan Thailand telah
membudidayakan kerang darah, namun belum terlalu populer. Pada daerah
tersebut, kerang darah telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk penyakit
kolera, hepatitis A dan disenteri. Pemanfaatan kerang darah sebagai obat
tradisional tersebut memberikan dugaan bahwa kerang darah memiliki suatu
senyawa aktif yang bersifat antibakteri. Senyawa antibakteri adalah senyawa
biologis atau kimia yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dan
aktivitas bakteri (Irianto 2006). Senyawa-senyawa aktif dari kerang darah yang
diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam bidang
farmasi, pangan, industri, dan lain-lain
1.2. Tujuan
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya senyawa
antibakteri pada kerang darah (Anadara granosa) melalui metode ekstraksi
bertingkat, sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai antara lain:
1) Mengekstrak komponen aktif dari kerang darah (Anadara granosa) melalui
metode ekstraksi bertingkat dengan pelarut non polar, semi polar dan polar.
2) Menguji aktivitas ekstrak yang dihasilkan sebagai senyawa antibakteri pada
bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.
3) Mengamati zona hambat ekstrak yang memiliki aktivitas terbaik pada
penyimpanan suhu 10oC dan 30oC.
4) Mengetahui komponen penyusun senyawa aktif pada kerang darah
(Anadara granosa) dari ekstrak terbaik melalui analisis fitokimia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kerang Darah (Anadara granosa)
Broom (1985) dalam Erianto (2005) menyusun sistematika kerang darah
(Anadara granosa) sebagai berikut:
filum : Mollusca
kelas : Bivalvia
famili : Arcidae
sub famili : Anadarinae
genus : Anadara
spesies : Anadara granosa
Kelas Pelecypoda dicirikan oleh bentuk kakinya seperti kampak. Storer
dan Usinger (1957) diacu dalam Mubarak (1987) menjelaskan bahwa ciri lain dari
kerang darah adalah mempunyai cangkang terdiri dari dua keping yang biasanya
simetris (oleh karena itu disebut juga kelas Bivalvia) dengan hinge dan ligamen
pada bagian dorsal serta memiliki satu atau dua pasang otot adduktor.
Gambar 1 Anatomi kerang. Sumber: Bunje (2001)

Broom (1985); Pathansali (1966) diacu dalam Erianto (2005) menjelaskan
bahwa kerang darah hidup di daerah pasang surut, umumnya ditemukan pada
lahan pantai yang berada di antara daerah rataan pasang dan rataan surut
berlumpur lunak berbatasan dengan hutan bakau dengan habitat ideal berupa
substrat lumpur halus berukuran kurang dari 0,124 mm sebanyak 90% pada
hamparan pasang (tidal flat) yang terlindung dari ombak, di luar muara sungai
dengan salinitas 18-30‰.
Kerang darah termasuk sebagai salah satu komoditas perikanan yang
produktivitasnya cukup baik. Tabel 1 menunjukkan total produksi dan nilai
produksi kerang darah pada tahun 2001-2005.
Tabel 1 Produksi kerang darah tahun 2001-2005
Tahun Total Produksi (ton) Nilai Produksi (rupiah) 2001 2002 2003 2004 2005
64.308 71.428 47.505 64.498 57.164
83.631.950 153.648.184 103.977.352 118.950.299 128.932.897
Sumber: DKP (2006).
Kandungan gizi kerang darah yang cukup baik menyebabkan kerang darah
banyak dibudidayakan sebagai alternatif sumber protein. Kadar lemak kerang
darah yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan lemak pada produk
perikanan lainnya, seperti ikan bandeng sebesar 4,8 g/100 g (Poedjiadi 1994),
menjadi salah satu alasan kerang darah digemari masyarakat untuk dikonsumsi.
Kandungan gizi yang terdapat pada kerang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Kandungan gizi kerang per 100 gram bahan
Komposisi Kadar (g) Air Abu Lemak Protein Karbohidrat
85 2,3
1,1 8,0 3,6
Sumber: Poedjiadi (1994)

2.2. Senyawa Bioaktif
Senyawa bioaktif merupakan suatu senyawa aktif yang termasuk metabolit
sekunder. Metabolit sekunder merupakan suatu komponen hasil metabolisme
yang unik dan terbatas, yang terkadang hanya dijumpai pada kelompok tertentu,
biasanya tidak dibutuhkan oleh sel (organisme) untuk hidup, tetapi berperan
dalam interaksi sel (organisme) dengan lingkungan, menjamin ketahanan hidup
organisme tersebut pada ekosistem hidupnya (Verpoorte dan Alfermann 2000).
Alkaloid merupakan golongan terbesar dari senyawa metabolit sekunder
pada tumbuhan dan hingga saat ini sebanyak 5500 jenis alkaloid telah diketahui.
Pada umumnya alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa yang
mengandung satu atau lebih atom nitrogen sebagai bagian dari sistem siklik.
Alkaloid seringkali bersifat racun bagi manusia, tetapi beberapa alkaloid memiliki
aktivitas farmakologis dan digunakan secara luas dalam bidang kesehatan
(Harborne 1987). Senyawa ini pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi diri
dari prodator karena bersifat racun pada satwa misalnya serangga, sebagai zat
perangsang dan pengatur tumbuh dan membantu aktivitas metabolisme dan
reproduksi tumbuhan (Verpoorte dan Alfermann 2000).
Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam
satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik,
yaitu skualena. Senyawa ini berstruktur siklik yang rumit, kebanyakan berupa
alkohol, aldehida atau asam karboksilat. Triterpenoid dapat digolongkan menjadi
empat golongan, yaitu triterpena, steroid, saponin dan glikosida jantung.
Triterpena yang dijumpai pada tumbuhan berfungsi sebagai pelindung untuk
menolak serangga dan serangan mikroba (Harborne 1987). Steroid terdapat pada
hampir semua tipe sistem kehidupan. Steroid yang dijumpai pada binatang
bertindak sebagai hormon, selain itu steroid juga digunakan secara luas sebagai
obat (Verpoorte dan Alfermann 2000). Saponin adalah glikosida triterpena dan
sterol yang terdeteksi pada lebih dari 90 suku tumbuhan. Saponin merupakan
senyawa yang bersifat seperti sabun yang dapat dideteksi berdasarkan
kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis sel darah. Golongan
triterpena terakhir adalah glikosida jantung atau kardenolida. Beberapa glikosida

jantung adalah racun, tetapi terdapat juga yang berkhasiat farmakologi, terutama
terhadap jantung, seperti tercermin pada namanya (Harborne 1987).
Flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam air dan dapat diekstrak
dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok
dengan eter. Flavonoid umumnya terdapat dalam tumbuhan. Flavonoid yang
banyak terdapat di alam adalah jenis flavon dan flavonol, sedangkan isoflavon dan
biflavonol hanya terdapat pada beberapa suku tumbuhan saja (Harborne 1987).
Sabir (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa senyawa flavonoid
memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri dengan beberapa
mekanisme yang berbeda, antara lain flavonoid menyebabkan terjadinya
kerusakan permeabilitas dinding bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil
interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Bryan 1982; Wilson dan Gisvold
1982 diacu dalam Sabir 2005), sementara Mirzoeva et al. (1997) diacu dalam
Sabir (2005) dalam penelitiannya berpendapat bahwa flavonoid mampu
melepaskan energi transduksi terhadap membran sitoplasma bakteri, selain itu
juga menghambat motilitas bakteri. Mekanisme yang berbeda dikemukakan oleh
Di Carlo et al. (1999) dan Estrela et al. (1995) diacu dalam Sabir (2005) yang
menyatakan bahwa gugus hidroksil yang terdapat pada struktur senyawa flavonoid
menyebabkan perubahan komponen organik dan transpor nutrisi yang akhirnya
akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap bakteri.
2.3. Ekstraksi
Departemen Kesehatan (2000) diacu dalam Adolf (2006) menjelaskan
ekstraksi adalah peristiwa penarikan komponen yang diinginkan dari suatu bahan
dengan cara pemisahan satu atau lebih komponen dari sumbernya. Struktur kimia
yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan dan stabilitas senyawa-senyawa
tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat dan derajat keasaman.,
dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung dalam bahan akan
mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat.
Metode ekstraksi yang dilakukan tergantung pada beberapa faktor, antara
lain tujuan ekstraksi, skala ekstraksi, sifat-sifat komponen yang akan diekstraksi
dan sifat-sifat pelarut yang akan digunakan. Prinsip metode ekstraksi
menggunakan pelarut organik adalah bahan yang akan diekstrak kontak langsung

dengan pelarut pada waktu tertentu, kemudian diikuti dengan melakukan
pemisahan dari bahan yang telah diekstrak (Houghton & Raman 1998).
Pemilihan pelarut organik yang akan digunakan dalam ekstraksi komponen
aktif merupakan faktor penting dan menentukan untuk mencapai tujuan dan
sasaran ekstraksi komponen. Tabel 3 menunjukkan sifat fisik beberapa jenis
pelarut organik yang dapat digunakan untuk ekstraksi. Semakin tinggi nilai
konstanta dielektrik, titik didih dan kelarutan dalam air, maka pelarut akan makin
polar (Sudarmadji et al. 2007).
Tabel 3 Sifat fisik dari beberapa pelarut
Pelarut Titik didih (oC) Titik beku (oC) Konstanta dielektrik (Debye)
Heksana Dietil eter Karbon disulfida Aseton Kloroform Metanol Tetrahidrofuran di-isopropil eter Karbon tetraklorida Etil asetat Etanol Benzena Sikloheksana Isopropanol Air Dioksan Toluena Asam asetat glasial N,N-dimetil formamida Dietilenaglikol
69* 35 46 56 61 65 66 68 76 77 78 80 81 82 100 102 111 118 154 245
-94* -116 -111 -95 -64 -98 -65 -60 -23 -84 -117
5,5 5,5
-89 0 12 -95 17 -61 -10
1,89* 4,3 2,6 20,7 4,8 32,6 7,6 3,9 2,2 6,0 24,3 2,3 2,0 18,3 78,5 2,2 2,4 6,2 34,8 37,7
Sumber: Nur dan Adijuwana (1989) *Sudarmadji et al. (2007)
Sifat penting yang harus diperhatikan dalam ekstraksi adalah kepolaran
senyawa dilihat dari gugus polarnya. Senyawa polar lebih mudah larut dalam
pelarut polar dan senyawa non polar lebih mudah larut dalam pelarut non polar.
Derajat polaritas tergantung pada tetapan dielektrik, makin besar tetapan
dielektrik semakin polar pelarut tersebut (Sudarmadji et al. 2007). Ekstraksi
bertingkat dilakukan secara berturut-turut dimulai dengan pelarut nonpolar
dilanjutkan dengan pelarut yang menengah kepolarannya (semi polar), kemudian

dengan pelarut polar, sehingga akan diperoleh ekstrak kasar (crude extract) yang
berturut-turut senyawa nonpolar, semi polar dan polar.
Heksana memiliki konstanta dielektrik sebesar 1,89 Db, indeks polaritas 0,
titik didih 69oC dan titik beku -94oC (Sudarmadji et al. 2007). Nilai konstanta
dielektrik pelarut heksana merupakan konstanta paling rendah apabila
dibandingkan dengan konstanta dielektrik pelarut yang lain, sehingga pelarut
heksana termasuk dalam pelarut non polar. Isomer heksana sangat tidak reaktif
dan sering digunakan sebagai pelarut organik yang inert.
Heksana merupakan salah satu jenis dari senyawa hidrokarbon, yaitu
persenyawaan organik yang hanya mengandung aton karbon dan hidrogen.
Heksana termasuk dalam hidrokarbon jenuh, artinya hidrokarbon dengan karbon-
karbon yang mempunyai satu ikatan. Senyawa dengan rantai lurus mempunyai
gaya tarik menarik antar molekul lebih besar daripada rantai cabang, sehingga
akan lebih sukar bereaksi dengan molekul lain. Sebagai contoh, heksana
merupakan pelarut non polar, molekul heksana tidak tertarik oleh molekul air,
sehingga heksana tidak larut dalam air. Heksana memiliki berat jenis yang lebih
rendah (0,66 g/ml) daripada air (1,0 g/ml), sehingga akan terapung dalam air. Api
yang disebabkan oleh minyak atau lemak tidak dapat dimatikan oleh air karena
minyak atau lemaknya akan mengapung di atas air. Air justru akan menyebarkan
apinya (Fessenden dan Fessenden 1997). Rumus umum dari heksana ditunjukkan
pada Gambar 2.
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
Gambar 2 Rumus umum heksana.
Sumber: Fessenden dan Fessenden (1997)
Heksana merupakan pelarut yang memiliki kemampuan melarutkan lilin,
lemak dan minyak dari bahan (Harborne 1987), sehingga pelarut heksana dipilih
sebagai pelarut pertama yang digunakan pada proses ekstraksi dengan tujuan agar
lemak bahan terpisahkan terlebih dahulu, sehingga tidak mengganggu atau
menghalangi keluarnya bahan aktif pada proses ekstraksi dengan pelarut-pelarut
selanjutnya. Asih dan Setawan (2008) menggunakan pelarut heksana pada awal
maserasi dan dilanjutkan dengan maserasi menggunakan metanol.

Etil asetat merupakan pelarut polar menengah (semi polar) yang volatil,
tidak beracun dan tidak higroskopis. Etil asetat dapat melarutkan air hingga 3%
dan larut dalam air hingga kelarutan 8% pada suhu kamar. Kelarutannya akan
meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Tetapi senyawa ini tidak stabil dalam air
yang mengandung asam atau basa. Etil asetat adalah senyawa organik yang
merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tidak
berwarna, memiliki aroma yang khas dan sering disingkat dengan EtOAc, dimana
Et mewakili gugus etil dan OAc mewakiliki asetat. Etil asetat diproduksi dalam
skala besar dan digunakan sebagai pelarut (Fessenden dan Fessenden 1997).
Sintesis etil asetat ditunjukkan pada Gambar 3.
CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O
Gambar 3 Sintesis etil asetat.
Sumber: Fessenden dan Fessenden (1997)
Etil asetat merupakan pelarut semi polar yang mampu mengekstrak fenol,
terpenoid, alkaloid, aglikon dan aglisida dari suatu bahan (Harborne 1987).
Pambayun et al. (2007) menggunakan etil asetat sebagai salah satu pelarut dalam
mengekstraksi gambir untuk mengetahui sifat antibakteri. Hasil dari penelitian
tersebut menunjukkan bahwa ekstrak gambir dengan pelarut etil asetat memiliki
aktivitas antibakteri paling baik apabila dibandingkan dengan ekstrak kloroform
dan etanol karena ekstrak etil asetat diduga mengandung senyawa fenol yang
paling tinggi, dimana senyawa fenol merupakan komponen terpenting terkait
dengan sifat antibakteri.
Metanol merupakan salah satu pelarut alkohol yang penting dan paling
sederhana. Metanol diperoleh dari proses reduksi karbon monoksida. Secara
singkat, gas alam dan uap air dibakar dalam tungku untuk membentuk gas
hidrogen dan karbon monoksida, kemudian gas hidrogen dan karbon monoksida
bereaksi dalam tekanan tinggi dengan bantuan katalis Cu untuk menghasilkan
metanol. Proses pembentukan metanol ditunjukkan pada Gambar 4. Metanol
(metil alkohol) merupakan cairan ringan tidak berwarna yang larut dalam air.
Pada kondisi ruang, metanol mudah menguap dan mudah terbakar. Metanol
bersifat racun, jika terminum dalam jumlah yang sangat kecil maupun melalui

pernafasan, maka metanol akan menimbulkan kebutaan. Terdapat laporan yang
menjelaskan bahwa terjadi kematian yang disebabkan mimum metanol kurang
dari 30 ml (Fessenden dan Fessenden 1997).
CO + 2H2 atm 150-100 C,260
Cur Katalisato0 CH3OH
Gambar 4 Reaksi pembentukan metanol. Sumber: Fessenden dan Fessenden (1997)
Metanol juga dikenal sebagai alkohol kayu atau spiritus dan merupakan
bentuk alkohol paling sederhana. Metanol digunakan sebagai bahan pendingin
anti beku karena titik bekunya yang rendah yaitu -98oC, pelarut, bahan bakar dan
sebagai bahan aditif pada industri etanol. Salah satu kelemahan metanol sebagai
bahan bakar adalah sifat korosi terhadap beberapa logam, termasuk aluminium.
Penggunaan metanol terbanyak saat ini adalah sebagai bahan pembuat bahan
kimia lainnya. Sekitar 40% metanol diubah menjadi formaldehid yang kemudian
diaplikasikan dalam berbagai macam produk seperti plastik, kayu lapis, cat,
peledak dan tekstil (Fessenden dan Fessenden 1997). Yuharmen et al. (2002)
menggunakan metanol sebagai pelarut dalam uji antimikroba dari lengkuas. Dari
penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa ekstrak metanol mengandung
flavonoid, fenol dan terpenoid.
2.4. Bakteri
Bakteri adalah sel prokariotik yang khas, uniseluler dan rata-rata berukuran
lebar 0,5-1,0 μm serta panjang hingga 10 μm. Bakteri memiliki peranan yang
cukup penting dalam memelihara lingkungan, yaitu menghancurkan bahan-bahan
yang tertumpuk di daratan maupun di perairan. Akan tetapi beberapa bakteri juga
mampu menimbulkan efek negatif, seperti menyebabkan penyakit pada manusia,
hewan dan tumbuhan (Irianto 2006).
2.4.1. Escherichia coli
Bakteri Escherichia coli termasuk dalam famili enterobacteriaceae. Bakteri
ini termasuk patogen gram negatif dan bersifat anaerob fakultatif, bersifat
kemoorganik dengan tipe metabolisme fermentatif dan respiratif, ada yang
bersifat motil dengan flagela peritrik dan ada juga yang nonmotil. Memiliki

batang tunggal dan berpasangan dengan ukuran 1,1-1,5 μm x 2,0-6,0 μm, diameter
koloni 2-3 μm, memiliki kapsul dan mikrokapsul. E. coli tumbuh pada temperatur
15-45oC dengan suhu optimum 37oC (Fardiaz 1992).
E. coli merupakan penghuni normal saluran pencernaan (coliform fecal)
manusia dan hewan, maka digunakan secara luas sebagai bioindikator pencemaran
lingkungan. Bakteri ini juga mengakibatkan banyak infeksi pada saluran
pencernaan makanan (enterik) manusia dan hewan (Pelczar dan Chan 1986).
Gambar 5 Bakteri Escherichia coli. Sumber: Wikipedia (2008b)
Bahan makanan yang sering terkontaminasi oleh E. coli antara lain daging
ayam, daging sapi, daging babi, ikan dan makanan hasil laut lainnya, telur dan
produk olahannya, sayuran, buah-buahan, sari buah serta minuman seperti susu
(Fardiaz 1992). E. coli merupakan penyebab utama meningitis pada bayi yang
baru lahir dan juga penyebab infeksi tractus urinarius pada manusia yang dirawat
di rumah sakit (nosocomial infection) (Greeenwood et al. 1995).
2.4.2. Staphylococcus aureus
Bakteri Staphylococcus aureus termasuk bakteri gram positif dan bersifat
anaerob fakultatif, berbentuk bulat tunggal, berpasangan atau bergerombol dengan
diameter 0,5-1,5 μm, tidak berkapsul dan berspora dan nonmotil. Bakteri ini
bersifat kemoorganotropik dengan tipe metabolisme fermentatif dan respiratif.
Bakteri ini dapat tumbuh pada konsentrasi NaCl 10% dengan suhu optimum
33-37oC dan pH 6-7, akan tetapi pada suhu 6,7-45,5oC serta pH 4,0-9,8 bakteri ini
dapat tumbuh dan berkembang biak (Pelczar dan Chan 1988).

Gambar 6 Bakteri Staphylococcus aureus. Sumber: Dyer (2008)
S. aureus dapat dijumpai pada kulit, selaput lendir, bisul-bisul dan luka-
luka. Bakteri ini sering ditemukan pada produk pangan dengan bahaya sedang
dan penyebarannya terbatas. Ciri-ciri khusus S. aureus penyebab adalah
memproduksi enterotoksin yang stabil terhadap pemanasan hingga 100oC selama
beberapa menit, memproduksi toksin epidermolitik yang menyebabkan kulit
melepuh dan menghasilkan Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST 1) yang
menyebabkan kerusakan pada jaringan (Greenwood et al. 1995).
S. aureus menghasilkan koagulase, dijumpai pada selaput hidung, kulit,
kantung rambut, dapat menyebabkan keracunan makanan serta komplikasi pada
influenza. Keracunan makanan yang umum terjadi karena termakannya toksin
yang dihasilkan oleh galur-galur toksigenik S. aureus yang tumbuh pada makanan
tercemar. Jumlah enterotoksin yang termakan menentukan waktu timbulnya
gejala serta parah tidaknya infeksi tersebut. Pada umumnya gejala-gejala mual,
pusing, muntah dan diare muncul 2-6 jam setelah mengkonsumsi makanan
tercemar tersebut (Greenwood et al. 1995).
2.5. Uji Aktivitas Antibakteri
Senyawa antibakteri didefinisikan sebagai senyawa biologis atau kimia
yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri.
Berdasarkan aktivitasnya, zat antibakteri dapat bersifat bakterisidal (membunuh
bakteri) dan bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri). Mekanisme kerja
zat antibakteri dalam menghambat pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain pH lingkungan, komponen medium, stabilitas obat, takaran inokulum,
lama inkubasi dan aktivitas metabolisme mikroorganisme (Irianto 2006).

Zat-zat yang digunakan sebagai antibakteri harus mempunyai beberapa
kriteria ideal, antara lain ekonomis, efektif, stabil, tidak bersifat racun bagi
manusia atau hewan lain, tidak bergabung dengan komponen organik lain,
memiliki aktivitas pada suhu kamar atau suhu tubuh, tidak menimbulkan karat
atau warna dan tidak mempengaruhi bau (Irianto 2006). Salah satu metode uji
aktivitas antibakteri yang banyak digunakan adalah metode uji aktivitas
antibakteri Noer dan Nurhayati (2006) yang disajikan pada Gambar 7.
Gambar 7 Tahapan uji aktivitas antibakteri (Noer dan Nurhayati 2006).
Kerusakan bakteri merupakan hasil interaksi antibakteri dengan bagian
tertentu pada sel bakteri. Interaksi antibakteri tersebut dapat menyebabkan
sejumlah perubahan pada sel bakteri yang berakhir pada kematian sel bakteri.
Penuangan agar ke dalam cawan petri
Penghomegenan
Pendinginan selama 15 menit atau sampai agar membeku
Pemberian 20 μl ekstrak pada paper disc dengan konsentrasi 2%
Peletakkan paper disc ke dalam cawan yang telah berisi bakteri uji
Inkubasi pada suhu 37oC selama 18-20 jam dalam posisi terbalik
Penginokulasian bakteri 20 μl dalam cawan petri steril
Pengamatan dan pengukuran zona bening

P
p
m
e
p
k
2
b
s
i
k
m
m
a
d
m
y
o
b
Perubahan
permeabilita
matinya sel,
enzim yang
penghambat
kerusakan to
2.6. Kloram
Kloram
bakteriostati
spektrum ya
ini masih di
karena harg
maju telah m
menyebabka
aplastik (Sya
Cara k
dengan men
mengganggu
yang efektif
otak (Syah e
Kloram
bakteriostati
yang terjad
as sel yang
, perubahan
akan menga
tan sintesis
otal (Pelczar
mfenikol
mfenikol ya
ik yang efe
ang luas, bai
igunakan se
anya yang m
melarang pe
an efek neg
ah et al. 200
kerja kloram
nghambat a
u pembentuk
f menembus
et al. 2005).
mfenikol m
ik yang tid
di antara la
akan meny
molekul pr
akibatkan ter
asam nuk
dan Chan 1
ang disebut
fektif mengh
ik bakteri gr
ecara luas ol
murah dan
enggunaan k
gatif pada k
05).
mfenikol dal
aktivitas pep
kan ikatan p
seluruh jari
Gambar 8 m
Gambar 8 S
Sumber:
merupakan
dak membu
ain kerusaka
yebabkan ter
rotein atau a
rganggunya m
kleat dan
988).
juga chlor
hambat per
ram positif m
leh negara-n
aktivitasnya
kloramfeniko
kesehatan, y
lam mengha
ptidil transf
peptida. K
ingan dalam
menunjukkan
Struktur klor
Wikipedia (
antibiotik
unuh bakteri
an pada di
rhambatnya
asam nuklea
metabolisme
protein se
romycetin m
rtumbuhan
maupun bak
negara deng
a yang stabil
ol sebagai a
yaitu timbu
ambat pertum
ferase dari
Kloramfeniko
m tubuh, term
n struktur kl
ramfenikol.
(2008a).
aminoglikos
i melainkan
inding sel,
pertumbuha
at, penghamb
e atau matiny
ehingga me
merupakan a
mikroorgani
kteri gram ne
gan pendapa
l, tetapi neg
antibiotik ka
lnya penyak
mbuhan bak
ribosom b
ol merupaka
masuk mata,
loramfenikol
sida, yaitu
n hanya m
perubahan
an sel atau
batan kerja
ya sel serta
enyebabkan
antimikroba
isme pada
egatif. Zat
atan rendah
gara-negara
arena dapat
kit anemia
kteri adalah
bakteri dan
an senyawa
syaraf dan
l.
antibiotik
menghambat

sintesa protein yang sangat diperlukan dalam perbanyakan dan pembelahan sel
bakteri. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang paling stabil. Zat ini juga cepat
dan hampir sempurna diabsorpsi oleh saluran pencernaan (Fardiaz 1992).
Darmowandowo dan Kaspan (2009) dalam artikelnya menyebutkan bahwa
dosis kloramfenikol yang biasa digunakan adalah 50 mg/kg/hari yang dibagi
menjadi empat kali pemberian. Dosis yang biasa diberikan pada laki-laki dewasa
±750 mg yang terbagi menjadi tiga hingga empat kali dalam sehari, dosis tersebut
akan menjadi dua kali lipat pada kondisi yang parah. Dosis yang diberikan pada
anak-anak, bayi prematur atau bayi yang baru lahir adalah setengah dari dosis
yang diberikan pada manusia dewasa, hal ini dikarenakan anak-anak, bayi
prematur atau bayi yang baru lahir belum mampu mencerna obat-obatan dengan
efektif.

3. METODOLOGI
3.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga bulan November 2008
di Laboratorium Karakteristik Bahan Baku, Laboratourium Mikrobiologi Hasil
Perairan, Laboratorium Biokimia Hasil Perairan, Program Studi Teknologi Hasil
Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pusat Antar Universitas Pangan
dan Gizi serta Pusat Studi Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor.
3.2. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada persiapan sampel antara lain pisau, talenan,
timbangan digital dan kertas label. Alat-alat untuk ekstraksi sampel antara lain
timbangan digital, gelas ukur, labu erlenmeyer, sudip kaca, kertas label, corong
kaca, nyilon mesh, pipet tetes, kertas saring whatman, aluminium foil dan kapas
steril. Alat-alat untuk evaporasi ekstrak antara lain vacuum rotary evaporator dan
botol steril. Alat-alat untuk uji aktivitas antibakteri antara lain tabung reaksi, rak
tabung reaksi, pipet tetes, pipet mikro, bulp, autoklaf, jarum ose, bunsen,
inkubator, vorteks, cawan petri, paper disc dan plastik wrapping.
Bahan yang digunakan sebagai sampel adalah kerang darah (A. granosa)
yang diambil dari pasar ikan Muara Angke, Jakarta Utara. Bahan untuk ekstraksi
adalah pelarut teknis (heksana, etil asetat dan metanol). Bahan untuk uji aktivitas
antibakteri adalah kloramfenikol sebagai antibakteri standar, NB (Nutrient Broth),
TSA (Trypticase Soy Agar), media MHA (Mueller Hinton Agar), bakteri uji
(Escherichia coli dan Staphylococcus aureus), akuades, korek api, spiritus dan
alkohol 70%. Sedangkan bahan untuk analisis fitokimia antara lain H2SO4 2N,
pereaksi Dragendorff, pereaksi Meyer, pereaksi Wagner, kloroform, H2SO4 pekat,
anhidrida asetat, serbuk magnesium dan amil alkohol.
3.3. Metode Kerja
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis proksimat kerang
darah, ekstraksi senyawa aktif dari kerang darah, uji aktivitas antibakteri dari
ekstrak yang dihasilkan, mengamati zona hambat yang dihasilkan pada
penyimpanan suhu 10oC dan 30oC selama tujuh hari dan analisis fitokimia.

Analisis proksimat kerang darah meliputi uji kadar air, kadar abu, kadar lemak,
kadar protein dan kadar karbohidrat. Ekstraksi senyawa bioaktif dari kerang
darah dilakukan secara bertingkat dengan tiga pelarut yang berbeda tingkat
kepolarannya, yaitu heksana (non polar), etil asetat (semi polar) dan metanol
(polar). Ekstrak yang telah diperoleh kemudian diuji aktivitasnya sebagai
senyawa antibakteri terhadap bakteri E. coli dan S. aureus. Ekstrak dengan
kemampuan penghambatan paling baik kemudian diamati zona hambatnya selama
tujuh hari pada suhu 10oC dan 30oC dan dianalisis fitokimia untuk mengetahui
komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak.
3.3.1. Analisis proksimat
a. Analisis kadar air (AOAC 1995)
Cawan kosong yang digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit
atau sampai diperoleh berat tetap, kemudian didinginkan dalam desikator
selama 30 menit dan ditimbang. Sampel kira-kira sebanyak 5 gram ditimbang
dan diletakkan dalam cawan kemudian dipanaskan dalam oven selama 24 jam
pada suhu 105oC. Cawan kemudian didinginkan dalam desikator kemudian
ditimbang kembali. Persentase kadar air dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
%100B
B2-B1airKadar % ×=
Keterangan : B = Berat sampel (gram)
B1 = Berat (sampel + cawan) sebelum dikeringkan
B2 = Berat (sampel + cawan) setelah dikeringkan
b. Analisis kadar abu (AOAC 1995)
Pengukuran kadar abu ditentukan dengan alat tanur. Cawan porselin
dipanaskan dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel
dimasukkan dalam cawan porselin kemudian dibakar sampai tidak berasap
lagi, lalu diabukan dalam tanur suhu 600oC sampai berwarna putih (semua
sampel menjadi abu) dan berat konstan. Setelah itu didinginkan dalam

desikator dan ditimbang. Rumus perhitungan kadar abu adalah sebagai
berikut:
%100(g) sampelBerat
(g)abu Berat abuKadar % ×=
c. Analisis kadar protein (AOAC 1995)
Sampel ditimbang sebanyak 1-2 gram lalu dimasukkan ke dalam labu
kjeldahl. Setelah itu ditambahkan 10 ml H2SO4 dan pelet kjeldahl kemudian
sampel didihkan dalam ruang asam sampai larutan berwarna hijau kebiruan
jernih. Larutan jernih ini lalu dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Labu
kjeldahl dibilas dengan aquades (1-2 ml) kemudian air bilasan dimasukkan ke
dalam labu ukur, selanjutnya diencerkan dengan aquades hingga 100 ml.
Sampel yang telah diencerkan dengan aquades dipipet sebanyak 10 ml
dan dimasukkan dalam alat destilasi, kemudian ditambahkan sedikit demi
sedikit NaOH 40% sebanyak 10 ml. Ujung tabung kondensor alat destilasi
harus terendam dalam erlenmeyer yang berisi larutan asam borat (H3BO3) 4%.
Dilakukan pemanasan alat destilasi hingga larutan asam borat yang semula
berwarna merah muda menjadi berwarna hijau kebiruan. Selang kondensor
kemudian dibilas dengan sejumlah aquades untuk menghindari kemungkinan
adanya nitrogen yang menempel pada selang. Setelah itu erlenmeyer yang
telah menangkap nitrogen dari sampel dititrasi dengan HCl 0,1 N hingga
terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Titrasi juga dilakukan terhadap
larutan blanko.
%100sampelBerat
14,007 HCl Nblanko) HCl ml - sampel (mlN % ×××
=
6,25N %Protein % ×=
d. Analisis kadar lemak (AOAC 1995)
Metode yang digunakan dalam analisis lemak adalah metode ekstraksi
soxhlet. Sampel sebanyak 5 gram dibungkus dengan kertas saring, setelah itu
kertas saring yang berisi contoh tersebut dimasukkan dalam labu soxhlet. Alat

kondensor diletakkan di bagian atas dan labu lemak diletakkan di bagian
bawah. Pelarut heksana dimasukkan ke dalam labu lemak secukupnya.
Selanjutnya dilakukan refluks selama minimal 5 jam sampai pelarut yang
turun kembali ke dalam labu lemak berwarna jernih.
Pelarut yang ada dalam labu lemak didestilasi, dan pelarut ditampung
kembali. Labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi kemudian dipanaskan
di dalam oven pada suhu 105oC hingga mencapai berat tetap dan setelah itu
didinginkan dalam desikator. Selanjutnya labu beserta lemak didalamnya
ditimbang dan berat lemak dapat diketahui.
%100(g) sampelBerat (g)lemak Berat lemakKadar % ×=
e. Perhitungan kadar karbohidrat (AOAC 1995)
Perhitungan kadar karbohidrat dilakukan secara by different, yaitu dengan
menggunakan rumus:
K.abu-K.air-K.protein-K.lemak-100%tkarbohidraKadar =
3.3.2. Ekstraksi senyawa bioaktif (Darusman et al. 1994)
Metode yang digunakan dalam ekstraksi senyawa aktif dari kerang darah
adalah metode ekstraksi bertingkat menurut Darusman et al. (1994) dengan tiga
pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya, yaitu heksana (non polar), etil asetat
(semi polar) dan metanol (polar). Tahapan proses ekstraksi kerang darah meliputi
penghancuran sampel, maserasi, penyaringan dan evaporasi. Tahap pertama
kerang dipisahkan dari cangkangnya, dicuci dan dicacah. Sampel yang telah
dihancurkan kemudian ditimbang sebanyak 200 gram dan dimasukkan dalam
erlenmeyer kemudian dimaserasi dalam 400 ml pelarut (perbandingan 1:2).
Heksana dipilih sebagai pelarut pertama dikarenakan sifat heksana yang
melarutkan lilin, lemak dan minyak dari suatu bahan (Harborne 1987), sehingga
diharapkan dengan mengekstrak bahan dalam pelarut heksana terlebih dahulu
akan menghilangkan lemak yang akan mempermudah pengeluaran senyawa aktif
dari bahan dengan pelarut-pelarut selanjutnya, yaitu etil asetat dan metanol.

Sampel dimaserasi dengan heksana selama 24 jam pada suhu ruang.
Setelah 24 jam, sampel disaring menggunakan nyilon mesh sebagai saringan
kasar, selanjutnya penyaringan dengan corong kaca dan kertas saring whatman
untuk memisahkan filtrat dengan ampas I. Ampas I kemudian dimaserasi dengan
pelarut etil asetat selama 24 jam, disaring sehingga diperoleh filtrat etil asetat dan
ampas II. Ampas II selanjutnya dimaserasi dengan pelarut metanol selama 24
jam, disaring sehingga diperoleh filtrat metanol dan residu III.
Filtrat heksana, filtrat etil asetat dan filtrat metanol yang diperoleh
selanjutnya dievaporasi dengan menggunakan vacuum rotary evaporator pada
suhu 40oC, sehingga diperoleh ekstrak kasar dari pelarut heksana, etil asetat dan
metanol. Ekstrak yang diperoleh dimasukkan dalam botol steril untuk mencegah
kontaminasi kemudian disimpan dalam freezer. Tahapan proses ekstraksi dapat
dilihat pada Gambar 9.
3.3.3. Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak kasar kerang darah (Anadara granosa)
(Noer dan Nurhayati 2006)
Uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap ekstrak kerang darah
(A. granosa). Uji ini meliputi persiapan media padat TSA, persiapann media cair
NB, persiapan suspensi bakteri, persiapan media padat MHA, prosedur uji
pendahuluan aktivitas antibakteri, prosedur uji aktivitas antibakteri dengan
berbagai konsentrasi dan pengukuran zona hambat. Bakteri uji yang digunakan
adalah E. coli dan S. aureus. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan
metode difusi agar menggunakan paper disc.
a) Persiapan media padat TSA
Penyegaran bakteri uji, yaitu E. Coli dan S. aureus dilakukan pada
media TSA (Trypticase Soy Agar). Media TSA dibuat dengan melarutkan
sebanyak 8 gram media TSA bubuk dalam aquades hingga volume 200 ml,
lalu dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih. TSA dipipet sebanyak 9 ml
dalam tabung reaksi dan masing-masing tabung ditutup dengan kapas dan
aluminium foil. Media lalu disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC
selama 15 menit. Setelah itu media dimiringkan sekitar 45 derajat dan
dibiarkan hingga membeku. Setelah membeku media selanjutnya disimpan
dalam refrigerator.

Gambar 9 Tahapan proses ekstraksi (Darusman et al. 1994). Keterangan: Produk
Proses
Pemisahan daging dari cangkang
Penimbangan
Pencacahan
Pencucian
Maserasi dengan heksana (24 jam)
Penyaringan
Evaporasi
Evaporasi
Penyaringan
Evaporasi
Maserasi dengan etil asetat (24 jam)
Maserasi dengan metanol (24 jam)
Kerang darah (Anadara granosa)
Ekstrak kasar heksana
Ekstrak kasar etil asetat
Ekstrak kasar metanol
Residu III
Ampas II
Ampas I
Penyaringan
Filtrat heksana
Filtrat etil asetat
Filtrat metanol

b) Persiapan media cair NB
Media NB (Nutrient Broth) dibuat dari 2,6 gram media NB bubuk yang
dilarutkan dalam aquades hingga volume 200 ml, selanjutnya dipanaskan
sambil diaduk hingga mendidih. NB dipipet sebanyak 9 ml kedalam tabung
reaksi dan masing-masing tabung ditutup menggunakan kapas dan alumunium
foil. Sebelum digunakan, media disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC
selama 15 menit. Setelah itu media didinginkan di tempat yang steril pada
suhu ruang.
c) Persiapan suspensi bakteri
Sebanyak 1 ose bakteri uji digoreskan pada media TSA dengan pola zig
zag secara aseptik, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam.
Setelah itu 1-2 ose bakteri uji dari media TSA dimasukkan ke dalam media
NB yang telah dingin secara aseptik. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC
selama 18-24 jam.
d) Persiapan media padat MHA
Media padat yang digunakan untuk pengujian aktivitas antibakteri
adalah media Mueller Hinton Agar (MHA). MHA dibuat dengan melarutkan
7,6 gram media MHA bubuk dalam aquades hingga volume 200 ml, kemudian
dipanaskan sambil diaduk hingga mendidih. Larutan dipipet 15 ml, kemudian
dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan masing-masing tabung ditutup dengan
kapas dan alumunium foil. Sebelum digunakan, media disterilisasi dengan
autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit. Media didinginkan pada suhu
ruang sampai agar membeku. Setelah membeku, media disimpan dalam
refrigerator.
e) Uji pendahuluan aktivitas antibakteri (modifikasi Noer dan Nurhayati 2006)
Media MHA cair sebanyak 15 ml ditambah dengan 20 μl bakteri uji
yang telah diukur OD-nya (Optical Density) antara 0,6-0,8 (Lalitha 2004)
pada panjang gelombang 600 nm, masing-masing 0,788 (E. coli) dan 0,723
(S. aureus). Media yang telah ditambah dengan bakteri uji dihomogenkan
dengan vorteks, kemudian segera dituangkan ke dalam cawan petri steril dan
digoyangkan membentuk angka delapan agar lebih menyebar secara merata.

Media agar tersebut didiamkan pada suhu ruang selama 15 menit atau sampai
agar membeku.
Ekstrak kerang darah yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri
adalah ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dan ekstrak kerang
darah dengan pelarut metanol karena ekstrak kerang darah dengan pelarut
heksana yang diperoleh sangat sedikit. Dalam uji aktivitas antibakteri, setiap
paper disc diberi ekstrak sebanyak 20 μl dengan konsentrasi 2% (20 mg
ekstrak yang dilarutkan dalam 1 ml metanol). Konsentrasi kloramfenikol yang
digunakan sebagai antibakteri kontrol juga sama dengan konsentrasi ekstrak
yang digunakan, yaitu 2%. Setelah seluruh pelarut ekstrak pada paper disc
menguap, masing-masing paper disc diletakkan dalam cawan petri yang telah
berisi agar dan bakteri, kemudian cawan petri dilapisi dengan plastik wrapping
untuk menghindari kontaminasi dan disimpan dalam inkubator dengan posisi
terbalik pada suhu 37oC selama 18-20 jam. Aktivitas antibakteri dapat dilihat
dengan mengamati zona hambat yang terbentuk disekitar paper disc. Diagram
alir uji pendahuluan aktivitas antibakteri dapat dilihat pada Gambar 10.
f) Prosedur uji aktivitas antibakteri pada berbagai konsentrasi ekstrak
(modifikasi Darusman et al. 1994)
Media MHA sebanyak 15 ml dalam keadaan cair ditambahkan dengan
20 μl bakteri uji yang telah diukur OD-nya (Optical Density) antara 0,6-0,8
(Lalitha 2004) pada panjang gelombang 600 nm, masing-masing 0,797
(E. coli) dan 0,750 (S. aureus), kemudian divorteks agar homogen dan segera
dituangkan ke dalam cawan petri steril dan digoyangkan membentuk angka
delapan agar menyebar secara merata. Media tersebut didiamkan pada suhu
ruang selama beberapa saat agar membeku.
Ekstrak kerang darah yang digunakan adalah ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol,
dengan konsentrasi masing-masing paper disc adalah 2%, 3,5%, 5% dan 6,5%
(modifikasi Darusman et al. 1994) sebanyak 20 μl. Konsentrasi kloramfenikol
yang digunakan sebagai antibakteri kontrol juga sama dengan konsentrasi
ekstrak yang digunakan, yaitu 2%, 3,5%, 5% dan 6,5%. Paper disc dibiarkan
sampai pelarutnya menguap, kemudian masing-masing paper disc diletakkan

dalam cawan petri berisi MHA dan bakteri yang telah membeku, kemudian
cawan petri dilapisi dengan plastik wrapping untuk mencegah kontaminasi
dan selanjutnya diinkubasi dengan posisi terbalik selama 18-20 jam pada suhu
37oC. Diagram alir uji aktivitas antibakteri pada berbagai konsentrasi ekstrak
dapat dilihat pada Gambar 11. Setelah diinkubasi selama 18-20 jam,
selanjutnya dilakukan pengamatan zona bening selama tujuh hari pada ekstrak
dengan kemampuan penghambatan paling baik dengan penyimpanan pada
suhu 10oC dan pada suhu 30oC untuk mengetahui kemampuan ekstrak dalam
menghambat pertumbuhan bakteri (modifikasi Darusman et al. 1994).
Gambar 10 Tahapan uji pendahuluan aktivitas antibakteri
(modifikasi Noer dan Nurhayati 2006). Keterangan: Produk
Proses
Penghomogenan dengan vorteks
Penuangan agar ke dalam cawan petri steril
Pendinginan selama 15 menit atau sampai agar membeku
Pemberian 20 μl ekstrak pada paper disc dengan konsentrasi 2%
Peletakkan paper disc ke dalam cawan yang telah berisi bakteri uji
Inkubasi pada suhu 37oC selama 18-20 jam dalam posisi terbalik
Penginokulasian bakteri 20 μl dalam 15 ml media MHA
Pengamatan dan pengukuran zona bening

g) Pengukuran zona hambat
Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk zona hambat
berupa zona bening disekeliling paper disc dan aktivitas antibakteri
dinyatakan negatif apabila tidak terbentuk zona bening. Diameter zona
hambat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
B-Ahambat Zona =
Keterangan :
A = Diameter zona hambat yang terbentuk (mm)
B = Diameter kertas cakram (mm)
Gambar 11 Tahapan uji aktivitas antibakteri pada berbagai konsentrasi ekstrak (modifikasi Darusman et al. 1994).
Keterangan: Produk Proses
Penghomogenan dengan vorteks
Penuangan agar ke dalam cawan petri steril
Pendinginan selama 15 menit atau sampai agar membeku
Pemberian paper disc ekstrak 20 μl dengan konsentrasi 2%, 3,5%, 5% dan 6,5%
Peletakkan paper disc ke dalam cawan yang telah berisi bakteri uji
Inkubasi pada suhu 37oC selama 18-20 jam dalam posisi terbalik
Penginokulasian bakteri (20 μl) dalam 15 ml media MHA
Pengamatan dan pengukuran zona bening

3.3.4. Analisis fitokimia
Identifikasi komponen aktif yang berperan sebagai antibakteri dalam
kerang darah (A. granosa) dilakukan terhadap senyawa alkaloid, flavonoid dan
steroid (Darusman et al. 1994) dengan metode sebagai berikut (Harborne 1987):
a) Alkaloid (Harborne 1987)
Sejumlah sampel dilarutkan dalam beberapa tetes asam sulfat 2N
kemudian diuji dengan tiga pereaksi Alkaloid, yaitu pereaksi Dragendorff,
Meyer dan Wagner. Hasil uji dinyatakan positif bila pereaksi Meyer terbentuk
endapan putih kekuningan, endapan cokelat dengan pereaksi Wagner dan
endapan merah sampai jingga dengan pereaksi Dragendorff.
b) Steroid (Harborne 1987)
Sejumlah sampel dilarutkan dalam 2 ml kloroform dalam tabung reaksi
yang kering. Ke dalamnya ditambahkan 10 tetes anhidrida asetat dan 3 tetes
H2SO4 pekat. Terbentuknya larutan berwarna merah untuk pertama kali
kemudian berubah menjadi biru dan hijau menunjukkan reaksi positif.
c) Flavonoid (Harborne 1987)
Sejumlah sampel ditambah serbuk magnesium 0,1 mg dan 0,4 ml amil
alkohol (campuran asam klorida 37% dan etanol 95% dengan volume sama)
dan 4 ml alkohol kemudian campuran dikocok. Terbentuknya warna merah,
kuning atau jingga pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Proksimat
Kerang darah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kerang
darah yang diambil dari pasar ikan Muara Angke, Jakarta Utara pada bulan
September 2008. Analisis proksimat yang dilakukan pada kerang darah meliputi
uji kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat. Data
analisis proksimat kerang darah ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Data proksimat kerang darah Tabel 5 Kadar proksimat kerang
Komponen Kadar (%)* Komponen Kadar (%)** Air Abu Protein Lemak Karbohidrat
81,82 2,00 11,84 0,60 3,75
Air Abu Protein Lemak Karbohidrat
85 2,3 8,0 1,1 3,6
*Hasil penelitian **Poedjiadi (1994)
Kerang darah contoh memiliki rendemen sebesar 17,17%. Nilai rendemen
diperoleh melalui perbandingan berat daging kerang darah setelah dipreparasi
dengan berat kerang darah sebelum dipreparasi dan dinyatakan dalam persen.
Berat kerang darah contoh sebelum dipreparasi adalah 6 kg dan berat daging
kerang darah contoh setelah dipreparasi adalah 1,03 kg. Perhitungan rendemen
daging kerang darah dapat dilihat pada Lampiran 1.
Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, diketahui bahwa kadar air kerang darah
contoh adalah 81,82%, nilai tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan
kadar air kerang secara umum menurut Poedjiadi (1994) yaitu sebesar 85%.
Analisis kadar abu kerang darah contoh menunjukkan hasil sebesar 2% dimana
nilai tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kadar abu kerang secara
umum menurut Poedjiadi (1994) yaitu sebesar 2,3%.
Kerang darah contoh memiliki kadar protein sebesar 11,84%, dimana nilai
tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan kadar kerang secara umum
menurut Poedjiadi (1994) yang menyebutkan bahwa kadar protein kerang adalah
8%. Kadar lemak kerang pada umumnya, yaitu 1,1% (Poedjiadi 1994), sedangkan
kadar lemak kerang darah contoh yang diperoleh adalah lebih rendah, yaitu

sebesar 0,60%. Kadar karbohidrat kerang darah contoh sebesar 3,75%. Nilai
tersebut telah sesuai dengan kadar kerang secara umum menurut Poedjiadi (1994)
yang menyebutkan bahwa kadar karbohidrat kerang adalah 3,6%.
Perbedaan kadar proksimat kerang darah contoh dengan kerang pada
umumnya diduga karena terjadinya perbedaan waktu dan lokasi pengambilan
contoh. Dugaan tersebut diperkuat oleh pernyataan Trilaksani dan Nurjanah
(2004) diacu dalam Erianto (2005) yang menjelaskan bahwa perbedaan komposisi
kimia kerang darah terjadi karena adanya perbedaan waktu dan lokasi
pengambilan contoh. Komposisi kimia kerang sangat bervariasi, tergantung pada
spesies, jenis kelamin, umur, musim dan habitat.
4.2. Ekstraksi Komponen Bioaktif
Tahap ekstraksi merupakan tahap awal ekstraksi senyawa bioaktif dari
kerang darah. Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode ekstraksi bertingkat menurut Darusman et al. (1994). Pelarut yang
digunakan dalam ekstaksi ini berturut-turut adalah heksana (non polar), etil asetat
(semi polar) dan metanol (polar). Kesempurnaan esktraksi bertingkat tergantung
pada jenis ekstraksi yang dilakukan, terutama apabila ekstraksi dilakukan secara
berulang dengan jumlah pelarut sedikit demi sedikit. Ekstraksi dengan pelarut
heksana dilakukan pada awal proses dengan tujuan memisahkan lipid dari bahan
sehingga tidak menghalangi keluarnya senyawa bioaktif pada ekstraksi dengan
pelarut-pelarut berikutnya. Proses ekstraksi selanjutnya digunakan pelarut etil
asetat untuk mengekstrak senyawa semi polar dan terakhir pelarut metanol untuk
mengekstrak senyawa polar.
Proses maserasi dilakukan selama 24 jam dengan cara merendam sampel
dalam pelarut dengan perbandingan 1:2. Pengadukan dilakukan sebanyak
beberapa kali untuk meningkatkan tumbukan antara partikel bahan yang
diekstraksi dengan pelarut sehingga komponen bioaktif yang keluar dari jaringan
dan larut dalam pelarut juga semakin meningkat.
Tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan yang terdiri dari penyaringan
dan evaporasi. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan ampas kerang darah
dengan filtrat yang mengandung senyawa aktif. Tahap evaporasi dilakukan dalam

penguap putar yang hampa (rotary vacuum evaporator) pada suhu tidak terlalu
tinggi (30-40oC) untuk mencegah terjadi kerusakan pada komponen aktif.
Ekstraksi kerang darah dengan tiga jenis pelarut menghasilkan ekstrak dari
pelarut heksana, ekstrak dari pelarut etil asetat dan ekstrak dari pelarut metanol
dengan berat masing-masing ekstrak ditunjukkan pada Tabel 6. Ekstrak yang
diperoleh dari ekstraksi kerang darah merupakan ekstrak kasar karena belum
mengalami pemurnian. Pemurnian ekstrak kasar dapat dilakukan dengan
fraksinasi untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan
utama yang lainnya(Harborne 1987).
Tabel 6 Berat ekstrak kasar kerang darah (A. granosa)
Jenis pelarut Berat ekstrak (mg) Heksana Etil asetat Metanol
3,00±1,40 107,50±3,50 995,50±0,70
Ekstrak kerang darah dengan pelarut heksana yang dihasilkan berupa pasta
kental yang berwarna kuning, ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat yang
dihasilkan berupa pasta kental yang berwarna cokelat muda dan ekstrak kerang
darah dengan pelarut metanol yang dihasilkan berupa pasta kental yang berwarna
cokelat tua. Gambar ekstrak kerang darah ditunjukkan pada Gambar 12. Ekstrak
kerang darah tertinggi dihasilkan dari pelarut polar yaitu metanol sebesar
995,50±0,70 mg dan ekstrak terkecil diperoleh dari pelarut non polar yaitu
heksana sebesar 3,00±1,40 mg. Pelarut metanol dapat menghasilkan rendemen
paling besar diduga karena kemampuan metanol dalam mengikat komponen-
komponen dari kerang darah lebih baik daripada pelarut etil asetat dan heksana.
Hasil tersebut didukung dengan pernyataan yang menjelaskan bahwa metanol
merupakan pelarut alkohol paling sederhana yang dapat membentuk ikatan
hidrogen dan dapat bercampur dengan air hingga kelarutan tak terhingga,
sehingga metanol sering digunakan sebagai pelarut dalam proses isolasi senyawa-
senyawa organik (Fessenden dan Fessenden 1997). Disamping itu, metanol juga
dapat melarutkan alkaloid kuartener, komponen fenolik, karotenoid, tanin, gula,
asam amino, glikosida serta beberapa senyawa non polar seperti lilin, minyak dan
lemak. Pelarut semi polar seperti etil asetat dapat mengekstrak senyawa fenol,

terpenoid, alkaloid, aglikon dan aglisida (Harborne 1987). Ekstrak yang
dihasilkan dari ekstraksi dengan pelarut heksana memiliki nilai yang rendah
dikarenakan heksana merupakan pelarut non polar yang biasa digunakan untuk
memisahkan lipid dari bahan.
Gambar 12 Ekstrak kerang darah.
Keterangan: A = Ekstrak kerang darah dengan pelarut heksana B = Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat C = Ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol
Jumlah ekstrak kerang darah yang diperoleh dari hasil penelitian ini sangat
sedikit, karena daging kerang yang diekstrak dicacah secara kasar, diduga dengan
pencacahan lebih halus akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena
partikel pelarut akan lebih banyak yang bertumbukan dengan partikel bahan.
Waktu ekstraksi juga diduga berpengaruh terhadap jumlah ekstrak kerang darah
yang dihasilkan. Pada penelitian ini ekstraksi kerang darah dilakukan selama 24
jam, apabila waktu ekstraksi ditambah, diduga jumlah senyawa aktif yang
terekstrak juga akan meningkat. Perbandingan pelarut dengan bahan pada
penelitian ini adalah 1:2, apabila jumlah pelarut ditambah, diduga juga akan
meningkatkan jumlah ekstrak. Dugaan tersebut diperkuat oleh pustaka yang
menyatakan bahwa hasil ekstraksi yang diperoleh tergantung pada beberapa
faktor, yaitu kondisi alamiah senyawa, metode ekstraksi yang digunakan, ukuran
BA C

partikel sampel, kondisi ekstraksi, lama ekstraksi dan perbandingan jumlah pelarut
dengan jumlah sampel (Houghton & Raman 1998).
Bobot ekstrak dengan pelarut heksana, ekstrak dengan pelarut etil asetat
dan ekstrak dengan pelarut metanol kerang darah yang dihasilkan dapat digunakan
untuk mengetahui nilai rendemen ekstrak. Rendemen merupakan perbandingan
antara bobot ekstrak yang dihasilkan dengan bobot awal dan dinyatakan dalam
persen. Rendemen ekstrak kerang darah mengalami peningkatan seiring dengan
peningkatan kepolaran pelarut yang digunakan (Gambar 13).
Gambar 13 Rendemen ekstrak kerang darah dengan tiga jenis pelarut.
Gambar 13 menunjukkan bahwa rendemen terbesar ekstrak kerang darah
adalah ekstrak dengan pelarut metanol, yaitu sebesar 0,4978% dan ekstrak terkecil
adalah ekstrak dengan pelarut heksana sebesar 0,0015%, sedangkan ekstrak
dengan pelarut etil asetat yang dihasilkan sebesar 0,0538%. Rendemen ekstrak
dengan pelarut metanol dan pelarut etil asetat pada kerang darah yang cukup besar
menunjukkan bahwa komponen organik pada kerang darah diduga bersifat polar
polar dan semi polar karena dapat larut pada pelarut metanol dan etil asetat.
0,0538
0,4978
0,00150.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Heksana Etil asetat Metanol
Jenis Pelarut
Ren
dem
en (%
)
RendemenEkstrak KerangDarah

4.3. Uji Aktivitas Antibakteri
4.3.1. Uji pendahuluan aktivitas antibakteri
Ekstrak kerang darah yang telah diperoleh dari proses ekstraksi
selanjutnya diuji aktivitasnya sebagai senyawa antibakteri terhadap dua jenis
bakteri patogen yang mewakili bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yaitu
S. aureus (OD = 0,723) dan E. coli (OD = 0,788). Lalitha (2004) menjelaskan
bahwa interval OD (Optical Density) bakteri yang digunakan pada uji antibakteri
adalah 0,6-0,8. Davis dan Strout (1971) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
antibiotik dengan diameter zona hambat 20 mm atau lebih berarti sangat kuat,
diameter zona hambat 10-20 mm berarti kuat, diameter zona hambat 5-10 mm
berarti sedang dan diameter zona hambat 5 mm atau kurang berarti lemah. Hasil
pengujian aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah dengan konsentrasi ekstrak
2% disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah pada konsentrasi 2%
Jenis bakteri
Diameter zona hambat (mm) Ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat
Ekstrak kerang darah dengan
pelarut metanol
Kontrol (kloramfenikol)
E. coli S. aureus
6 7
- -
23 28
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat memiliki daya hambat sedang dalam menghambat pertumbuhan
bakteri E. coli dengan diameter zona hambat sebesar 6 mm dan bakteri S. aureus
dengan diameter zona hambat sebesar 7 mm. Ekstrak kerang darah dengan
pelarut metanol tidak menunjukkan aktivitas penghambatan baik pada
pertumbuhan E. coli maupun S. aureus, hal ini diduga karena komponen aktif
kerang darah yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri pada ekstrak kerang
darah dengan pelarut metanol lebih rendah apabila dibandingkan dengan ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat, selain itu diduga karena konsentrasi
ekstrak yang digunakan terlalu rendah sehingga tidak menunjukkan aktivitas
antibakteri. Pelarut etil asetat merupakan pelarut organik yang banyak digunakan
sebagai pelarut dalam ekstraksi senyawa antimikroba, misalnya ekstraksi senyawa
antimikroba dari daun ketimun dan babadotan (Gunawan et al. 1999) dan

ekstraksi senyawa antibakteri dari produk gambir (Pambayun et al. 2007).
Aktivitas antimikroba in vitro dipengaruhi beberapa hal, seperti pH lingkungan,
komponen-komponen media, stabilitas obat, takaran inokulum, lama inkubasi
serta aktivitas metabolisme mikroorganisme (Irianto 2006). Uji aktivitas
antibakteri tidak dilakukan pada ekstrak kerang darah dengan pelarut heksana
karena rendemen ekstrak yang sedikit.
Hasil positif uji antibakteri oleh ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat dan hasil negatif uji antibakteri oleh ekstrak kerang darah dengan pelarut
metanol pada konsentrasi 2% menunjukkan dugaan bahwa komponen aktif pada
kerang darah yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri bersifat semi polar
karena terlarut pada pelarut etil asetat yang bersifat semi polar. Dugaan ini
didukung oleh pustaka yang menyatakan bahwa senyawa polar lebih mudah larut
dalam pelarut polar, senyawa semi polar mudah larut pada pelarut semi polar dan
senyawa non polar lebih larut dalam pelarut non polar (Sudarmadji et al. 2007).
Kloramfenikol sebagai antibakteri kontrol mampu menghasilkan zona
hambat dengan diameter sebesar 23 mm pada E. coli dan 28 mm pada S. aureus
pada konsentrasi kloramfenikol sebesar 2%. Berdasarkan diameter zona hambat
yang dihasilkan, kloramfenikol termasuk antibakteri dengan kemampuan
penghambatan kuat. Hasil tersebut didukung oleh penjelasan pada penelitian
Davis dan Strout (1971) yang menyatakan bahwa antibiotik dengan diameter zona
hambat 10-20 mm termasuk antibiotik kuat.
Zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol jauh lebih besar apabila
dibandingkan dengan zona hambat yang dihasilkan ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol. Hal tersebut
dikarenakan kloramfenikol merupakan antibiotik yang memiliki spektrum luas
dalam menghambat pertumbuhan bakteri baik gram positif maupun gram negatif
(Pelczar dan Chan 1988).
4.3.2. Uji aktivitas antibakteri dengan berbagai konsentrasi
Uji aktivitas antibakteri pada media MHA (Mueller Hinton Agar) dari
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan
pelarut metanol pada beberapa konsentrasi dilakukan berdasarkan uji pendahuluan
aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah. Konsentrasi ekstrak kerang darah yang

digunakan adalah 2%, 3,5%, 5% dan 6,5% (modifikasi Darusman et al. 1994)
dengan ukuran masing-masing diameter zona hambat yang dihasilkan tertera pada
Tabel 8.
Uji aktivitas antibakteri dengan berbagai konsentrasi ekstrak dilakukan
untuk mengetahui konsentrasi minimum dari tiap ekstrak yang dapat menghambat
aktivitas pertumbuhan bakteri uji. Uji aktivitas dilakukan pada 15 ml media MHA
menggunakan paper disk yang telah ditetesi 20 μl ekstrak dengan konsentrasi
masing-masing adalah 2%, 3,5%, 5% dan 6,5% terhadap dua bakteri uji, yaitu
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Contoh perhitungan konsentrasi
ekstrak per paper disk dapat dilihat pada Lampiran 6.
Tabel 8 Aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah pada berbagai konsentrasi
Konsentrasi ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat (%)
Zona hambat (mm)
E. coli S. aureus
2 3,5 5 6,5
1 2 3 4
3 4 6 7
Konsentrasi ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol (%)
Zona hambat (mm)
E. coli S. aureus
2 3,5 5 6,5
- -
0,5 1
- -
0,5 1
Konsentrasi kloramfenikol (%)
Zona hambat (mm) E. coli S. aureus
2 3,5 5 6,5
25 27 31 36
31 38 41 43
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli (OD = 0,797)
dan bakteri S. aureus (OD = 0,750) pada semua konsentrasi ekstrak. Ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat memiliki aktivitas lemah dalam
menghambat pertumbuhan E. coli pada semua konsentrasi ekstrak karena
diameter zona hambat yang dihasilkan oleh keempat konsentrasi ekstrak kurang
dari 5 mm. Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat memiliki aktivitas

lemah dalam menghambat pertumbuhan S. aureus pada konsentrasi 2% dan 3,5%
dengan diameter zona hambat masing-masing 3 mm dan 4 mm tetapi memiliki
aktivitas sedang pada konsentrasi 5% dan 6,5% dengan diameter zona hambat
masing-masing 6 mm dan 7 mm. Hasil pengukuran diameter zona hambat
tersebut menunjukkan bahwa ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
dengan konsentrasi 6,5% pada bakteri E. coli memiliki kekuatan sama dengan
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat 3,5% dalam menghambat aktivitas
pertumbuhan bakteri S. aureus yaitu dengan diameter zona hambat sebesar 4 mm.
Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dengan konsentrasi 5% dalam
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli memiliki diameter zona hambat yang
sama dengan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat 2% dalam
menghambat bakteri S. aureus yaitu sebesar 3 mm.
Ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol tidak menunjukkan aktivitas
penghambatan pada pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus pada konsentrasi
2% dan 3,5%, tetapi menunjukkan aktivitas lemah pada konsentrasi 5% dan 6,5%
dengan diameter zona hambat masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Hal tersebut
diduga karena komponen aktif yang berpotensi sebagai antibakteri yang terlarut
dalam ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol lebih rendah apabila
dibandingkan dengan komponen antibakteri yang terlarut pada etil asetat sehingga
kemampuan penghambatan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol lebih
rendah.
Diameter zona hambat yang dihasilkan ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol pada bakteri
E. coli selalu lebih kecil apabila dibandingkan dengan diameter zona hambat
bakteri S. aureus. Kondisi tersebut diduga karena E. coli lebih tahan terhadap
senyawa antibakteri apabila dibandingkan dengan S. aureus. Dugaan tersebut
didukung oleh pernyataan yang menyebutkan bahwa bakteri gram positif lebih
sensitif terhadap penambahan desinfektan daripada bakteri gram negatif
(Greenwood et al. 1995). Alakomi et al. (2000) diacu dalam Adolf (2006) juga
menjelaskan bahwa S. aureus merupakan bakteri gram positif yang memiliki 40
lapisan peptidoglikan dan merupakan 50% dari bahan dinding sel. Bakteri E. coli
adalah bakteri gram negatif yang memiliki 1-2 lapisan peptidoglikan dan

merupakan 5-10% dari bahan dinding sel tetapi bakteri gram negatif memiliki
lapisan tambahan pada dinding sel yang disebut membran luar terdiri dari lapisan
lipopolisakarida yang berfungsi sebagai penghalang masuknya senyawa-senyawa
yang tidak diperlukan sel, sehingga bakteri gram negatif lebih resisten terhadap
adanya senyawa asing, seperti senyawa antibakteri, karena terlebih dulu ditahan
oleh membran luar yang berupa lipopolisakarida.
Daya hambat yang dihasilkan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat lebih besar daripada daya hambat yang dihasilkan oleh ekstrak kerang darah
dengan pelarut metanol dikarenakan etil asetat merupakan pelarut semi polar yang
mampu mengekstrak senyawa fenol, terpenoid dan alkaloid sedangkan pelarut
metanol mampu mengekstrak alkaloid kuartener dan komponen fenolik lainnya
(Harborne 1987). Darusman et al. (1994) menjelaskan bahwa beberapa
komponen yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri antara lain senyawa
alkaloid, terpenoid dan flavonoid.
Zona hambat yang dihasilkan oleh kloramfenikol, baik bakteri E. coli
maupun S. aureus, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan zona hambat
yang dihasilkan oleh ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol dan ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat. Hal ini dikarenakan kloramfenikol
mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam spektrum yang luas dalam
konsentrasi rendah. Aktivitas antibakteri kloramfenikol tidak bisa dibandingkan
dengan aktivitas antibakteri ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
maupun ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol dari segi diameter zona
hambat yang dihasilkan, tetapi apabila dilihat dari segi keamanan maka ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut
metanol akan memiliki keunggulan karena sumber bahan bakunya yang berasal
dari alam, sedangkan kloramfenikol merupakan senyawa antimikroba sintesis
yang berbahaya bagi kesehatan. Darmowandowo dan Kaspan (2009) menyatakan
bahwa akumulasi kloramfenikol yang berlebihan dalam tubuh akan menyebabkan
gangguan kesehatan seperti gangguan pada sumsum tulang belakang, leukimia
dan gray baby syndrome.
Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol pada uji

pendahuluan aktivitas antibakteri berbeda dengan diameter zona hambat ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat dan ekstrak kerang darah dengan pelarut
metanol pada uji aktivitas antibakteri dengan berbagai konsentrasi ekstrak, hal ini
diduga karena terjadi perbedaan waktu pengambilan sampel kerang darah.
Kerang darah yang digunakan pada uji pendahuluan aktivitas antibakteri diambil
dari pasar ikan Muara Angke, Jakarta Utara pada bulan September 2008
sedangkan kerang darah yang digunakan pada uji aktivitas antibakteri pada
berbagai konsentrasi ekstrak diambil dari pasar ikan Muara Angke, Jakarta Utara
pada bulan November 2008. Perbedaan waktu pengambilan sampel tersebut
diduga berkaitan dengan perbedaan musim, karena perbedaan musim
menyebabkan terjadinya perubahan metabolisme pada tubuh organisme akibat
perubahan kondisi lingkungan, sehingga menyebabkan komponen aktif yang
terdapat dalam tubuh juga mengalami perubahan. Dugaan tersebut didukung oleh
Hans (2004) yang menyebutkan bahwa senyawa bioaktif hasil ekstraksi dari
organisme yang hidup pada lingkungan dengan tingkat gangguan rendah berbeda
dengan senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh organisme yang hidup pada
lingkungan dengan tingkat gangguan tinggi. Hal ini dikarenakan organisme yang
hidup di lingkungan dengan tingkat gangguan rendah menggunakan energinya
untuk pertumbuhan dan reproduksi, sehingga produksi metabolit sekunder yang
dihasilkan lebih rendah. Organisme yang hidup pada lingkungan dengan tingkat
gangguan tinggi menggunakan energinya untuk pertumbuhan, reproduksi dan
memproduksi metabolit sekunder sebagai fasilitas untuk pertahanan diri, sehingga
ketika dilakukan ekstraksi maka senyawa bioaktif yang dihasilkan dari organisme
yang hidup di daerah dengan gangguan tinggi akan lebih besar daripada
organisme yang hidup di daerah dengan gangguan lingkungan yang lebih rendah.
4.3.3. Pengamatan zona hambat pada penyimpanan suhu 10oC dan 30oC
Aktivitas desinfektan bergantung dari beberapa faktor, antara lain
konsentrasi desinfektan, jumlah dan tipe mikroorganisme, serta perlakuan suhu
dan pH (Greenwood et al. 1995). Pada penelitian ini dilakukan pengamatan
diameter zona hambat selama tujuh hari pada suhu 10oC dan suhu 30oC dengan
tujuan mengetahui kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri.

Ekstrak yang digunakan adalah ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
karena berdasarkan uji pendahuluan aktivitas antibakteri, ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat menunjukkan kemampuan penghambatan lebih baik
apabila dibandingkan dengan ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol.
a. Suhu 10oC
Suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri dan efektivitas
kerja senyawa antibakteri. Suhu dibawah suhu optimum untuk pertumbuhan
dapat menekan laju metabolisme dan apabila suhu cukup rendah maka
metabolisme dan pertumbuhan bakteri akan terhenti. Tetapi bakteri mempunyai
kemampuan yang unik untuk dapat bertahan hidup pada keadaan yang sangat
dingin (Pelczar dan Chan 1988). Suhu rendah pada umumnya akan meningkatkan
efektivitas kerja senyawa antibakteri (Irianto 2006).
Tabel 9 Pengamatan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
pada penyimpanan suhu 10oC
Konsentrasi ekstrak
Kekeruhan zona hambat E. coli S. aureus
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H72% + + + ++ ++ ++ ++ - - + + + + + 3,5% + + + ++ ++ ++ ++ - - + + + + +5% - - - - + + + - - - - - + + 6,5% - - - - + + + - - - - - - -
Keterangan : (-) = jernih (+) = sedikit keruh (++) = keruh (+++) = lebih keruh
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa kemampuan ekstrak kerang
darah dengan pelarut etil asetat mengalami penurunan aktivitas dalam
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan bakteri S. aureus pada penyimpanan
suhu 10oC yang ditandai dengan peningkatan kekeruhan zona hambat seiring
dengan meningkatnya waktu penyimpanan. Pada hari pertama pengamatan
terhadap bakteri E. coli, ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat 2% dan
3,5% menunjukkan zona hambat yang sedikit keruh, sedangkan ekstrak kerang
darah dengan pelarut etil asetat 5% dan 6,5% menunjukkan zona hambat yang
jernih.

Zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat konsentrasi
2% dan 3,5% mulai mengalami peningkatan kekeruhan pada hari keempat
pengamatan. Peningkatan kekeruhan zona hambat dari agak keruh menjadi keruh
tersebut menunjukkan bahwa terdapat bakteri yang tumbuh, diduga akibat telah
berkurangnya aktivitas senyawa antibakteri dari ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat. Bakteri E. coli tidak dapat tumbuh pada suhu 10oC karena suhu
tersebut berada di bawah kisaran suhu pertumbuhan E. coli. Hal ini telah sesuai
dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa bakteri E. coli tumbuh pada suhu
15-45oC (Fardiaz 1992). Bakteri yang tumbuh pada zona hambat tersebut diduga
merupakan bakteri kontaminasi yang mampu tumbuh pada suhu lingkungan 10oC.
Hal ini dikarenakan pada metode uji terdapat proses penghomogenan dengan
menggunakan vorteks, sehingga diduga kontaminasi berasal dari proses tersebut.
Aktivitas penghambatan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
dengan konsentrasi 5% dan 6,5% mulai menunjukkan penurunan pada hari kelima
pengamatan yang ditandai dengan peningkatan kekeruhan zona hambat yang
dihasilkan. Pada hari keempat hingga hari ketujuh pengamatan, zona hambat
yang terbentuk menjadi lebih keruh yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan
bakteri. Zona hambat yang semula jernih berubah menjadi agak keruh
menunjukkan adanya aktivitas pertumbuhan bakteri pada zona hambat tersebut.
Peningkatan kekeruhan pada media agar diduga karena terjadi penurunan
efektivitas ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dalam menghambat
pertumbuhan bakteri E. coli.
Zona hambat yang dihasilkan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus pada konsentrasi 2%,
3,5%, 5% dan 6,5% menunjukkan zona yang jernih pada hari pertama
pengamatan. Peningkatan kekeruhan zona hambat selama penyimpanan terjadi
pada ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada konsentrasi 2%, 3,5%
dan 5%, tetapi tidak terjadi pada ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
6,5%. Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dengan konsentrasi 2% dan
3,5% mengalami peningkatan kekeruhan zona hambat mulai pada hari ketiga
pengamatan yang ditandai dengan perubahan zona dari jernih menjadi sedikit
keruh. Ekstak kerang darah dengan pelarut etil asetat dengan konsentrasi 5%

mengalami peningkatan kekeruhan zona hambat pada hari keenam pengamatan
yang ditandai dengan perubahan zona hambat yang semula jernih menjadi sedikit
keruh. Terjadinya peningkatan kekeruhan pada zona hambat yang dihasilkan
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dalam menghambat pertumbuhan
bakteri S. aureus tersebut diduga karena terjadinya penurunan aktivitas kerja dari
senyawa antibakteri yang diberikan serta kemampuan bakteri uji dalam
berkembang biak pada suhu lingkungan sebesar 10oC. Dugaan tersebut diperkuat
dengan pernyataan bahwa bakteri S. aureus mampu tumbuh pada interval suhu
6,7-45,5oC (Pelczar dan Chan 1988).
Havsteen (2002) diacu dalam Sabir (2005) juga menyatakan bahwa
penurunan metabolisme senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri
akan berakibat pada penurunan aktivitas antibakteri, sehingga terjadi
kemungkinan bakteri tumbuh kembali. Penurunan aktivitas antibakteri ini
tergantung dari waktu kontak senyawa antibakteri dengan bakteri uji, semakin
lama kontak senyawa antibakteri dengan bakteri uji, maka akan semakin menurun
aktivitas senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji.
Ukuran diameter zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat pada bakteri S. aureus yang lebih besar apabila dibandingkan dengan
diameter zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada bakteri
E. coli. Hal ini diduga karena bakteri S. aureus lebih rentan terhadap senyawa
asing yang bertindak sebagai senyawa antibakteri apabila dibandingkan dengan
bakteri E. coli. Dugaan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang menjelaskan
bahwa S. aureus merupakan bakteri yang sensitif terhadap beberapa bahan
antimikroba, seperti benzylpenisilin, ampisilin, amoksilin, karbenisilin, azlosilin
dan piperasilin yang merupakan golongan penisilin (Greenwood et al. 1995).
Zona hambat yang dihasilkan oleh kloramfenikol dalam menghambat
pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus menunjukkan zona yang jernih pada
konsentrasi kloramfenikol 2%, 3,5%, 5% dan 6,5% (Tabel 10). Peningkatan
kekeruhan zona hambat kloramfenikol dengan konsentrasi 2% dalam menghambat
pertumbuhan bakteri E. coli terjadi pada hari keenam pengamatan yang ditandai
dengan berubahnya zona hambat yang semula jernih menjadi agak keruh.

Tabel 10 Pengamatan zona hambat kloramfenikol pada penyimpanan suhu 10oC
Konsentrasi kloramfenikol
Kekeruhan zona hambat E. coli S. aureus
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H72% - - - - - + + - - - - - - + 3,5% - - - - - - + - - - - - - + 5% - - - - - - - - - - - - - - 6,5% - - - - - - - - - - - - - -
Keterangan : (-) = jernih (+) = sedikit keruh (++) = keruh (+++) = lebih keruh
Kloramfenikol dengan konsentrasi 3,5% juga mengalami perubahan
kekeruhan dari jernih menjadi agak keruh pada hari ketujuh pengamatan, tetapi
zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol dengan konsentrasi 5% dan 6,5%
tetap jernih hingga hari ketujuh pengamatan. Peningkatan kekeruhan zona hambat
dari agak keruh menjadi keruh tersebut menunjukkan bahwa terdapat bakteri yang
tumbuh, diduga akibat telah berkurangnya aktivitas senyawa antibakteri dari
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat. Bakteri yang tumbuh pada zona
hambat tersebut diduga merupakan bakteri kontaminasi yang mampu tumbuh pada
suhu lingkungan 10oC. Hal ini dikarenakan pada metode uji terdapat proses
penghomogenan dengan menggunakan vorteks, sehingga diduga kontaminasi
berasal dari proses tersebut. Bakteri E. coli tidak dapat tumbuh pada suhu 10oC
karena suhu tersebut berada di bawah kisaran suhu pertumbuhan E. coli. Hal ini
telah sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa bakteri E. coli tumbuh
pada suhu 15-45oC (Fardiaz 1992).
Peningkatan kekeruhan zona hambat kloramfenikol dalam menghambat
pertumbuhan bakteri S. aureus terjadi pada hari ketujuh pengamatan yaitu pada
kloramfenikol dengan konsentrasi 2% dan 3,5%, tetapi kloramfenikol pada
konsentrasi 5% dan 6,5% tetap jernih hingga hari ketujuh pengamatan. Zona
hambat yang dihasilkan kloramfenikol terhadap bakteri E. coli dan S. aureus yang
masih jernih dan stabil hingga akhir pengamatan tersebut menunjukkan bahwa
kloramfenikol mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun
bakteri gram negatif. Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan bahwa
kloramfenikol merupakan senyawa antibiotik yang paling stabil dan masih banyak

digunakan oleh masyarakat di negara-negara berkembang karena harganya yang
murah dan aktivitas yang baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada
spektrum luas, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, apabila
dibandingkan dengan antibiotik-antibiotik lainnya (Syah et al. 2005).
Ukuran diameter zona hambat yang dihasilkan oleh kloramfenikol pada
bakteri S. aureus lebih besar apabila dibandingkan dengan diameter zona hambat
yang dihasilkan kloramfenikol pada bakteri E. coli. Hal ini diduga karena bakteri
S. aureus lebih sensitif terhadap senyawa asing yang bertindak sebagai senyawa
antibakteri apabila dibandingkan dengan bakteri E. coli. Dugaan tersebut
diperkuat oleh pernyataan yang menjelaskan bahwa bakteri S. aureus merupakan
bakteri yang sensitif terhadap beberapa bahan antimikroba, antara lain
benzylpenisilin, ampisilin, amoksilin, karbenisilin, azlosilin dan piperasilin yang
merupakan golongan penisilin (Greenwood et al. 1995).
b. Suhu 30oC
Zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat terhadap
bakteri E. coli dan S. aureus pada penyimpanan suhu 30oC terus mengalami
peningkatan kekeruhan (Tabel 11). Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat pada konsentrasi 2% dan 3,5% menunjukkan zona hambat sedikit keruh
dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, tetapi ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat dengan konsentrasi 5% dan 6,5% menunjukkan zona
hambat jernih. Zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada
konsentrasi 2% dan 3,5% mengalami perubahan keadaan menjadi keruh pada hari
ketiga pengamatan dan lebih keruh pada hari kelima pengamatan. Ekstrak kerang
darah dengan pelarut etil asetat pada konsentrasi 5% yang semula jernih berubah
sedikit keruh pada hari ketiga pengamatan, menjadi keruh pada hari kelima
pengamatan dan lebih keruh pada hari ketujuh pengamatan. Zona hambat ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat pada konsentrasi 6,5% yang jernih berubah
sedikit keruh pada hari ketiga pengamatan dan menjadi keruh pada hari keenam
pengamatan.

Tabel 11 Pengamatan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada penyimpanan suhu 30oC
Konsentrasi ekstrak
Kekeruhan zona hambat E. coli S. aureus
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
2% + + ++ ++ +++
+++
+++ - + ++ ++ ++
+ +++
+++
3,5% + + ++ ++ +++
+++
+++ - + ++ ++ ++ ++
+ +++
5% - - + + ++ ++ +++ - - + + ++ ++ ++
6,5% - - + + + ++ ++ - - + + + ++ ++
Keterangan : (-) = jernih (+) = sedikit keruh (++) = keruh (+++) = lebih keruh
Zona hambat yang ditunjukkan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus pada hari pertama
adalah jernih pada konsentrasi ekstrak 2%, 3,3%, 5% dan 6,5% (Tabel 11).
Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat pada konsentrasi 2% mengalami
peningkatan kekeruhan zona hambat menjadi sedikit keruh pada hari kedua
pengamatan, keruh pada hari ketiga pengamatan dan lebih keruh pada hari kelima
pengamatan. Zona hambat yang dihasilkan ekstrak kerang darah dengan pelarut
etil asetat pada konsentrasi 3,5% berubah menjadi sedikit keruh pada hari kedua
pengamatan, keruh pada hari ketiga pengamatan dan lebih keruh pada hari
keenam hingga ketujuh pengamatan. Ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat 5% menunjukkan peningkatan kekeruhan zona hambat mulai pada hari
ketiga pengamatan, yaitu menjadi sedikit keruh dan menjadi keruh pada hari
kelima pengamatan. Zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat pada konsentrasi 6,5% mengalami peningkatan
kekeruhan pada hari ketiga pengamatan, yaitu menjadi sedikit keruh dan menjadi
keruh pada hari keenam hingga ketujuh pengamatan.
Peningkatan kekeruhan zona hambat diduga karena kemampuan
penghambatan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat telah mengalami
penurunan, sehingga bakteri kembali mengalami pertumbuhan. Dugaan tersebut
diperkuat oleh pernyataan Havsteen (2002) diacu dalam Sabir (2005) yang

menjelaskan bahwa semakin lama waktu kontak senyawa antibakteri dengan
bakteri uji, maka akan terjadi penurunan aktivitas antibakteri, hal ini diduga akibat
terjadinya penurunan metabolisme senyawa-senyawa dalam ekstrak yang
berpotensi sebagai antibakteri.
Dugaan lain mengenai penyebab peningkataan kekeruhan zona hambat
adalah bakteri uji mampu tumbuh dan berkembang biak pada suhu 30oC. Dugaan
tersebut didukung oleh pustaka yang menyatakan bahwa bakteri E. coli mampu
tumbuh pada suhu 15-45oC (Fardiaz 1992) dan bakteri S. aureus mampu tumbuh
pada suhu 6,7-45,5oC (Pelczar dan Chan 1988). Sumber lain menyebutkan bahwa
aktivitas mematikan bakteri berbanding terbalik antara suhu dengan waktu. Pada
umumnya semakin rendah suhu yang digunakan maka waktu yang dibutuhkan
untuk membunuh mikroorganisme tersebut akan semakin lama. Tetapi dalam hal
uji aktivitas antibakteri, peningkatan suhu akan mengurangi tegangan permukaan
sehingga mengurangi viskositas dan akhirnya mengurangi absorpsi. Akibat
berkurangnya absorpsi ini, efektivitas desinfektan akan berkurang (Irianto 2006).
Kekeruhan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
dalam menghambat pertumbuhan S. aureus lebih baik apabila dibandingkan
dengan kekeruhan zona hambat ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Hal ini diduga karena S. aureus
yang merupakan bakteri gram positif dikenal sebagai bakteri yang lebih rentan
terhadap antibiotik sehingga kemampuan ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut lebih tahan lama. Dugaan
tersebut diperkuat oleh pernyataan yang menjelaskan bahwa bakteri S. aureus
merupakan bakteri yang sensitif terhadap beberapa bahan antimikroba, antara lain
benzylpenisilin, ampisilin, amoksilin, karbenisilin, azlosilin dan piperasilin yang
merupakan golongan penisilin (Greenwood et al. 1995).
Uji aktivitas antibakteri dengan kloramfenikol sebagai antibakteri kontrol
menunjukkan peningkatan kekeruhan zona hambat pada bakteri E. coli dan bakteri
S. aureus (Tabel 12). Zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol dalam
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli adalah jernih pada konsentrasi 2%,
3,5%, 5% dan 6,5%. Zona hambat kloramfenikol 2% dan 3,5% berubah menjadi
sedikit keruh pada hari kelima hingga ketujuh pengamatan, zona hambat

kloramfenikol 5% berubah menjadi sedikit keruh pada hari keenam hingga hari
ketujuh pengamatan dan zona hambat kloramfenikol 6,5% berubah menjadi
sedikit keruh pada hari ketujuh pengamatan.
Tabel 12 Pengamatan zona hambat kloramfenikol pada penyimpanan suhu 30oC
Konsentrasi kloramfenikol
Kekeruhan zona hambat E. coli S. aureus
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H72% - - - - + + + - - - - - + +3,5% - - - - + + + - - - - - - + 5% - - - - - + + - - - - - - + 6,5% - - - - - - + - - - - - - +
Keterangan : (-) = jernih (+) = sedikit keruh (++) = keruh (+++) = lebih keruh
Zona hambat kloramfenikol dalam menghambat pertumbuhan bakteri
S. aureus menunjukkan zona yang jernih pada konsentrasi kloramfenikol 2%,
3,5%, 5% dan 6,5%. Zona hambat kloramfenikol 2% mulai berubah menjadi
sedikit keruh pada hari keenam pengamatan, sedangkan zona hambat
kloramfenikol 3,5%, 5% dan 6,5% berubah menjadi sedikit keruh pada hari
ketujuh pengamatan.
Zona hambat yang dihasilkan oleh kloramfenikol dalam menghambat
pertumbuhan bakteri E. coli dan bakteri S. aureus cenderung stabil dari awal
hingga akhir pengamatan, diduga karena kloramfenikol merupakan antibiotik
yang efektif dalam menghambat pertumbuhan kedua jenis bakteri uji. Dugaan ini
diperkuat dengan pustaka yang menyatakan bahwa kloramfenikol merupakan
antibiotik berspektrum luas yang aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri
gram positif dan bakteri gram negatif (Pelczar dan Chan 1988).
Kloramfenikol merupakan antibiotik yang telah disintesis dan diproduksi
secara massal. Antibiotik ini mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme
pada spektrum yang luas dan hingga saat ini masih banyak digunakan oleh
masyarakat, terutama masyarakat di negara-negara dengan pendapatan rendah,
karena harganya yang relatif murah dan efektivitasnya yang stabil. Tetapi di
negara-negara maju, penggunaan kloramfenikol sebagai antibiotik telah jarang

dijumpai karena efek yang ditimbulkan oleh kloramfenikol cukup serius, yaitu
dapat menyebabkan anemia aplastik (Syah et al. 2005).
Diameter zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol terhadap bakteri
S. aureus lebih besar daripada zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol
terhadap bakteri E. coli. Hal ini dikarenakan bakteri S. aureus lebih sensitif
terhadap penambahan antibiotik, seperti β-lactam, tetrasiklin dan kloramfenikol
(Pelczar dan Chan 1988). Alakomi et al. (2000) diacu dalam Adolf (2006)
menyebutkan bahwa bakteri E. coli yang merupakan bakteri gram negatif yang
memiliki lapisan tambahan pada dinding sel dan dikenal dengan membran luar.
Membran luar ini tersusun atas lipopolisakarida yang berfungsi sebagai
penghalang masuknya senyawa-senyawa yang tidak diperlukan sel, sehingga
bakteri E. coli lebih tahan terhadap penambahan antibiotik.
4.4. Analisis Fitokimia
Analisis fitokimia merupakan analisis yang diterapkan untuk mengetahui
golongan senyawa yang terkandung dalam suatu bahan yang tidak dibutuhkan
untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek menguntungkan bagi manusia.
Komponen fitokimia bukan merupakan zat gizi karena tanpa komponen tersebut
tubuh manusia tetap melakukan metabolisme secara normal, tetapi konsumsi
senyawa fitokimia akan membantu meningkatkan kesehatan dan ketahanan tubuh
manusia (Astawan dan Kasih 2008). Alasan lain melakukan analisis fitokimia
adalah untuk menentukan ciri senyawa aktif penyebab efek racun atau efek
bermanfaat dari suatu ekstrak. Senyawa-senyawa yang biasanya diuji dengan
menggunakan metode fitokimia antara lain senyawa fenol, terpenoid, asam
organik, lipid, senyawa nitrogen, gula dan turunannya serta beberapa
makromolekul (Harborne 1987). Berkaitan dengan fungsinya sebagai antibakteri,
analisis fitokimia terhadap ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat meliputi
analisis senyawa alkaloid, steroid dan flavonoid (Darusman et al. 1994). Tabel 13
menunjukkan hasil analisis fitokimia terhadap ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat.

Tabel 13 Analisis fitokimia ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
Jenis senyawa Hasil Tanda Alkaloid :
Wagner Meyer Dragendorff
(+) (+) (+)
Terbentuk endapan coklat Terdapat endapan putih Terdapat endapan jingga
Steroid (+) Larutan berwarna hijau
Flavonoid (-) Tidak terbentuk warna kekuningan pada lapisan amil alkohol
Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat mengandung senyawa metabolit sekunder yang berupa alkaloid
dan steroid, sedangkan senyawa flavonoid menunjukkan hasil negatif dalam
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat. Uji alkaloid terhadap ekstrak
kerang darah dengan pelarut etil asetat dinyatakan positif karena ketika
direaksikan dengan pereaksi Wagner membentuk endapan berwarna cokelat,
ketika direaksikan dengan pereaksi Meyer membentuk endapan berwarna putih
dan ketika direaksikan dengan pereaksi Dragendorff akan membentuk endapan
berwarna jingga. Gambar hasil analisis fitokimia disajikan pada Gambar 14.
Alkaloid merupakan grup terbesar senyawa metabolit sekunder yang
terdapat pada produk alami dan sering kali memiliki sifat beracun sehingga
digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harborne 1987). Sifat beracun
dari alkaloid memperkuat alasan bahwa ekstrak kerang darah dengan pelarut etil
asetat memiliki aktivitas antibakteri. Verpoorte dan Alfermann (2000)
menyebutkan bahwa alkaloid pada tumbuhan berfungsi sebagai pelindung dari
prodator karena bersifat racun pada satwa misalnya serangga, sebagai zat
perangsang dan pengatur tumbuh dan membantu aktivitas metabolisme dan
reproduksi tumbuhan. Yunus (1998) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
alkaloid memiliki sifat farmakologis, salah satunya adalah memperlebar saluran
pernafasan pada penderita sesak nafas.

(a) (b)
(c)
(d) (e)
Gambar 14 Hasil analisis fitokimia ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat.
Keterangan: (a) Uji alkaloid dengan pereaksi Dragendorff (b) Uji alkaloid dengan pereaksi Meyer (c) Uji alkaloid dengan pereaksi Wagner (d) Uji Steroid (e) Uji flavonoid
Uji steroid terhadap ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
menunjukkan hasil positif yang ditunjukkan dengan terbentuknya larutan
berwarna hijau. Steroid merupakan senyawa yang dapat dijumpai hampir pada
semua makhluk hidup kecuali pada bakteri (Fessenden dan Fessenden 1997).
Steroid telah banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, seperti sebagai bahan
terapeutik yaitu bahan untuk pengobatan suatu penyakit (Pelczar dan Chan 1988).
Yunus (1998) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa steroid dapat digunakan
sebagai obat antiintlamasi pada penderita asma, sebagai senyawa mampu
memerangi kolesterol jahat dalam tubuh dan bermanfaat sebagai afrodisiaka.
Pemanfaatan steroid sebagai bahan obat-obatan tersebut dapat memperkuat
dugaan adannya senyawa antibakteri pada ekstrak kerang darah dengan pelarut
etil asetat.
Uji flavonoid terhadap ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat tidak
menunjukkan hasil positif karena lapisan amil alkohol tidak menunjukkan adanya
perubahan warna kuning atau jingga. Flavonoid merupakan senyawa metabolit

sekunder yang berperan sebagai faktor pertahanan alam, seperti mencegah
serangan bakteri, yang ditemukan pada sebagian besar tumbuhan. Flavonoid
terdapat pada semua tumbuhan berpembuluh (Harborne 1987). Sabir (2005)
menjelaskan bahwa flavonoid memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan
bakteri secara in vitro. Bryan (1982); Wilson dan Gisvold (1982) diacu dalam
Sabir (2005) menjelaskan bahwa senyawa flavonoid memiliki kemampuan
menghambat pertumbuhan bakteri dengan beberapa mekanisme yang berbeda,
antara lain flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding
bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan
DNA bakteri, sementara Mirzoeva et al. (1997) diacu dalam Sabir (2005) dalam
penelitiannya berpendapat bahwa flavonoid mampu melepaskan energi transduksi
terhadap membran sitoplasma bakteri, selain itu juga menghambat motilitas
bakteri. Mekanisme yang berbeda dikemukakan oleh Di Carlo et al. (1999) dan
Estrela et al. (1995) diacu dalam Sabir (2005) yang menyatakan bahwa gugus
hidroksil yang terdapat pada struktur senyawa flavonoid menyebabkan perubahan
komponen organik dan transpor nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan
timbulnya efek toksik terhadap bakteri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berat ekstrak kerang darah dengan pelarut heksana adalah 3,00±1,40 mg,
ekstrak dengan pelarut etil asetat sebesar 107,50±3,50 mg dan ekstrak dengan
pelarut metanol sebesar 995,50±0,70 mg. Uji pendahuluan aktivitas antibakteri
dengan konsentrasi ekstrak 2% menunjukkan hasil bahwa ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat mampu menghambat pertumbuhan E. coli dengan
diameter zona hambat sebesar 6 mm dan menghambat pertumbuhan S. aureus
dengan diameter zona hambat sebesar 7 mm, sedangkan ekstrak kerang darah
dengan pelarut metanol tidak menunjukkan penghambatan pada kedua bakteri uji.
Uji aktivitas antibakteri dilakukan pada ekstrak dengan konsentrasi 2%,
3,5%, 5% dan 6,5%. Daya hambat rendah ditunjukkan oleh ekstrak kerang darah
dengan pelarut etil asetat dalam menghambat pertumbuhan E. coli pada setiap
konsentrasi ekstrak (< 5 mm) dan daya hambat sedang dalam menghambat S.
aureus (5-10 mm). Ekstrak kerang darah dengan pelarut metanol tidak
menunjukkan aktivitas penghambatan pada konsentrasi 2% dan 3,5%, tetapi
menunjukkan penghambatan lemah pada konsentrasi ekstrak 5% dan 6,5% (< 5
mm). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa senyawa antibakteri yang terdapat
pada kerang darah diduga bersifat semi polar karena larut dalam pelarut etil asetat.
Pengamatan zona hambat selama tujuh hari pada suhu 10oC dan 30oC
menunjukkan penurunan efektivitas antibakteri dari ekstrak kerang darah dengan
pelarut etil asetat yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan kembali bakteri
S. aureus dan bakteri E. coli.
Analisis fitokimia terhadap ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat
menunjukkan hasil positif terhadap senyawa alkaloid dan steroid, tetapi
menunjukkan hasil negatif terhadap senyawa flavonoid.
5.2. Saran
Perlu dilakukan pemisahan dan pemurnian masing-masing komponen dari
ekstrak kerang darah dengan pelarut etil asetat dan pengkajian lain dari ekstrak
kerang darah, misalnya sebagai senyawa antioksidan.

DAFTAR PUSTAKA
Adolf JN. 2006. Kajian mekanisme antibakteri ekstrak andaliman (Zanthozylum acanthopodium DC) terhadap bakteri patogen pangan [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
[AOAC] Official Method of Analysis of The Assosiation of Official Analytical of
Chemist. 1995. Arlington, USA: Published by The Assosiation of Official Analytical of Chemist Inc.
Asih IARA, Setawan IMA. 2008. Senyawa Golongan Flavonoid pada Ekstrak n-
butanol Kulit Batang Bungur (lagerstroemia speciosa pers.). Jurnal Kimia 2: 111-116.
Astawan M, Kasih AL. 2008. Khasiat Warna-Warni Makanan. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama. Broom MJ. 1985. The Biology and Culture of Marine Bivalvia Mollusca of The
Genus Anadara. Manila: International Centre for Living Aquatic Resources Management.
Bryan LE. 1982. Bacterial Resistance and Susceptibility to Chemotherapheutic
agents. Cambridge: Cambridge University Press. Bunje P. 2001. Bankia setacea and Chlamys sp.
www.ucmp.berkeley.edu/.../biv_anatomy.gif [16 Januari 2006]. Darmowandowo W, Kaspan MF. 2009. Demam tifoid.
http://www.pediatrik.com/isi03.php [21 JAnuari 2009]. Darusman LK, Sajuthi D, Sutriah K, Pamungkas D. 1994. Ekstraksi komponen
bioaktif sebagai bahan obat dari karang-karangan, bunga karang, dan ganggang di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu (Tahap II: Fraksinasi dan Bioassay). Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian; Jakarta, Januari 1994. Jakarta: DIKTI-Depdikbud. hlm 18-29.
Davis WW, Strout TR. 1971. Disc Plate Method of Microbiological Antibiotic
Assay. Applied Microbiology 22:666-670. Di Carlo G, Mascolo N, Izzo AA, Capasso F. 1999. Falvonoids: old and new
aspects of a class of natural therapeutic drugs. Life Sci 65:337–53. [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Perikanan Tangkap.
www.dkp.go.id [9 Desember 2008]. Dyer SD. 2008. Infection desease Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
(MRSA). www.netwellness.org/.../mrsa.cfm [29 November 2008].

Erianto D. 2005. Analisis pengolahan dan pengembangan budidaya kerang darah (Anadara granosa) di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Estrela C, Sydney GB, Bammann LL, Felippe Jr O. 1995. Mechanism of action
calcium and hydroxyl ions of calcium hydroxide on tissue and bacteria. Brazil Dent J 6:85–90.
Fardiaz S. 1992. Mikrobiologi Pangan I. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan
dan Gizi, Institut Pertanian Bogor. Fessenden RJ, Fessenden JS. 1997. Dasar-Dasar Kimia Organik. Maun S, Anas
K, Sally TS, penerjemah; Jakarta: Binarupa Aksara. Terjemahan dari Fundamental of Organic Chemistry.
Greenwood D, Slack RCB, Peutherer JF, editor. 1995. Medical Microbiology.
Ed ke-14. Hongkong: ELBS. Gunawan PW, Yulinah E, Soediro I. 1999. Uji Antiinfeksi pada Punggung Kelinci
dan Telaah Fitokimia Ekstrak Etil Asetat dan Etanol Daun Ketimun dan Babadotan [tesis]. Bandung: Sekolah Farmasi ITB.
Hans A. 2004. Transplantasi spons Laut Aaptos aaptos (Porifera: Demospongiae)
pertumbuhan, sintasan, perkembangan gamet dan bioaktivitas antibakteri ekstrak kasar dan fraksinya [disertasi]. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Harborne JB. 1987. Metode Fitokimia. Padmawinata K, Soediro I, penerjemah;
Bandung: ITB. Terjemahan dari: Phytochemical Methods. Havsteen BH. 2002. The biochemistry and medical significance of flavonoids.
Pharmacol Ther 96:67–202. Houghton PJ dan Raman A. 1988. Laboratory Handbook for Fractination of
Natural Extract: Methods of Extraction and Sample Clean-up. London: Chapman dan Hall Ltd.
Inswiasri, Agustina L, Tri T. 1995. Kandungan logam kadmium dalam biota laut
jenis kerang-kerangan dari Teluk Jakarta. Cermin Dunia Kedokteran 103:19-21.
Irianto K. 2006. Mikrobiologi: Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 1. Bandung:
Yrama Widya.
Lalitha. 2004. Manual an Antimicrobial Suspectibility Testing. India: Indian Association of Medical Microbiologist.

Mirzoeva OK, Grishanin RN, Calder PC. 1997. Antimicrobial action of propolis and some of its components: the effects on growth, membrane potential, and motility of bacteria. Microbiol Res 152:239-46.
Mubarak H. 1987. Distribusi Anadara spp. (Pelecypoda; Archidae) dalam
hubungannya dengan karakteristik lingkungan perairan dan asosiasinya dengan jenis-jenis moluska bentik lain di Teluk Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat [tesis]. Bogor: Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Ninda. 17-30 April 2008. Be Fit: Brain-Workout. Olga 56:88. Noer IS, Nurhayati L. 2006. Bioaktivitas Ulva reticulata forsskal asal Gili Kondo
Lombok Timur terhadap bakteri. Biotika 5:45-60. Nur MA, H Adijuwana. 1989. Teknik Pemisahan dan Analisis Biologis. Bogor:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, PAU Ilmu Hayat, Institut Pertanian Bogor.
Pambayun R, Gardjito M, Sudarmadji M, Kuswanto KR. 2007. Kandungan Fenol
dan Sifat Antibakteri Ekstrak Produk Gambir (Uncaria gambir Roxb). Majalah Farmasi Indonesia 3: 141-145.
Pathansali D. 1966. Notes on Biology of Coockle Culture Anadara granosa L.
Proc IPFC Fish II: 11. Pelczar MJJr, Chan ECS. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi 1. Hadioetomo RS,
Imas T, Tjitrosomo SS, Angka SL, penerjemah; Jakarta: UI Pr. Terjemahan dari Elements of Microbiology.
Pelczar MJJr, Chan ECS. 1988. Dasar-Dasar Mikrobiologi 2. Hadioetomo RS,
Imas T, Tjitrosomo SS, Angka SL, penerjemah; Jakarta: UI Pr. Terjemahan dari Elements of Microbiology.
Poedjiadi A. 1994. Dasar-Dasar Biokimia. Jakarta: UI Press. Sabir A. 2005. Aktivitas antibakteri flavonoid propolis Trigona sp terhadap
bakteri Streptococcus mutans (in vitro). Majalah Kedokteran Gigi (Dent J) 38:135-141.
Storer TI, Usinger RL. 1957. General Zoology. New York: McGraw Hill Book
Coy. Inc. Sudarmadji S, Haryono B, Suhardi. 2007. Analisa Bahan Makanan dan
Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Syah D, Utama S, Mahrus Z, Fauzan F, Siahaan R, Oktavia O, Supriyadi S, Kartawijaya W. 2005. Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan. Bogor.
Tan LWH dan Ng PKL. 2008. Blood Cockle Anadara granosa.
www.mangrove.nus.edu.sg [7 Maret 2008]. Trilaksani W, Nurjanah. 2004. Teknologi Pengolahan Kerang-kerangan. Makalah
disampaikan pada Program Retooling TPSDP kerjasama DIKTI-PKSPL. Departemen Teknologi Hasil Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Verpoorte R, Alfermann AW. 2000. Metabolic Engineering of Plant Secondary
Metabolism. Belanda: Kluwer Academic Publishers. Wikipedia. 2008a. Chloramphenicol. http://en.wikipedia.org/wiki/
Chloramphenicol [25 November 2008]. Wikipedia. 2008b. Escherichia coli. http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
[25 November 2008]. Wilson, Gisvold. 1982. Kimia farmasi dan medisinal organik. Ed ke-8. Jakarta:
Dirjen Dikti dan Kebudayaan. Yuharmen, Erianti Y, Nurbalatif. 2002. Uji Aktivitas Antimikroba Minyak Atsiri
dan Ekstrak Metanol lengkuas (Alpinia galanga). Artikel Kimia: 1-8. Yunus F. 1998. Manfaat Kortikosteroid pada Asma Bronkial. Cermin Dunia
Kedokteran 121:10-15.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan rendemen daging kerang darah (A. granosa)
Berat kerang awal (sebelum preparasi) = 6 kg
Berat kerang setelah preparasi = 1,03 kg
%100preparasisetelah kerangBerat
awal kerangBerat darah kerangRendemen ×=
%17,17%100kg 1,03
kg 6=×=
Lampiran 2. Kerang darah (A. granosa) yang digunakan untuk penelitian

Lampiran 3. Ekstraksi kerang darah (Anadara granosa)
Maserasi heksana
Maserasi etil asetat
Maserasi metanol

Lampiran 4. Perhitungan rendemen ekstrak kerang darah (A. granosa)
Berat awal daging kerang darah = 200 g = 200.000 mg
Berat ekstrak heksana setelah evaporasi = 3 mg
Berat ekstrak etil asetat setelah evaporasi = 107,5 mg
Berat ekstrak heksana setelah evaporasi = 995,5 mg
%100evaporasisetelah ekstrak Berat
awal dagingBerat hdara kerang heksanaekstrak Rendemen ×=
%0015,0%100mg 200000
mg 3=×=
%100evaporasisetelah ekstrak Berat
awal dagingBerat hdara kerangasetat etilekstrak Rendemen ×=
%0538,0%100mg 200000
mg 107,5=×=
%100evaporasisetelah ekstrak Berat
awal dagingBerat hdara kerang metanolekstrak Rendemen ×=
%4978,0%100mg 200000
mg 995,5=×=

Lampiran 5. Uji pendahuluan aktivitas antibakteri pada bakteri E. coli
Keterangan:
E20 : Ekstrak etil asetat 2% E50 : Ekstrak etil asetat 5% M20 : Ekstrak metanol 2% M50 : Ekstrak metanol 5% M100 : Ekstrak metanol 10% Bagian tengah merupakan kontrol (Kloramfenikol 2%)

Lampiran 6. Uji pendahuluan aktivitas antibakteri pada bakteri S. aureus
Keterangan:
E20 : Ekstrak etil asetat 2% E50 : Ekstrak etil asetat 5% M20 : Ekstrak metanol 2% M50 : Ekstrak metanol 5% M100 : Ekstrak metanol 10% Bagian tengah merupakan kontrol (Kloramfenikol 2%)
Lampiran 7. Contoh perhitungan konsentrasi ekstrak
Konsentrasi ekstrak 2% (b/v)
Berat ekstrak = 20 mg
Volume pelarut = 1 ml
Volume ekstrak per disk = 20 μl
Jadi untuk membuat larutan dengan konsentrasi 2% membutuhkan 20 mg ekstrak
dan diencerkan dengan 1 ml pelarut.

Lampiran 8. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat dan metanol kerang darah pada bakteri E. coli
Keterangan:
E1 : Ekstrak etil asetat 2% E2 : Ekstrak etil asetat 3,5% E3 : Ekstrak etil asetat 5% E4 : Ekstrak etil asetat 6,5% M1 : Ekstrak metanol 2% M2 : Ekstrak metanol 3,5% M3 : Ekstrak metanol 5% M4 : Ekstrak metanol 6,5%

Lampiran 9. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat dan metanol kerang darah pada bakteri S. aureus
Keterangan:
E1 : Ekstrak etil asetat 2% E2 : Ekstrak etil asetat 3,5% E3 : Ekstrak etil asetat 5% E4 : Ekstrak etil asetat 6,5% M1 : Ekstrak metanol 2% M2 : Ekstrak metanol 3,5% M3 : Ekstrak metanol 5% M4 : Ekstrak metanol 6,5%

Lampiran 10. Uji aktivitas antibakteri kontrol (kloramfenikol) pada bakteri E. coli
Keterangan:
1 : Kloramfenikol 2% 2 : Kloramfenikol 3,5% 3 : Kloramfenikol 5% 4 : Kloramfenikol 6,5%

Lampiran 11. Uji aktivitas antibakteri kontrol (kloramfenikol) pada bakteri S. aureus
Keterangan:
1 : Kloramfenikol 2% 2 : Kloramfenikol 3,5% 3 : Kloramfenikol 5% 4 : Kloramfenikol 6,5%

Lampiran 12. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-1
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 13. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-2
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 14. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-3
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 15. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-4
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 16. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-5
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 17. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-6
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 18. Pengamatan zona hambat suhu 10oC hari-7
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 19. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-1
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 20. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-2
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 21. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-3
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 22. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-4
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 23. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-5
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 24. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-6
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli

Lampiran 25. Pengamatan zona hambat suhu 30oC hari-7
Penghambatan ekstrak etil asetat
terhadap bakteri E. coli
Penghambatan ekstrak etil terhadap
bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli
Penghambatan kloramfenikol (2% dan
6,5%) terhadap bakteri S. aureus
Penghambatan kloramfenikol (3,5%
dan 5%) terhadap bakteri E. coli