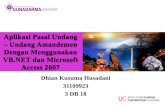2009_08_24_11_01_20faunaindonesia-dhian
description
Transcript of 2009_08_24_11_01_20faunaindonesia-dhian

FaunaIndonesia
ISSN 0216-9169
Pusat Penelitian Biologi - LIPIBogor
Volume 8, No. 2 Desember 2008
Xenopsylla cheopis
Mas
yara
k a t
Z o o l o g i
I n
do
ne
sia
MZ I

Fauna Indonesia merupakan Majalah llmiah Populer yang diterbitkan oleh Masyarakat Zoologi Indonesia (MZI). Majalah ini memuat hasil pengamatan
ataupun kajian yang berkaitan dengan fauna asli Indonesia,diterbitkan secara berkala dua kali setahun
ISSN 0216-9169
Redaksi
HaryonoAwit Suwito
Mohammad IrhamKartika Dewi
R. Taufiq Purna Nugraha
Tata Letak
Kartika DewiR. Taufiq Purna Nugraha
Alamat Redaksi
Bidang Zoologi Puslit Biologi - LIPIGd. Widyasatwaloka, Cibinong Science CenterJI. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911
TeIp. (021) 8765056-64Fax. (021) 8765068
E-mail: [email protected]
Foto sampul depan :Xenopsylla cheopis - Foto : R.T.P. Nugraha
FaunaIndonesia

PEDOMAN PENULISAN
Redaksi FAUNA INDONESIA menerima sumbangan naskah yang belum pemah diterbitkan, dapat berupa hasil pengamatan di lapangan/laboratorium suatu jenis binatang yang didukung data pustaka, berita tentang catatan baru suatu jenis binatang atau studi pustaka yang terkait dengan fauna asli Indonesia yang bersifat ilmiah populer. Penulis tunggal atau utama yang karangannya dimuat akan mendapatkan 2 eksemplar secara cuma-cuma.
Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Makalah disusun dengan urutan: Judul, nama pengarang, ringkasan/summary, pendahuluan, isi (dibagi menjadi beberapa sub judul, misalnya: ciri-ciri morfologi, habitat, perilaku, distribusi, manfaat dan konservasinya, tergantung topiknya), kesimpulan dan saran ( jika ada) dan daftar pustaka.
Naskah diketik dengan spasi ganda pada kertas HVS A4 menggunakan program MS Word, maksimal 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Selain dalam badan dokumen, gambar juga turut disertakan dalam file terpisah dengan format jpg. Gambar dan tabel disusun dalam bentuk yang mudah dimengerti dibuat pada lembar terpisah dan disertai keterangan secara berurutan. Naskah dikirimkan ke redaksi sebanyak 2 eksemplar beserta disketnya.
Acuan dan daftar pustaka, untuk acuan menggunakan sistem nama-tahun, misalnya Kottelat (1995), Weber & Beaufort (1916), Kottelat et al., (1993), (Odum, 1971). Daftar pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama penulis pertama. Hanya pustaka yang diacu yang dicantumkan pada daftar tersebut, dengan urutan: nama pengarang, tahun penerbitan, judul makalah/buku, volume dan halaman. Khusus untuk buku harus dicantumkan nama penerbit, kota, negara dan jumlah halaman. Untuk pustaka yang diacu dari internet harus mencantumkan tanggal akses.

Nomor Penerbitan ini dibiayai oleh : “Proyek Diseminasi Informasi Biota Indonesia”
Pusat Penelitian Biologi - LIPI

i
PENGANTAR REDAKSI
Pada saai ini isu mengenai pemanasan global dan dampaknya semakin santer dibicarakan di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Analisa terhadap perkiraan dampak dan upaya pencegahan terus dikembangkan. Salah satu komponen kehidupan yang akan terkena dampak tersebut adalah fauna. Oleh karena itu majalah Fauna Indonesia semakin penting peranannya untuk menghimpun dan menyebarluaskan informasi mengenai fauna yang ada di bumi Nusantara ini. Kepada para pembaca dan pihak terkait diharapkan ikut berkontribusi untuk turut serta menyebarkan informasi yang dimiliki kepada khalayak luas.
Pada Vol 8 (2) ini Fauna Indonesia menyajikan informasi yang menarik untuk disimak, yaitu : Keragaman jenis dan potensi ikan di perairan Pulau Boboko, Taman Nasional Ujung Kulon, Potensi ikan belida dan upaya konservasinya, Subulura andersoni, Nematoda Parasit Pada Tikus, Catatan mengenai Cumi Punggung Berlian, Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 (Teuthida : Thysanoteuthidae), Siput telanjang (Slug) sebagai hama tanaman budidaya, Danau Mesangat : habitat terakhir Buaya Badas Hitam, Crocodylus siamensis di Indonesia, Tungau, caplak , kutu dan pinjal.
Fauna Indonesia edisi ini bisa hadir di hadapan para pembaca atas bantuan pendanaan dari Proyek Diseminasi Informasi Biota Indonesia Tahun 2009. Oleh sebab itu, Redaksi Fauna Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI dan KSK Proyek Diseminasi Informasi Biota Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Kepala Bidang Zoologi-Pusat Penelitian Biologi yang telah memfasilitasi, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan ini. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca.
Redaksi

ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR REDAKSI .............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... ii
KERAGAMAN JENIS DAN POTENSI IKAN DI PERAIRAN PULAU BOBOKO, TAMAN NASIONAL UJUNG KULON.. .................................................................................................... 1
Gema Wahyudewantoro
POTENSI IKAN BELIDA DAN UPAYA KONSERVASINYA .............................................................. 6
Haryono
Subulura andersoni, NEMATODA PARASIT PADA TIKUS ...................................................................10
Kartika Dewi
CATATAN MENGENAI CUMI PUNGGUNG BERLIAN, Thysanoteuthis rhombusTROSCHEL, 1857 (TEUTHIDA : THYSANOTEUTHIDAE) .....................................................................................18
Nova Mujiono
SIPUT TELANJANG (SLUG) SEBAGAI HAMA TANAMAN BUDIDAYA ...................................21
N. R. Isnaningsih
DANAU MESANGAT : HABITAT TERAKHIR BUAYA BADAS HITAM, Crocodylus siamensis DI INDONESIA ......................................................................................................................................................25
Hellen Kurniati
TUNGAU, CAPLAK , KUTU DAN PINJAL ............................................................................................29
Dhian Dwibadra

29
FaunaIndonesia
Mas
yara
k a t Z o o l o g i I nd
on
esia
MZ I
Fauna Indonesia Vol 8(2) Desember 2008 : 29-33
TUNGAU, CAPLAK , KUTU DAN PINJAL
Dhian DwibadraBidang Zoologi,Pusat Penelitian Biologi LIPI
Summary
Mite, tick, lice and flea belong to the phyllum Arthropoda. Most of them are important to humans because they not only can parasitize animals and men, but also transmit various diseases. Because of the lack of sufficient knowledge, many people tend to misidentify these four groups. The knowledge of mite, tick, lice and flea biol-ogy are needed to avoid misidentification among them.
Pendahuluan
Seringkali terdapat kerancuan dalam masyarakat untuk menyebut binatang yang kecil, mengganggu manusia dan hewan peliharaan dengan satu sebutan tunggal yaitu kutu. Padahal terdapat kemungkinan bahwa binatang pengganggu tersebut dari kelompok yang berbeda. Kelompok hewan yang sering menimbulkan kerancuan dalam penyebutan adalah tungau (mite), caplak (tick), kutu (lice) dan pinjal (flea). Disini akan dibahas mengenai keempat binatang tersebut sehingga dapat memahami dan membedakannya.
Klasifikasi
Tungau, caplak, kutu dan pinjal tergabung dalam satu filum yang sama yaitu Arthropoda. Tungau dan caplak berada dibawah satu kelas (Arachnida) dan anak kelas yang sama yaitu Acari, namun keduanya tergolong dalam suku yang berbeda. Caplak termasuk dalam golongan suku Ixodidae dan Argasidae sedangkan suku yang lain disebut tungau saja (Krantz, 1978). Bagaimana dengan posisi kutu dan pinjal dalam klasifikasi? Menurut Borror dkk. (1996) kutu dan pinjal termasuk dalam kelas Insekta (serangga) namun berbeda bangsa. Kutu seringkali dibagi menjadi dua bangsa yang terpisah yaitu Mallophaga (kutu penggigit) dan Anoplura (kutu penghisap). Kutu penghisap sering pula disebut “tuma” oleh masyarakat
Indonesia. Ahli entomologi dari Inggris, Jerman dan Australia hanya mengenali satu bangsa tunggal yaitu Phthiráptera, dengan empat anak bangsa (salah satunya Anoplura). Pinjal termasuk dalam bangsa Siphonaptera. Beberapa suku yang terdapat di Indonesia antara lain Pulicidae, Ischnopsyllidae, Hystrichopsyllidae, Pygiopsyllidae, Ceratophyllidae dan Leptosyllidae. Pinjal tikus dan kucing yang umum ditemukan termasuk dalam Pulicidae.
Morfologi
Sama seperti anggota arachnida lainnya (laba-laba, kalajengking dll.), tubuh tungau dan caplak terbagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian depan disebut cephalothorax (prosoma) dan bagian belakang tubuh disebut abdomen (ophistosoma). Meskipun demikian, tidak terdapat batas yang jelas diantara dua bagian tubuh tersebut. Tungau dan caplak dewasa mempunyai alat-alat tubuh pada arachnida seperti khelisera dan palpus (alat sensori) yang terdapat di bagian , dan enathosoma/capitulum, dan empat pasang kaki (Kendall, 2008). Sebagian besar tungau (Gambar 1 A) berukuran sangat kecil, memiliki panjang kurang dari 1 mm. Namun ada pula tungau besar yang dapat mencapai panjang 7.000 µm. Pada gnathosoma tungau terdapat epistoma, tritosternum (berfungsi dalam transport cairan tubuh), palpus yang beruas-ruas, khelisera, corniculi, hipostoma berseta yang

30
FAUNA INDONESIA Vol 8(2) Desember 2008 : 29 - 33
masing-masing sangat beragam dalam hal bentuk dan jumlah ruasnya tergantung pada kelompoknya. Khelisera pada tungau teradaptasi untuk menusuk, menghisap atau mengunyah. Tubuh dilindungi oleh dorsal shield/scutum. Tungau memiliki stigma (alat pertukaran O2 dan CO2) yang letaknya bervariasi yaitu di punggung dorsal, antara pangkal kaki/coxa 2 dan 3, di sebelah coxa ke tiga atau diantara khelisera. Letak stigma menjadi kunci penting untuk membedakan bangsa tungau. Caplak (Gambar 1 B) memiliki ukuran lebih besar dari pada tungau. Panjang tubuh dapat mencapai 2.000-30.000 µm. Selain ukurannya, caplak dibedakan dari tungau berdasarkan letak stigma yang berada di bawah coxa (pangkal kaki) ke empat. Caplak juga memiliki karakter-karakter khas tersendiri pada hipostoma (Gambar 2), memiliki ocelli/mata, tetapi tidak memiliki epistoma, corniculi dan tritosternum. Caplak dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu caplak berkulit keras/hard tick (Ixodidae) dan caplak berkulit lunak/soft tick (Argasidae) karena tidak memiliki scutum (Krantz, 1978; Evans, 1992). Hipostoma pada caplak merupakan suatu struktur yang terdiri dari gigi-gigi yang tersusun teratur dan menonjol. Struktur inilah yang digunakan untuk menusuk tubuh induk semang ketika caplak menghisap darah. Hipostoma dilindumgi oleh khelisera (Vredevoe, 1997). Kutu termasuk anggota kelompok serangga yang mempunyai tiga pasang kaki dan sayap yang mereduksi. Dua kelompok kutu yaitu kutu penghisap/tuma dan kutu penggigit memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda. Ukuran tubuh kutu penghisap mencapai 0,4-6,5 mm; kepala kutu penghisap biasanya lebih sempit daripada protoraksnya; sungut beruas-ruas; mata mereduksi dan bagian-bagian mulut haustellat. Tuma memiliki tiga stilet penusuk (dorsal, tengah dan ventral) pada bagian mulutnya dan satu rostrum pendek pada ujung anterior kepala. Dari tempat itu tiga stilet penusuk dijulurkan. Stilet tersebut kira-kira panjangnya sama dengan kepala dan apabila tidak dipakai dapat ditarik masuk ke dalam satu struktur seperti kantung panjang di bawah saluran pencernaan. Stilet dorsal berfungsi sebagai saluran makanan. Stilet tengah mengandung air liur dan berfungsi sebagai hipofaring, sedangkan stilet ventral sebagai penusuk utama diperkirakan berfungsi sebagai labium. Kaki-kaki kutu penghisap pendek dan memiliki cakar pengait yang termodifikasi untuk melekat pada induk semang.
Kutu penggigit bertubuh pipih; berukuran tubuh 2-6 mm; bagian mulut mandibulat; mata majemuk mereduksi; lebar kepala sama atau lebih dengan protoraksnya; tarsi beruas 2-5 dan tidak memiliki cerci (Borror dkk., 1996; Elzinga, 1978). Pinjal berbentuk tubuh menyerupai biji lamtoro pipih kesamping; berukuran + 3 mm; seluruh tubuh tertutup bulu-bulu; mulut berupa mulut penusuk dan penghisap. Kaki ke tiga dari pinjal berukuran lebih besar dan lebih panjang daripada dua pasang kaki lainnya sehingga memungkinkannya untuk melompat. Lompatannya sangat jauh dan tinggi dibandingkan ukuran tubuhnya (Kadarsan dkk., 1983).
Habitat
Tungau terdapat pada hampir semua habitat. Beberapa tungau tidak membahayakan, hidup pada bahan organik yang mati atau membusuk atau sebagai predator invertebrata kecil lainnya. Sebagian lagi bersifat membahayakan karena hidup sebagai parasit pada tumbuhan, hewan dan bahkan pada manusia. Caplak adalah ektoparasit penghisap darah pada hewan vertebrata. Contoh caplak berkulit keras di Indonesia adalah caplak sapi (Boophilus microplus), caplak anjing (Rhipicephalus sanguineus)(Gambar 1 G) , caplak babi (Dermacentor auratus). Contoh tungau ektoparasit antara lain gurem atau sieur (Dermanyssus gallinae) yang menyerang ayam, tungau kudis manusia (Sarcoptes scabiei) (Gambar 1 F), tungau ajing (Demodex canis) dll. Selain itu adapula yang bersifat endoparasit, misalnya tungau dari suku Rhinonyssidae yang ditemukan pada saluran pernafasan burung (Krantz, 1978 & Kadarsan, 1983). Kutu merupakan serangga ektoparasit yang dapat ditemukan pada burung, mamalia dan bahkan manusia. Kutu seringkali ditemukan hanya pada bagian tubuh tertentu induk semangnya. Tuma memakan cairan tubuh termasuk darah induk semang. Contoh tuma antara lain tuma kepala (Pediculus humanus capitis)(Gambar 1 C) dan tuma kerbau (Haematopinus tuberculatus). Kutu penggigit pada umumnya memakan bulu dan serpihan kulit induk semang. Kutu ini biasanya berkumpul di bagian dada, paha dan sayap unggas. Contoh kutu penggigit adalah Menopon gallinae (Gambar 1 D) (Harvey & Yen, 1989; Kadarsan dkk., 1983).

31
DWIBADRA - TUNGAU, CAPLAK, KUTU DAN PINJAL
Gambar 1. A. Tungau Macrocheles (foto: K. Dewi, 2008) ; B. Caplak (sumber: www.kendall-bioresearch.co.uk) ; C. Kutu penghisap Pediculus humanus capitis (sumber: www.entm.purdue.edu) ; D. Kutu penggigit Menopon gallinae (sumber: www.ento.csiro.au) ; E. Xenopsylla cheopis (sumber: www.summagallicana.it) ; F. Sarcoptes scabiei (sumber: www.newworldencyclopedia.org) ; G. Rhipicephalus sanguineus (sumber: webpages.lincoln.ac.uk)
a
b
c
Gambar 3. Capitulum caplak a). Hipostoma, b). Gigi, c). Palpus (sumber http://entomology.ucdavis.edu dengan modifikasi)
A
C
B
D
F G
E

32
Pinjal ditemukan dekat dengan induk semangnya, baik di rambut, bulu-bulu atau di sarangnya. Pinjal dewasa menghisap darah induk semang. Contoh pinjal adalah pinjal kucing (Ctenophalides felis) dan pinjal tikus (Xenopsylla cheopis) (Gambar 1 E).
Siklus hidup
Proses reproduksi pada tungau dan caplak bervariasi. Siklus hidup yang dijalaninya berupa: telur-larva-nimpha-tungau/caplak dewasa. Larva tungau dan caplak hanya memiliki 3 pasang kaki. Larva caplak, setelah makan darah induk semang, akan tumbuh menjadi nimpha yang memiliki 4 pasang kaki. Nimpha makan darah dan akan tumbuh menjadi caplak dewasa. Setelah makan satu kali sampai kenyang, caplak dewasa betina akan bertelur kemudian ia mati. Caplak betina setelah kenyang menghisap darah dapat membengkak sampai 20-30 kali ukuran semula. Caplak memerlukan + 1 tahun untuk menyelesaikan satu siklus hidup di daerah tropis dan lebih dari satu tahun di daerah lebih dingin. Caplak dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa makan jika belum mendapatkan induk semangnya. Caplak dapat hidup pada 1-3 induk semang berbeda selama fase pertumbuhannya sehingga dikenal dengan sebutan caplak berinduk semang satu, berinduk semang dua dan berinduk semang tiga (Vredevoe, 1997). Kutu menjalani proses metamorfosa yang tidak sempurna, yaitu telur-nimpha-individu dewasa. Seluruh siklus hidup terjadi di tubuh induk semang. Telur kutu akan menempel pada rambut induk semang dengan bantuan zat perekat yang dihasilkannya. Sedangkan siklus hidup yang dijalani pinjal merupakan metamorfosa sempurna yaitu telur-larva-pupa-dewasa. Larva yang baru menetas tidak memiliki kaki. Fase pupa adalah fase yang tidak memerlukan makanan (Kadarsan dkk., 1983).
Potensi
Sebagai binatang parasit, tungau, caplak dan pinjal dapat menularkan berbagi macam organisme penyebab penyakit. Misalnya Ornithodoros (caplak kulit lunak) dapat menularkan larva filaria pada ular phyton dan gerbil. Beberapa organisme dapat bersifat zoonosis yaitu dapat menular dari binatang ke manusia. Organisme pathogen dapat ditularkan
melalui air liur, serpihan kulit akibat garukan dan feses (Evans, 1992). Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat infestasi caplak dan tungau antara lain: scrub thypus, rocky mountain spotted fever, tularemia, Lyme disease (Krantz, 1978). Infestasi pinjal bahkan pernah menyebabkan epidemi pes di daerah Boyolali, Jawa Tengah pada akhir 1960an. Hal ini disebabkan karena pinjal dapat menularkan bakteri Yersinia pestis, penyebab penyakit pes, dari tikus ke manusia (Kadarsan dkk., 1983). Infestasi kutu pada hewan ternak dan binatang peliharaan dapat menyebabkan iritasi dan menurunnya kesehatan. Luka garukan (akibat rasa gatal yang ditimbulkan) dapat menyebabkan infeksi sekunder. Serangan gurem pada unggas dapat menyebabkan ayam gelisah karena gatal dan mengakibatkan merosotnya produksi daging dan telur.
Daftar Pustaka
Borror, D. J., C. A. Triplehorn & N. F. Johnson. 1996. Pengenalan Pelajaran Serangga. Ed. 6. Penerjemah: S. Partosoedjono. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. xviii + 1083 hal.
Elzinga, R. J. 1978. Fundamentals of Entomology. Prentice Hall of India Private Ltd. New Delhi. x+325 hal.
Evans, G. O. 1992. Principles of Acarology. Cambridge University Press, UK. xviii+563 pp.
Harvey, M. S & A. L. Yen. 1989. Worms to Wasps, an Illustrated Guide to Australia’s Terrestrial Invertebrates. Oxford University Press. 202 hal.
Kadarsan, S., A. Saim, E. Purwaningsih, H. B. Munaf, I. Budiarti & S. Hartini. 1983. Binatang Parasit. Lembaga Biologi Nasional-LIPI. Bogor. 119 hal.
Kendall, D. A. 2008. Mites & Ticks in Insect & Other arthropod. www.kendall-bioresearch.co.uk/mite.htm.
Krantz, G. W. 1978. A Manual of Acarology. 2nd ed. Oregon State University Book Store, Inc. Corvalis. 509 pp.
FAUNA INDONESIA Vol 8(2) Desember 2008 : 29 - 33

33
DWIBADRA - TUNGAU, CAPLAK, KUTU DAN PINJAL
Vredevoe, L. 1997. Background Information on the Biology of Ticks.. http://entomology.ucdavis.edu/faculty/rbkimsey/tickbio.html.