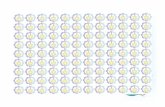Study Kasus Faktor Risiko dengan Riwayat Tuberculosis paru
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Study Kasus Faktor Risiko dengan Riwayat Tuberculosis paru
i
ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF
PADA NY. R DI PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL
(Study Kasus Faktor Risiko dengan Riwayat Tuberculosis paru)
KARYA TULIS ILMIAH
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Diploma III kebidanan
Disusun Oleh :
ADE RUNITA KURNIANINGSIH
16070089
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
TAHUN 2019
ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Karya Tulis Ilmiah dengan Judul :
Asuhan kebidanan komprehensif dengan faktor resiko tinggi dengan riwayat
tuberculosis paru pada Ny. R di Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2018.
Adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Ade Runita Kurnianingsih
NIM : 16070089
Tegal, …………………….
Penulis
(Ade Runita Kurnianingsih)
iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal, saya yang
bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ADE RUNITA KURNIANINGSIH
Nim : 16070089
Jurusan / Program Studi : DIII Kebidanan
Jenis Karya : Karya Tulis Ilmiah
Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Harapan
Bersama Tegal Hak Bebas Royalty Nonekslusif ( None Exclusive
Royalry Free Righ) atas Karya Tulis Ilmiah saya yang berjudul :
ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. R DI
PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus Faktor
Risiko dengan Riwayat Tuberculosis Paru) Beserta perangkat yang ada
(jika di perlukan). Dengan Hak bebas Royalty/Noneksklusifini Politeknik
Harapan Bersama Tegal berhak menyimpan mengalih
mediakan/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat dan mempublikasikan Karya. Tulis Ilmiah saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan pemilik Hak
Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Di buat di : Tegal
Pada tanggal : 2 September 2019
Yang menyatakan
ADE RUNITA KURNIANINGSIH
iv
HALAMAN PERSETUJUAN
Karya Tulis Ilmiah dengan Judul :
“ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF DENGAN FAKTOR RESIKO
TINGGI DENGAN RIWAYAT TUBERCULOSIS PARU NY. R DI
PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018”.
Disusun oleh :
Nama : Ade Runita Kurnianingsih
NIM : 16070089
Telah mendapat persetujuan pembimbing dan siap dipertahankan di depan tim
penguji Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Politeknik Harapan
Bersama Kota Tegal .
Tegal, …………………
Pembimbing I : Novia Ludha Arisanti, S. ST ( )
Pembimbing II : Meyliya Qudriani, S. ST. M. Kes ( )
iv
v
HALAMAN PENGESAHAN
Karya Tulis Ilmiah ini diajukan oleh :
Nama : Ade Runita Kurnianingsih
NIM : 16070089
Program Studi : DIII Kebidanan
Judul : Asuhan Kebidanan Komprehensif Dengan Faktor Resiko
Tinggi dengan Riwayat Tuberculosis Paru Pada Ny. R Di
Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2018.
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli
Madya Kebidanan pada Program Studi D III Kebidanan Politeknik Harapan
Bersama Tegal.
Tegal, ............................
DEWAN PENGUJI
Penguji I : Juhrotun Nisa, S. ST., MPH (…………………………)
Penguji II : Novia Ludha Arisanti, S. ST (…………………………)
Penguji III : Meyliya Qudriani, S. ST., M. Kes (…………………………)
Ketua Program Studi D III Kebidanan
Politeknik Harapan Bersama Tegal
(Nilatul Izzah, S.ST., M. Keb)
vi
TUBERCULOSIS PARU
(Studi kasus terhadap Ny. R di Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal)
Ade Runita Kurnianingsih1, Novia Ludha Arisanti2, Meyliya Qudriani3
Email : [email protected] 2Diploma III Kebidanan, Politeknik Harapan Bersama Tegal 3
Diploma III Kebidanan, Politeknik Harapan Bersama Tegal
ABSTRAK
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tegal tahun 2016 terdapat 33
kasus kematian per 27.314 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu pada
tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 14 kasus kematian per 24.225 kelahiran
hidup dan menurut data angka kematian ibu di Puskesmas Tarub pada tahun 2017
yaitu sebanyak 2 kasus kematian yang disebabkan karena emboli air ketuban dan
penyakit jantung. Menurut data yang di peroleh dari Puskesmas Tarub tahun 2017
jumlah ibu hamil yang termasuk faktor resiko sebanyak 323 dan resiko tinggi
sebanyak 52 dari jumlah ibu hamil 1018, ibu hamil dengan faktor resiko umur >35
tahun sebanyak 123 kasus dan ibu hamil dengan penyakit paru-paru sebanyak 10
kasus dari total ibu hamil di Puskesmas Tarub.
Peneliti ini menggunakan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian adalah
ibu hamil Ny. R berusia 33 tahun dengan riwayat tubercukosis paru. Data di ambil
sejak bulan agustus sampai September 2018. Data di ambil dengan menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil selama kehamilan subyek sampai
nifas dan pada bbl tidak ada masalah apapun.
Saran : apabila ditemukan kasus yang sama perlu adanya kolaborasi dengan
dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam selama kehamilan
sampai nifas, selain itu perlu melibatkan keluarga untuk memberi dukungan pada
ibu.
Kata Kunci : tuberculosis paru, kebidanan
Daftar Pustaka : 49 (2008-2017)
vii
KATA PENGANTAR
Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Atas segala
rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini
dengan judul “ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. R DI
PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL (Study Kasus Faktor Resiko
Tinggi dengan Riwayat Tuberculosis Paru)
Penulis menyadari dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini banyak sekali
kesalahan dan kekeliruan, tapi berkat bimbingan dan arahan dari semua pihak
akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :
1. MC, Chambali, B.Eng.EE., M.KOM. Selaku direktur Politeknik Harapan
Bersama Kota Tegal.
2. Nilatul Izah, S.ST.M.Keb. Selaku Ketua Prodi DIII Kebidanan Politeknik
Harapan Bersama Kota Tegal.
3. Novia Ludha Arisanti, S. ST, selaku pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Pintalit BP Purba, S. ST, selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Meyliya Qudriani, S. ST. M. Kes, selaku pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ny. R beserta keluarga selaku pasien dalam pelaksanaan asuhan kebidanan
yang telah membantu dan memberikan partisipasinya dalam pembuatan
viii
7. Karya Tulis Ilmiah dan dilakukan pemeriksaan sehingga penulis memahami
akan hamil, persalinan, dan nifas.
8. Semua dosen dan staf karyawan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
9. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung baik secara material, moral,
dan spiritual.
10. Semua pihak yang tidak dapat di tulis dan disebutkan satu persatu yang turut
membantu dalam penyusunan laporan studi kasus.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan Karya Tulis
Ilmiah ini, masih jauh dari kata sempurna, disebabkan keterbatasan
pengetahuan penulis. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu.
.
Tegal, …………………….
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
HALAMAN ORISINALITAS .................................................................................. ii
HALAMAN PUBLIKASI ........................................................................................ iii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... v
ABSTRAK ............................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang …………………………………………………………... 1
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………….. 7
C. Tujuan Penulisan …………………………...……………………………. 7
D. Ruang Lingkup ………………………………...………………………... 8
E. Manfaat Penulisan ………………………………...…………………….. 9
F. Metode Memperoleh Data ……………………………………………..... 10
G. Sistematika Penulisan …………………………………………………… 12
BAB II TINJAUAN TEORI …………………………………………………….. 14
A. Teori Kehamilan ………………………………………………………...... 14
1. Pengertian Kehamilan ……………………………………....……….. 14
a. Definisi …………………………………………………….…….. 14
x
b. Perubahan psikologi ibu hamil ………………………………….. 14
c. Tanda bahaya pada kehamilan ………………………………….... 16
d. Penatalaksanaan kehamilan ………………………………………. 16
e. Standar minimal kunjungan kehamilan ……………………........... 19
f. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 20
g. Kebutuhan gizi ibu hamil ………………………………………… 21
2. Konsep dasar kehamilan dengan riwayat tuberculosis paru …………. 27
a. Definisi tuberculosis pada kehamilan ……………………………. 27
b. Tanda-tanda tuberculosis ………………………………………… 28
c. Penyebab tuberculosis …………………………………………… 28
d. Sifat-sifat mycobacterium tuberculosis …………………………... 28
e. Penularan tuberculosis ………………………………………….…. 29
f. Klasifikasi penyakit tuberculosis ……………………………….... 29
g. Faktor-faktor penyebab tuberculosis paru ……………………….. 30
h. Pencegahan penyakit tuberculosis paru …………………….……. 31
i. Prognosa …………………………………………………….…... 32
j. Efek tuberculosis paru pada kehamilan …………………….…... 33
k. Penatalaksanaan medis pada kehamilan dengan tuberculosis ….. 33
l. Skrining tuberculosis paru pada kehamilan …………….……… 37
B. Teori Persalinan ………………………………………………………… 42
a. Definisi ………………………………………………………………. 42
b. Mekanisme persalinan ……………………………………………… 42
c. Fisiolosis persalinan …………………………………………………. 44
d. Tanda dan gejala persalinan ………………………………………… 51
xi
e. Tanda-tanda persalinan ……………………………………………… 51
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ………………………. 54
g. Penatalaksanaan dalam proses persalinan …………………………… 56
h. Lima benang merah dalam asuhan kebidanan ……………………… 64
i. Laserasi jalan lahir …………………………………………………… 69
C. Teori Nifas ………………………………………………………………. 70
a. Definisi …………………………………………………………….… 70
b. Fisiologis nifas ………………………………….…………………... 70
c. Tanda bahaya masa nifas ………………………………….………. 70
d. Tuberculosis dalam nifas ……………………………….…....…….. 76
D. Teori Bayi Baru Lahir ………………………………………..….…….. 77
a. Definisi ……………………………………………………..…….... 77
b. Kriteria bayi baru lahir normal ……………………….……..……… 77
c. Tanda-tanda bayi baru lahir ………………………….………..…… 78
d. Asuhan segera pada bayi baru lahir ………………….…………..… 78
e. Perawatan bayi baru lahir …………………………….…………..... 78
f. Inisiasi menyusu dini ………………………………………………… 79
g. Tuberculosis pada bayi baru lahir …………………………………… 80
E. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan ………………………………………. 81
1. Asuhan kebidanan varnay ……………………………………………. 81
a. Langkah ………………………………………………………….. 81
b. Konsep dasar managemen kebidanan ……………………………. 81
2. Manajemen kebidanan dengan metode varnay ……………………… 81
3. Menejemen kebidanan dengan metode soap …………………………. 89
xii
4. Landasan hokum kewenangan bidan ……………………………….... 90
BAB III TINJAUAN KASUS ……………………………………………………. 94
A. ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN ………………………… 94
B. ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN …………………...…. 116
C. ASUHAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS ……………………….. 144
D. ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR ……………….. 169
BAB IV PEMBAHASAN ………………………………………………………. 183
A. Kehamilan ………………………………………………………………. 184
B. Persalinan ……………………………………………………………….. 236
C. Masa Nifas ……………………………………………………………… 385
D. Bayi Baru Lahir ………………………………………………………… 333
BAB V PENUTUP …………………………………………………………….. 359
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 :Partograf
Lampiran 2 : Lembar Konsultasi KTI
Lampiran 3 : Pengkajian Postpartum
Lampiran 4 : Buku KIA.
Lampiran 5 : Dokumentasi.
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kunjungan Pemeriksaan Antenatal ........................................................ 18
Tabel 2.2 Penatalaksanaan Masa Nifas ……………………………………… ... 76
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian seorang ibu
sewaktu hamil, melahirkan atau dalam waktu 42 hari sesudah berakhirnya
kehamilan, tidak bergantung pada tempat atau usia kehamilan. Kematian ibu
dibagi menjadi kematian langsung dan kematian tidak langsung. Secara
global 70% kematian ibu tergolong pada kematian ibu langsung yaitu
disebabkan oleh perdarahan (22% biasanya perdarahan pasca persalinan),
sepsis (15%), hipertensi dalam kehamilan (12%) partus macet (8%),
komplikasi aborsi tidak aman (13%). Sedangkan angka kematian perinatal
(perinatal mortality rate) terdiri atas jumlah anak yang tidak menunjukkan
tanda-tanda hidup waktu dilahirkan ditambah jumlah anak yang meninggal
dalam minggu pertama kehidupannya, untuk 1000 kelahiran. Angka kematian
bayi (infant mortallity rate), yakni angka kematian bayi sampai umur 1 tahun,
di Negara maju telah turun dengan cepat dan sekarang mencapai angka
dibawah 25 pada 1000 kelahiran. Penyebab kematian bayi yaitu prematuritas,
kelainan congenital, asfiksia, perlukaan kelahiran (Prawirohardjo,2014).
Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa
kehamilan, persalinan dan nifas, yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan,
dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan atau terjatuh disetiap 100.000 kelahiran hidup pertahun (Dinas
kesehatan RI,2017 ).
2
Pada umumnya penyakit paru-paru tidak mempengaruhi kehamilan
persalinan dan nifas, kecuali penyakitnya tidak terkontrol, berat dan luas yang
di sertai sesak nafas dan hipoksia. Walaupun kehamilan menyebabkan sedikit
perubahan pada system pernafasan, karena uterus yang membesar dapat
mendorong diafragma dan paru-paru ke atas serta sisa dalam udara kurang,
namun penyakit tersebut tidak selalu menjadi lebih parah (Sofian, 2012).
Pengaruh Tuberkulosis Paru terhadap Kehamilan, Dulu pernah
dianggap bahwa wanita dengan tuberkulosis paru aktif mempunyai insidensi
yang lebih tinggi secara bermakna dibandingkan wanita hamil tanpa infeksi
tuberkulosis paru dalam hal abortus spontan dan kesulitan persalinan. Banyak
sumber yang mengatakan peranan tuberkulosis terhadap kehamilan antara
lain meningkatnya abortus, pre-eklampsi, serta sulitnya persalinan. Penelitian
terbaru menunjukkan bahwa hal tersebut tergantung dari letak tuberkulosis
apakah paru atau nonparu serta apakah tuberkulosis terdiagnosis semasa
kehamilan. Pada penelitian terhadap wanita-wanita Indian yang mendapat
pengobatan selama 6-9 bulan semasa kehamilan maka kematian janin 6 kali
lebih besar dan insidens dari prematuritas, KMK ( kecil untuk masa
kehamilan), BBLR (berat badan lahir rendah) (<2500g) adalah 2 kali lipat.
Pengaruh tidak langsung tuberkulosis terhadap kehamilan ialah efek
teratogenik terhadap janin karena obat anti tuberkulosis yang diberikan
kepada sang ibu. Efek samping pasien yang mendapat terapi anti tuberkulosis
yang adekuat adalah gangguan pada traktus genitalis dimana traktus genitalis
terinfeksi dari fokus primer TB paru (Najoan Nan Warouw, 2011).
3
Penyakit kronis ini masih banyak terdapat di negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit ini dapat dijumpai dalam keadaan
aktif dan keadaan tenang. Penyakit paru-paru, yang dalam keadaan aktif, akan
menimbulkan masalah bagi ibu, bayi, dan orang sekelilingnya, jadi
sebenarnya adalah masalah social (Sofian, 2012).
Prevalensi tuberculosis di Indonesia semua bentuk sebesar 660 per
100.000 penduduk (SPTB 2016-2017) insiden kasus tuberculosis sebanyak
403 per 100.000 penduduk. Sekitar 1.000.000 kasus tuberculosis baru
pertahun (Depkes, 2016-2017).
Penurunan angka kematian ibu di Indonesia terjadi sejak tahun 1991
sampai 2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun demikian, SDKI tahun
2012 menunjukan peningkatan angka kematian ibu yang signifikan yaitu
menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu
kembali menunjukan penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS)
tahun 2015. Penyebab tertinggi kematian ibu ditahun 2016 yaitu 32% karena
perdarahan, 26% hipertensi, penyebab lainnya seperti faktor hormonal 21%,
kardiovaskuler 13%, dan infeksi 8% (Kemenkes RI, 2016).
Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017
sebanyak 475 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah kasus
kematian ibu tahun 2016 yang sebanyak 602 kasus. Dengan demikian angka
kematian ibu provinsi jawa tengah juga mengalami penurunan dari 109,65
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi 88,05 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2017. Dari 475 kasus kematian maternal terjadi
4
pada waktu nifas sebesar 60%, 26,32% pada waktu hamil dan 13,68% pada
waktu bersalin (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017).
Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 8,9
per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian
bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun.
Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan
masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat
pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program
kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, serta kondisi lingkungan
sosial ekonomi. Apabila angka kematian bayi disuatu wilayah tinggi,
menunjukan status kesehatan di wilayah tersebut rendah (Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal 2017).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Angka Kematian
Ibu di Kabupaten Tegal pada tahun 2011 mengalami perubahan yaitu 100,3
per 100.000 kelahiran hidup (27 kematian ibu maternal dari 26.919 kelahiran
hidup), tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 120,8 per 100.000
kelahiran hidup (33 kematian ibu maternal dari 26.919 kelahiran hidup), di
tahun 2016 yang mencapai 130,8 per 100.000 kelahiran hidup (33 kematian
ibu maternal dari 27.314 kelahiran hidup). Pada tahun 2017 lebih rendah
dibandingkan angka kematian ibu, Penyebab kematian ibu terbanyak
disebabkan oleh komplikasi obstetrik yaitu perdarahan sebanyak 25%, infeksi
7,5%, eklampsia 5%, abortus 5,5%, partus lama/macet 4%, emboli obstetric
2,5%, komplikasi masa purpereum 2% tuberculosis 0,5%, hipertensi 0,5%.
Angka kematian ibu tersebut sudah memenuhi target Indikator Indonesia
5
Sehat 2010 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan
dengan Resti (primigravida kurang dari 20 tahun/lebih dari 35 tahun 21%,
anak lebih dari 4 29%, jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang
kurang dari 2 tahun 9%, tinggi badan kurang dari 145 cm 13%, berat badan
kurang dari 38 kg 8%, lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm 8%, riwayat
hipertensi 8%). Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 2016-2019, sedangkan
jumlah ibu hamil di Kabupaten Tegal ada 23.343 pada tahun 2017. Angka
kematian ibu sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 120.3 kematian
ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 (Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal Tahun 2017).
Menurut data yang di peroleh dari Puskesmas Tarub pada tahun 2017
Angka Kematian Ibu sebanyak 2 kasus yang disebabkan oleh air ketuban dan
penyakit jantung, sedangkan Angka Kematian Bayi sebanyak 7 kasus yang
disebabkan oleh BBLR dan Aspirasi ASI, BBLR dan asfiksia, BBLR dan
kelainan paru, Hipotermi dan Asfiksia dan Angka Kematian Bayi pada tahun
2018 meningkat menjadi 8 kasus yang disebabkan oleh hipotermi, BBLR,
infeksi, prematur dan BBLR, penyakit kongenital, asfiksia, dan aspirasi
pneumonia (Puskesmas Tarub, 2017-2018).
Jumlah ibu hamil yang termasuk faktor resiko di Puskesmas Tarub
2017 sebanyak 323 dan resiko tinggi sebanyak 52 dari jumlah ibu hamil
1018, jumlah ibu bersalin 973 dan jumlah ibu nifas sebanyak 35. Rincian
faktor resiko yaitu umur < 20 tahun sebanyak 17 kasus, umur > 35 tahun 123
kasus, paritas > 4 11 kasus, jarak anak < 2 tahun 40 kasus, tinggi badan < 145
cm 7 kasus, kelenjar tyroid 2 kasus. Rincian resiko tinggi yaitu hemoglobin 8-
6
11 gr sebanyak 7 kasus, anemia sedang < 8 gr 6 kasus, hipertensi 10 kasus,
preeklampsia atau eklampsi 8 kasus, kelainan letak janin 8 kasus, antepartum
hemorargic atau perdarahan antepartum 3 kasus, jantung 4 kasus, paru-paru
10 kasus, hipertensi 1 kasus, HbsAg 9 kasus, voluntary conselingand testing 1
kasus, gemelly 3 kasus, oligohidramnion 3 kasus, infeksi menular seksual 1
kasus. Jumlah ibu bersalin sebanyak 922 kasus, jumlah ibu nifas 922 kasus
dan jumlah bayi 915 kasus (Puskesmas Tarub, 2017).
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) bekerja sama
dengan Pemerintahan Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan
Internasional Amerika Serikat (USAID) mencanangkan Program USAID
jalin untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Merupakan
prioritas utama pemerintah dalam pembangunan jangka menengah nasional
tahun 2015-2019 dan merupakan target Sustainable Development Goals yang
harus dicapai pada tahun 2030. Maka hal ini sudah berjalan banyak intervensi
yang telah dilakukan pemerintah Indonesia mulai ditingkat masyarakat,
peningkatan kualitas pelayanan ditingkat primer dan rumah sakit,
memperkuat jejaring rujukan, meningkatkan akses, dan pembiayaan jaminan
kesehatan.
Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah membuat program One Student One Client (OSOC) program ini
merupakan program pendekatan dengan memberikan asuhan secara
komprehensif karena pasien dengan resiko tinggi perlu mendapatkan
pendampingan sejak kehamilan sampai kelahiran bayi untuk mendeteksi
secara dini adanya komplikasi sehingga dapat langsung ditangani sesuai
7
dengan kebutuhan pasien dan bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi
kegawatdaruratan terhadap ibu maupun bayi.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil studi
kasus yang berjudul “Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. R umur 33
tahun G3P2A0 dengan Faktor Resiko Tinggi dengan Riwayat Tubercullosis
Paru di puskesmas Tarub Kabupaten Tegal tahun 2018”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut “Bagaimana Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. R
umur 33 Tahun G3 P2 A0 dengan Faktor Resiko Tinggi Riwayat
Tuberculosis Paru di Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2018 ? ”
C. Tujuan Penulisan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa untuk memperoleh
gambaran dan pengalaman secara nyata yang dapat digunakan dalam
memberikan Asuhan Kebidanan pada ibu dengan faktor resiko umur lebih
35 tahun, berdasarkan menejemen kebidanan yang didokumentasikan
menggunakan 7 langkah Varney dan metode SOAP.
2. Tujuan Khusus
a. Penulis mampu melakukan pengkajian data pada ibu hamil, bersalin,
nifas, dan bayi baru lahir, dapat menginterpretasikan data dan hasil
pengkajian sehingga dapat merumuskan diagnosa kebidanan, masalah
8
dan kebutuhan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
khususnya pada Ny. R umur 33 Tahun G3 P2 A0 dengan faktor resiko
tinggi riwayat tuberculosis paru di wilayah kerja Puskesmas Tarub
Kabupaten Tegal Tahun 2018”
b. Dapat merumuskan diagnosa potensial yang muncul, menentukan
kebutuhan terhadap tindakan segera, menyusun perencanaan atau
intervensi yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan yang telah
dibuat dalam tindakan nyata, melakukan evaluasi dan
mendokumentasikan hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu
hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir pada Ny. R umur 33 tahun
G3 P2 A0 dengan faktor resiko tinggi riwayat tuberculosis paru di
wilayah kerja Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2018”
D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dari laporan studi kasus :
1. Sasaran
Penulis mengambil kasus ini dengan sasaran Ny. R umur 38 tahun G3
P2 A0 dengan faktor resiko tinggi riwayat Tuberculosis Paru.
2. Tempat
Tempat pengambilan studi kasus proposal Karya Tulis Ilmiah ini di
wilayah kerja Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal.
9
3. Waktu
a. Waktu pengambilan kasus : 21 agustus 2018 sampai
dengan 14 September
2018.
b. Waktu penyusunan Karya Tulis Ilmiah : dimulai dari penyusunan
proposal menjadi Karya
Tulis Ilmiah..
E. Manfaat Penulisan
1. Bagi Mahasiswa
a. Merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi
bidan dalam melakukan asuhan yang komprehensif.
b. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan asuhan
kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi
baru lahir, agar dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat
selama masa pendidikan.
2. Bagi Institusi Pendidikan
a. Dapat digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk
kebidanan khususnya pada ibu hamil dengan faktor resiko umur >
35 tahun.
b. Sebagai tolak ukur dalam mengaplikasikan asuhan kebidanan
komprehensif oleh mahasiswa dalam mengevaluasi hasil
pembelajaran.
10
3. Bagi Tenaga Kesehatan
Menambah wawasan dalam melakukan pengkajian terhadap masalah-
masalah kesehatan khususnya pada kehamilan, persalinan, dan nifas
dengan resiko tinggi.
4. Bagi Masyarakat
Diharapakan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selama hamil,
persalinan, nifas dan bayi baru lahir di tenaga kesehatan.
F. Metode Memperoleh Data
Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode kasus yaitu
bertujuan untuk mengetahui penatalaksanaan pada kasus yang akan dikaji
sesuai dengan Standar Manajemen Kebidanan.
Dalam penyususnan Karya Tulis Ilmiah ini berdasarkan teori yang
dipadukan dengan praktik dan pengalaman penulis memerlukan data yang
obyektif dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan
masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :
1. Wawancara (Interview)
Penulis melakukan tanya jawab kepada Ny. R dan suami untuk
mendapatkan data yang diperlukan, seperti identitas, riwayat
kesehatan, riwayat obstetri, riwayat haid, riwayat kontrasepsi,
kebutuhan dan pola kebiasaan ibu sehari-hari, data psikologi ibu, data
sosial ekonomi, data perkawinan, dan data pengetahuan ibu.
11
2. Pengamatan (Observasi)
Yaitu suatu prosedur yang berencana antara lain meliputi melihat,
mendengar, dan mencatat sejumlah aktifitas tertentu yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti, dikaji dari hasil yang telah
dilakukan. Dari hasil observasi didapatkan data objektif seperti
pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan obstetri, dan pemeriksaan
penunjang.
3. Pemeriksaan Fisik
Memulai pemeriksaan fisik pasien untuk menentukan status kesehatan
pasien yang dilakukan secara langsung kepada klien dengan cara :
a. Inspeksi adalah pemeriksaan dengan cara melihar bagian tubuh
yang diperiksa melalui pengamatan atau penglihatan.
b. Palpasi adalah pemeriksaan melalui perabaan terhadap bagian-
bagian tubuh yang mengalami kelainan dan mengetahui posisi
janin dalam perut ibu.
c. Auskultasi adalah pemeriksaan fisik dengan pendengaran untuk
mendengarkan denyut jantung janin (DJJ) menggunakan Doppler
linek.
d. Perkusi adalah pemeriksaan fisik dengan mengetuk bagian tubuh
menggunakan tangan atau alat bantu seperti hammer untuk
mengetahui reflek patella.
12
4. Dokumentasi
Pendokumentasian data pasien dengan cara pencatatan saat melakukan
pelayanan kebidanan pada pasien maupun mempelajari dokumentasi
yang didapatkan dari tenaga kesehatan lain seperti dokter.
5. Studi Keputusan
Penulis mempelajari berbagai buku, hand out, mengambil data dari
internet, ataupun mempelajari kembali materi kuliah yang berkaitan
dengan kasus yang didapatkan yaitu Faktor resiko Tinggi Riwayat
Tubercullosis Paru.
G. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini agar dapat lebih mudah, jelas,
dan berkesinambungan, maka penulis menyusun Karya Tulis Ilmiah ini
secara sistematik. Adapun sistematik penyususnan yang dipakai adalah
sebagai berikut :
1. BAB I (Pendahuluan)
Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode memperoleh data
dan sistematika penulisan.
2. BAB II (Tinjauan Pustaka)
Berisi tentang teori terdiri dari kehamilan normal, tuberculosis
paru, persalinan normal, nifas normal, dan BBL normal.
13
3. BAB III (Tinjauan Kasus)
Memuat keseluruhan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan.
Jenis kasus yang diambil yaitu kasus komprehensif resiko tinggi. Kasus
dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Asuhan
kebidanan ditulis sesuai dengan urutan manajemen kebidanan 7 langkah
Varney, yaitu mulai dari pengumpulan data sampai evaluasi pada
asuhan kebidanan kehamilan dan juga menggunakan sistem SOAP pada
asuhan kebidanan nifas, bayi baru lahir serta catatan persalinan.
4. BAB IV (Pembahasan)
Dengan menggunakan 7 langkah varney yang meliputi pengkajian,
intepretasi data, diagnosa potensial, kebutuhan tindakan segera,
perencanaan, implementasi, evaluasi, yang meliputi tentang kesamaan
antara kesenjangan teori dan praktek dilapangan dan pembahasan.
5. BAB V (Penutup)
Berisi kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
14
BAB II
TINJAUAN TEORI
A. Teori Kehamilan
1. Pengertian Kehamilan
a. Definisi
Kehamilan didefinisikan sebagai hasil fertilisasi atau penyatuan
dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau
implantasi. Bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi,
kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10
bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional
(Widatiningsih,2017).
b. Perubahan psikologi ibu hamil
Perubahan psikologi ibu hamil menurut (Ummi, 2011) :
1) Trimester pertama
Setelah terjadi peningkatan hormon esterogen dan
progesteron dalam tubuh, maka akan muncul berbagai macam
ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu misalnya mual
muntah, keletihan dan pembesaran pada payudara. Hal ini akan
memicu perubahan psikologi seperti berikut ini :
a) Ibu untuk membenci kehamilannya, merasakan
kekecewaan, penolakan, kecemasan dan kesedihan
b) Mencari tahu secara aktif apakah memang benar-benar
hamil dengan memperhatikan perubahan pada tubuhnya
15
dan sering kali memberitahukan orang lain apa yang
dirahasiakannya
c) Hasrat melakukan seks berbeda-beda pada setiap wanita.
Ada yang menigkat libidonya, tetapi ada juga yang
mengalami penurunan. Pada wanita yang mengalami
penurunan libido, akan menciptakan suatu kebutuhan
untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan
suami. Banyak wanita hamil yang merasakan kebutuhann
untuk dicintai dan mencintai, tetapi bukan dengan seks.
Sedangkan, libido yang sangat besar dipengaruhi oleh
kelelahan, rasa mual, pembesaran payudara, keprihatinan
dan kekuatiran.
d) Sedangkan bagi suami sebagai calon ayah akan timbul
kebanggaan, tetapi bercampur dengan keprihatinan akan
kesiapan untuk mencari nafkah bagi keluarga.
2) Trimester Kedua
Trimester kedua biasanya ibu merasa sehat dan sudah
tebiasa dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa tidak
nyaman akibat kehamilan sudah mulai berkurang. Perut ibu
pun belum terlalu besar sehingga belum dirasakan ibu sebagai
beban. Ibu sudah menerima kehamilannya dan dapat mulai
menggunakan energi dan pikirannya secara lebih konstruktif.
Pada trimester ini pula ibu dapat merasakan gerakan janinnya
dan ibu mulai merasakan kehadiran bayinya sebagai seseorang
diluar dirinya dan dirinya sendiri. Banyak ibu yang merasa
terlepas dari rasa kecemasan dan rasa tidak nyaman seperti
16
yang dirasakannya pada trimester pertama dan merasakan
meningkatnya libido.
3) Trimester Ketiga
Trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu dan
waspada sebab pada saat itu ibu akan tidak sabar menunggu
kehadiran bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut
merupakan dua hal yang meningkatkan ibu akan bayinya.
Kadang-kadang ibu merasakan khawatir bahwa bayinya akan
lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu meningkatkan
kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala terjadinya
persalinan pada ibu. Sering kali ibu merasa khawatir atau takut
kalau bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. Kebanyakan
ibu juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan
menghindari orang atau benda apa saja yang dianggap
membahayakan bayinya. Seorang ibu mungkin mulai merasa
takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada
waktu melahirkan.
c. Tanda bahaya pada kehamilan
Menurut (Elisabeth, 2015) :
Perdarahan pervaginam, sakit kepala yang hebat, penglihatan
kabur, bengkak diwajah dan jari-jari tangan, keluar cairan
pervaginam, gerakan janin tidak terasa, nyeri abdomen yang hebat.
d. Penatalaksanaan kehamilan
Pelayanan ante natalcare minimal 10 T menurut (Elisabeth, 2015) :
1) Timbang Berat Badan dan Tinggi Badan
Bila tinggi badan < 145 cm, maka faktor risiko panggul
sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal.
17
Penimbangan berat badan setiap kali periksa, sejak bulan ke-4
pertambahan berat badan paling sedikit 1 kg/ bulan.
2) Tekanan Darah
Diukur setiap kali ibu datang atau berkunjung. Deteksi
tekanan darah yang cenderung naik diwaspadai adanya gejala
hipertensi dan preeklamsi. Apabila turun dibawah normal kita
pikirkan kearah anemia. Tekanan darah normal berkisar
sytole/diastole 110/80-120/80 MmHg. Pengukuran Lingkar
Lengan Atas (LILA )
Bila < 23,5 cm menunjukan ibu hamil menderita Kurang
Energi Kronis ( Ibu hamil KEK) dan berisiko melahirkan Bayi
Berat Lahir Rendah (BBRL)
3) Ukur Lingkar lengan atas
Pengukuran ini merupakan satu cara untuk mendeteksi dini
adanya kekurangan gizi saat hamil. Jika kekurangan nutrisi.
Penyaluran gizi janin akan berkurang dengan mengakibatkan
pertumbuhan terhambat juga potensi bayi lahir dengan berat
rendah. Cara pengukuran ini di lakukan dengan pita ukur
mengukur jarak pangkal bahu ke ujung siku, dan lingkar lengan
atas (LILA).
4) Pengukuran tinggi rahim
Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat
pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan.
5) Penentuan letak janin (presentasi janin) dan perhitungan denyut
jantung janin
Apabila trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau
kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak
18
atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120
kali / menit atau lebih dari 160 kali/menit menunjukan ada tanda
gawat janin segera rujuk.
6) Penentuan status imunisasi Tetanus Toksoid (TT)
Oleh petugas untuk selanjutnya bilamana diperlukan
mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas
kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.
Tabel 2.1. Kunjungan Pemeriksaan Antenatal
Imunisasi Selang waktu
minimal
Lama perlindungan
TT 1 pada kunjungan
ANC pertama
Langkah awal pembentukan
kekebalan tubuh terhadap
penyakit tetanus
TT 2 1 bulan setelah TT 1 3 tahun
TT 3 6 bulan setelah TT2 5 tahun
TT 4 12 bulan setelah
TT3
10 tahun
TT 5 12 bulan setelah
TT4
7 tahun
7) Pemberian tablet tambah darah
Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah
darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah
diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual.
8) Tes laboratorium
a) Tes golongan darah, untuk mempersiapkan donor bagi ibu
hamil bila diperlukan
19
b) Tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan
darah (anemia)
c) Tes pemeriksaan urine (air kencing )
d) Tes pemeriksaan darah lainnya, sesuai indikasi seperti
malaria, Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan lain
lain
9) Konseling atau penjelasan
Tenaga Kesehatan member penjelasan mengenai
perawatan Kehamilan, pencegahan kelainan bawaan,
persalinan dan inisiasi menyusui dini, nifas, perawatan bayi
baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana dan imunisasi
pada bayi.
Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan
ibu hamil
10) Tata laksana atau mendapatkan pengobatan
Jika Ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil
e. Standar minimal kunjungan kehamilan
Menurut WHO (2013) dalam Saifuddin (2006), setiap wanita
hamil, menghadapi risiko komplikasi yang bisa mengancam
jiwanya. Oleh karena itu, setiap wanita hamil memerlukan
sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu :
1) 1 kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum minggu
14)
2) 1 kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-
28)
3) 2 kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36
dan sesudah minggu ke-36)
20
f. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
(P4K)
Menurut (Maryunani, 2013), Program Perencanaan Persalinan
Pencegahan Komplikasi (P4K) salah satu program untuk
mendukung desa siaga yang diarahkan pada konsep persiapan
persalinan dan kesiagaan menghadapi komplikasi.
Komplikasi adalah kegiatan dalam ante natalcare yang
dilakukan bidan terkait dengan pelayanan kebidanan sosial
bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan
keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan
agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
Tujuan P4K
1) Tujuan Umum :
Tujuan umum yaitu meningkatkan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih sehingga menurunkan unmet need keluarga
berencana pada ibu (Anonim, 2008).
Meningkatkan pelayanan ibu hamil agar melahirkan
dengan aman dan selamat (Pambudi, 2008 dalam Maryunani,
2013).
2) Tujuan Khusus menurut (Maryunani, 2013) :
a) Dipahaminya setiap persalinan berisiko oleh suami, keluarga,
dan masyarakat luas.
b) Memfokuskan pada motivasi kepada keluarga saat antenatal
care oleh bidan, adanya rencana persalinan aman yang
disepakati antara ibu hamil, suami, keluarga dengan bidan
terdapatnya sasaran dan terpasangnya stiker P4K.
21
c) Adanya kesiapan menghadapi komplikasi (transportasi, calon
donor darah dan dana) yang disepakati ibu hamil, suami,
keluarga dengan bidan.
d) Adanya dukungan secara luas dari tokoh-tokoh masyarakat
baik formal maupun non formal, kader, dukun bayi.
e) Memantau kemitraan antara bidan, dukun bayi dan kader.
f) Dan adanya rencana alat kontrasepsi setelah melahirkan
setelah melahirkan yang disepakati antara ibu hamil, suami
dan keluarga, dengan bidan atau tenaga kesehatan.
g. Kebutuhan gizi ibu hamil
Menurut (Ariani, 2017), akan meningkat dari biasanya dimana
pertukaran dari hampir semua bahan itu terjadi sangat aktif
terutama pada trimester III. Karena peningkatan jumlah konsumsi,
makan perlu ditambah terutama konsumsi pangan sumber energi
untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin.
Kebutuhan gizi ibu hamil antara lain :
1) Kebutuhan energi
Selama proses kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan
kalori sejalan dengan adanya peningkatan laju metabolik basal
dan penambahan berat badan yang akan meningkatkan
penggunaan kalori selama aktifitas. Selain itu juga selama
hamil, ibu membutuhkan tambahan energi/kalori untuk
pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, jaringan
payudara, dan cadangan lemak. Kebutuhan kalori kira-kira
sekitar 15% dari kalori normal. Tambahan energi yang
diperlukan selama hamil yaitu 27.000 – 80.000 Kkal atau 100
Kkal/hari. Sedangkan energi yang dibutuhkan oleh janin
22
sendiri untuk tumbuh dan berkembang adalah 50-95
Kkal/Kg/hari atau sekitar 175-350 Kkal/hari pada janin dengan
berat badan 3,5 kg. Sumber energi bisa didapat dengan
mengkonsumsi beras, jagung, gandum, kentang, ubi jalar, ubu
kayu, dan sagu.
2) Karbohidrat
Janin memerlukan 40 gram glukosa/hari yang akan
digunakan sebagai sumber energi. Glukosa sangat dibutuhkan
karena akan membantu dalam sintesis lemak, glikogen, dan
pembentukan struktur polisakarida. Karbohidrat merupakan
sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama
kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama
dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber
kalori utama. Pilihan yang dianjurkan adalah karbohidrat
kompleks seperti roti, serealia, nasi dan pasta. Selain
mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat kompleks juga
meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil
untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar
dan wasir (Haemorroid).
Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Ibu hamil
membutuhkan karbohidrat sekitar 1.500 kalori. Bahan
makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah serealia
(padi-padian) dan produk olahanya, juga kentang umbi dan
jagung. Namun, karena tidak semua sumber karbohidrat baik,
maka ibu hamil harus bisa memilih yang tepat. Misalnya,
sumber karbohidrat yang perlu dibatasi adalah gula dan
makanan yang mengandung banyak gula, seperti cake, dan
23
permen. Sedangkan karbohidrat yang sebaiknya dikonsumsi
adalah karbohidrat kompleks yang terdapat pada roti gandum,
kentang, serelia atau padi-padian yang tidak di giling.
Mengkonsumsi cukup karbohidrat kompleks dapat mencegah
sembelit.
3) Protein dan asam amino
Protein digunakan untuk proses pertumbuhan dan
perkembangan janin, protein memiliki peranan penting.
Selama kehamilan terjadi peningkatan protein yang signifikan
yaitu 68%. Peran protein selama proses kehamilan diantaranya
yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga
untuk pembentukan plasenta dan cairan amnion, pertumbuhan
jaringan maternal seperti pertumbuhan mammae ibu dan
jaringan uterus, dan penambahan volume darah. Total protein
fetal yang diperlukan selama masa gestasi berkisar antara 350-
450 gr.
Secara keseluruhan jumlah protein yang diperlukan oleh
ibu hamil yaitu kurang lebih 60-76 gram setiap hari atau
sekitar 925 gram dari total protein yang dibutuhkan selama
kehamilan. Ini dapat diartikan bahwa wanita hamil
membutuhkan protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan
wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk
membentuk jaringan baru, maupun plasenta dan janin. Sumber
protein bisa didapat melalui protein hewani dan nabati. Protein
hewani meliputi daging, ikan, unggas, telur dan kerang.
Sedangkan untuk protein hewani bisa didapat dari daging sapi,
ikan, unggas. Bahan makanan sumber protein nabati adalah
24
kacang-kacangan seperti tahu, tempe, oncom dan selai kacang.
Selain itu, karena protein yang berasal dari ternak juga kaya
dengan lemak, maka seimbangkan asupan protein hewani dan
nabati. Pilih bahan makanan protein hewani yang berlemak
rendah.
4) Lemak
Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam
kandungan membutuhkan lemak sebagai lemak kalori utama.
Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk
pertumbuhan janin dan plasenta. Pada kehamilan yang normal,
kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir
trimester III. Tubuh wanita hamil juga akan mendukung
persiapan untuk wanita menyusui stelah bayi lahir.
5) Vitamin
Yang larut dalam lemak antara lain :
a) Vitamin A
Vitamin A dari Ibu dibutuhkan oleh janin yaitu
kurang dari 25 mg/hari, sedangkan vitamin A yang
dibutuhkan pada kehamilan trimester tiga yaitu berkisar
200 mg/hari.
b) Vitamin D
Vitamin D dari janin berasal dari 25-OH vitamin D
ibu yang berada di dalam otot dan hati fetus. Kebutuhan
vitamin D selama kehamilan belum diketahui secara pasti
tetapi diperkirakan 10mg/hari.
25
c) Vitamin E
Vitamin E mulai diakumulasikan oleh fetus pada
akhir minggu ke 8-10 usia gestasi, ketika terjadi
peningkatan akumulasi lemak. Untuk tetap menjaga
pertumbuhan dan perkembangan fetus yang baik
diperlukan reverensi diet asupan vitamin E yaitu sebanyak
2 mg/hari. Pada waktu hamil terjadi peningkatan 25%.
Untuk ibu hamil kebutuhannya sekitar 15 mg (22,5 IU)
dan ibu yang menyusui sekitar 19 mg (28,5 IU).
d) Vitamin K
Vitamin K fungsinya belum begitu optimal pada masa
kehamilan didalam fetus.
Vitamin yang larut dalam air antara lain :
a) Vitamin C
Kebutuhan vitamin C untuk bayi pada masa
kehamilan menjelang kelahiran yaitu berkisar antara 3-4
mg/hari. Ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 70
mg perhari. Untuk mencegah kekurangan vitamin C
selama proses kehamilan diperlukan tambahan vitamin C
sebanyak 10 mg/hari dengan peningkatan sebanyak 33%.
Dibutuhkan untuk memperkuat pembuluh darah dan
mencegah perdarahan, mengurangi rasa sakit sebanyak
50% saat bekerja, mengurangi resiko infeksi setelah
melahirkan dan membantu gigi dan tulang bayi.
b) Thiamin
Menggunakan status pengukuran thiamin maternal
dapat diketahui kebutuhan thiamin selama kehamilan,
26
yaitu dengan cara memasukan eksresi thiamin urin dan
aktivitas dari enzim thiamin dependen seperti translokasi
sel merah yang akhirnya dapat digunakan sebagai indikasi
adanya peningkatan thiamin selama kehamilan.
c) Vitamin B6
Vitamin B6 penting untuk metabolisme asam amino.
Pada masa kehamilan diperlukan intake protein yang lebih
tinggi karena adanya proses pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat sehingga diperlukan juga
adanya vitamin B6 yang besar untuk melakukan
metabolisme dengan peningkatan 100%. Vitamin B6
dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi mual
dan muntah.
d) Asam Folat
Asam folat memiliki peranan penting yaitu dalam hal
pencegahan terjadinya defek tubaneural seperti spina
bifida dan anensefali yang sangat berbahaya bagi
perkembangan selanjutnya. Dari hasil survey mengatakan
bahwa kebanyakan wanita mengkonsumsi folat lebih
sedikit dari kebutuhan yaitu 0,2 mg perhari dengan
peningkatan 33%. Reverensi diet asupan folat untuk
wanita hamil yaitu 400 mg/hari yaitu dimana terjadi
peningkatan sebanyak 10% dari sebelumnya. Makanan
yang kaya akan asam folat dapat dijumpai pada sayuran
hijau, jus jeruk, asparagus dan brokoli. Asam folat
merupakan kelompok vitamin B paling utama selama
masa kehamilan karena dapat mencegah cacat tabung
syaraf (neural tube defects) seperti Spina Bifida. Ibu hamil
harus meningkatkan asupan folat hingga 0,4-0,5 mg/hari.
27
2. Konsep dasar kehamilan dengan riwayat tuberculosis paru
Menurut (Sofian, 2011) :
a. Definisi tuberculosis pada kehamilan
Pada umumnya penyakit paru-paru tidak mempengaruhi
kehamilan, persalinan dan nifas, kecuali penyakitnya tidak terkontrol,
berat dan luas di sertai sesak dan hipoksia. Walaupun kehamilan
menyebabkan sedikit perubahan pada system pernafasan, karena
uterus yang membesar dapat mendorong diafragma dan paru-paru ke
atas serta sisa dalam udara kurang, namun penyakit tersebut tidak
selalu menjadi lebih parah.
Pengaruh Tuberkulosis Paru terhadap Kehamilan Dulu pernah
dianggap bahwa wanita dengan tuberkulosis paru aktif mempunyai
insidensi yang lebih tinggi secara bermakna dibandingkan wanita
hamil tanpa infeksi tuberkulosis paru dalam hal abortus spontan dan
kesulitan persalinan. Banyak sumber yang mengatakan peranan
tuberkulosis terhadap kehamilan antara lain meningkatnya abortus,
pre-eklampsi, serta sulitnya persalinan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa hal tersebut tergantung dari letak tuberkulosis
apakah paru atau nonparu serta apakah tuberkulosis terdiagnosis
semasa kehamilan. Pada penelitian terhadap wanita-wanita Indian
yang mendapat pengobatan selama 6-9 bulan semasa kehamilan maka
kematian janin 6 kali lebih besar dan insidens dari: prematuritas,
KMK ( kecil untuk masa kehamilan), BBLR (berat badan lahir
rendah) (<2500g) adalah 2 kali lipat. Pengaruh tidak langsung
tuberkulosis terhadap kehamilan ialah efek teratogenik terhadap janin
karena obat anti tuberkulosis yang diberikan kepada sang ibu. Efek
28
samping pasien yang mendapat terapi anti tuberkulosis yang adekuat
adalah gangguan pada traktus genitalis dimana traktus genitalis
terinfeksi dari fokus primer TB paru.
b. Tanda-tanda tuberculosis
Ada beberapa tanda saat paru seseorang terjangkit tuberculosis
paru, diantaranya :
1) Batuk-batuk berdahak selama 3 minggu lebih
2) Batuk-batuk mengeluarkan dahak bercampur darah
3) Sesak nafas dan rasa nyeri dada
4) Nafsu makan menurun
5) Berkeringat pada malam hari walaupun tanpa kegiatan
c. Penyebab tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab terjadinya
penyakit tuberculosis. Bakteri ini pertama kali di deskripsikan tanggal
24 maret 1882 oleh Robert Koch. Bakteri ini juga sering di sebut
abasilus Koch. Bentuk, penanaman dan sifat-sifat dari mycobacterium
tuberculosis dapat diuraikan sebagai berikut Bentuk Mycobacterium
Tuberculosis berbentuk batang lurus atau agak bengkok dengan
ukuran 2-4 cm dan lebar 0,2-0,5. Pewarnaan ziehl-neelsen di
pergunakan untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam.
d. Sifat-sifat mycobacterium tuberculosis
1) Mycobacterium tidak tahan panas, akan mati pada 6 oC selama 15-
20 menit.
2) Biarkan dapat mati jika terkena sinar matahari langsung selama 2
jam.
3) Dalam dahak bakteri ini dapat bertahan selama 20-30 jam.
29
4) Basil yang berada dalam percikan bahan dapat bertahan hidup
selama 8-10 hari.
5) Dalam suhu kamar, biarkan basil ini dapat hidup selama 6-8 jam
bulan dapat disimpan dalam lemari dengan suhu 20o C selama 2
tahun.
6) Bakteri ini tahan terhadap berbagai khemikalian dan disinfektan,
antara lain phenol 5% asam sulfat 15% asam sitrat 3% dan NaOH
4%.
7) Basil ini dapat di hancurkan oleh yodium tinetur dalam waktu 5
menit, sementara dengan alcohol 80% akan hancur dalam 2-10
menit kemudian.
e. Penularan tuberculosis paru
Penyebaran kuman tuberculosis bakteri tahan asam positif. Pada
batuk/bersin, penderita menyebaran kuman ke udara dalam bentuk
droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat
bertahan hidup di udara pada suhu selama beberapa jam. Orang dapat
terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan
kemudian menmyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui
system peredaran darah, system saluran limfe, saluran nafas atau
penyebaran langsung ke bagian tubuh lain.
f. Klasifikasi penyakit tuberculosis
Bentuk penyakit tuberculosis ini dapat di klasifikasikan menjadi
tuberculosis paru dan tuberculosis ekstra paru.
1) Tuberculosis paru
Penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering di jumpai,
tuberculosis yang menyerang jaringan paru-paru termasuk pleura
30
(selaput paru). Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, tuberculosis
paru dibagi menjadi dua yaitu bakteri tahan asam positif dan
bakteri tahan asam negative.
2) Tuberculosis Ekstra Paru
Penyakit ini merupakan tuberculosis yang menyerang organ
tubuh lain selain paru-paru misalnya pleura, selaput otak, selaput
jantung (pericardium), kelenjar limfe, tulang persendian, kulit, usus,
ginjal, saluran kencing dan alat kelamin. Oleh karna itu, penyakit
tuberculosis ini kemudian dinamakan penyakit yang tidak pandang
bulu, karena dapat menyerang seluruh organ dalam tubuh manusia
secara bertahap. Dengan kondisi organ tubuh yang telah rusak,
tentu saja dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya.
g. Faktor-Faktor Penyebab Tuberculosis Paru
Kondisi social ekonomi, status gizi, umur jenis kelamin, dan
faktor toksis pada manusia, ternyata menjadi faktor penting dari
penyakit tuberculosis berikut ini penjelasanya :
1) Faktor Sosial Ekonomi
Faktor social ekonomi di sini sangat erat kaitanya dengan
kondisi rumah, kepadatan hunian, lingkungan rumah,serta
lingkungan dan sanitasi tempat bekerja yang buruk. Pendapatan
yang kecil membuat orang tidak layak untuk memenuhi syarat-
syarat kesehatan.
2) Status Gizi
Kekurangan kalori, protein, vitamin, zat besi dan lain-lain
(malnutrisi), akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang,
31
sehingga rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk tuberculosis
paru. Keadaan ini merupakan faktor penting yang berpengaruh di
Negara miskin, baik pada orang dewasa maupun anak-anak.
3) Umur
Penyakit tuberculosis paru peling sering ditemukan pada usia
muda atau usia produktif, yaitu 15-50 tahun. Pada usia lanjut, lebih
dari 55 tahun system imunologi seseorang menurun, sehingga
sangat rentan terhadap penyakit, termasuk tenyakit tuberculosis
paru.
4) Jenis Kelamin
Sedikit dalam periode setahun sekitar 1 juta perempuan yang
meninggal akibat tuberculosis paru. Dari fakta ini, dapat di
simpulkan bahwa kaum perempuan lebih rentan terhadap kamatian
akibat serangan tuberculosis paru dibandingkan akibat proses
kehamilan dan persalinan. Pada laki-laki penyakit ini lebih tinggi,
karena rokok dan minuman keras dapat menurunkan system
pertahanan tubuh. Sehingga, wajar jika merokok peminum alcohol
sering di sebut sebagai agen dari penyakit tuberculosis.
5) Vertilisasi
Mempunyai banyak fungsi yaitu menjaga agar aliran udara di
dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan
oksigen yang di perlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap
terjaga.
h. Pencegahan penyakit tuberculosis paru
32
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit
terjangkitnya tuberculosis paru. Pencegahan-pencegahan berikut dapat
dikerjakan oleh penderita, masyarakat maupun petugas kesehatan.
1) Bagi penderita pencegahan penularan dapat dilakukan dengan
menutup mulut saat batuk, dan membuang dahak tidak di
sembarang tempat.
2) Bagi masyarakat pencegahan penularan dapat dilakukan terhadap
bayi, yaitu dengan memberikan vaksin bacillus calmette guerin.
3) Bagi petugas kesehatan pencegahan dapat di lakukan dengan
memberikan penyuluhan tentang penyakit tuberculosis, yang
meliputi gejala, bahaya, dan akibat yang di timbulkannya terhadap
kehidupan masyarakat pada umumnya.
4) Petugas kesehatan juga harus segera melakukan pengisolaisan dan
pemeriksaan terhadap orang-orang yang terinfeksi, atau dengan
memberikan pengobatan khusus kepada penderita tuberculosis.
i. Prognosa
Secara umum penderita yang tidak begitu parah di obati paling
tidak, prosesnya bisa dihambat oleh kinerja obat-obat kemoterapi
modern yang dikonsumsi. Tetapi selain dari kegagalan paru atau
hemoptoe. Pada beberapa kasus, perjalanan penyakit terus memburuk
sehingga terjadi destroyed lung, suatu keadaan di sebut phtysis
gallopans (sangat kurus dan lemah).
Secara teoritis pada penyakit tuberculosis terdapat 10-100 juta
basil. Satu diantara 100 ribu basil akan resisten terhadap salah satu
obat anti tuberculosis (OAT) pada tiga bulan pertama penderita diberi
obat secara intensif yaitu dengan pemberian kombinasi Isoniazid dan
33
Ethambutol. Ada beberapa orang yang cenderung pada cara
pengobatan yang lebih singkat, dikarenakan batasnya biaya.
j. Efek tuberculosis paru pada kehamilan
Dimana peningkatan diafragma akibat kehamilan akan
menyebabkan kavitas paru bagian bawah mengalami kolaps yang
disebut pneumo-peritoreum.
k. Penatalaksanaan medis pada kehamilan dengan tuberculosis
Menururt Meiyanti 2007. Penatalaksanaan pasien TBC pada
kehamilan tidak berbeda dengan TBC tanpa kehamilan. Hal-hal yang
harus diperhatikan adalah pemberian OAT yang bisa menimbulkan
efek teratogenik terhadap janin. Penatalaksanaan secara umum terbagi
atas penderita dengan TBC aktif dan TBC laten. Wanita hamil dengan
TBC aktif biasanya diterapi dengan tidak mempertimbangkan
trisemester kehamilan. OAT yang digunakan tidak berbeda dengan
wanita yang tidak hamil.Golongan utama OAT seperti isoniazid,
rifampisin, etambutol digunakan secara luas pada wanita hamil. Obat-
obat tersebut dapat melalui plasenta dalam dosis rendah dan tidak
menimbulkan efek teratogenik pada janin. Pada pemberian isoniazid
sebaiknya diberikan piridoksin 50 mg/hari untuk mencegah terjadinya
neuropati perifer. Pemeriksaan fungsi hati sebaiknya dilakukan saat
pemberian isonizid dan rifampisin. Pemberian vitamin K dilakukan
pada akhir trismester ketiga kehamilan dan bayi yang baru lahir. Pada
kasus multidrug resistant (MDR) digunakan pirazinamid, akan tetapi
pirazinamid tidak digunakan secara rutin pada wanita hamil karena
terdapat efek teratogenik. Paraamino salisilat (PAS) telah digunakan
secara aman pada wanita hamil akan tetapi obat tersebut ditoleransi
34
tubuh secara buruk. Tuberkulosis laten adalah pasien dengan uji
tuberkulin positif dan secara klinis tidak ada tanda-tanda terjadi
tuberkulosis aktif. Terapi pada TBC laten tergantung faktor risiko dan
hasil konversi uji tuberkulin. Pemberian terapi pada TBC laten
biasanya ditunda sampai 2-3 bulan setelah kelahiran. Pada pasien yang
mempunyai risiko kontak dengan individu BTA positif dan infeksi
HIV, terapi diberikan setelah trisemester pertama pada kehamilan
dengan konversi uji tuberkulin positif dalam 2 tahun terakhir.
Sedangkan pada wanita hamil dengan TBC laten yang sebelumnya
telah diterapi secara adekuat tidak memerlukan terapi profilaksis
isoniazid (300 mg selama 6-12 bulan). Penatalaksanaan TBC pada
wanita hamil harus diberikan secara tepat dan adekuat, serta mencegah
timbulnya efek samping teratogenik pada janin. Pasien TBC aktif
dengan sputum BTA positif diberikan isoniazid, rifampisin, etambutol
dan piridoksin selama 9 bulan pada populasi risiko TBC rendah. Pada
populasi dengan risikoTBC tinggi dan adanya resisten obat anti TBC
tinggi perlu penambahan pirazinamid. Pasien dengan uji tuberkulin
positif, sputum BTA negatif, biakan negatif dan foto toraks
menunjukkan infiltrat atau adanya kavitas, diberikan isoniazid,
rifampisin, etambutol dan piridoksin selama 9 bulan. Sedangkan bila
pada foto toraks terlihat proses penyakit yang telah menyembuh
(terdapat kalsifikasi pada kelenjar getah bening dan lesi parenkim),
dilakukan observasi pada pasien. Pengobatan diberikan secara tepat
setelah melahirkan atau diberi pengobatan profilaksis dengan
isoniazid dan piridoksin selama 9 bulan yang dimulai pada trisemester
kedua kehamilan. Pasien dengan konversi uji tuberkulin terbaru
35
positif, foto toraks normal serta pemeriksaan bakteriologis negatif,
maka dilakukan observasi selama kehamilan, pengobatan diberikan
setelah melahirkan atau dengan pemberian profilaksis isoniazid dan
piridoksin selama 9 bulan dimulai pada trisemester kedua kehamilan.
Pasien dengan resistensi organisme maka diberikan isoniazid,
rifampisin, etambutol, pirazinamid sesuai dengan uji sensitivitas. Pada
pasien dengan ketidakmampuan mentoleransi isoniazid dan
rifampisin, maka diberikan etambutol atau obat lain yang tersedia.
Menurut Najoan Nan Warouw 2007. Penatalaksanaan Umum
Penatalaksanaan Pasien Hamil dengan Tes PPD Positif.
1) Masa kehamilan trimester I
a) Kurangi aktivitas fisik (bedrest) Terpenuhinya kebutuhan nutrisi
(tinggi kalori tinggi protein) Pemberian vitamin dan Fe
Dukungan keluarga & kontrol teratur.
b) Dianjurkan penderita datang sebagai pasien permulaan atau
terakhir dan segera diperiksa agar tidak terjadi penularan pada
orang-orang disekitarnya. Dahulu pasien tuberkulosis paru
dengan kehamilan harus dirawat dirumah sakit, tetapi sekarang
dapat berobat jalan dengan pertimbangan istirahat yang cukup,
makanan bergizi, mencegah penularan pada keluarga dll.
c) Pasien sejak sebelum kehamilan telah menderita TB paru Æ
Obat diteruskan tetapi penggunaan rifampisin di stop.
d) Bila pada pemeriksaan antenatal ditemukan gejala klinis
tuberkulosis paru (batuk-batuk/batuk berdarah, demam, keringat
malam, nafsu makan menurun, nyeri dada,dll) maka sebaiknya
diperiksakan PPD (Purified Protein Derivate), bila hasilnya
36
positif maka dilakukan pemeriksaan foto dada dengan pelindung
pada perut, bila tersangka tuberkulosis maka dilakukan
pemeriksaan sputum BTA 3 kali dan biakan BTA. Diagnosis
ditegakkan dengan adanya gejala klinis dan kelainan
bakteriologis, tetapi diagnosis dapat juga dengan gejala klinis
ditambah kelainan radiologis paru.
2) Masa kehamilan trimester II dan III
Pada penderita TB paru yang tidak aktif, selama kehamilan
tidak perlu dapat pengobatan. Sedangkan pada yang aktif,
hendaknya jangan dicampurkan dengan wanita hamil lainnya pada
pemeriksaan antenatal dan ketika mendekati persalinan sebaiknya
dirawat di rumah sakit; dalam kamar isolasi. Gunanya untuk
mencegah penularan, untuk menjamin istirahat dan makanan yang
cukup serta pengobatan yang intensif dan teratur. Dianjurkan untuk
menggunakan obat dua macam atau lebih untuk mencegah
timbulnya resistensi kuman. Untuk diagnosis pasti dan pengobatan
selalu bekerja sama dengan ahli paru-paru.3-5 Penatalaksanaan
sama dengan masa kehamilan trimester pertama tetapi pada
trimester kedua diperbolehkan menggunakan rifampisin sebagai
terapi. Medikamentosa (Dilakukan atas konsultasi dengan
Internest)
a) PPD (+) tanpa kelainan radiologis maupun gejala klinis: - INH
400 mg selama 1 tahun.
b) TBC aktif (BTA +) - Rifampisin 450-600 mg/hr selama 1 bulan,
dilanjutkan 600 mg 2x seminggu selama 5-8 bulan - INH 400
37
mg/hr selama 1 bulan, dilanjutkan 700 mg 2x seminggu selama
5-8 bulan Æ Etambutol 1000 mg/hr selama 1 bulan.
l. Skrining tuberculosis paru pada kehamilan
Prenatal screening test atau tes skrining saat hamil adalah
seperangkat prosedur yang dilakukan selama kehamilan untuk
menentukan apakah bayi cenderung memiliki kelainan atau cacat lahir
tertentu. Sebagian besar tes ini tidak invasif. Tes-tes ini biasanya
dilakukan selama trimester pertama dan kedua, tapi beberapa juga
dilakukan pada trimester ketiga.
Tes skrining saat hamil hanya bisa memberi tahu risiko atau
kemungkinan adanya kondisi tertentu pada janin. Bila hasil tes
skrining positif, maka diperlukan lagi tes diagnosis untuk
mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut beberapa skrining tes
yang menjadi prosedur rutin untuk ibu hamil.
Tes skrining saat hamil trimester
Tes skrining trimester pertama bisa dimulai sejak kehamilan 10
minggu, yang merupakan kombinasi antara ultrasonografi (USG) janin
dan tes darah ibu.
1. USG
Tes ini dilakukan untuk menentukan ukuran dan posisi bayi.
Selain itu juga membantu menentukan adanya risiko janin
mengalami cacat lahir, dengan mengamati struktur tulang dan
organ bayi. USG nuchal translucency (NT) adalah pengukuran
peningkatan atau ketebalan cairan di bagian belakang leher janin
pada usia kehamilan 11-14 minggu dengan USG. Bila ada cairan
38
lebih banyak dari biasanya, berarti ada risiko Down syndrome pada
bayi yang lebih tinggi.
2. Tes darah
Selama trimester pertama, dilakukan dua jenis tes serum darah
ibu, yaitu Pregnancy-associated plasma protein (PAPP-A) dan
hormon hCG (Human chorionic gonadotropin). Ini merupakan
protein dan hormon yang diproduksi oleh plasenta pada awal
kehamilan. Jika hasilnya tidak normal, berarti ada peningkatan
risiko kelainan kromosom. Tes darah juga dilakukan untuk
mengetahui adanya penyakit menular pada bayi, atau disebut
dengan tes TORCH. Tes ini merupakan akronim dari lima jenis
infeksi menular yaitu toksoplasmosis, penyakit lain (termasuk HIV,
sifilis, dan campak), rubella (campak Jerman), sitomegalovirus, dan
herpes simplex. Selain itu, tes darah juga akan digunakan untuk
menentukan golongan darah dan Rh (rhesus) Anda, yang
menentukan hubungan Rh Anda dengan janin yang sedang tumbuh.
3. Chorionic villus sampling
Chorionic villus sampling adalah tes skrining invasif yang
dilakukan dengan mengambil potongan kecil dari plasenta. Tes ini
biasanya dilakukan antara minggu ke 10 dan 12 kehamilan. Tes ini
biasanya merupakan tes lanjutan dari USG NT dan tes darah yang
tidak normal. Tes ini dilakukan untuk lebih memastikan adanya
kelainan genetik pada janin seperti Down syndrome.
39
Tes skrining saat hamil trimester 2
1. Tes darah
Tes darah saat hamil trimester kedua mencakup beberapa tes
darah yang disebut multiple markers. Tes ini dilakukan untuk
mengetahui adanya risiko cacat lahir atau kelainan genetik pada
bayi. Tes ini sebaiknya dilakukan pada minggu ke 16 sampai 18
kehamilan.
Tes darah tersebut meliputi:
Kadar alpha-fetoprotein (AFP). Ini adalah protein yang
biasanya diproduksi oleh hati janin dan terdapat dalam cairan
yang mengelilingi janin (cairan amnion atau ketuban), dan
menyilang plasenta ke dalam darah ibu. Tingkat AFP yang
tidak normal mungkin meningkatkan risiko seperti spina
bifida, sindrom Down atau kelainan kromosom lainnya, cacat
di perut janin, dan kembar.
Kadar hormon yang diproduksi plasenta, antara lain hCG,
estriol, dan inhibun.
2. Tes gula darah
Tes gula darah digunakan untuk mendiagnosis diabetes
gestasional. Ini merupakan kondisi yang bisa berkembang selama
kehamilan. Kondisi ini dapat meningkatkan kelahiran secara
caesar karena bayi dari ibu dengan diabetes gestasional biasanya
memiliki ukuran yang lebih besar. Tes ini juga bisa dilakukan
setelah hamil jika wanita memiliki kadar gula darah tinggi selama
kehamilan. Atau jika Anda memiliki kadar gula darah rendah
setelah melahirkan.Ini merupakan serangkaian tes yang dilakukan
40
setelah Anda minum cairan manis yang mengandung gula. Jika
Anda positif memiliki diabetes gestasional, Anda memiliki risiko
diabetes yang lebih tinggi dalam 10 tahun berikutnya, dan Anda
harus mendapatkan tes lagi setelah kehamilan.
3. Amniocentesis
Selama amniosentesis, cairan ketuban dikeluarkan dari rahim
untuk diuji. Ini berisi sel janin dengan susunan genetik yang sama
seperti bayi, serta berbagai bahan kimia yang diproduksi oleh
tubuh bayi. Ada beberapa jenis amniosentesis. Tes amniosentesis
genetik untuk kelainan genetik, misalnya spina bifida. Tes ini
biasanya dilakukan setelah minggu ke 15 kehamilan. Tes ini
dianjurkan jika: Skrining tes saat hamil menunjukkan hasil yang
tidak normal.
Memiliki kelainan kromosom selama kehamilan sebelumnya.
Ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih.
Memiliki riwayat jeluarga dengan kelainan genetik tertentu.
Tes skrining saat hamil trimester
Skrining Strepococcus Group B
Strepococcus Group B (GBS) adalah kelompok bakteri yang
dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil dan bayi yang baru
lahir. GBS pada wanita sehat sering ditemukan di daerah mulut,
tenggorokan, saluran pencernaan, dan vagina. GBS di vagina
umumnya tidak berbahaya bagi wanita terlepas dari sedang hamil atau
tidaknya. Namun, bisa sangat berbahaya bagi bayi yang baru lahir
yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. GBS dapat
41
menyebabkan infeksi serius pada bayi yang terinfeksi saat lahir. Tes
ini dilakukan dengan mengusap vagina dan rektum ibu hamil pada
usia kehamilan ke 35 sampai 37 minggu. Jika hasil skrining GBS
positif, Anda akan diberikan antibiotik saat dalam proses persalinan
untuk mengurangi risiko bayi terkena infeksi GBS.
42
B. Teori Persalinan
2. Pengertian Persalinan
a. Definisi
Persalinan adalah proses pengeluaran (kelahiran) hasil konsepsi
yang dapat hidup diluar uterus melalui vagina ke dunia luar. Proses
tersebut dapat dikatakan normal atau spontan. Jika bayi yang
dilahirkan berada pada posisi letak belakang kepala dan berlangsung
tanpa bantuan atau pertolongan, serta tidak melukai ibu dan bayi.
Pada umumnya proses ini berlangsung dalam waktu kurang dari 24
jam (Jenny, 2013).
b. Mekanisme persalinan
Mekanisme persalinan menurut Rukiyah (2009) :
1) Turunya kepala janin
Sebetulnya janin mengalami penurunan terus menerus
dalam jalan lahir sejak kehamilan TM III, antara lain masuknya
bagian terbesar janin kedalam pintu atas panggul (PAP) yang
pada primigravida 38 minggu atau selambat-lambatnya awal
kala II.
2) Fleksi
Pada permulaan persalinan kepala janin biasanya berada
dalam sikap fleksi. Dengan adanya his dan tahanan dasar
panggul yang makin besar, maka kepala janin makin turun dan
semakin fleksi sehingga dagu janin menekan pada dada dan
43
belakang kepala (oksiput) menjadi bagian bawah. Keadaan ini
disebut fleksi maksimal.
3) Rotasi dalam/putaran paksi dalam
Makin turunya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin
akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang
rongga panggul atau diameter anterior posterior kepala janin
akan bersesuaian dengan diameter terkecil antero posterior pintu
bawah panggul. Hal ini mungkin karena kepala janin bergerak
spiral atau seperti sewaktu turun dalam jalan lahir. Bahu tidak
berputar bersama-sama dengan kepala akan membentuk sudut
45. Keadaan demikian disebut putaran paksi dalam ubun-ubun
kecil berada dala simfisis.
4) Ekstensi
Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar
panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini
disebabkan karena sumbu jalan lahir pada putaran bawah
panggul mengarah kedepan dan keatas, sehingga kepala harus
mengadakan ekstensi untuk melaluinya kalau tidak terjadi
ekstensi maka kepala akan tertekan pada pertemuan dan
menembusnya. Dengan ekstensi ini maka subocciput bertindak
sebagai Hipomochilon (sumbu putar). Kemudian lahirlah
berturut-turut sinsiput (puncak kepala) , dahi, hidung, mulut, dan
akhir dagu.
44
5) Rotasi luar/putaran paksi luar
Setelah ekstensi kemudian diikuti dengan putaran paksi luar
yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaiakan kembali
dengan sumbu panjang bahu, sehingga panjang bahu dengan
sumbu panjang kepala janin berada pada satu garis lurus.
6) Ekspulsi
Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah
sympisis dan menjadi hipomochlion untuk kelahiran bahu
belakang. Kemudian bahu belakang menyusul dan selanjutnya
seluruh tubuh bayi lahir searah dengan paksi jalan lahir.
c. Fisiologis persalinan
Menurut (Rukiah, 2009), Proses persalinan dapat terjadi dengan
adanya perubahan hormone estrogen, progesterone, prostaglandin,
uterus yang menjadi besar dan meregang, tekanan pada ganglion
cervicale dan penurunan fungsi plasenta.
Tahapan dari persalinan terdiri atas kala I (kala pembukaan),
kala II (kala pengeluaran janin), kala III (pelepasan plasenta), kala
IV (kala pengawasan/observasi/pemulihan).
1) Kala I
Kala I dimulai dari saat persalinan mulai (pembukaan nol)
sampai pembukaan lengkap (10 cm). Proses ini terbagi dalam 2
fase, yaitu :
a) Fase laten berlangsung 8 jam, serviks membuka sampai 3 cm.
45
b) Fase aktif berlangsung selama 7 jam, serviks membuka dari 4
cm sampai 10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering, dibagi
dalam 3 fase yaitu:
(1) Fase akselerasi dalam 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4
cm.
(2) Fase dilatasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan
berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm.
(3) Fase deselerasi pembukaan menjadi lambat sekali, dalam
waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap.
Fase diatas terjadi pada primigravida ataupun
multigravida, tetapi pada multigravida memiliki jangka waktu
yang lebih pendek. Pada multigravida kala I berlangsung ± 8
jam, sedangkan pada primigravida ± 12 jam.
2) Kala II
Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.
Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam
pada multi. Pada kala pengeluaran janin telah turun masuk ruang
panggul sehingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul
yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan, karena
tekanan pada rectum ibu merasa seperti mau buang air besar
dengan tanda anus membuka. Pada waktu his kepala janin mulai
kelihatan, vulva membuka, perinium membuka, perinium
meregang. Dengan adanya his ibu dan dipimpin untuk
mengejan, maka lahir kepala diikuti oleh seluruh badan janin.
46
Gejala utama kala II adalah sebagai berikut:
a) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit, dengan
durasi 30 sampai 50 detik.
b) Menjelang akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai dengan
pengeluaran cairan secara mendadak.
c) Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti
keinginan mengejan akibat tertekannya pleksus
frankenhauser.
d) Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala
bayi sehingga terjadi:
(1) Kepala membuka pintu
(2) Subocciput bertindak sebagai hipomoglion, kemudian
secara berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung
dan muka, serta kepala seluruhnya.
e) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar,
yaitu penyesuaian kepala pada punggung.
f) Setelah putaran paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi
ditolong dengan cara:
(1) Kepala dipegang pada oscciput dan dibawah dagu,
kemudian ditarik dengan menggunakan cunam kebawah
untuk melahirkan bahu depan dan ke atas untuk
melahirkan bahu belakang.
(2) Setelah kedua bahu lahir, ketiak dikait untuk melahirkan
sisa badan bayi.
47
(3) Bayi lahir diikuti oleh sisa air ketuban.
g) Lamanya kala II untuk multigravida 1,5-2 jam dan
primigravida 1,5-1 jam.
3) Kala III
Kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya
plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Proses
lepasnya plasenta dapat diperkirakan dengan mempertahankan
tanda-tanda dibawah ini.
a) Uterus menjadi bundar
b) Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen
bawah rahim
c) Tali pusat bertambah panjang.
d) Terjadi semburan darah tiba-tiba.
Manajemen aktif kala III adalah sebagai berikut :
(1) Pemberian suntikan okstitoksin dalam 1 menit pertama
setelah bayi lahir
(2) Melakukan penengangan tali pusat terkendali (PTT)
(3) Massase Fundus Uteri
Pengeluaran selaput ketuban. Selaput janin biasanya
lahir dengan mudah, namun kadang-kadang masih ada
bagian plasenta yang tertinggal. Bagian tertinggal tersebut
dapat dikeluarkan dengan cara:
(a) Menarik pelan-pelan
(b) Memutar atau memilinnya seperti tali
48
(c) Memutar klem
(d) Menual atau digital.
Plasenta dan selaput ketuban harus diperiksa secara
teliti setelah dilahirkan. Apakah setiap bagian plasenta
lengkap atau tidak lengkap. Bagian plasenta yang
diperiksa yaitu permukaan maternal yang pada
normalnya memiliki 6-20 kotiledon, permukaan fetal,
dan apakah terdapat tanda-tanda plasenta suksenturia.
Jika plasenta tidak lengkap, maka disebut ada sisa
plasenta. Keadaan ini dapat menyebabkan perdarahan
yang banyak dan infeksi.
Kala III terdiri dari dua fase, yaitu:
a) Fase pelepasan plasenta
Beberapa cara pelepasan plasenta antara lain:
(1) Schultze
Proses lepasnya plasenta seperti menutup
payung. Cara ini merupakan cara yang paling
sering terjadi (80%). Bagian yang lepas terlebih
dulu adalah bagian tengah, lalu terjadi retro
plasental hematoma yang menolak plasenta mula-
mula bagian tengah, kemudian selanjutnya.
Menurut cara ini, perdarahan biasanya tidak ada
sebelum plasenta lahir dan berjumlah banyak
setelah plasenta lahir.
49
(2) Duncan
Berbeda dengan sebelumnya, pada cara ini
lepasnya plasenta mulai dari pinggir 20%. Darah
akan mengalir keluar antara selaput ketuban.
Pengeluarannya juga serempak dari tengah dan
pinggir plasenta.
b) Fase pengeluaran plasenta
Perasat-perasat untuk mengetahui lepasnya plasenta
adalah:
(1) Kustner
Meletakkan tangan disertai tekanan diatas
simfisis, tali pusat diregangkan, maka bila tali
pusat masuk berarti belum lepas. Jika diam atau
maju berarti sudah lepas.
(2) Klein
Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Bila
tali pusat kembali berarti belum lepas
(3) Strassman
Tegangkan tali pusaat dan ketok pada fundus,
bila tali pusat bergetar berarti plasenta belum lepas.
Tanda-tanda plasenta lepas adalah rahim menonjol
diatas simpisis, tali pusat bertambah panjang,
50
rahim bundar dan keras, serta keluar darah secara
tiba-tiba.
4) Kala IV
Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post
partum. Kala ini terutama bertujuan untuk melakukan observasi
karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam
pertama. Darah yang keluar selama perdarahan harus ditakar
sebaik-baiknya. Kehilangan darah pada persalinan biasanya
disebabkan oleh luka pada saat pelepasan plasenta dan robekan
pada serviks dan perinium. Rata-rata jumlah perdarahan yang
dikatakan normal adalah 250 cc, biasanya 100-300 cc. Jika
perdarahan lebih 500 cc, maka dianggap tidak normal, dengan
demikian harus dicari penyebabnya. Penting untuk diingat jangan
meninggalkan wanita bersalin 1 jam sesudah bayi dan plasenta
lahir. Sebelum pergi meninggalkan ibu yang baru melahirkan,
periksa ulang terlebih dahulu dan perhatikan 7 pokok penting
berikut :
a) Kontraksi rahim baik atau tidaknya diketahui dengan
pemeriksaan palpasi. Jika perlu lakukan massase dan berikan
uterotonika, seperti methergin, atau erimetrin dan oksitosin.
b) Perdarahan ada atau tidak
c) Kandung kemih harus kosong, jika penuh, ibu dianjurkan
berkemih dan kalau tidak bisa, lakukan kateter.
d) Luka-luka jahitannya baik atau tidak, ada perdarahan atau
tidak.
51
e) Plasenta dan selaput ketuban harus lengkap.
f) Keadaan umum ibu, tekanan darah, nadi, pernapasan dan
masalah lain.
g) Bayi dalam keadaan baik.
d. Tanda dan gejala persalinan
Tanda dan gejala persalinan menurut (Rukiah, 2009) :
1) Tanda-tanda permulaan persalinan:
a) Lightening
Lightening yaitu kepala turun memasuki pintu atas
panggul terutama pada primigravida. Perut kelihatan lebih
melebar, fundus uteri menurun, perasaan sering kencing atau
susah kencing karena kandung kemih tertekan oleh bagian
terbawah janin.
b) Fase labor
Fase labor adalah perasaan sakit diperut dan pinggang
oleh adanya kontraksi lemah dari uterus.
c) Bloody show
Serviks menjadi lembek, mulai mendatar dan sekresinya
bertambah bisa bercampur darah.
e. Tanda-tanda persalinan
Menurut (Jenny, 2013), terdapat beberapa teori yang
berkaitan dengan mulai terjadinya kekuatan his sehingga menjadi
awal mula terjadinya proses persalinan, walaupun hingga kini
belum dapat diketehui dengan pasti penyebab terjadinya persalinan.
52
1) Teori penurunan progesteron
Kadar hormon akan mulai menurun pada kira-kira 1-2
minggu sebelum persalinan dimulai. Terjadinya kontraksi otot
polos uterus pada persalinan akan menyebabkan rasa nyeri
yang hebat yang belum diketahui secara pasti penyebabnya,
tetapi terdapat beberapa kemungkinan, yaitu :
a) Hipoksia pada miometrium yang sedang berkontraksi.
b) Adanya penekanan ganglia saraf serviks pada uterus bagian
bawah otot-otot yang saling bertautan.
c) Peregangan serviks pada saat dilatasi atau pendataran
serviks, yaitu pemendekan saluran serviks dari panjang
sekitar 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan
tepi hampir setipis kertas.
d) Peritonium yang berada diatas fundus mengalami
peregangan.
2) Teori keregangan
Ukuran uterus yang makin membesar dan mengalami
penegangan akan mengakibatkan otot-otot uterus mengalami
iskemia sehingga mungkin dapat menjadi faktor yang dapat
mengganggu sirkulasi uterroplasenta yang pada akhirnya
membuat plasenta mengalami degenerasi. Ketika uterus
berkontraksi dan menimbulkan tekanan pada selaput ketuban,
tekanan hidrostatik kantong amnion akan melebarkan saluran
serviks.
53
3) Teori oksitosin interna
Hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin.
Adanya perubahan keseimbangan antara estrogen dan
progesteron dapat mengubah tingkat sensitivitas otot rahim
dan akan mengakibatkan terjadinya kontraksi uterus yang
disebut Braxton hicks. Penurunan kadar progesteron karena
usia kehamilan yang sudah tua akan mengakibatkan aktivitas
oksitosin meningkat.
Beberapa tanda-tanda dimulainya proses persalinan adalah
sebagai berikut :
a) Terjadinya his persalinan
Sifat his persalinan adalah :
(1) Pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan
(2) Sifatnya teratur, interval makin pendek dan kekuatan
makin besar.
(3) Makin beraktivitas (jalan), kekuatan akan makin
bertambah.
b) Pengeluaran lendir dan darah
Terjadinya his persalinan mengakibatkan terjadinya
perubahan pada serviks yang akan menimbulkan :
(1) Pendataran dan pembukaan
(2) Pembukaan menyebabkan lendir yang terdapat pada
kanalis servikalis lepas.
(3) Terjadinya perdarahan karena kapiler pembuluh darah
pecah.
54
c) Pengeluaran cairan
Pada beberapa kasus persalinan akan terjadi pecah
ketuban. Sebagian besar, keadaan ini terjadi menjelang
pembukaan lengkap.
d) Hasil-hasil yang didapat pada pemeriksaan dalam
Perlunakan serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks.
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
Menurut (Jenny, 2013), adapun faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi proses persalinan adalah penumpang (passanger),
jalan lahir (passage), kekuatan (power), posisi ibu (positioning),
dan respon psikologis (psychology response). Masing-masing dari
faktor tersebut dapat dijelaskan berikut ini :
1) Penumpang (passanger)
Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta.
Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai janin adalah ukuran
kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin.
Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam plasenta adalah
letak, besar dan luasnya.
2) Jalan lahir (passage)
Jalan lahir terbagi atas dua, yaitu jalan lahr keras dan jalan
lahir lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalan lahir
keras adalah ukuran dan bentuk tulang panggul, sedangkan
yang perlu diperhatikan dari jalan lahir lunak adalah segmen
bawah uterus yang dapat meregang, serviks, otot dasar
panggul, vagina dan introitus vagina.
55
3) Kekuatan (power)
Faktor kekuatan dalam persalinan dibagi dua yaitu :
a) Kekuatan primer (kontraksi involunter)
Kontraksi yang berasal dari segmen atas uterus yang
menebal dan dihantarkan ke uterus bawah dalam bentuk
gelombang. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan
kontraksi involunter ini antara lain frekuensi, durasi, dan
inensitas kontraksi. Kekuatan primer ini mengakibatkan
serviks menipis dan berdilatasi sehingga janin turun.
b) Kekuatan sekunder (kontraksi volunter)
Pada kekuatan ini, otot-otot diafragma dan abdomen
ibu berkontraksi dan mendorong keluar isi ke jalan lahir
sehingga menimbulkan tekanan intra abdomen. Tekanan ini
menekan uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan
dalam mendorong keluar. Kekuatan sekunder tidak
mempengaruhi dilatasi serviks lengkap, kekuatan ini cukup
penting dalam usaha untuk mendorong keluar dari uterus
dan vagina.
5) Posisi ibu (positioning)
Posisi ibu dapat memengaruhi adaptasi anatomi dan
fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang diberikan pada ibu
bertujuan untuk menghilangkan rasa letih, memberi rasa
nyaman dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak (contoh posisi
berdiri, berjalan, duduk dan jongkok) memberi sejumlah
56
keuntungan, salah satunya adalah memungkinkan gaya
gravitasi membantu penurunan janin. Selain itu, posisi ini
dianggap dapat mengurangi kejadian penekanan tali pusat.
6) Respon psikologi (psychology response)
Dapat dipengaruhi oleh :
a) Dukungan ayah bayi/pasangan selama proses persalinan
b) Dukungan kakek-nenek (saudara dekat) selama persalinan
c) Saudara kandung selama persalinan.
g. Penatalaksaan dalam proses persalinan
Menurut (Jenny, 2013), langkah asuhan persalinan normal
Melihat tanda dan gejala kala dua :
1) Melihat tanda gejala kala II/ persalinan, meliputi ada dorongan
meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva
membuka.
2) Menyiapkan dan memastikan kelengkapan alat partus dan
obat-obatan essential, meliputi bak instrument yang berisi 3
pasang sarung tangan steril, ½ kocker, gunting tali pusat, spuit
3 cc, klem tali pusat, benang tali pusat, kassa. Obat-obatan
yaitu oksitosin 10 IU, methergin, lidocain, betadin. Hecting set
yang berisi jarum kulit dan jarum otot, benang, pinset antomis,
pinset cyrugis, gunting. Perlengkapan ibu yaitu pakaian ibu,
kain, pembalut, celana dalam, gurita ibu dan lain-lain.
Perlengkapan bayi yaitu baju bayi, bedong, topi bayi, bedong,
topi bayi. Perlengkapan alat pelindung dari alat pelindung diri
57
untuk bidan meliputi celemek, masker, kacamata, sepatu boot
dan topi.
3) Memakai celemek
4) Melepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai,
mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir,
kemudian keringkan tangan dengan handuk yang bersih dan
kering
5) Memakai sarung tangan disinvektan tingkat tinggi pada tangan
yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6) Memasukaan oksitosin kedalam tabung suntik (gunakan
tangan yang memakai sarung tangan disinvektan tingkat tinggi
atau steril) pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik.
7) Membersihkan vulva dan perinium dengan hati-hati, dari
depan kebelakang dengan kapas atau kassa yang dibasahi air
disinvektan tingkat tinggi.
8) Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan
lengkap.
9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan
tangan kedalam larutan klorin 0,5% kemudian lepaskan dan
rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5%
selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan air mengalir
setelah sarung tangan dilepaskan.
58
10) Memeriksa detak jantung janin setelah kontraksi atau saat
uterus relaksasi untuk memastikan bahwa detak jantung janin
dalam batas normal (120-160x/menit).
11) Memberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan
janin baik, serta bantu ibu dalam menemukan posisi yang
nyaman dan sesuai dengan keinginannya.
12) Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi
meneran
13) Melakukan bimbingan meneran pada saat ibu ada dorongan
kuat untuk meneran
14) Menganjurkan ibu untuk istirahat yaitu dengan minuman atau
makanan pada saat tidak ada kontraksi/his.
15) Menganjurkan ibu untuk mengambil posisi yang nyaman,
jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran.
16) Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di atas
perut ibu, jika kepala bayi sudah terlihat diameter 5 cm
didepan vulva.
17) Melakukan kai bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah
bokong ibu
18) Membuka tutup partus set dan perhatikan kembali
kelengkapan alat dan bahan
19) Memakai sarung tangan disinvektan tingkat tinggi pada
kedua tangan
59
20) Melindungi perinium dengan satu tangan yang dilapisi
dengan kain bersih dan kering setelah tampak kepala bayi
dengan diameter 5-6 cm membuka vulva. Tangan yang lain
menahan kepala bayi untuk menahan posisi kepala bayi tetap
defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk
meneran perlahan atau bernafas cepat dari dangkal saat 1/3
bagian kepala bayi telah keluar dari vagina.
21) Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil
tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan
proses kelahiran bayi.
22) Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara
spontan.
23) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar pegang secara
biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan
lembut gerakan kepala kebawah dan disertai hingga bahu
depan muncul dibawah arcus pubis dan kemudian gerakan
kearah atas dan disertai untuk melahirkan bahu belakang.
24) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan atas kearah perinium
ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah.
Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan
dan siku sebelah atas.
25) Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas
berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang
kedua mata kaki (masukkan telunjuk di antara kaki kemudian
60
pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari
lainnya).
26) Menilai bayi dengan cepat, kemudian letakkan bayi diatas
perut ibu
27) Mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka, kepala dan
bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa
membersihkan verniks. Ganti handuk bersih dengan
handuk/kain yang kering. Biarkan bayi diatas perut ibu..
28) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada
lagi bayi kedua dalam uterus
29) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar
uterus berkontraksi baik dan mempercepat keluarnya
plasenta
30) Menyuntikan oksitosin 10 unit IM (intra muskuler) di 1/3
paha atas bagian distal leteral (lakukan aspirasi sebelum
menyuntikan oksitosin)
31) Menjepit tali puast dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat
bayi. Mendorong isi tali pusat kearah distal (ibu) dan
jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem
pertama
32) Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi),
dan lakukan pemotongan tali pusat diantara 2 klem
tersebut.
33) Mengikat tali pusat dengan benang tali pusat.
61
34) Meletakan bayi diatas perut ibu untuk inisiasi menyusu
dini dengan posisi kepala bayi di tengah-tengah
payudara, kepala menghadap kesalah satu payudara ibu,
kaki dan tangan seperti katak, kemudian selimuti bayi
dengan kain dan kepala bayi diberi topi sehingga dapat
mencegah bayi dari bahaya terjadinya hipotermi.
35) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10
cm dari vulva.
36) Meletakan satu tangan diatas kain perut ibu, pada tepi
atas simpisis, untuk mendeteksi adanya kontraksi.
Tangan yang lain memegang tali pusat.
37) Menegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan
yang lain mendorong uterus kearah belakang atas (dorso
kranial) secara hati-hati (untuk mencegah involusi uteri).
Pertahankan posisi tangan dorso kranial selama 30-40
detik.
38) Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial
hingga plasenta terlepas, minta ibu untuk meneran
sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar
lantai dan kemudian kearah atas mengikuti poros jalan
lahir (tetap lakukan dorso kranial).
39) Melahirkan plasenta, saat plasenta muncul di introtius
vagina. Pegang dan putar plasenta (searah jarum jam)
hingga selaput ketuban terpilin kemudian lahirkan dan
62
tempatkan plasenta pada tempat/wadah yang sudah
disediakan.
40) Melakukan massase uterus, letakkan telapak tangan di
fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar
dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba
keras).
41) Mematikan plasenta telah dilahirkan lengkap dengan
memeriksa kedua sisi plasenta.
42) Mengevaluasi kemungkinan terjadi laserasi pada vagina
dan perinium. Lakukan penjahitan jika terjadi laserasi
yang menyebabkan pendarahan.
43) Memastikan uterus berkontraksi baik atau keras dan
tidak terjadi pendarahan pada pervaginam
44) Mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin
0,5% dan keringkan menggunakan handuk.
45) Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap
15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan
setiap 30 menit selama 1 jam paca persalinan.
46) Mengajurkan ibu dan keluarga cara melakukan massase
uterus dan menilai kontraksi
47) Mengevaluasi jumlah darah
48) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi
bernafas dengan baik (40-60x/menit) serta suhu tubuh
normal (36,5-37,5 oC).
63
49) Menempatkasn semua peralatan bekas pakai dalam
larutan klorin 0,3% untuk mendekontaminasi (10 menit).
Cuci dan bilas peralatan yang telah didekontaminasi
50) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat
sampah yang sesuai
51) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinvektan
tingkat tinggi. Bersihkan sisa cairan, lendir dan darah.
Membantu ibu memakai pakaian yang lebih bersih dan
kering.
52) Memastikan ibu merasa nyaman dan bantu ibu
memberikan ASI . Anjurkan keluarga untuk memberi ibu
minuman dan makanan yang diinginkan.
53) Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin
0,5%
54) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan
klorin 0,5%, balikkan bagian dalam ke luar dan rendam
larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
55) Memakai kembali sarung tangan disinvektan tingkat
tinggi setelah 1 jam inisiasi menyusu dini selesai
56) Melakukan penimbangan /pengukuran bayi, beri tetes
mata antibiotik profilaksin, dan vitamin K 1mg intra
muskuler dipaha kiri anterolateral.
57) Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan
imunisasi hepatitis B dipaha kanan anterolateral.
64
58) Mencelupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin
0,5%, balikan bagian dalam keluar dan rendam larutan
klorin 0,5% selama 10 menit.
59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir
60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang)
periksa
h. Lima benang merah dalam asuhan kebidanan
Menurut JNPK – KR (2008), ada lima aspek dasar atau lima
benang merah, yang penting dan saling terkait dalam asuhan
persalinan yang bersih dan aman. Berbagai aspek tersebut
melekat pada setiap persalinan, baik normal maupun patologis.
Lima benang merah tersebut adalah :
1) Membuat keputusan klinik
Membuat keputusan merupakan proses yang menentukan
untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang
diperlukan oleh pasien. Keputusan itu harus akurat,
komprehensif dan aman, baik bagi pasien dan keluarganya
maupun petugas yang memberikan pertolongan. Tujuan
langkah dalam membuat keputusan klinik adalah sebagai
berikut:
a) Pengumpulan data utama yang relevan untuk membuat
keputusan.
b) Menginterpretasikan data dan mengidentifikasi masalah.
65
c) Membuat diagnosis atau menentukan masalah yang
terjadi atau dihadapi.
d) Menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk
mengatasi masalah.
e) Menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi
untuk solusi masalah.
f) Melaksanakan asuhan atau intervensi terpilih.
g) Memantau dan mengevaluasi efektifitas asuhan atau
intervensi.
2) Asuhan sayang ibu
Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai
budaya, kepercayaan dan keinginan sang ibu. Beberapa
prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan mengikut
sertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan
kelahiran bayi.
3) Pencegahan infeksi
Tindakan pencegahan infeksi tidak terpisah dari
komponen-komponen lain dalam asuhan selama persalinan
dan kelahiran bayi. Tindakan ini harus diterapkan dalam
setiap aspek asuhan untuk melindungi ibu, bayi baru lahir,
keluarga, penolong persalinan dan tenaga kesehatan lainnya
dengan mengurangi infeksi karena bakteri, virus dan jamur.
Dilakukan pula upaya untuk menurunkan resiko penularan
penyakit-penyakit berbahaya yang hingga kini belum
66
ditemukan pengobatannya, seperti hepatitis dan Human
Immunodeficiency Virus.
4) Pencatatan (dokumentasi)
Pencatatan adalah bagian penting dari proses membuat
keputusan klinik karena memungkinkan penolong persalinan
untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang diberikan
selama proses persalinan dan kelahiran bayi.
5) Rujukan
Rujukan adalah kondisi optimal dan tepat waktu ke
fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap, diharapkan
mampu menyelamatkan jiwa para ibu dan bayi baru lahir.
Sangat sulit untuk menduga kapan penyulit akan terjadi
sehingga kesiapan untuk merujuk ibu atau bayinya ke
fasilitas rujukan secara optimal dan tepat waktu (jika penyulit
terjadi) menjadi syarat bagi keberhasilan upaya
penyelamatan.
Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan rujukan
disingkat BAKSOKUDA yaitu :
B (Bidan) : Pastikan bahwa ibu dan/atau bayi baru lahir di
damping oleh penolong persalinan yang
kompeten untuk menatalaksana gawat darurat
obstetri dan bayi baru lahir untuk di bawa ke
fasilitas rujukan.
67
A (Alat) : Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk
asuhan persalinan, masa nifas dan bayi baru
lahir (tabung suntik, selang IV, alat resusitasi,
dll) bersama ibu ke tempat rujukan.
Perlengkapan dan bahan-bahan mungkin di
perlukan jika ibu melahirkan dalam perjalanan
menuju fasilitas rujukan.
K (Keluarga) : Beritahu ibu dan keluarga mengenai kondisi
terakhir ibu dan/ bayi dan mengapa ibu dan/
bayi perlu di rujuk. Jelaskan pada mereka
alasan dan tujuan merujuk ibu ke fasilitas
rujukan tersebut. Suami atau anggota keluarga
yang lain harus menemani ibu dan bayi baru
lahir hingg ke fasilitas rujukan.
S (Surat) : Berikan surat ke tempat rujukan. Surat ini
harus memberikan identifikasi mengenai ibu
dan/ bayi baru lahir, cantumkan alasan rujukan
dan uraian hasil pemeriksaan, asuhan atau
obat-obatan yang di terima ibu dan/ bayi baru
lahir. Sertakan juga pertograf yang di pakai
untuk membuat keputusan klinik.
O (Obat) : Bawa obat-obatan esensial pada saat
mengantar ibu ke fasilitas rujukan. Obat-
68
obatan tersebut mungkin di perlukan selama di
perjalanan.
K (Kendaraan) : Siapkan kendaraan yang paling
memungkinkan untuk merujuk ibu dalam
kondisi cukup nyaman. Selain itu, pastikan
kondisi kendaraan cukup baik untuk mencapai
tujuan pada waktu yang tepat.
U (Uang) : Ingatkan pada keluarga agar membawa uang
dalam jumlah yang cukup untuk membeli
obat-obatan yang di perlukan dan bahan-bahan
kesehatan lain yang di perlukan selama ibu
dan/ bayi baru lahir tinggal di fasilitas rujukan.
DA (Darah) : Menyiapkan keluarga atau tetangga yang
mempunyai golongan darah sama ke palang
merah Indonesia minimal 24 jam sebelum
pasien lahir untuk mempersiapkan pasien
apabila memerlukan transfusi darah.
i. Resiko jika pasien kambuh dalam proses persalinan
Menurut Sulistyawati (2009), bila seseorang yang terkena
tuberculosis paru kambuh pada saat bersalin pada ibu akan terjadi
sesak napas, batuk-batuk dan lemas. Dan yang akan terjadi pada
janin fetal distres karena asupan oksigen ibu ke janin berkurang.
Menurut Najoan Nan Warouw (2007), masa Persalinan
Pasien yang sudah cukup mendapat pengobatan selama kehamilan
69
biasanya masuk kedalam persalinan dengan proses tuberkulosis
yang sudah tenang. Persalinan pada wanita yang tidak mendapat
pengobatan dan tidak aktif lagi, dapat berlangsung seperti biasa,
akan tetapi pada mereka yang masih aktif, penderita ditempatkan
dikamar bersalin tertentu ( tidak banyak digunakan penderita
lain). Persalinan ditolong dengan kala II dipercepat misalnya
dengan tindakan ekstraksi vakum atau forsep, dan sedapat
mungkin penderita tidak mengedan, diberi masker untuk
menutupi mulut dan hidungnya agar tidak terjadi penyebaran
kuman ke sekitarnya. Sedapat mungkin persalinan berlangsung
pervaginam. Sedangkan sectio caesarea hanya dilakukan atas
indikasi obstetrik dan tidak atas indikasi tuberkulosis paru.
j. Laserasi jalan lahir
Menurut JNPK – KR (2008) laserasi diklasifikasikan
berdasarkan luasnya robekan yaitu :
1) Derajat satu dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perinium.
2) Derajat dua dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perinium dan otot perinium.
3) Derajat tiga dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perinium dan otot perinium dan otot sfingter ani.
4) Derajat empat dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit
perinium dan otot perinium dan otot sfingter ani dan dinding
dengan rektum.
70
C. Teori Nifas
2. Pengertian Nifas
a. Definisi
Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir
ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil
yang berlangsung kira-kira 6 minggu (Nanny Lia Dewi, 2013)
b. Fisiologis Nifas
Menurut (Marmi, 2014), masa nifas dibagi menjadi tiga tahapan
yaitu:
1) Puerperium dini
Suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri
dan berjalan-jalan.
2) Puerperium intermedial
Suatu masa kepulihan menyeluruh dari organ-organ reproduksi
selama kurang lebih enam sampai delapan minggu.
3) Remote puerperium
Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam
keadaan sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau
waktu persalinan mengalami komplikasi.
c. Tanda bahaya masa nifas
Menurut (Nanny Lia Dewi, 2013) :
1) Pendarahan pervaginam
Perdarahan post partum paling sering diartikan sebagai
keadaan kehilangan darah lebih dari 500 ml selama 24 jam
71
pertama sesudah kelahiran bayi. Perdarahan post partum adalah
merupakan penyebab penting kehilangan darah serius yang
paling sering dijumpai dibagian obstetrik. Sebagai penyebab
langsung kematian ibu, perdarahan post partum merupakan
penyebab sekitar keseluruhan kematian akibat perdarahan
obstetrik yang diakibatkan oleh perdarahan post partum.
Perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah
bersalin didefinisikan sebagai perdarahan. Terdapat beberapa
masalah mengenai definisi ini :
a) Perkiraan kehilangan darah biasanya tidak sebanyak yang
sebenarnya, kadang-kadang hanya setengah dari biasanya.
Darah tersebut bercampur dengan cairan amnion atau dengan
urine, darah juga tersebar pada spon, handuk dan kain
didalam ember dan dilantai.
b) Volume darah yang hilang juga bervariasi akibatnya sesuai
dengan kadar hemoglobin seorang ibu. Seorang ibu dengan
kadar hemoglobin normal akan dapat menyesuaikan diri
terhadap kehilangan darah yang akan berakibat fatal pada
anemia. Seorang ibu yang sehat dan tidak anemi pun dapat
mengalami akibat fatal dari kehilangan darah.
c) Perdarahan dapat terjadi dengan lambat dengan waktu
beberapa jam dan kondisi ini dapat tidak dikenali sampai
terjadi syok.
72
Penilaian resiko pada saat antenatal tidak dapat
memperkirakan akan terjadinya perdarahan pasca persalinan.
Penanganan aktif kala III sebaiknya dilakukan pada semua
wanita yang bersalin karena hal ini dapat menurunkan insiden
perdarahan pasca persalinan akibat atonia uteri. Semua ibu
pasca bersalin harus dipantau dengan ketat untuk
mendiagnosis perdarahan pasca persalinan.
2) Infeksi masa nifas
Beberapa bakteri dapat menyebabkan infeksi setelah
persalinan. Infeksi masa nifas masih merupakan penyebab
tertinggi angka kematian ibu. Infeksi alat genetalia merupakan
komplikasi masa nifas. Infeksi yang meluas ke saluran urine,
payudara dan pembedahan merupakan penyebab terjadinya
angka kematian ibu tinggi. Gejala umum infeksi dapat berupa
uterus lembek, kemerahan, dan rasa nyeri pada payudara.
3) Infeksi alat genital
Ibu beresiko terjadi infeksi post partum karena adanya luka
pada bekas pelepasan plasenta, laserasi pada saluran genital
termasuk episiotomi pada perineum, dinding vagina dan serviks,
infeksi post seksio caesar kemungkinan yang terjadi. Infeksi
masa nifas atau sepsis peurperalis adalah infeksi pada traktus
genetalia yang terjadi pada setiap saat antara awitan pecah
ketuban (ruptur membrani) atau persalinan dan 42 hari setelah
persalinan atau abortus, dimana terdapat dua atau lebih dari hal-
73
hal berikut nyeri pelvik, demam 38.5 derajat celcius atau lebih,
rabas vagina yang abnormal, rabas vagina yang berbau busuk
dan bakteri hambatan dalam kecepatan penurunan uterus.
4) Sakit kepala, nyeri epigastrik, penglihatan kabur
Wanita yang baru melahirkan sering mengeluh sakit kepala
hebat atau penglihatan kabur.
Penanganan :
a) Jika ibu sadar periksa nadi, tekanan darah dan pernafasan
b) Jika ibu tidak bernafas periksa lakukan ventilasi dengan
masker dan balon, lakukan, intubasi jika perlu dan jika
pernafasan dangkal periksa dan bebaskan jalan nafas dan beri
oksigen 4-6 liter/menit.
c) Jika pasien tidak sadar atau koma bebaskan jalan nafas,
baringkan pada sisi kiri, ukuran suhu, periksa apakah ada
kaku tengkuk.
5) Pembengkakan di wajah atau ekstremitas
Periksa adanya varises, periksa kemerahan pada betis,
periksa apakah tulang kering, pergelangan kaki, kaki oedema.
6) Demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih
Pada masa nifas dini, sensitivitas kandung kemih terhadap
tegangan air kemih didalam vesika sering menurun akibat
trauma persalinan serta analgesia epidural atau spinal sensasi
peregangan kandung kemih juga mungkin berkurang akibat rasa
74
tidak nyaman yang ditimbulkan oleh episiotomi yang lebar,
laserasi uretra atau hematom dinding vagina.
7) Rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di kaki
(Thrombopeblitis).
Selama masa nifas, dapat terbentuk thrombus sementara
pada vena manapun dipelvis yang mengalami dilatasi dan
mungkin lebih sering mengalaminya. Faktor predisposisi :
a) Obesitas
b) Peningakatan umur maternal dan tingginya paritas
c) Riwayat sebelumnya mendukung
d) Anastesi dan pembedahan dengan kemungkinan trauma yang
lama pada keadaan pembuluh vena
e) Anemia maternal
f) Hipotermi atau penyakit jantung
g) Endometritis
h) Varicostitis
i) Manifestasi, Timbul secara takut, timbul rasa nyeri akibat
terbakar, nyeri tekan permukaan.
Penatalaksanaan masa nifas menurut (Saifudin, 2009) :
Tabel 2.2. Penatalaksanaan Masa Nifas
Kunjungan Waktu Tujuan
1 6-8 jam
setelah
persalinan
Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri
Mendeteksi dan merawat penyebab lain
perdarahan rujuk bila perdarahan
berlanjut
Memberikan konseling pada ibu atau
75
salah satu anggota keluarga bagaimana
mencegah perdarahan masa nifas
karena atonia uteri
Pemberian ASI awal
Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir
Menjaga bayi tetap sehat dengan cara
mencegah hipotermia
Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu
dan bayi lahr 2 jam pertama setelah
lahir atau sampai ibu dan bayi dalam
keadaan stabil.
2 6 hari
setelah
persalinan
Memastikan involusi uteri berjalan
normal, uterus berkontraksi
Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal
Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istiraahat.
Memastikan ibu menyusui dengan baik
dan tak memperlihatkan tanda-tanda
penyulit.
Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat,
menjaga bayi tetap hangat dan merawat
bayi sehari-hari.
3 2 minggu
setelah
persalinan
Sama seperti diatas (6 hari setelah
persalinan)
4 6 minggu
setelah
persalinan
Menanyakan pada ibu tentang penyulit-
penyulit yang ia atau bayi alami
Memberikan konseling untuk memakai keluarga berencana atau berKB secara
dini.
Tujuan asuhan masa nifas (Nanny Lia Dewi, 2013)
a) Mendeteteksi adanya perdarahan masa nifas tujuan untuk
menghindarkan adanya kemungkinan perdarahan post partum
dan infeksi.
76
b) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun
psiologis.
c) Melaksanakan skrining secara komperhensif dengan
mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi
komplikasi pada ibu maupun bayinya.
d) Memberikan pendidikan kesehatan diri, nutrisi, keluarga
berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya,
dan perawatan bayi sehat.
e) Memberikan pendidikan mengenai laktasi dan perawatan
payudara yaitu menjaga payudara tetap bersih dan kering serta
menggunakan bra yang menyokong payudara.
d. Tuberculosis dalam Nifas
Menurut Najoan Nan Warouw (2007), masa Nifas Penelitian
terdahulu menyatakan bahwa pengaruh kehamilan terhadap
tuberkulosis paru justru menonjol pada masa nifas. Hal tersebut
mungkin karena faktor hormonal, trauma waktu melahirkan,
kesibukan ibu dengan bayinya dll. Tetapi masa nifas saat ini tidak
selalu berpengaruh asal persalinan berjalan lancar, tanpa
perdarahan banyak dan infeksi. Cegah terjadinya perdarahan
pospartum seperti pada pasien-pasien lain pada umumnya. Setelah
penderita melahirkan, penderita dirawat diruang observasi selama
6-8 jam, kemudian penderita dapat dipulangkan langsung. Diberi
obat uterotonika, dan obat TB paru diteruskan, serta nasihat
perawatan masa nifas yang harus mereka lakukan. Penderita yang
tidak mungkin dipulangkan, harus dirawat di ruang isolasi.
77
D. Teori Bayi Baru Lahir
1. Pengertian bayi baru lahir
a. Definisi
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia
kehamilan 37 – 42 minggu dan berat badannya 2.500 – 4.000 gram
( Dewi, 2013).
Bayi baru lahir normal adalah bayi lahir pada usia kehamilan
37 – 42 minggu dengan berat lahir antara 2.500 – 4.000 gram
(Sondakh, 2013).
b. Kriteria bayi baru lahir normal
Menurut Sondakh (2013) kriteria bayi yang normal berukuran
Berat badan 2500-4000 gram, Panjang badan 48-52 cm, Lingkar
kepala 33-35 cm, Lingkar dada 31-33 cm.Bunyi jantung dalam satu
menit pertama ± 180 kali/menit, kemudian turun sampai 140-120
kali/menit pada saat bayi berumur 30 menit, Pernafasan cepat pada
menit-menit pertama kira-kira 80 kali/menit disertai pernafasan
cuping hidung, retraksi suprasternal dan interkostar, serta rintihan
hanya berlangsung 10-15 menit, Kulit kemerahan dan licin karena
jaringan subkutan cukup terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa,
Rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik, Kuku
agak panjang dan lemas, Genetalia testis sudah turun ke skrotum
(pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora
(pada bayi perempuan), Reflek hisap, menelan dan moro telah
terbentuk, Eliminasi urin dan mekonium normalnya keluar pada 24
78
jam pertama, mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan
dan lengket.
c. Tanda – tanda bayi baru lahir
Bayi baru lahir dikatakan normal jika mempunyai beberapa
tanda antara lain : Appearance (warna kulit), seluruh tubuh
kemerahan, Pulse (heart rate) atau frekuensi jantung > 100 x/menit,
Grimace (reaksi terhadap rangsangan), Menangis, batuk/bersin,
Activity (tonus otot), Gerakan aktif, Respiration (usaha nafas), bayi
menangis kuat (Mochtar, 2014).
d. Asuhan segera pada bayi baru lahir
Menurut Sondakh (2013), Jika bayi menangis atau pernafasan
saat bayi lahir, fasilitas ibu menyusui dini dan selanjutnya rawat
gabung bayi dengan ibu. Lalu lakukan perawatan segera pada bayi
baru lahir normal.
1) Setelah pengeringan, menggantikan handuk basah dengan handuk
kering.
2) Klem, potong tali pusat dengan dua ikatan.
3) Periksa pernafasan dan warna kulit setiap 5 menit, setelah 5 menit
lakukan penilaian umum bayi menggunakan skor APGAR.
4) Pastikan bahwa ruangan hangat untuk mencegah hipotermia,
tarulah bayi.
e. Perawatan bayi baru lahir
Disamping perawatan umum dan khusus untuk masalah bayi,
berikan perawatan umum dan perawatan lanjut.
79
1) Buat perencanaan perawatan umum yang meliputi kebutuhan bayi.
2) Pantau kemajuan – kemajuan bayi dengan melakukan penilaian
umum terus menerus tanpa terlalu mengganggu bayi yaitu
Frekuensi nafas. Denyut jantung. Warna kulit. Suhu tubuh.
Kecepatan dan volume cairan IV. Frekuensi dan volume pemberian
minum.
3) Siap dengan perubahan perencanaan perawatan bila terjadi
perubahan kondisi bayi yang ditentukan oleh hasil pemantauan
khusus dan minum.
4) Bayi ditimbang berat badannya, diukur panjang badan lahirnya dan
dicatat.
5) Perawatan mata bayi yaitu dengan sibersihkan kemudian diberikan
obat untuk mencegah blenorea :
a) Metode Crede dengan tetesan nitras argenti 1-2 % sebanyak 1
tetes pada masing-masing mata.
b) Salep penisilin atau salem mata gentamisin.
6) Diperiksa anus, genetalia eksterna dan jenis kelamin bayi
7) Jika pemeriksaan normal maka bayi sudah diperbolehkan untuk
diberikan kepada ibu dan keluarga.
f. Inisiasi menyusu dini
Inisiasi menyusu dini adalah meletakkan bayi baru lahir
tengkurap didada ibunya setelah tubuh bayi dikeringkan dengan kain
bersih (kecuali pada bagian tangan bayi), kontak kulit – ke – kulit,
bagian punggung bayi ditutup dengan selimut, kepala bayi boleh
80
diberi topi (untuk mencegah hipotermia), dan bayi akan mencari
puting ibunya dalam waktu satu jam setelah lahir (Astuti, 2015).
Inisiasi menyusu dini memberikan banyak keuntungan baik bagi
ibu dan bayi. Bagi ibu dapat mengurangi perdarahan dengan adanya
kontraksi uterus saat bayi menyusu dan saat bayi merangkak mencari
putting ibu (breast crawl) (Astuti, 2015).
g. Tuberculosis pada bayi baru lahir
Menurut Najoan Nan Warouw (2007), pencegahan pada bayi :
1. Jangan pisahkan anak anak dari ibunya, kecuali ibu sakit sangat
parah,
2. Apabila ibu dahak negatif, segera bayi diberikan BCG,
3. Apabila dahak sediaan langsung ibu positif selama kehamilan, atau
tetap demikian saat melahirkan :
a) Bila bayi tampak sakit saat dilahirkan dan anda mencurigai
adanya tuberkulosis kongenital berilah pengobatan anti TB yang
lengkap.
b) Bila anak tampak sehat, berikanlah isoniazid 5 mg/kgbb dalam
dosis tunggal setiap hari selama 2 bulan. Kemudian lakukan tes
tuberkulin. Jika negatif, hentikan isoniazid dan berikan BCG.
Jika positif, lanjutkan isoniazid selama 4 bulan lagi. Jangan
berikan BCG pada saat diberikan isoniazid atau jangan lakukan
tes tuberkulin dan berikan isoniazid selama 6 bulan. Di banyak
negara adalah paling aman bagi ibu untuk menyusui bayinya.
Air Susu Ibu (ASI) merupakan gizi yang paling tinggi mutunya
bagi bayi.
81
E. Tinjauan Teori Asuhan Kebidanan
1. Asuhan kebidanan varney
a. Langkah
Pengumpulan data dasar
Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang
akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi
klien.Pengkajian data wanita hamil terdiri atas anamnesa, pemeriksaan
fisik, dan pemeriksaan
b. Konsep dasar management kebidanan
Pengertian
Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka
pikir yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan
secara sistematis, mulai dari mengumpulkan datan, menganalisis data,
menegakan diagnosis kebidanan, menyusun rencana asuhan,
melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan
rencana asuhan, dan mendokumentasikan asuhan (Teori Praktik
Kebidanan 2008).
2. Manajemen kebidanan dengan metode VARNEY
Proses manajemen kebidanan terdiri dari tujuh langkah yang
berurutan dan setiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses
dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi.
Ketujuh langkah tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang dapat
diaplikasikan dalam situasi apapun. Langkah-langkah tersebut adalah
sebagai berikut.
82
Langkah 1 : Pengumpulan Data Dasar / Pengkajian
Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data
yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap.
Data dasar ini meliputi :
a. Data subyektif
1) Biodata pasien
a) Nama
Selain sebagai identitas, upayakan agar bidan memanggil
dengan nama panggilan sehingga hubungan komunikasi antara
bidan dan pasien menjadi lebih akrab.
b) Umur
Data ini ditanyakan untuk menentukan apakah ibu didalam
persalinan beresiko karena usia atau tidak.
c) Agama
Sebagai dasar bidan dalam memberikan dukungan mental dan
spriritual terhadap pasien dan keluarga sebelum dan pada saat
kelahiran.
d) Pendidikan
Tingkat pendidikan ini akan sangat mempengaruhi daya
tangkap dan tanggap pasien terhadap instruksi yang diberikan
bidan pada proses persalinan.
e) Pekerjaan
Data ini menggambarkan tingkat social ekonomi, pola
sosialisasi dan data pendukung dalam menentukan pola
komunikasi yang akan dipilih selama asuhan.
83
f) Suku bangsa
Data ini berhubungan dengan social budaya yang dianut oleh
pasien dan keluarga yang berkaitan dengan persalinan.
g) Alamat
Data ini memberi gambaran mengenai jarak dan waktu yang
ditempuh pasien menuju lokasi persalinan.
h) Biodata suami
Nama dimaksudkan untuk lebih mengenal dan untuk
membedakan dengan pasangan lainnya, umur ditulis untuk
mengetahui perbedaan usia dengan istrinya.
2) Riwayat pasien
a) Keluhan utama
Ditanyakan untuk mengetahui alasan pasien datang ke fasilitas
pelayanan kesehatan.
b) Riwayat kebidanan
Ditanyakan untuk memprediksi jalannya proses persalinan dan
untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan penyulit selama
proses persalinan.
c) Riwayat kehamilan seseorang
Yang perlu dikaji adalah riwayat antenatal care, imunisasi
tetanus toxoid dan kebutuhan selama kehamilan.
84
d) Riwayat haid
Data ini secara tidak langsung memang berhubungan dengan
masa persalinan, namun dari data yang kita peroleh kita akan
mempunyai gambaran tentang keadaan dasar dari organ
reproduksi, dari riwayat haid ini kita dapat mengetahui pertama
haid terakhirnya.
e) Riwayat kesehatan
Dasar dari riwayat kesehatan ini dapat kita gunakan sebagai
‘’warning” akan adanya penyulit saat persalinan. Beberapa data
penting tentang riwayat kesehatan pasien yang perlu kita ketahui
adalah apakah pasien pernah atau sedang menderita penyakit
seperti jantung, diabetes mellitus, ginjal, hypertensi, hipotensi,
hepatitis atau anemia.
f) Pola kebutuhan sehari-hari :
1) Pola nutrisi
Data ini penting untuk diketahui agar bisa mendapatkan
gambaran bagaimana pasien mencukupi asupan gizi selama
hamil dengan masa awal persalinan.
2) Pola eliminasi
Dikaji untuk mengetahui apakah ada gangguan dalam
defekasi dan miksi.
3) Pola istirahat
Istirahat sangat diperlukan oleh pasien untuk
mempersiapkan energi menghadapi proses persalinannya.
85
4) Pola personal
Ditanyakan karena sangat berkaitan dengan kenyamanan
pasien dalam menjalani proses persalinan.
5) Pola seksual
Dikaji untuk mengetahui aktifitas seksual ibu, apakah ada
keluhan atau tidak.
6) Data perkawinan
Data ini penting untuk kita kaji karena dari data ini kita
akan mendapatkan gambaran mengenai suasana rumah tangga
pasangan serta kepastian mengenai siapa yang mendampingi
persalinan.
7) Keadaan sosial budaya
Data ini ditanyakan untuk mengetahui keadaan psikososial
pasien, apakah ibu merasa cemas atau tidak, karena keadaan
psikologis ibu sangat berpengaruh pada proses persalinan.
8) Data pengetahuan
Dikaji untuk pengetahuan atau kepahaman ibu tentang
persalinan.
b. Data obyektif
Data ini dikumpulkan melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi
dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan secara berurutan.
86
1) Keadaan umum
Dasar ini didapatkan dengan mengamati keadaan pasien secara
keseluruhan, hasil pengamatan yang dilaporkan kriterianya adalah
baik dan lemah.
2) Kesadaran
Untuk mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, kita
dapat melakukan pengkajian derajat kesadaran pasien dari keadaan
komposmentis sampai dengan koma.
3) Tanda vital
Pengukuran tanda tanda vital meliputi tekanan darah yang
normalnya dibawah 130/90 mmHg, temperatur normalnya 36-37 C,
deyut nadi normalnya 55-90 x/menit.
4) Pengukuran tinggi badan
Untuk mengetahui tingkat kesehatan klien apakah mempunyai
berat badan yang normal atau klien mengalami gizi buruk.
5) Berat Badan
Pada wanita hamil, terjadi penambahan berat badan. Perkiraan
peningkatan berat badan yang dianjurkan 4 kg pada kehamilan
trimester I, 0,5 kg/minggu pada kehamilan trimester II sampai III
totalnya sekitar 15-16 kg.
6) Leher
Bisa dilihat dan diperiksa apakah ada pembesaran kelenjar
tiroid dan vena jugularis atau tidak.
87
7) Dada dan aksila
a) Dada dilihat apakah kedua paru bergerak bersamaan bernafas,
pada paru apakah terdapat suara nafas.
b) Payudara biasa dilihat dan diperiksa ukuran, bentuk, warna kulit,
dan puting susu, apakah ada benjolan atau tidak, sakit atau tidak.
c) Aksila biasa dilihat dan diraba apakah ada benjolan atau tidak,
sakit atau tidak.
d) Abdomen bisa dilihat untuk mengetahui keadaan abdomen,
perlu diperhatikan juga apakah ada strie gravidarum.
8) Anggota gerak
Mengetahui keadaan tangan dan kaki, apakah pucat atau tidak,
ada varises atau tidak dan oedem atau tidak.
9) Genetalia
Genetalia eksterna dilihat labia mayora, labia minor, genetalia
internal dilihat ada tidaknya oedem.
10) Pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan persalinan meliputi
pemeriksaan leopold untuk menentukan letak janin, pengukuran
tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, frekuensi dan lamanya
kontraksi, auskultasi dengan mengecek detak jantung janin, dan
pemeriksaan dalam yaitu keadaan portio, effacement, pembukaan,
selaput ketuban, bagian terendah, titik penunjuk, penurunan, dan
bagian terkemuka.
88
11) Pemeriksaan laboratorium meliputi kadar haemogoblin, haematokrit,
golongan darah, hepatitis b, dan kadar leukosit, serta pemeriksaan
urin.
Langkah 2 : Interpretasi Data Dasar / identifikasi diagnosis dan masalah
Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap
didiagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi
yang benar atas dasar data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang
sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau
diagnosis yang spesifik. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang
ditegakkan oleh profesi (bidan) dalam lingkup praktik kebidanan dan
memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan.
Langkah 3 : Diagnosa Potensial
Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lain berdasarkan
masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi. Langkah ini
membutuhkan antisipasi, bila memungkinan dilakukan pencegahan, sambil
mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila
diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Melakukan asuhan
yang aman penting sekali dalam hal ini. Tujuan dari langkah ketiga ini
adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul.
Langkah 4 : Antisipasi Penanganan Segera
Mengidentisifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter
dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim
kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.
Langkah 5 : Intervensi
89
Pada langkah ini dilakukan perencenaan yang menyeluruh, ditentukan
langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan
manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau
diantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap
dapat dilengkapi.
Langkah 6 : Implementasi
Langkah ini, rencana asuhan yang menyeluruh di langkah kelima
harus dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa
dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan
sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya.
Langkah 7 : Evaluasi
Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang
sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah
benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah
diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis.
3. Manajemen kebidanan dengan metode SOAP
Dalam metode SOAP, S adalah data subyektif, O adalah data obyektif,
A adalah Analysis/Assesment, dan P adalah Planning merupakan catatan
yang bersifat sederhana, jelas, logis, dan singkat. Prinsip dari metode
SOAP ini merupakan proses pemikiran penatalaksanaan manajemen
kebidanan.
a. Data Subyektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang
pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang
dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan
90
langsung dengan diagnosa. Data subyektif ini nantinya akan
menguatkan diagnosis yang akan disusun.
b. Data Obyektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur,
hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan
diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluar atau orang lain
dapat dimasukkan dalam data obyektif ini sebagai data penunjang. Data
ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang
berhubungan dengan diagnosis.
c. Analysis/Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan
interpretasi (kesimpulan) dari data subyektif dan data obyektif. Karena
keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan
ditemukan informasi baru dalam data subyektif maupun data obyektif,
maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga
menuntut bidan untuk melakukan analisis data yang dinamis tersebut
dalam rangka mengikuti perkembangan data pasien. Analisis data
adalah melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan, mencakup
: diagnosis atau masalah potensial serta perlunya antisipasi
diagnosa/masalah potensial dan tindakan segera.
d. Planning / perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan
yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis
dan interpretasi data.
4. Landasan hukum kewenangan bidan
Menurut Permenkes RI NO.28 Tahun 2017 Tentang Izin
Penyelenggaraan Praktik Bidan.
91
Pasal 15
(1) Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau
bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) Praktik Kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Praktik Mandiri Bidan.
(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
(1) klinik
(2) puskesmas
(3) rumah sakit dan/atau
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
Pasal 18
Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki
kewenangan untuk memberikan :
a. pelayanan kesehatan ibu
b. pelayanan kesehatan anak, dan
c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Pasal 19
(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan,
masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan :
(a) konseling pada masa sebelum hamil
92
(b) antenatal pada kehamilan normal
(c) persalinan normal
(d) ibu menyusui, dan
(e) konseling pada masa antara dua kehamilan.
(3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:
(a) episiotomi
(b) pertolongan persalinan normal
(c) penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
(d) penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
(e) pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil
(f) pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
(g) fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air susu ibu
eksklusif
(h) pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan post
partum
(i) penyuluhan dan konseling
(j) bimbingan pada kelompok ibu hamil, dan
(k) pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.
Pasal 20
(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak
prasekolah.
93
(2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:
(a) pelayanan neonatal esensial.
(b) penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan.
(c) pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak
prasekolah.
(d) konseling dan penyuluhan.
94
BAB III
TINJAUAN KASUS
ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. R
UMUR 33 TAHUN G3 P2 A0 DI PUSKESMAS TARUB
KABUPATEN TEGAL
(Study Kasus Faktor Risiko dengan Riwayat Tuberculosis paru)
A. Asuhan Kebidanan pada Kehamilan
1. Pengkajian Data
Tanggal : 21 Agustus 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subyektif
Dari hasil anamnesa yang telah dilakukan didapatkan data Ny. R umur 33
tahun, Suku Bangsa jawa, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT,
Suami bernama Tn. W umur 33 tahun, Agama islam, Suku Bangsa jawa,
Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat di desa Bulakwaru RT 10/
RW 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
1) Alasan datang
Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dan ingin
mengetahui keadaan ibu dan janinnya.
2) Keluhan utama
Ibu mengatakan tenggorokan panas
95
3) Riwayat Obstetri dan ginekologi
a) Riwayat Kehamilan, persalinan, nifas yang lalu
Ibu mengatakan persalinan pertama dengan umur kehamilan 36
minggu, BB 3100 gram, jenis persalinan spontan, penolong
persalinan Bidan, dengan nifas normal. Keadaan anak saat ini
hidup, sekarang berumur 10 tahun dan jenis kelaminnya laki-
laki, persalinan yang kedua dengan kehamilan 36 minggu, BB
3200 gram, jenis persalinan spontan, penolong persalinan Bidan,
dengan nifas normal. Keadaan sekarang berumur 4 tahun dan
jenis kelaminnya laki-laki.
b) Riwayat kehamilan sekarang
Kehamilan ini merupakan kehamilan ketiga dan tidak pernah
mengalami keguguran, antenatal care (ANC) pertama kali di
Puskesmas, tanggal 20 januari 2018 ibu dengan keluhan
terlambat haid dan timbul tanda-tanda hamil seperti mual dan
pusing, sering miksi dan dilakukan test kehamilan dengan hasil
positif, dan umur kehamilan 9 minggu. Ny. R sudah melakukan
pemeriksaan kehamilan baik di dr. SpOg maupun di puskesmas.
Pada trimester I ibu melakukan pemeriksaan 2x di puskesmas,
trimester II 4x di puskesmas, trimester III sebanyak 5x, 4x di
puskesmas 1x di BPM dan 1x di dr SpOg, selama hamil ibu
mengkonsumsi tablet tambah darah kurang lebih 80 tablet, ibu
sudah mendapatkan imunisasi TT I pada tanggal 21 agustus
2018. keluhan trimester I mual muntah dan pusing. Terapi yang
96
di berikan metokloramide 3x1 (untuk meredakan mual) tablet Fe
1x1 (vitamin penambah darah). trimester II pusing pilek dan
pegal. Terapi yang di berikan sangovitin IxI (vitamin penambah
darah) vit C IxI.
c) Riwayat haid
Ibu mengatakan pertama kali menstruasi (menarche) pada usia
12 tahun, siklus 28 hari, lamanya 6 hari, banyaknya 3 kali ganti
pembalut dalam sehari, dan tidak merasakan nyeri baik sebelum
atau sesudah mendapatkan menstruasi, Hari Pertama Haid
Terakhir (HPHT) 16 november 2017. Serta ibu mengalami
keputihan selama 3 hari, tidak gatal, warnanya jernih, bau khas.
d) Riwayat Penggunaan Kontrasepsi
Ibu mengatakan menggunakan KB pil, lamanya 1 tahun, tidak
ada keluhan, alasan lepas anjuran dari dokter karena sedang
mengkonsumsi obat TB, rencana yang akan datang Kb suntik 3
bulan, alasan praktis.
4) Riwayat kesehatan
a) Penyakit yang pernah di derita
Ibu mengatakan pernah menderita penyakit tuberculosis paru
pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 ibu sudah dinyatakan
sembuh total oleh dokter spesialis paru, ibu tidak pernah
mengalami gejala mual muntah, BAK yang berwarna kuning
keruh seperti teh, mual, demam, pembesaran hati, nyeri ulu
hati, kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning (Hepatitis),
97
diare tidak sembuh-sembuh, demam, batuk yang
berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan tubuh
menurun, sariawan di bagian mulut atas dan mulut bawah yang
tak kunjung sembuh Human Immunodeficiency Virus (HIV),
gatal pada genetalia, keputihan yang berbau busuk, berwarna
hijau Infeksi Menular Seksual (IMS), Penyakit Keturunan
seperti mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu Diabetes
Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing,
tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak nafas saat udara
dingin dan banyak debu, pernafasan berbunyi mengik
(Asma), nyeri dada bagian atas, jantung berdebar-debar, sesak
nafas, dan mudah lelah (Jantung).
b) Kesehatan ibu sekarang
Ibu mengatakan pernah menderita penyakit infeksi Tuberculosis
(TBC) pada tahun 2016, namun pada tahun 2017, ibu sudah
dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis paru, ibu tidak
mengalami penyakit dengan gejala mual muntah, demam,
pembesaran hati, nyeri ulu hati, BAK yang berwarna kuning
keruh seperti teh, kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning
(Hepatitis), diare, demam, dan batuk yang berkepanjangan, berat
badan menurun drastis, kekebalan tubuh menurun, sariawan di
bagian mulut atas dan mulut bawah yang tak kunjung sembuh,
Human Immunodeficiency Virus (HIV), gatal pada genetalia,
98
keputihan yang berbau busuk,berwarna hijau Infeksi Menular
Seksual (IMS), Penyakit Keturunan seperti mudah lapar, mudah
haus, mudah mengantuk, sering kencing di malam hari, luka
yang sukar sembuh yaitu Diabetes Mellitus (DM), tekanan
darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing, tengkuk terasa pegal
(Hipertensi), sesak nafas saat udara dingin dan banyak debu,
pernafasan berbunyi mengik (Asma), nyeri dada bagian
atas,jantung berdebar-debar, sesak nafas, dan mudah lelah
(Jantung).
c) Riwayat Kesehatan Keluarga
Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita
penyakit infeksi seperti batuk lebih dari 2 minggu, disertai
darah, demam, menggigil pada malam hari, berat badan
menurun yaitu Tuberculosis (TBC), mual muntah, demam,
nyeri ulu hati, pembesaran hati, BAK yang berwarna kuning
keruh seperti teh, kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning
(Hepatitis), diare tidak sembuh-sembuh, demam, dan batuk
yang berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan
tubuh menurun, sariawan di bagian mulut atas dan bawah yang
tak kunjung sembuh, Human Immunodeficiency Virus (HIV),
gatal pada genetalia, keputihan yang berbau busuk,berwarna
hijau Infeksi Menular Seksual (IMS). Penyakit Keturunan
seperti mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu Diabetes
99
Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing
,tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak nafas saat udara dingin
dan banyak debu, pernafasan berbunyi mengik (Asma), nyeri
dada bagian atas,jantung berdebar-debar, sesak nafas, dan
mudah lelah (Jantung) .
Ibu mengatakan didalam keluarga tidak ada yang mempunyai
riwayat bayi kembar.
5) Kebiasaan
Ibu mengatakan selama hamil tidak ada pantangan makanan, tidak
pernah minum jamu, tidak pernah minum obat-obatan selain dari
tenaga kesehatan, tidak pernah minum-minuman keras, tidak
merokok sebelum dan selama hamil, serta tidak memelihara binatang
seperti ayam, kucing, anjing, burung, dan lain-lain.
6) Kebutuhan Sehari-hari
a) Pola nutrisi
Ibu mengatakan selama hamil frekuensi makan 3 kali/hari, porsi 1
porsi piring sedang, menu bervariasi seperti nasi, lauk dan sayur,
sedangkan frekuensi minum 6-7 kali/hari, terkadang minum air
putih dan air teh. Pola nutrisi sekarang frekuensi makan 2-3
kali/hari, porsi 1 porsi piring sedang, menu bervariasi seperti nasi,
lauk dan sayur, sedangkan frekuensi minum 6-8 kali/hari, minum
air putih dan susu.
100
b) Pola eliminasi
Selama hamil frekuensi buang air besar, 1-2 kali sehari, warna
kuning kecoklatan, konsistensi lunak, tidak ada gangguan, buang
air kecil sering, frekuensi 5-7 kali/hari, bau khas, warna kuning
jernih, dan tidak ada gangguan. Frekuensi buang air besar
sekarang 1-2 kali sehari, warna kecoklatan, konsistensi agak
keras, tidak ada gangguan. buang air kecil sering, frekuensi 6-8
kali/hari, bau khas, warna kuning jernih, dan tidak ada gangguan.
c) Pola istirahat
Pola istirahat sebelum hamil siang 1-2 jam malam 6-8 jam. Pola
istirahat selama hamil siang 1-2 jam malam 6-7 jam, tidak ada
gangguan.
d) Pola aktivitas
Pola aktivitas sebelum hamil sebagai ibu rumah tangga, biasa
mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak
menyuci, mengepel, Pola aktivitas selama hamil sebagai ibu
rumah tangga biasanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga
yang ringan seperti menyapu, memasak.
e) Pola personal hygiene
Pola mandi sebelum hamil 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok
gigi 2x, ganti baju 2x sehari. Pola mandi selama hamil 2x sehari,
keramas 2 hari sekal, gosok gigi 2x, ganti baju 2-3x sehari.
101
f) Pola seksual
Pola seksual sebelum hamil kalau suami pulang satu minggu 2x.
Pola seksual selama hamil kalau suami pulang satu minggu 1x.
7) Data Psikologi
Ibu mengatakan ini anak dari pernikahan yang sah, ibu merasa
senang, suami serta keluarga juga senang dengan kehamilannya saat
ini, dan ibu sudah siap untuk menjalani proses kehamilan ini sampai
proses kelahiran bayinya nanti.
8) Data sosial ekonomi
Ibu mengatakan penghasilan suaminya cukup untuk memenuhi
kebutuhannya sehari-hari, tanggung jawab perekonomianya di
tanggung oleh suami, dan pengambilan keputusan oleh bersama
(suami dan istri).
9) Data perkawinan
Ibu mengatakan status perkawinannya sah secara agama, ini adalah
perkawinan yang pertama dan lama perkawinanya sudah 11 tahun.
Usia saat pertama kali menikah pada umur 22 tahun.
10) Data spiritual
Ibu mengatakan rajin sholat, selalu berdoa untuk keluarga, ibu dan
janinnya.
11) Data sosial budaya
Ibu mengatakan tidak percaya dengan adat istiadat setempat seperti
selama hamil membawa gunting agar terhindar dari gangguan
makhluk halus.
102
12) Data pengetahuan ibu
Ibu mengatakan sudah mengetahui persiapan persalinan dan ibu
sudah mengetahui cara merawat bayi dan memandikan bayi.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Fisik
Dari hasil pemeriksaan yang telah di lakukan terdapat hasil
kesadaran composmetis, keadaan umum baik, tanda vital Tekanan
Darah 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit, Pernapasan 20 x/menit,
Suhu 36,5oC, Tinggi Badan 151 Cm, Berat Badan sebelum hamil
60 kg, sekarang 67 kg, kenaikan berat badan 7 kg, Lingkar Lengan
Atas (LILA) 27 cm.
Pada pemeriksaan status present dari kepala sampai kaki, kepala
mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, tidak berketombe, muka
tidak pucat dan tidak oedem, mata simetris, penglihatan baik,
konjungtiva tidak anemis, sclera tidak ikterik, hidung bersih, tidak
ada pembesaran polip, lendir tidak ada infeksi sinusitis, mulut dan
bibir lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada gigi, gusi
tidak epulis, bentuk telinga simetris, bersih, pendengaran baik, leher
tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan tidak ada pembesaran
vena jugularis. Aksila tidak ada pembesaran kelenjar limfe,
pernafasan teratur bentuk dada normal, tidak ada retraksi dinding
dada, mamae simetris, abdomen tidak ada luka bekas operasi,
genetalia kebersihan terjaga tidak ada varices, tidak oedem, tidak
103
ada kelenjar bartolini, anus tidak ada hemoroid, dan extremitas tidak
oedem, kuku tidak pucat dan tidak ada varices.
2) Pemeriksaan obstetri
a) Inspeksi
Muka terlihat tidak pucat, tidak oedem, tidak ada cloasma
gravidarum, mamae bentuk simetris, puting susu bersih,
hiperpigmentasi areola, tidak ada benjolan yang abnormal, tidak
ada bekas operasi pada payudara, kolostrum/ ASI sudah keluar,
abdomen normal, uterus membesar sesuai dengan umur
kehamilan, tidak ada garis linea nigra dan strie gravidarum.
Tidak ada luka bekas operasi, genetalia normal, tidak ada luka
bekas operasi, anus tidak hemoroid.
b) Palpasi
Leopold I tinggi fundus uterus (TFU) 3 jari di bawah processus
xifoideus, pada bagian atas perut ibu teraba bulat, Lunak, tidak
melenting (bokong janin), Leopold II bagian kanan perut ibu
teraba panjang ada tahanan (punggung janin) bagian kiri perut ibu
teraba kecil-kecil, (extremitas janin), Leopold III pada bagian
perut ibu teraba bulat, keras yaitu (kepala) dan kepala sudah tidak
bisa di goyangkan, Leopold IV bagian bawah perut ibu kepala
sudah masuk pintu atas panggul/divergen 4/5 bagian. TFU 33
cm, dan taksiran berat badan janin TBBJ 33 – 11 = 22 x 155 =
3.410 Gram, Hari Perkiraan Lahir HPL 23 Agustus 2018 dan
umur kehamilan 39 minggu + 6 hari.
104
c) Auskultasi
Denyut jantung janin (DJJ)/ regular 136 x/menit dan teratur.
d) Perkusi
Reflek patella kanan dan kiri (+) positif
e) Pemeriksaan panggul luar
Distansia spinarum, distansia klistarum, konjungata eksternal dan
lingkar panggul tidak dilakukan.
f) Pemeriksaan penunjang
Pada tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil haemoglobin 11,1 gr %,
protein urin (-), reduksi urin (-), golongan darah O, HBSAg (-)
Non Reaktif, HIV (-) Non Reaktif, dan Sypilis (-) Non Reaktif.
2. Interpretasi Data
a. Diagnosa (nomenklatur)
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka didapatkan diagnosa
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 39 minggu + 6 hari, hamil dengan
faktor risiko yaitu riwayat Tuberculosis.
1) Data subyektif
Ibu mengatakan Bernama Ny. R umur 33 tahun, ibu mengatakan ini
kehamilan ke tiga dan tidak pernah keguguran, hari pertama haid
terakhir ibu tanggal 16 november 2017.
2) Data obyektif
Keadaan umum baik, kesadaran composmetis, tanda vital tekanan
darah 110/70 mmHg, nadi 80 x/m, respirasi 20x/m, suhu tubuh
36,5oC, Leopold I Tinggi Fundus Uterus (TFU) 3 jari di bawah
105
processus xifoideus, pada bagian atas perut ibu teraba bulat. Lunak,
tidak melenting (bokong janin), Leopold II bagian kanan perut ibu
teraba panjang ada tahanan (punggung janin) bagian kiri perut ibu
teraba kecil-kecil (extremitas janin), Leopold III pada bagian perut
ibu teraba bulat, keras, yaitu (kepala) dan kepala sudah tidak bisa di
goyangkan, Leopold IV bagian bawah perut ibu kepala sudah masuk
pintu atas panggul/divergen 4/5 bagian. Tinggi Fundus Uterus (TFU)
33 cm, dan taksiran berat badan janin (TBBJ) 33 – 11 = 22 x 155 =
3.410 Gram.
b. Masalah
Dapat meningkatnya abortus, pre-eklampsi, serta sulitnya persalinan.
c. Kebutuhan
KIE mengenai TBC dalam kehamilan.
3. Diagnosa potensial
Bahaya pada kehamilan dapat menyebabkan Abortus, pre-eklampsia, sulitnya
persalinan.
Bahaya bagi ibu hamil dapat menyebabkan prematuritas, KMK (kecil untuk
masa kehamilan), BBLR (berat bayi lahir rendah).
4. Antisipasi penanganan segera
kolaborasi dengan dokter SpOg.
5. Intervensi
a. Beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan.
b. Anjurkan ibu untuk konsultasi dengan dokter
c. Anjurkan ibu untuk terus mengkonsumsi tablet Fe secara teratur.
106
d. Beritahu ibu cara mengkonsumsi tablet tambah darah.
e. Beri tahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.
f. Beritahu ibu dan keluarga untuk menjaga kebersihan rumah.
g. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
h. Beritahu pada ibu tentang persiapan persalinan.
i. Beritahu ibu tanda persalinan.
j. Anjurkan ibu untuk kunjungan ulang.
6. Implementasi
a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan.
Keadaan ibu dan janinnya saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan usia
kehamilan ibu.
b. Menganjurkan ibu untuk konsultasi dengan dokter kandungan untuk
mengetahui keadaan janin yang ada di perut ibu.
c. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi tablet Fe secara teratur untuk
mencegah terjadinya anemia pada kehamilan.
d. Memberitahu ibu cara mengkonsumsi tablet tambah darah yaitu dengan
menggunakan air putih atau air jeruk untuk mempercepat daya penyerapan
obat ke tubuh, di minum pada malam hari untuk mengurangi efek samping
obat.
e. Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berkalori,
berprotein tinggi seperti yang mengandung karbohidrat (padi, singkong,
gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan dan
lain-lain), protein hewani (susu, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, dan
lain lain), mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak (daging).
107
f. Memberitahu ibu dan keluarga untuk membersihkan rumah yaitu dengan
cara menyapu setiap hari, membuka jendela di pagi hari berguna supaya
udara tetap segar di dalam rumah, membuang sampah pada tempatnya.
g. Menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
h. Memberitahu ibu untuk mempersiapkan persiapan persalinan seperti baju
ibu , baju bayi, kain kurang lebih 4 lembar,dll.
i. Memberitahu ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-kenceng semakin
sering, keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah bercampur lendir
dari jalan lahir.
j. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu dan jika
ibu ada keluhan atau muncul tanda-tanda persalinan segera datang ke
tenaga kesehatan terdekat
7. Evaluasi
a. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang telah di lakukan.
b. Ibu bersedia melakukan konsultasi dengan dokter
c. Ibu bersedia untuk mengkonsumsi tablet Fe secara teratur.
d. Ibu sudah mengerti cara mengkonsumsi tablet tambah darah yang benar.
e. Ibu sudah mengerti untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.
f. Ibu dan keluarga sudah mengerti cara menjaga kebersihan rumah.
g. Bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
h. Ibu sudah mempersiapkan persiapan persalinan.
i. Ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalinan.
j. Ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang.
108
DATA PERKEMBANGAN KE 1
(ANC KUNJUNGAN KE-2)
Tanggal : 23 Agustus 2018
Jam : 16.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bernama Ny. R umur 33 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan
yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran, ibu mengatakan kenceng-
kenceng.
1) Kebutuhan sehari-hari
a) Pola nutrisi
Ibu mengatakan selama nifas makan sehari 3x/hari, porsi 1 piring
sedang, menu bervariasi seperti nasi, lauk, dan sayur, sedangkan
frekuensi minum 6-7 kali /hari, macamnya air putih dan kadang-kadang
teh,
b) Pola eliminasi
Selama nifas frekuensi buang air besar 1-2 kali sehari, warna kuning
kecoklatan, konsistensi lembek, tidak ada gangguan. Buang air kecil
frekuensi 6-8 kali/hari, bau khas, warna kuning jernih, dan tidak ada
gangguan.
c) Pola istirahat
ibu mengatakan istirahat siang 1-2 jam, dan malam 6-7 jam.
109
d) Pola aktivitas
Ny. R sebagai ibu rumah tangga biasa mengerjakan pekerjaan rumah
seperti menyapu dan memasak.
e) Pola personal hygiene
Ibu mandi sehari 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2 kali
sehari, ganti baju 2-3 kali.
f) Pola seksual
Ibu mengatakan belum melakukannya.
b. Data Obyektif
Dari hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, terdapat hasil keadaan baik,
Kesadaran composmetis, Tekanan Darah 100/70 mmHg, Nadi 80 x/menit,
Pernafasan 20 x/menit, Suhu tubuh 36,5oC, konjungtiva merah muda, muka
tidak pucat dan tidak oedem, penglihatan baik. hidung bersih, mulut dan bibir
lembab, tidak ada stomatitis, leher tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan
tidak ada pembesaran vena jugularis. Mamae bentuk simetris puting susu
bersih, hyperpigmentasi areola, tidak ada benjolan yang abnormal,
kolostrum/ASI sudah keluar, pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan.
Leopold I tinggi fundus uterus (TFU) 3 jari di bawah processus xifoideus, pada
bagian atas perut ibu teraba bulat, lunak, tidak melenting (bokong janin),
Leopold II bagian kanan perut ibu teraba panjang ada tahanan (punggung
janin) bagian kiri perut ibu teraba kecil-kecil, (extremitas janin), Leopold III
pada bagian perut ibu teraba bulat, keras, yaitu (kepala) dan kepala sudah tidak
bisa di goyangkan, Leopold IV bagian bawah perut ibu kepala sudah masuk
pintu atas panggul/divergen 4/5 bagian. Tinggi Fundus Uterus (TFU) 33 cm,
110
dan taksiran berat badan janin (TBBJ) 33 – 11 = 22 x 155 = 3.410 Gram,
extremitas tidak oedem dan tidak ada varises, serta tidak ada tanda-tanda
homan.
c. Assesment
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu, janin tunggal, hidup intra
uterin, letak memanjang, punggung kanan, presentasi kepala, divergen dengan
faktor risiko pada kehamilan Riwayat Tuberculosis Paru.
d. Penatalaksanaan
1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
TD normal, DJJ normal, Gerakan janin aktif
Keadaan ibu dan janin Baik
Evaluasi : ibu sudah tahu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, kondisi
ibu dan janin dalam keadaan baik.
2. Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berkalori,
berprotein tinggi seperti yang mengandung karbohidrat (padi, singkong,
gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan dan
lain-lain), protein hewani (susu, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, dan
lain lain), mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak (daging)
lebih dari porsi biasa.
Evaluasi : ibu bersedia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.
3. Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
Evaluasi : ibu bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan berat.
111
4. Mengajari ibu untuk memacu kontraksi secara alami dengan cara jalan-jalan
pada pagi hari/sore hari, atau dengan cara memainkan puting susu.
Evaluasi : ibu sudah mengerti cara memacu kontraksi.
5. Mengingatkan kembali pada ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-
kenceng semakin sering keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah
bercampur lendir dari jalan lahir.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalilnan.
6. Menganjurkan ibu untuk memilih tempat persalinan.
Evaluasi : ibu mengatakan ingin bersalin di puskesmas tarub.
7. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi/ jika ada
keluhan serta jika muncul tanda-tanda persalinan segera menghubungi
tenaga kesehatan terdekat.
Evaluasi : ibu sudah mengerti
112
DATA PERKEMBANGAN KE 2
(ANC KUNJUNGAN KE-3)
Tanggal : 24 Agustus 2018
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bernama Ny. R umur 33 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan
yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran, ibu mengatakan kenceng-
kenceng.
1) Kebutuhan sehari-hari
a) Pola nutrisi
Ibu mengatakan selama nifas makan sehari 3x/hari, porsi 1 piring sedang,
menu bervariasi seperti nasi, lauk, dan sayur, sedangkan frekuensi
minum 6-7 kali /hari, macamnya air putih dan kadang-kadang teh,
b) Pola eliminasi
Selama nifas frekuensi buang air besar 1-2 kali sehari, warna kuning
kecoklatan, konsistensi lembek, tidak ada gangguan. Buang air kecil
frekuensi 6-8 kali/hari, bau khas, warna kuning jernih, dan tidak ada
gangguan.
c) Pola istirahat
ibu mengatakan istirahat siang 1-2 jam, dan malam 6-7 jam.
113
d) Pola aktivitas
Ny. R sebagai ibu rumah tangga biasa mengerjakan pekerjaan rumah
seperti menyapu dan memasak.
e) Pola personal hygiene
Ibu mandi sehari 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2 kali
sehari, ganti baju 2-3 kali.
f) Pola seksual
Ibu mengatakan belum melakukannya.
b. Data Obyektif
Dari hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, terdapat hasil keadaan baik,
Kesadaran composmetis, Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit,
Pernafasan 20 x/menit, Suhu tubuh 36,7oC, konjungtiva merah muda, muka
tidak pucat dan tidak oedem, penglihatan baik. hidung bersih, mulut dan bibir
lembab, tidak ada stomatitis, leher tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan
tidak ada pembesaran vena jugularis. Mamae bentuk simetris puting susu
bersih, hyperpigmentasi areola, tidak ada benjolan yang abnormal,
kolostrum/ASI sudah keluar, pembesaran uterus sesuai dengan usia
kehamilan. Leopold I tinggi fundus uterus (TFU) 3 jari di bawah processus
xifoideus, pada bagian atas perut ibu teraba bulat, lunak, tidak melenting
(bokong janin), Leopold II bagian kanan perut ibu teraba panjang ada tahanan
(punggung janin) bagian kiri perut ibu teraba kecil-kecil (extremitas janin),
Leopold III pada bagian perut ibu teraba bulat, keras, yaitu (kepala) dan
kepala sudah tidak bisa di goyangkan, Leopold IV bagian bawah perut ibu
kepala sudah masuk pintu atas panggul/divergen 4/5 bagian. Tinggi Fundus
114
Uterus (TFU) 33 cm, dan Taksiran Berat Badan Janin (TBBJ) 33 – 11 = 22 x
155 = 3.410 Gram, extremitas tidak oedem dan tidak ada varises, serta tidak
ada tanda-tanda human.
c. Assesment
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu+1 hari, janin tunggal, hidup
intra uterin, letak memanjang, punggung kanan, presentasi kepala, divergen
dengan faktor risiko pada kehamilan Riwayat Tuberculosis Paru.
d. Penatalaksanaan
1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
TD normal, DJJ normal, Gerakan janin aktif
Keadaan ibu dan janin Baik
Evaluasi : ibu sudah tahu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, kondisi
ibu dan janin dalam keadaan baik.
2. 2. Menganjurkan ibu untuk melakukan menemuai dokter SpOg dan
melakukan USG untuk mengetahui kondisi ibu dan janin
Evaluasi : ibu bersedia dan mau melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
Evaluasi : ibu bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan berat.
4. Mengajari ibu kembali untuk memacu kontraksi secara alami dengan cara
jalan-jalan pada pagi hari/sore hari, atau dengan cara memainkan puting
susu.
Evaluasi : ibu sudah mengerti cara memacu kontraksi.
115
5. Mengingatkan kembali pada ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-
kenceng semakin sering keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah
bercampur lendir dari jalan lahir.
Evaluasi : ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalilnan.
6. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi/ jika
ada keluhan serta jika muncul tanda-tanda persalinan segera menghubungi
tenaga kesehatan terdekat.
Evaluasi : ibu sudah mengerti
116
ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN PADA NY. R DI PUSKESMAS
TARUB KABUPATEN TEGAL
B. Asuhan kebidanan pada persalinan
1. Pengkajian Data
Tanggal : 25 agustus 2018
Jam : 10.20 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subyektif
1) Biodata
Dari hasil anamnesa yang telah dilakukan di dapatkan data Ny.
R, Berumur 33 tahun, Agama islam, Suku Bangsa jawa,
Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Suami
Ny. R Bernama Tn. W Umur 33 tahun, Suku Bangsa Jawa,
Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta. Alamat di
desa Bulakwaru Rt 10 Rw 02 Kecamatan Tarub Kabupaten
Tegal.
2) Alasan Datang
Ny. R mengatakan ingin melahirkan
3) Keluhan Utama
Ibu mengatakan kenceng-kenceng semakin sering sejak jam
23.00 WIB (24/08/2018).
117
4) Riwayat obstetrik dan ginekologi
a) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas tahun lalu
Ibu mengatakan persalinan pertama dengan umur
kehamilan 36 minggu, BB 3100 gram, jenis persalinan
spontan, penolong persalinan Bidan, dengan nifas normal.
Keadaan anak saat ini hidup, sekarang berumur 10 tahun
dan jenis kelaminnya laki-laki. Persalinan yang kedua
dengan kehamilan 36 minggu, BB 3200 gram, jenis
persalinan spontan, penolong persalinan Bidan, dengan
nifas normal, Keadaan sekarang berumur 4 tahun dan jenis
kelaminnya laki-laki.
b) Riwayat kehamilan sekarang
Kehamilan ini merupakan kehamilan ketiga dan tidak
pernah mengalami keguguran, antenatal care (ANC)
pertama kali di Puskesmas, tanggal 20 januari 2018 ibu
dengan keluhan terlambat haid dan timbul tanda-tanda
hamil seperti mual dan pusing, sering miksi dan dilakukan
test kehamilan dengan hasil positif, dan umur kehamilan 9
minggu. Ny. R sudah melakukan pemeriksaan kehamilan
baik di dr. SpOg maupun di puskesmas. Pada trimester I
ibu melakukan pemeriksaan 2x di puskesmas, trimester II
4x di puskesmas, trimester III sebanyak 5x, 4x di
puskesmas 1x di BPM dan 1x di dr SpOg, selama hamil
118
ibu mengkonsumsi tablet tambah darah kurang lebih 80
tablet, ibu sudah mendapatkan imunisasi TT I pada
tanggal 21 agustus 2018. keluhan trimester I mual muntah
dan pusing. Terapi yang di berikan metokloramide 3x1
(untuk meredakan mual) tablet Fe 1x1 (vitamin penambah
darah). trimester II pusing pilek dan pegal. Terapi yang di
berikan sangovitin IxI (vitamin penambah darah) vit C IxI.
c) Riwayat haid
Ibu mengatakan pertama kali menstruasi (menarche) pada
usia 12 tahun, siklus 28 hari, lamanya 6 hari, banyaknya 3
kali ganti pembalut dalam sehari, dan tidak merasakan
nyeri baik sebelum atau sesudah mendapatkan menstruasi,
Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) 16 november 2017.
Serta ibu mengalami keputihan selama 3 hari, tidak gatal,
warnanya jernih, bau khas.
d) Riwayat Penggunaan Kontrasepsi
Ibu mengatakan menggunakan KB pil, lamanya 1 tahun,
tidak ada keluhan, alasan lepas anjuran dari dokter karena
sedang mengkonsumsi obat Tb, rencana yang akan datang
Kb suntik 3 bulan, alasan praktis.
5) Riwayat kesehatan
a) Penyakit yang pernah di derita
Ibu mengatakan pernah menderita penyakit infeksi yaitu
tuberculosis paru pada tahun 2016, namun pada tahun
119
2017 ibu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis
paru, ibu tidak pernah mengalami gejala mual muntah,
BAK yang berwarna kuning keruh seperti teh, mual,
demam, pembesaran hati, nyeri ulu hati, kulit tubuh
dan sclera mata berwarna kuning (Hepatitis), diare tidak
sembuh-sembuh, demam, batuk yang berkepanjangan,
berat badan menurun drastis, kekebalan tubuh menurun,
sariawan di bagian mulut atas dan mulut bawah yang tak
kunjung sembuh Human Immunodeficiency Virus (HIV),
gatal pada genetalia, keputihan yang berbau busuk,
berwarna hijau Infeksi Menular Seksual (IMS), Penyakit
Keturunan seperti mudah lapar, mudah haus, mudah
mengantuk, sering kencing di malam hari, luka yang
sukar sembuh yaitu Diabetes Mellitus (DM), tekanan
darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing, tengkuk terasa
pegal (Hipertensi), sesak nafas saat udara dingin dan
banyak debu, pernafasan berbunyi mengik (Asma),
nyeri dada bagian atas, jantung berdebar-debar, sesak
nafas, dan mudah lelah (Jantung)
Ibu mengatakan tidak pernah mengalami
kecelakaan/trauma dan ibu mengatakan tidak pernah
memiliki riwayat penyakit yang di operasi seperti mioma,
kista, dan kanker serviks.
120
b) Kesehatan ibu sekarang
Ibu mengatakan penyakit ibu tidak mengalami penyakit
dengan gejala mual muntah, demam, pembesaran hati,
nyeri ulu hati, BAK yang berwarna kuning keruh seperti
teh, kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning
(Hepatitis), diare, demam, dan batuk yang
berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan
tubuh menurun, sariawan di bagian mulut atas dan mulut
bawah yang tak kunjung sembuh Human
Immunodeficiency Virus (HIV), gatal pada genetalia,
keputihan yang berbau busuk,berwarna hijau Infeksi
Menular Seksual (IMS), Penyakit Keturunan seperti
mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu
Diabetes Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg, pusing, tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak
nafas saat udara dingin dan banyak debu, pernafasan
berbunyi mengik (Asma), nyeri dada bagian atas, jantung
berdebar-debar, sesak nafas, dan mudah lelah (Jantung) .
c) Riwayat Kesehatan Keluarga
Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita
penyakit infeksi seperti batuk lebih dari 2
121
minggu, disertai darah, demam, menggigil pada malam
hari, berat badan menurun yaitu Tuberculosis (TBC),
mual muntah, demam, nyeri ulu hati, pembesaran hati,
BAK yang berwarna kuning keruh seperti teh, kulit
tubuh dan sclera mata berwarna kuning (Hepatitis), diare
tidak sembuh-sembuh, demam, dan batuk yang
berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan
tubuh menurun, sariawan di bagian mulut atas dan mulut
bawah yang tak kunjung sembuh, Human
Immunodeficiency Virus (HIV), gatal pada genetalia,
keputihan yang berbau busuk, berwarna hijau Infeksi
Menular Seksual (IMS). Penyakit Keturunan seperti :
mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu
Diabetes Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg, pusing, tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak
nafas saat udara dingin dan banyak debu, pernafasan
berbunyi mengik (Asma), nyeri dada bagian atas, jantung
berdebar-debar, sesak nafas, dan mudah lelah (Jantung) .
Ibu mengatakan didalam keluarga tidak ada yang
mempunyai riwayat bayi kembar.
6) Kebiasaan
Ibu mengatakan selama hamil tidak ada pantangan makanan
apapun, tidak pernah mengkonsumsi jamu, tidak pernah
122
mengkonsumsi obat-obatan selain dari tenaga kesehatan, tidak
pernah mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok sebelum
dan selama hamil, di rumah ibu tidak memelihara binatang
seperti kucing, anjing,burung, dan lain-lain.
7) Kebutuhan Sehari-hari
a) Pola Nutrisi
Ibu mengatakan waktu hamil frekuensi makan 2-3 kali/hari,
porsi 1 piring sedang, menu bervariasi seperti nasi, lauk dan
sayur, sedangkan frekuensi minum 6-7 kali/hari, macamnya
air putih, air susu. Pola nutrisi sekarang frekuensi Makan 1
kali pada jam 06.00 wib porsi 1 piring sedang, menu seperti
nasi, telor, dan tempe goreng, tidak ada makan dipantang,
sedangkan frekuensi minum 2 gelas terakhir minum jam
06.10 wib, minum air putih, air susu.
b) Pola Eliminasi
Ibu mengatakan frekuensi Buang Air Besar (BAB), selama
hamil 1-2 kali sehari, warna, kecoklatan, konsistensi keras,
tidak ada ganguan. Buang air kecil (BAK) sering, frekuensi
5-7 kali/hari, bau khas, warna kuning jernih, dan tidak ada
ganguan. BAB terakhir jam 06.30 wib, tidak ada ganguan.
Ibu BAK sekali, terakhir jam 10.30 wib, bau khas, warna
kuning jernih, tidak ada gangguan.
123
c) Pola istirahat
Ibu mengatakan pola istirahat selama hamil siang 1-2 jam
malam 6–7 jam. Pola istirahat sekarang tidur malam 3 jam,
ibu mengatakan perutnya masih mules.
d) Pola Aktivitas
Ibu mengatakan pola aktivitas selama hamil sebagai ibu
rumah tangga, biasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti
menyapu, memasak, mencuci. Pola aktivitas sekarang jalan-
jalan di sekeliling tempat tidur, tidur miring kiri.
e) Pola Personal Hygiene
Pola mandi selama hamil 2x sehari, keramas 2 hari sekali,
gosok gigi 2x, ganti baju 2x sehari. Pola mandi, keramas,
gosok gigi dan ganti baju terakhir jam 06.30 wib.
f) Pola Seksual
Pola seksual selama hamil kalau suami pulang satu minggu
sekali, sekarang belum melakukan.
8) Data Psikologi
Ibu mengatakan ini anak dari pernikahan yang sah, ibu merasa
senang, suami serta keluarga juga senang dengan kehamilan
ibu saat ini, dan ibu sudah siap untuk merawat bayinya.
9) Data Sosial Ekonomi
Ibu mengatakan penghasilan suaminya cukup untuk kebutuhan
sehari-hari, tanggung jawab perekonomiannya ditanggung
124
suami, dan pengambilan keputusan oleh bersama
(suami&istri).
10) Data Perkawinan
Ibu mengatakan status perkawinannya sah secara agama, ini
adalah perkawinan yang pertamanya dan lama perkawinannya
sudah 11 tahun, usia pertama kali menikah umur 22 tahun.
11) Data Spiritual
Ibu mengatakan belum melakukan sholat, ibu selalu berdoa
untuk keselamatan ibu dan janinnya.
12) Data Sosial Budaya
Ibu tidak percaya dengan adat istiadat setempat seperti kalau
mau melahirkan pintu dan jendelanya harus dibuka semua.
13) Data Pengetahuan
Ibu mengatakan sudah mengetahui tanda-tanda persalinan.
b. Data Obyektif
Dari hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat hasil
kesadaran composmetis, Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80
x/menit, Pernafasan 20 x/menit Suhu 36,5oC, Tinggi Badan 151
cm, BB 67 kg, Lingkar Lengan Atas (LILA) 27 cm.
Pada pemeriksaan status present dari kepala sampai kaki, kepala
mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, tidak berketombe muka
tidak pucat dan tidak oedem, mata simetris, penglihatan baik,
konjungtiva tidak anemis, sclera tidak ikterik, hidung bersih, tidak
ada pembesaran polip, tidak ada sinusitis, mulut dan bibir lembab,
125
tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada gigi, gusi tidak epulis,
bentuk telinga simetris, bersih, pendengaran baik, leher tidak ada
pembesaran kelenjar tyroid, dan tidak ada pembesaran vena
jugularis. Aksila tidak ada pembesaran kelenjar limfe, pernafasan
teratur bentuk dada normal, tidak ada retraksi dinding dada, mamae
simetris, abdomen tidak ada luka bekas operasi, genetalia
kebersihan terjaga tidak ada varices, tidak oedem, tidak ada
kelenjar bartolini, anus tidak ada hemoroid, dan extremitas tidak
oedem, kuku tidak pucat dan tidak ada varices.
Pada pemeriksaan obstetric secara inspeksi muka terlihat tidak
pucat, tidak oedem, tidak ada cloasma gravidarum, mamae bentuk
simetris, puting susu bersih, hiperpigmentasi areola, tidak ada
benjolan yang abnormal, tidak ada bekas operasi pada payudara,
kolostrum/ ASI sudah keluar, abdomen normal, uterus membesar
sesuai dengan umur kehamilan, tidak ada garis linea nigra dan strie
gravidarum. tidak ada luka bekas operasi, genetalia normal, tidak
ada luka bekas operasi, anus tidak hemoroid.
Pada pemeriksaan palpasi Leopold I tinggi fundus uterus 3 jari di
bawah processus xifoideus, pada bagian atas perut ibu teraba bulat,
Lunak, tidak melenting (bokong janin), Leopold II bagian kanan
perut ibu teraba panjang ada tahanan (punggung janin)
bagian kiri perut ibu teraba kecil-kecil, (extremitas janin), Leopold
III pada bagian perut ibu teraba bulat, keras, yaitu (kepala) dan
kepala sudah tidak bisa di goyangkan, Leopold IV bagian bawah
126
perut ibu kepala sudah masuk pintu atas panggul/divergen 3/5
bagian. Tinggi Fundus Uterus 33 cm. Taksiran berat badan janin
dengan menggunakan rumus Mc. Donald yaitu 33 – 11 = 22 x 155
= 3.410 Gram, hari perkiraan lahir 23 Agustus 2018 dan umur
kehamilan 39 minggu + 6 hari, denyut jantung janin 138 x/menit,
teratur, gerakan janin aktif dan kontraksi Rahim 2 kali dalam 10
menit lamanya 25 detik, pengeluaran pervagina lendir bercampur
darah.
Setelah pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan dalam atas
indikasi adanya kontraksi rahim dengan tujuan untuk menilai
apakah ibu sudah dalam proses persalinan. Hasil pemeriksaan
dalam yaitu kondisi vagina normal, tidak ada benjolan, keadaan
portio tebal, effacement 20-30%, pembukaan 2 cm, selaput ketuban
(+) positif, titik tunjuk ubun-ubun kecil, presentasi
kepala,penurunan kepala, hodge II dan tidak ada bagian terkemuka,
pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan Hb, pemeriksaan
protein urine dan pemeriksaan USG tidak di lakukan.
2. Intepretasi Data
a. Diagnosa (Nomenklatur)
Ny, R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu+2 hari, janin
tunggal, hidup, intra uterin, letak memanjang, punggung kanan,
presentasi kepala, divergen inpartu kala I fase laten normal, dengan
riwayat tuberculosis paru.
127
1) Data Subyektif
Ibu mengatakan bernama Ny. R umur 33 tahun, Ibu
mengatakan ini kehamilan ke tiga, sudah pernah melahirkan 2
kali dan tidak pernah keguguran. kenceng-kenceng dari jam
23.00 (24/08/2018).
2) Data Obyektif
Keadaan ibu baik, kesadaran composmetis, TD 110/70 mmHg,
Nadi 80 x/menit, Suhu 36,5oC, R 20 x/menit, Tb 151 cm, BB
68 Kg, LILA 27 cm, Palpasi Leopold I tinggi fundus uterus 33
cm, bagian fundus teraba bulat, lunak, tidak melenting, yaitu
bokong, Leopold II pada bagian kanan perut ibu teraba keras,
memanjang, dan ada tahanan, yaitu punggung janin,pada
bagian kiri perut ibu teraba bagian kecil yaitu kaki, dan tangan
janin, Leopold III pada bagian bawah perut ibu teraba bulat,
keras, dan tidak bisa di goyangkan, yaitu kepala janin, Leopold
IV kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, divergen atau
3/5 bagian, TBBJ 3410 gram, DJJ 138 x/menit, teratur ,
gerakan janin aktif dan kontraksi Rahim 2 kali dalam 10 menit
lamanya 25 detik, pengeluaran pervagina lendir bercampur
darah.
Hasil pemeriksaan keadaan portio tebal, effacement 20-30%,
pembukaan 2 cm, selaput ketuban (+) positif, titik tunjuk ubun-
ubun kecil (UUK), presentasi kepala, penurunan kepala hodge
II, dan tidak ada bagian terkemuka.
128
b. Masalah
Tidak ada
c. Kebutuhan
Tidak ada
3. Diagnosa Potensial
Tidak ada
4. Antisipasi Penanganan Segera
Konsultasi dengan dokter jaga
5. Intervensi
a. Beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan
b. Berikan asuhan sayang ibu
c. Anjurkan ibu untuk tetap tenang saat ada kontraksi
d. Memberitahu keluarga untuk menyiapkan perlengkapan yang di
butuhkan untuk persalinan
e. Lakukan pemantauan kemajuan persalinan kala 1 dengan
pengawasan 10.
6. Implementasi
a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
Keadaan ibu dan bayi baik
TD : normal Detak Jantung Janin (DJJ) : normal
Suhu : normal
Ibu sudah dalam proses persalinan
b. Memberikan asuhan sayang ibu seperti menjaga privasi ibu,
menghadirkan suami/ keluarga mendampingi ibu saat persalinan,
129
memberikan asupan energy berupa (makanan/minuman) pada saat
kontraksi mereda, memijat bagian yang terasa sakit untuk
mengurangi rasa sakit, menganjurkan ibu untuk berjalan-jalan
supaya kepala bayi semakin turun dan mempercepat proses
persalinan, menganjurkan ibu jika ingin BAB atau BAK untuk ke
kamar mandi dengan di damping keluarga.
c. Menganjurkan ibu agar tetap tenang karena rasa sakit saat proses
persalinan itu hal yang normal.
d. Memberitahu keluarga untuk menyiapkan kebutuhan bersalin bagi
ibu pakaian ganti, kain kering dan bersih sebanyak 4 lembar,
pembalut, dan untuk pakaian bayi, popok, kain bayi, topi, selimut,
kain dan bedong.
e. Melakukan pemantauan kemajuan persalinan kala 1 dengan
pengawasan 10 yaitu DJJ dan kontraksi setiap 30 menit, tensi, nadi,
suhu, urine, nutrisi, pembukaan, penurunan kepala, penyusupan,
setiap 4 jam sekali.
7. Evaluasi
a. Ibu sudah mengerti hasil pemeriksaan yang telah di lakukan
b. Suami dan keluarga sudah berada di samping ibu, suami dan
keluarga sudah mengerti untuk memberi asupan energy berupa
makanan dan minuman kepada ibu, suami dan keluarga sudah
mengerti untuk memijat bagian yang terasa sakit, ibu sudah jalan-
jalan dan ibu sudah mengerti alasan di sarankan untuk berjalan-
130
jalan, ibu sudah mengerti kalau merasa mules ingin BAB/BAK
langsung ke kamar mandi dan keluarga siap mengantarkan.
c. Ibu mengerti apa yang di sarankan bidan
d. Perlengkapan persalinan sudah di siapkan
e. Pemantauan sudah dilakukan dan hasil terlampir
131
KALA II
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 17.00 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan kencengnya semakin sering dan lama
b. Data Obyektif
Keadaan umum : baik
Tekanan darah : 120/70 mmHg
Denyut nadi : 80 x/menit
Pernafasan : 20 x/menit
Suhu tubuh : 36,5 ˚C
Kontraksi : 4x10’x45”
Kekuatan HIS : kuat
Detak jantung janin : 138x/menit
PPV : lendir darah
Adanya tanda kala II : - Dorongan ingin meneran
ii. Tekanan pada anus
iii. Perineum menonjol
iv. Vulva membuka
132
c. Assessment
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu+2 hari janin tunggal,
hidup, intra uterin,letak memanjang, punggung kanan, presentasi kepala,
divergen inpartu kala II fase aktif dengan faktor resiko riwayat
tubercolusis paru.
d. Penatalaksanaan
1) Mengenali adanya tanda gejala kala II seperti dorongan ingin
meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka.
Evaluasi : tanda gejala kala II sudah terlihat
2) Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk
mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan 1 buah alat suntik
sekali pakai 3 cc ke dalam wadah partus set.
Evaluasi : alat dan obat sudah lengkap, peralatan ibu dan bayi sudah
lengkap, ampul sudah di patahkan dan spuit 3 cc sudah ada dalam
partus set.
3) Memakai alat pelindung diri seperti : clemek, masker, kaca mata, topi
dan sepatu boot.
Evaluasi : APD lengkap sudah di pakai
4) Memastikan lengan / tangan tidak memakai perhiasan, mencuci
tangan dengan sabun di air mengalir
Evaluasi : semua perhiasan sudah di lepas dan sudah mencuci tangan
5) Memakai sarung tangan DTT pada tangan kanan yang di gunakan
untuk periksa dalam
Evaluasi : sarung tangan sudah di pakai
133
6) Mengambil alat suntik sekali pakai dengan tangan kanan, isi dengan
oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
Evaluasi : oksitosin 1 ml sudah di masukan ke dalam spuit dan sudah
di masukan kembali ke dalam perus set.
7) Membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas DTT (basah)
dengan gerakan dari vulva ke perineum
Evaluasi : vulva dan perineum sudah di bersihkan
8) Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah
lengkap dan selaput ketuban sudah pecah atau belum
Evaluasi : pemeriksaan sudah dilakukan dengan hasil keadaan portio
sudah tidak teraba, effacement 100%, pembukaan 10 cm, selaput
ketuban negative, warna jernih, bagian terendah kepala, titik tunjuk
ubun-ubun kecil (UUK), penurunan kepala hodge IV atau 0/5 bagian,
tidak ada bagian yang menumbung.
9) Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan kedalam larutan
klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan
merendamnya dalam larutan klorin 0,5%
Evaluasi : sarung tangan sudah di lepas dan di rendam kedalam
larutan klorin 0,5%.
10) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus hilang
Evaluasi : Detak jantung janin 140 x/menit dan teratur
134
11) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik,
meminta ibu untuk meneran saat ada kofvntraksi, bila ia sudah merasa
ingin meneran
Evaluasi : ibu dan keluarga sudah mengerti
12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk
meneran, (pada saat ada kontraksi, bantu ibu dalam posisi setelah
duduk dan pastikan ia merasa nyaman)
Evaluasi : ibu dan keluarga sudah mengerti
13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang
kuat untuk meneran
Evaluasi : ibu mengerti dan bersedia
14) Saat kepala janin terlihat di vulva dengan diameter 5-6 cm, memasang
handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu
Evaluasi : handuk sudah di letakan di perut ibu
15) Mengambil kain bersih, melipat 1/3 bagian dan meletakkannya
dibawah bokong ibu
Evaluasi : kain sudah terpasang
16) Membuka tutup partus set dan mengecek kelengkapan alat dan bahan.
Evaluasi : tutup pertus set sudah membuka dan alat sudah lengkap.
17) Memakai sarung tangan pada kedua tangan
Evaluasi : kedua tangan sudah memakai sarung tangan DTT.
18) Saat sub-occiput tampak dibawah simfisis, tangan kanan melindungi
perineum dengan dialas lipatan kain di bawah bokong, sementara
135
tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi yang
terlalu cepat saat kepala lahir.
Evaluasi : kepala sudah lahir
19) Menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain/ kassa yang
bersih.
Evaluasi : sudah di lakukan
20) Memeriksa leher bayi kemungkinan adanya lilitan tali pusat
Evaluasi : tidak ada lilitan tali pusat
21) Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan
Evaluasi : kepala bayi sudah melakukan putaran paksi luar
22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua telapak
tangan secara biparietal di kepala janin, tarik secara hati-hati ke arah
bawah sampai bahu anterior / depan lahir, kemudian tarik secara hati-
hati ke atas sampai bahu posterior/belakang lahir.
Evaluasi : bahu bayi sudah lahir
23) Setelah bahu lahir, tangan kanan menyangga kepala, leher dan bahu
janin bagian posterior dengan posisi ibu jari pada leher (bagian bawah
kepala) dan ke empat jari pada bahu dan dada / punggung janin,
sementara tangan kiri memegang lengan dan bahu janin bagian
anterior saat badan dan lengan lahir
Evaluasi : bahu dan kepala bayi sudah di sangga
24) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri pinggang ke
arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai
bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin)
136
Evaluasi : bayi sudah lahir normal jam 17.15 Wib
25) Menilai tangisan, gerakan bayi dan warna kulit
Evaluasi : bayi menangis kuat dan gerakan aktif, warna kulit
kemerahan
26) Meletakan bayi di atas perut ibu, mengeringkan dengan kain yang
bersih dan keringkan dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya
kecuali telapak tangan dan mengganti kain yang basah dengan kain
yang kering dan bersih.
Evaluasi : bayi sudah di keringkan dan di selimuti dengan kain.
27) Mengganti kain bayi dengan kain kering dan bersih, membedong bayi
hingga kepala
Evaluasi : kain sudah di ganti dengan kain kering dan bersih
28) Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal
Evaluasi : tidak ada janin yang kedua
29) Memberitahu ibu akan disuntik oksitosin gunanya untuk melahirkan
plasenta
Evaluasi : ibu sudah mengerti dan bersedia
30) Menyutikan Oksitosin 10 unit secara intra muskuler pada bagian luar
paha kanan 1/3 atas setelah melakukan aspirasi terlebih dahulu untuk
memastikan bahwa ujung jarum tidak mengenai pembuluh darah
Evaluasi : oksitosin sudah di suntikan di 1/3 paha kanan ibu
31) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari umbilicus
bayi. Melakukan urutan tali pusat ke arah ibu dan memasang klem
diantara kedua 2 cm dari klem pertama.
137
Evaluasi : tali pusat sudah di jepit
32) Memegang tali pusat diantara 2 klem menggunakan tangan kiri,
dengan perlindungan jari-jari tangan kiri, memotong tali pusat di
antara kedua klem
Evaluasi : tali pusat sudah di potong
33) Meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi tengkurap di dada ibu,
luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada / perut ibu, kaki
di renggangkan seperti kaki katak dan usahakan kepala bayi berada di
antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara
ibu selama 1 jam .
Evaluasi : bayi dilakukan IMD
138
MANAGEMENT AKTIV KALA III
Tanggal : 25 agustus 2018
Jam : 17.16 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Subyektif :
Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.
Ibu mengatakan badanya lemes dan perutnya mules.
b. Obyektif :
Keadaan umum baik, tinggi fundus uterus setinggi pusat, kontraksi keras,
kandung kemih kosong, perdarahan pervagina (PPV) 30 cc.
c. Assessment :
Ny, R umur 33 tahun P3 A0 dengan kala III normal.
d. Penatalaksanaan
34) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva
Evaluasi : sudah di lakukan
35) Meletakkan tangan kiri di atas simpisis menahan bagian bawah uterus,
sementara tangan kanan memegang tali pusat menggunakan klem atau
kain kasa dengan jarak antara 5-10 cm dari vulva
Evaluasi : tangan kiri sudah di atas simpisis dan tangan kanan memegang
tali pusat
36) Saat kontraksi, memegang tali pusat dengan tangan kanan sementara
tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorso kranial.Bila
139
uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau keluarga untuk
melakukan stimulasi putting susu
Evaluasi : sudah dilakukan dorso kranial
37) Jika dengan peregangan tali pusat terkendali tali pusat terlihat bertambah
panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta , minta ibu untuk meneran
sedikit sementara tangan kanan menarik tali pusat ke arah bawah
kemudian ke atas sesuai dengan kurva jalan lahir hingga plasenta tampak
pada vulva.
Evaluasi : sudah dilakukan dan ibu sudah mengerti
38) Setelah plasenta tampak di vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan
hati-hati.Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta dengan kedua
tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta
dan mencegah robeknya selaput ketuban.
Evaluasi : plasenta lahir jam 17.25 wib
39) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan
menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari
tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
Evaluasi : fundus sudah di massase
40) Sambil tangan kiri melakukan masase pada fundus uteri, periksa bagian
maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk
memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir
lengkap, dan memasukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia
Evaluasi : sudah di bersihkan dan tidak ada sisa selaput ketuban yang
tertinggal
140
Kala IV
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 17.26 WIB
a. Subyektif
Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya. ibu mengatakan lemas dan lelah.
b. Obyektif
Keadaan umum baik, tanda-tanda vital TD 120/80, S 36,5oC, R 20 x/menit, N
80 x/menit, kontraksi uterus keras, perdarahan 100 cc, kandung kemih 30 cc.
c. Assessment
Ny. R umur 33 tahun P3 A0 dengan kala IV normal.
d. Penatalaksanaan
41) Memeriksa apakah ada robekan pada introitus vagina dan perenium yang
menimbulkan perdarahan aktif.Bila ada robekan yang menimbulkan
perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan
Evaluasi : adanya robekan jalan lahir derajat 2
42) Periksa kembali kontraksi uterus dan tanda adanya perdarahan
pervaginam, pastikan kontraksi uterus baik
Evaluasi : kontraksi keras, perdarahan 30 cc
43) Membersihkan sarung tangan dari lendir dan darah di dalam larutan klorin
0,5 %, kemudian bilas tangan yang masih mengenakan sarung tangan
dengan air yang sudah di desinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya
Evaluasi : sarung tangan sudah di bersihkan menggunakan larutan klorin
0,5 %
141
44) Mengikat tali pusat kurang lebih 1 cm dari umbilicus dengan sampul mati
Evaluasi : tali pusat sudah di ikat menggunakan simpul mati
45) Mengikat balik tali pusat dengan simpul mati untuk kedua kalinya
Evaluasi : tali pusat sudah di ikat dengan simpul mati
46) Melepaskan klem pada tali pusat dan memasukkannya dalam wadah berisi
larutan klorin 0, 5%
Evaluasi : klem sudah di lepas dan sudah di masukan di wadah yang berisi
larutan klorin 0,5 %
47) Membedong kembali bayi
Evaluasi :bayi sudah di bedong
48) Berikan bayi pada ibu untuk disusui
Evaluasi : bayi sedang di lakukan IMD selama satu jam
49) Lanjutkan pemantauan terhadap kontraksi uterus, tanda perdarahan
pervaginam dan tanda vital ibu.
Evaluasi : sudah di lakukan pemantauan kontraksi keras, perdarahan 30
cc,tensi normal, suhu normal, nadi normal, respirasi normal.
50) Mengajarkan ibu/keluarga untuk memeriksa uterus yang memiliki
kontraksi baik dan mengajarkan masase uterus apabila kontraksi uterus
tidak baik.
Evaluasi : ibu sudah di ajari cara massase dan ibu sudah mengerti
51) Mengevaluasi jumlah perdarahan yang terjadi
Evaluasi : jumlah pengeluaran darah ibu 100 cc
52) Memeriksa nadi ibu
Evaluasi : nadi ibu 80 x/menit
142
53) Merendam semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5 %
Evaluasi : peralatan sudah di rendam di larutan klorin 0,5 %
54) Membuang barang-barang yang terkontaminasi ke tempat sampah yang di
sediakan
Evaluasi : sampah sudah di buang di tempatnya masing-masing
55) Membersihkan ibu dari sisa air ketuban, lendir dan darah dan
menggantikan pakaiannya dengan pakaian bersih/kering
Evaluasi : pakaian ibu sudah di ganti dengan kain bersih dan kering
56) Memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk
membantu apabila ibu ingin minum
Evaluasi : ibu sudah merasa nyaman dan keluarga siap membantu ibu
57) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%
Evaluasi : tempat persalinan sudah di bersihkan menggunakan larutan
klorin 0,5 %
58) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan
sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan
klorin 0,5 %
Evaluasi : sarung tangan sudah di lepas dan sudah di rendam di larutan
klorin 0,5 %
59) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
Evaluasi : sudah di lakukan
60) Melengkapi partograf dan memeriksa tekanan darah.
Evaluasi : partograf sudah di lengkapi
143
PANTAUAN PERSALINAN KALA IV Jam
Ke Waktu Tekanan Darah Nadi Suhu Tinggi Fundus Uteri Kontraksi
Uterus Kandung
Kemih Perdarahan
1 17:40 120/70 mmHg 80x 36,5 2Jr Pusat Keras Kosong 30 cc
14:55 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 10 cc
18:10 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
18:25 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
2 18:55 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
19:25 120/70 mmHg 80x 36,5 2Jr Pusat Keras Kosong 10 cc
Total 65 cc
144
ASUHAN KEBIDANAN NIFAS
PADA NY. R DI PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL
C. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas Post Partum 2 Jam
a) Pengkajian Data
Tanggal : 25 agustus 2018
Jam : 21.15 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subyektif
a) Biodata
Dari hasil anamnesa yang telah dilakukan di dapatkan data Ny.
R, berumur 33 tahun, Agama islam, Suku bangsa jawa,
Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan IRT, Suami Ny. R Bernama
Tn. W umur 33 tahun, Suku Bangsa Jawa, Agama islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan swasta. Alamat di desa Bulakwaru
Rt 10 Rw 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
b) Alasan Datang
-
c) Keluhan Utama
Ibu mengatakan perutnya masih mulas
d) Riwayat obstetrik dan ginekologi
a) Riwayat kehamilan, persalinan, nifas tahun lalu
Ibu mengatakan persalinan pertama dengan umur
kehamilan 36 minggu, jenis persalinan spontan, penolong
145
persalinan Bidan, BB 3100 gram, jenis kelamin laki-laki
dengan nifas normal dan sekarang berumur 10 tahun.
Persalinan yang kedua dengan kehamilan 36 minggu, jenis
persalinan spontan, penolong persalinan Bidan, BB 3200
gram, jenis kelamin laki-laki dengan nifas normal. Keadaan
sekarang berumur 4 tahun.
b) Riwayat kehamilan sekarang
Ibu mengatakan ini kehamilan ketiga dan tidak pernah
mengalami keguguran, antenatal care (ANC) pertama kali
di Puskesmas, tanggal 20 januari 2018 ibu dengan keluhan
terlambat haid dan timbul tanda-tanda hamil seperti mual
dan pusing, sering miksi dan dilakukan test kehamilan
dengan hasil positif, dan umur kehamilan 9 minggu. Ny, R
sudah melakukan pemeriksaan kehamilan baik di dr. SpOg
maupun di puskesmas. Pada trimester I ibu melakukan
pemeriksaan 2x di puskesmas, trimester II 4x di puskesmas,
trimester III sebanyak 5x, 4x di puskesmas 1x di BPM dan
1x di dr SpOg, selama hamil ibu mengkonsumsi tablet
tambah darah kurang lebih 80 tablet, ibu sudah
mendapatkan imunisasi TT I pada tanggal 21 agustus 2018.
keluhan trimester I mual muntah dan pusing. Terapi yang di
berikan metoklorpramide 3x1 (untuk meredakan mual)
tablet Fe 1x1 (vitamin penambah darah). trimester II pusing
146
pilek dan pegal. Terapi yang di berikan sangovitin IxI
(vitamin penambah darah) vit C IxI.
c) Riwayat Persalinan Sekarang
Waktu persalinan tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.15 wib,
persalinan spontan, tidak ada penyulit waktu persalinan,
ketuban pecah jam 17.10 wib, warna jernih, bau khas, bayi
lahir jam 17.15 wib, berat badan bayi 3700 gram, jenis
kelamin perempuan.
e) Riwayat Kesehatan
a) Penyakit yang pernah di derita
Ibu mengatakan pernah menderita penyakit infeksi
seperti batuk lebih dari 2 minggu, disertai darah, demam,
menggigil pada malam hari, berat badan menurun yaitu
Tuberculosis (TBC), ibu tidak pernah mengalami gejala
mual muntah, BAK yang berwarna kuning keruh seperti
teh, mual, demam, pembesaran hati, nyeri ulu hati,
kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning (Hepatitis),
diare tidak sembuh-sembuh, demam, batuk yang
berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan
tubuh menurun, sariawan di bagian mulut atas dan mulut
bawah yang tak kunjung sembuh Human Immunodeficiency
Virus (HIV), gatal pada genetalia, keputihan yang berbau
busuk, berwarna hijau Infeksi Menular Seksual (IMS),
Penyakit Keturunan seperti mudah lapar, mudah haus,
147
mudah mengantuk, sering kencing di malam hari, luka
yang sukar sembuh yaitu Diabetes Mellitus (DM), tekanan
darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing, tengkuk terasa
pegal (Hipertensi), sesak nafas saat udara dingin dan
banyak debu, pernafasan berbunyi mengik (Asma),
nyeri dada bagian atas, jantung berdebar-debar, sesak
nafas, dan mudah lelah (Jantung)
Ibu mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan/trauma
dan ibu mengatakan tidak pernah memiliki riwayat
penyakit yang di operasi seperti mioma, kista, dan kanker
serviks.
b) Kesehatan ibu sekarang
Ibu mengatakan penyakit infeksi Tuberculosis (TBC) yang
pernah dialami sudah sembuh, ibu tidak mengalami
penyakit dengan gejala mual muntah, demam, pembesaran
hati, nyeri ulu hati, BAK yang berwarna kuning keruh
seperti teh, kulit tubuh dan sclera mata berwarna kuning
(Hepatitis), diare, demam, dan batuk yang berkepanjangan,
berat badan menurun drastis, kekebalan tubuh menurun,
sariawan di bagian mulut atas dan mulut bawah yang tak
kunjung sembuh, Human Immunodeficiency Virus (HIV),
gatal pada genetalia, keputihan yang berbau busuk,berwarna
hijau Infeksi Menular Seksual (IMS), Penyakit Keturunan
seperti mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
148
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu
Diabetes Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg, pusing, tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak
nafas saat udara dingin dan banyak debu, pernafasan
berbunyi mengik (Asma), nyeri dada bagian atas,jantung
berdebar-debar, sesak nafas, dan mudah lelah (Jantung)
c) Riwayat Kesehatan Keluarga
Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada yang menderita
penyakit infeksi seperti batuk lebih dari 2 minggu, disertai
darah, demam, menggigil pada malam hari, berat badan
menurun yaitu Tuberculosis (TBC), mual muntah, demam,
nyeri ulu hati, pembesaran hati, BAK yang berwarna
kuning keruh seperti teh, kulit tubuh dan sclera mata
berwarna kuning (Hepatitis), diare tidak sembuh-sembuh,
demam, dan batuk yang berkepanjangan, berat badan
menurun drastis, kekebalan tubuh menurun, sariawan di
bagian mulut atas dan bawah yang tak kunjung sembuh,
Human Immunodeficiency Virus (HIV), gatal pada
genetalia, keputihan yang berbau busuk,berwarna hijau
Infeksi Menular Seksual (IMS). Penyakit Keturunan seperti
mudah lapar, mudah haus, mudah mengantuk, sering
kencing di malam hari, luka yang sukar sembuh yaitu
Diabetes Mellitus (DM), tekanan darah lebih dari 140/90
mmHg, pusing ,tengkuk terasa pegal (Hipertensi), sesak
149
nafas saat udara dingin dan banyak debu, pernafasan
berbunyi mengik (Asma), nyeri dada bagian atas,jantung
berdebar-debar, sesak nafas, dan mudah lelah (Jantung) .
Ibu mengatakan didalam keluarga tidak ada yang
mempunyai riwayat bayi kembar.
f) Kebiasaan
Ibu mengatakan selama hamil tidak ada pantangan makanan
apapun, tidak pernah mengkonsumsi jamu, tidak pernah
mengkonsumsi obat-obatan selain dari tenaga kesehatan, tidak
pernah mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok sebelum
dan selama hamil, di rumah ibu tidak memelihara binatang
seperti kucing, anjing,burung, dan lain-lain.
g) Riwayat haid
Ibu mengatakan pertama kali menstruasi (menarche) pada usia
12 tahun, siklus 28 hari, lamanya 6 hari, banyaknya 3 kali ganti
pembalut dalam sehari, dan tidak merasakan nyeri baik
sebelum atau sesudah mendapatkan menstruasi, Hari Pertama
Haid Terakhir (HPHT) 16 november 2017. serta ibu
mengalami keputihan selama 3 hari, tidak gatal, warnanya
jernih, bau khas.
h) Riwayat Penggunaan Kontrasepsi
Ibu mengatakan menggunakan KB pil, lamanya 1 tahun, tidak
ada keluhan, alasan lepas karena sedang mengkonsumsi obat
150
Tb, rencana yang akan datang Kb suntik 3 bulan, alasan
praktis.
i) Kebutuhan Sehari-hari
a) Pola Nutrisi
Pola makan selama hamil porsi sedang, jenis aneka ragam,
macam aneka ragam. Pola makan sekarang porsi sedang,
jenis nasi, ayam, sayur, sop, tahu, jenis, nasi, lauk pauk,
sayur. Pola minum selama hamil 6-8 gelas jenis air putih air
susu, gangguan tidak ada. Pola minum sekarang 3 gelas (2
gelas air putih & 1 gelas air teh).
b) Pola Eliminasi
Buang air besar selama hamil 1-2 x/hari, konsistensi agak
keras, gangguan tidak ada. Sekarang ibu belum buang air
besar. Buang air kecil selama hamil 5-8 x/hari, warna
kuning jernih, tidak ada gangguan. Buang air kecil sekarang
2 kali terakhir jam 20.30 wib, warna jernih, tidak ada
gangguan.
c) Pola Istirahat
Selama hamil siang 1-2 jam, malam 6-7 jam tidak ada
gangguan. Sekarang ibu belum istirahat.
d) Pola aktivitas
Selama hamil ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga
seperti menyapu, memasak. Aktivitas ibu sekarang
mobilisasi miring kanan kiri, duduk, turun dari tempat
151
tidur, jalan-jalan di sekeliling tempat tidur dan kamar
mandi tanpa bantuan orang lain.
e) Pola Personal Hygiene
Selama hamil mandi 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok
gigi 2x, ganti baju 2-3 x sehari. Sekarang ibu mengatakan
belum mandi, belum melakukan keramas, gosok gigi belum
melakukan, ganti baju 1x.
f) Pola Seksual
Selama hamil frekuensi 1 minggu 1 kali jika suami pulang,
tidak ada gangguan. Sekarang belum melakukan hubungan.
j) Data Psikologi
Ibu mengatakan status anak yang di kandung sah menurut
agama, ibu mengatakan senang dengan kelahiran anaknya,
suami dan keluarga juga ikut senang atas kelahiran anak ibu,
ibu siap untuk merawat bayinya.
k) Data Sosial Ekonomi
Ibu mengatakan penghasilan mencukupi, tanggung jawab
perekonomian suami, pengambilan keputusan oleh bersama
(suami&istri).
l) Data Perkawinan
Ibu mengatakan status perkawinannya sah tercantum di KUA,
ini perkawinan pertamanya, menikah di usia 22 tahun, dan usia
lamanya sudah 11 tahun.
152
m) Data Spiritual
Ibu mengatakan belum melakukan ibadah
n) Data Sosial Budaya
Ibu mengatakan tidak mempercayai adat istiadat setempat
seperti dalam masa nifas 40 hari tidak boleh keluar rumah.
o) Data Pengetahuan Ibu
Ibu mengatakan sudah mengetahui cara memandikan bayi.
b. Data Obyektif
1) Pemeriksaan Fisik
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat hasil
keadaan umum baik. Kesadaran composmentis. Tanda vital
Tekanan darah 110/80 mmHg, Suhu 36oC, Nadi 78 x/ menit,
Pernafasan 20 x/ menit, tinggi fundus uterus 3 jari di bawah
pusat, Kandung kemih kosong, Kontraksi keras.
Pada pemeriksaan status present dari kepala sampai kaki,
kepala mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, muka tidak
pucat, muka tidak oedem, mata simetris, penglihatan baik,
konjungtiva tidak anemis, sclera tidak iketerik, hidung bersih,
tidak ada pembesaran polip, tidak ada sinusis, mulut dan bibir
lembab, tidak ada stomatis, tidak ada caries pada gigi, gusi
tidak epulus, bentuk telinga simetris, bersih, pendengaran baik,
leher tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan tidak ada
pembesaran vena jugularis. Aksila tidak ada pembesaran
kelenjar limfe, pernafasan teratur dada bentuk simetris, tidak
153
ada retraksi dinding dada, mamae bentuk simetris, bersih, tidak
ada luka bekas operasi, kolostrum/ASI sudah keluar. Pada
pemeriksaan palpasi tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat,
kontraksi uterus keras. Pengeluaran vagina lochea rubra, warna
merah, konsistensi cair, khas, dengan estimasi perdarahan 30
cc luka jahitan baik . Extremitas tidak oedem dan tidak ada
varises, tidak ada tanda-tanda human.
2) Pemeriksaan Obstetrik
1. Inspeksi
Muka tidak pucat, tidak oedem, tidak ada cloasma
gravidarum, mamae bentuk simetris, hiperpigmentasi
areola, puting susu bersih, kolostrum/ ASI sudah keluar,
kebersihan terjaga, abdomen normal, tidak ada luka bekas
operasi, genetalia normal, luka jahitan baik.
2. Palpasi
palpasi tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, kontraksi
uterus keras. Pengeluaran pervagina lochea rubra, warna
merah, konsistensi cair, bau khas, dengan estimasi
perdarahan 30 cc dan luka jahitan baik.
3. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium,
pemeriksaan rontgen dan Ultrasonography tidak di
lakukan.
154
b) Interprestasi Data
a. Diagnosa (Nomenklatur)
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka didapatkan diagnosa
Ny. R umur 33 tahun P3 A0 2 jam post partum dengan Nifas
normal.
1) Data Subyektif
Ibu mengatakan senang bayinya sudah lahir, masih lelah dan
perutnya masih terasa mulas. ASI nya sudah keluar.
2) Data Obyektif
Keadaan umum ibu baik, kesadaran compomentis. Tanda-tanda
vital Tekanan darah 110/80 mmHg, Suhu 36oC, Nadi 78
x/menit, Pernafasan 20x/menit. Pada pemeriksaan palpasi
tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus
keras. Pengeluaran pervagina lochea rubra, warna merah,
konsistensi cair, bau khas, dengan estimasi perdarahan 30 cc
dan luka jahitan baik.
b. Masalah
Ibu mengatakan perutnya masih terasa mulas
c. Kebutuhan
Istirahat yang cukup, asupan nutrisi.
c) Diagnosa Potensial
Tidak ada
d) Antisipasi Penanganan Segera
Tidak ada
155
e) Intervensi
a. Beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
b. Beritahu ibu penyebab dari rasa mulesnya
c. Ajari ibu untuk memassase perut jika tidak keras
d. Beritahu ibu tanda-tanda bahaya masa nifas
e. Beritahu pada ibu untuk menjaga personal hygiene
f. Beritahu ibu untuk melakukan mobilisasi dini, dan keluarga untuk
membantunya.
g. Beritahu ibu perawatan luka jahitan
h. Beritahu ibu untuk memberikan ASI esklusif dan berikan asi setiap
bayi menginginkanya
i. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup
j. Ajarkan ibu cara menyusui yang benar
k. Memberikan obat terapi post partum kepada ibu
f) Implementasi
a. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
bahwa keadaan ibu saat ini baik-baik saja
TD : 110/80 mmhg S : 36 o C
N : 78 x/menit R : 20 x/menit
b. Memberitahu ibu tentang penyebab perut ibu masih mulas
dikarenakan adanya proses involusi uterus/ kembalinya Rahim
kebentuk semula seperti sebelum hamil, jadi hal tersebut wajar di
alami saat masa nifas.
156
c. Mengajari ibu untuk memassase (pijat) perut caranya yaitu tangan
kanan diletakan di atas fundus ibu dan masasse 5-10 detik atau
sampai fundus (Rahim ) ibu keras, tanda kontraksi baik yaitu keras
dan tanda kontraksi yaitu jelek, fungsi dari memijat/memassase perut
untuk mengurangi perdarahan setelah melahirkan.
d. Memberitahu ibu tentang bahaya masa nifas yaitu pendarahan
pervaginam, keluar cairan yang berbau busuk dari jalan lahir,
tekanan darah lebih dari 140/90, mmHg, pandangan mata kabur,
sakit kepala yang tidak hilang ketika di bawa tidur, bengkak pada
kaki, tangan dan muka (tanda pre eklamsia). Nyeri ulu hati nyeri
payudara, payudara bengkak dan kemerahan, kehilangan nafsu
makan, mual muntah dan demam tinggi lebih dari 38ᵒC. Apabila
terdapat tanda-tanda bahaya tersebut segera dating ke tenaga
kesehatan.
e. Memberitahu ibu cara menjaga personal hygiene yaitu menjaga
daerah genetalia dengan membersihkannya menggunakan air dingin
dari atas ke bawah, mengganti pembalut 2x/hari jika basah saat
buang air besar atau buang air kecil, menggunakan celana dalam
yang menyerap keringat, serta menjaga kebersihan tubuh yang
lainnya.
f. Memberitahu ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan cara
miring kanan kiri, duduk. Dan peran keluarga untuk membantu jika
ibu ada kesulitan.
157
g. Memberitahu ibu cara perawatan luka jahitan yaitu jika ibu gunakan
kassa steril dan betadine, kassa steril di tetesi betadine di tempelkan
ke luka jahitan. lakukan rutin jika ibu setelah BAB/BAK.
h. Memberitahu ibu untuk memberikan ASI esklusif yaitu pemberian
ASI saja selama enam bulan pertama tanpa minuman / makanan lain
kecuali obat dan vitamin dan berikan asi setiap bayi
menginginkanya.
i. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, istirahat siang 1-2
jam, malam 6-8 jam, jika bayi sedang tidur ajurkan ibu untuk
istirahat juga dan disini peran suami juga di perlukan untuk sama-
sama membantu menjaga bayi.
j. Mengajarkan ibu cara menyusui yang benar yaitu Pastikan ibu dan
bayi berada dalam kondisi rileks dan nyaman
Posisi kepala bayi harus lebih tinggi dibandingkan tubuhnya ibu
dapat menyangga dengan tangan ataupun mengganjal dengan bantal.
Mendekatkan bayi ke payudara ketika bayi mulai membuka
mulutnya dan ingin menyusu, dekatkan bayi ke payudara ibu.
Tunggu hingga mulutnya terbuka lebar dengan posisi lidah ke arah
bawah. Jika bayi belum melakukannya, ibu dapat membimbing bayi
dengan dengan menyentuh lembut bagian bawah bibir bayi dengan
puting susu ibu. Perlekatan yang benar posisi perlekatan terbaik bayi
menyusui yaitu mulut bayi tidak hanya menempel pada puting,
namun pada area bawah puting payudara dan selebar mungkin.
Tanda bahwa perlekatan sudah baik yaitu ketika ibu tidak merasakan
158
nyeri saat bayi menyusu dan bayi memperoleh ASI yang mencukupi.
Ibu dapat mendengarkan saat bayi menelan ASI. Membetulkan
posisi bayi Jika ibu merasa nyeri, lepas perlekatan dengan
memasukan jari kelingking ke dalam mulut dan letakkan di antara
gusinya. Gerakan ini akan membuatnya berhenti menyusu sementara
anda bisa menyesuaikan posisi bayi. Kemudian, coba lagi untuk
perlekatan yang lebih baik. Setelah perlekatan sudah benar,
umumnya bayi akan dapat menyusu dengan baik.
k. Memberikan obat terapi post partum asam mefenamat 500 mg,
amoxicillin 500 mg, tablet fe 200 mg, dan vit A dengan dosis
200.000 ui.
g) Evaluasi
a. Ibu sudah mengerti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
b. Ibu sudah mengerti penyebab dari rasa mulesnya
c. Ibu sudah mengerti dan bisa cara memassase fundus
d. Ibu sudah mengerti tanda bahaya nifas
e. Ibu sudah mengerti cara menjaga kebersihan diri
f. Ibu sudah mengerti untuk tidak menunda jika ibu ingin bab/bak
g. Ibu sudah tahu perawatan luka jahitan
h. Ibu bersedia untuk memberikan ASI esklusif dan memberikan setiap
bayi menginginkannya
i. Ibu sudah mengerti cara mengatur pola istirahat dan suami siap
untuk membantu menjaga bayinya
j. Ibu sudah tahu cara menyususi yang benar
160
KUNJUNGAN NIFAS KE 2 ( 6 HARI)
Tanggal : 31 Agustus 2018
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan sudah bisa mengurus bayinya, ASI nya keluar lancar dan tidak
ada keluhan.
a) Kebutuhan Sehari-hari
b) Pola Nutrisi
Ibu mengatatakan makan sehari 3x porsi 1 piring sedang, menu aneka
ragam dan bermacam-macam, tidak ada makanan yang di pantang,
sedangkan frekuensi minum 8-10 gelas/hari, macam air putih
c) Pola Eliminasi
Ibu mengatakan frekuensi BAB 1-2 x/hari, konsistensi lembek, warna
kuning kecoklatan, tidak ada gangguan, BAK frekuensi 7-8 x/hari, bau
khas, warna kuning jernih, tidak ada gangguan.
d) Pola istirahat
Ibu mengatakan istirahatnya siang 1-2 jam malam 6–7 jam.
e) Pola Aktivitas
Ibu mengatakan sebagai ibu rumah tangga, biasa mengerjakan pekerjaan
rumah seperti menyapu, memasak, mencuci.
f) Pola Personal Hygiene
Pola mandi 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2x, ganti baju 2x
sehari.
161
g) Pola Seksual
Ibu mengatakan sampai saat ini belum melakukan hubungan.
b. Data Obyektif
Keadaan ibu baik, kesadaran composmentis. Tanda-tanda vital tekanan darah
110/70 mmHg, Suhu 36ᵒC, Nadi 80 x/menit, Pernafasan 20x /menit, muka tidak
pucat dan oedem, konjungtiva merah muda, sclera putih, bentuk payudara
simetris, puting susu menonjol, ASI sudah keluar banyak. Pada pemeriksaan
palpasi tinggi fundus uteri sudah tidak teraba kontraksi keras, pengeluaran
pervaginam lochea serosa, warna kecoklatan, luka jahitan kering, tidak ada
tanda-tanda homan.
c. Assesment
Ny. R umur 33 tahun P3 A0 6 hari Post Partum dengan nifas normal.
d. Penatalaksanaan
1. Memberitahu ibu hasil pemerikasaan yang telah dilakukan yaitu keadaan
ibu saat ini baik-baik saja
TD : 110/70 mmHg N : 80 x/menit
S : 36,0 C R : 20 x/menit
Luka jahitan sudah kering dan baik
Evaluasi : ibu sudah mengerti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
2. Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi kalori
tinggi protein seperti yang mengandung karbohidrat (padi, singkong,
gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan dan
lain-lain), protein hewani (susu, telor, ikan, daging ayam, daging sapi dan
162
lain-lain), mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak nabati
(lemak jagung dan lain-lain), lemak hewani (lemak ikan dan lain-lain).
Evaluasi : ibu bersedia untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.
3. Memberitahu ibu kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan
pertama yaitu 14 gelas sehari
Evaluasi : ibu dalam sehari mengkonsumsi air minum sebanyak 15 gelas
4. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri, termasuk daerah
kemaluan dengan cara cebok yang benar yaitu di bersihkan mulai dari
depan ke belakang menggunakan sabun dan air, ganti pembalut sesering
mungkin.
Evaluasi : ibu sehari mandi 2x, gosok gigi 2x, ganti baju 2x, ibu sudah
mengerti cara cebok yang benar, dan ibu sehari ganti pembalut sesering
mungkin.
5. Memberitahu ibu istirahat cukup siang 1-2 jam maam 6-8 jam atau saat
bayi istirahat ibu juga istirahat.
Evaluasi : istirahat siang ibu kurang lebih 1 jam, malam 6-8 jam saat ibu
istirahat bayi di gendong suami/ ibu.
6. Memberitahu ibu perawatan bayi yang benar yaitu memandikan bayi 2x
sehari, menjaga kehangatan bayi dengan cara di bedong dan menyelimuti
bayi, mengganti popok bayi jika bayi BAK/BAB.
Evaluasi : bayi mandi sehari 2x, bayi selalu di bedong dan di selimuti, jika
bayi bak/bab ibu segera mengganti popok bayi dan membersihkannya.
163
7. Memberitahu ibu jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena
akan membuat bayi stress.
Evaluasi : bayi tidak pernah menangis terlalu lama
8. Memberitahu untuk memberikan ASI esklusif yaitu bayi hanya diberikan
asi saja dari umur 0-6 bulan tanpa tambahan minuman atau makanan
apapun kecuali obat dan vitamin.
Evaluasi : ibu sudah mengerti penjelasan bidan dan ibu bersedia menyusui
bayinya dengan asi esklusif.
9. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi atau
jika ada keluhan segera datang ke tenaga kesehatan.
Evaluasi : ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang
164
CATATAN KUNJUNGAN NIFAS KE 2 ( 14 HARI )
Tanggal : 08 September 2018
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan tidak ada keluhan ASInya lancar.
1. Kebutuhan Sehari-hari
a) Pola Nutrisi
Ibu mengatatakan makan sehari 3x porsi 1 piring sedang, menu aneka
ragam dan bermacam-macam, tidak ada makanan yang di pantang,
sedangkan frekuensi minum 8-10 gelas/hari, macam air putih
b) Pola Eliminasi
Ibu mengatakan frekuensi BAB 1-2 x/hari, konsistensi lembek, warna
kuning kecoklatan, tidak ada gangguan, BAK frekuensi 7-8 x/hari, bau
khas, warna kuning jernih, tidak ada gangguan.
c) Pola istirahat
Ibu mengatakan istirahatnya siang 1-2 jam malam 6–7 jam.
d) Pola Aktivitas
Ibu mengatakan sebagai ibu rumah tangga, biasa mengerjakan
pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, mencuci.
e) Pola Personal Hygiene
Pola mandi 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2x, ganti baju
2x sehari.
165
f) Pola Seksual
Ibu mengatakan sampai saat ini belum melakukan hubungan.
b. Data Obyektif
Keadaan ibu baik, kesadaran composmetis. Tanda-tanda vital tekanan darah
120/70 mmHg, suhu 36,7oC, nadi 82 x/menit, pernafasan 20 x/menit, muka
tidak oedem, konjungtiva merah muda, sclera putih, bentuk payudara simetris,
putting susu menonjol, ASI keluar lancer, pada pemeriksaan palpasi tinggi
fundus uteri sudah tidak teraba, kontraksi keras, pengeluaran pervagina lochea
Alba, warna putih cair, luka jahitan sudah kering dan baik, tidak ada tanda-
tanda human.
c. Assessment
Ny. R umur 33 tahun P3 A0 14 hari post partum dengan nifas normal.
d. Penatalaksanaan
1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan yaitu kaedaan
ibu saat ini baik-baik saja
Td : 120/70 mmHg nadi : 82 x/menit
Suhu : 36,7o C pernafasan : 20 x/menit
Luka jahitan sudah kering dan baik
Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan
2. Mengingatkan kembali pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang
bergizi tinggi tinggi kalori tinggi protein seperti yang mengandung
karbohidrat (padi, singkong, gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu,
tempe, kacang-kacangan dan lain-lain), protein hewani
(susu,telor,ikan,daging ayam,daging sapid an lain-lain), mineral dan
166
vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak nabati (lemak jagung dan lain-
lain), lemak hewani (lemak ikan dan lain-lain).
Evaluasi : ibu bersedia untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.
3. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang kontrasepsi KB
meliputi :
a. KB pil
Kb pil yaitu kontrasepsi yang mengandung hormone progesterone dan
estrogen. cara kerjanya seperti mencegah implantasi, menekan ovulasi,
mengentalkan lendir serviks, mempengaruhi pergerakan tuba sehingga
transportasi ovum terganggu.
Keuntungan kb pil yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, dapat di
gunakan sebagai metode jangka panjang, siklus haid teratur.
Kerugiannya yaitu mual, pusing, berat badan naik, nyeri payudara, dan
perdarahan hebat.
b. KB suntik
Kb suntik yaitu kontrasepsi yang mengandung hormone progestin dan
estrogen yang di suntikan pada bokong, kb suntik terdiri dari kb suntik
1 bulan yaitu kb suntik yang mengandung hormone progestin dan
estrogen. keuntungan kb 1 bulan, menimbulkan haid yang teratur tiap
bulan, kesuburan lebih cepat kembali, setelah suntikan di hentikan,
kerugian kb 1 bulan, penyuntikan lebih sering 1 bulan sekali,
mempengaruhi ASI, dan kb suntik 3 bulan yaitu suntikan yang
mengandung hormone progestin saja, dan tidak mempengaruhi
pemberian ASI. Efek sampingnya haid tiak teratur, mual dan sakit
167
kepala, terjadi perubahan berat badan, keuntungan KB suntik 3 bulan,
penyuntikan di lakukan setiap 3 bulan, tidak mempengaruhi produksi
ASI.
c. KB kondom
Kondom adalah sarung karet tipis penutup alat kelamin laki-laki yang
menampung cairan sel mani saat pria ejakulasi, keuntungan murah,
mudah di beli, mudah di pakai sendiri, kerugian, selalu harus ada
persendiaan mengganggu kenyamanan senggama, kadang-kadang
menimbulkan alergi.
d. Kb Implant/ Susuk
Adalah kapsul batangan yang berbentuk seperti korek api, ada yang
berjumlah 2 biji untuk pemakaian 3 tahun dan 6 biji untuk 5 tahun.
Keuntungan aman digunakan setelah melahirkan dan menyusui,
mengurangi nyeri haid. Kerugian nyeri kepala dan mual, peningkatan
dan penurunan berat badan, membutuhkan tindakan bedah minor untuk
pemasangan dan pencabutan.
e. Kb IUD/ AKDR
Adalah alat kontrasepsi yang dimasukan kedalam Rahim, umumnya
berbentuk T. keuntungan metode jangka panjang 8-10 tahun, tidak
mempengatruhi ASI, kesuburan akan segera kembali jika alat
dikeluarkan, Kerugian terdapat bercak darah, dapat terjadi infeksi, efek
samping, nyeri/kram saat haid, keputihan.
168
f. Kb Tubektomi / MOW
Adalah kontrasepsi permanen pada perempuan untuk mereka yang
tidak ingin mempunyai anak lagi. Keuntungan tidak mempengaruhi
ASI, tidak mengganggu hubungan intim. Kerugian peluang untuk
mempunyai anak lagi sangat kecil, memerlukan operasi minor.
Evaluasi : ibu sudah mengerti macam-macam kontasepsi
4. Memberikan saran pada ibu KB yang cocok untuk ibu menyusui supaya
tidak mengganggu produksi ASI dan yang tidak mengandung hormonal
yaitu KB IUD.
Evaluasi : ibu mengatakan akan mendiskusikan dulu dengan suaminya.
5. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi atau
jika ada keluhan segera datang ke tenaga kesehatan.
Evaluasi : ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang
169
ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR
PADA BY. NY. R DI PUSKESMAS TARUB KABUPATEN TEGAL
D. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Normal
1. Pengkajian Data
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 19.15 wib
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subyektif
1. Biodata
Bayi Ny, R umur 0 hari jenis kelamin perempuan.
Nama Ny. R, berumur 33 tahun, agama islam, suku bangsa
jawa, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
Suami Ny. R bernama Tn. W umur 33 tahun, Suku Bangsa
Jawa, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta. alamat
di desa bulakwaru Rt 10 Rw 02 Kecamatan Tarub Kabupaten
Tegal.
2. Riwayat Kesehatan Keluarga
a. Penyakit kelainan darah
Ibu mengatakan di dalam keluarga tidak ada yang
mengalami penyakit kelainan darah seperti lemas, pusing,
kulit pucat. Konjungtiva pucat, nafsu makan turun dan
detak jantung lebih cepat (Anemia). Timbulnya rasa sakit
dan kaku pada kepala dan leher, muntah, penglihatan
170
kabur dan kejang (Hemofilia). Sakit kepala di sertai
menggigil, demam, bintik merah, di permukaan kulit,
muntah, keringat di malam hari, gampang terjadi
perdarahan seperti memarbdan mimisan (Leukimia).
b. Kelainan congenital
Ibu mengatakan di dalam keluarga tidak ada yang
mengalami kelainan congenital seperti kepala bayi tampak
lebih besar seperti ada cairan (Hidrocephalus), kepala
tampak lebih kecil dari ukuran normal (Mikrocephalus),
tidak ada tempurung kelapa (Anencephaly), tidak ada bibir
sumbing, tidak ada lubang anus (Atresia ani),
perlengketan dua jari atau lebih (Sindaktil), jumlah jari
lebih dari lima (Polisindaktil).
c. Penyakit infeksi
Ibu mengatakan di dalam keluarga tidak ada yang
mengalami penyakit keturunan seperti batuk lebih dari 2
minggu, disertai darah, demam, menggigil pada malam
hari, berat badan menurun yaitu Tuberculosis (TBC),
mual muntah, demam, nyeri ulu hati, pembesaran hati,
BAK yang berwarna kuning keruh seperti teh, kulit
tubuh dan sclera mata berwarna kuning (Hepatitis), diare
tidak sembuh-sembuh, demam, dan batuk yang
berkepanjangan, berat badan menurun drastis, kekebalan
tubuh menurun, sariawan di bagian mulut atas dan bawah
171
yang tak kunjung sembuh, Human Immunodeficiency
Virus (HIV), gatal pada genetalia, keputihan yang berbau
busuk,berwarna hijau Infeksi Menular Seksual (IMS).
d. Penyakit keturunan
Penyakit Keturunan seperti mudah lapar, mudah haus,
mudah mengantuk, sering kencing di malam hari, luka
yang sukar sembuh yaitu Diabetes Mellitus (DM),
tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, pusing ,tengkuk
terasa pegal (Hipertensi), sesak nafas saat udara dingin
dan banyak debu, pernafasan berbunyi mengik (Asma),
nyeri dada bagian atas,jantung berdebar-debar, sesak
nafas, dan mudah lelah (Jantung) .
e. Riwayat gemelly
Ibu mengatakan di dalam keluarga tidak ada yang
mempunyai bayi kembar.
3. Riwayat Kehamilan
Kehamilan ini merupakan kehamilan yang ketiga dan tidak
pernah mengalami keguguran, antenatal care (ANC) pada
trimester I ibu melakukan pemeriksaan 2x di puskesmas,
trimester II sebanyak 4x (3x di puskesmas dan 1x di dr.
SpOg), trimester III sebanyak 5x (3x di puskesmas 1x di Bpm
1x di dr SpOg), ibu mengatakan selalu mendapatkan tablet
tambah darah dan di minum 1x1 setiap malam rutin selama
172
hamil, ibu mengatakan sudah mendapatkan imunisasi TT 1x
pada tanggal 21 Agustus 2018.
4. Riwayat Penggunaan Kontrasepsi
Ibu mengatakan menggunakan KB pil, lamanya 1 tahun, tidak
ada keluhan, alasan lepas karena sedang mengkonsumsi obat
Tb, rencana yang akan datang kb suntik 3 bulan, alasan praktis.
5. Kebutuhan Sehari-hari Bayi
a) Pola Nutrisi
Ibu mengatakan bayinya hanya di berikan air susu ibu
(ASI).
b) Pola Eliminasi
Ibu mengatakan bayinya sudah buang air besar jam 17.50
wib, warna hitam, konsistensi lembek, dan bayi belum
buang air kecil.
c) Pola Istirahat
Bayi belum istirahat
d) Pola Personal Hygiene
Bayi belum dimandikan, belum ganti popok, dan belum
ganti baju.
b. Data Obyektif
Persalinan pada tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.15 wib, jenis
persalinan spontan, penolong persalinan bidan, selama proses
persalinan hanya di berikan suntik Oxytocin 10 ui pada kala III.
173
lama persalinan kala I 16 jam, kala II 15 menit, kala III 10 menit.
ketuban pecah jam 17.10 wib warna jernih, bau khas.
Segera setelah lahir dilakukan tindakan pernilaian segera setelah
lahir tangisan kuat, kulit kemerahan, gerakan aktif, mengeringkan
bayi, perawatan dan pemotongan tali pusat dan inisiasi menyusui
dini (IMD).
Pemeriksaan fisik keadaan umum baik, suhu tubuh 36,7oC, denyut
jantung 124 x/menit, respirasi 44 x/menit. Panjang badan 49 cm,
berat badan 3700 gram, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 cm,
lingkar lengan atas 11,5 cm.
Pemeriksaan pada bayi kepala mesochepal, tidak ada caput
succedenum, tidak ada cepal hematoma, sutura sudah menutup,
muka warna kemerahan, tidak ada tanda lahir, mata bentuk
simetris, tidak ada kelainan, reflek pupil aktif, hidung bentuk
normal, tidak ada nafas cuping hidung, tidak ada kelainan, mulut
dan bibir merah muda, tidak ada cyanosis, tidak ada labioskisis dan
labiopalatoskisis, telinga bentuk simetris, tidak ada kelainan, kulit
warna kemerahan, dada bentuk normal, tidak ada retraksi dinding
dada, abdomen bentuk simetris, tidak ada perdarahan tali pusat,
genetalia labia mayor menutupi labia minor, ada lubang anus,
ekstermitas atas dan bawah tidak ada polidaktil dan sindaktil, kuku
tidak pucat, dan gerakan aktif, rooting ada dan aktif, reflek graps
ada aktif, reflek sucking ada aktif, reflek moro ada aktif, tonic neek
ada aktif, reflek babynski ada aktif.
174
Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium,
pemeriksaan rontgen. Tidak di lakukan.
2. Intepretasi Data
a. Diagnosa (Nomenklatur)
Bayi Ny. R lahir spontan jenis kelamin perempuan, menangis kuat,
keadaan baik, bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit
kemerahan, dengan bayi baru lahir normal.
Data Subyektif
Ibu mengatakan kondisi bayinya baik, menyusunya kuat, menangis
tidak merintih dan tidak ada keluhan.
Data Obyektif
Keadaan umum baik, tanda-tanda vital suhu 36,5oC, denyut
jantung 124 x/menit, pernafasan 44 x/menit, bayi menangis kuat,
gerakan aktif, warna kulit kemerahan, tali pusat tidak ada
perdarahan.
b. Masalah
Tidak ada
c. Kebutuhan
Tidak ada
3. Diagnosa Potensial
Tidak ada
4. Antisipasi Penanganan Segera
Tidak ada
175
5. Intervensi
a. Lakukan pemeriksaan antropometri
b. Beritahu ibu hasil pemeriksaan fisik yang telah di lakukan
c. Berikan Vitamin K dan salep mata
d. Lakukan perawatan tali pusat
e. Pertahankan suhu tubuh bayi agar tetap hangat
f. Pastikan bayi mendapatkan ASI
g. Beritahu ibu tanda bahaya bayi baru lahir
h. Berikan imunisasi Hb 0
6. Implementasi
a. Melakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil keadaan bayi sehat dan
normal bayi kepala mesochepal, tidak ada caput succedenum, tidak ada
cepal hematoma, sutura sudah menutup, muka warna kemerahan, tidak ada
tanda lahir, mata bentuk simetris, tidak ada kelainan, reflek pupil aktif,
hidung bentuk normal, tidak ada nafas cuping hidung, tidak ada kelainan,
mulut dan bibir merah muda, tidak ada cyanosis, tidak ada labioskisis dan
labiopalatoskisis, telinga bentuk simetris, tidak ada kelainan, kulit warna
kemerahan, dada bentuk normal, tidak ada retraksi dinding dada, abdomen
bentuk simetris, tidak ada perdarahan tali pusat, genetalia labia mayor
menutupi labia minor, ada lubang anus, ekstermitas atas dan bawah tidak
ada polidaktil dan sindaktil, kuku tidak pucat, dan gerakan aktif, rooting
ada dan aktif, reflek graps ada aktif, reflek sucking ada aktif, reflek moro
ada aktif, tonic neek ada aktif, reflek babynski ada aktif
176
b. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan dengan hasil
keadaan bayi ibu saat ini sehat dan normal.
Jenis kelamin : perempuan
Suhu : 36,7o C denyut jantung : 124 x/menit
Pernapasan : 44 x/menit Berat badan : 3700 gram
lingkar kepala : 34 cm Panjang badan : 49 cm
lingkar dada : 33 cm
c. Memberikan suntikan Vitamin K pada paha kiri bayi bagian luar secara
intra muscular, dan salep mata tetracyclin pada mata kanan dan kiri.
d. Melakukan perawatan tali pusat yaitu menyiapkan kasa steril kmudian
dibersihkan tali pusat dari pangkal hingga ujung tali pusat kemudian
membungkus tali pusat dengan kassa steril tanpa tambahan apapun.
e. Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara mengganti kain yang kotor
dengan kain yang bersih dan kering, kemudian membedong bayi dan
memakaikan topi ke kepala bayi.
f. Memastikan bayi mendapat ASI segera setelah bayi lahir dari ibu
g. Memberitahu tanda bahaya bayi baru lahir yaitu bayi tidak mau menyusu,
pernafasan cepat, warna kulit pucat, bayi merintih.
h. Memberikan imunisasi HB 0 dengan dosis 0.5 cc pada bagian paha kanan
bayi bagian luar secara inta muscular di berikan 1 jam setelah Vitamin K
7. Evaluasi
a. Ibu sudah mengetahui keadaan bayibya saat ini
b. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
c. Ibu sudah mengetahui bayinya sudah di berikan vitamin K
177
d. Ibu sudah mengetahui cara perawatan tali pusat
e. Ibu sudah mengerti cara menjaga suhu tubuh bayi
f. Ibu sudah memberikan asi kepada bayinya
g. Ibu sudah mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir
h. Ibu sudah mengetahui bayinya sudah di berikan imunisasi HB 0
178
KUNJUNGAN NEONATAL KE 2 (6 HARI)
Tanggal : 31 Agustus 2018
Jam : 19.00 wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan, menyusu kuat, buang air kecil
lebih dari 6 kali, buang air besar setiap hari 1-2 kali konsistensi lembek.
b. Data Obyektif
Keadaan umum bayi baik, berat bayi 3900 gram, panjang badan 52 cm, suhu
badan 37,0oC, denyut jantung 120 x/menit, pernafasan 40 x/menit, mata tidak
ikterik, bayi menyusu kuat kebutuhan asi terpenuhi, tali pusat sudah kering dan
lepas pada tanggal 30 agustus 2018, tidak ada ruam pada kulit bayi, bayi aktif
dan tidak rewel, perut bayi tidak kembung, dalam sehari bayi buang air kecil
kurang lebih 6-7 kali, buang air besar 1-2 kali konsistensi lembek, warna
kuning kecoklatan, kebersihan, bayi dimandikan sehari 2 kali pagi dan sore
hari, ganti popok setiap kali bayi buang air kecil dan besar dan selalu di
bersihkan area genetalia sampai bokong menggunakan air dan sabun/ tisu
basah.
c. Assessment
Bayi Ny, R umur 5 hari jenis kelamin perempuan dengan bayi baru lahir
normal.
d. Penatalaksanaan
1. Memberikan kapada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu
keadaan bayi saat ini baik-baik saja
179
Suhu : 36,7oC pernafasan : 40 x/menit
Detak jantung : 120 x/menit
Evaluasi : ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan bayinya.
2. Mengingatkan kembali tanda bahaya bayi baru lahir yaitu tidak mau
menyusu, suhu tubuh naik, bayi rewel.
Evaluasi : ibu sudah mengerti tanda bahaya bayi lahir
3. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri bayi dengan cara
memandikan bayi 2 x sehari, ganti baju 2x sehari, mengganti popok setelah
bayi buang air kecil dan besar.
Evaluasi : ibu selalu menjaga kebersihan bayinya
4. Mengingatkan kembali ibu untuk selalu memberikan asi esklusif tanpa
tambahan makanan apapun kecuali obat dan vitamin
Evaluasi : ibu selalu memberikan asi dan tidak memberikan makanan
tambahan apapun.
180
KUNJUNGAN NEONATAL KE III (14 Hari)
Tanggal : 08 september 2018
Jam : 14.00 wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan, menyusu kuat .
b. Data Obyektif
Keadaan umum bayi baik, berat bayi 3900 gram, panjang badan 52 cm, suhu
badan 36,5oC, denyut jantung 120 x/menit, pernafasan 42 x/menit, mata tidak
ikterik, bayi menyusu kuat kebutuhan asi terpenuhi, bayi aktif dan tidak rewel,
perut bayi tidak kembung, dalam sehari bayi buang air kecil kurang lebih 6-7
kali, buang air besar 1-2 kali konsistensi lembek, warna kuning kecoklatan,
kebersihan, bayi dimandikan sehari 2 kali pagi dan sore hari, ganti popok setiap
kali bayi buang air kecil dan besar dan selalu di bersihkan area genetalia
sampai bokong menggunakan air dan sabun/ tisu basah.
c. Assessment
Bayi Ny. R umur 14 hari jenis kelamin perempuan dengan bayi baru lahir
normal.
d. Penatalaksanaan
a) Memberitahu kapada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu
keadaan bayi saat ini baik-baik saja
Suhu : 36,5oC pernafasan : 42 x/menit
Detak jantung : 120 x/menit
181
b) Mengingatkan kembali ibu untuk menjaga kebersihan diri bayi dengan cara
memandikan bayi 2 x sehari, ganti baju 2x sehari, mengganti popok setelah
bayi buang air kecil dan besar gunanya untuk mencegah terjadinya iritasi.
Evaluasi : ibu selalu menjaga kebersihan bayinya
c) Mengingatkan ibu untuk rutin ke posyandu untuk imunisasi bayi &
melakukan tumbuh kembang bayinya.
Evaluasi : ibu bersedia membawa bayinya ke posyandu
d) Memberitahu ibu jika terjadi sesuatu pada bayi seperti suhu badan naik/
panas, diare, menangis terus menerus .untuk segera di bawa ke tenaga
kesehatan / puskesmas terdekat untuk di berikan penanganan yang tepat.
Evaluasi : ibu mengerti penjelasan bidan.
182
CATATAN KUNJUNGAN NIFAS
Catatan kunjungan nifas yang ke-3 dan ke-4 penulis tidak melakukan pemantauan
secara langsung di karenakan sedang prektek klinik kebidanan di daerah rumah
sakit gunung djati kota Cirebon jadi penulis melakukan pemantauan lewat
telephone seluler.
Dari hasil telepon tanggal 16 oktober 2018 hasilnya adalah ibu mengatakan
keadaan ibu baik, tidak ada keluhan, pengeluaran darah berwarna putih (lochea
alba), tidak berbau, ASI keluar lancar. Dan pada bayinya keadaannya baik, tidak
ada keluhan, masih di beri ASI esklusif, istirahat cukup, dan sudah diberi
imunisasi BCG dan Polio 1 pada tanggal 4 oktober 2018.
Namun, setelah selesai praktik tepatnya pada tanggal 7 dsember 2018, penulis
mendatangi rumah Ny. R, untuk memastikan keadaan ibu dan perkembangan
bayinya. Keadaan ibu baik, tidak ada keluhan, ASI keluar lancar, luka jahitan
sudah kering, ibu rutin periksa di puskesmas. Dan keadaan bayinya baik, tidak ada
keluhan, berat badan semakin bertambah, bayinya aktif, tidak rewel, masih di
berikan ASI ibu, rutin keposyandu untuk imunisasi dan pemantauan tumbuh
kembang bayi, pada tanggal 1 november 2018, bayi di berikan imunisasi DPT 1
dan Polio 2, dan tanggal 6 desember di beri imunisasi DPT 2 dan polio 3.
183
BAB IV
PEMBAHASAN
Setelah melakukan Asuhan Kebidanan Komprehensif dengan
Faktor Resiko Tinggi Riwayat Tuberculosis pada Ny. R umur 33
tahun G3P2A0 di Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2018.
Penulis akan membahas antara teori yang diuraikan sebelumnya
dengan membandingkan antara teori dan praktek serta
penatalaksanaan kasus dengan konsep teori yang diuraikan pada BAB
II, dengan harapan dapat memperoleh gambaran secara nyata dan
sejauh mana asuhan kebidanan secara komprehensif yang telah
diberikan.
Pada penatalaksanaan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan
konsep dasar asuhan kebidanan yang sesuai teori yang ada.
Menerangkan manajemen kebidanan menurut Varney terdiri atas 7
langkah yang berurutan yaitu pengkajian, interpretasi data, diagnosa
potensial, antisipasi penanganan segera, intervensi, implementasi dan
evaluasi. Selain itu catatan manajemen kebidanan juga dapat
diterapkan dengan menggunakan metode SOAP (Subyektif, Obyektif,
Assesment, Planning) yang merupakan catatan bersifat sederhana,
jelas, logis dan singkat. Adapun uraian yang ditemukan
pembahasannya akan dijelaskan satu persatu dimulai dari kehamilan,
pada saat persalinan dan pada saat nifas.
184
A. Kehamilan
1. Pengkajian Data
Menurut Hani (2012), Pada langkah pertama ini ditemukan semua
informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan
dengan kondisi klien. Pengkajian data wanita hamil terdiri atas anamnesa,
pemeriksaan klien. Pengkajian data wanita terdiri atas anamnesa,
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
a. Data Subyektif
Menurut Mufdilah (2014), data subyektif adalah data yang didapatkan
dari klien sebagai suatu pendapat terhadap situasi dan kejadian.
1) Identitas
a) Nama
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), nama
lengkap ibu, termasuk nama panggilannya. Nama merupakan
identitas khusus yang membedakan seseorang dengan orang lain.
Hendaknya klien dipanggil sesuai dengan nama panggilan yang
biasa baginya atau yang disukainya agar klien merasa nyaman serta
lebih mendekatkan hubungan interpersonal bidan dengan klien.
Dalam praktek didapatkan ibu bernama Ny. R dan suami
bernama Tn. W. Dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara kasus dengan teori.
b) Umur
185
Menurut Manuba (2012), yang menjadi faktor resiko ibu hamil
adalah umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.
Sedangkan, usia ibu hamil yang termasuk usia reproduksi sehat
adalah usia 20-35 tahun. Alasan usia tersebut dikatakan reproduksi
sehat karena usia dibawah 20 tahun, Rahim dan panggul sering
kalli belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akhirnya, ibu hamil
pada usia itu mungkin mengalami persalinan lamaatau macet, atau
gangguan lainnya karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas
dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sedangkan pada umur
35 tahun atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun, akibatnya ibu
hamil pada usia itu mempuyai anak cacat, persalinan lama dan
perdarahan.
Pada kasus ini bernama Ny. R umur 33 tahun tergolong pada
umur normal/produktif atau umur yang sehat pada masa kehamilan.
Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan antara kasus
dengan teori.
c) Agama
Menurut Anggraini (2010), diperlukan untuk mengetahui
keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau mengarahkan
pasien dalam berdoa.
Dalam kasus ini Ny. R menganut agama Islam dan dari data
yang didapatkan tidak terdapat tradisi keagamaan ditempat tinggal
Ny. R yang merugikan kehamilannya dengan agama yang dianut.
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara
teori dan kasus.
186
d) Suku Bangsa
Menurut Anggraini (2010), berpengaruh pada adat istiadat atau
kebiasaan sehari – hari.
Pada kasus Ny. R suku bangsanya adalah jawa dan sudah
diberikan asuhan kebidanan sesuai sosial budaya Ny. R. Dengan
demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara kasus
dengan teori.
e) Pendidikan
Menurut Sulistyawati (2010), pendidikan sebagai dasar bidan
untuk menentukan metode yang paling tepat dalam penyampaian
informasi. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi daya
tangkap dan tanggap pasien terhadap instruksi atau informasi yang
diberikan bidan pada pasien.
Dalam pengkajian data dalam hal pendidikan penulis
memperoleh data bahwa pada Ny. R berpendidikan SD. Namun
pasien dapat menangkap atau memahami informasi yang telah
diberikan oleh Bidan karena berdasarkan pengalaman kehamilan
yang lalu.
f) Pekerjaan
Menurut Anggraini (2010), gunanya untuk mengukur tingkat
social ekonominya, karena ini juga mempengaruhi dalam gizi
pasien tersebut.
Pada kasus Ny. R pekerjaan yang dimiliki yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta
187
dengan penghasilan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara
kasus dengan teori.
g) Alamat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), alamat
memberi gambaran mengenai jarak dan waktu yang ditempuh
pasien menuju pelayanan kesehatan, serta mempermudah
kunjungan rumah bila diperlukan.
Ibu mengatakan beralamat di Desa Bulakwaru RT 10 RW 02
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Ny. R melakukan pemeriksaan
kehamilannya secara rutin ke pelayanan kesehatan, penulis juga
melakukan kunjungan rumah dalam rangka melakukan asuhan
kebidanan pada masa hamil sampai masa nifas, sehingga pada
kasus ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik.
2) Keluhan Utama
Menurut Sulistyawati (2012), Untuk mengetahui masalah yang
dihadapi yang berkaitan dengan masalah hamil, sehingga dapat secara
dini terdeteksi.
Pada pengkajian yang dilakukan pada Ny. R didapatkan hasil
bahwa ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan. Dalam hal
ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.
3) Riwayat Obstetri dan Ginekologi
Menurut Anggraini (2010), riwayat obstetric diperlukan untuk
mengetahui berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah
188
anak, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan dan
keadaan nifas yang lalu.
a) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu
Menurut Manuaba (2012), riwayat obstetri dan ginekologi
untuk mengetahui riwayat persalinan dan kehamilan yang lalu.
Jika riwayat persalinan lalu buruk maka kehamilan saat ini harus
diwaspadai. Jumlah anak ideal hanya sampai kehamilan ketiga,
sudah termasuk grandemultipara harus diwaspadai perdarahan post
partum.
Pada kasus Ny. R, ibu mengatakan waktu anak pertama
kehamilanya normal, persalinan dengan umur kehamilan 36
minggu, berat badan 3100 gram, jenis persalinan spontan,
penolong persalinan Bidan, dengan nifas normal. Pada anak kedua
kehamilan normal, persalinan spontan, penolong persalinan Bidan,
dengan nifas normal. Jadi pada kasus ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b) Riwayat kunjungan Antenatal Care/Kehamilan sekarang
Menurut Walyani (2015), kunjungan Antenatal Care minimal
satu kali pada trimester pertama (K1), satu kali pada trimester dua
dan dua kali pada trimester ketiga (K4). Menurut Pantikawati
(2010), kunjungan antenatal care minimal dilakukan 4 kali, yaitu
pada kunjungan trimester pertama (0-14 minggu) dilakukan 1 kali
kunjungan. Pada kunjungan trimester kedua (14-28 minggu)
dilakukan 1 kali kunjungan serta pada kunjungan trimester ketiga
(29-36 minggu) dilakukan 2 kali kunjungan.
Dari data yang didapat dari buku kesehatan ibu dan anak
milik Ny. R selama hamil melaksanakan antenatal care secara
teratur. Pada trimester I ibu melakukan pemeriksaan 2x, trimester
189
II 4x, trimester III sebanyak 5x. Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tujuan pemberian imunisasi TT
adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum, efek
samping vaksin TT yaitu nyeri, kemerah-merahan dan bengkak
untuk 1-2 hari pada tempat penyuntikan ini akan sembuh tanpa
perlu pengobatan.
Dalam hal ini ibu mendapatkan imunisasi TT, imunisasi yang
diberikan belum sesuai karena pasien baru imunisasi satu kali
pada tanggal 21 agustus 2018 di usia kehamilan 40 minggu,
sehingga ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tablet fe mengandung 250 mg
Sulfat Ferrous 0,25 mg asam folat yang diikat dengan laktosa.
Tujuan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan nifas,
karena pada masa kehamilan kebutuhannya meningkat seiring
dengan pertumbuhan janin.
Pada kasus Ny. R sudah mendapatkan tablet tambah darah 1x
250 mg selama memeriksakan kehamilannya yaitu 162 tablet.
Sehingga tidak ada kesenjangan anatara teori dan kasus.
c) Riwayat Haid
Dari data yang didapat pada kasus Ny. R pertama kali
menstruasi (menarche) pada usia 12 tahun, siklus 28 hari,
lamanya 6 hari, banyaknya 3 kali ganti pembalut dalam sehari,
dan tidak merasakan nyeri baik sebelum atau sesudah
mendapatkan menstruasi, Hari Pertama Haid Terakhir 16
190
november 2017. Serta ibu mengalami keputihan selama 3 hari,
tidak gatal, warnanya jernih, bau khas.
Menurut Manuaba (2010), bahwa idealnya lama menstruasi
terjadi selama 4-7 hari. Bayaknya pemakaian pembalut antara 1-3
kali ganti pembalut dalam sehari, dan adanya disminorea
disebabkan oleh faktor anatomis maupun adanya kelainan
ginekologi.
Pada pengakajian yang didapatkan pada Ny. R bahwa
menarche pada usia 12 tahun, lama haid 7 hari, dalam sehari ganti
pembalut sebanyak 3 kali dan tidak ada gangguan saat haid.
Sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
d) Riwayat Kontrasepsi/KB
Menurut Anggraini (2010), untuk mengetahui apakah pasien
pernah ikut keluarga berencana dengan kontrasepsi jenis apa,
berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi
serta rencana selanjutnya akan menggunakan kontrasepsi apa.
Riwayat penggunaan kontrasepsi Ny. R, mengatatakan
pernah memakai alat kontrasepsi pil dan alasan berhenti kerena
sedang mengkonsumsi obat tuberculosis. Dan rencana yang akan
datang ibu mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi
suntik, karena lebih praktis. Dengan demikian antara teori dan
kasus tidak ada kesenjangan.
4) Riwayat Kesehatan
191
Menurut Manuaba (2010), bahwa riwayat kesehatan perlu dikaji
karena jika terdapat cacat lahir perlu dilakukan evaluasi lebih
mendalam, dan adanya hamil kembar sering bersifat menurun.
Menurut Sofian (2011), Pada umumnya penyakit paru-paru tidak
mempengaruhi kehamilan, persalinan dan nifas, kecuali penyakitnya
tidak terkontrol, berat dan luas di sertai sesak dan hipoksia. Walaupun
kehamilan menyebabkan sedikit perubahan pada system pernafasan,
karena uterus yang membesar dapat mendorong diafragma dan paru-
paru ke atas serta sisa dalam udara kurang, namun penyakit tersebut
tidak selalu menjadi lebih parah.
Pada kasus Ny. R sebelum kehamilan Ny. R telah menderita
penyakit tuberculosis namun sekarang sudah sembuh, sehingga pada
Ny. R di kehamilan ini dengan riwayat tuberculosis.
Menurut Suhardjo (2010), penyakit infeksi hepatitis pada
kehamilan dapat meningkatkan kelahiran premature, infeksi neonatus
atau tertularnya hepatitis dari ibu ke bayi ditularkan secara vertikal
melalui penelanan cairan ibu yang terinfeksi peripartum, termasuk air
susu ibu. Infeksi neonatal biasanya bisa dicegah dengan penapisan
prenatal dengan globulin imun hepatitis segera sesudah kelahiran.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit infeksi seperti kuning pada mata dan
kulit, demam, mual, muntah, dan buang air kecil berwarna kuning
pekat seperti teh (Hepatitis B), dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
192
Menurut J. Leveno (2013), penyakit infeksi Human
Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) dapat menyebabkan komplikasi
kehamilan yaitu persalinan preterm, hambatan pertumbuhan janin, dan
lahir mati, dikaitkan dengan infeksi pada ibu. Penularan terjadi pada
periode peripartum bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dan tidak
diobati akan terinfeksi.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya, dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit infeksi seperti diare, sariawan tidak
kunjung sembuh, muncul ruam pada kulit, berat badan menurun
drastic dan kekebalan tubuh menurun yaitu Human Immunodeficiency
Virus (HIV/AIDS), dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), penyakit menular seksual dapat
menimbulkan morbiditas dan mortalitas terhadap ibu maupun bayi
yang dikandungnya.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit infeksi seperti keputihan yang berbau
busuk, berwarna kehijauan dan gatal pada daerah genetalia yaitu
Infeksi Menular Seksual (IMS), sehingga tidak ada kesenjangan
anatara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), diabetes mellitus merupakan
gangguan metabolisme yang ringan, tetapi hiperglikemia ringan tetap
dapat memberikan penyulit pada ibu berupa preeklampsia,
193
polihidramnion, infeksi saluran kemih, persalinan section caesarea,
trauma persalinan akibat bayi besar.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti mudah haus, mudah
lapar, sering buang air kecil di malam hari yaitu diabetes mellitus,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), hipertensi dalam kehamilan
adalah hipertensi terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu,
selama persalinan dan dalam 48 jam pasca persalinan, kenaikan pada
diastolik ≥ 90 mmHg pada 2 pengukuran berjarak 1 jam atau lebih.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti sakit kepala, tekanan
darah lebih dari 140/ 90 mmHg yaitu hipertensi, sehinnga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), kehamilan yang disertai penyakit
jantung selalu saling mempengaruhi karena kehamilan memberatkan
penyakit jantung dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan janin dalam rahim.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti nyeri dada bagian kiri
atas, jantung berdebar – debar, sesak nafas, dan mudah lelah yaitu
jantung, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), kehamilan bersama dengan mioma
uteri hanya mungkin terjadi bila miomanya dalam situasi mioma uteri
194
intramural, mioma uteri subserosa, mioma uteri yang bertangkai.
Pengaruh mioma uteri pada kehamilan bisa terjadi infertilitas bila
menutupi lumen tuba falopi, mengganggu tumbuh kembang hasil
konsepsi yang telah berimplantasi (terjadi abortus, persalinan
prematur) karena terjadi vaskularisasi sehingga plasenta tidak mampu
memberi nutrisi yang cukup.
Pada kasus ini, Ny. R mengatakan tidak pernah dan tidak sedang
menderita penyakit yang dioperasi seperti mioma uteri, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sofian (2011), kehamilan ganda atau hamil kembar
adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih di sebabkan oleh faktor
keturunan.
Pada kasus Ny. R mengatakan dalam keluarga tidak ada yang
mempunyai riwayat bayi kembar, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
5) Kebiasaan
Menurut Kusmiyati (2009), kebiasaan minum jamu merupakan
salah satu kebiasaan yang beresiko bagi wanita hamil karena efek
minum jamu dapat membahayakan tumbuh kembang janin seperti
menimbulkan kecacatan, abortus, berat badan lahir rendah, partus
prematurus, asfiksia neonatorum, kelainan ginjal dan jantung janin,
sedangkan efek pada ibu dapat menyebabkan keracunan, kerusakan
jantung, ginjal, serta perdarahan. Alkohol yang dikonsumsi ibu hamil
dapat membahayakan jantung ibu hamil dan merusak janin, termasuk
195
menimbulkan kecacatan dan kelainan pada janin dan menyebabkan
kelahiran premature. Efek pemakaian alkohol dalam kehamilan adalah
pertumbuhan janin terhambat, kecacatan, kelainan jantung dan
kelainan neonatal.
Kebiasaan merokok pada ibu hamil menimbulkan efek yang
membahayakan bagi janin seperti kelahiran berat badan bayi rendah,
persalinan preterm, kematian perinatal, selain mempunyai efek yang
membahayakan janin juga membahayakan ibu berkaitan dengan
penyakit paru, jantung, hipertensi, kanker paru.
Dalam kasus ini Ny. R tidak mempunyai kebiasaan minum jamu,
mengkonsumsi alkohol, merokok, sehingga antara teori dan kasus
tidak ada kesenjangan.
6) Kebutuhan sehari-hari
a) Pola Nutrisi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
makan sebelum hamil umumnya 3x perhari, komposisi berupa nasi
atau penggantinya dengan porsi 1 piring makan dan lauk pauk
bervariasi, dan buah – buahan. Perubahan selama hamil kebutuhan
kalori meningkat yaitu 300 kalori per hari. Ibu hamil seharusnya
mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup protein, vitamin
dan zat besi. Kelebihan karbohidrat, gula dan garam akan
menyebabkan janin tumbuh terlalu besar dan juga berpotensi terjadi
preeklamsia, asupan gizi harus seimbang.
196
Menurut Arisman (2010), kebutuhan gizi ibu selama hamil
meningkat karena selain diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
gizi ibu juga diperlukan untuk janin yang dikandungnya.
Pemenuhan gizi selama hamil juga diperlukan untuk persiapan ASI
serta tumbuh kembang bayi.
Menurut Sulistyawati (2013), frekuensi makan akan memberi
petunjuk tentang seberapa banyak asupan makanan yang
dikonsumsi ibu. Jumlah makan per hari memberikan volume atau
seberapa banyak makanan yang ibu makan dalam waktu satu kali
makan.
Pada kasus ini penulis memperoleh data bahwa Ny. R sebelum
hamil ataupun selama hamil setiap hari makan 3 kali sehari dengan
porsi satu piring yang terdiri dari nasi, lauk dan sayur, tidak ada
pantangan makan dan tidak ada gangguan dalam pola makan,
sehingga ada kesenjangan dengan teori Widatiningsih dan Tungga
Dewi karena Ny. R selama hamil makan 3x per hari tidak ada
peningkatan dalam frekuensi/ jumlah makan perhari dan kebutuhan
kalorinya kurang mencukupi dalam sehari.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), jumlah
kebutuhan minum perhari orang dewasa ataupun sebelum hamil
yaitu 8 gelas per hari atau 2 liter. Kebutuhan air adalah 30 ml/kg
berat badan, jika berat badan 60 kg, maka kebutuhan cairan sekitar
1800 ml, jenis minuman bisa air putih, teh, atau susu. Perubahan
selama hamil, kebutuhan cairan ibu hamil bertambah 300 ml.
197
Hindari minuman bersoda, batasi minum kopi, sebaiknya
mengkonsumsi susu untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang
meningkat selama hamil.
Pada kasus ini penulis memperoleh data bahwa Ny. R sebelum
hamil 6-7 gelas /hari, selama hamil 6- 8 gelas perhari jenisnya air
putih, susu dan tidak ada gangguan pada pola minum, sehingga
tidak ada kesenjangan dengan teori Widatiningsih dan Tungga
Dewi dengan kasus.
b) Pola Eliminasi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
buang air besar perhari dikatakan lancar apabila teratur, misalnya
sehari 1- 2 kali, sehari 1 kali, atau 2 hari sekali hingga 3 hari sekali,
jika lebih dari 3 hari perlu diwaspadai, selain itu juga tidak ada
keluhan/ masalah seperti diare, feses keras. Perubahan selama
hamil bisa terjadi konstipasi akibat pengaruh hormone
progesterone dan relaksin yang menurunkan tonus dan motilitas
usus (sehingga penyerapan zat makanan menjadi lambat).
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil ataupun
selama hamil setiap hari buang air besar sebanyak 1-2 kali perhari,
warna kuning kecoklatan, konsistensi lembek dan tidak ada
gangguan pada buang air besar, sehingga dalam kasus ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
buang air kecil perhari dikatakan normal yaitu 4- 7 kali perhari,
warna urine yang baik yaitu jernih yang menandakan kecukupan
198
cairan dan tidak ada keluhan yang dirasakan. Jika urine berwarna
kuning dan pekat menunjukkan kekurangan intake cairan.
Perubahan selama hamil bisa terjadi peningkatan frekuensi
mikturisi dari kondisi sebelum hamil karena berkurangnya
kapasitas kandung kemih akibat tertekan oleh pembesaran uterus.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil buang air
kecil sebanyak 5-7 kali perhari dan selama hamil ada perubahan
yaitu buang air kecil sebanyak 6-8 kali perhari, warna kuning jernih
dan tidak ada gangguan pada buang air kecil, sehingga dalam kasus
ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
c) Pola istirahat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017 ), pola
istirahat yang baik untuk ibu hamil yaitu tidur siang kurang lebih 1
jam, tidur malam kurang lebih 8 jam.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil ataupun
selama hamil istirahatnya cukup yaitu tidur siang1- 2 jam dan tidur
malam 6-8 jam dan tidak ada gangguan pada istirahatnya, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d) Aktifitas
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), aktivitas
fisik yang tergolong ringan saat melakukan aktivitas fisik tidak
merasa terengah- engah atau jantung berdetak lebih kencang dari
biasanya, tubuh juga tidak membakar banyak kalori menjadi energi
seperti memasak, mencuci, menyapu, jalan – jalan santai.
199
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil melakukan
aktivitas seperti menyapu, memasak, mencuci, mengepel. Dan
selama hamil melakukan aktivitas seperti menyapu dan memasak,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
e) Pola personal hygiene (PH)
Menurut Kusmiyati (2009), wanita perlu mempelajari cara
membersihkan alat kelamin yaitu dengan gerakan dari depan
kebelakang setiap kali selesai buang air kecil atau buang air besar
dan mengeringkan vagina/ alat kelamin menggunakan tisu, lap atau
handuk yang bersih.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), mandi yang
baik frekuensinya 1-2 kali sehari, keramas 2–3 kali seminggu, ganti
pakaian (termasuk pakaian dalam) minimal 2 kali sehari, gosok gigi
2- 3 kali sehari.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil ataupun
selama hamil mandi 2 kali dalam sehari, keramas 2- 3 kali
seminggu, ganti pakaian 2 kali sehari, gosok gigi 3 kali sehari,
sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
f) Pola seksual
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
seksual dipengaruhi faktor antara lain yaitu usia, lamanya
200
pernikahan, kondisi kesehatan, hubungan seksual pasangan yang
sehat adalah 1-3 kali dalam seminggu. Perubahan selama hamil
pada trimester ke tiga abdomen semakin besar dan rasa tidak
nyaman muncul dan hasrat seksual menurun.
Menurut Hani (2011), pola hubungan seksual, frekuensi
berhubungan, kelainan dan masalah seksual.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sebelum hamil pola
seksualnya yaitu kalau suaminya pulang satu minggu 2x,
sedangkan selama hamil pola seksualnya kalau suami pulang satu
minggu 1x.sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
7) Riwayat Psikologi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), kehamilan ini
diharapkan/ tidak oleh ibu dan suami, serta respon dan dukungan
keluarga terhadap kehamilan ini. Setiap kehamilan hendaknya
diharapkan oleh ibu maupun suami dan keluarga.
Menurut Sulistyawati (2012), adanya beban psikologis yang
ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan
bayi yang nantinya akan terlihat ketika bayi lahir.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan merasa senang dengan
kehamilannya saat ini. Suami dan keluarga juga merasa senang
dengan kehamilannya, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
8) Riwayat Sosial Ekonomi
201
Menurut Sulistyawati (2012), tingkat sosial ekonomi sangat
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologi ibu hamil,
pada ibu hamil dengan tingkat sosial ekonomi yang baik, otomatis
akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologi yang baik pula.
Sementara pada ibu hamil dengan kondisi ekonomi yang lemah maka
akan mendapatkan banyak kesulitan, terutama masalah pemenuhan
kebutuhan primer.
Pada kasus Ny. R tanggung jawab perekonomian ditanggung oleh
suami dengan penghasilan mencukupi dan pengambilan keputusan
ditentukan oleh suami dan istri. Dan dengan demikian tidak terdapat
kesenjangan antara teori dengan kasus.
9) Data Perkawinan
Menurut Sulistyawati (2012), perkawinan ini penting untuk di
kaji karena data ini akan mendapatkan gambaran mengenai suasana
rumah tangga pasangan.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), status
perkawinan, termasuk pernikahan ini yang keberapa dan lamanya
menikah.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan status perkawinannya sah sudah
terdaftar di Kantor Urusan Agama, ini adalah perkawinan yang
pertama dan lama perkawinannya yaitu 11 tahun dan usia saat
menikah umur 22 tahun, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
10) Data spiritual
202
Menurut Astuti (2012), data spiritual klien perlu ditanyakan
apakah keadaan rohaninya saat itu sedang baik atau sedang stress
karena suatu masalah. Wanita hamil dan keadaan rohaninya sedang
tidak stabil, hal ini akan mempengaruhi terhadap kehamilannya.
Kebutuhan spiritual mempertahankan atau mengembalikan keyakinan
dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan
maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa
percaya dengan Tuhan.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan rajin sholat, selalu berdoa untuk
keluarga, ibu dan janinnya, sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
11) Data Sosial Budaya
Menurut Marmi (2011), ada beberapa kebiasaan adat istiadat yang
dapat merugikan kesehatan ibu hamil. Tenaga kesehatan harus dapat
menyiapkan hal ini dengan bijaksana jangan sampai menyinggung
“kearifan lokal” yang sudah berlaku di daerah tersebut.
Pada kasus ini, ibu mengatakan tidak percaya adat istiadat
setempat seperti membawa gunting agar terhindar dari gangguan
makhluk halus. sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
12) Data Pengetahuan Ibu
Menurut Pantikawati (2010), untuk mengetahui seberapa jauhnya
pengetahuan ibu tentang masalah kehamilan. Hal ini dibutuhkan agar
ibu tahu tentang hal – hal yang berkaitan dengan kehamilannya.
203
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tingkat
pengetahuan ibu meliputi hal – hal apa yang sudah diketahui ibu, dan
hal – hal apa yang ingin diketahui ibu.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan sudah mengetahui persiapan
persalinan dan ibu sudah mengetahui cara merawat bayi dan
memandikan bayi. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b. Data Obyektif
Menurut Sulistyawati (2012), untuk melengkapi data dalam
menegakkan diagnosis, maka kita harus melakukan pengkajian, data
objektif melalui pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan
pemeriksaan yang dilakukan secara berurutan.
1) Pemeriksaan fisik
a) Keadaan umum
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), keadaan
umum dikatakan baik jika pasien memperlihatkan respons yang
adekuat terhadap stimulasi lingkungan dan orang lain, serta secara
fisik pasien tidak mengalami kelemahan. Klien dimasukkan
dalam kriteria lemah ini jika kurang atau tidak memberikan
respons yang baik terhadap lingkungan dan orang lain, dan pasien
sudah tidak mampu lagi untuk berjalan sendiri.
Dari data yang diperoleh pada kasus Ny. R keadaan umum
baik karena pasien masih mampu berjalan sendiri dan mampu
memberikan respon saat melakukan kunjungan antennal care,
204
sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
b) Kesadaran
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), kesadaran
composmentis yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat
menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk
mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya
kesadaran composmentis atau kesadaran maksimal sampai dengan
koma atau pasien tidak dalam keadaan sadar.
Dari data yang diperoleh pada kasus Ny. R kesadaran
composmentis hal tersebut dapat terlihat ketika dalam
pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan dari bidan
dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
c) Tanda – tanda vital
Menurut Sulistyawati (2012), pada pemeriksaan tanda –
tanda vital didapat tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu.
Menurut Hani (2011), tekanan darah ibu hamil sistolik tidak
boleh mencapai 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg.
Perubahan sistolik 30 mmHg dan diastolik diatas tekanan darah
205
sebelum hamil, menandakan toxemia gravidarum atau keracunan
kehamilan.
Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Hidayah, dkk (2011), suhu dikaji untuk mengetahui
tanda – tanda infeksi, batas normal 36,5- 37,50C.
Pada kasus Ny. R didapatkan suhu tubuh normal yaitu
36,50C. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), nadi dikaji untuk mengetahui
denyut nadi pasien yang dihitung selama 1 menit, batas
normalnya 60-80 x/menit.
Pada kasus Ny. R didapatkan nadi 80 x/menit, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), pernafasan dikaji untuk
mengetahui frekuensi pernapasan pasien yang dihitung selama 1
menit, batas normal yaitu 18-24 x/menit.
Pada kasus Ny. R pernafasan normal yaitu 20 x/menit,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d) Tinggi badan
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Ibu hamil
dengan tinggi badannya kurang dari 145 cm, tergolong risiko
tinggi karena kemungkinan besar memiliki panggul yang sempit.
Pada kasus Ny. R didapatkan tinggi badan 151 cm, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
206
e) Berat badan
Menurut Sulistyawati (2012), pada wanita hamil terjadi
penambahan berat badan yang dianjurkan 4 kg pada kehamilan
trimester I yaitu 0,5 kg/minggu, pada kehamilan trimester II
sampai trimester III totalnya sekitar 15- 16 kg.
Pada kasus Ny. R di dapatkan berat badan ibu sebelum hamil
60 kg, sekarang 67 kg, terjadi kenaikan berat badan 7 kg,
sehingga ada kesenjangan dengan teori Sulistyawati karena
kenaikan berat badan Ny. R kurang dari 15 – 16 kg selama TM II
dan III.
f) Lingkar Lengan Atas
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Standar
minimal ukuran lingkar lengan atas pada wanita dewasa atau usia
reproduksi adalah 23,5 cm. Jika ukuran lingkar lengan atas
kurang dari 23,5 cm maka tergolong risiko terhadap kekurangan
energi kronis.
Pada kasus Ny. R didapatkan lingkar lengan atas 27 cm,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
g) Pemeriksaan status present dari kepala sampai kaki
Menurut Pantikawati (2010), dalam pemeriksaan fisik ini
dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sesuatu yang
dapat membahayakan kehamilan seperti oedema pada wajah,
ikterus dan anemia pada mata, bibir pucat, tanda – tanda infeksi
pada telinga, adanya pembesaran kelenjar tyroid dan limfe,
207
adanya retraksi dinding dada, pembesaran hepar dan kelainan
pada genetalia, anus dan ekstermitas.
Pada kasus Ny. R hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
bentuk kepala mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, tidak
berketombe, muka tidak pucat dan tidak oedem, mata simetris,
penglihatan baik, konjungtiva tidak anemis, sclera tidak ikterik,
hidung bersih, tidak ada pembesaran polip, lendir tidak ada
infeksi sinusitis, mulut dan bibir lembab, tidak ada stomatitis,
tidak ada caries pada gigi, gusi tidak epulis, bentuk telinga
simetris, bersih, pendengaran baik, leher tidak ada pembesaran
kelenjar tyroid, dan tidak ada pembesaran vena jugularis. Aksila
tidak ada pembesaran kelenjar limfe, pernafasan teratur bentuk
dada normal, tidak ada retraksi dinding dada, mamae simetris,
abdomen tidak ada luka bekas operasi, genetalia kebersihan
terjaga tidak ada varices, tidak oedem, tidak ada kelenjar
bartolini, anus tidak ada hemoroid, dan extremitas tidak oedem,
kuku tidak pucat dan tidak ada varices. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
2) Pemeriksaan obstetrik
a) Inspeksi
Menurut Suryati (2011), inspeksi adalah memeriksa dengan
cara melihat atau memandang untuk melihat keadaan umum
klien, gejala kehamilan dan adanya kelainan.
208
Menurut Prawirohardjo (2010), pada dinding perut akan
terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam dan kadang –
kadang juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan
ini dikenal dengan nama striae gravidarum. Pada banyak
perempuan kulit digaris pertengahan perutnya (linea alba) akan
berubah menjadi hitam kecoklatan yang di sebut dengan linea
nigra. Selain pada areola dan daerah genetalia juga akan terlihat
pigmentasi yang berlebihan.
Hasil pemeriksaan obstetrik Ny. R didapatkan pemeriksaan
inspeksi pada payudara yaitu simetris, puting susu menonjol,
kolostrum/ASI belum keluar, kebersihan payudara bersih, pada
abdomen tidak ada bekas luka operasi, tidak ada striae
gravidarum, ada linea nigra, pembesaran uterus sesuai dengan
umur kehamilan. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik
secara inspeksi adalah normal, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b) Palpasi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tinggi
fundus uterus berdasarkan perabaan pada usia kehamilan 12
minggu fundus teraba di antara 1- 2 jari di atas simpisis, usia
kehamilan 16 minggu fundus teraba di antara simpisis- pusat ,
usia kehamilan 20 minggu fundus dapat teraba 2- 3 jari di bawah
pusat, pada usia kehamilan 24 minggu fundus teraba tepat di
umbilicus, usia kehamilan 28 minggu teraba 2- 3 jari di atas
209
pusat, usia kehamilan 32 minggu, fundus teraba di pertengahan
antara umbilicus dan prosesus xyphoideus, usia kehamilan 36
minggu fundus teraba 3 jari di bawah prosesus xyphoideus, usia
kehamilan 40 minggu, fundus teraba di pertengahan antara
umbilicus dan proesesus xyphoideus.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterusnya
pertengahan antara umbilicus dan proesesus xyphoideus, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Leopold I
untuk menentukan bagian teratas perut ibu, Leopold II untuk
menentukan bagian janin yang ada di sebelah kanan dan kiri ibu,
Leopold III untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah
uterus, Leopold IV untuk menentukan bagian bawah janin sudah
masuk panggul atau belum. Pada primigravida usia kehamilan 37
minggu kepala harusnya sudah masuk panggul, pada multigravida
mungkin kepala baru masuk panggul saat inpartu dikarenakan
tonus otot abdomen yang sudah mengendur tidak cukup bisa
menekan kepala janin untuk memasuki panggul.
Setelah dilakukan pemeriksaan palpasi pada Ny. R
didapatkan Leopold I (menggunakan teknik jari) yaitu mulai raba
dari prossesus xypoideus teraba bulat, kenyal, tidak melenting
yaitu bokong. Leopold II, sebelah kiri ibu teraba bagian kecil-
kecil janin yaitu ekstremitas. Sebelah kanan ibu teraba panjang
seperti papan ada tahanan yaitu punggung. Leopold III, teraba
210
bagian bulat, keras, melenting yaitu kepala. Leopold IV, bagian
terendah janin sudah masuk pintu atas panggul/ divergen.
Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sofian (2011), mengukur tinggi fundus uteri dari
simpisis, usia kehamilan 22- 28 minggu TFU 24-25 cm diatas
simfisis, usia kehamilan 28 minggu TFU 26,7 cm di atas simfisis,
usia kehamilan 30 minggu TFU 29,5-30 cm di atas simfisis, usia
kehamilan 32 minggu TFU 29,5-30 cm di atas simfisis, usia
kehamilan 34 minggu TFU 31 cm di atas simfisis, usia kehamilan
36 minggu TFU 32 cm diatas simfisis, usia kehamilan 38 minggu
TFU 33 cm di atas simfisis, usia kehamilan 40 minggu TFU 37,7
cm di atas simfisis.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterinya 33 cm,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Mc. Donald, tinggi fundus uterus 33 cm. Taksiran
berat badan janin = (tinggi fundus uterus – N) x 155 yaitu N bila
11 kepala sudah masuk pintu atas panggul dan 12 bila kepala
belum masuk pintu atas panggul.
Teori tinggi fundus uteri dari simpisis didapatkan tinggi
fundus uterus 33 cm, untuk mengetahui taksiran berat badan janin
= (33 - 11) = 22 x 155 = 3.410 gram. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
c) Auskultasi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Denyut
jantung janin umumnya sudah jelas terdengar dengan Doppler
mulai usia kehamilan 16 minggu. Nilai normal DJJ antara 120-
211
160 x/menit teratur dengan punctum maksimum 1 terletak sesuai
dengan punggung janin.
Pada pemeriksaan detak jantung janin pada Ny. R adalah 138
x/menit. Pada kasus Ny. R dinyatakan denyut jantung janin
hasilnya normal. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori
dengan kasus.
d) Perkusi
Menurut Manuaba (2010), perkusi yaitu pemeriksaan fisik
dengan mengetuk daerah tertentu dari bagian tubuh dengan jari
atau alat, guna kemudian mendengar suara resonansinya dan
meneliti resistensinya. Menggunakan alat reflek hammer yang
diketukkan pada lutut dengan bergantian.
Pada pemeriksaan perkusi Ny. R dengan cara bergantian
hasilnya positif. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori
dengan kasus.
e) Pemeriksaan panggul
Menurut Marmi (2011), pemeriksaan panggul luar tidak
dapat dipergunakan untuk penilaian apakah persalinan dapat
berlangsung secara biasa atau tidak, walaupun ukuran – ukuran
luar dapat memberi petunjuk pada kita kemungkinan panggul
sempit. Ukuran-ukuran panggul luar yaitu distansia spinarum
jarak antara spina illiaca anterior superior kiri dan kanan (23-26
cm), distansia cristarum (26-29 cm), konjunggata eksterna (18-20
cm) dan ukuran lingkar panggul (80-90 cm).
212
Pada kasus Ny. R tidak dilakukan pemeriksaan panggul luar
karena ibu sudah pernah melahirkan dan diperiksa saat kehamilan
pertama dan kedua keadaan normal, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
f) Pemeriksaan penunjang
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017),
Pemeriksaan Laboratorium meliputi Kadar hemoglobin pada
kunjungan pertama dan pada usia di atas 28 minggu. Nilai
normalnya dalam kehamilan adalah 11 g/dL. Pada Trimester II
nilai 10,5 g/dL masih dianggap fisiologis karena proses
hemodilusi sedang di ambang puncaknya. Pemeriksaan urine
untuk protein atas indikasi untuk menegakkan diagnosa pre
eklamsia. Pemeriksaan glukosa urine atas indikasi untuk
mendeteksi faktor risiko diabetes dalam kehamilan. Pemeriksaan
Golongan darah diperlukan bila ibu belum pernah melakukan
pemeriksaan. Pemeriksaan lainnya ultra sonography .
Pada kasus Ny. R dilakukan pemeriksaan penunjang pada
tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil haemoglobin 11,1 gr %,
protein urin (-), reduksi urin (-), golongan darah O, HBSAg (-)
Non Reaktif, HIV (-) Non Reaktif, dan Sypilis (-) Non Reaktif.
Dapat disimpulkan pada kasus Ny. R tidak ada kesenjangan
antara kasus dan teori.
2. Interpretasi Data
Menurut Mufdillah (2012), mengidentifikasi diagnosa kebidanan
dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data – data yang
telah dikumpulkan.
a. Diagnosa (Nomenklatur)
213
Menurut Sulistyawati (2010), mengatakan bahwa diagnosa
nomenklatur terdiri dari paritas adalah riwayat reproduksi wanita
yang berkaitan dengan kehamilannya (jumlah kehamilan), usia
kehamilan (dalam minggu), kala dan fase persalinan, keadaan janin,
normal atau tidak normal.
Menurut Sofian (2011), Pada umumnya penyakit paru-paru
tidak mempengaruhi kehamilan, persalinan dan nifas, kecuali
penyakitnya tidak terkontrol, berat dan luas di sertai sesak dan
hipoksia. Walaupun kehamilan menyebabkan sedikit perubahan pada
system pernafasan, karena uterus yang membesar dapat mendorong
diafragma dan paru-paru ke atas serta sisa dalam udara kurang,
namun penyakit tersebut tidak selalu menjadi lebih parah.
Pada kasus Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu,
janin tunggal, hidup, intra uteri, letak memanjang, punggung kanan,
presentasi kepala, dengan riwayat tuberculosis paru. Sehingga pada
kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antar teori dan kasus.
b. Masalah
Menurut Sulistyawati (2014), dalam asuhan kebidanan istilah
masalah dan diagnosa keduanya dapat dipakai karena beberapa
masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa, tetapi perlu
dipertimbangkan untuk membuat rencana yang menyeluruh. Masalah
sering berhubungan dengan bagaimana wanita itu mengalami
kenyataan terhadap diagnosisnya.
Pada kasus Ny. R ditemukan adanya masalah yaitu riwayat
tuberculosis paru, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori
dengan kasus.
214
c. Kebutuhan
Menurut Sulistyawati (2012), dalam hal ini bidan menentukan
kebutuhan pasien berdasarkan keadaan dan masalahnya dengan cara
memberikan konseling sesuai kebutuhan.
Pada kasus ini dilakukan asuhan kebidanan sesuai kebutuhan
terhadap Ny. R yaitu istirahat yang cukup, makan makanan yang
bergizi, minum tablet tambah darah 1x1 di malam hari. Dapat
disimpulkan dalam kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
3. Diagnosa Potensial
Menurut Sulistyawati (2012), pada langkah ini kita mengidentifikasi
masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah.
Langkah ini membutuhkan antisipasi penanganan, bila memungkinkan
dilakukan pencegahan, sambil terus mengamati kondisi klien. Bidan
diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial
benar-benar terjadi.
Pada diagnosa potensial Ny. R tidak terjadi apa-apa atau normal
karena bidan sudah memberikan asuhan yang sesuai. Komplikasi yang
terjadi pada kasus Ny. R diagnosa masalah yang muncul untuk bagi ibu
yaitu sesak nafas, batuk-batuk dan lemas.
Menurut Wiknjosastro (2010), ibu hamil yang menderita
tuberculosis paru akan berdampak pada janin yaitu fetal distres. Pada
kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus.
215
4. Antisipasi Penangan Segera
Menurut Hani (2011), pada langkah ini, bidan menetapkan
kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi dan
kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien.
Selain itu juga mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh atau
dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan tim
kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.
Pada kasus Ny. R antisipasi penanganan segera adalah kolaborasi
dengan dokter Sp.Og, kolaborasi dengan laboratorium, pemeriksaan
tekanan darah. sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
5. Intervensi
Menurut Sulistyawati (2012), pada langkah ini direncanakan asuhan
yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya, dalam menyusun
perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada pengambilan
keputusan untuk dilaksanakannya suatu rencana asuhan harus disetujui
oleh pasien.
Pada langkah ini intervensi yang diberikan pada kasus Ny. R yaitu
beri hasil pemeriksaan, beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan, anjurkan ibu untuk konsultasi dengan dokter, anjurkan ibu untuk
terus mengkonsumsi tablet Fe secara teratur, beritahu ibu untuk
mengkonsumsi makanan yang bergizi, anjurkan ibu untuk tidak
melakukan pekerjaan yang berat, beritahu pada ibu tentang persiapan
persalinan, beritahu ibu tanda persalinan, anjurkan ibu untuk kunjungan
216
ulang. Dari data yang didapatkan pada Ny. R intervensi yang diberikan
sesuai dengan kebutuhan yang ada, beritahu ibu pola hidup sehat.
6. Implementasi
Menurut Sulistyawati (2012), pada langkah ini rencana asuhan yang
menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima
dilaksanakan secara efisien dan aman.
Pada kasus ini implementasi dilakukan setelah rencana tindakan
dilakukan atau diberikan, setelah dilakukan tindakan pada Ny. R hasilnya
Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan yaitu Keadaan
ibu dan janinnya saat ini dalam keadaan baik.
Menurut Hani (2011), melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan
tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Selain itu juga
mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh atau dokter dan untuk
dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan tim kesehatan yang lain
sesuai dengan kondisi klien.
Menganjurkan ibu untuk konsultasi dengan dokter kandungan untuk
mengetahui keadaan janin yang ada di perut ibu.
Menurut Manuaba (2013), seseorang yang dinyatakan hamil wajib di
berikan tablet tambah darah karena untuk mencegah terjadinya anemia
dan untuk pencegahan perdarahan saat melahirkan, tablet tambah darah
di berikan minimal 90 tablet selama hamil diminum teratur, karena efek
dari tablet Fe mual sehingga di minum pada malam hari untuk
mengurangi nrasa mual tersebut.
Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi tablet Fe secara teratur
untuk mencegah terjadinya anemia pada kehamilan. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara kasus dan teori.
217
Menurut Waryono (2010), kehamilan menyebabkan meningkatnya
metabolisme energi, karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya
meningkat selama kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan
besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme ibu.
Kebutuhan energi untuk kehamilan perlu tambahan kira-kira 80.000
kalori selama masa kurang lebih 280 hari, hal ini perlu tambahan ekstra
sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari selama hamil, sumber
makanan yang menghasilkan energi di dapat dari padi, singkong,
gandum). Kebutuhan protein wanita hamil juga meningkat, bahkan
mencapai 68% dari sebelum hamil. Jumlah protein yang harus tersedia
sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gr yang tertimbun
dalam jaringan ibu, plasenta, serta janin, untuk kebutuhan protein
penambahan hingga 12 g/hari selama kehamilan, sumber protein di dapat
dari (susu, telur ikan, tahu, tempedan kacang-kacangan). Kebutuhan
mineral dan vitamin pada wanita hamil juga mengalami peningkatan
sebanyak 250 gram, mineral sangat penting bagi ibu hamil untuk
mencegah terjadinya dehidrasi, vitamin untuk menjaga kesehatan ibu,
sumber mineral dan vitamin di dapat dari sayur dan buah-buahan.
Kebutuhan lemak tiap trimesternya sebesar 10 gram/hari atau total
kebutuhan lemak menjadi 85 gram/hari, lemak berperan sebagai
cadangan makanan bagi ibu, sumber lemak di dapat dari daging hewani.
Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi,
berkalori, berprotein tinggi seperti yang mengandung karbohidrat (padi,
singkong, gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-
kacangan dan lain-lain), protein hewani (susu, telur, ikan, daging ayam,
218
daging sapi, dan lain lain), mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan),
lemak (daging). Sehingga tidak ada kesenjangan antara kasus dan teori.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), aktivitas fisik
yang tergolong ringan saat melakukan aktivitas fisik tidak merasa
terengah- engah atau jantung berdetak lebih kencang dari biasanya, tubuh
juga tidak membakar banyak kalori menjadi energi.
Menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberitahu ibu persiapan persalinan yaitu tempat persalinan,
biaya, penolong (bidan/dokter), perlengkapan ibu (pembalut, kain,
pakaian ibu) dan perlengkapan bayi (baju, kain, popok bayi), donor darah
untuk antisipasi apabila terjadi kegawatdaruratan.
Menurut Sulistyawati (2010), tanda-tanda memasuki persalinan yaitu
terjadinya kontraksi dengan karakteristik pinggang terasa sakit menjalar
kedepan, sifat kontraksi teratur, interval makin pendek, dan kekuatan
makin besar, terjadi perubahan pada serviks (menjadi lembe), pengeluaran
lendir dan darah, pengeluaran cairan ketuban.
Memberitahu ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-kenceng
semakin sering, keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah
bercampur lendir dari jalan lahir. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2009), dalam antenatal care setidaknya ibu
melakukan kunjungan 4 kali selama kehamilan yaitu trimester I
kunjungan minimal 1 kali, trimester II kunjungan minimal 1 kali,
219
trimester III kunjungan minimal 2 kali. Kunjungan ulang dilakukan atau
jadwalkan 4 minggu sekali sampai umur 28 minggu, selanjutnya setiap 2
minggu sekali sampai umur kehamilan 36 minggu dan setiap 1 minggu
sekali sampai bersalin.
Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu dan
jika ibu ada keluhan atau muncul tanda-tanda persalinan segera datang ke
tenaga kesehatan terdekat. Dengan demikian pada kasus ini tidak terdapat
kesenjangan antara teori dengan kasus.
Memberitahu ibu pola hidup sehat olahraga teratur, makan makanan
yang sehat dan bergizi, mandi sehari minimal 2x, kondisi rumah yang
bersih, adanya ventilasi udara seperti jendela yang selalu dibuka pada
pagi hari supaya cahaya matahari dapat masuk kedalam rumah agar
kondisi rumah tidak lembab dan tidak ada perkembang biakan bakteri.
7. Evaluasi
Pada langkah ini penulis melakukan evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien
(Sulistyawati, 2012).
Pada kasus ini evaluasi dilakukan setelah rencana tindakan dilakukan
atau diberikan, setelah dilakukan tindakan pada Ny. R hasilnya adalah
Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang telah di lakukan. Ibu
bersedia melakukan konsultasi dengan dokter. Ibu sudah mengerti
tentang pola hidup sehat. Ibu bersedia untuk mengkonsumsi tablet Fe
secara teratur. Ibu sudah mengerti untuk mengkonsumsi makanan yang
bergizi. Bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat. Ibu sudah
220
mempersiapkan persiapan persalinan. Ibu sudah mengetahui tanda-tanda
persalinan. Ibu bersedia untuk melakukan kunjungan ulang. Saya tidak
memberitahu pola hidup sehat akan tetapi Ny. R sudah mengetahui pola
hidup sehat yang benar seperti ibu melakukan pekerjan rumah (menyapu,
memasak), setiap pagi ibu selalu jalan-jalan di sekitar kompleks rumah
supaya terpapar sinar matahari, dan ibu selalu membuka jendela di pagi
hari. Dengan demikian pada kasus ini tidak terdapat kesenjangan antara
teori dengan kasus.
221
DATA PERKEMBANGAN I
(ANC KUNJUNGAN KE-2)
Tanggal : 23 Agustus 2018
Jam : 16.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Ibu mengatakan bernama Ny. R umur 33 tahun, ibu mengatakan ini
kehamilan yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran, ibu
mengatakan kenceng-kenceng.
Menurut Sulistyawati (2010), tanda-tanda memasuki persalinan yaitu
terjadinya kontraksi dengan karakteristik pinggang terasa sakit menjalar
kedepan, sifat kontraksi teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin
besar, terjadi perubahan pada serviks (menjadi lembek), pengeluaran lendir dan
darah, pengeluaran cairan ketuban.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan kenceng-kenceng, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
b. Data Obyektif
Menurut Sulistyawati (2012), keadaan umum dikaji untuk mengamati
keadaan pasien secara keseluruhan, normalnya keadaan umum baik apabila
pasien memperlihatkan respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain,
serta secara fisik pasien tidak mengalami ketergantungan dalam berjalan.
Sedangkan dikatakan lemah apabila pasien kurang atau tidak memberikan
222
respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain, serta pasien sudah tidak
mampu berjalan sendiri.
Dalam kasus Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik
sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk mendapatkan
gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya kesadaran Composmentis atau
kesadaran maksimal sampai dengan koma atau pasien tidak dalam keadaan
sadar.
Pada kasus Ny. R di dapatkan hasil kesadaran Composmentis. hal tersebut
dapat terlihat ketika dalam pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan
dari bidan dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Hani (2011), tekanan darah ibu hamil sistolik tidak boleh
mencapai 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Perubahan sistolik 30
mmHg dan diastolik diatas tekanan darah sebelum hamil, menandakan toxemia
gravidarum atau keracunan kehamilan. Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan
darah 100/70 mmHg, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Hidayah, dkk (2011), suhu dikaji untuk mengetahui tanda – tanda
infeksi, batas normal 36,5- 37,50C. Pada kasus Ny. R didapatkan suhu tubuh
normal yaitu 36,5oC, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), nadi dikaji untuk mengetahui denyut nadi
pasien yang dihitung selama 1 menit, batas normalnya 60-80 x/menit. Pada
kasus Ny. R didapatkan nadi 80 x/menit, sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
223
Menurut Sulistyawati (2012), pernafasan dikaji untuk mengetahui
frekuensi pernapasan pasien yang dihitung selama 1 menit, batas normal yaitu
18-24 x/menit. Pada kasus Ny. R pernafasan normal yaitu 20 x/menit, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tinggi fundus uterus
berdasarkan perabaan pada usia kehamilan 12 minggu fundus teraba di antara
1- 2 jari di atas simpisis, usia kehamilan 16 minggu fundus teraba di antara
simpisis- pusat , usia kehamilan 20 minggu fundus dapat teraba 2- 3 jari di
bawah pusat, pada usia kehamilan 24 minggu fundus teraba tepat di umbilicus,
usia kehamilan 28 minggu teraba 2- 3 jari di atas pusat, usia kehamilan 32
minggu, fundus teraba di pertengahan antara umbilicus dan prosesus
xyphoideus, usia kehamilan 36 minggu fundus teraba 3 jari di bawah prosesus
xyphoideus, usia kehamilan 40 minggu, fundus teraba di pertengahan antara
umbilicus dan proesesus xyphoideus.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterusnya pertengahan antara
umbilicus dan proesesus xyphoideus, sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Leopold I untuk
menentukan bagian teratas perut ibu, Leopold II untuk menentukan bagian
janin yang ada di sebelah kanan dan kiri ibu, Leopold III untuk menentukan
bagian janin yang ada di bawah uterus, Leopold IV untuk menentukan bagian
bawah janin sudah masuk panggul atau belum. Pada primigravida usia
kehamilan 37 minggu kepala harusnya sudah masuk panggul, pada
multigravida mungkin kepala baru masuk panggul saat inpartu dikarenakan
224
tonus otot abdomen yang sudah mengendur tidak cukup bisa menekan kepala
janin untuk memasuki panggul.
Setelah dilakukan pemeriksaan palpasi pada Ny. R didapatkan Leopold I
(menggunakan teknik jari) yaitu mulai raba dari prossesus xypoideus teraba
bulat, kenyal, tidak melenting yaitu bokong. Leopold II, sebelah kiri ibu teraba
bagian kecil-kecil janin yaitu ekstremitas. Sebelah kanan ibu teraba panjang
seperti papan ada tahanan yaitu punggung. Leopold III, teraba bagian bulat,
keras, melenting yaitu kepala. Leopold IV, bagian terendah janin sudah masuk
pintu atas panggul/ divergen. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Sofian (2011), mengukur tinggi fundus uteri dari simpisis, usia
kehamilan 22- 28 minggu TFU 24-25 cm diatas simfisis, usia kehamilan 28
minggu TFU 26,7 cm di atas simfisis, usia kehamilan 30 minggu TFU 29,5-30
cm di atas simfisis, usia kehamilan 32 minggu TFU 29,5-30 cm di atas simfisis,
usia kehamilan 34 minggu TFU 31 cm di atas simfisis, usia kehamilan 36
minggu TFU 32 cm diatas simfisis, usia kehamilan 38 minggu TFU 33 cm di
atas simfisis, usia kehamilan 40 minggu TFU 37,7 cm di atas simfisis.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterinya 33 cm, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Mc. Donald, tinggi fundus uterus 33 cm. Taksiran berat badan
janin = (tinggi fundus uterus – N) x 155 yaitu N bila 11 kepala sudah masuk
pintu atas panggul dan 12 bila kepala belum masuk pintu atas panggul.
225
Teori tinggi fundus uteri dari simpisis didapatkan tinggi fundus uterus 33
cm, untuk mengetahui taksiran berat badan janin = (33 - 11) = 22 x 155 =
3.410 gram. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), tanda homan adalah metode yang dilakukan untuk
mengetahui adanya tromboflebitis, tanda homan positif dapat menghambat
sirkulasi darah ke organ distal .
Pada kasus Ny. R tidak ada tanda human, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut Hani (2011), diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang di
tegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standard
nomenklatur diagnosa kebidanan.
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu, janin tunggal, hidup
intra uterin, letak memanjang, punggung kanan, presentasi kepala, divergen
dengan faktor resiko tinggi pada kehamilan Riwayat Tuberculosis Paru.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diambil diagnosa seperti
diatas dimana tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Muslihatun (2009), planning atau penatalaksanaan adalah
membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan
disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Dalam planning juga
harus mencantumkan pelaksanaan dan evaluasi, pelaksanaan asuhan harus
sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.
226
Pada kasus Ny. R hasilnya Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah
di lakukan yaitu Keadaan ibu dan janinnya saat ini dalam keadaan baik. Ibu
sudah tahu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, kondisi ibu dan janinya
dalam keadaan baik. Sehingga dalam teori dan kasus tidak ada kesenjangan.
Menurut Waryono (2010), kehamilan menyebabkan meningkatnya
metabolisme energi, karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya
meningkat selama kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besarnya
organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme ibu. Kebutuhan
energi untuk kehamilan perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori selama masa
kurang lebih 280 hari, hal ini perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih
300 kalori setiap hari selama hamil, sumber makanan yang menghasilkan
energi di dapat dari padi, singkong, gandum). Kebutuhan protein wanita hamil
juga meningkat, bahkan mencapai 68% dari sebelum hamil. Jumlah protein
yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gr yang
tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta janin, untuk kebutuhan protein
penambahan hingga 12 g/hari selama kehamilan, sumber protein di dapat dari
(susu, telur ikan, tahu, tempedan kacang-kacangan). Kebutuhan mineral dan
vitamin pada wanita hamil juga mengalami peningkatan sebanyak 250 gram,
mineral sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah terjadinya dehidrasi,
vitamin untuk menjaga kesehatan ibu, sumber mineral dan vitamin di dapat
dari sayur dan buah-buahan. Kebutuhan lemak tiap trimesternya sebesar 10
gram/hari atau total kebutuhan lemak menjadi 85 gram/hari, lemak berperan
227
sebagai cadangan makanan bagi ibu, sumber lemak di dapat dari daging
hewani.
Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berkalori,
berprotein tinggi seperti yang mengandung karbohidrat (padi, singkong,
gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan dan lain-
lain), protein hewani (susu, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain
lain), mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak (daging). Ibu
bersedia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara kasus dan teori.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), aktivitas fisik yang
tergolong ringan saat melakukan aktivitas fisik tidak merasa terengah- engah
atau jantung berdetak lebih kencang dari biasanya, tubuh juga tidak membakar
banyak kalori menjadi energi.
Menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat. Ibu
bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan berat. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistiyawati (2010), cara merangsang kontraksi secara alami
dapat di lakukan dengan jalan santai di pagi dan sore hari, cara ini di lakukan
untuk menurunkan kepala bayi, atau dengan cara memainkan puting susu
karena dengan memainkan putting susu dapat mempengaruhi produksi
hormone oksitosin yang dapat merangsang kontraksi, hal ini di indikasikan
pada umur kehamilan yang cukup yaitu umur kehamilan 38-40 minggu.
Mengajari ibu untuk memacu kontraksi secara alami dengan cara jalan-
jalan pada pagi hari/sore hari, atau dengan cara memainkan puting susu. Ibu
228
sudah mengerti cara memacu kontraksi secara alami, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2010), tanda-tanda memasuki persalinan yaitu
terjadinya kontraksi dengan karakteristik pinggang terasa sakit menjalar
kedepan, sifat kontraksi teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin
besar, terjadi perubahan pada serviks (menjadi lembek), pengeluaran lendir dan
darah, pengeluaran cairan ketuban.
Mengingatkan kembali pada ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-
kenceng semakin sering, keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah
bercampur lendir dari jalan lahir. Ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalinan.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2009), dalam antenatal care setidaknya ibu
melakukan kunjungan 4 kali selama kehamilan yaitu trimester I kunjungan
minimal 1 kali, trimester II kunjungan minimal 1 kali, trimester III kunjungan
minimal 2 kali. Kunjungan ulang dilakukan atau jadwalkan 4 minggu sekali
sampai umur 28 minggu, selanjutnya setiap 2 minggu sekali sampai umur
kehamilan 36 minggu dan setiap 1 minggu sekali sampai bersalin.
Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu dan jika ibu
ada keluhan atau muncul tanda-tanda persalinan segera datang ke tenaga
kesehatan terdekat. Ibu sudah mengerti. Dengan demikian pada kasus ini tidak
terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus.
229
DATA PERKEMBANGAN II
(ANC KUNJUNGAN KE-3)
Tanggal : 24 Agustus 2018
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data subyektif
Ibu mengatakan bernama Ny. R umur 33 tahun, ibu mengatakan ini
kehamilan yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran, ibu
mengatakan kenceng-kenceng.
Menurut Sulistyawati (2010), tanda-tanda memasuki persalinan yaitu
terjadinya kontraksi dengan karakteristik pinggang terasa sakit menjalar
kedepan, sifat kontraksi teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin
besar, terjadi perubahan pada serviks (menjadi lembek), pengeluaran lendir dan
darah, pengeluaran cairan ketuban.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan kenceng-kenceng, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
b. Data obyektif
Menurut Sulistyawati (2012), keadaan umum dikaji untuk mengamati
keadaan pasien secara keseluruhan, normalnya keadaan umum baik apabila
pasien memperlihatkan respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain,
serta secara fisik pasien tidak mengalami ketergantungan dalam berjalan.
Sedangkan dikatakan lemah apabila pasien kurang atau tidak memberikan
230
respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain, serta pasien sudah tidak
mampu berjalan sendiri.
Dalam kasus Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik
sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk mendapatkan
gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya kesadaran Composmentis atau
kesadaran maksimal sampai dengan koma atau pasien tidak dalam keadaan
sadar.
Pada kasus Ny. R di dapatkan hasil kesadaran Composmentis. hal tersebut
dapat terlihat ketika dalam pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan
dari bidan dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Hani (2011), tekanan darah ibu hamil sistolik tidak boleh
mencapai 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Perubahan sistolik 30
mmHg dan diastolik diatas tekanan darah sebelum hamil, menandakan toxemia
gravidarum atau keracunan kehamilan. Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan
darah 110/70 mmHg, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Hidayah, dkk (2011), suhu dikaji untuk mengetahui tanda – tanda
infeksi, batas normal 36,5- 37,50C. Pada kasus Ny. R didapatkan suhu tubuh
normal yaitu 36,7oC, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), nadi dikaji untuk mengetahui denyut nadi
pasien yang dihitung selama 1 menit, batas normalnya 60-80 x/menit. Pada
kasus Ny. R didapatkan nadi 80 x/menit, sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
231
Menurut Sulistyawati (2012), pernafasan dikaji untuk mengetahui
frekuensi pernapasan pasien yang dihitung selama 1 menit, batas normal yaitu
18-24 x/menit. Pada kasus Ny. R pernafasan normal yaitu 20 x/menit, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tinggi fundus uterus
berdasarkan perabaan pada usia kehamilan 12 minggu fundus teraba di antara
1- 2 jari di atas simpisis, usia kehamilan 16 minggu fundus teraba di antara
simpisis- pusat , usia kehamilan 20 minggu fundus dapat teraba 2- 3 jari di
bawah pusat, pada usia kehamilan 24 minggu fundus teraba tepat di umbilicus,
usia kehamilan 28 minggu teraba 2- 3 jari di atas pusat, usia kehamilan 32
minggu, fundus teraba di pertengahan antara umbilicus dan prosesus
xyphoideus, usia kehamilan 36 minggu fundus teraba 3 jari di bawah prosesus
xyphoideus, usia kehamilan 40 minggu, fundus teraba di pertengahan antara
umbilicus dan proesesus xyphoideus.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterusnya pertengahan antara
umbilicus dan proesesus xyphoideus, sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Leopold I untuk
menentukan bagian teratas perut ibu, Leopold II untuk menentukan bagian
janin yang ada di sebelah kanan dan kiri ibu, Leopold III untuk menentukan
bagian janin yang ada di bawah uterus, Leopold IV untuk menentukan bagian
bawah janin sudah masuk panggul atau belum. Pada primigravida usia
kehamilan 37 minggu kepala harusnya sudah masuk panggul, pada
multigravida mungkin kepala baru masuk panggul saat inpartu dikarenakan
232
tonus otot abdomen yang sudah mengendur tidak cukup bisa menekan kepala
janin untuk memasuki panggul.
Setelah dilakukan pemeriksaan palpasi pada Ny. R didapatkan Leopold I
(menggunakan teknik jari) yaitu mulai raba dari prossesus xypoideus teraba
bulat, kenyal, tidak melenting yaitu bokong. Leopold II, sebelah kiri ibu teraba
bagian kecil-kecil janin yaitu ekstremitas. Sebelah kanan ibu teraba panjang
seperti papan ada tahanan yaitu punggung. Leopold III, teraba bagian bulat,
keras, melenting yaitu kepala. Leopold IV, bagian terendah janin sudah masuk
pintu atas panggul/ divergen. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Sofian (2011), mengukur tinggi fundus uteri dari simpisis, usia
kehamilan 22- 28 minggu TFU 24-25 cm diatas simfisis, usia kehamilan 28
minggu TFU 26,7 cm di atas simfisis, usia kehamilan 30 minggu TFU 29,5-30
cm di atas simfisis, usia kehamilan 32 minggu TFU 29,5-30 cm di atas simfisis,
usia kehamilan 34 minggu TFU 31 cm di atas simfisis, usia kehamilan 36
minggu TFU 32 cm diatas simfisis, usia kehamilan 38 minggu TFU 33 cm di
atas simfisis, usia kehamilan 40 minggu TFU 37,7 cm di atas simfisis.
Pada kasus Ny. R di dapatkan tinggi fundus uterinya 33 cm, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Mc. Donald, tinggi fundus uterus 33 cm. Taksiran berat badan
janin = (tinggi fundus uterus – N) x 155 yaitu N bila 11 kepala sudah masuk
pintu atas panggul dan 12 bila kepala belum masuk pintu atas panggul.
233
Teori tinggi fundus uteri dari simpisis didapatkan tinggi fundus uterus 33
cm, untuk mengetahui taksiran berat badan janin = (33 - 11) = 22 x 155 =
3.410 gram. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), tanda homan adalah metode yang dilakukan untuk
mengetahui adanya tromboflebitis, tanda homan positif dapat menghambat
sirkulasi darah ke organ distal.
Pada kasus Ny. R tidak ada tanda human, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut Hani (2011), diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang di
tegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standard
nomenklatur diagnosa kebidanan.
Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu + 1 hari, janin tunggal,
hidup intra uterin, letak memanjang, punggung kanan, presentasi kepala,
divergen dengan faktor resiko tinggi pada kehamilan Riwayat Tuberculosis
Paru. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diambil diagnosa
seperti diatas dimana tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Muslihatun (2009), planning atau penatalaksanaan adalah
membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan
disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Dalam planning juga
harus mencantumkan pelaksanaan dan evaluasi, pelaksanaan asuhan harus
sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.
234
Pada kasus Ny. R hasilnya Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah
di lakukan yaitu Keadaan ibu dan janinnya saat ini dalam keadaan baik. Ibu
sudah tahu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, kondisi ibu dan janinya
dalam keadaan baik. Sehingga dalam teori dan kasus tidak ada kesenjangan.
Menurut Abraham (2014), pada dasarnya pemeriksaan kandungan
(ultrasonography) dilakukan untuk mengecek kesehatan dan perkembangan
janin selama di dalam rahim.
Menganjurkan ibu untuk menemui dokter SpOg dan melakukan
ultrasonography untuk mengetahui kondisi janin.
Menganjurkan pada ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat. Ibu
bersedia untuk tidak melakukan pekerjaan berat. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistiyawati (2010), cara merangsang kontraksi secara alami
dapat di lakukan dengan jalan santai di pagi dan sore hari, cara ini di lakukan
untuk menurunkan kepala bayi, atau dengan cara memainkan puting susu
karena dengan memainkan putting susu dapat mempengaruhi produksi
hormone oksitosin yang dapat merangsang kontraksi, hal ini di indikasikan
pada umur kehamilan yang cukup yaitu umur kehamilan 38-40 minggu.
Mengajari ibu untuk memacu kontraksi secara alami dengan cara jalan-
jalan pada pagi hari/sore hari, atau dengan cara memainkan puting susu. Ibu
sudah mengerti cara memacu kontraksi secara alami, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2010), tanda-tanda memasuki persalinan yaitu
terjadinya kontraksi dengan karakteristik pinggang terasa sakit menjalar
235
kedepan, sifat kontraksi teratur, interval makin pendek, dan kekuatan makin
besar, terjadi perubahan pada serviks (menjadi lembek), pengeluaran lendir dan
darah, pengeluaran cairan ketuban.
Mengingatkan kembali pada ibu tanda-tanda persalinan yaitu kenceng-
kenceng semakin sering, keluar air ketuban dari jalan lahir, keluar darah
bercampur lendir dari jalan lahir. Ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalinan.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2009), dalam antenatal care setidaknya ibu
melakukan kunjungan 4 kali selama kehamilan yaitu trimester I kunjungan
minimal 1 kali, trimester II kunjungan minimal 1 kali, trimester III kunjungan
minimal 2 kali. Kunjungan ulang dilakukan atau jadwalkan 4 minggu sekali
sampai umur 28 minggu, selanjutnya setiap 2 minggu sekali sampai umur
kehamilan 36 minggu dan setiap 1 minggu sekali sampai bersalin.
Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu dan jika ibu
ada keluhan atau muncul tanda-tanda persalinan segera datang ke tenaga
kesehatan terdekat. Ibu sudah mengerti. Dengan demikian pada kasus ini tidak
terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus.
236
B. Asuhan Kebidanan Pada Persalinan
Perkembangan Kala I
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 10.20 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
1. Pengkajian Data
Menurut Hani (2012), Pada langkah pertama ini ditemukan semua
informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan
dengan kondisi klien. Pengkajian data wanita hamil terdiri atas
anamnesa, pemeriksaan klien. Pengkajian data wanita terdiri atas
anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
a. Data Subyektif
Menurut Mufdilah (2014), data subyektif adalah data yang
didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap situasi dan
kejadian.
1) Identitas
a) Nama
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), nama
lengkap ibu, termasuk nama panggilannya. Nama merupakan
identitas khusus yang membedakan seseorang dengan orang
lain. Hendaknya klien dipanggil sesuai dengan nama panggilan
yang biasa baginya atau yang disukainya agar klien merasa
nyaman serta lebih mendekatkan hubungan interpersonal bidan
dengan klien.
237
Dalam praktek didapatkan ibu bernama Ny. R dan suami
bernama Tn. W. Dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara kasus dengan teori.
b) Umur
Menurut Manuba (2012), yang menjadi faktor resiko ibu
hamil adalah umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35
tahun. Sedangkan, usia ibu hamil yang termasuk usia
reproduksi sehat adalah usia 20-35 tahun. Alasan usia tersebut
dikatakan reproduksi sehat karena usia dibawah 20 tahun,
Rahim dan panggul sering kalli belum tumbuh mencapai
ukuran dewasa. Akhirnya, ibu hamil pada usia itu mungkin
mengalami persalinan lama atau macet, atau gangguan lainnya
karena ketidak siapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung
jawabnya sebagai orang tua. Sedangkan pada umur 35 tahun
atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun, akibatnya ibu hamil
pada usia itu mempuyai anak cacat, persalinan lama dan
perdarahan.
Pada kasus ini bernama Ny. R umur 33 tahun tergolong
pada umur normal/produktif atau umur yang sehat pada masa
kehamilan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan
antara kasus dengan teori.
238
c) Agama
Menurut Anggraini (2010), diperlukan untuk mengetahui
keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau
mengarahkan pasien dalam berdoa.
Dalam kasus ini Ny. R menganut agama Islam dan dari
data yang didapatkan tidak terdapat tradisi keagamaan
ditempat tinggal Ny. R yang merugikan kehamilannya dengan
agama yang dianut. Dengan demikian penulis tidak
menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
d) Suku Bangsa
Menurut Anggraini (2010), berpengaruh pada adat istiadat
atau kebiasaan sehari – hari.
Pada kasus Ny. R suku bangsanya adalah jawa dan sudah
diberikan asuhan kebidanan sesuai sosial budaya Ny. R
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan
antara kasus dengan teori.
e) Pendidikan
Menurut Sulistyawati (2010), pendidikan sebagai dasar
bidan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam
penyampaian informasi. Tingkat pendidikan ini sangat
mempengaruhi daya tangkap dan tanggap pasien terhadap
instruksi atau informasi yang diberikan bidan pada pasien.
Dalam pengkajian data dalam hal pendidikan penulis
memperoleh data bahwa pada Ny. R berpendidikan SD. Jadi
tidak ada kesenjangan antara kasus dengan teori tersebut diatas
239
karena pasien menangkap atau memahami informasi yang
telah diberikan oleh Bidan.
f) Pekerjaan
Menurut Anggraini (2010), gunanya untuk mengukur
tingkat social ekonominya, karena ini juga mempengaruhi
dalam gizi pasien tersebut.
Pada kasus Ny. R pekerjaan yang dimiliki yaitu sebagai
ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai karyawan
swasta dengan penghasilan cukup memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan
antara kasus dengan teori.
g) Alamat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), alamat
memberi gambaran mengenai jarak dan waktu yang ditempuh
pasien menuju pelayanan kesehatan, serta mempermudah
kunjungan rumah bila diperlukan.
Ibu mengatakan beralamat di Desa Bulakwaru RT 10 RW
02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Ny. R melakukan
pemeriksaan kehamilannya secara rutin ke pelayanan
kesehatan, penulis juga melakukan kunjungan rumah dalam
rangka melakukan asuhan kebidanan pada masa hamil sampai
masa nifas, sehingga pada kasus ini tidak ditemukan
kesenjangan antara teori dan praktik.
240
2) Alasan Datang
Menurut Hani (2010), alasan wanita datang ke tempat bidan
atau klinik, yang di ungkapkan dengan kata-katanya sendiri.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan ingin melahirkan. Sehingga
tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
3) Keluhan Utama
Menurut Sulistyawati (2012), keluhan utama ditanyakan untuk
mengetahui alasan pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Sulistyawati (2012), tanda-tanda masuk dalam
persalinan adalah terjadinya his atau kontraksi dalam persalinan,
pengeluaran lendir dan darah sebagai penanda persalinan dan
pengeluaran cairan.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan kenceng-kenceng semakin
sering sejak jam 23.00 wib (24/08/18). Sehingga tidak ditemukan
adanya kesenjangan antara teori dan kasus.
4) Riwayat Obstetri dan Ginekologi
Menurut Anggraini (2010), riwayat obstetric diperlukan untuk
mengetahui berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah
anak, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan
dan keadaan nifas yang lalu.
a) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu
Menurut Manuaba (2012), riwayat obstetri dan ginekologi
untuk mengetahui riwayat persalinan dan kehamilan yang lalu.
Jika riwayat persalinan lalu buruk maka kehamilan saat ini
harus diwaspadai. Jumlah anak ideal hanya sampai kehamilan
241
ketiga, sudah termasuk grandemultipara harus diwaspadai
perdarahan post partum.
Pada kasus Ny. R, ibu mengatakan ini kehamilan yang
ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran. Jadi pada kasus
ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
b) Riwayat kunjungan Antenatal Care/Kehamilan sekarang
Menurut Walyani (2015), kunjungan Antenatal Care
minimal satu kali pada trimester pertama (K1), satu kali pada
trimester dua dan dua kali pada trimester ketiga (K4).
Menurut Pantikawati (2010), kunjungan antenatal care
minimal dilakukan 4 kali, yaitu pada kunjungan trimester
pertama (0-14 minggu) dilakukan 1 kali kunjungan. Pada
kunjungan trimester kedua (14-28 minggu) dilakukan 1 kali
kunjungan serta pada kunjungan trimester ketiga (29-36
minggu) dilakukan 2 kali kunjungan.
Dari data yang didapat dari buku kesehatan ibu dan anak
milik Ny. R selama hamil melaksanakan antenatal care secara
teratur. Pada trimester I ibu melakukan pemeriksaan 2x,
trimester II 4x, trimester III sebanyak 5x. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tujuan pemberian imunisasi
TT adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum,
efek samping vaksin TT yaitu nyeri, kemerah-merahan dan
bengkak untuk 1-2 hari pada tempat penyuntikan ini akan
sembuh tanpa perlu pengobatan.
242
Dalam hal ini ibu mendapatkan imunisasi TT, imunisasi
yang diberikan belum sesuai, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tablet fe mengandung 250
mg Sulfat Ferrous 0,25 mg asam folat yang diikat dengan
laktosa. Tujuan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil
dan nifas, karena pada masa kehamilan kebutuhannya
meningkat seiring dengan pertumbuhan janin.
Pada kasus Ny. R sudah mendapatkan tablet tambah
darah 1x 250 mg selama memeriksakan kehamilannya yaitu
90 tablet. Sehingga tidak ada kesenjangan anatara teori dan
kasus.
c) Riwayat Haid
Dari data yang didapat pada kasus Ny. R pertama kali
menstruasi (menarche) pada usia 12 tahun, siklus 28 hari,
lamanya 6 hari, banyaknya 3 kali ganti pembalut dalam sehari,
dan tidak merasakan nyeri baik sebelum atau sesudah
mendapatkan menstruasi, Hari Pertama Haid Terakhir 16
november 2017. Serta ibu mengalami keputihan selama 3 hari,
tidak gatal, warnanya jernih, bau khas.
Menurut Manuaba (2010), bahwa idealnya lama
menstruasi terjadi selama 4-7 hari. Bayaknya pemakaian
pembaalut antara 1-3 kali ganti pembalut dalam sehari, dan
243
adanya disminorea disebabkan oleh faktor anatomis maupun
adanya kelainan ginekologi.
Pada pengakajian yang didapatkan pada Ny. R bahwa
menarche pada usia 12 tahun, lama haid 7 hari, dalam sehari
ganti pembalut sebanyak 3 kali dan tidak ada gangguan saat
haid. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
d) Riwayat Kontrasepsi/KB
Menurut Anggraini (2010), untuk mengetahui apakah
pasien pernah ikut keluarga berencana dengan kontrasepsi
jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan
kontrasepsi serta rencana selanjutnya akan menggunakan
kontrasepsi apa.
Riwayat penggunaan kontrasepsi Ny. R, mengatatakan
pernah memakai keluarga berencana pil dan alasan lepasnya
kerena sedang mengkonsumsi obat tuberculosis. Dan rencana
yang akan datang ibu mengatakan ingin menggunakan
keluarga berencana suntik, karena lebih praktis. Dengan
demikian antara teori dan kasus tidak ada kesenjangan.
5) Riwayat Kesehatan
Menurut Manuaba (2010), bahwa riwayat kesehatan perlu
dikaji karena jika terdapat cacat lahir perlu dilakukan evaluasi
lebih mendalam, dan adanya hamil kembar sering bersifat
menurun.
244
Menurut Sofian (2011), Pada umumnya penyakit paru-paru
tidak mempengaruhi kehamilan, persalinan dan nifas, kecuali
penyakitnya tidak terkontrol, berat dan luas di sertai sesak dan
hipoksia. Walaupun kehamilan menyebabkan sedikit perubahan
pada system pernafasan, karena uterus yang membesar dapat
mendorong diafragma dan paru-paru ke atas serta sisa dalam
udara kurang, namun penyakit tersebut tidak selalu menjadi lebih
parah.
Pada kasus Ny. R sebelum kehamilan Ny. R telah menderita
penyakit tuberculosis namun sekarang sudah sembuh, sehingga
antara kasus dan teori tidak ada kesenjangan.
Menurut Suhardjo (2010), penyakit infeksi hepatitis pada
kehamilan dapat meningkatkan kelahiran premature, infeksi
neonatus atau tertularnya hepatitis dari ibu ke bayi ditularkan
secara vertikal melalui penelanan cairan ibu yang terinfeksi
peripartum, termasuk air susu ibu. Infeksi neonatal biasanya bisa
dicegah dengan penapisan prenatal dengan globulin imun
hepatitis segera sesudah kelahiran.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit infeksi seperti kuning pada
mata dan kulit, demam, mual, muntah, dan buang air kecil
berwarna kuning pekat seperti teh (Hepatitis B), dalam hal ini
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
245
Menurut J. Leveno (2013), penyakit infeksi Human
Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) dapat menyebabkan
komplikasi kehamilan yaitu persalinan preterm, hambatan
pertumbuhan janin, dan lahir mati, dikaitkan dengan infeksi pada
ibu. Penularan terjadi pada periode peripartum bayi lahir dari ibu
yang terinfeksi HIV dan tidak diobati akan terinfeksi.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya, dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit infeksi seperti diare, sariawan
tidak kunjung sembuh, muncul ruam pada kulit, berat badan
menurun drastic dan kekebalan tubuh menurun yaitu Human
Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS), dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), penyakit menular seksual
dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas terhadap ibu
maupun bayi yang dikandungnya.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit infeksi seperti keputihan yang
berbau busuk, berwarna kehijauan dan gatal pada daerah genetalia
yaitu Infeksi Menular Seksual (IMS), sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), diabetes mellitus merupakan
gangguan metabolisme yang ringan, tetapi hiperglikemia ringan
tetap dapat memberikan penyulit pada ibu berupa preeklampsia,
246
polihidramnion, infeksi saluran kemih, persalinan section
caesarea, trauma persalinan akibat bayi besar.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit keturunan seperti mudah haus,
mudah lapar, sering buang air kecil di malam hari yaitu diabetes
mellitus, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), hipertensi dalam kehamilan
adalah hipertensi terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20
minggu, selama persalinan dan dalam 48 jam pasca persalinan,
kenaikan pada diastolik ≥ 90 mmHg pada 2 pengukuran berjarak
1 jam atau lebih.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit keturunan seperti sakit kepala,
tekanan darah lebih dari 140/ 90 mmHg yaitu hipertensi, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), kehamilan yang disertai penyakit
jantung selalu saling mempengaruhi karena kehamilan
memberatkan penyakit jantung dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit keturunan seperti nyeri dada
bagian kiri atas, jantung berdebar – debar, sesak nafas, dan mudah
lelah yaitu jantung, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
247
Menurut Manuaba (2010), kehamilan bersama dengan mioma
uteri hanya mungkin terjadi bila miomanya dalam situasi mioma
uteri intramural, mioma uteri subserosa, mioma uteri yang
bertangkai. Pengaruh mioma uteri pada kehamilan bisa terjadi
infertilitas bila menutupi lumen tuba falopi, mengganggu tumbuh
kembang hasil konsepsi yang telah berimplantasi (terjadi abortus,
persalinan prematur) karena terjadi vaskularisasi sehingga
plasenta tidak mampu memberi nutrisi yang cukup.
Pada kasus ini, Ny. R mengatakan tidak pernah dan tidak
sedang menderita penyakit yang dioperasi seperti mioma uteri,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sofian (2011), kehamilan ganda atau hamil kembar
adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih di sebabkan oleh
faktor keturunan.
Pada kasus Ny. R mengatakan dalam keluarga tidak ada yang
mempunyai riwayat bayi kembar, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
6) Kebiasaan
Menurut Kusmiyati (2009), kebiasaan minum jamu
merupakan salah satu kebiasaan yang beresiko bagi wanita hamil
karena efek minum jamu dapat membahayakan tumbuh kembang
janin seperti menimbulkan kecacatan, abortus, berat badan lahir
rendah, partus prematurus, asfiksia neonatorum, kelainan ginjal
dan jantung janin, sedangkan efek pada ibu dapat menyebabkan
248
keracunan, kerusakan jantung, ginjal, serta perdarahan. Alkohol
yang dikonsumsi ibu hamil dapat membahayakan jantung ibu
hamil dan merusak janin, termasuk menimbulkan kecacatan dan
kelainan pada janin dan menyebabkan kelahiran premature. Efek
pemakaian alkohol dalam kehamilan adalah pertumbuhan janin
terhambat, kecacatan, kelainan jantung dan kelainan neonatal.
Pada kasus Ny. R, mengatakan selama hamil tidak ada
pantangan makanan apapun, tidak pernah mengkonsumsi jamu,
tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan selain dari tenaga
kesehatan, tidak pernah mengkonsumsi minuman keras, tidak
merokok sebelum dan selama hamil, di rumah ibu tidak
memelihara binatang seperti kucing, anjing,burung, dan lain-
lain. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
7) Kebutuhan Sehari-hari
a) Pola nutrisi
Menurut Sulistyawati (2009), pada saat hamil ibu harus
makan makanan yang mengandung nilai gizi bermutu tinggi.
Gizi pada ibu hamil harus ditingkatkan hingga 300 kalori
perhari, ibu hamil seharusnya mengkonsumsi makanan yang
mengandung gizi seimbang.
Pada kasus ini penulis memperoleh data bahwa selama
hamil Ny. R mengatakan waktu hamil frekuensi makan 2-3
kali/hari, porsi 1 piring sedang, menu bervariasi seperti nasi,
lauk dan sayur, sedangkan frekuensi minum 6-7 kali/hari,
249
macamnya air putih, air susu. Pola nutrisi sekarang frekuensi
Makan 1 kali pada jam 06.00 wib porsi 1 piring sedang, menu
seperti nasi, telor, dan tempe goreng, tidak ada makan
dipantang, sedangkan frekuensi minum 2 gelas terakhir
minum jam 06.10 wib, minum air putih, air susu. Dalam hal
ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
b) Eliminasi
Menurut Sulistyawati (2009), masalah buang air kecil
tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar, dan
mencegah terjadinya infeksi kandung kemih yaitu dengan
minum dan menjaga kebersihan alat kelamin.
Pada kasus ini ibu mengatakan frekuensi Buang Air Besar
, selama hamil 1-2 kali sehari, warna, kecoklatan, konsistensi
keras, tidak ada ganguan. Buang air kecil sering, frekuensi 5-7
kali/hari, bau khas, warna kuning jernih, dan tidak ada
ganguan. BAB terakhir jam 06.30 wib, tidak ada ganguan. Ibu
buang air kecil sekali, terakhir jam 10.30 wib, bau khas, warna
kuning jernih, tidak ada gangguan. Sehingga dalam kasus ini
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus
c) Personal hygiene
Menurut Sulistyawati (2012), data ini perlu dikaji karena
bagaimanapun juga hal ini akan mempengaruhi kesehatan
pasien dan bayinya. Jika pasien mempunyai kebiasaan yang
kurang baik dalam perawatan kebersihan diri dirinya, maka
250
bidan harus dapat memberikan bimbingan mengenai cara
perawatan kebersihan diri dan bayinya sedini mungkin.
Wanita perlu mempelajari cara membersihkan alat kelamin
yaitu dengan gerakan dari depan kebelakang setiap kali selesai
berkemih atau buang air besar dan harus menggunakan tissue,
lap atau handuk yang bersih dan kering.
Pada kasus ini ibu mengatakan Pola mandi selama
hamil 2x sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2x, ganti
baju 2x sehari. Pola mandi, keramas, gosok gigi dan ganti
baju terakhir jam 06.30 wib. Dengan demikian tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
8) Data Psikologi
Menurut Marmi (2011) faktor psikologis setiap tahap usia
kehamilan, ibu akan mengalami perubahan baik yang bersifat fisik
maupun psikologis. Ibu harus melakukan adaptasi pada setiap
perubahan yang terjadi. Dalam menjalani proses itu ibu hamil
sangat membutuhkan dukungan yang intensif dari suami maupun
keluarga dengan cara menunjukan perhatian dan kasih sayang.
Pada kasus ini ibu mengatakan ini anak dari pernikahan yang
sah, ibu merasa senang, suami serta keluarga juga senang dengan
kehamilan ibu saat ini, dan ibu sudah siap untuk merawat
bayinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
251
9) Data sosial ekonomi
Menurut Sulistyawati (2012), tingkat sosial ekonomi sangat
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologi ibu
hamil, pada ibu hamil dengan tingkat sosial ekonomi yang baik,
otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologis
yang baik pula. Sementara pada ibu hamil dengan kondisi
ekonomi yang lemah maka ia akan mendapatkan banyak
kesulitan, terutama masalah pemenuhan kebutuhan primer.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan Ibu mengatakan
penghasilan suaminya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,
tanggung jawab perekonomiannya ditanggung suami, dan
pengambilan keputusan oleh bersama (suami&istri). Dengan
demikian tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
10) Data perkawinan
Menurut Sulistyawati (2012), perkawinan ini penting untuk
dikaji karena data ini akan mendapatkan gambaran mengenai
suasana rumah tangga.
Menurut Manuaba (2010), lama menikah dengan batas ideal
dan diikuti hamil setelah 2 tahun.
Pada kasus Ny. R status perkawinannya Ibu mengatakan
status perkawinannya sah secara agama, ini adalah perkawinan
yang pertamanya dan lama perkawinannya sudah 11 tahun, usia
pertama kali menikah umur 22 tahun. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
252
11) Data spiritual
Menurut Astuti (2012), data spiritual klien perlu ditanyakan
apakah keadaan rohaninya saat itu sedang baik ataukah sedang
stress karena suatu masalah. Wanita hamil dengan keadaan
rohaninya sedang tidak stabil hal ini akan mempengaruhi terhadap
kehamilannya. Kebutuhan spiritual mempertahankan atau
mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta
kebutuhan untuk mendapat maaf atau pengampunan, mencintai,
menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan.
Pada kasus ini Ny. R Ibu mengatakan belum melakukan
sholat, ibu selalu berdoa untuk keselamatan ibu dan janinnya.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
12) Data sosial budaya
Menurut Anggraini (2010), data sosial budaya perlu dikaji
untuk mengetahui pasien dan keluarga yang menganut adat
istiadat yang menguntungkan atau merugikan pasien.
Dalam kasus ini Ny. R Ibu tidak percaya dengan adat istiadat
setempat seperti kalau mau melahirkan pintu dan jendelanya
harus dibuka semua. Dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
13) Data pengetahuan
Menurut Pantikawati (2011), untuk mengetahui seberapa jauh
pengetahuan ibu tentang masalah kehamilan. Hal ini dibutuhkan
253
agar ibu tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan
kehamilannya.
Pada kasus ini Ny. R Ibu mengatakan sudah mengetahui
tanda-tanda persalinan. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
b. Data Objektif
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk mendapatkan
gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya kesadaran
composmentis atau kesadaran maksimal sampai dengan koma atau
pasien tidak dalam keadaan sadar. Pada kasus Ny. R kesadaran
composmentis hal tersebut dapat terlihat ketika dalam pemeriksaan
yaitu ibu masih dapat menerima pesan dari bidan dengan baik,
sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), pada pemeriksaan tanda – tanda
vital didapat tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu.
Menurut Hani (2011), tekanan darah ibu hamil sistolik tidak boleh
mencapai 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Perubahan
sistolik 30 mmHg dan diastolik diatas tekanan darah sebelum hamil,
menandakan toxemia gravidarum atau keracunan kehamilan. Pada
kasus Ny. R didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Hidayah, dkk (2011), suhu dikaji untuk mengetahui tanda
– tanda infeksi, batas normal 36,5- 37,50C. Pada kasus Ny. R
254
didapatkan suhu tubuh normal yaitu 36,50C, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), nadi dikaji untuk mengetahui denyut
nadi pasien yang dihitung selama 1 menit, batas normalnya 60-80
x/menit. Pada kasus Ny. R didapatkan nadi 80 x/menit, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), pernafasan dikaji untuk mengetahui
frekuensi pernapasan pasien yang dihitung selama 1 menit, batas
normal yaitu 18-24 x/menit. Pada kasus Ny. R pernafasan normal yaitu
20 x/menit, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Standar
minimal ukuran lingkar lengan atas pada wanita dewasa atau usia
reproduksi adalah 23,5 cm. Jika ukuran lingkar lengan atas kurang dari
23,5 cm maka tergolong risiko terhadap kekurangan energi kronis.
Pada kasus Ny. R didapatkan lingkar lengan atas 27 cm, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), dalam pemeriksaan fisik ini
dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat
membahayakan kehamilan seperti oedema pada wajah, ikterus dan
anemia pada mata, bibir pucat, tanda – tanda infeksi pada telinga,
adanya pembesaran kelenjar tyroid dan limfe, adanya retraksi dinding
dada, pembesaran hepar dan kelainan pada genetalia, anus dan
ekstermitas.
255
Pada kasus Ny. R hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bentuk
kepala mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, tidak berketombe,
muka tidak pucat dan tidak oedem, mata simetris, penglihatan baik,
konjungtiva tidak anemis, sclera tidak ikterik, hidung bersih, tidak ada
pembesaran polip, lendir tidak ada infeksi sinusitis, mulut dan bibir
lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada gigi, gusi tidak
epulis, bentuk telinga simetris, bersih, pendengaran baik, leher tidak
ada pembesaran kelenjar tyroid, dan tidak ada pembesaran vena
jugularis. Aksila tidak ada pembesaran kelenjar limfe, pernafasan
teratur bentuk dada normal, tidak ada retraksi dinding dada, mamae
simetris, abdomen tidak ada luka bekas operasi, genetalia kebersihan
terjaga tidak ada varices, tidak oedem, tidak ada kelenjar bartolini,
anus tidak ada hemoroid, dan extremitas tidak oedem, kuku tidak
pucat dan tidak ada varices. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Suryati (2011), inspeksi adalah memeriksa dengan cara
melihat atau memandang untuk melihat keadaan umum klien, gejala
kehamilan dan adanya kelainan.
Menurut Prawirohardjo (2010), pada dinding perut akan terjadi
perubahan warna menjadi kemerahan, kusam dan kadang – kadang
juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal
dengan nama striae gravidarum. Pada banyak perempuan kulit digaris
pertengahan perutnya (linea alba) akan berubah menjadi hitam
256
kecoklatan yang di sebut dengan linea nigra. Selain pada areola dan
daerah genetalia juga akan terlihat pigmentasi yang berlebihan.
Hasil pemeriksaan obstetrik Ny. R didapatkan pemeriksaan
inspeksi pada payudara yaitu simetris, puting susu menonjol,
kolostrum/ASI belum keluar, kebersihan payudara bersih, pada
abdomen tidak ada bekas luka operasi, tidak ada striae gravidarum,
ada linea nigra, pembesaran uterus sesuai dengan umur kehamilan.
Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik secara inspeksi adalah
normal, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Leopold I
tinggi fundus uterus ditentukan dengan jari, tingginya sesuai dengan
usia kehamilan dan bagian yang berada pada fundus, Leopold II untuk
menentukan bagian janin yang ada di sebelah kanan dan kiri ibu,
Leopold III untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah uterus,
Leopold IV untuk menentukan bagian bawah janin sudah masuk
panggul atau belum. Pada primigravida usia kehamilan 37 minggu
kepala harusnya sudah masuk panggul, pada multigravida mungkin
kepala baru masuk panggul saat inpartu dikarenakan tonus otot
abdomen yang sudah mengendur tidak cukup bisa menekan kepala
janin untuk memasuki panggul.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tinggi fundus
uterus berdasarkan perabaan pada usia kehamilan 12 minggu fundus
teraba di antara 1- 2 jari di atas simpisis, usia kehamilan 16 minggu
fundus teraba di antara simpisis- pusat , usia kehamilan 20 minggu
257
fundus dapat teraba 2- 3 jari di bawah pusat, pada usia kehamilan 24
minggu fundus teraba tepat di umbilicus, usia kehamilan 28 minggu
teraba 2- 3 jari di atas pusat, usia kehamilan 32 minggu, fundus teraba
di pertengahan antara umbilicus dan prosesus xyphoideus, usia
kehamilan 36 minggu fundus teraba 3 jari di bawah prosesus
xyphoideus, usia kehamilan 40 minggu, fundus teraba di pertengahan
antara umbilicus dan proesesus xyphoideus.
Menurut Sofian (2011), mengukur tinggi fundus uteri dari
simpisis, usia kehamilan 22- 28 minggu 24-25 cm diatas simfisis, usia
kehamilan 28 minggu 26,7 cm di atas simfisis, usia kehamilan 30
minggu 29,5-30 cm di atas simfisis, usia kehamilan 32 minggu 29,5-
30 cm di atas simfisis, usia kehamilan 34 minggu 31 cm di atas
simfisis, usia kehamilan 36 minggu 32 cm diatas simfisis, usia
kehamilan 38 minggu 33 cm di atas simfisis, usia kehamilan 40
minggu 37,7 cm di atas simfisis.
Setelah dilakukan pemeriksaan palpasi pada Ny. R didapatkan
Leopold I (menggunakan teknik jari) yaitu mulai raba dari prossesus
xypoideus teraba bulat, kenyal, tidak melenting yaitu bokong. Tinggi
fundus uterus 3 jari di bawah prosesus xypoideus. Leopold II, sebelah
kiri ibu teraba bagian kecil-kecil janin yaitu ekstremitas. Sebelah
kanan ibu teraba panjang seperti papan ada tahanan yaitu punggung.
Leopold III, teraba bagian bulat, keras, melenting yaitu kepala.
Leopold IV, bagian terendah janin sudah masuk pintu atas
258
panggul/Divergen. Sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori
dan kasus.
Teori tinggi fundus uteri menurut Leopold/perabaan dapat
disimpulkan bahwa kasus Ny. R pada pemeriksaan obstetrik Leopold I
di dapatkan tinggi fundus uterus 33 cm dan sesuai dengan umur
kehamilan sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Mc. Donald, tinggi fundus uterus 33 cm. Taksiran berat
badan janin = (tinggi fundus uterus – N) x 155 yaitu N bila 11 kepala
sudah masuk pintu atas panggul dan 12 bila kepala belum masuk pintu
atas panggul.
Teori tinggi fundus uteri dari simpisis didapatkan tinggi fundus
uterus 33 cm, untuk mengetahui taksiran berat badan janin = (33 - 11)
= 22 x 155 = 3.410 gram. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), Denyut jantung
janin umumnya sudah jelas terdengar dengan Doppler mulai usia
kehamilan 16 minggu. Nilai normal DJJ antara 120-160 x/menit
teratur dengan punctum maksimum 1 terletak sesuai dengan punggung
janin.
Pada pemeriksaan detak jantung janin pada Ny. R adalah 138
x/menit. Pada kasus Ny. R dinyatakan denyut jantung janin hasilnya
normal. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus.
Menurut JNPK-KR (2012), memantau kontraksi uterus gunakan
jarum detik dengan cara letakkan tangan penolong diatas uterus dan
259
palpasi jumlah kontraksi yang terjadi dalam kurun waktu 10 menit.
Tentukan durasi atau lama setiap kontraksi yang terjadi minimal 2 kali
kontraksi dalam 10 menit. Pada kasus Ny. R didapatkan kontraksi
uterus 2 kali dalam 10 menit lamanya 25 detik. Sehingga ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Yanti (2009), pemeriksaan dalam bertujuan untuk
menegakkan diagnosa dalam persalinan, dilihat dari penurunan kepala
janin, penipisan serviks, dilatasi serviks, dan keadaan ketuban. Kala I
dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks
menjadi lengkap (10 cm). proses ini terbagi menjadi 2 fase yaitu fase
laten ( 8 jam ) serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif ( 6 jam )
serviks membuka dari 4 cm sampai 10 cm. kontraksi lebih kuat dan
sering selama fase aktif.
Dari hasil pemeriksaan dalam pada Ny. R pada fase laten
didapatkan hasil data objektif keadaan portio tebal, effacement 20-
30% , pembukaan 2 cm, selaput ketuban utuh, bagian terendah kepala,
titik penunjuk ubun – ubun kecil, penurunan Hodge II, bagian
menumbung tidak ada, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
2. Interpretasi Data
Menurut Mufdillah (2012), mengidentifikasi diagnosa kebidanan
dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data – data yang
telah dikumpulkan.
260
a. Diagnosa nomenklatur
Menurut Sulistiyawati (2014), pada langkah ini dilakukan
identifikasi terhadap diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien
berdasarkan interpretasi data yang benar atas data-data yang telah
dikumpulkan. Langkah awal dari perumusan diagnosa atau masalah
adalah pengolahan data dan analisis dengan menggabungkan data
atau satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta. Diagnosa
kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidan dalam lingkup
praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosa
kebidanan.
Ny. R Umur 33 tahun G3 P2 A0 hamil 40 minggu+ 2 hari, janin
tunggal, hidup intra uterin, letak memanjang, punggung kanan,
presentasi kepala, divergen, inpartu kala I Fase laten normal, dengan
riwayat tuberculosis paru. Dalam kasus Ny. R tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2010), Persalinan adalah proses
pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan
(37- 42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala
yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi pada ibu maupun
pada janin.
b. Masalah
Menurut Sulistyawati (2014), dalam asuhan kebidanan istilah
masalah dan diagnosa keduanya dapat dipakai karena beberapa
masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa, tetapi perlu
261
dipertimbangkan untuk membuat rencana yang menyeluruh. Masalah
sering berhubungan dengan bagaimana wanita itu mengalami
kenyataan terhadap diagnosisnya.
Pada kasus Ny. R ditemukan adanya masalah yaitu riwayat
tuberculosis paru, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara teori
dengan kasus.
c. Kebutuhan
Menurut Sulistyawati (2012), dalam hal ini bidan menentukan
kebutuhan pasien berdasarkan keadaan dan masalahnya dengan cara
memberikan konseling sesuai kebutuhan.
Pada kasus ini dilakukan asuhan kebidanan sesuai kebutuhan
terhadap Ny. R yaitu istirahat yang cukup, makan makanan yang
bergizi, minum tablet tambah darah 1x1 di malam hari. Dapat
disimpulkan dalam kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
3. Diagnosa Potensial
Menurut Sulistyawati (2012), pada langkah ini kita
mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan
rangkaian masalah. Langkah ini membutuhkan antisipasi penanganan,
bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil terus mengamati
kondisi klien. Bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau
masalah potensial benar-benar terjadi.
Menurut Sulistyawati (2009), bila seseorang yang terkena
tuberculosis paru kambuh pada saat bersalin pada ibu akan terjadi sesak
262
napas, batuk-batuk dan lemas. Dan yang akan terjadi pada janin fetal
distres karena asupan oksigen ibu ke janin berkurang.
Pada kasus ini pada yang bisa di alami oleh ibu sesak nafas, batuk-
batuk, lemes. Dan bagi janin fetal distres. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
4. Antisipasi penanganan segera
Menurut Hani (2011), pada langkah ini, bidan menetapkan
kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi dan
kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien.
Selain itu juga mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh atau
dokter dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan tim
kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.
Menurut Anggraini (2010), langkah ini memerlukan
kesinambungan dari manajemen kebidanan. Identifikasi dan menetapkan
perlunya tindakan segera oleh bidan dan dokter atau untuk di
konsultasikan atau di tangani bersama dengan anggota tim kesehatan
lain sesuai kondisi lain.
Pada kasus ini jika pasien kambuh akan di konsulkan dengan
dokter jaga, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
5. Intervensi
Menurut Sulistyawati (2012), pada langkah ini direncanakan asuhan
yang menyeluruh berdasarkan langkah yang sebelumnya. Dalam
menyusun perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada
263
pengambilan keputusan untuk dilaksanakannya suatu rencana asuhan
harus disetujui oleh pasien.
Pada kasus ini penulis melakukan intervensi sesuai kebutuhan Ny. R
beritahu ibu hasil pemeriksaan. Berikan asuhan sayang ibu. Anjurkan
ibu untuk tetap tenang saat ada kontraksi. Memberitahu keluarga untuk
menyiapkan perlengkapan yang di butuhkan untuk persalinan. Lakukan
pemantauan kemajuan persalinan kemajuan persalinan kala I dengan
pengawasan 10.
6. Implementasi
Menurut Muslihatun (2009), planning atau penatalaksanaan adalah
membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan
disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.
Tindakan yang tenaga kesehatan berikan pada Ny. R, memberitahu
ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu keadaan ibu dan janin
baik, dan ibu sudah ada di proses persalinan. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), asuhan sayang ibu adalah asuhan
dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan dan keinginan
sang ibu. Salah satu prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah dengan
mengikutsertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan
kelahiran bayi.
Memberikan asuhan saying ibu seperti menjaga privasi ibu,
menghadirkan suami/ keluarga mendampingi ibu saat persalinan,
memberikan asupan energy berupa (makanan/minuman) pada saat
264
kontraksi mereda, memijat bagian yang terasa sakit untuk mengurangi
rasa sakit, menganjurkan ibu untuk berjalan-jalan supaya kepala bayi
semakin turun dan mempercepat proses persalinan, menganjurkan ibu
jika ingin buang air kecil atau buang air besar untuk ke kamar mandi
dengan di damping keluarga. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Jenny (2013), Kontraksi yang berasal dari segmen atas
uterus yang menebal dan dihantarkan ke uterus bawah dalam bentuk
gelombang. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kontraksi
involunter ini antara lain frekuensi, durasi, dan inensitas kontraksi.
Kekuatan primer ini mengakibatkan serviks menipis dan berdilatasi
sehingga janin turun.
Menurut Jenny (2013), otot-otot diafragma dan abdomen ibu
berkontraksi dan mendorong keluar isi ke jalan lahir sehingga
menimbulkan tekanan intra abdomen. Tekanan ini menekan uterus pada
semua sisi dan menambah kekuatan dalam mendorong keluar. Kekuatan
sekunder tidak mempengaruhi dilatasi serviks lengkap, kekuatan ini
cukup penting dalam usaha untuk mendorong keluar dari uterus dan
vagina.
Menganjurkan ibu untuk tetap tenang karena rasa sakit saat proses
persalinan itu hal yang normal. Sehingga antara kasus dan teori tidak
ada kesenjangan.
Menurut Prawirohardjo (2009), partograf adalah alat bantu yang
digunakan selama persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf
265
adalah untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dan
mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan
demikian, juga dapat dilaksanakan deteksi secara dini, setiap
kemungkinan terjadinya partus lama. Jika digunakan secara tepat dan
konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk
mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan yang
diberikan selama selama persalinan dan kelahiran, serta menggunakan
informasi yang tercatat, sehingga secara dini mengidentifikasi adanya
penyulit persalinan, dan membuat keputusan klinik yang sesuai dan
tepat waktu.
Lakukan pemantauan kemajuan persalinan kala 1 dengan
pengawasan 10, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
7. Evaluasi
Pada langkah ini penulis melakukan evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien
(Sulistyawati, 2012).
Pada kasus ini evaluasi dilakukan setelah rencana tindakan dilakukan
atau diberikan, setelah dilakukan tindakan pada Ny. R hasilnya ibu sudah
mengerti hasil pemeriksaan yang telah di lakukan. Suami dan keluarga
sudah berada di samping ibu, suami dan keluarga sudah mengerti untuk
memberi asupan energy berupa makanan dan minuman kepada ibu,
suami dan keluarga sudah mengerti untuk memijat bagian yang terasa
sakit, ibu sudah jalan-jalan dan ibu sudah mengerti alasan di sarankan
266
untuk berjalan-jalan, ibu sudah mengerti kalau merasa mules ingin
BAB/BAK langsung ke kamar mandi dan keluarga siap mengantarkan.
Ibu mengerti apa yang di sarankan bidan. Pemantauan sudah dilakukan
dan hasil terlampir
267
Kala II
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 17.00 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subjektif
Menurut buku yang ditulis Rohani, dkk (2011), tanda dan gejala
kala II his semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit, ibu
merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu
merasakan makin meningkatnya tekanan pada rektum dan atau vagina,
perinium terlihat menonjol, vulva – vagina dan sfingter ani terlihat
membuka, peningkatan pengeluaran lendir dan darah.
Pada kasus yang penulis ambil bahwa ibu mengatakan
kencengnya semakin sering dan lama, sehingga dalam hal ini tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
b. Data Objektif
Menurut buku yang ditulis Rohani, dkk (2011), kala II atau kala
pengeluaran janin, kala II persalinan dimulai ketika pembukaan
serviks sudah lengkap yaitu 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi.
Kala II pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara
1 jam.
Pada kasus yang penulis ambil data objektif yang didapat antara
lain tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 36,5°C,
pernapasaan 20 x/menit, ibu mengalami kontraksi 4 kali dalam 10
268
menit lamanya 45 detik, kekuatan HIS kuat, detak jantung janin 138
x/menit. Adanya tanda gejala kala II yaitu ada dorongan meneran,
tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut buku yang di tulis Rukiah (2010), dimulai dari
pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Pada kala pengeluaran
janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadi pada otot –
otot dasar karena tekanan pada rektum ibu merasa seperti mau buang
air besar dengan tanda anus membuka.
Diagnosa pada kasus Ny. R umur 33 tahun G3P2A0 hamil 40
minggu lebih 2 hari, janin tunggal, hidup intra uterin, letak
memanjang, punggung kanan, presentasi kepala, divergen inpartu kala
II fase aktif dengan faktor resiko riwayat tuberkulosis, dalam hal ini
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Prawirohardjo (2014), tujuan asuhan persalinan normal
adalah mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat
kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya
yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga
prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat
yang optimal.
269
Asuhan persalinan yang diberikan pada ibu adalah asuhan
persalinan normal 60 langkah dimana kala II ini dilakukan langkahnya
sebagai berikut :
27) Mengenali adanya tanda gejala kala II seperti dorongan ingin
meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva
membuka.
Evaluasi : tanda gejala kala II sudah terlihat
28) Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk
mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan 1 buah alat
suntik sekali pakai 3 cc ke dalam wadah partus set.
Evaluasi : alat dan obat sudah lengkap, peralatan ibu dan bayi
sudah lengkap, ampul sudah di patahkan dan spuit 3 cc sudah
ada dalam partus set.
29) Memakai alat pelindung diri seperti clemek, masker, kaca mata,
topi dan sepatu boot.
Evaluasi : alat pelindung diri lengkap sudah di pakai
30) Memastikan lengan / tangan tidak memakai perhiasan, mencuci
tangan dengan sabun di air mengalir
Evaluasi : semua perhiasan sudah di lepas dan sudah mencuci
tangan
31) Memakai sarung tangan disinfektan tingkat tinggi pada tangan
kanan yang di gunakan untuk periksa dalam
Evaluasi : sarung tangan sudah di pakai
270
32) Mengambil alat suntik sekali pakai dengan tangan kanan, isi
dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus
set.
Evaluasi : oksitosin 1 ml sudah di masukan ke dalam spuit dan
sudah di masukan kembali ke dalam perus set.
33) Membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas
disinvektan tingkat tinggi (basah) dengan gerakan dari vulva ke
perineum
Evaluasi : vulva dan perineum sudah di bersihkan
34) Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah
lengkap dan selaput ketuban sudah pecah atau belum
Evaluasi : pemeriksaan sudah dilakukan dengan hasil keadaan
portio sudah tidak teraba, effacement 100%, pembukaan 10 cm,
selaput ketuban negative, warna jernih, bagian terendah kepala,
titik tunjuk ubun-ubun kecil, penurunan kepala hodge IV atau
0/5 bagian, tidak ada bagian yang menumbung.
35) Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan kedalam
larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan
terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%
Evaluasi : sarung tangan sudah di lepas dan direndam kedalam
larutan klorin 0,5%
36) Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus hilang
Evaluasi : Detak jantung janin 140 x/menit dan teratur
271
37) Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin
baik, meminta ibu untuk meneran saat ada kofvntraksi, bila ia
sudah merasa ingin meneran
Evaluasi : ibu dan keluarga sudah mengerti
38) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk
meneran, (pada saat ada kontraksi, bantu ibu dalam posisi
setelah duduk dan pastikan ia merasa nyaman)
Evaluasi : ibu dan keluarga sudah mengerti
39) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan
yang kuat untuk meneran
Evaluasi : ibu mengerti dan bersedia
40) Saat kepala janin terlihat di vulva dengan diameter 5-6 cm,
memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut
ibu
Evaluasi : handuk sudah di letakan di perut ibu
41) Mengambil kain bersih, melipat 1/3 bagian dan meletakkannya
dibawah bokong ibu
Evaluasi : kain sudah terpasang
42) Membuka tutup partus set dan mengecek kelengkapan alat dan
bahan.
Evaluasi : tutup pertus set sudah membuka dan alat sudah
lengkap.
43) Memakai sarung tangan pada kedua tangan
272
Evaluasi : kedua tangan sudah memakai sarung tangan
disinvektan tingkat tinggi.
44) Saat sub-occiput tampak dibawah simfisis, tangan kanan
melindungi perineum dengan dialas lipatan kain di bawah
bokong, sementara tangan kiri menahan puncak kepala agar
tidak terjadi defleksi yang terlalu cepat saat kepala lahir.
Evaluasi : kepala sudah lahir
45) Menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain/ kassa yang
bersih.
Evaluasi : sudah di lakukan
46) Memeriksa leher bayi kemungkinan adanya lilitan tali pusat
Evaluasi : tidak ada lilitan tali pusat
47) Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara
spontan
Evaluasi : kepala bayi sudah melakukan putaran paksi luar
48) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua
telapak tangan secara biparietal di kepala janin, tarik secara hati-
hati ke arah bawah sampai bahu anterior / depan lahir, kemudian
tarik secara hati-hati ke atas sampai bahu posterior/belakang
lahir.
Evaluasi : bahu bayi sudah lahir
49) Setelah bahu lahir, tangan kanan menyangga kepala, leher dan
bahu janin bagian posterior dengan posisi ibu jari pada leher
(bagian bawah kepala) dan ke empat jari pada bahu dan dada /
273
punggung janin, sementara tangan kiri memegang lengan dan
bahu janin bagian anterior saat badan dan lengan lahir
Evaluasi : bahu dan kepala bayi sudah di sangga
50) Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri pinggang
ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang
tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara
kedua lutut janin)
Evaluasi : bayi sudah lahir normal jam 17.15 Wib.
51) Menilai tangisan, gerakan bayi dan warna kulit
Evaluasi : bayi menangis kuat dan gerakan aktif, warna kulit
kemerahan
52) Meletakan bayi di atas perut ibu, mengeringkan dengan kain
yang bersih dan keringkan dari muka, kepala, dan bagian tubuh
lainnya kecuali telapak tangan dan mengganti kain yang basah
dengan kain yang kering dan bersih.
Evaluasi : bayi sudah di keringkan dan di selimuti dengan kain.
53) Mengganti kain bayi dengan kain kering dan bersih,
membedong bayi hingga kepala
Evaluasi : kain sudah di ganti dengan kain kering dan bersih
54) Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal
Evaluasi : tidak ada janin yang kedua
55) Memberitahu ibu akan disuntik oksitosin gunanya untuk
melahirkan plasenta
Evaluasi : ibu sudah mengerti dan bersedia
274
56) Menyutikan Oksitosin 10 unit secara intra muskuler pada bagian
luar paha kanan 1/3 atas setelah melakukan aspirasi terlebih
dahulu untuk memastikan bahwa ujung jarum tidak mengenai
pembuluh darah
Evaluasi : oksitosin sudah di suntikan di 1/3 paha kanan ibu
57) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari
umbilicus bayi. Melakukan urutan tali pusat ke arah ibu dan
memasang klem diantara kedua 2 cm dari klem pertama.
Evaluasi : tali pusat sudah di jepit
58) Memegang tali pusat diantara 2 klem menggunakan tangan kiri,
dengan perlindungan jari-jari tangan kiri, memotong tali pusat di
antara kedua klem
Evaluasi : tali pusat sudah di potong
59) Meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi tengkurap di
dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada /
perut ibu, kaki di renggangkan seperti kaki katak dan usahakan
kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih
rendah dari puting payudara ibu selama 1 jam .
Evaluasi : bayi dilakukan inisiasi menyusui dini
Dalam kasus ini kala II berlangsung selama 15 menit, bayi lahir
pukul 17.15 WIB, jenis kelamin perempuan, pada kala II setiap
langkah- langkahnya sudah sesuai dengan teori menurut
Prawirohardjo (2014), sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
275
Manajemen aktif Kala III
Tanggal : 25 Agustus 2018
Waktu : 17.16 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subjektif
Menurut Rohani, dkk (2011), kala III atau kala pengeluaran
plasenta, kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir
dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya
berlangsung 5 – 30 menit setelah bayi lahir.
Pada kasus data subjektif yang didapat pada kala III yaitu ibu
mengatakan senang karena bayinya sudah lahir, ibu mengatakan
perutnya masih mules, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b. Data Objektif
Menurut Rukiah (2009), tanda tanda pelepasan plasenta yaitu
terjadi perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uteri, tali pusat
memanjang, atau terjulur keluar melalui vulva atau vagina, adanya
semburan darah secara tiba – tiba.
Pada kasus Ny. R data Objektif yang didapat pada kala III antara
lain tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi keras, terdapat tanda-
tanda pelepasan plasenta yaitu tali pusat semakin memanjang, ada
semburan darah, uterus membulat, sehingga dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
276
c. Assesment
Menurut buku yang ditulis Rukiah (2009), batasan kala III, masa
setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses pengeluaran plasenta.
Pada kasus Ny. R didapat assesment sebagai berikut Ny. R umur
33 tahun P3A0 dengan inpartu kala III normal, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Berdasarkan teori medis menurut Prawirohardjo (2014),
manajemen aktif kala III terdiri dari empat langkah utama, yaitu
memeriksa kembali tinggi fundus uteri untuk memastikan tidak ada
janin ganda, pemberian suntik oksitosin dalam satu menit pertama
setelah bayi lahir, melakukan penegangan tali pusat terkendali,
massase fundus uteri segera setelah plasenta lahir.
Dengan melaksanakan manajemen aktif kala III pada asuhan
persalinan yang penulis berikan pada ibu sesuai dengan asuhan
persalinan normal dengan 60 langkah adalah melakukan tindakan pada
langkah – langkah berikut :
61) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari
vulva
Evaluasi : sudah di lakukan
62) Meletakkan tangan kiri di atas simpisis menahan bagian bawah
uterus, sementara tangan kanan memegang tali pusat
277
menggunakan klem atau kain kasa dengan jarak antara 5-10 cm
dari vulva
Evaluasi : tangan kiri sudah di atas simpisis dan tangan kanan
memegang tali pusat
63) Saat kontraksi, memegang tali pusat dengan tangan kanan
sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah
dorso kranial. Bila uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu
atau keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu
Evaluasi : sudah dilakukan dorso kranial
64) Jika dengan peregangan tali pusat terkendali tali pusat terlihat
bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta , minta
ibu untuk meneran sedikit sementara tangan kanan menarik tali
pusat ke arah bawah kemudian ke atas sesuai dengan kurva jalan
lahir hingga plasenta tampak pada vulva.
Evaluasi : sudah dilakukan dan ibu sudah mengerti
65) Setelah plasenta tampak di vulva, teruskan melahirkan plasenta
dengan hati-hati.Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta
dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk
membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput
ketuban.
Evaluasi : plasenta lahir jam 17.25 wib
66) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus
uteri dengan menggosok fundus secara sirkuler menggunakan
278
bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik
(fundus teraba keras)
Evaluasi : fundus sudah di massase
67) Sambil tangan kiri melakukan masase pada fundus uteri, periksa
bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan
untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban
sudah lahir lengkap, dan memasukkan ke dalam kantong plastik
yang tersedia
Evaluasi : sudah di bersihkan dan tidak ada sisa selaput ketuban
yang tertinggal
Menurut Sofian (2011), ujung tali pusat pada bayi diikat kuat
dengan benang / tali disinfeksi tingkat tinggi atau klem pastik / klem
tali pusat sehingga tidak ada perdarahan. Pada kasus Ny. R tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
279
PANTAUAN PERSALINAN KALA IV Jam
Ke Waktu Tekanan Darah Nadi Suhu Tinggi
Fundus Uteri Kontraksi
Uterus Kandung
Kemih Perdarahan
1 17:40 120/70 mmHg 80x 36,5 2Jr Pusat Keras Kosong 30 cc
14:55 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 10 cc
18:10 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
18:25 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
2 18:55 120/70 mmHg 80x 2Jr Pusat Keras Kosong 5 cc
19:25 120/70 mmHg 80x 36,5 2Jr Pusat Keras Kosong 10 cc
Total 65 cc
280
Kala IV
Tanggal : 25 Agustus 2018
Waktu : 17.26 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subjektif
Menurut buku yang ditulis Rohani, dkk (2011), kala IV atau kala
pengawasan, kala IV di mulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir
dua jam setelah proses tersebut.
Pada kasus Ny. R data Subjektif yang didapat pada kala IV yaitu
ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya, ibu mengatakan
masih merasa mules.
b. Data Objektif
Menurut buku yang ditulis oleh Rukiah (2009), kala IV
dimulainya saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum,
komplikasi yang dapat timbul pada kala IV adalah sub involusi uteri
di karenakan uterus tidak berkontraksi, perdarahan yang disebabkan
oleh atonia uteri, laserasi jalan lahir, sisa plasenta.
Menurut buku yang ditulis Rohani, dkk (2011), observasi yang
harus dilakukan pada kala IV Tingkat kesadaran, pemeriksaan tanda –
tanda vital yaitu takanan darah, nadi, suhu, pernafasan, kontraksi
uterus, terjadinya perdarahan, perdarahan dianggap masih normal jika
jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc.
281
Pada kasus Ny. R data Objektif yang didapat keadaan umum
baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/menit, pernafasan
20x/menit, Plasenta lahir lengkap jam 17.25 WIB, diameter plasenta
kurang lebih 20 cm, kedalaman plasenta 5 cm, plasenta utuh,
kontraksi baik/keras, perdarahan kurang lebih 100 cc, kandung kemih
kosong, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
c. Assesment
Menurut buku yang ditulis Sondakh (2013), kala IV dimulai dari
saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum. Kala ini bertujuan
untuk melakukan observasi karena perdarahan post partum paling
sering terjadi pada 2 jam pertama.
Pada kasus Ny. R didapat assessment sebagai berikut Ny. R umur
33 tahun P3A0 dengan inpartu kala IV normal, sehingga dalam hal ini
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Rohani, dkk (2011), asuhan dan pemantauan kala IV
Lakukan rangsangan taktil (seperti pemijatan) pada uterus, untuk
merangsang uterus berkontraksi, evaluasi tinggi fundus dengan
meletakkan jari tangan secara melintang antara pusat dan fundus
uteri, perkirakan kehilangan darah secara keseluruhan, Periksa
perinium dari perdarahan aktif (misalnya apakah ada laserasi atau
episiotomi), evaluasi kondisi ibu secara umum, dokumentasi semua
asuhan dan temuan selama kala IV persalinan di halaman belakang
282
partograf segera setelah asuhan diberikan atau setelah penilaian
dilakukan.
Dengan melaksanakan pemantauan kala IV pada asuhan
persalinan yang penulis berikan pada ibu sesuai dengan asuhan
persalinan normal dengan 60 langkah adalah melakukan tindakan pada
langkah sebagai berikut :
68) Memeriksa apakah ada robekan pada introitus vagina dan
perenium yang menimbulkan perdarahan aktif.Bila ada robekan
yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan
Evaluasi : adanya robekan jalan lahir derajat 2
69) Periksa kembali kontraksi uterus dan tanda adanya perdarahan
pervaginam, pastikan kontraksi uterus baik
Evaluasi : kontraksi keras, perdarahan 30 cc
70) Membersihkan sarung tangan dari lendir dan darah di dalam
larutan klorin 0,5 %, kemudian bilas tangan yang masih
mengenakan sarung tangan dengan air yang sudah di desinfeksi
tingkat tinggi dan mengeringkannya
Evaluasi : sarung tangan sudah di bersihkan menggunakan larutan
klorin 0,5 %
71) Mengikat tali pusat kurang lebih 1 cm dari umbilicus dengan
sampul mati
Evaluasi : tali pusat sudah di ikat menggunakan simpul mati
72) Mengikat balik tali pusat dengan simpul mati untuk kedua kalinya
Evaluasi : tali pusat sudah di ikat dengan simpul mati
283
73) Melepaskan klem pada tali pusat dan memasukkannya dalam
wadah berisi larutan klorin 0, 5%
Evaluasi : klem sudah di lepas dan sudah di masukan di wadah
yang berisi larutan klorin 0,5 %
74) Membedong kembali bayi
Evaluasi : bayi sudah di bedong
75) Berikan bayi pada ibu untuk disusui
Evaluasi : bayi sedang di lakukan inisiasi menyusui dini selama
satu jam
76) Lanjutkan pemantauan terhadap kontraksi uterus, tanda
perdarahan pervaginam dan tanda vital ibu.
Evaluasi : sudah di lakukan pemantauan kontraksi keras,
perdarahan 30 cc,tensi normal, suhu normal, nadi normal,
respirasi normal.
77) Mengajarkan ibu/keluarga untuk memeriksa uterus yang memiliki
kontraksi baik dan mengajarkan masase uterus apabila kontraksi
uterus tidak baik.
Evaluasi : ibu sudah di ajari cara massase dan ibu sudah mengerti
78) Mengevaluasi jumlah perdarahan yang terjadi
Evaluasi : jumlah pengeluaran darah ibu 100 cc
79) Memeriksa nadi ibu
Evaluasi : nadi ibu 80 x/menit
80) Merendam semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5
%
284
Evaluasi : peralatan sudah di rendam di larutan klorin 0,5 %
81) Membuang barang-barang yang terkontaminasi ke tempat sampah
yang di sediakan
Evaluasi : sampah sudah di buang di tempatnya masing-masing
82) Membersihkan ibu dari sisa air ketuban, lendir dan darah dan
menggantikan pakaiannya dengan pakaian bersih/kering
Evaluasi : pakaian ibu sudah di ganti dengan kain bersih dan
kering
83) Memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk
membantu apabila ibu ingin minum
Evaluasi : ibu sudah merasa nyaman dan keluarga siap membantu
ibu
84) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%
Evaluasi : tempat persalinan sudah di bersihkan menggunakan
larutan klorin 0,5 %
85) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%
melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan
merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %
Evaluasi : sarung tangan sudah di lepas dan sudah di rendam di
larutan klorin 0,5 %
86) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
Evaluasi : sudah di lakukan
87) Melengkapi partograf dan memeriksa tekanan darah.
Evaluasi : partograf sudah di lengkapi
285
Pada kasus Ny. R dalam kala IV tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
c. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas
1. Asuhan pada masa nifas 2 jam post partum
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 21.15 WIB
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subjektif
Menurut Anggraini (2010), data subjektif diperoleh dengan cara
tatap muka dengan pasien secara langsung yang meliputi keadaan ibu
sekarang dan keluhan utama.
1) Identitas pasien
a) Nama
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), nama
lengkap ibu, termasuk nama panggilannya. Nama merupakan
identitas khusus yang membedakan seseorang dengan orang
lain. Hendaknya klien dipanggil sesuai dengan nama panggilan
yang biasa baginya atau yang disukainya agar klien merasa
nyaman serta lebih mendekatkan hubungan interpersonal bidan
dengan klien.
Dalam praktek didapatkan ibu bernama Ny. R dan suami
bernama Tn. W. dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara kasus dengan teori.
286
b) Umur
Menurut Manuba (2012), yang menjadi faktor resiko ibu
hamil adalah umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35
tahun. Sedangkan, usia ibu hamil yang termasuk usia
reproduksi sehat adalah usia 20-35 tahun. Alasan usia tersebut
dikatakan reproduksi sehat karena usia dibawah 20 tahun,
Rahim dan panggul sering kalli belum tumbuh mencapai
ukuran dewasa. Akhirnya, ibu hamil pada usia itu mungkin
mengalami persalinan lama atau macet, atau gangguan lainnya
karena ketidak siapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung
jawabnya sebagai orang tua. Sedangkan pada umur 35 tahun
atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun, akibatnya ibu hamil
pada usia itu mempuyai anak cacat, persalinan lama dan
perdarahan.
Pada kasus ini bernama Ny. R umur 33 tahun tergolong
pada umur normal atau umur produktif atau umur yang sehat
pada masa kehamilan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara kasus dengan teori.
c) Agama
Menurut Anggraini (2010), diperlukan untuk mengetahui
keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau
mengarahkan pasien dalam berdoa.
Dalam kasus ini Ny. R menganut agama Islam dan dari data
yang didapatkan tidak terdapat tradisi keagamaan ditempat
tinggal Ny. R yang merugikan kehamilannya dengan agama
287
yang dianut. Dengan demikian penulis tidak menemukan
kesenjangan antara teori dan kasus.
d) Suku Bangsa
Menurut Anggraini (2010), berpengaruh pada adat istiadat
atau kebiasaan sehari – hari.
Pada kasus Ny. R suku bangsanya adalah jawa dan sudah
diberikan asuhan kebidanan sesuai sosial budaya Ny. R
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan
antara kasus dengan teori.
e) Pendidikan
Menurut Sulistyawati (2010), pendidikan sebagai dasar
bidan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam
penyampaian informasi. Tingkat pendidikan ini sangat
mempengaruhi daya tangkap dan tanggap pasien terhadap
instruksi atau informasi yang diberikan bidan pada pasien.
Dalam pengkajian data dalam hal pendidikan penulis
memperoleh data bahwa pada Ny. R berpendidikan SD. Jadi
tidak ada kesenjangan antara kasus dengan teori tersebut diatas
karena pasien menangkap atau memahami informasi yang
telah diberikan oleh Bidan.
f) Pekerjaan
Menurut Anggraini (2010 ), gunanya untuk mengukur
tingkat social ekonominya, karena ini juga mempengaruhi
dalam gizi pasien tersebut.
Pada kasus Ny. R pekerjaan yang dimiliki yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta
288
dengan penghasilan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan
antara kasus dengan teori.
g) Alamat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), alamat
memberi gambaran mengenai jarak dan waktu yang ditempuh
pasien menuju pelayanan kesehatan, serta mempermudah
kunjungan rumah bila diperlukan.
Ibu mengatakan beralamat di Desa Bulakwaru RT 10 RW
02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Ny. R melakukan
pemeriksaan kehamilannya secara rutin ke pelayanan
kesehatan, penulis juga melakukan kunjungan rumah dalam
rangka melakukan asuhan kebidanan pada masa hamil sampai
masa nifas, sehingga pada kasus ini tidak ditemukan
kesenjangan antara teori dan praktik.
2) Keluhan Utama
Menurut Sulistyawati (2010), keluhan utama ditanyakan untuk
mengetahui alasan pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan masih merasa mulas.
Menurut Saleha (2009), setelah melahirkan uterus akan terus
berkontraksi, hal ini terjadi untuk mencegah perdarahan pasca
persalinan. Kontraksi uterus ini seringkali dirasakan tidak nyaman
oleh ibu karena akan menimbulkan rasa mulas dan nyeri. Hal ini
akan berlangsung 2 sampai 3 hari setelah melahirkan.
289
Sehingga pada kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
3) Riwayat Obstetri dan Ginekologi
Menurut Anggraini (2010), riwayat obstetric diperlukan untuk
mengetahui berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah
anak, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan
dan keadaan nifas yang lalu.
a) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu
Menurut Manuaba (2012), riwayat obstetri dan ginekologi
untuk mengetahui riwayat persalinan dan kehamilan yang lalu.
Jika riwayat persalinan lalu buruk maka kehamilan saat ini
harus diwaspadai. Jumlah anak ideal hanya sampai kehamilan
ketiga, sudah termasuk grandemultipara harus diwaspadai
perdarahan post partum.
Pada kasus Ny. R, ibu mengatakan ini kehamilan yang
ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran. Jadi pada kasus
ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
b) Riwayat kunjungan Antenatal Care/Kehamilan sekarang
Menurut Walyani (2015), kunjungan Antenatal Care
minimal satu kali pada trimester pertama (K1), satu kali pada
trimester dua dan dua kali pada trimester ketiga (K4). Menurut
Pantikawati (2010), kunjungan ANC minimal dilakukan 4 kali,
yaitu pada kunjungan trimester pertama (0-14 minggu)
dilakukan 1 kali kunjungan. Pada kunjungan trimester kedua
(14-28 minggu) dilakukan 1 kali kunjungan serta pada
290
kunjungan trimester ketiga (29-36 minggu) dilakukan 2 kali
kunjungan.
Dari data yang didapat dari buku kesehatan ibu dan anak
milik Ny. R selama hamil melaksanakan antenatal care secara
teratur. Pada trimester I ibu melakukan pemeriksaan 2x,
trimester II 4x, trimester III sebanyak 5x. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tujuan pemberian imunisasi
TT adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum,
efek samping vaksin TT yaitu nyeri, kemerah-merahan dan
bengkak untuk 1-2 hari pada tempat penyuntikan ini akan
sembuh tanpa perlu pengobatan.
Dalam hal ini ibu mendapatkan imunisasi TT, imunisasi
yang diberikan belum sesuai, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), tablet fe mengandung 250 mg
Sulfat Ferrous 0,25 mg asam folat yang diikat dengan laktosa.
Tujuan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan
nifas, karena pada masa kehamilan kebutuhannya meningkat
seiring dengan pertumbuhan janin.
Pada kasus Ny. R sudah mendapatkan tablet tambah darah
1x 250 mg selama memeriksakan kehamilannya yaitu 90
tablet. Sehingga tidak ada kesenjangan anatara teori dan kasus.
291
c) Riwayat persalinan sekarang
Menurut Sofian (2011), macam-macam persalinan dibagi
menjadi dua yaitu berdasarkan cara persalinan dan umur
kehamilan, menurut cara persalinan ada partus normal atau
disebut partus spontan.
Pada kasus Ny. R waktu persalinan tanggal 25 Agustus
2018 jam 17.15 wib, persalinan spontan, tidak ada penyulit
waktu persalinan, ketuban pecah jam 17.10 wib, warna jernih,
bau khas, bayi lahir jam 17.15 wib, berat badan bayi 3700
gram, jenis kelamin perempuan.
4) Riwayat Kesehatan
Menurut Manuaba (2010), bahwa riwayat kesehatan perlu
dikaji karena jika terdapat cacat lahir perlu dilakukan evaluasi
lebih mendalam, dan adanya hamil kembar sering bersifat
menurun.
Menurut Sofian (2011), Pada umumnya penyakit paru-paru
tidak mempengaruhi kehamilan, persalinan dan nifas, kecuali
penyakitnya tidak terkontrol, berat dan luas di sertai sesak dan
hipoksia. Walaupun kehamilan menyebabkan sedikit perubahan
pada system pernafasan, karena uterus yang membesar dapat
mendorong diafragma dan paru-paru ke atas serta sisa dalam
udara kurang, namun penyakit tersebut tidak selalu menjadi lebih
parah.
292
Pada kasus Ny. R sebelum kehamilan Ny. R telah menderita
penyakit tuberculosis namun sekarang sudah sembuh, sehingga
antara kasus dan teori tidak ada kesenjangan.
Menurut Suhardjo (2010), penyakit infeksi hepatitis pada
kehamilan dapat meningkatkan kelahiran premature, infeksi
neonatus atau tertularnya hepatitis dari ibu ke bayi ditularkan
secara vertikal melalui penelanan cairan ibu yang terinfeksi
peripartum, termasuk air susu ibu. Infeksi neonatal biasanya bisa
dicegah dengan penapisan prenatal dengan globulin imun
hepatitis segera sesudah kelahiran.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit infeksi seperti kuning pada mata dan
kulit, demam, mual, muntah, dan buang air kecil berwarna kuning
pekat seperti teh (Hepatitis B), dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut J. Leveno (2013), penyakit infeksi Human
Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) dapat menyebabkan
komplikasi kehamilan yaitu persalinan preterm, hambatan
pertumbuhan janin, dan lahir mati, dikaitkan dengan infeksi pada
ibu. Penularan terjadi pada periode peripartum bayi lahir dari ibu
yang terinfeksi HIV dan tidak diobati akan terinfeksi.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya, dan pada keluarga
tidak ada yang menderita penyakit infeksi seperti diare, sariawan
tidak kunjung sembuh, muncul ruam pada kulit, berat badan
menurun drastic dan kekebalan tubuh menurun yaitu Human
293
Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS), dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), penyakit menular seksual
dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas terhadap ibu
maupun bayi yang dikandungnya.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit infeksi seperti keputihan yang
berbau busuk, berwarna kehijauan dan gatal pada daerah genetalia
yaitu Infeksi Menular Seksual (IMS), sehingga tidak ada
kesenjangan anatara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), diabetes mellitus merupakan
gangguan metabolisme yang ringan, tetapi hiperglikemia ringan
tetap dapat memberikan penyulit pada ibu berupa preeklampsia,
polihidramnion, infeksi saluran kemih, persalinan section
caesarea, trauma persalinan akibat bayi besar.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti mudah haus,
mudah lapar, sering buang air kecil di malam hari yaitu diabetes
mellitus, sehinngga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2009), hipertensi dalam kehamilan
adalah hipertensi terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20
minggu, selama persalinan dan dalam 48 jam pasca persalinan,
kenaikan pada diastolik ≥ 90 mmHg pada 2 pengukuran berjarak
1 jam atau lebih.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti sakit kepala,
294
tekanan darah lebih dari 140/ 90 mmHg yaitu hipertensi, sehinnga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), kehamilan yang disertai penyakit
jantung selalu saling mempengaruhi karena kehamilan
memberatkan penyakit jantung dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
Pada kasus Ny. R saat ini, sebelumnya dan pada keluarga tidak
ada yang menderita penyakit keturunan seperti nyeri dada bagian
kiri atas, jantung berdebar – debar, sesak nafas, dan mudah lelah
yaitu jantung, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Manuaba (2010), kehamilan bersama dengan mioma
uteri hanya mungkin terjadi bila miomanya dalam situasi mioma
uteri intramural, mioma uteri subserosa, mioma uteri yang
bertangkai. Pengaruh mioma uteri pada kehamilan bisa terjadi
infertilitas bila menutupi lumen tuba falopi, mengganggu tumbuh
kembang hasil konsepsi yang telah berimplantasi (terjadi abortus,
persalinan prematur) karena terjadi vaskularisasi sehingga
plasenta tidak mampu memberi nutrisi yang cukup.
Pada kasus ini, Ny. R mengatakan tidak pernah dan tidak
sedang menderita penyakit yang dioperasi seperti mioma uteri,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sofian (2011), kehamilan ganda atau hamil kembar
adalah kehamilan dengan dua janin atau lebih di sebabkan oleh
faktor keturunan.
295
Pada kasus Ny. R mengatakan dalam keluarga tidak ada yang
mempunyai riwayat bayi kembar, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
5) Kebiasaan
Menurut Kusmiyati (2009), kebiasaan minum jamu merupakan
salah satu kebiasaan yang beresiko bagi wanita hamil karena efek
minum jamu dapat membahayakan tumbuh kembang janin seperti
menimbulkan kecacatan, abortus, berat badan lahir rendah, partus
prematurus, asfiksia neonatorum, kelainan ginjal dan jantung
janin, sedangkan efek pada ibu dapat menyebabkan keracunan,
kerusakan jantung, ginjal, serta perdarahan. Alkohol yang
dikonsumsi ibu hamil dapat membahayakan jantung ibu hamil
dan merusak janin, termasuk menimbulkan kecacatan dan
kelainan pada janin dan menyebabkan kelahiran premature. Efek
pemakaian alkohol dalam kehamilan adalah pertumbuhan janin
terhambat, kecacatan, kelainan jantung dan kelainan neonatal.
Kebiasaan merokok pada ibu hamil menimbulkan efek yang
membahayakan bagi janin seperti kelahiran berat badan bayi
rendah, persalinan preterm, kematian perinatal, selain mempunyai
efek yang membahayakan janin juga membahayakan ibu
berkaitan dengan penyakit paru, jantung, hipertensi, kanker paru.
Dalam kasus ini Ny. R tidak mempunyai kebiasaan minum
jamu, mengkonsumsi alkohol, merokok, sehingga antara teori dan
kasus tidak ada kesenjangan.
296
6) Riwayat Haid
Dari data yang didapat pada kasus Ny. R pertama kali
menstruasi (menarche) pada usia 12 tahun, siklus 28 hari,
lamanya 6 hari, banyaknya 3 kali ganti pembalut dalam sehari,
dan tidak merasakan nyeri baik sebelum atau sesudah
mendapatkan menstruasi, Hari Pertama Haid Terakhir 16
november 2017. Serta ibu mengalami keputihan selama 3 hari,
tidak gatal, warnanya jernih, bau khas.
Menurut Manuaba (2010), bahwa idealnya lama menstruasi
terjadi selama 4-7 hari. Bayaknya pemakaian pembalut antara 1-3
kali ganti pembalut dalam sehari, dan adanya disminorea
disebabkan oleh faktor anatomis maupun adanya kelainan
ginekologi.
Pada pengkajian yang didapatkan pada Ny. R bahwa menarche
pada usia 12 tahun, lama haid 7 hari, dalam sehari ganti pembalut
sebanyak 3 kali dan tidak ada gangguan saat haid. Sehingga
dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
7) Riwayat Kontrasepsi/KB
Menurut Anggraini (2010), untuk mengetahui apakah pasien
pernah ikut keluarga berencana dengan kontrasepsi jenis apa,
berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi
serta rencana selanjutnya akan menggunakan kontrasepsi apa.
Riwayat penggunaan kontrasepsi Ny. R, mengatakan pernah
memakai keluarga berencana pil dan alasan lepasnya kerena
sedang mengkonsumsi obat tuberculosis. Dan rencana yang akan
297
datang ibu mengatakan ingin menggunakan keluarga berencana
suntik, karena lebih praktis. Dengan demikian antara teori dan
kasus tidak ada kesenjangan.
8) Kebutuhan sehari-hari
a) Pola nutrisi
Menurut Nugroho (2014), kebutuhan nutrisi dan cairan ibu
nifas yaitu memerlukan nutrisi dan cairan untuk pemulihan
kondisinya setelah melahirkan dan untuk memenuhi produksi
air susu.
Pada kasus Ny. R mengatakan pola makan sekarang porsi
sedang, jenis nasi, ayam, sayur sop, tahu, jenis nasi, lauk,
sayur. Pola minum sudah 3 gelas macamnya 2 gelas air putih
dan 1 gelas teh manis. Sehingga pada kasus Ny. R tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
b) Pola Eliminasi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
buang air besar perhari dikatakan lancar apabila teratur,
misalnya sehari 1- 2 kali, sehari 1 kali, atau 2 hari sekali hingga
3 hari sekali, jika lebih dari 3 hari perlu diwaspadai, selain itu
juga tidak ada keluhan/ masalah seperti diare, feses keras.
Perubahan selama hamil bisa terjadi konstipasi akibat pengaruh
hormone progesterone dan relaksin yang menurunkan tonus dan
motilitas usus (sehingga penyerapan zat makanan menjadi
lambat).
298
Pada kasus ini Ny. R mengatakan selama hamil 1-2 x/hari,
konsistensi agak keras,gangguan tidak ada. Sekarang ibu belum
buang air besar, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
buang air kecil perhari dikatakan normal yaitu 4- 7 kali perhari,
warna urine yang baik yaitu jernih yang menandakan kecukupan
cairan dan tidak ada keluhan yang dirasakan. Jika urine
berwarna kuning dan pekat menunjukkan kekurangan intake
cairan. Perubahan selama hamil bisa terjadi peningkatan
frekuensi mikturisi dari kondisi sebelum hamil karena
berkurangnya kapasitas kandung kemih akibat tertekan oleh
pembesaran uterus.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan . Buang air kecil selama
hamil 5-8 x/hari, warna kuning jernih, tidak ada gangguan.
Buang air kecil sekarang 2 kali terakhir di jam 20.30 wib, warna
jernih, tidak ada gangguan, sehingga dalam kasus ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
c) Pola istirahat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), pola
istirahat yang baik untuk ibu hamil yaitu tidur siang kurang
lebih 1 jam, tidur malam kurang lebih 8 jam.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan selama hamil istirahat
siang 1-2 jam, malam 6-7 jam tidak ada gangguan. Sekarang ibu
belum istirahat, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
299
d) Aktifitas
Menurut Yefi (2015), ambulasi dini (early ambulation)
adalah membimbing ibu selekas mungkin turun dari tempat tidur
setelah persalinan akan membantu ibu cepat pulih asal dilakukan
secara bertahap dan hati – hati. Langkah – langkah mobilisasi
dini yang dapat dilakukan ibu untuk turun dari tempat tidur
adalah sebagai berikut awali dengan mengatur napas, miring
kiri, miring kanan dan duduk. Duduk dengan tubuh ditahan
dengan tangan, geserkan kaki ke sisi ranjang dan biarkan kaki
menggantung sebentar dan dengan bantuan orang lain, perlahan
– lahan ibu berdiri dan masih berpegangan pada tempat tidur,
jika terasa pusing duduklah kembali stabilkan diri beberapa
menit sebelum melangkah.
Menurut Manuaba (2010), perawatan mobilisasi dini
mempunyai keuntungan melancarkan pengeluaran lochea,
mengurangi infeksi puerperium, mempercepat involusi alat
kandungan, melancarkan fungsi alat gastrointestinal dan alat
perkemihan, meningkatkan kelancaran peredaran darah,
sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran
metabolisme.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan selama hamil ibu
mengatakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu,
memasak. Aktivitas ibu sekarang mobilisasi miring kanan kiri,
duduk, turun dari tempat tidur, jalan-jalan di sekeliling tempat
300
tidur dan kamar mandi tanpa bantuan orang lain,sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
e) Pola personal hygiene (PH)
Menurut Kusmiyati (2009), wanita perlu mempelajari cara
membersihkan alat kelamin yaitu dengan gerakan dari depan
kebelakang setiap kali selesai buang air kecil atau buang air
besar dan mengeringkan vagina/ alat kelamin menggunakan tisu,
lap atau handuk yang bersih.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), mandi
yang baik frekuensinya 1-2 kali sehari, keramas 2–3 kali
seminggu, ganti pakaian (termasuk pakaian dalam) minimal 2
kali sehari, gosok gigi 2- 3 kali sehari.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan selama hamil mandi 2x
sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2x, ganti baju 2-3 x
sehari. Sekarang ibu mengatakan belum mandi, belum
melakukan keramas, gosok gigi belum melakukan, ganti baju
1x, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
f) Pola seksual
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), frekuensi
seksual dipengaruhi faktor antara lain yaitu usia, lamanya
pernikahan, kondisi kesehatan, hubungan seksual pasangan
yang sehat adalah 1-3 kali dalam seminggu.
301
Menurut Hani (2011), pola hubungan seksual, frekuensi
berhubungan, kelainan dan masalah seksual.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan selama hamil frekuensi 1
minggu 1x jika suami pulang, tidak ada gangguan. Sekarang
belum melakukan hubungan, dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
9) Riwayat Psikologi
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), kehamilan
ini diharapkan/ tidak oleh ibu dan suami, serta respon dan
dukungan keluarga terhadap kehamilan ini. Setiap kehamilan
hendaknya diharapkan oleh ibu maupun suami dan keluarga.
Menurut Sulistyawati (2012), adanya beban psikologis yang
ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan
bayi yang nantinya akan terlihat ketika bayi lahir.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan merasa senang dengan
kehamilannya saat ini. Suami dan keluarga juga merasa senang
dengan kehamilannya, sehingga dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
10) Riwayat Sosial Ekonomi
Menurut Sulistyawati (2012), tingkat sosial ekonomi sangat
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologi ibu
hamil, pada ibu hamil dengan tingkat sosial ekonomi yang baik,
otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologi yang
baik pula. Sementara pada ibu hamil dengan kondisi ekonomi
302
yang lemah maka akan mendapatkan banyak kesulitan, terutama
masalah pemenuhan kebutuhan primer.
Pada kasus Ny. R tanggung jawab perekonomian ditanggung
oleh suami dengan penghasilan mencukupi dan pengambilan
keputusan ditentukan oleh suami dan istri. Dan dengan demikian
tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus.
11) Data Perkawinan
Menurut Sulistyawati (2012), perkawinan ini penting untuk di
kaji karena data ini akan mendapatkan gambaran mengenai suasana
rumah tangga pasangan.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), status
perkawinan, termasuk pernikahan ini yang keberapa dan lamanya
menikah.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan status perkawinannya sah
sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama, ini adalah perkawinan
yang pertama dan lama perkawinannya yaitu 11 tahun dan usia saat
menikah umur 22 tahun, sehingga dalam hal ini tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
12) Data spiritual
Menurut Astuti (2012), data spiritual klien perlu ditanyakan
apakah keadaan rohaninya saat itu sedang baik atau sedang stress
karena suatu masalah. Wanita hamil dan keadaan rohaninya sedang
tidak stabil, hal ini akan mempengaruhi terhadap kehamilannya.
Kebutuhan spiritual mempertahankan atau mengembalikan
303
keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk
mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin
hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan.
Pada kasus ini Ny. R mengatakan belum melakukan ibadah,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
13) Data Sosial Budaya
Menurut Marmi (2011), ada beberapa kebiasaan adat istiadat
yang dapat merugikan kesehatan ibu hamil. Tenaga kesehatan
harus dapat menyiapkan hal ini dengan bijaksana jangan sampai
menyinggung “kearifan lokal” yang sudah berlaku di daerah
tersebut.
Pada kasus ini, ibu mengatakan tidak mempercayai adat
istiadat setempat seperti dalam masa nifas 40 hari tidak boleh
keluar rumah. sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
14) Data Pengetahuan Ibu
Menurut Pantikawati (2010), untuk mengetahui seberapa
jauhnya pengetahuan ibu tentang masalah kehamilan. Hal ini
dibutuhkan agar ibu tahu tentang hal – hal yang berkaitan dengan
kehamilannya.
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), tingkat
pengetahuan ibu meliputi hal – hal apa yang sudah diketahui ibu,
dan hal – hal apa yang ingin diketahui ibu.
304
Pada kasus ini Ny. R mengatakan mengetahui cara
memandikan bayi. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b. Data obyektif
Menurut Sulistyawati (2012), untuk melengkapi data dalam
menegakkan diagnosis, maka kita harus melakukan pengkajian, data
objektif melalui pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan
pemeriksaan yang dilakukan secara berurutan.
1) Pemeriksaan fisik
a) Keadaan umum
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), keadaan
umum dikatakan baik jika pasien memperlihatkan respons
yang adekuat terhadap stimulasi lingkungan dan orang lain,
serta secara fisik pasien tidak mengalami kelemahan. Klien
dimasukkan dalam kriteria lemah ini jika kurang atau tidak
memberikan respons yang baik terhadap lingkungan dan
orang lain, dan pasien sudah tidak mampu lagi untuk berjalan
sendiri.
Dari data yang diperoleh pada kasus Ny. R keadaan umum
baik karena pasien masih mampu berjalan sendiri dan mampu
memberikan respon saat melakukan kunjungan antennal
care, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
305
b) Kesadaran
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017),
kesadaran composmentis yaitu kesadaran normal, sadar
sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang
keadaan sekelilingnya.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk
mendapatkan gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya
kesadaran composmentis atau kesadaran maksimal sampai
dengan koma atau pasien tidak dalam keadaan sadar.
Dari data yang diperoleh pada kasus Ny. R kesadaran
composmentis hal tersebut dapat terlihat ketika dalam
pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan dari bidan
dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
c) Tanda – tanda vital
Menurut Sulistyawati (2012), pada pemeriksaan tanda –
tanda vital didapat tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu.
Menurut Hani (2011), tekanan darah ibu hamil sistolik
tidak boleh mencapai 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90
mmHg. Perubahan sistolik 30 mmHg dan diastolik diatas
tekanan darah sebelum hamil, menandakan toxemia
gravidarum atau keracunan kehamilan.
306
Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan darah 110/80
mmHg, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Hidayah, dkk (2011), suhu dikaji untuk
mengetahui tanda – tanda infeksi, batas normal 36,5- 37,50C.
Pada kasus Ny. R didapatkan suhu tubuh normal yaitu
360C. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), nadi dikaji untuk
mengetahui denyut nadi pasien yang dihitung selama 1 menit,
batas normalnya 60-80 x/menit.
Pada kasus Ny. R didapatkan nadi 78 x/menit, sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2012), pernafasan dikaji untuk
mengetahui frekuensi pernapasan pasien yang dihitung
selama 1 menit, batas normal yaitu 18-24 x/menit.
Pada kasus Ny. R pernafasan normal yaitu 20 x/menit,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), involusi uterus atau pengerutan
uterus merupakan proses kembalinya uterus pada kondisi
sebelum hamil. Pada saat setelah proses persalinan uterus
akan terus mengalami perubahan. Setelah plasenta lahir
uterus akan mengecil menjadi teraba 2 jari dibawah pusat.
Hal itu terjadi karena adanya kontraksi uterus yang baik dan
keras.
307
Pada kasus Ny. R tinggi fundus uterusnya 3 jari di bawah
pusat dan kontraksi keras, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), lochea rubra berwarna merah
karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding
rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium,
muncul pada hari ke 1 sampai hari ke 4 pasca persalinan.
Pada kasus Ny. R pengeluaran darahnya berwarna merah,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d) Pemeriksaan status present dari kepala sampai kaki
Menurut Pantikawati (2010), dalam pemeriksaan fisik ini
dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sesuatu
yang dapat membahayakan kehamilan seperti oedema pada
wajah, ikterus dan anemia pada mata, bibir pucat, tanda –
tanda infeksi pada telinga, adanya pembesaran kelenjar tyroid
dan limfe, adanya retraksi dinding dada, pembesaran hepar
dan kelainan pada genetalia, anus dan ekstermitas.
Pada kasus Ny. R hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
bentuk kepala mesochepal, rambut bersih, tidak rontok, tidak
berketombe, muka tidak pucat dan tidak oedem, mata
simetris, penglihatan baik, konjungtiva tidak anemis, sclera
tidak ikterik, hidung bersih, tidak ada pembesaran polip,
lendir tidak ada infeksi sinusitis, mulut dan bibir lembab,
tidak ada stomatitis, tidak ada caries pada gigi, gusi tidak
308
epulis, bentuk telinga simetris, bersih, pendengaran baik,
leher tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan tidak ada
pembesaran vena jugularis. Aksila tidak ada pembesaran
kelenjar limfe, pernafasan teratur bentuk dada normal, tidak
ada retraksi dinding dada, mamae simetris, abdomen tidak
ada luka bekas operasi, kolostrum/ air susu ibu sudah keluar.
Pada pemeriksaan palpasi fundus uterus 3 jari di bawah
pusat, kontraksi uterus keras, pengeluaran pervagina lochea
rubra, warna merah, konsistensi cair, khas, dengan estimasi
perdarahan 30 cc luka jahitan baik. Ekstremitas tidak oedem
dan tidak ada varises, tidak ada tanda-tanda human.
2) Pemeriksaan obstetrik
a) Inspeksi
Menurut Suryati (2011), inspeksi adalah memeriksa
dengan cara melihat atau memandang untuk melihat keadaan
umum klien, gejala nifas dan adanya kelainan.
Menurut Prawirohardjo (2010), pada dinding perut akan
terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam dan
kadang – kadang juga akan mengenai daerah payudara dan
paha. Perubahan ini dikenal dengan nama striae gravidarum.
Pada banyak perempuan kulit digaris pertengahan perutnya
(linea alba) akan berubah menjadi hitam kecoklatan yang di
sebut dengan linea nigra. Selain pada areola dan daerah
genetalia juga akan terlihat pigmentasi yang berlebihan.
309
Hasil pemeriksaan obstetrik Ny. R didapatkan
pemeriksaan inspeksi pada payudara yaitu simetris, puting
susu menonjol, kolostrum/ASI sudah keluar, kebersihan
payudara bersih, pada abdomen tidak ada bekas luka operasi,
tidak ada striae gravidarum, ada linea nigra, luka jahitan
baik. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik secara
inspeksi adalah normal, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
b) Palpasi
Menurut Saleha (2009), involusi uterus atau pengerutan
uterus merupakan proses kembalinya uterus pada kondisi
sebelum hamil. Pada saat setelah proses persalinan uterus
akan terus mengalami perubahan. Setelah plasenta lahir uterus
akan mengecil menjadi teraba 2 jari dibawah pusat. Hal itu
terjadi karena adanya kontraksi uterus yang baik dan keras.
Pada kasus ini tinggi fundus uterusnya 2 jari di bawah
pusat, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), lochea rubra berwarna merah
karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding
rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium,
muncul pada hari ke 1 sampai hari ke 4 pasca persalinan.
Pada kasus ini lochea Ny. R yaitu lochea rubra berwarna
merah, konsistensi cair, dan bau khas, sehingga tidak ada
kesenjangan antara kasus dan teori.
310
Menurut Saleha (2009), pengeluaran darah pada ibu
postpartum 2 jam umunya berkisar 20-60 cc, jika lebih dari itu
di sebut perdarahan dan segera lakukan tindakan.
Pada kasus ini estimasi perdarahan Ny. R yaitu 30 cc,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
c) Pemeriksaan penunjang
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017),
Pemeriksaan Laboratorium meliputi Kadar hemoglobin pada
kunjungan pertama dan pada usia di atas 28 minggu. Nilai
normalnya dalam kehamilan adalah 11 g/dL. Pada Trimester
II nilai 10,5 g/dL masih dianggap fisiologis karena proses
hemodilusi sedang di ambang puncaknya. Pemeriksaan urine
untuk protein atas indikasi untuk menegakkan diagnosa pre
eklamsia. Pemeriksaan glukosa urine atas indikasi untuk
mendeteksi faktor risiko diabetes dalam kehamilan.
Pemeriksaan Golongan darah diperlukan bila ibu belum
pernah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan lainnya
ultrasonography .
Pada kasus ini tidak di lakukan pemeriksaan penunjang
dengan alasan pasien menolaknya karena keterbatasan biaya.
2. Interpretasi Data
Menurut Mufdillah (2012), mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan
masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data – data yang telah
dikumpulkan.
311
a. Diagnosa nomenklatur
Menurut Sulistyawati (2014), pada langkah ini dilakukan
identifikasi terhadap diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien
berdasarkan interpretasi data yang benar atas data-data yang telah
dikumpulkan. Langkah awal dari perumusan masalah atau diagnose
adalah pengolahan data dan analisis dengan menggabungkan data
satu dengan yang lainnya sehingga tergambar fakta.
Dari kasus Ny. R hasil pemeriksan yang di lakukan maka di
dapatkan diagnose Ny. R umur 33 tahun P2A0 2 jam post partum
dengan nifas normal.
b. Masalah
Menurut Sulistyawati (2014), dalam asuhan kebidanan istilah
masalah dan diagnosa keduanya dapat dipakai karena beberapa
masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa, tetapi perlu
dipertimbangkan untuk membuat rencana yang menyeluruh.
Masalah sering berhubungan dengan bagaimana wanita itu
mengalami kenyataan terhadap diagnosisnya.
Pada kasus Ny. R ibu mengatakan masih merasa mulas.
Menurut Saleha (2009), setelah melahirkan uterus akan terus
berkontraksi, hal ini terjadi untuk mencegah perdarahan pasca
persalinan. Kontraksi uterus ini seringkali dirasakan tidak nyaman
oleh ibu karena akan menimbulkan rasa mulas dan nyeri. Hal ini
akan berlangsung 2 sampai 3 hari setelah melahirkan. Sehingga
antara teori dan kasus tidak ada kesenjangan.
312
c. Kebutuhan
Menurut Hani (2011), kebutuhan adalah hal-hal yang
dibutuhkan oleh klien dan belum teridentifikasikan dalam diagnosa
dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisis data.
Menurut Nugroho (2014), ibu nifas memerlukan nutrisi dan
cairan untuk pemulihan kondisi kesehatan setelah melahirkan,
cadangan tenaga serta untuk memenuhi produksi air susu ibu.
Nutrisi dan cairan tersebut yaitu mengandung karbohidrat, protein,
lemak, zat besi, vitamin dan mineral.
Pada kasus ini kebutuhan Ny. R adalah asupan nutrisi yang
cukup, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Nugroho (2014), Ibu nifas memerlukan istirahat
cukup, istirahat tidur yang dibutuhkan yaitu sekitar 8 jam pada
malam hari dan pada siang hari 1 jam.
Pada kasus ini kebutuhan Ny. R yaitu istirahat yang cukup,
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
3. Diagnosa potensial
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan
rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi.
Berdasarkan temuan tersebut bidan dapat melakukan antisipasi agar
diagnosis atau masalah tersebut tidak terjadi.
Pada kasus Ny. R tidak ditemukan diagnosa potensial sehingga
tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
313
4. Antisipasi Penanganan Segera
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter
untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim
kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien.
Pada kasus Ny. R tidak ditemukan antisipasi penanganan segera
sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
5. Intervensi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), direncanakan
asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah
sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal
yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah
yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan
terjadi selanjutnya. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui
oleh kedua belah pihak yaitu bidan dan pasien.
Pada langkah ini penulis melakukan intervensi sesuai kebutuhan
Ny. R beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan. Beritahu
ibu penyebab dari rasa mulesnya. Ajari ibu untuk memassase perut jika
tidak keras. Beritahu ibu tanda-tanda bahaya masa nifas. Beritahu pada
ibu untuk menjaga personal hygiene. Beritahu ibu dan keluarga jika ibu
ingin buang air kecil atau buang air besar tidak boleh di tahan. Beritahu
ibu perawatan luka jahitan . Beritahu ibu untuk memberikan ASI
esklusif dan berikan asi setiap bayi menginginkanya. Anjurkan ibu
untuk istirahat yang cukup. Ajarkan ibu cara menyusui yang benar.
314
Memberikan obat terapi post partum kepada ibu. Sehingga pada kasus
Ny. R tidak ada kesenjangan antara kasus dan teori.
6. Implementasi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), langkah ini
adalah melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah
kelima (perencanaan) secara aman dan efisien. Realisasi dari
perencanaan yang dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota
keluarga yang lain.
Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan bahwa
keadaan ibu saat ini baik.
Menurut Saleha (2009), setelah melahirkan uterus akan terus
berkontraksi, hal ini terjadi untuk mencegah perdarahan pasca
persalinan. Kontraksi uterus ini seringkali dirasakan tidak nyaman oleh
ibu karena akan menimbulkan rasa mulas dan nyeri. Hal ini akan
berlangsung 2 sampai 3 hari setelah melahirkan. Sehingga antara teori
dan kasus tidak ada kesenjangan.
Pada kasus ini bidan bidan memberitahu ibu tentang penyebab
perut ibu masih mulas dikarenakan adanya proses involusi uterus/
kembalinya Rahim kebentuk semula seperti sebelum hamil, jadi hal
tersebut wajar di alami saat masa nifas. Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), caranya memassase (pijat) perut yaitu
tangan kanan diletakan di atas fundus ibu dan masasse 5-10 detik atau
sampai fundus (Rahim ) ibu keras, tanda kontraksi baik yaitu keras dan
315
tanda kontraksi yaitu jelek, fungsi dari memijat/memassase perut untuk
mengurangi perdarahan setelah melahirkan.
Mengajari ibu untuk memassase (pijat) perut caranya yaitu tangan
kanan diletakan di atas fundus ibu dan masasse 5-10 detik atau sampai
fundus (Rahim ) ibu keras, tanda kontraksi baik yaitu keras dan tanda
kontraksi yaitu jelek, fungsi dari memijat/memassase perut untuk
mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Bahiyatun (2009) tanda bahaya dalam nifas terdiri dari
muntah tidak enak badan, sakit pada bagian bawah perut atau
punggung, sakit kepala yang terus menerus, nyeri ulu hati dan
pandangan mata kabur, bengkak pada wajah, tangan atau kaki,
perdarahan, pengeluaran cairan dari jalan lahir yang berbau busuk, sakit
jika buang air kecil, payudara kemerahan, panas dan sakit, betis
menjadi keras kemerahan panas dan sakit atau nyeri, kehilangan nafsu
makan dalam waktu yang lama, perasaan yang sedih atau tidak mampu
merawat bayinya dan diri sendiri.
Memberitahu ibu tentang bahaya masa nifas yaitu pendarahan
pervaginam, keluar cairan yang berbau busuk dari jalan lahir, tekanan
darah lebih dari 140/90, mmHg, pandangan mata kabur, sakit kepala
yang tidak hilang ketika di bawa tidur, bengkak pada kaki, tangan dan
muka (tanda pre eklamsia). Nyeri ulu hati nyeri payudara, payudara
bengkak dan kemerahan, kehilangan nafsu makan, mual muntah dan
demam tinggi lebih dari 38oC Apabila terdapat tanda-tanda bahaya
316
tersebut segera datang ke tenaga kesehatan. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara kasus dan teori.
Menurut Nurgoho (2014), kebersihan diri berguna untuk
mengurangi infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman. Anjurkan ibu
untuk menjaga kebersihan diri dengan cara mandi 2 kali sehari,
mengganti pakaian dan alas tempat tidur serta lingkungan dimana ibu
tinggal. Ibu harus tetap bersih, merawat perinium dengan baik,
bersihkan alat genetalia menggunakan air bersih dari depan ke
belakang, mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali atau tiap
pembalut penuh.
Memberitahu ibu cara menjaga personal hygiene yaitu menjaga
daerah genetalia dengan membersihkannya menggunakan air dingin
dari atas ke bawah, mengganti pembalut 2x/hari jika basah saat buang
air besar atau buang air kecil, menggunakan celana dalam yang
menyerap keringat, serta menjaga kebersihan tubuh yang lainnya.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Hanni (2016), cara perawatan luka jahitan cukup
memnggunakan kasa steril dan obat merah, kasa steril tetesi obat merah
di tempelkan ke luka jahitan. Lakukan pada saat buang air besar dab
buang air kecil.
Memberitahu ibu cara perawatan luka jahitan yaitu jika ibu
gunakan kassa steril dan betadine, kassa steril di tetesi betadine di
tempelkan ke luka jahitan. lakukan rutin jika ibu setelah BAB/BAK.
317
Menurut Sondakh (2013), air susu ibu (ASI) eksklusif yaitu
memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan apapun kecuali vitamin
dan obat-obatan dari bidan atau dokter sampai bayi berusia 6 bulan, dan
menyusui bayi sesuai keinginan atau On Demand).
Menurut Nugroho (2014), Ibu nifas memerlukan istirahat cukup,
istirahat tidur yang dibutuhkan yaitu sekitar 8 jam pada malam hari dan
pada siang hari 1 jam.
Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, istirahat siang 1-2
jam, malam 6-8 jam, jika bayi sedang tidur ajurkan ibu untuk istirahat
juga dan disini peran suami juga di perlukan untuk sama-sama
membantu menjaga bayi.
Menurut Saleha (2009), cara menyusui sangat mempengaruhi
kenyamanan bayi menghisap air susu ibu. Bidan memberikan
pendidikan kesehatan tentang cara menyusui yang benar pada minggu
pertama setelah persalinan agar tidak menimbulkan masalah.
Mengajarkan ibu cara menyusui yang benar yaitu pastikan ibu dan
bayi berada dalam kondisi rileks dan nyaman
Posisi kepala bayi harus lebih tinggi dibandingkan tubuhnya ibu dapat
menyangga dengan tangan ataupun mengganjal dengan bantal.
Mendekatkan bayi ke payudara ketika bayi mulai membuka mulutnya
dan ingin menyusu, dekatkan bayi ke payudara ibu. Tunggu hingga
mulutnya terbuka lebar dengan posisi lidah ke arah bawah. Jika bayi
belum melakukannya, ibu dapat membimbing bayi dengan dengan
menyentuh lembut bagian bawah bibir bayi dengan puting susu ibu.
318
Perlekatan yang benar posisi perlekatan terbaik bayi menyusui yaitu
mulut bayi tidak hanya menempel pada puting, namun pada area bawah
puting payudara dan selebar mungkin. Tanda bahwa perlekatan sudah
baik yaitu ketika ibu tidak merasakan nyeri saat bayi menyusu dan bayi
memperoleh ASI yang mencukupi. Ibu dapat mendengarkan saat bayi
menelan ASI. Membetulkan posisi bayi Jika ibu merasa nyeri, lepas
perlekatan dengan memasukan jari kelingking ke dalam mulut dan
letakkan di antara gusinya. Gerakan ini akan membuatnya berhenti
menyusu sementara Anda bisa menyesuaikan posisi bayi. Kemudian,
coba lagi untuk perlekatan yang lebih baik. Setelah perlekatan sudah
benar, umumnya bayi akan dapat menyusu dengan baik. Sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberikan obat terapi post partum asam mefenamat 500 mg,
amoxicillin 500 mg, tablet fe 200 mg.
7. Evaluasi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita
berikan kepada pasien. Dalam melakukan evaluasi seberapa efektif
tindakan dan asuhan yang kita berikan kepada pasien, kita perlu
mengkaji respon pasien dan meningkatkan kondisi yang kita targetkan
pada panyususnan perencanaan. Hasil pengkajian ini kita jadikan
sebagai acuan dalam penatalaksanaan berikutnya.
Pada kasus Ny. R telah dilakukan kefektifan dan asuhan yang telah
diberikan yaitu Ibu sudah mengerti hasil pemeriksaan yang telah
319
dilakukan. Ibu sudah mengerti penyebab dari rasa mulesnya. Ibu sudah
mengerti dan bisa cara memassase fundus. Ibu sudah mengerti tanda
bahaya nifas. Ibu sudah mengerti cara menjaga kebersihan diri. Ibu
sudah mengerti untuk tidak menunda jika ibu ingin bab/bak. Ibu sudah
tahu perawatan luka jahitan. Ibu bersedia untuk memberikan ASI
esklusif dan memberikan setiap bayi menginginkannya. Ibu sudah
mengerti cara mengatur pola istirahat dan suami siap untuk membantu
menjaga bayinya. Ibu sudah tahu cara menyususi yang benar. Obat
terapi sudah di berikan kepada ibu dan ibu sudah meminumnya.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
320
KUNJUNGAN NIFAS KE 2 ( 6 HARI)
Tanggal : 31 Agustus 2018
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data subyektif
Menurut Anggraini (2010), data subjektif diperoleh dengan cara tatap
muka dengan pasien secara langsung yang meliputi keadaan ibu sekarang dan
keluhan utama.
Pada kasus yang penulis ambil pada data subjektif, Ibu mengatakan
sudah bisa mengurus bayinya, ASI nya keluar lancar dan tidak ada keluhan.
Menurut Saleha (2009), adaptasi masa nifas terbagi menjadi fase taking
in, taking hold dan letting go. Fase taking hold Berlangsung 3-4 hari post
partum, ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima
tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu
menjadi sangat sensitif sehingga mudah tersinggung.
b. Data Objektif
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), kesadaran
composmentis yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab
semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk mendapatkan
gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya kesadaran composmentis atau
kesadaran maksimal sampai dengan koma atau pasien tidak dalam keadaan
sadar.
321
Pada kasus Ny. R kesadaran composmentis hal tersebut dapat terlihat
ketika dalam pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan dari bidan
dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Anggraini (2015), pada tanda- tanda vital, tekanan darah pada
proses persalinan akan terjadi peningkatan sekitar 15 mmHg untuk sistol dan
10 mmHg untuk diastole. Kemudian pasca bersalin akan kembali normal dan
stabil. Suhu setelah 12 jam pertama kelahiran bayi umumnya suhu badan
kembali normal. Nadi 60 – 80 x/menit, > 100 x/menit abnormal. Keadaaan
pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila
suhu dan denyut nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya,
kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas.
Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 360C,
nadi 80 x/menit, pernafasan 20 x/menit, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), dalam pemeriksaan fisik ini dilakukan
untuk mendeteksi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat membahayakan
pada masa nifas seperti oedema wajah, ikterus dan anemia pada mata, bibir
pucat, tanda- tanda infeksi pada telinga, adanya pembesaran kelenjar tyroid
dan limfe, adanya retraksi dinding dada, pembesaran hepar, kelainan pada
genetalia, anus dan ektremitas.
Pada kasus Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan fisik yang telah
dilakukan, muka tidak pucat, konjungtiva merah muda, sclera putih, payudara
322
simetris, puting susu menonjol, ASI sudah keluar banyak, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), involusi uterus atau pengerutan uterus
merupakan proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Pada saat
setelah proses persalinan uterus akan terus mengalami perubahan. Setelah
plasenta lahir uterus akan mengecil menjadi teraba pertengahan simpisis-
pusat. Hal itu terjadi karena adanya kontraksi uterus yang baik dan keras.
Berat uterus 500 gram. sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), masa puerperium diikuti pengeluaran cairan
sisa lapisan endometrium dan sisa dari implantasi plasenta yang disebut
lochea. lochea sanguinolenta berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir,
hari ke 3 -7 pascapersalinan.
Pada kasus Ny. R pengeluaran pervaginam lochea sanguinolenta,
berwarna kekuningan, luka jahitan masih basah, sehingga dalam hal ini tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Saleha (2009), tanda homan adalah metode yang dilakukan
untuk mengetahui adanya tromboflebitis, tanda homan positif dapat
menghambat sirkulasi darah ke organ distal.
Pada kasus Ny. R tidak ada tanda-tanda human, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
323
c. Assessment
Menurut Hani (2011), diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang di
tegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standard
nomenklatur diagnosa kebidanan.
Pada kasus yang penulis ambil didapat assessment yaitu Ny. R umur 33
tahun P3 A0 6 hari Post Partum dengan nifas normal. sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Muslihatun (2009), planning atau penatalaksanaan adalah
membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan
disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Dalam planning juga
harus mencantumkan pelaksanaan dan evaluasi, pelaksanaan asuhan harus
sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.
Asuhan yang diberikan pada masa nifas 6 hari post partum adalah
memberitahu ibu hasil pemerikasaan yang telah dilakukan. Memberitahu ibu
untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Memberitahu ibu kebutuhan air
minum pada ibu menyusui. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri.
Memberitahu ibu istirahat cukup. Memberitahu ibu perawatan bayi yang benar.
Memberitahu ibu jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama.
Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang.
Menurut Nugroho (2014), ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk
pemulihan kondisi kesehatan setelah melahirkan, cadangan tenaga serta untuk
memenuhi produksi air susu ibu. Nutrisi dan cairan tersebut yaitu mengandung
karbohidrat, protein, lemak, zat besi, vitamin dan mineral. Pada kasus ini bidan
324
memberikan pendidikan kesehatan tentang pola nutrisi dengan cara
Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi kalori
tinggi protein seperti yang mengandung karbohidrat (padi, singkong, gandum,
dan lain-lain), protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan dan lain-lain),
protein hewani (susu, telor, ikan, daging ayam, daging sapi dan lain-lain),
mineral dan vitamin (sayur dan buah-buahan), lemak nabati (lemak jagung dan
lain-lain), lemak hewani (lemak ikan dan lain-lain). Evaluasi : ibu bersedia
untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Sulistyawati (2014), kebutuhan minum ibu nifas dalam sehari
mencapai 2500 – 3000 ml perharinya atau setara dengan 12-15 gelas.
Memberitahu ibu kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan
pertama yaitu 14 gelas sehari. Evaluasi, ibu dalam sehari mengkonsumsi air
minum sebanyak 15 gelas. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Nurgoho (2014), kebersihan diri berguna untuk mengurangi
infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman. Anjurkan ibu untuk menjaga
kebersihan diri dengan cara mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas
tempat tidur serta lingkungan dimana ibu tinggal. Ibu harus tetap bersih,
merawat perinium dengan baik, bersihkan alat genetalia menggunakan air
bersih dari depan ke belakang, mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali atau
tiap pembalut penuh.
Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri, termasuk daerah
kemaluan dengan cara cebok yang benar yaitu di bersihkan mulai dari depan ke
325
belakang menggunakan sabun dan air, ganti pembalut sesering mungkin.
Evaluasi, ibu sehari mandi 2x, gosok gigi 2x, ganti baju 2x, ibu sudah mengerti
cara cebok yang benar, dan ibu sehari ganti pembalut sesering mungkin.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Yefi (2015), kebutuhan istirahat pada ibu nifas sama seperti
kebutuhan tidur pada umumnya yaitu siang hari kurang lebih 2 jam dan pada
malam hari kurang lebih 7 jam.
Memberitahu ibu istirahat cukup siang 1-2 jam maam 6-8 jam atau saat
bayi istirahat ibu juga istirahat. Evaluasi, istirahat siang ibu kurang lebih 1 jam,
malam 6-8 jam saat ibu istirahat bayi di gendong suami/ ibu. Sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberitahu ibu perawatan bayi yang benar yaitu memandikan bayi 2x
sehari, menjaga kehangatan bayi dengan cara di bedong dan menyelimuti bayi,
mengganti popok bayi jika bayi buang air kecil atau buang air besar. Evaluasi,
bayi mandi sehari 2x, bayi selalu di bedong dan di selimuti, jika bayi bak/bab
ibu segera mengganti popok bayi dan membersihkannya.
Memberitahu ibu jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena
akan membuat bayi stress. Evaluasi, bayi tidak pernah menangis terlalu lama.
Menurut Saleha, 2009 progam dan kebijakan teknis masa nifas adalah
paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas untuk mengetahui status ibu dan
bayi untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah yang terjadi, yaitu
6-8 jam setelah persalinan, 7 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah
persalinan dan 6 minggu setelah persalinan.
326
Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi atau
jika ada keluhan segera datang ke tenaga kesehatan. Evaluasi, ibu bersedia
untuk melakukan kunjungan ulang. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
327
CATATAN KUNJUNGAN NIFAS KE 2 ( 14 HARI )
Tanggal : 08 September 2018
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Menurut Anggraini (2010), data subjektif diperoleh dengan cara tatap
muka dengan pasien secara langsung yang meliputi keadaan ibu sekarang dan
keluhan utama.
Pada kasus yang penulis ambil pada data subjektif, ibu mengatakan Ibu
mengatakan tidak ada keluhan ASInya lancar.
b. Data Obyektif
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), kesadaran
composmentis yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab
semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
Menurut Sulistyawati (2012), kesadaran dikaji untuk mendapatkan
gambaran tentang kesadaran pasien, normalnya kesadaran composmentis atau
kesadaran maksimal sampai dengan koma atau pasien tidak dalam keadaan
sadar.
Pada kasus Ny. R kesadaran composmentis hal tersebut dapat terlihat
ketika dalam pemeriksaan yaitu ibu masih dapat menerima pesan dari bidan
dengan baik, sehingga dalam kasus ini tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
328
Menurut Anggraini (2015), pada tanda- tanda vital, tekanan darah pada
proses persalinan akan terjadi peningkatan sekitar 15 mmHg untuk sistol dan
10 mmHg untuk diastole. Kemudian pasca bersalin akan kembali normal dan
stabil. Suhu setelah 12 jam pertama kelahiran bayi umumnya suhu badan
kembali normal. Nadi 60 – 80 x/menit, > 100 x/menit abnormal. Keadaaan
pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila
suhu dan denyut nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya,
kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas.
Pada kasus Ny. R didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,70C,
nadi 82 x/menit, pernafasan 20 x/menit, sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Pantikawati (2010), dalam pemeriksaan fisik ini dilakukan
untuk mendeteksi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat membahayakan
pada masa nifas seperti oedema wajah, ikterus dan anemia pada mata, bibir
pucat, tanda- tanda infeksi pada telinga, adanya pembesaran kelenjar tyroid
dan limfe, adanya retraksi dinding dada, pembesaran hepar, kelainan pada
genetalia, anus dan ektremitas.
Pada kasus Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan fisik yang telah
dilakukan, muka tidak oedem, konjungtiva merah muda, sclera putih, bentuk
payudara simetris, putting susu menonjol, ASI keluar lancar, sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sofian (2011), tinggi fundus uteri 2 minggu yaitu sudah tidak
teraba. Pada kasus Ny. R dilakukan pemeriksaan palpasi tinggi fundus uteri
329
sudah tidak teraba, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), masa puerperium diikuti pengeluaran cairan
sisa lapisan endometrium dan sisa dari implantasi plasenta yang disebut
lochea. Lochea Serosa berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi, pada hari
ke 7 – 14 pascapersalinan.
Pada kasus Ny. R pengeluaran pervaginam lochea serosa berwarna
kuning kecoklatan, sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Saleha (2009), tanda homan adalah metode yang dilakukan
untuk mengetahui adanya tromboflebitis, tanda homan positif dapat
menghambat sirkulasi darah ke organ distal.
Pada kasus Ny. R tidak ada tanda-tanda human. Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut Hani (2011), diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang di
tegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standard
nomenklatur diagnosa kebidanan.
Pada kasus yang penulis ambil didapat assesment yaitu Ny. R umur 33
tahun P3 A0 14 hari post partum dengan nifas normal.
d. Penatalaksanaan
Menurut Muslihatun (2009), planning atau penatalaksanaan adalah
membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan
disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Dalam planning juga
330
harus mencantumkan pelaksanaan dan evaluasi, pelaksanaan asuhan harus
sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.
Pada kasus yang penulis ambil penatalaksanaannya yaitu Memberitahu
ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan yaitu kaedaan ibu saat ini baik-
baik saja dan luka jahitannya sudah kering. Evaluasi, ibu sudah mengetahui
hasil pemeriksaan
Menurut Nugroho (2014), ibu nifas memerlukan nutrisi dan cairan untuk
pemulihan kondisi kesehatan setelah melahirkan, cadangan tenaga serta untuk
memenuhi produksi air susu ibu. Nutrisi dan cairan tersebut yaitu
mengandung karbohidrat, protein, lemak, zat besi, vitamin dan mineral.
Mengingatkan kembali pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang
bergizi tinggi tinggi kalori tinggi protein seperti yang mengandung
karbohidrat (padi, singkong, gandum, dan lain-lain), protein nabati (tahu,
tempe, kacang-kacangan dan lain-lain), protein hewani
(susu,telor,ikan,daging ayam,daging sapid an lain-lain), mineral dan vitamin
(sayur dan buah-buahan), lemak nabati (lemak jagung dan lain-lain), lemak
hewani (lemak ikan dan lain-lain). Evaluasi, ibu bersedia untuk mengonsumsi
makanan yang bergizi. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang kontrasepsi KB
meliputi
a. KB pil yaitu kontrasepsi yang mengandung hormone progesterone dan
estrogen. cara kerjanya seperti mencegah implantasi, menekan ovulasi,
mengentalkan lendir serviks, mempengaruhi pergerakan tuba sehingga
331
transportasi ovum terganggu. Keuntungan kb pil yaitu tidak mengganggu
hubungan seksual, dapat di gunakan sebagai metode jangka panjang, siklus
haid teratur. Kerugiannya yaitu mual, pusing, berat badan naik, nyeri
payudara, dan perdarahan hebat.
b. KB suntik yaitu kontrasepsi yang mengandung hormone progestin dan
estrogen yang di suntikan pada bokong, kb suntik terdiri dari kb suntik 1
bulan yaitu kb suntik yang mengandung hormone progestin dan estrogen.
keuntungan kb 1 bulan, menimbulkan haid yang teratur tiap bulan,
kesuburan lebih cepat kembali, setelah suntikan di hentikan, kerugian kb 1
bulan, penyuntikan lebih sering 1 bulan sekali, mempengaruhi ASI, dan kb
suntik 3 bulan yaitu suntikan yang mengandung hormone progestin saja,
dan tidak mempengaruhi pemberian ASI. Efek sampingnya haid tiak
teratur, mual dan sakit kepala, terjadi perubahan berat badan, keuntungan
KB suntik 3 bulan, penyuntikan di lakukan setiap 3 bulan, tidak
mempengaruhi produksi ASI.
c. KB kondom sarung karet tipis penutup alat kelamin laki-laki yang
menampung cairan sel mani saat pria ejakulasi, keuntungan murah, mudah
di beli, mudah di pakai sendiri, kerugian, selalu harus ada persendiaan
mengganggu kenyamanan senggama, kadang-kadang menimbulkan alergi.
d. Kb Implant/ Susuk Adalah kapsul batangan yang berbentuk seperti korek
api, ada yang berjumlah 2 biji untuk pemakaian 3 tahun dan 6 biji untuk 5
tahun. Keuntungan aman digunakan setelah melahirkan dan menyusui,
mengurangi nyeri haid. Kerugian nyeri kepala dan mual, peningkatan dan
332
penurunan berat badan, membutuhkan tindakan bedah minor untuk
pemasangan dan pencabutan.
e. Kb IUD/ AKDR Adalah alat kontrasepsi yang dimasukan kedalam Rahim,
umumnya berbentuk T. keuntungan metode jangka panjang 8-10 tahun,
tidak mempengatruhi ASI, kesuburan akan segera kembali jika alat
dikeluarkan, Kerugian terdapat bercak darah, dapat terjadi infeksi, efek
samping, nyeri/kram saat haid, keputihan.
f. Kb Tubektomi / MOW Adalah kontrasepsi permanen pada perempuan
untuk mereka yang tidak ingin mempunyai anak lagi. Keuntungan tidak
mempengaruhi ASI, tidak mengganggu hubungan intim. Kerugian peluang
untuk mempunyai anak lagi sangat kecil, memerlukan operasi minor.
Evaluasi, ibu sudah mengerti macam-macam kontasepsi.
Memberikan saran pada ibu KB yang cocok untuk ibu menyusui supaya
tidak mengganggu produksi ASI dan yang tidak mengandung hormonal yaitu
KB IUD. Evaluasi, ibu mengatakan akan mendiskusikan dulu dengan
suaminya.
Menurut Yefi (2015), kebijakan program nasional masa nifas paling
sedikit 4 kali kunjungan yang dilakukan yaitu 6-8 jam setelah persalinan, 6
hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan dan 6 minggu setelah
persalinan.
Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi atau
jika ada keluhan segera datang ke tenaga kesehatan. Evaluasi, ibu bersedia
untuk melakukan kunjungan ulang. Sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
333
D. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Normal
1. Pengkajian Data
Tanggal : 25 Agustus 2018
Jam : 19.15 wib
Tempat : Puskesmas Tarub
a. Data Subjektif
Menurut Anggraini (2010), data subjektif diperoleh dengan cara
tatap muka dengan pasien secara langsung, yang meliputi biodata pasien
dan keluhan utama.
1. Biodata
Menurut Sondakh (2013), untuk memudahkan identifikasi, perlu
adanya pengenal pada bayi.
Pada kasus ini didapatkan data subjektif Ibu mengatakan Bayi Ny.
R umur 0 hari jenis kelamin perempuan.
a) Nama
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), nama
lengkap ibu, termasuk nama panggilannya. Nama merupakan
identitas khusus yang membedakan seseorang dengan orang lain.
Hendaknya klien dipanggil sesuai dengan nama panggilan yang
biasa baginya atau yang disukainya agar klien merasa nyaman serta
lebih mendekatkan hubungan interpersonal bidan dengan klien.
Dalam praktek didapatkan ibu bernama Ny. R dan suami
bernama Tn. W. dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada
kesenjangan antara kasus dengan teori.
334
b) Umur
Menurut Manuba (2012), yang menjadi faktor resiko ibu hamil
adalah umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.
Sedangkan, usia ibu hamil yang termasuk usia reproduksi sehat
adalah usia 20-35 tahun. Alasan usia tersebut dikatakan reproduksi
sehat karena usia dibawah 20 tahun, Rahim dan panggul sering kali
belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akhirnya, ibu hamil pada
usia itu mungkin mengalami persalinan lama atau macet, atau
gangguan lainnya karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas
dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sedangkan pada umur
35 tahun atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun, akibatnya ibu
hamil pada usia itu mempuyai anak cacat, persalinan lama dan
perdarahan.
Pada kasus ini bernama Ny. R umur 33 tahun tergolong pada
umur normal atau umur produktif atau umur yang sehat pada masa
kehamilan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan
antara kasus dengan teori.
c) Agama
Menurut Anggraini (2010), diperlukan untuk mengetahui
keyakinan pasien tersebut untuk membimbing atau mengarahkan
pasien dalam berdoa.
Dalam kasus ini Ny. R memnganut agama Islam dan dari data
yang didapatkan tidak terdapat tradisi keagamaan ditempat tinggal
Ny. R yang merugikan kehamilannya dengan agama yang dianut.
335
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara
teori dan kasus.
d) Suku Bangsa
Menurut Anggraini (2010), berpengaruh pada adat istiadat atau
kebiasaan sehari – hari.
Pada kasus Ny. R suku bangsanya adalah jawa dan sudah
diberikan asuhan kebidanan sesuai sosial budaya Ny. R Dengan
demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara kasus
dengan teori.
e) Pendidikan
Menurut Sulistyawati (2010), pendidikan sebagai dasar bidan
untuk menentukan metode yang paling tepat dalam penyampaian
informasi. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi daya
tangkap dan tanggap pasien terhadap instruksi atau informasi yang
diberikan bidan pada pasien.
Dalam pengkajian data dalam hal pendidikan penulis
memperoleh data bahwa pada Ny. R berpendidikan SD. Jadi tidak
ada kesenjangan antara kasus dengan teori tersebut diatas karena
pasien menangkap atau memahami informasi yang telah diberikan
oleh Bidan.
f) Pekerjaan
Menurut Anggraini (2010), gunanya untuk mengukur tingkat
social ekonominya, karena ini juga mempengaruhi dalam gizi
pasien tersebut.
Pada kasus Ny. R pekerjaan yang dimiliki yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta
336
dengan penghasilan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian penulis tidak menemukan kesenjangan antara
kasus dengan teori.
g) Alamat
Menurut Widatiningsih dan Tungga Dewi (2017), alamat
memberi gambaran mengenai jarak dan waktu yang ditempuh
pasien menuju pelayanan kesehatan, serta mempermudah
kunjungan rumah bila diperlukan.
Ibu mengatakan beralamat di Desa Bulakwaru RT 10 RW 02
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Ny. R melakukan pemeriksaan
kehamilannya secara rutin ke pelayanan kesehatan, penulis juga
melakukan kunjungan rumah dalam rangka melakukan asuhan
kebidanan pada masa hamil sampai masa nifas, sehingga pada
kasus ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik.
2. Riwayat kesehatan keluarga
Menurut Muslihatun (2010), hidrosefalus merupakan kelainan
patologis bawaan pada otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan
serebrospinal dikarenakan adanya tekanan intrakranial yang
meningkat. Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki
riwayat penyakit kongenital dalam keluarga seperti kepala bayi
tampak lebih besar seperti ada cairan (hidrosefalus) sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Muslihatun (2010), mikrosefalus adalah kelainan
bawaan dimana lingkar kepala lebih kecil daripada ukuran normal
337
karena otak tidak berkembang dengan baik. Menurut Ny. R dalam
kasus ini bayinya tidak memiliki riwayat penyakit kongenital dalam
keluarga seperti kepala bayi tampak lebih kecil dari ukuran normal
(Mikrochefalus). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Sondakh (2013), anensephaly adalah kelainan bawaan
dimana sebagian besar tulang tengkorak dan otak bayi tidak terbentuk.
Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki riwayat
penyakit kongenital dalam keluarga seperti tidak ada tempurung
kepala (Anensephaly). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori
dan kasus.
Menurut Dewi (2013), atresia ani terjadi karena tidak adanya
lubang di tempat yang seharusnya berlubang karena cacat bawaan.
Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki riwayat
penyakit kongenital dalam keluarga seperti tidak ada lubang anus
(atresia ani). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sondakh (2013), sindaktili adalah kelainan bawaan yang
ditemukan pada jari-jari tangan, jari-jari tidak terpisah dan bersatu
dengan jari yang lain. Terjadi hanya pada kulit dan jaringan lunak
saja atau pada tulang dengan tulang. Menurut Ny. R dalam kasus ini
bayinya tidak memiliki riwayat penyakit kongenital dalam keluarga
seperti adanya perlekatan dua jari atau lebih (sindakttili). Sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
338
Menurut Sondakh (2013), polidaktili merupakan kelainan
genetika yang ditandai dengan banyaknya jumlah jari tangan atau jari
kaki melebihi normal. Polidaktili dapat terjadi pada kedua jari tangan
kanan dan kiri atau salah satu saja. Menurut Ny. R dalam kasus ini
bayinya tidak memiliki riwayat penyakit kongenital dalam keluarga
seperti jumlah jari lebih dari lima (Polidaktili). Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut World Health Organization (WHO) 2013, anemia adalah
suatu kondisi dimana terdapat kekurangan sel darah merah atau
hemoglobin dibawah batas normal, anemia bisa terjadi karena faktor
bawaan atau genetik yang ditandai dengan gejala badan terasa lemas
dan cepat lelah, kulit pucat atau kekuningan, detak jantung tidak
beraturan, nafas pendek, pusing berkunang-kunang, nyeri dada, tangan
dan kaki terasa dingin.Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak
memiliki riwayat penyakit kelainan darah dalam keluarga dengan
gejala lemas, pusing, pucat pada kuku dan telapak tangan, konjungtiva
pucat, nafsu makan turun dan detak jantung lebih cepat (Anemia).
Sehingga pada kasus Ny. R tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
Menurut Maryunani (2009), hemofilia merupakan penyakit
bawaaan yang menyebabkan gangguan perdarahan karena kekurangan
faktor pembekuan darah. Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya
tidak memiliki riwayat penyakit kelainan darah dalam keluarga
dengan gejala timbulnya rasa sakit dan kaku pada bagian kepala dan
339
leher, muntah, penglihatan kabur dan kejang (Hemofilia). Sehingga
tidak ada kesenjangan atara teori dan kasus.
Menurut Maryunani (2009), leukimia adalah kanker yang
menyerang sel-sel darah putih, dimana sel darah putih berfungsi untuk
melindungi tubuh dari penyakit. Menurut Ny. R dalam kasus ini
bayinya tidak memiliki riwayat penyakit kelainan darah dalam
keluarga dengan gejala sakit kepala disertai menggigil, demam, bintik
merah,dipermukaan kulit, muntah, keringat keluar di malam hari,
gampang terjadi perdarahan seperti memar dan mimisan (Leukimia).
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut J. Leveno (2013), penyakit infeksi seperti tuberculosis
(TBC) dapat mempengaruhi kehamilan seperti kelahiran premature,
berat badan lahir rendah (BBLR), retriksi pertumbuhan dan
meningkatkan angka mortalitas perinatal. Menurut Ny. R dalam kasus
ini bayinya tidak memiliki riwayat penyakit infeksi dalam keluarga
dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, demam
dimalam hari, berat badan menurun Tuberculosis (TBC). Sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Suhardjo (2010), penyakit infeksi hepatitis pada
kehamilan dapat meningkatkan kelahiran premature, infeksi neonatus
atau tertularnya hepatitis dari ibu ke bayi ditularkan secara vertikal
melalui penelanan cairan ibu yang terinfeksi peripartum, termasuk
ASI. Infeksi neonatal biasanya bisa dicegah dengan penapisan
prenatal dengan globulin imun hepatitis segera sesudah kelahiran.
340
Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki riwayat
penyakit infeksi dalam keluarga dengan gejala demam, mual, muntah,
mata dan kulit kuning, air seni berwarna kuning pekat seperti teh
(Hepatitis). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2014), penyakit menular seksual dapat
menimbulkan morbiditas dan mortalitas terhadap ibu maupun bayi
yang di kandungnya. Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak
memiliki riwayat penyakit infeksi dalam keluarga dengan gejala
keputihan berwarna hijau gatal dan berbau (IMS). Sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Ebie et al (2011), infeksi Saluran Kemih (ISK)
merupakan infeksi yang disebabkan adanya pertumbuhan
mikroorganisme di dalam saluran kemih. Menurut Ny. R dalam kasus
ini bayinya tidak memiliki riwayat penyakit infeksi dalam keluarga
dengan gejala sakit dan panas pada saat buang air kecil (ISK).
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut J. Leveno (2013), penyakit infeksi Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dapat menyebabkan komplikasi
kehamilan yaitu persalinan preterm, hambatan pertumbuhan janin, dan
lahir mati, dikaitkan dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus
(HIV) pada ibu. Penularan terjadi pada periode peripartum bayi lahir
dari ibu yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
tidak diobati akan terinfeksi. Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya
tidak memiliki riwayat penyakit infeksi dalam keluarga dengan gejala
341
batuk dan diare berkepanjangan, berat badan menurun drastis, muncul
ruam pada kulit, keringat dingin pada malam hari, sariawan yang tidak
kunjung sembuh, daya tahan tubuh menurun (HIV/AIDS). Sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Fadlu dan Feryanto (2013), Penyakit asma merupakan
kelainan saluran pernafasan yang ditandai dengan inflamasi saluran
nafas kronik dengan episode obstruksi saluran nafas akut akibat
adanya stimulus oleh berbagai macam alergen dan dalam kehamilan
berresiko keguguran, persalinan prematur atau gangguan pertumbuhan
janin .Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki riwayat
penyakit keturunan dalam keluarga dengan gejala sesak nafas disertai
bunyi ngik-ngik, batuk dan sesak diudara kotor dan dingin sehingga
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Leveno (2013), penyakit hipertensi dalam kehamilan
dapat menyebabkan solusio plasenta, preeklamsia, kelahiran
premature. Menurut Ny. R dalam kasus ini bayinya tidak memiliki
riwayat penyakit keturunan dalam keluarga dengan gejala sakit kepala
di bagian tengkuk dan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg
(Hipertensi). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Prawirohardjo (2014), ibu hamil dengan kelainan
jantung bawaan mempunyai kecenderungan untuk melahirkan bayi
dengan kelainan jantung bawaan. Menurut Ny. R dalam kasus ini
bayinya tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dalam keluarga
dengan gejala jantung berdebar-debar, mudah lelah, nyeri dada bagian
342
atas dan bila dibawa istirahat tidak hilang (Jantung). Sehingga tidak
ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Maryunani (2009), penyakit diabetes mellitus pada
kehamilan dapat menyebabkan resiko ibu seperti abortus spontan,
preeklamsia atau hipertensi akibat kehamilan, persalinan preterm,
polihidramnion, infeksi, hipoglikemia. Dan resiko komplikasi pada
janin dapat menyebabkan hipoglikemia, hiperglikemia, kelainan
kongenital/malformasi, macrosomia, pertumbuhan janin terhambat,
ketoasidosis dan kematian janin. Menurut Ny. R dalam kasus ini
bayinya tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dalam keluarga
dengan gejala sering buang air kecil, cepat lapar dan haus serta mudah
mengantuk Diabetes Militus (DM). Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Manuaba (2010), bahwa riwayat kesehatan perlu dikaji
karena jika terdapat cacat lahir perlu dilakukan evaluasi mendalam
dan adanya hamil kembar sering bersifat menurun. Menurut Ny. R
dalam kasus ini bayinya tidak memiliki keturunan riwayat bayi
kembar (Gemelli). Sehingga pada kasus ini tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
3. Riwayat kehamilan
Kehamilan ini merupakan kehamilan yang ketiga dan tidak
pernah mengalami keguguran, antenatal care (ANC) pada trimester I
ibu melakukan pemeriksaan 2x di puskesmas, trimester II sebanyak
4x (3x di puskesmas dan 1x di dr. SpOg), trimester III sebanyak 5x
343
(3x di puskesmas 1x di Bpm 1x di dr SpOg), ibu mengatakan selalu
mendapatkan tablet tambah darah dan di minum 1x1 setiap malam
rutin selama hamil, ibu mengatakan sudah mendapatkan imunisasi TT
1x pada tanggal 21 Agustus 2018.
4. Riwayat Kontrasepsi/KB
Menurut Anggraini (2010), untuk mengetahui apakah pasien
pernah ikut keluarga berencana dengan kontrasepsi jenis apa, berapa
lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta
rencana selanjutnya akan menggunakan kontrasepsi apa.
Riwayat penggunaan kontrasepsi Ny. R, mengatatakan pernah
memakai keluarga berencana pil dan alasan lepasnya karena sedang
mengkonsumsi obat tuberculosis. Dan rencana yang akan datang ibu
mengatakan ingin menggunakan keluarga berencana suntik, karena
lebih praktis. Dengan demikian antara teori dan kasus tidak ada
kesenjangan.
5. Kebutuhan sehari-hari bayi
Menurut Sondakh (2013), air susu ibu (ASI) eksklusif yaitu
memberikan air susu ibu (ASI) saja tanpa tambahan makanan
apapun kecuali vitamin dan obat-obatan dari bidan atau dokter
sampai bayi berusia 6 bulan, dan menyusui bayi sesuai keinginan
atau (On Demand).
Pada kasus ini ibu mengatakan bayinya hanya di berikan air
susu ibu (ASI). Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
344
Menurut Sondakh (2013), personal hygiene pada bayi yakni
setiap kali bayi buang air kecil atau buang air besar segera bersihkan
dan keringkan dengan baik, mengganti kasa pada tali pusat bayi
setiap mandi untuk mencegah terjadinya infeksi, mandi 2 kali sehari
untuk mencegah terjadinya.
Pada kasus ini Bayi belum dimandikan, belum ganti popok, dan
belum ganti baju. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus.
b. Data obyektif
Menurut Sofian (2011), macam-macam persalinan dibagi menjadi
dua yaitu berdasarkan cara persalinan dan umur kehamilan, menurut cara
persalinan ada partus normal atau disebut partus spontan.
Persalinan pada tanggal 25 Agustus 2018 jam 17.15 wib, jenis
persalinan spontan, penolong persalinan bidan, selama proses persalinan
hanya di berikan suntik Oxytocin 10 ui pada kala III. lama persalinan
kala I 16 jam, kala II 15 menit, kala III 10 menit. ketuban pecah jam
17.10 wib warna jernih, bau khas.
Segera setelah lahir dilakukan tindakan pernilaian segera setelah
lahir tangisan kuat, kulit kemerahan, gerakan aktif, mengeringkan bayi,
perawatan dan pemotongan tali pusat dan inisiasi menyusui dini (IMD).
345
Nilai Apgar Score
1’ 5’ 10’
A : Appeareance 2 2 2
P : Pulse 2 2 2
G : Grimace 2 2 2
A : Activity 2 2 2
R : Respiration 2 2 2
Jumlah 10 10 10
2. Intepretasi Data
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), Langkah ini
adalah menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan
sehingga ditemukan diagnosis atau masalah.
d. Diagnosa (Nomenklatur)
Menurut Hani (2011), diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang
di tegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi
standar nomenklatur diagnosa kebidanan.
Bayi Ny. R lahir spontan jenis kelamin perempuan, menangis
kuat, keadaan baik, bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit
kemerahan, dengan bayi baru lahir normal. sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
e. Masalah
Menurut Sulistyawati (2013), dalam asuhan kebidanan istilah
masalah atau diagnosa keduanya dapat dipakai karena beberapa
346
masalah tidak didefinisikan sebagai diagnosa, tetapi perlu
dipertimbangkan untuk membuat rencana yang menyeluruh. Masalah
sering berhubungan bagaimana wanita itu mengalami kenyataan
terhadap diagnosanya.
Pada kasus bayi Ny. R tidak ditemukan adanya masalah, sehingga
tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
f. Kebutuhan
Menurut Hani (2011), kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan
oleh klien dan belum teridentifikasikan dalam diagnosa dan masalah
yang didapatkan dengan melakukan analisis data.
Pada kasus bayi Ny. R tidak ditemukan adanya masalah, sehingga
dalam hal ini tidak ada kebutuhan dan tidak menemukan kesenjangan
antara teori dan kasus.
3. Diagnosa potensial
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan
rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan
temuan tersebut bidan dapat melakukan antisipasi agar diagnosis atau
masalah tersebut tidak terjadi.
Pada kasus bayi Ny. R tidak ditemukan diagnosa potensial sehingga
tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
4. Antisipasi Penanganan Segera
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter
347
untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim
kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien.
Pada kasus bayi Ny. R tidak ditemukan antisipasi penanganan segera
sehingga tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus.
5. Intervensi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), direncanakan
asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah
sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi hal
yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah
yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan terjadi
selanjutnya. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui oleh kedua
belah pihak yaitu bidan dan pasien
Pada langkah ini penulis melakukan intervensi sesuai kebutuhan bayi
Ny. R diantaranya seperti Lakukan pemeriksaan antropometri. Beritahu
ibu hasil pemeriksaan fisik yang telah di lakukan. Berikan Vitamin K dan
salep mata. Lakukan perawatan tali pusat. Pertahankan suhu tubuh bayi
agar tetap hangat. Pastikan bayi mendapatkan ASI. Beritahu ibu tanda
bahaya bayi baru lahir. Berikan imunisasi Hb 0.
6. Implementasi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), langkah ini
adalah melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah
kelima (perencanaan) secara aman dan efisien. Realisasi dari
perencanaan yang dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota
keluarga yang lain.
348
Menurut Sondakh (2013), perawatan bayi baru lahir yaitu menjaga
kehangatan, melakukan pencegahan infeksi, merawat tali pusat, memberi
tahu tanda – tanda bahaya pada bayi baru lahir, memberitahu tentang
nutrisi pada bayi. Melakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil
keadaan bayi sehat dan normal bayi kepala mesochepal, tidak ada caput
succedenum, tidak ada cepal hematoma, sutura sudah menutup, muka
warna kemerahan, tidak ada tanda lahir, mata bentuk simetris, tidak ada
kelainan, reflek pupil aktif, hidung bentuk normal, tidak ada nafas cuping
hidung, tidak ada kelainan, mulut dan bibir merah muda, tidak ada
cyanosis, tidak ada labioskisis dan labiopalatoskisis, telinga bentuk
simetris, tidak ada kelainan, kulit warna kemerahan, dada bentuk
normal, tidak ada retraksi dinding dada, abdomen bentuk simetris, tidak
ada perdarahan tali pusat, genetalia labia mayor menutupi labia minor,
ada lubang anus, ekstermitas atas dan bawah tidak ada polidaktil dan
sindaktil, kuku tidak pucat, dan gerakan aktif, rooting ada dan aktif,
reflek graps ada aktif, reflek sucking ada aktif, reflek moro ada aktif,
tonic neek ada aktif, reflek babynski ada aktif, sehingga tidak ada
kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah di lakukan dengan
hasil keadaan bayi ibu saat ini sehat dan normal. Jenis kelamin
perempuan, Suhu 36,7o C, denyut jantung 124 x/menit, Pernapasan 44
x/menit ,Berat badan 3700 gram, lingkar kepala 34 cm, Panjang
badan : 49 cm, lingkar dada 33 cm.
349
Menurut Sofian (2011), vitamin K merupakan vitamin larut dalam
lemak yang memiliki peranan dalam pembekuan darah. Pemberian
suntikan vitamin K 1 mg dilakukan pada setiap bayi baru lahir sebagai
tindakan pencegahan terjadinya perdarahan karena perdarahan akibat
defisiensi vitamin K (PDVK). Memberikan suntikan Vitamin K pada
paha kiri bayi bagian luar secara intra muscular, dan salep mata
tetracyclin pada mata kanan dan kiri. Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Melakukan perawatan tali pusat yaitu menyiapkan kasa steril
kmudian dibersihkan tali pusat dari pangkal hingga ujung tali pusat
kemudian membungkus tali pusat dengan kassa steril tanpa tambahan
apapun.
Menurut Sondakh (2013), tetap menjaga kehangatan bayi baru lahir
ketika dipindahkan dari pemancar panas dapat mencegah terjadinya
hipotermi yaitu dengan memakaikan pakaian, topi dan selimut yang
kering, mengganti popok ketika basah, jangan meletakkan bayi dekat
dengan jendela, dinding atau benda apapun yang dingin.
Mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara mengganti kain yang
kotor dengan kain yang bersih dan kering, kemudian membedong bayi
dan memakaikan topi ke kepala bayi. Sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
Menurut Sondakh (2013), Inisiasi Menyusui Dini (IMD) atau
permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera
setelah lahir. Kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya dibiarkan
350
setidaknya selama 1 jam segera setelah lahir, kemudian bayi akan
mencari payudara ibu dengan sendirinya. Cara bayi melakukan inisiasi
menyusui dini ini dinamakan the brest crawl atau merangkak mencari
payudara. Memastikan bayi mendapat ASI segera setelah bayi lahir dari
ibu. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Menurut Sondakh (2013), tanda bahaya bayi baru lahir yaitu
pernapasan sulit atau lebih dari 60 kali/menit, warna kulit kuning
(terutama pada 24 jam pertama), biru atau pucat, tali pusat merah,
bengkak, keluar cairan, bau busuk, berdarah, suhu meningkat lebih dari
37,50C, sering kejang. Memberitahu tanda bahaya bayi baru lahir yaitu
bayi tidak mau menyusu, pernafasan cepat, warna kulit pucat, bayi
merintih. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberikan imunisasi HB 0 dengan dosis 0.5 cc pada bagian paha
kanan bayi bagian luar secara inta muscular di berikan 1 jam setelah
Vitamin K.
7. Evaluasi
Menurut Helen Varney dalam Mangkuji dkk (2013), pada langkah
ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan
kepada pasien. Dalam melakukan evaluasi seberapa efektif tindakan dan
asuhan yang kita berikan kepada pasien, kita perlu mengkaji respon
pasien dan meningkatkan kondisi yang kita targetkan pada panyusunan
perencanaan. Hasil pengkajian ini kita jadikan sebagai acuan dalam
penatalaksanaan berikutnya.
351
Pada kasus bayi Ny. R telah dilakukan kefektifan dan asuhan yang
telah diberikan yaitu Ibu sudah mengetahui keadaan bayinya saat ini. Ibu
sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ibu sudah
mengetahui bayinya sudah di berikan vitamin K. Ibu sudah mengetahui
cara perawatan tali pusat. Ibu sudah mengerti cara menjaga suhu tubuh
bayi. Ibu sudah memberikan asi kepada bayinya . Ibu sudah mengetahui
tanda bahaya bayi baru lahir.Ibu sudah mengetahui bayinya sudah di
berikan imunisasi HB 0. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan
kasus
352
KUNJUNGAN NEONATAL KE 2 (6 HARI)
Tanggal : 31 Agustus 2018
Jam : 19.00 wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Menurut Kemenkes RI (2010), anamnesis ditanyakan pada ibu atau
keluarganya tentang masalah kesehatan pada bayinya.
Menurut Manuaba (2010), ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi
ASI saja tanpa tambahan makanan apapun kecuali vitamin, mineral dari
tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter sampai bayi berumur 6 bulan.
Pada kasus ini ibu mengatakan tidak ada masalah pada bayinya, ibu
mengatakan bayinya tidak ada keluhan, menyusu kuat, buang air kecil lebih
dari 6 kali, buang air besar setiap hari 1-2 kali konsistensi lembek. Sehingga
tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
b. Data Obyektif
Menurut Sondakh (2013), kriteria bayi baru lahir normal apabila berat
badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar kepala 33-35 cm,
lingkar dada 31-33 cm, bunyi jantung dalam satu menit pertam ± 180
kali/menit, kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi
berumur 30 menit, pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80
kali/menit disertai pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan
interkostar, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit, kulit kemerahan
dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan dilapisi verniks
353
kaseosa, rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik, kuku agak
panjang dan lemas, genetalia: testis sudah turun ke skrotum (pada bayi laki-
laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan),
reflek hisap, menelan dan moro telah terbentuk, eliminasi urin dan mekonium
normalnya keluar pada 24 jam pertama.
Menurut Sondakh (2013), fungsi ginjal belum sempurna selama dua
tahun pertama kehidupannya. Biasanya terdapat urin dalam jumlah yang kecil
pada kandung kemih bayi saat lahir, tetapi ada kemungkinan urin tersebut
tidak dikeluarkan selama 12-24 jam. Berkemih sering terjadi setelah periode
ini dengan frekuensi 6-10 kali sehari dengan warna urin yang pucat. Kondisi
ini menunjukkan masukan cairan yang cukup.
Menurut Sofian (2011), fungsi tali pusat adalah menjaga kelangsungan
hidup bayi dalam kandungan dengan menyalurkan osksigen dan nutrisi,
setelah bayi dilahirkan tali pusat di potong dan diikat karena bayi sudah bisa
bernafas sendiri. Tali pusat dalam beberapa hari akan terlepas sendiri setelah
mengalami proses nekrosis menjadi kering pada hari ke 6 sampai hari ke 8
dengan meninggalkan granulasi kecil yang setelah sembuh akan membentuk
umbilikus atau pusar.
Pada kasus bayi Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan Keadaan umum
bayi baik, berat bayi 3900 gram, panjang badan 52 cm, suhu badan 37,0oC,
denyut jantung 120 x/menit, pernafasan 40 x/menit, mata tidak ikterik, bayi
menyusu kuat kebutuhan asi terpenuhi, tali pusat sudah kering dan lepas pada
tanggal 30 agustus 2018, tidak ada ruam pada kulit bayi, bayi aktif dan tidak
rewel, perut bayi tidak kembung, dalam sehari bayi buang air kecil kurang
354
lebih 6-7 kali, buang air besar 1-2 kali konsistensi lembek, warna kuning
kecoklatan, kebersihan, bayi dimandikan sehari 2 kali pagi dan sore hari,
ganti popok setiap kali bayi buang air kecil dan besar dan selalu di bersihkan
area genetalia sampai bokong menggunakan air dan sabun/ tisu basah.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut Mangkuji dkk (2013), assesment adalah pendokumentasian
hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu
identifikasi. Pada kasus bayi Ny. R didapatkan kesimpulan dari uraian data
subyektif dan data obyektif adalah Bayi Ny, R umur 5 hari jenis kelamin
perempuan dengan bayi baru lahir normal. sehingga tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Mangkuij, dkk (2013), planning merupakan pendokumentasian
tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment. Rencana asuhan
ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal
mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya.
Pada kasus yang penulis ambil memberikan asuhan antara lain
Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan
bayinya saat ini baik dan sehat. Mengingatkan kembali tanda bahaya bayi
baru lahir yaitu tidak mau menyusu, suhu tubuh naik, bayi rewel.
Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri bayi dengan cara
memandikan bayi 2 x sehari, ganti baju 2x sehari, mengganti popok setelah
bayi buang air kecil dan besar. Mengingatkan kembali ibu untuk selalu
355
memberikan asi esklusif tanpa tambahan makanan apapun kecuali obat dan
vitamin.
Menurut Sondakh (2013), tanda bahaya bayi baru lahir yaitu pernapasan
sulit atau lebih dari 60 kali/menit, warna kulit kuning (terutama pada 24 jam
pertama), biru atau pucat, tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, bau busuk,
berdarah, suhu meningkat lebih dari 37,50C, sering kejang. Mengingatkan
kembali tanda bahaya bayi baru lahir yaitu tidak mau menyusu, suhu tubuh
naik, bayi rewel. Evaluasi ibu sudah mengerti tanda bahaya bayi lahir.
Sehinga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan diri bayi dengan cara
memandikan bayi 2 x sehari, ganti baju 2x sehari, mengganti popok setelah
bayi buang air kecil dan besar. Evaluasi ibu selalu menjaga kebersihan
bayinya.
Mengingatkan kembali ibu untuk selalu memberikan asi esklusif tanpa
tambahan makanan apapun kecuali obat dan vitamin. Evaluasi ibu selalu
memberikan asi dan tidak memberikan makanan tambahan apapun.
356
KUNJUNGAN NEONATAL KE III (14 Hari)
Tanggal : 08 september 2018
Jam : 14.00 wib
Tempat : Rumah Ny. R
a. Data Subyektif
Menurut Kemenkes RI (2010), anamnesis ditanyakan pada ibu atau
keluarganya tentang masalah kesehatan pada bayinya.
Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan, menyusu kuat.
b. Data Obyektif
Menurut Sondakh (2013), kriteria bayi baru lahir normal apabila berat
badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar kepala 33-35 cm,
lingkar dada 31-33 cm, bunyi jantung dalam satu menit pertam ± 180
kali/menit, kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat bayi
berumur 30 menit, pernafasan cepat pada menit-menit pertama kira-kira 80
kali/menit disertai pernafasan cuping hidung, retraksi suprasternal dan
interkostar, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit, kulit kemerahan
dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk dan dilapisi verniks
kaseosa, rambut lanugo telah hilang, rambut kepala tumbuh baik, kuku agak
panjang dan lemas, genetalia: testis sudah turun ke skrotum (pada bayi laki-
laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (pada bayi perempuan),
reflek hisap, menelan dan moro telah terbentuk, eliminasi urin dan mekonium
normalnya keluar pada 24 jam pertama.
357
Pada kasus bayi Ny. R didapatkan hasil pemeriksaan Keadaan umum
bayi baik. Keadaan umum bayi baik, berat bayi 3900 gram, panjang badan 52
cm, suhu badan 36,5oC, denyut jantung 120 x/menit, pernafasan 42 x/menit,
mata tidak ikterik, bayi menyusu kuat kebutuhan asi terpenuhi, bayi aktif dan
tidak rewel, perut bayi tidak kembung, dalam sehari bayi buang air kecil
kurang lebih 6-7 kali, buang air besar 1-2 kali konsistensi lembek, warna
kuning kecoklatan, kebersihan, bayi dimandikan sehari 2 kali pagi dan sore
hari, ganti popok setiap kali bayi buang air kecil dan besar dan selalu di
bersihkan area genetalia sampai bokong menggunakan air dan sabun/ tisu
basah. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
c. Assesment
Menurut Mangkuji dkk (2013), assesment adalah pendokumentasian
hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu
identifikasi. Bayi Ny. R umur 14 hari jenis kelamin perempuan dengan bayi
baru lahir normal. sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
d. Penatalaksanaan
Menurut Mangkuij, dkk (2013), planning merupakan pendokumentasian
tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment. Rencana asuhan
ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal
mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya.
Memberitahu kapada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu
keadaan bayi saat ini baik-baik saja.
Menurut Sondakh (2013), orang tua di ajarkan cara merawat bayi dan
melakukan perawatan harian untuk bayi baru lahir meliputi pemberian ASI
358
sesuai dengan keb2utuhan setiap 2-3 jam, dimulai dari hari pertama, menjaga
kehangatan bayi dengan kain bersih, hangat dan kering, serta mengganti
popok jika basah atau kotor, menjaga tali pusat tetap bersih dan kering serta
menjaga keamanan bayi terhadap infeksi dan trauma. Mengingatkan kembali
ibu untuk menjaga kebersihan diri bayi dengan cara memandikan bayi 2 x
sehari, ganti baju 2x sehari, mengganti popok setelah bayi buang air kecil dan
besar gunanya untuk mencegah terjadinya iritasi. Evaluasi ibu selalu menjaga
kebersihan bayinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
Mengingatkan ibu untuk rutin ke posyandu untuk imunisasi bayi &
melakukan tumbuh kembang bayinya. Evaluasi ibu bersedia membawa
bayinya ke posyandu.
Menurut Dewi (2013), jadwal kunjungan neonatus pertama 6-8 jam,
kunjungan neonatus ke dua 3-7 hari, dan kunjungan neonatus ke tiga 8-28
hari. Memberitahu ibu jika terjadi sesuatu pada bayi seperti suhu badan naik/
panas, diare, menangis terus menerus. untuk segera di bawa ke tenaga
kesehatan / puskesmas terdekat untuk di berikan penanganan yang tepat.
Evaluasi ibu mengerti penjelasan bidan.
359
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin,
nifas normal dan bayi baru lahir normal sejak tanggal 21 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 08 September 2018, hasil yang didapatkan sesuai
dengan yang diharapkan yaitu :
1. Pada langkah pengumpulan data dasar baik data subyektif maupun data
obyektif yang diperoleh dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru
lahir Ny. R secara fisiologis berjalan dengan normal. Sehingga penulis
tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus
2. Pada langkah interpretasi data sesuai dengan data subyektif dan data
obyektif yang diperoleh pada kasus Ny. R didapatkan diagnosa :
a. Kehamilan
Ny. R umur 33 tahun GIII PII A0 hamil 40 minggu janin tunggal,
hidup, intra uterin, letak memanjang, punggung kanan, presentasi
kepala, konvergen dengan resiko tinggi pada kehamilan.
b. Persalinan
Ny. R umur 33 tahun GIII PII A0 hamil 40 minggu + 2 hari janin
tunggal, hidup intra uteri, letak memanjang , punggung kanan,
presentasi kepala divergen dengan inpartu kala II normal
360
c. Nifas
Ny. R umur 33 tahun P3 A0 2 jam, 6 hari, 14 hari post partum dengan
nifas normal
d. Bayi baru lahir (BBL)
Bayi Ny. R umur 0 hari, 6 hari, 14 hari jenis kelamin perempuan
dengan bayi baru lahir normal.
Pada langkah diagnosa potensial Ny. R pada kehamilannya terdapat
diagnosa potensial bahaya bagi ibu sesak napas, batuk
berkepanjangan. Bahaya bagi janin yaitu bayi bisa lahir dengan berat
badan rendah, dalam kondisi terburuk, jika TBC ibu tertular pada bayi
yang sedang di kandung, pertumbuhan janin akan menjadi lambat,
bahkan, kondisi tersebut bisa mengakibatkan keguguran. Pada
persalinannya terdapat diagnosa potensial Ibu mengalami sesak nafas,
batuk-batuk, lemas. Bagi janin fetal distres
Pada langkah ini antisipasi penanganan segera yang dilakukan
yaitu pada kehamilan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan
(SpOg). Pada persalinan kolaborasi dengan dokter Puskesmas Tarub.
3. Pada langkah perencanaan atau asuhan pada kehamilan, persalinan, nifas
dan bayi baru lahir (BBL) Ny. R sudah sesuai dengan teori yaitu asuhan
kebidanan sesuai dengan perencanaan kebutuhan pasien.
4. Pada langkah pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif adalah pada
asuhan kehamilan patologis dengan dilakukannya mulai dari anamnesa
kemudian pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.
Persalinan normal, nifas normal dan bayi baru lahir (BBL) normal
361
dilakukan dengan pemberian asuhan, pemeriksaan dan kunjungan rumah.
Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.
5. Pada langkah pelaksanaan evaluasi terhadap tindakan asuhan kebidanan
dalam kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir (BBL) Ny. R yang
dilakukan juga sesuai dengan harapan.
B. SARAN
1. Untuk Tenaga/Pelayanan Kesehatan
Diharapkan dapat meningkatkan dalam mutu pelayanan medis,
melaksanakan pelayanan kebidanan secara komprehensif sesuai dengan
kompetensinya dan meningkatkan kualitas antenatal care terpadu dengan
mengikuti sertakan semua petugas sesuai dengan peran atau tugasnya
seperti perlu adanya nutrisionis untuk memantau gizi pada ibu hamil
khusunya ibu hamil dengan resiko tinggi.
2. Untuk Institusi
Diharapkan dapat mengembangkan penelitian untuk meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan mahasiswa tentang asuhan kebidanan pada
kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.
3. Untuk Mahasiswa
Dengan adanya pembuatan karya tulis ilmiah ini, mahasiswa
diharapkan bisa meenjadi motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan
keterampilan terutama dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang terbaik di masyarakat dalam
rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
362
4. Untuk masyarakat
Diharapkan untuk masyarakat agar kebih memahami dan mengerti
akan bahaya hamil beresiko tinggi serta di harapkan pula untuk ibu hamil
selalu memantau perkembangan kehamilannya dengan melakukan
pemeriksaan yang rutin dan selalu menjaga keadaannya. sehingga tidak
terdapat resiko yang membahayakan bagi ibu dan janin.
DAFTAR PUSTAKA
Adipati. 2013. Asuhan Patologi Kehamilan. Yogjakarta: Nuha Medika.
Atikah. 2011. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo.
Amin. 2019. Tingkat pengetahuan ibu primigravida tentang persiapan persalinan
normal. Kebumen
Anonim. 2008. Perencanaan persalinan Puskesmas . Bandar Lampung: Depkes
Sofian. 2011. Penyakit tuberculosis paru. Jakarta.
Depkes RI. 2007. Tentang Kebidanan. Jakarta.
Dinkes Kabupaten Tegal 2016. Angka kematian ibu dan bayi. Dinkes Kabupaten
Tegal.
Dinkes Jateng 2017. Profil Kesehatan AKI dan AKB. Jateng.
Kementrian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat
Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA). Jakarta: Departemen Kesehatan
Kristiyanasari 2010. Gizi ibu hamil. Yogyakarta : Nuha Medika
Manuaba, IBG. 2009. Gawat Darurat Obstetri Ginekologi dan Obstretri
Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan. Jakarta: EGC.
Manuaba, IBG. 2009. Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta: EGC.
Proverawati. 2009. Buku Ajar Gizi Untuk Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.
Prawirohardjo, Sarwono. 2007. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
Prawirohardjo, Sarwono. 2009. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina
Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Purwandari. 2016. Hubungan antara paritas ibu dengan kejadian plasenta previa.
Surakarta.
Rukiyah, Ai Yeyeh, et al. 2009. Asuhan Kebidanan IV (Patology Kebidanan).
Jakarta: CV. Trans Info Media
Rukiyah, Ai Yeyeh, et al. 2011. Asuhan Kebidanan I (Kehamilan). Jakarta: CV.
Saifudin. 2009. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: YBP-S.
Sulistyawati. 2012. Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan. Jakarta: Salemba
Medika.
Anggraini, Yeti. 2010. Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Yogyakarta : Pustaka
Rihama.
Arfiana dan Lusiana Arum. 2016. Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita dan Anak
Prasekolah. Yogyakarta : Transmedika.
Arisman, 2009. Buku Ajar Ilmu Gizi dalam daur Kehidupan. Jakarta : Penerbit
Buku Kedokteran.
Asfuah, Sitidan, Proverawati, Atikah. 2009. Buku Ajar Gizi Untuk Kebidanan.
Yogyakarta : Nuha Medika
Depkes RI.2012. Kekurangan Energi Kronis. Jakarta : Depkes RI.
Dinkes. Kabupaten Tegal 2017. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi
Kabupaten Tegal. Dinkes Kabupaten Tegal.
Dinkes. Provinsi Jateng. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2017.
Eny Retna Ambarwati dan Diah Wulandari. 2010. Asuhan Kebidanan Nifas.
Yogyakarta : Nuha Medika.
Hani, Umi. 2011. Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis. Jakarta :
Salemba Medika.
Ida Ayu Chandranita Manuaba, dkk. 2010. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan,
dan KB untuk pendidikan bidan. Jakarta : EGC.
Kemenkes Kesehatan RI. 2013. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas
Kesehatan Dasar dan Rujukan. World Health Organization.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Pedoman Penanggulangan
Kurang Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil. Direktorat Bina Gizi.
Kementrian Kesehatan RI. 2010. Buku Saku Kesehatan Neonatal dan Esensial.
Kementrian Kesehatan RI. 2017. Profil Kesehatan Indonesia 2016. Jakarta :
Kemenkes RI.
Kusmiyati, Y & Heni Wahyuningsih & Sujiyanti. 2009. Perawatan Ibu hamil
(Asuhan Ibu Hamil). Yogyakarta : Fitrimaya.
Larasati. 2018. Hubungan Paritas Terhadap Kejadian Plasenta Previa di RSIA
Sitti Khadijah I Makassar. Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia. Vol 2
(1) : 56 – 62.
Leveno J. Kennenth. 2013. Manual Williams Komplikasi Kehamilan. Jakarta :
Penerbit buku kedokteran EGC.
Lia, D & Vivian Nannya & Tri Sunarsih. 2011. Asuhan Neonatus Bayi dan Anak
Balita. Jakarta : Salemba Medika.
Maryunani, A & Retno Murti Suryaningsih & Ery Fatmawati. 2011. Asuhan
Kebidanan Patologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Mufdillah, dkk. 2012. Konsep Kebidanan Edisi Revisi. Yogyakarta : Nuha
Medika.
Muslikhatun, W. 2009. Dokumentasi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya.
Pantikawati. 2010. Asuhan Kebidanan I (Kehamilan). Yogyakarta : Nuha Medika.
Prawirohardjo, Sarwono. 2009. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan dan
Neonatal, Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohadrjo.
Prawirohardjo, Sarwono. 2014. Buku Acuan Pelayanan Kesehatan Maternal dan
Neonatal. Jakarta : Bina Pustaka.
Proverawati, Atikah. 2011. Anemia dan Anemia Kehamilan. Yogyakarta : Nusa
Medika.
Puskesmas Pagiyanten 2017. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi
Kabupaten Tegal. Dinkes Kabupaten Tegal.
Rohani dan Reni Saswita. 2011. Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan.
Jakarta: Salemba Medika
Rukiyah, A., Lia Yulianti, Hj. Maemunah, & Hj. Lilik Susilawati. 2009. Asuhan
Kebidanan 4. Jakarta : Trans Info Media.
Rukiyah, A., Lia Yulianti, Hj. Maemunah, & Hj. Lilik Susilawati. 2009. Asuhan
Kebidanan I (Kehamilan). Jakarta : Trans Info Media.
Saleha, Sitti. 2009. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Jakarta : Salemba
Medika.
Sofian, Amru. 2011. Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri. Jakarta : EGC
Sondakh,J.J. 2013. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta :
Salemba Medika.
Sukmawati, Lilis Mamuroh, Witdiawati 2018. Faktor Yang Berhubungan Dengan
Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Pembangunan.
Jurnal Keperawatan BSI. Vol 6 (1) : 1 – 11.
Sulistyawati, A. 2011. Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan. Jakarta :
Salemba Medika.
Sulistyawati, A. 2012. Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan. Jakarta :
Salemba Medika.
Sulistyawati, A. 2013. Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan. Jakarta :
Salemba Medika.
Sulistyawati, Ari. 2009. Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan. Jakarta :
Salemba Medika.
Waryono. 2010. Gizi Reproduksi. Yogyakarta : Pustaka Rihama.
Widatiningsih dan Tungga Dewi. 2017. Praktik Terbaik Asuhan Kehamilan.
Jakarta: Trans Medika.
Yefi Marliandiani dan Nyna Puspita Ningrum. 2015. Asuhan Kebidanan Pada
Masa Nifas dan Menyusui. Jakarta : Salemba Medika.
Yulifah, Rita. 2014. Konsep Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika.
Meiyanti, 2007. Penatalaksanaan tuberculosis pada kehamilan. Vol.26 – No. 3
Najoan Nan Warouw*, Aloysius Suryawan** (2007). Manajaemen TBC dalam
Kehamilan .
ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. R DI PUSKESMAS TARUB
KABUPATEN TEGAL
(Studi Kasus Faktor Risiko dengnan Riwayat Tuberculosis Paru) Ade Runita Kurnianingsih1, Novia Ludha Arisanti2, Meyliya Qudriani3
Email : [email protected] 1, 2 Diploma III Kebidanan Politeknik Harapan Bersama Tegal, 3 Diploma III
Kebidanan, Politeknik Harapan Bersama Tegal
Abstrak Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tegal tahun 2016 terdapat 33 kasus kematian per
27.314 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu
14 kasus kematian per 24.225 kelahiran hidup dan menurut data angka kematian ibu di Puskesmas
Tarub pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2 kasus kematian yang disebabkan karena emboli air ketuban
dan penyakit jantung. Menurut data yang di peroleh dari Puskesmas Tarub tahun 2017 jumlah ibu
hamil yang termasuk faktor resiko sebanyak 323 dan resiko tinggi sebanyak 52 dari jumlah ibu hamil
1018, ibu hamil dengan faktor resiko umur >35 tahun sebanyak 123 kasus dan ibu hamil dengan
penyakit paru-paru sebanyak 10 kasus dari total ibu hamil di Puskesmas Tarub.
Tujuan Umum meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa untuk memperoleh
gambaran dan pengalaman secara nyata yang dapat digunakan dalam memberikan Asuhan Kebidanan
pada ibu dengan faktor resiko umur lebih 35 tahun, berdasarkan menejemen kebidanan yang
didokumentasikan menggunakan 7 langkah Varney dan metode SOAP.
Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode kasus yaitu bertujuan untuk mengetahui
penatalaksanaan pada kasus yang akan dikaji sesuai dengan Standar Manajemen Kebidanan. Dalam
penyususnan Karya Tulis Ilmiah ini berdasarkan teori yang dipadukan dengan praktik dan pengalaman
penulis memerlukan data yang obyektif dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam
pemecahan masalah dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan (Observasi)pemeriksaan
fisik, dokumentasi,studi keputusan.
Memuat keseluruhan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan. Jenis kasus yang diambil yaitu
kasus komprehensif resiko tinggi. Kasus dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
Asuhan kebidanan ditulis sesuai dengan urutan manajemen kebidanan 7 langkah Varney, yaitu mulai
dari pengumpulan data sampai evaluasi pada asuhan kebidanan kehamilan dan juga menggunakan
sistem SOAP pada asuhan kebidanan nifas, bayi baru lahir serta catatan persalinan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan studi kasus, Subyek penelitian adalah ibu hamil Ny. R berusia 33 tahun
dengan Riwayat tuberculosis paru. Data di abmbil dari bulan Agustus sampai September 2018. Data di
ambil dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil selama kehamilan subyek
sampai nifas, dan pada bayi baru lahir, tidak ada masalah apapun.
Saran : apabila ditemukan kasus yang sama perlu adanya kolaborasi dengan dokter spesialis
kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam selama kehamilan sampai nifas, selain itu perlu
melibatkan keluarga untuk memberi dukungan pada ibu.
Kata Kunci : tuberculosis paru, Hamil dengan Riwayat Tuberculosis Paru
Kasus: Seorang ibu hamil (Ny. R.) usia 33 tahun dengan umur kehamilan 40 minggu GIII PII A0
dengan riwayat Tuberculosis paru namun sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, pada saat
hamil, bersalin, sampai nifas 40 hari pasien tidak ada mengalami kambuh lagi.
I. PENDAHULUAN
Menurut Prawirohardjo, 2014
“Kematian ibu atau kematian maternal
adalah kematian seorang ibu sewaktu
hamil, melahirkan atau dalam waktu 42
hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak
bergantung pada tempat atau usia
kehamilan.[1]
Pada umumnya penyakit paru-paru
tidak mempengaruhi kehamilan
persalinan dan nifas, kecuali penyakitnya
tidak terkontrol, berat dan luas yang di
sertai sesak nafas dan hipoksia. Walaupun
kehamilan menyebabkan sedikit
perubahan pada system pernafasan,
karena uterus yang membesar dapat
mendorong diafragma dan paru-paru ke
atas serta sisa dalam udara kurang, namun
penyakit tersebut tidak selalu menjadi
lebih parah.[2]
Pengaruh Tuberkulosis Paru terhadap
Kehamilan, Dulu pernah dianggap bahwa
wanita dengan tuberkulosis paru aktif
mempunyai insidensi yang lebih tinggi
secara bermakna dibandingkan wanita
hamil tanpa infeksi tuberkulosis paru
dalam hal abortus spontan dan kesulitan
persalinan. Banyak sumber yang
mengatakan peranan tuberkulosis
terhadap kehamilan antara lain
meningkatnya abortus, pre-eklampsi, serta
sulitnya persalinan. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa hal tersebut
tergantung dari letak tuberkulosis apakah
paru atau nonparu serta apakah
tuberkulosis terdiagnosis semasa
kehamilan. Pada penelitian terhadap
wanita-wanita Indian yang mendapat
pengobatan selama 6-9 bulan semasa
kehamilan maka kematian janin 6 kali
lebih besar dan insidens dari prematuritas,
KMK ( kecil untuk masa kehamilan),
BBLR (berat badan lahir rendah)
(<2500g) adalah 2 kali lipat. Pengaruh
tidak langsung tuberkulosis terhadap
kehamilan ialah efek teratogenik terhadap
janin karena obat anti tuberkulosis yang
diberikan kepada sang ibu. Efek samping
pasien yang mendapat terapi anti
tuberkulosis yang adekuat adalah
gangguan pada traktus genitalis dimana
traktus genitalis terinfeksi dari fokus
primer TB paru.[3]
Prevalensi tuberculosis di Indonesia
semua bentuk sebesar 660 per 100.000
penduduk (SPTB 2016-2017) insiden
kasus tuberculosis sebanyak 403 per
100.000 penduduk. Sekitar 1.000.000
kasus tuberculosis baru pertahun.[4]
Berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal, Angka Kematian Ibu di
Kabupaten Tegal pada tahun 2011
mengalami perubahan yaitu 100,3 per
100.000 kelahiran hidup (27 kematian ibu
maternal dari 26.919 kelahiran hidup),
tahun 2015 mengalami penurunan yaitu
sebesar 120,8 per 100.000 kelahiran hidup
(33 kematian ibu maternal dari 26.919
kelahiran hidup), di tahun 2016 yang
mencapai 130,8 per 100.000 kelahiran
hidup (33 kematian ibu maternal dari
27.314 kelahiran hidup). Pada tahun 2017
lebih rendah dibandingkan angka
kematian ibu, Penyebab kematian ibu
terbanyak disebabkan oleh komplikasi
obstetrik yaitu perdarahan sebanyak 25%,
infeksi 7,5%, eklampsia 5%, abortus
5,5%, partus lama/macet 4%, emboli
obstetric 2,5%, komplikasi masa
purpereum 2% tuberculosis 0,5%,
hipertensi 0,5%. Angka kematian ibu
tersebut sudah memenuhi target Indikator
Indonesia Sehat 2010 sebesar 150 per
100.000 kelahiran hidup. Jika
dibandingkan dengan Resti (primigravida
kurang dari 20 tahun/lebih dari 35 tahun
21%, anak lebih dari 4 29%, jarak
persalinan terakhir dan kehamilan
sekarang kurang dari 2 tahun 9%, tinggi
badan kurang dari 145 cm 13%, berat
badan kurang dari 38 kg 8%, lingkar
lengan atas kurang dari 23,5 cm 8%,
riwayat hipertensi 8%). Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal 2016-2019, sedangkan
jumlah ibu hamil di Kabupaten Tegal ada
23.343 pada tahun 2017. Angka kematian
ibu sudah melampaui target yang
diharapkan yaitu 120.3 kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup pada tahun
2017.[5]
Menurut data yang di peroleh dari
Puskesmas Tarub pada tahun 2017 Angka
Kematian Ibu sebanyak 2 kasus yang
disebabkan oleh air ketuban dan penyakit
jantung, sedangkan Angka Kematian Bayi
sebanyak 7 kasus yang disebabkan oleh
BBLR dan Aspirasi ASI, BBLR dan
asfiksia, BBLR dan kelainan paru,
Hipotermi dan Asfiksia dan Angka
Kematian Bayi pada tahun 2018
meningkat menjadi 8 kasus yang
disebabkan oleh hipotermi, BBLR,
infeksi, prematur dan BBLR, penyakit
kongenital, asfiksia, dan aspirasi
pneumonia.[6]
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan studi kasus dengan subyek
penelitian pada studi kasus ini adalah ibu
hamil Ny. R umur 33 tahun G3 P2 A0
dengan riwayat Tuberculosis paru.
Pengambilan data dilakukan sejak
tanggal 21 Agustus sampai 14 September.
Tempat pengambilan studi kasus ini di
Puskesmas Tarub Kabupaten Tegal.
Tujuan dilakukannya studi kasus ini
yaitu bahwa diharapkan penulis mampu
mengkaji dan memberikan asuhan
kebidanan pada Ny. R dengan Riwayat
Tuberculosis paru secara komprehensif
dengan menerapkan managemen asuhan
kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.
Pengumpulan data dilakukan mulai
dari wawancara (anamnesa), observasi
perilaku klien selama kehamilan sampai
dengan nifas, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang, studi
dokumentasi, dan studi pustaka.
Data yang telah didapatkan
kemudian didokumentasikan dengan
menggunakan managemen asuhan
kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.
III. STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN
a. Kehamilan
Penelitian studi kasus ini
dilakukan untuk mengkaji kasus
kebidaanan patologis dengan tujuan
yaitu untuk memberikan asuhan
kebidanan secara komprehensif
sehingga dapat menurunkan angka
kematian ibu dan angka kematian bayi
dengan cara melakukan pendekatan
dengan klien sedini mungkin sejak
kehamilan untuk membuat skrining
awal sehingga jika terjadi komplikasi
langsung ditangani sesuai dengan
kebutuhan klien.[7]
Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan bahwa ibu mengalami
penyakit keturunan yaitu penyakit
tuberculosis paru dengan ciri-ciri batuk
lebih dari 3 minggu, batuk bercampur
darah, berkeringat pada malam hari
meski tidak melakukan aktivitas.
Apabila klien pernah menderita
penyakit keturunan, maka ada
kemungkinan janin yang ada dalam
kandungannya tersebut berisiko
menderita penyakit yang sama.
Berdasarkan penelitian didapatkan
hasil pada kehamilan dilakukan
kunjungan 2 kali pada kunjungan
pertama terdapat masalah mual dan
muntah kemudian di tes urine pasien
positif hamil dengan umur kehamilan 9
minggu,tekanan darah 100/60, berat
badan 60 kg, LILA 28,5 cm, tinggi
badan 149 cm, HPHT 16-11-2017, HTP
23-8-2018, kemudian pasien di cek
laboratorium dengan hasil pp test +, HB
(-), Hbsag (-), HIV (-), sipilys (-), bidan
memberikan metodopamine 3x1, fe 1x1,
dan bidan memberikan nasihat makan
sedikit tapi sering dan perbanyak minum
air putih. Dan pada kujungan 2 dan 3
tidak ada masalah.
Dalam kasus Ny. R didapatkan
hasil pemeriksaan yaitu berat badan 67
kg dan penambahan berat badan selama
hamil yaitu 7 kg, Sehingga dalam kasus
ini ada kesenjangan antara teori dan
kasus, kemungkinan resiko yang terjadi
yaitu suplai ASI yang kurang saat
menyusui, resiko anemia dan BBLR.[8]
b. Bersalin
Pada tanggal 25 Agustus 2018 ibu
datang ke Puskesmas ingin melahirkan
dengan keluhan kenceng_ kenceng
semakin sering sejak jam 23.00 WIB
(24/08/2018), kemudian bidan
melakukan pemeriksaan dengan hasil
kesadaran composmetis, TD 110/70
mmhg, nadi 80 x/menit, pernafasan
20x/menit, suhu 36,5oc, TB 151 cm, BB
67 kg, LILA 27 cm, pemeriksaan dari
ujung rambut sampai ujung kaki tidak
ada masalah, pemeriksaan palpasi
Leopold 1 TFU 3 jari di bawah px,
teraba bokong, Leopold II bagian kanan
ibu teraba punggung janin, bagian kiri
perut ibu teraba ekstremitas, Leopold III
teraba kepala, Leopold IV sudah masuk
panggul divergen 3/5 bagian, TFU 33
cm, TBBJ 3.410 gram, HPL 23 Agustus
2018, umur kehamilan 39 minggu + 6
hari, DJJ 136 x/menit, kontraksi 2 kali
dalam 10 menit lamanya 25 detik,
pengeluaran pervagina lendir bercampur
darah.
Dilakukan pemeriksaan dalam atas
indikasi adanya kontraksi Rahim dengan
tujuan untuk menilai apakah ibu sudah
dalam proses persalinan, Hasil
pemeriksaan kondisi vagina normal,
tidak ada benjolan, keadaan portio tebal,
effacement 20-30%, pembukaan 2 cm,
selaput ketuban utuh, titik tunjuk UUK,
presentasi kepala, penurunan kepala
hodge II, dan tidak ada bagian yang
terkemuka, pemeriksaan penunjang
seperti pemeriksaan HB, protein urine
dan pemeriksaann USG tidak di
lakukan. Diagnosa potensial tidak ada,
Antisipasi penanganan segera konsultasi
dengan dokter jaga.
Implementasi bidan memberitahu
ibu hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan, ibu sudah dalam proses
persalinan evaluasi ibu sudah mengerti
hasil pemeriksaan yang telah di lakukan.
Bidan memberikan asuhan sayang ibu.
Menganjurkan ibu agar tetap tenang
karena rasa sakit saat proses persalinan
itu hal yang normal, evaluasi ibu
mengerti apa yang disarankan bidan.
Memberitahu keluarga untuk
menyiapkan kebutuhan bersalin bagi ibu
pakaian ganti, kain kering dan bersih
sebanyak 4 lembar, pembalut, dan untuk
pakaian bayi, popok, kain bayi, topi,
selimut, kain dan bedong, evaluasi
perlengkapan persalinan sudah
disiapkan. Bidan melakukan
pemantauan kemajuan persalinan kala 1
dengan pengawasan 10, evaluasi
pemantauan sudah terlampir. Pada jam
17.00 WIB pembukaan lengkap
dilakukan pertolongan persalinan bayi
lahir secara spontan jenis kelamin
perempuan, gerakan aktif, menangis
kuat, warna kulit kemerahan, lakukan
pemotongan tali pusat, berat badan 3700
gram, panjang badan 49 cm, lingkar
kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm,
penilaian bayi baru lahir dilakukan
dengan apgar score dengan hasil
10/10/10.
c. Nifas
Pada kasus Ny. R KN 1 4 jam post
partum di dapatkan data subyektif ibu
mengeluh perutnya masih mulas, hal ini
menunjukan tidak ada kesenjangan
antara teori dan kasus. pada pola nutrisi
ibu terakhir makan jam 19.00 WIB
porsi makan sedang, jenisnya nasi,
ayam, sayur, sop, tahu, minum 2 gelas
air putih & 1 gelas air teh, pada pola
eli,inasi ibu sudah BAK 2 kali terakhir
jam 20.30 WIB, ibu mengatakan belum
istrahat dari setelah bersalin, AKtivitas
ibu sekarang mobilisasi miring kanan
dan kiri, duduk, turun dari tempat tidur,
jalan-jalan di sekeliling tempat tidur dan
kamar mandi tanpa bantuan orang lain,
ibu mengatakan tidak mempercayai adat
istiadat setempat sepeti dalam masa
nifas 40 hari tidak boleh keluar rumah.
Dari hasil pemeriksaan fisik yang
telah dilakukan terdapat keadaan umum
baik, kesadaran composmentis TD
110/80 mmhg, suhu 36oc, nadi 78
x/menit, Pernafasan 20 x/ menit, tinggi
fundus uterus 3 jari di bawah pusat,
Kandung kemih kosong, Kontraksi
keras, perdarahan 30 cc lochea rubra
dan luka bekas jahitan baik.[9]
Data obyektif yang di dapatkan
antara lain Ny. R umur 33 tahun P3 A0
4 jam post partum dengan nifas normal,
sehingga tidak ada kesenjangan antara
teori dan kasus.
Pada KN ke 2 (6 hari post partum)
ibu mengatakan sudah bisa mengurus
bayinya, ASInya sudah keluar lancar
dan tidak ada keluhan.
Pola Nutrisi Ibu mengatatakan
makan sehari 3x porsi 1 piring sedang,
menu aneka ragam dan bermacam-
macam, tidak ada makanan yang di
pantang, sedangkan frekuensi minum 8-
10 gelas/hari, macam air putih. Pola
Eliminasi ibu mengatakan frekuensi
BAB 1-2 x/hari, konsistensi lembek,
warna kuning kecoklatan, tidak ada
gangguan, BAK frekuensi 7-8 x/hari,
bau khas, warna kuning jernih, tidak ada
gangguan. Pola istirahat ibu mengatakan
istirahatnya siang 1-2 jam malam 6–7
jam. Pola Aktivitas ibu mengatakan
sebagai ibu rumah tangga, biasa
mengerjakan pekerjaan rumah seperti
menyapu, memasak, mencuci. Pola
Personal Hygiene pola mandi 2x sehari,
keramas 2 hari sekali, gosok gigi 2x,
ganti baju 2x sehari. Pola Seksual ibu
mengatakan sampai saat ini belum
melakukan hubungan.[10]
Pemeriksaan Obyektif keadaan ibu
baik, kesadaran composmentis. Tanda-
tanda vital tekanan darah 110/70
mmHg, Suhu 36ᵒC, Nadi 80 x/menit,
Pernafasan 20x /menit, muka tidak
pucat dan oedem, konjungtiva merah
muda, sclera putih, bentuk payudara
simetris, puting susu menonjol, ASI
sudah keluar banyak. Pada pemeriksaan
palpasi tinggi fundus uteri sudah tidak
teraba kontraksi keras, pengeluaran
pervaginam lochea serosa, warna
kecoklatan, luka jahitan kering, tidak
ada tanda-tanda homan.
Intervensi memberitahu ibu hasil
pemerikasaan yang telah dilakukan
yaitu keadaan ibu saat ini baik-baik saja
TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36,0
c, R 20 x/menit, Luka jahitan sudah
kering dan baik, evaluasi ibu sudah
mengerti hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan. Memberitahu ibu untuk
mengkonsumsi makanan yang bergizi
tinggi kalori tinggi protein seperti yang
mengandung karbohidrat (padi,
singkong, gandum, dan lain-lain),
protein nabati (tahu, tempe, kacang-
kacangan dan lain-lain), protein hewani
(susu, telor, ikan, daging ayam, daging
sapi dan lain-lain), mineral dan vitamin
(sayur dan buah-buahan), lemak nabati
(lemak jagung dan lain-lain), lemak
hewani (lemak ikan dan lain-lain).
evaluasi ibu bersedia untuk
mengonsumsi makanan yang bergizi.
Memberitahu ibu kebutuhan air minum
pada ibu menyusui pada 6 bulan
pertama yaitu 14 gelas sehari, evaluasi
ibu dalam sehari mengkonsumsi air
minum sebanyak 15 gelas .Memberitahu
ibu untuk menjaga kebersihan diri,
termasuk daerah kemaluan dengan cara
cebok yang benar yaitu di bersihkan
mulai dari depan ke belakang
menggunakan sabun dan air, ganti
pembalut sesering mungkin. evaluasi
ibu sehari mandi 2x, gosok gigi 2x,
ganti baju 2x, ibu sudah mengerti cara
cebok yang benar, dan ibu sehari ganti
pembalut sesering mungkin.
Memberitahu ibu istirahat cukup siang
1-2 jam maam 6-8 jam atau saat bayi
istirahat ibu juga istirahat.evaluasi
istirahat siang ibu kurang lebih 1 jam,
malam 6-8 jam saat ibu istirahat bayi di
gendong suami/ ibu. Memberitahu ibu
perawatan bayi yang benar yaitu
memandikan bayi 2x sehari, menjaga
kehangatan bayi dengan cara di bedong
dan menyelimuti bayi, mengganti popok
bayi jika bayi BAK/BAB. evaluasi bayi
mandi sehari 2x, bayi selalu di bedong
dan di selimuti, jika bayi bak/bab ibu
segera mengganti popok bayi dan
membersihkannya. Memberitahu ibu
jangan membiarkan bayi menangis
terlalu lama karena akan membuat bayi
stress. evaluasi bayi tidak pernah
menangis terlalu lama. Memberitahu
untuk memberikan ASI esklusif yaitu
bayi hanya diberikan asi saja dari umur
0-6 bulan tanpa tambahan minuman atau
makanan apapun kecuali obat dan
vitamin. evaluasi ibu sudah mengerti
penjelasan bidan dan ibu bersedia
menyusui bayinya dengan asi esklusif.
Menganjurkan ibu untuk melakukan
kunjungan ulang 2 minggu lagi atau jika
ada keluhan segera datang ke tenaga
kesehatan. evaluasi ibu bersedia untuk
melakukan kunjungan ulang.
Kunjungan ke 2 (14 hari post
partum) jam 14.00 WIB di rumah Ny.
R, ibu mengatakan tidak ada keluhan
ASInya lancar. Dilakukan pemeriksaan
dengan hasil keadaan ibu baik,
kesadaran composmetis. Tanda-tanda
vital tekanan darah 120/70 mmHg, suhu
36,7oC, nadi 82 x/menit, pernafasan 20
x/menit, muka tidak oedem, konjungtiva
merah muda, sclera putih, bentuk
payudara simetris, putting susu
menonjol, ASI keluar lancer, pada
pemeriksaan palpasi tinggi fundus uteri
sudah tidak teraba, kontraksi keras,
pengeluaran pervagina lochea Alba,
warna putih cair, luka jahitan sudah
kering dan baik, tidak ada tanda-tanda
human. Dan ibu dalam keadaan baik.
d. Bayi baru lahir
Kunjungan ke 1 Persalinan
tanggal 25 agustus 2018 jam 17. 15
wib jenis persalinan spontan,
penolong persalinan bidan, selama
proses persalinan hanya di berikan
oxytocin 10 ui pada kala III, selama
persalinan kala I 16 jam, kala II 15
menit, ketuban pecah jam 17.10 WIB
warna jernih bau kas.
Segera setelah lahir dilakukan
pernilaian segera setelah lahir
tangisan kuat, kulit kemerahan,
gerakan aktif, mengeringkan bayi,
perawatan tali pusat dan IMD.
Pemeriksaan fisik keadaan umum
baik, suhu tubuh 36,5oC, denyut
jantung 124 x/menit, respirasi 44 kali
permenit, panjang badan 49 cm, berat
badan 3700 gram, LIKA 34 cm,
LIDA 33 cm, LILA 11,5 cm,
pemeriksaan dari ujung kepala sampai
ujung kaki normal.tidak ada masalah,
diagnosa potensial tidak ada,
antisipasi penanganan segera tidak
ada.
Intervensi lakukan pemeriksaan
antropometri, evaluasi sudah di
lakukan pemeriksaan. Beritahu ibu
hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan, evaluasi ibu sudah
mengetahui hasil pemeriksaan.
Berikan vitamin k pada salep mata,
evaluasi ibu sudah mengetahui
bayinya sudah di berikan salep mata.
Lakukan perawatan tali pusat,
evaluasi ibu sudah mengerti cara
perawatan tai pusat. Pastikan bayi
mendapatkan ASI, evaluasi ibu sudah
memberikan bayinya ASI. Beritahu
ibu tanda bahaya bayi baru lahir,
evaluasi ibu sudah mengerti tanda
bahaya bayi baru lahir, berikan
imunisasi HB. 0, evaluasi bayi sudah
di berikan imunisasi HB.0.
Kunjungan neonates ke 2 (6 hari )
tanggal 31 agustus jam 19.00 di
rumah Ny. R ibu mengatakan bayinya
tidak ada keluhan, menyusu kuat,
BAK lebih dari 6 kali,BAB setiap
hari 1-2 kali konsistensi lembek.
Data Obyektif keadaan baik, BB
3900 gram, PB 52 cm, suhu tubuh
37oC, denyut jantung 120x/menit,
pernapasan 40 x/menit, tali pusat
sudah lepas pemeriksaan ujung
rambut sampai kaki normal.[11]
Penatalaksanaan Memberikan
kapada ibu hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan yaitu keadaan bayi
saat ini baik-baik saja Suhu 36,7oC
pernafasan 40 x/menit Detak jantung
120 x/menit evaluasi ibu sudah
mengetahui hasil pemeriksaan
bayinya. Mengingatkan kembali tanda
bahaya bayi baru lahir yaitu tidak
mau menyusu, suhu tubuh naik, bayi
rewel. evaluasi ibu sudah mengerti
tanda bahaya bayi lahir. Memberitahu
ibu untuk menjaga kebersihan diri
bayi dengan cara memandikan bayi 2
x sehari, ganti baju 2x sehari,
mengganti popok setelah bayi buang
air kecil dan besar. Evaluasi ibu
selalu menjaga kebersihan bayinya.
Mengingatkan kembali ibu untuk
selalu memberikan asi esklusif tanpa
tambahan makanan apapun kecuali
obat dan vitamin. Evaluasi ibu selalu
memberikan asi dan tidak
memberikan makanan tambahan
apapun.
Kunjungan neonatus 3 (14 hari)
tanggal 8 september 2018, jam 14.00
WIB rumah Ny. R, ibu mengatakan
bayinya tidak ada keluhan, menyusu
kuat.
Data Obyektif keadaan baik, BB
3900 gram, PB 52 cm, suhu tubuh
36,5oC, denyut jantung 120x/menit,
pernapasan 42 x/menit, pemeriksaan
ujung rambut sampai kaki normal.
Penatalaksanaan memberitahu
kapada ibu hasil pemeriksaan yang
telah dilakukan yaitu keadaan bayi
saat ini baik-baik saja Suhu 36,5oC
pernafasan 42 x/menit Detak jantung
120 x/menit.
Mengingatkan kembali ibu untuk
menjaga kebersihan diri bayi dengan
cara memandikan bayi 2 x sehari,
ganti baju 2x sehari, mengganti popok
setelah bayi buang air kecil dan besar
gunanya untuk mencegah terjadinya
iritasi. evaluasi ibu selalu menjaga
kebersihan bayinya.
Mengingatkan ibu untuk rutin ke
posyandu untuk imunisasi bayi &
melakukan tumbuh kembang bayinya.
evaluasi ibu bersedia membawa
bayinya ke posyandu.
Memberitahu ibu jika terjadi
sesuatu pada bayi seperti suhu badan
naik/ panas, diare, menangis terus
menerus .untuk segera di bawa ke
tenaga kesehatan / puskesmas
terdekat untuk di berikan penanganan
yang tepat. evaluasi ibu mengerti
penjelasan bidan.
Pada penelitian kasus Ny. R
dengan faktor risiko dengan riwayat
tuberculosis paru tidak ditemukan
adanya kesenjangan antara teori dan
kasus karena penyakit yang di derita
ibu tidak mengalami kekambuahan
pada saat hamil, bersalin dan nifas,
serta pada bayi lahir dalam keadaan
sehat.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah
didapatkan oleh penulis pada saat
melakukan asuhan kebidanan secara
komprehensif, penulis mendapatkan
gambaran serta pengalaman secara nyata
tentang asuhan kebidanan yang meliputi
asuhan kebidanan pada ibu hamil,
bersalin, nifas dan bayi baru lahir normal
pada kasus Ny. R dan Bayi An. R yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus –
14 September 2018.
Penulis mampu memberikan
asuhan kebidanan pada Ny. R dengan
faktor risiko dengan riwayat tuberculosis
paru secara komprehensif di Wilayah
Puskesmas Tarub, Kabupaten Tegal
dengan menerapkan managemen asuhan
kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.
V. DAFTAR PUSTAKA
[1].Prawirohardjo, Sarwono. 2014. Ilmu
kebidanan. Jakarta : PT Bina Pustaka
Sarwono Prawirohardjo.
[2].Sofian, 2017. Penyakit Tuberculosis
paru, kebidanan.
[3].Najoan Nan Warouw, 2011. Pengaruh
Tuberculosis paru pada kehamilan.
[4].Depkes, 2016-2017. Prevalensi
tuberculosis di Indonesia.
[5].Dinas kesehatan Kabupaten Tegal,
2011. Angka Kematian Ibu.
[6].Puskesmas Tarub, 2017-2018. Profil
kesehatan Puskesmas Tarub 2017-
2018.Tarub.
[7].Maryunani, A & Retno Murti
Suryatiningsih & Ery Fatmawati. 2011.
Asuhan kebidanan patologi.
Yogyakarta : pustaka pelajar.
[8].Pantikawati, 2010. Asuhan Kebidanan
1 (kehamilan).
[9]..Saleha, Siti. 2009. Asuhan Kebidanan
pada Masa Nifas. Jakarta : Salemba
Medika.
[10].Sulistyawati, 2013. Kebutuhan Nifas.
[11].Lia, D & Retno Murti Suryaningsih&
Ery Fatmawati. 2011. Kriteria bayi baru
lahir normal