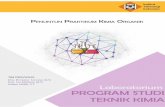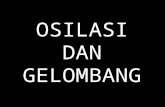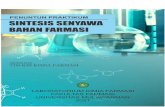PENUNTUN EKSPERIMEN FISIKA II - Jurusan Fisika – FMIPA UHO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of PENUNTUN EKSPERIMEN FISIKA II - Jurusan Fisika – FMIPA UHO
PENUNTUN
EKSPERIMEN FISIKA II
Dosen pengampu
Viska Indah Variani, S.Si., M.Si
Muhammad Harun Al Rasyid, S.Si., M.Si
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2020
JUDUL DAN ASISTEN PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA 2
No KODE TOPIK JUDUL PRAKTIKUM ASISTEN KOORD. ASISTEN
1 I Cincin Terbang Mirad
Muh. Asharudin
2 II Koil Tesla
Nur Mildatin
Nisa
3 III Pengolahan data XRF Kharisma
4 IV Serapan Sinar Radioaktif
Nova Elisa
Putri
5 V Konversi Energi II
Andri
Gunawan
JADWAL EKSPERIMEN FISIKA 2
Minggu
ke
TOPIK PRAKTIKUM
I II III IV V
0 KONTRAK KULIAH DAN DEMO ALAT
1 A11;B11 A21;B21 A31;B31 A41;B41 A51;B51
2 A21;B21 A31;B31 A41;B41 A51, A52 A11;B11
3 A31;B31 A41;B41 A51, A52 A11;B11 A21;B21
4 A41;B41 A51, A52 A11;B11 A21;B21 A31;B31
5 A51;B51 A11;B11 A21;B21 A31;B31 A41;B41
6 INHALL (MAKSIMAL 1 TOPIK & JIKA DINYATAKAN LAYAK INHALL)
7 UJIAN AKHIR
A = shift 1
B = shift 2
TATA TERTIB
1. Praktikan wajib hadir tepat waktu, membawa penuntun eksperimen, memakai jas
laboratorium&sandal jepit karet bersih
2. Sebelum menjalani responsi, praktikan harus dapat menunjukkan hasil pengerjaan tugas yang
telah diberikan asisten (sesuai dengan judul eksperimennya) 1 minggu sebelumnya
3. Praktikum diawali dengan responsi. Praktikan berkesempatan belajar ulang jika dinilai benar-
benar tidak dapat menjawab dan mengulang responsinya namun hal itu akan mengurangi nilai
praktikum kelompoknya.
4. Data hasil eksperimen langsung ditulis pada Lembar Data dan seusai eksperimen wajib minta
disahkan dengan Acc asisten. Lembar data tsb nanti disatukan bersama Laporan Praktikum.
5. Penyusunan Laporan Praktikum dikerjakan oleh kelompok. Laporan ditulis tangan rapi dan grafik
diolah menggunakan Excel. Pembahasan harus ilmiah dan secara fisika.
6. Format Laporan Praktikum : Judul, Dasar Teori (minimal 3 literatur), Lembar Data, Pengolahan
Data, Pembahasan, Kesimpulan, Tugas, Daftar Pustaka. Sampul Laporan disertakan kode
kelompok, semua nama dan stambuk hanya praktikan yang turut mengambil data dan
mengerjakan pembuatan Laporan Praktikum.
7. Laporan Praktikum dan Revisi Laporan Praktikum dikumpulkan dan diambil pada dosen
pengampu atau coordinator praktikum setiap kali praktikum sebelum jam eksperimen dimulai.
8. Seluruh Laporan Praktikum yang telah mendapatkan Acc dari dosen pengampu harus dijilid rapi
dengan cover diberi keterangan kode kelompok, nama&stambuk seluruh anggota kelompok.
Hasil jilid dikumpulkan kembali sebagai prasyarat mengikuti ujian Eksperimen Fisika 2.
9. Seorang praktikan dinyatakan layak inhall jika telah menyerahkan surat dokter atau surat ijin dari
orang tua selambatnya 1 minggu setelah ketidakhadirannya kepada dosen pengampu atau
koordinator asisten
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Eksperimen 1 CINCIN TERBANG
A. TUJUAN 1. Praktikan dapan menjelaskan fenomena cincin terbang. 2. Praktikan dapat menentukan rapat konduktivitas bahan cincin.
3. Praktikan dapat menentukan permeabilitas medium. B. DASAR TEORI
Suatu loop konduktor yang mengalami perubahan fluks magnetik akan timbul gaya gerak listrik (ggl imbas Faraday) sebesar :
� = − ���� (1.1)
tanda minus menyatakan bahwa, polaritas ggl induksi sedemikian rupa hingga menimbulkan fluks magnet yang melawan perubahan fluks magnet eksternal yang menembus loop (hukum Lentz. 1835). Hukum imbas Faraday mendasari kerja tranformator. Pada transformator ideal berlaku :
���
= �
�� ���
= �
(1.2)
V : tegangan primer, N : jumlah lilitan, I : arus, indeks p : primer dan indek s : sekunder.
Setiap muatan yang bergerak menimbulkan medan magnet disekelilingnya. Peristiwa ini pertama kali diamati oleh Oersted dalampenelitiannya tahun 1820. Biot-Savart melanjutkan penelitian Oersted, ia menemukan bahwa konduktor yang mengalirkan arus mantap menghasilkan medan magnet. Medan magnet dB pada suatu titik yang disebabkan oleh elemen arus mantap dengan panjang ds adalah :
�� = ��� �� × �̂
�� (1.3)
ds = elemen, dengan arah = arah arus
r)
= vektor satuan dengan arah elemen ke titik pengamatan P.
km = konstanta = 7010
4
Wb/A.m
Medan magnet total B pada suatu titik karena arus konduktor dengan ukuran tertentu :
� = ���4� � �� × �̂
�� (1.4)
Berdasarkan hukum Lorentz, muatan listrik yang bergerak dalam medan medan magnet
mengalami gaya magnet :
� = �� × � (1.5) Arus listrik, I :
� = ��� �� = �/ � = (�"#$%& × �)/� = � # (1.6)
Jadi (1.5) menjadi :
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
� = � # × � (1.7)
Berdasarkan (1.4) dan (1.5), pada kawat sejajar berarus menghasilkan gaya magnet :
� = ��(��)2�ℎ (1.8)
L merupakan panjang kawat (salah satu), h jarak antara dua kawat, F adalah gaya tarik jika arus searah, dan merupakan gaya tolak jika arah arus berlawanan. C. ALAT DAN BAHAN
1. Unit eksperimen cincin terbang. 2. Transformator variabel. 3. Amperemeter Clamp. 4. Penggaris/meteran.
D. PROSEDUR EKSPERIMEN
1. Sambung stiker unit cincin terbang pada transformator variabel. 2. Atur tegangan nol pada transformator variabel dan sambung ke stopkontak. 3. Masukkan cincin Al pada unit cincin terbang. 4. Putar pengatur tegangan transformator variabel hingga cincin tepat mulai terangkat. 5. Catat arus kumparan dan arus cincin. 6. Perbesar lagi tegangan transformator menjadi 125 V. 7. Catat arus kumparan, arus cincin dan ketinggian cincin terangkat. 8. Ulangi terus langkah 6 dan 7 dengan menaikkan tegangan transformator (setiap
kenaikan tegangan sebesar 10 V) hingga mencapai 195 V. 9. Ganti cincin dengan bahan lain, dan lakukan hal yang sama di atas.
Catatan: jumlah kumparan primer 1000 lilitan.
Gambar 1.1 Unit eksperimen cincin terbang
E. TUGAS 1. Jelaskan tentang kaitan antara nilai permeabilitas bahan dan rapat konduktivitas
suatu medium dengan kemampuan terbang sebuah bahan cincin 2. Mengapa cincin saat terbang terasa panas ketika dipegang? 3. Mengapa bahan cincin harus dibuat dari bahan konduktor dan bilamana cincin dapat
terbang keluar dari batang inti (jika arus listrik mantap)?
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Eksperimen 2 KOIL TESLA
A. TUJUAN 1. Praktikan dapat menjelaskan peristiwa resonansi rangkaian koil Tesla. 2. Praktikan dapat menjelaskan prinsip pancaran gelombang elektromagnetik. 3. Praktikan dapat menjelaskan prinsip pesawat penerima gelombang elektromagnetik.
B. DASAR TEORI Koil Tesla merupakan tranformator resonan yang berinti udara. Tranformator ini
bekerja pada frekuensi tinggi dan dapat menghasilkan tegangan sangat tinggi dengan menimbulkan cahaya spektakuler. Bagaimana koil Tesla dapat menghasilkan tegangan ekstra tinggi? Koil Tesla merupakan tranformator resonan, ini berarti koil Tesla memiliki frekuensi khusus dalam kerjanya, yaitu frekuensi resonan. Frekunsi resonan tersebut unik untuk setiap desain, jadi tidak ada frekuensi resonan yang bersifat umum.
Apakah yang menentukan frekuensi resonan? Koil Tesla bekerja berdasarkan rangkaian RLC yang kompleks. Komponen induktif (L) adalah koil itu sendiri, yang terdiri atas sejumlah gulungan. Komponen kapasitif (C) terdiri atas kapasitor, permukaan antar kawat sekunder, dan dan terminal elektroda. Komponen hambatan (R) merupakan sifat resistif pada gulungan sekunder (pada frekuensi resonansi).
Untuk menghasilkan frekuensi resonan, pulsa energi harus diumpankan pada laju dan frekuensi yang tepat. Analogi hal ini adalah seperti bel. Agar bel berdengung mesti dipukul. Jika dipukul terlalu keras, akan merusak bel. Jika pukulan perulang tidak tepat menyebabkan nada bel tidak jernih.
Gambar 2.1 Sifat kapasitif induktor (kiri), rangkaian koil Tesla (kanan)
Pulsa energi datang dari rangkaian primer. Rangkain ini terdiri atas (1) tranformator tegangan tinggi, (2) kapasitor primer (yang berupa plat Al-kaca), (3) celah bunga api, dan (4) koil primer (yang berukuran diameter besar). Rangkaian ini membangkitkan osilator tipe kasar. Apa yang terjadi dengannya? Transformator memuati kapasitor hingga tegangan tinggi dan bunga api melompat pada celah. Ketika bunga api muncul, energi pada kapasitor ditumpahkan pada koil primer. Koil primer ini menghasilkan medan magnet setelah arus listrik dari kapasitor mengalir melewatinya. Medan magnet menimbulkan induksi diri dan arus kembali memuati kapasitor. Medan magnet yang menimbulkan ggl imbas pada koil sekunder. Proses pengisian-pengosongan C–L ini berlangsung terus. Frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai kapasitansi kapasitor primer dan koil primer. Kedua komponen tersebut bersama-sama menghasilkan apa yang disebut rangkaian resonan paralel. Desain koil Tesla tertentu, frekuensi diatur dengan mengubah induktansi koil primer, yaitu mengubah jumlah gulungan yang difungsikan.
Jika frekuensi osilasi primer sama dengan frekuensi sekunder (sekunder yang secara fisis hanya berupa koil tetapi sesungguhnya merupakan rangkaian RLC, lihat gambar kiri), maka terjadi transfer energi yang sangat besar. Mengingat perbandingan jumlah lilitan koil Ns/Np
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
besar, tegangan primer tinggi, maka tegangan sekunder menjadi sangat tinggi, dan sanggup mengionisasi udara, maka timbullah cahaya.
C. ALAT DAN BAHAN 1. Unit koil Tesla. 2. Lampu TL. 3. Kabel penghubung. 4. Power Supply
Gambar 2.2 Unit eksperimen koil Tesla
D. PROSEDUR EKSPERIMEN 1. Susun plat Al dan kaca silih berganti sebanyak 12 tingkat membentuk 6 kapasitor yang
tersambung paralel. 2. Rangkai power supply High Voltage, kapasitor, koil Tesla, membentuk unit
eksperimen koil Tesla, sesuai gambar di atas. 3. Letakkan lampu TL di sekitar koil sekunder. 4. On kan power supply, dan amati nyala lampu TL, nyatakan mati, redup, atau terang. 5. Ukur intensitas gelombang elektromagnetik pada jarak 1m dari koil sekunder. 6. Kurangi jumlah kapasitor yang disambung (menjadi 5), rangkai kembali. 7. Ulangi langkah 4 dan 5. 8. Kurangi jumlah kapasitor yang disambung (menjadi 4), rangkai kembali. 9. Ulangi langkah 4 dan 5. 10. Kurangi jumlah kapasitor yang disambung (menjadi 3), rangkai kembali. 11. Ulangi langkah 4 dan 5. 12. Kurangi jumlah kapasitor yang disambung (menjadi 2), rangkai kembali. 13. Ulangi langkah 4 dan 5. 14. Kurangi jumlah kapasitor yang disambung (menjadi 1), rangkai kembali. 15. Ulangi langkah 4 dan 5. 16. Kurangi tap (penyambungan) jumlah lilitan koil. 17. Ulangi langkah 4 dan 5. 18. Lakukan terus untuk mendapatkan intensitas gelombang elektromagnetik terbesar. 19. Amati pancaran bunga api pada ujung koil sekunder.
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Catatan : Hati-hati, Anda bekerja dengan rangkaian listrik tegangan ekstra tinggi!!! Agar pengamatan nyala lampu jelas, lakukan pengamatan pada ruangan dengan intensitas cahaya kurang.
No. Jumlah kapasitor Jumlah lilitan Lampu TL
20. Susun Unit koil Tesla yang lain tanpa power supply yang berfungsi sebagai pesawat penerima.
21. Letakkan unit penerima tersebut pada jarak 1m, dan letakkan lampu TL. 22. On kan koil Tesla (pemancar), dan amati nyala lampu TL. 23. Variasikan jumlah kapasitor dan lilitan primer (koil primer), hingga diperoleh
penerimaan gelombang elektromagnetik yang maksimal.
E. TUGAS 1. Jelaskan prinsip kerja sebuah kapasitor dan apa arti nilai kapasitansi pada sebuah
kapasitor ? 2. Jelaskan tentang kaitan antara proses induksi diri dan ggl imbas 3. Jelaskan garis besar proses fisika yang menyebabkan lampu TL bisa menyala walaupun
tidak terhubung langsung dengan sumber arus ?
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
EKSPERIMEN 3
PENGOLAHAN DATA XRF (X-Ray Fluorescence)
A. Tujuan
1. Praktikan memahami prinsip kerja alat XRF. 2. Praktikan memahami cara pengolahan data XRF. 3. Praktikan dapat menentukan jenis unsur penyusun bahan/sampel yang diuji
menggunakan program penganalisa grafik XRF.
B. Landasan Teori
Wilhelm Conrad Rontgen seorang fisikawan Jerman menerima penghargaan nobel dalam fisika pada tahun 1901 karena menemukan sinar-X. Sinar-X termasuk gelombang elektromagnetik berenergi 200 eV sampai 1 MeV dengan panjang gelombangnya terbentang sekitar 0,1 Ǻ hingga 1 Ǻ. Panjang gelombang yang sangat kecil menyebabkan sinar-X mempunyai daya tembus tinggi.
Gambar 3.1. Spektrum panjang gelombang elektromagnetik
Sinar-X berdasarkan cara pembentukannya terbagi atas 2 macam, yaitu sinar-X karakteristik dan sinar-X bremsstrahlung. Sinar-X karakteristik memiliki spektrum diskrit sedangkan sinar-X bremstrahlung memiliki spektrum kontinu seperti diperlihatkan pada gambar 3.2.
Gambar 3.2. Spektrum Sinar-X keluaran tabung sinar-X dengan energi maksimum 150 KeV
a. Sinar-X Karakteristik
Sinar-X karakteristik merupakan energi yang dilepaskan oleh elektron atom tereksitasi dalam rangka mencapai kondisi stabilnya. Elektron tersebut berpindah dari tingkat energi tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah untuk mengisi hole. Energi yang dilepaskan sebesar selisih energi antara kedua tingkat energi elektron pada atom tersebut. Oleh karena
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
setiap jenis atom memiliki besar tingkat-tingkat energi yang khas maka energi sinar-X yang dihasilkan untuk setiap atom bernilai khas pula sehingga disebut sinar-X karakteristik. Proses terjadinya sinar-X karakteristik digambarkan pada gambar 3.3
Gambar 3.3 Arah eksitasi elektron.
Sinar-X karakteristik terjadi karena elektron atom yang berada pada kulit K terionisasi
sehingga terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar-X karakteristik Kα. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar-X karakteristik Kβ. Jika elektron pada kulit L (n=2) yang terpental, maka garis-garis spektrum lainnya yang disebut deret L (Lα,Lβ,Lγ) akan terpancar. Demikian pula jika yang terpental adalah elektron pada kulit M (n=3), akan disertai dengan pemancaran yang disebut deret M dan seterusnya. Transisi Kα berprobabilitas paling besar untuk terjadi karena jarak kulit K dan L lebih dekat dibandingkan transisi Kβ sehingga muncul lebih banyak intensitas garis Kα pada spektrum karakteristik sebuah unsur.
b. Sinar-X Bremsstrahlung
Sinar-X Bremsstrahlung adalah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman (Dradjat, 2013). Proses terjadinya sinar-X jenis ini jika elektron bergerak dengan kecepatan tinggi melintas dekat inti suatu atom menyebabkan elektron membelok dengan tajam karena gaya tarik elektrostatik inti atom yang kuat. Untuk dapat membelok maka elektron harus melakukan pengereman dengan cara melepaskan sebagian energinya. Energi yang dilepaskan berupa sinar-X bremsstrahlung. Sinar-X bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar.
Gambar 3.4. Proses terjadinya Sinar-X bremsstrahlung.
Oleh sebab itu pada spektrum energi sinar-X dari suatu atom berelektron banyak akan terlihat puncak-puncak tajam berintensitas tinggi yang dihasilkan oleh sinar-X karakteristik dan spektrum sinar-X bremsstrahlung dengan energi kontinu seperti terlihat pada gambar 3.2.
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Metode XRF (X-ray Fluorescence) adalah salah satu metode karakterisasi non destructive yang biasa dipakai untuk menganalisis komposisi unsur penyusun dari suatu sampel meliputi jenis dan konsentrasinya. Proses yang terjadi dalam kerja alat XRF adalah sampel ditembak dengan sinar-X sehingga elektron orbital dalam kulit atom sampel yang dikarakterisasi tereksitasi ke kulit yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Elektron lain dari kulit yang memiliki tingkat energi lebih tinggi akan mengisi hole tersebut. Kelebihan energi elektron yang berpindah antara dua kulit berbeda tingkat energi itu dilepaskan sebagai sinar-X karakteristik yang dipancarkan oleh atom sampel. Hasil karakterisasi menggunakan metode XRF adalah spektrum hubungan energi dan intensitas sinar-X. Puncak-puncak tajam pada spektrum menunjukkan keberadaan jenis suatu unsur bergantung pada besar energinya dan intensitas menunjukkan konsentrasinya.
Program Cassy Lab adalah program bawaan alat XRF yang berfungsi sebagai pengontrol alat sekaligus pengolah data XRF. Pengolahan data XRF menggunakan program Cassy Lab memiliki beberapa hal yang bersifat kurang efisien. Program Penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016) disusun dalam rangka otomatisasi pengolah data XRF khusus untuk menentukan jenis dan konsentrasi unsur dalam sebuah sampel.
C. Alat dan Bahan 1. Komputer PC 2. Program Cassy Lab XRF 3. Program penganalisa grafik XRF (Versi Umi K 2016). 4. Data sekunder XRF
D. Prosedur Eksperimen 1. Jalankan program Cassy Lab 2. Ambil data sekunder XRF ke dalam program Cassy Lab. Data akan ditampilkan dalam
bentuk tabel dan grafik. 3. Kalibrasi energi menggunakan program Cassy Lab 4. Tentukan jenis unsur dalam sampel menggunakan program Cassy Lab.
Program Cassy Lab Tahapan langkah kalibrasi energi dan penentuan jenis unsur dalam software Cassy Lab : a. Kalibrasi energi
1. Klik kanan “Energy Calibration”. 2. Jendela dialog pada “Energy Calibration”, masukkan nilai energi Kα unsur Fe (6,403
keV) dan nilai energi Kα unsur Zn (8,638 keV) 3. Menandai nomor channel pada energi 6,403 keV dan 8,638 keV. 4. Masukkan nilai yang diperoleh kedalam jendela dialog “Energy Calibration”. 5. Klik “Accept”.
b. Penentuan jenis unsur
1. Klik kanan “X-Ray Energies”. 2. Pilih jenis setiap unsur yang ada pada tabel periodik unsur dengan cara mengklik satu
persatu. Jika jenis unsur yang dipilih sudah sesuai dengan puncak spektrum klik “Adopt” dan setelah selesai klik “Ok”.
5. Ambil data XRF pada tabel Cassy Lab untuk diimpor ke dalam tabel program Penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016)
6. Tentukan jenis unsur dan konsentrasi menggunakan program Penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016)
2. Program Penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016) Tahapan langkah pengolahan data XRF :
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
a. Ambil data XRF sampel dari tabel Cassy Lab dengan cara letakkan kursor dalam tabel data
Cassy Lab lalu klik kanan. Muncul jendela pop up menu dan pilih submenu Copy Table.
b. Masukkan data tabel dari program Cassy Lab ke dalam tabel program penganalisis grafik XRF dengan cara letakkan kusor dalam tabel program penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016) kemudian klik kanan sehingga muncul jendela pop up menu dan pilih submenu Paste Data.
c. Tampilkan data XRF dalam bentuk grafik dengan cara letakkan kusor dalam tabel program penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016) kemudian klik kanan sehingga muncul jendela pop up menu dan pilih submenu Take Data
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
d. Penentuan puncak-puncak spektrum dengan cara letakkan kusor dalam grafik program penganalisis grafik XRF (Versi Umi K 2016) kemudian klik kanan sehingga muncul jendela pop up menu dan pilih submenu Tentukan puncak-puncak
e. Penentuan jenis unsur dalam sampel dengan cara pilih menu utama Data dan pilih submenu Tentukan unsur atau tekan shortcut key Ctrl+U
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
f. Penentuan konsentrasi unsur dalam sampel dengan cara pilih menu utama Data dan pilih submenu Tentukan konsentrasi atau tekan shortcut key Ctrl+K
7. Bandingkan perolehan hasil analisis data XRF antara menggunakan program Cassy Lab dengan program penganalisis grafik XRF.
8. Ulangi langkah pengolahan data sekunder XRF untuk 2 sampel sekunder XRF yang lain. E. Tugas
1. Jelaskan tentang energi ikat elektron orbital dan kaitannya dengan energi sinar-X karakteristik ?
2. Jelaskan apa perbedaan dari sinar X karakteristik Kα,Kβ,Kɣ,Lα,Lβ, dan Lɣ serta dari beberapa sinar X karakteristik tersebut nilai manakah yang probabilitasnya paling sering muncul ? Berikan penjelasanmu
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Eksperimen 4 SERAPAN SINAR RADIOAKTIF
A. TUJUAN 1. Praktikan dapat menjelaskan prinsip kerja Geiger Muller Counter (GM). 2. Praktikan dapat menentukan daerah Plateau Geiger Muller. 3. Praktikan dapat menentukan konstanta serapan sinar radioaktif suatu bahan.
B. DASAR TEORI Detektor Geiger Muller terdiri atas tabung ionisasi gas yang diberi tegangan tinggi
antara katoda dan anodanya. Dinding tabung detektor sebelah dalam dilapis logam berfungsi sebagai katoda, dan kawat di tengah tabung berfungsi sebagai anoda. Kedua ujung tabung gas ditutup dengan bahan isolator.
Bila ada partikel radioaktif masuk ke dalam tabung detektor maka akan terjadi ionisasi atom-atom gas. Ion positif akan bergerak menuju katoda sedangkan elektron (ion negatif) tertarik ke anoda. Pergerakan elektron menuju anoda akan memiliki kecepatan lebih besar daripada ion positif karena elektron mempunyai massa yang relatif ringan daripada massa ion positif. Selama pergerakan elektron menuju anoda, elektron tersebut juga akan menumbuk atom-atom gas isian sehingga terbentuklah pasangan ion sekunder. Jumlah pasangan ion sekunder yang terbentuk tergantung besar energi partikel radiasi yang masuk ke dalam tabung detektor. Proses ionisasi sekunder akan terjadi terus menerus hingga terjadi pengumpulan elektron yang cukup besar di anoda. Pengumpulan muatan (avalanche) pada anoda akan menyebabkan tegangan menurun dan menghasilkan pulsa listrik.
+++++++
- - - - - - -
R
C
Anoda
Katoda
HV
Counter
C
Gambar 4.1 Tabung Geiger Muler
Bila beda potensial antara kedua elektroda dinaikkan, maka jumlah ion yang masuk ke dalam elektroda juga akan semakin banyak sehingga pulsa listrik atau arus yang terbentuk akan bertambah atau tetap. Jumlah molekul yang terionisasi oleh partikel radiasi sama dengan jumlah ion yang terbentuk (daerah ionisasi) terjadinya ionisasi sekunder dan multiplikasi (daerah proporsional) dan daerah Geiger Muller. aGrafik beda potensial detektor vs jumlah ion dapat dilihat pada Gambar 5.2. Pada daerah ionisasi dan daerah proporsional, tinggi pulsa sebanding dengan energi partikel radiasi yang masuk ke dalam detektor GM. Tetapi pada daerah Geiger Muller tinggi pulsa sama untuk semua jenis radiasi dengan berbeda energi pada tabung dengan diskriminator (pembatas tinggi pulsa) pada alat pencatat dan penguat, jumlah cacahan tiap satuan waktu terhadap tegangan elektroda akan diperoleh
grafik karakteristik tabung Geiger Muller peka terhadap radiasi partikel , , , tergantung pada tebal dindingnya.
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Daerah Plateau Beda potensial pada waktu cacah dimulai disebut potensial ambang, sesudah kenaikan
tajam, lalu cacahan hampir konstan dengan pertambahan tegangan. Daerah inilah disebut daerah Plateau yang merupakan daerah kerja Geiger Muller, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Plateau merupakan daerah tegangan operasi detektor Geiger-Mueller dimana detektor dapat bekerja secara optimal. Daerah plateau dapat dilihat pada grafik hubungan antara tegangan terhadap laju cacah per menit atau counting rate. Tegangan operasi detektor akan baik apabila memiliki panjang daerah plateau lebih dari 100 V dan slope garis grafik plateau kurang dari 10%. Panjang plateau dapat ditentukan dari selisih antar tegangan awal terjadinya plateau (V1) dengan tegangan akhir plateau (V2) sesuai dengan persamaan 4.1
Panjang plateau = V2-V1 (4.1)
Daerah
Plateau
Daerah
Pengosongan
V
N
Potensial
Ambang
Gambar 4.2 Hubungan antara beda potensial dengan pencacahan Geiger Muller Slope garis grafik daerah plateau
����� ����� = � �
�������
������� ��������100% (4.2)
dengan R1= Jumlah cacahan persatuan waktu pada tegangan V1 (cpm) R2 = Jumlah cacahan persatuan waktu pada tegangan V2 (cpm) Pada beda potensial yang lebih tinggi setelah daerah Plateau, akan terjadi pengosongan dan pencacahan terus naik. Serapan Sinar Radioaktif
Sumber suatu bahan radioaktif akan meluruh dengan memancarkan sejumlah partikel tertentu dalam waktu tertentu pada suatu luasan Am2. Tingkat pancaran dinyatakan :
∆(#$�%$�)
(4.3)
Fraksi partikel yang dapat bertahan ‘hidup’ baik dalam bahan penyerap maupun bahan
penghambur dinyatakan oleh:
∆⁄
∆⁄=
= �$(� (4.4)
V1 V2
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
dengan No menyatakan jumlah cacahan permenit sebelum memasuki material penyerap, N
adalah jumlah cacahan permenit setelah sinar radioaktif melintasi bahan, (cm-1) adalah koefisien penyerapan/penghamburan (bergantung jenis material), dan x (cm) adalah tebal bahan penyerap/penghambur.
x cm
N
(cpm)
No
Gambar 4.3 Peluruhan jumlah cacahan radioaktif oleh bahan penyerap
C. ALAT DAN BAHAN 1. Detektor Geiger Muller, sebagai pendeteksi radiasi. 2. Unit Geiger Muller Counter, sebagai pencacah radiasi. 3. Sumber radioaktif, sebagai penghasil sinar radioaktif. 4. Seng dan keramik/tegel, sebagai bahan penyerap.
D. PROSEDUR EKSPERIMEN 1. Menentukan daerah Plateau
1) Rangkai alat seperti gambar berikut :
Gambar 4.4 Unit eksperimen serapan radioaktif
Keterangan: a) Source : sumber radioaktif b) M : material yang diukur c) P : probe tabung GM
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
d) 123 : display digital tegangan / counter e) Start : Mulai menghitung f) Time : Pemilihan waktu counter g) V : Pengatur tegangan GM
2) Atur waktu 10 sekon. 3) Atur tegangan mula-mula 280 V. 4) On kan tombol Start kemudian tekan tombol Counts. 5) Amati pencacahan. 6) Tambahkan tegangan menjadi 320 V. 7) Amati lagi pencacahan. 8) Ulangi untuk setiap kenaikan 20 V, dan amati pencacahannya. 9) Plot grafik hubungan tegangan (V) terhadap cacahan (N). 10) Hitung slope dan panjang daerah plateau pada grafik tsb.
2. Pengukuran serapan
Berdasarkan plot grafik prosedur eksperimen sebelumnya di atas akan diperoleh daerah Plateau. Selanjutnya tentukan tegangan anoda kira-kira tengah-tengah daerah Plateau sebagai tegangan operasi detektor. Selanjutnya siapkan 2 macam bahan berbeda jenis namun memiliki ketebalan yang sama. Kedua macam bahan akan berperan sebagai penyerap radioaktif : 1) Pindahkan sumber radiasi, dan lakukan pencacahan sebagai cacah latar. 2) Pasang kembali source dan lakukan pencacahan 5 kali, catat sebagai N0. 3) Ukur ketebalan 1 lapis bahan penyerap A 4) Pasang bahan penyerap A sebanyak 1 lapis, lakukan pencacahan 5 kali. 5) Ulangi langkah 3 sebanyak 3 kali penambahan jumlah lapisan bahan penyerap A. 6) Ulangi langkah ke 3 – 5 untuk bahan penyerap B. 7) Plot grafik hubungan ketebalan bahan penyerap (x mm) terhadap ln N/N0 untuk
bahan penyerap A dan bahan penyerap B dalam 1 grafik skaligus 8) Tentukan nilai koefisien serapan masing-masing bahan penyerap A dan bahan
penyerap B. Bandingkan nilai koefisien serapan kedua bahan dan analisalah. Catatan : Setiap pengukuran dikurangi cacah latar
E. TUGAS 1. Apakah arti nilai koefisien serapan pada suatu bahan ? 2. Apakah arti nilai gradien grafik yang anda buat pada prosedur eksperimen 2.7 ? 3. Mengapa daerah plateau sebuah detektor harus dicari terlebih dahulu sebelum detektor
dapat digunakan untuk mendeteksi partikel radioaktif ? Jelaskan !
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Eksperimen 5 KONVERSI ENERGI II
A. TUJUAN 1. Praktikan dapat mengukur intensitas radiasi energi matahari. 2. Praktikan dapat menghitung daya listrik yang dapat dibangkitkan oleh sel surya 3. Praktikan dapat menentukan efisiensi konversi energi matahari menjadi energi listrik
B. LANDASAN TEORI Sel surya merupakan suatu alat konversi energi dari bahan semikonduktor yang dapat
mengubah energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Efek perubahan tersebut dinamakan efek fotovoltaik yang pertama kali ditemukan oleh Lenard. Pada tahun 1941 Ohl mulai menggunakan silikon sebagai bahan sel surya dengan menerapkan teknologi grown p-n junction. Sampai saat ini sel surya sudah dapat ditemukan dari berbagai jenis bahan seperti Si, Ge, Cds, CU2S, GaAs, Pb,Te dalam bentuk lapisan film tipis (thin film) pada substrat kaca, logam atau plastik. Dari semua jenis bahan semikonduktor tersebut, silikon merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sel surya karena silikon tersedia dalam jumlah yang besar di alam yaitu sekitar 25 % kerak bumi terdiri atas silikon.
Radiasi surya merupakan paket-paket energi yang disebut foton dengan energi sebesar
� = ��� = ℎ�. Radiasi tersebut sebelum sampai di permukaan bumi harus melalui atmosfir
terlebih dahulu. Besar radiasi surya secara kontinyu yang diterima oleh bumi dalam atmosfir adalah 1,7 x 1017 watt. Besarnya daya radiasi surya yang tiba pada suatu permukaan adalah :
� = �( ) ���
∞
� � (5.1)
dengan A = luas permukaan, N (λ) = jumlah foton/cm3 detik.
Energi surya yang sampai pada permukaan sel surya akan diserap dan mengakibatkan terjadinya efek fotovoltaik dalam sel surya tersebut. Foton yang terserap melepaskan energinya pada elektron yang terdapat pada pita valensi dan kemudian digunakan oleh elektron-elektron pada pita valensi melompat ke pita konduksi. Hole adalah kekosongan pita valensi akibat ditinggalkan oleh elektron valensi yang melompat ke pita konduksi. Jumlah elektron tereksitasi sama banyaknya dengan jumlah hole. Jumlah pasangan elektron-hole yang dibangkitkan persatuan volume persatuan waktu pada suatu titik yang jaraknya x dalam semikonduktor adalah :
G (λ,X) = α (λ) No (λ) exp [-α (λ) X] (5.2)
Dimana :
G (λ,X) = Jumlah pasangan elektron hole yang dibangkitkan oleh cahaya dengan panjang gelombang persatuan volume dan persatuan waktu pada jarak x di dalam semikonduktor.
α (λ) = koefisien penyerapan untuk panjang gelombang. No (λ) = Jumlah foton persatuan luas tertentu dalam satu detik untuk panjang
gelombang.
Hole yang terbentuk pada pita valensi akan berfungsi sebagai pembawa muatan positif sedangkan elektron pada pita konduksi yang berfungsi sebagai pembawa muatan negatif.
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
Perpindahan elektron ini hanya terjadi jika energi foton sama sama atau lebih besar dari energi celah (Eg) bahan semikonduktor. Untuk silikon energi celah (gap) Eg = 1,11 eV. Sel surya pada umumnya merupakan penggabungan antara bahan semikonduktor tipe-n dan semikonduktor tipe-p. Dari penggabungan ini diharapkan elektron dan lubang akan mengalir dari bahan sebagai arus listrik. Secara ideal arus sel surya adalah :
�� = � �exp ������ − 1� (5.3)
dan tegangan keluarannya adalah :
� = ��� ln ($%&
$'+ 1) (5.4)
Dengan Iph adalah arus foton dan Io adalah arus balik jenuh. Besarnya daya yang dihasilkan oleh sel surya adalah:
P = Vout I out (5.5)
Dengan Vout = tegangan keluaran sel surya dan Iout = arus keluaran sel surya. Persamaan arus yang dihasilkan oleh sel surya besarnya :
� = �� exp � ��)
− 1� − �* (5.6)
Dengan Io = arus balik jenuh, Is = arus yang ditimbulkan oleh radiasi surya, V = tegangan keluaran sel surya, VT = KT/q dimana K = Konstanta Boltzmann = 1.380658.10-23 Joule/Kelvin, T = suhu (Kelvin) dan q = muatan elektron = 1.60217723. 10-19 Coulomb.
Efisiensi sel surya merupakan perbandingan antara energi keluaran dan energi matahari yang sampai pada permukaan bahan dengan persamaan :
+ = �,-.$/-.00123
4 100% = �7$7123
4 100% (5.7)
Dengan
FF = faktor pengisian = ( Vm. Im)/(Voc. Isc) Vm = tegangan maksimum Im = arus maksimum Voc = tegangan terbuka Isc = arus rangkaian singkat
C. ALAT DAN BAHAN 1. Lux meter 2. Stopwatch 3. Panel sel surya 4. Multimeter digital 5. Thermometer 6. Kabel penghubung
Penuntun Praktikum Eksperimen Fisika II
Laboratorium Fisika FMIPA UHO Tahun 2020
D. PROSEDUR EKSPERIMEN 1. Rangkai alat seperti pada gambar di bawah ini
Gambar 5.1. Rangkaian eksperimen sel surya
2. Atur potensiometer RV sehingga tegangan pada voltmeter bernilai nol (V=0). Catatlah
arus yang terbaca pada amperemeter sebagai Isc (arus singkat).
3. Putar potensiometer sehingga diperoleh pasangan nilai V – I. Ulangi langkah ini untuk
berbagai nilai V – I.
4. Atur potensiometer RV sehingga arus pada amperemeter bernilai nol (I=0). Catatlah
tegangan yang terbaca pada voltmeter sebagai Voc (tegangan terbuka).
5. Ulangi langkah 2-4 sebanyak 3 kali untuk berbagai intensitas cahaya.
E. TUGAS
1. Apakah pita konduksi, pita valensi dan energi gap itu ? Jelaskan sifat pita konduksi,
pita valensi dan energi gap pada bahan konduktor, semikonduktor dan isolator
2. Bagaimana proses fisika yang terjadi pada sel surya sehingga dapat mengubah energi
cahaya matahari menjadi energi listrik ?