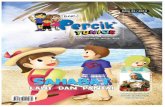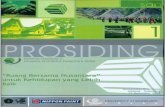Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi! - Pokja AMPL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi! - Pokja AMPL
Media Informasi Air Minumdan Penyehatan Lingkungan
Diterbitkan olehKelompok Kerja Air Minumdan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL)
Penanggung JawabDirektur Permukiman dan Perumahan
BappenasDirektur Penyehatan Lingkungan
Kementerian KesehatanDirektur Pengembangan Air Minum
Kementerian Pekerjaan UmumDirektur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna Kementerian Dalam Negeri
Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri
Pemimpin RedaksiOswar Mungkasa
Dewan RedaksiMaraita Listyasari
Nugroho Tri Utomo
Redaktur PelaksanaEko Budi Harsono
Desain dan ProduksiAgus Sumarno
Sofyar
Sirkulasi/SekretariatAgus Syuhada
Nur Aini
Alamat RedaksiJl. RP Soeroso 50, Jakarta Pusat.
Telp./Faks.: (021) 31904113Situs Web: http//www.ampl.or.ide-mail: [email protected]
Redaksi menerima kirimantulisan/artikel dari luar.
Isi berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.
DaftarIsi
Dari Redaksi ............................................................................................................. 3 Suara Anda................................................................................................................ 4Laporan Utama
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Hak Asasi Atas Air............................... 5Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia.................................................... 10Sekilas Hak Asasi Manusia (HAM)..............................................................13
Regulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia........ 14Agenda HariAntiKemiskinanInternasional, SulitnyaAksesAirMinumdanSanitasiBagiandariKemiskinan.................16Wacana Persoalan Hak atas Air dan Rumah (tulisan pertama)................................ 18 Negara Harus Menjamin Hak Rakyat Atas Air.............................................24 Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!...................................... 28 Wawancara NugrohoTriUtomo,DirekturPermukimandanPerumahanBappenas......31 HamongSantono,KRUHA...........................................................................34 APatraMZen,DirekturYLBHI....................................................................36Inovasi Teknologi Oksidasi untuk Air Bersih .......................................................... 38 TanahLiatMediaEfektifMenjernihkanKeruhnyaAirGambut..................41Sisi Lain Syariat Islam sebagai Solusi........................................................................ 45Reportase DialogPublikWaspadaiKonflikAir KonflikAirMinumPerluDiantisipasiPemerintahDaerah.........................46 30%KematianBalitaAkibatSanitasiBuruk...............................................48 WorkshopHCTPSBagiGuruSDDKIJakarta Baru Tiga Persen Masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun.............................49 “PolitikAir”HarusJadiPerhatianPemerintahDaerah...............................50 SinergiProgramJejaringAMPLdenganGBCI.............................................53Panduan Sejumlah Teknologi Mendapatkan Air Bersih ........................................... 54Info CD..................................................................................................................... 55Info Buku.................................................................................................................56Info Situs ................................................................................................................. 57Pustaka AMPL......................................................................................................... 58Fakta PerluInvestasi150MilliarUS$CegahKrisisAirDunia.............................. 59
Edisi III, 2010
3
DariRedaksi
POKJA
Tidak terasa kita telah melewati hari raya Idul Fitri 1431 Hijriah. Bagi para pembaca yang merayakannya kami menyampaikan Selamat Idul Fitri. Dari hati yang paling dalam kami memohonkan Maaf Lahir
Bathin. Semoga kita semua menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi.
Pada awal September, tiba-tiba saja kita semua mendengar berita tentang dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB terkait penetapan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia. Sebagian kalangan mungkin terkejut tetapi banyak juga yang menerimanya biasa-biasa saja dengan berbagai alasan. Bisa saja karena sebenarnya hak asasi manusia telah menjadi pembicaraan yang hangat di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Hal ini juga ditunjang oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun sebenarnya ide tentang hak asasi manusia sendiri telah termaktub dalam UUD 1945. Sementara pengakuan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia sendiri di Indonesia secara implisit telah teradopsi dalam regulasi yang ada. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Resolusi ini merupakan kemajuan luar biasa bagi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Menjadi suatu obsesi berkepanjangan bagi pemangku kepentingan bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, kita berharap masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air minum dapat berkurang secara signifikan. Tentu saja, caranya tidak sederhana. Terutama mempertimbangkan masih banyaknya pemerintah daerah yang bahkan belum menyadari sepenuhnya bahwa penyediaan air minum merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Tentu saja jalan masih panjang. Dalam kaitan itu, kemudian kami ingin menjadikan momen keluarnya resolusi tersebut untuk kembali membangkitkan semangat kita semua akan besarnya tanggungjawab yang masih tersisa. Masih 100 juta lagi saudara kita yang belum tersentuh akses air minum.
Menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab penyediaan air minum kepada pemerintah daerah juga bukan pilihan yang bijak. Kita semua seyogyanya bersama-sama bahu membahu dengan pemerintah daerah menuntaskan pekerjaan rumah ini. Sebagaimana salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu saling membantu dan bersinergi mencapai tujuan bersama. Mari. Tunggu apa lagi (OM).
4
Kuliah Kerja di Majalah Percik
Perkenalkan nama saya Muhammad Chaidir, mahasiswa Ilmu Komunikasi Uni-versitas Moestopo Beragama Jakarta. Saya membaca majalah Percik yang berada di Perpustakaan Kampus beberapa waktulalu. Melihat isi serta sejumlah isu yang se-cara khusus membahas tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang disajikan begitu lugas, cerdas dan bernasmembuat saya tertarik untuk membuat Tu-gas Akhir Terkait dengan fungsi media yang bapak kelola terkait dengan pembangunan AMPL di Indonesia.
Saya sangat berharap pengelola Majalah Percik bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitianuntuk tugas akhir saya tentang Fungsi Me-dia Internal Dalam Program Pemerintah Percepatan Pembangunan AMPL. Jika bapak bersedia saya akan kirimkan surat pengantar dariKampussertaProposalTugasAkhirSaya.Terimakasih. Salam Percik
Muhammad ChaidirUniversitas Moestopo Jakarta
Terimakasih atas perhatian dan keper-cayaan anda terhadap Majalah Percik. Silah-kan saja kirimkan secara resmi permohonan anda untuk melakukan penelitian. Dengan senang hati kami akan membantu. Salam Percik
Mari Kita Hormati Air Siapakah yang bisa hidup tanpa air? Be-
gitu besar kegunaan air dalam kehidupan di dunia ini. Saat kita gerah dan kotor setelah beraktifitas sehari-hari, kita menyiramkanbadan kitadenganair untukmandi. Kemu-dian kita meneguk air kalau dahaga, danbegitubanyaksekaliaktifitaskehidupankitayang sangat bergantung pada air.
Begitulekatnyaairdalamkehidupankita,sehinggabisasajaadayangtidakmenyadarimanfaatnya. Manfaat itu baru terasa bila kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ketika saluran air mengalami gang-guan, dan keluarnya air menjadi mampat
dankotor,itusudahsangatme-resahkan kita. Ba-
gaimana kalau air sudah tidak kita dapatilagi? Bencana kekeringan yang menimpa,selain bencana banjir yang begitu dahsyat terjadi karena kesalahan mahluk di dunia ini yangbegituserakahdantidakpedulidengankondisi alamnya.
Begitu besar kekuatan air dalam kehidup-an ini, karena itulah sayangilah air denganmenggunakannyasebaik-baiknya.Selainitu,kekuatan air akan semakin bertambah dan berpengaruh positif pada diri kita bila saathendakmenggunakanair,misalnyamaumi-num,kitaberdoaterlebihdahulu.Halterse-but dibuktikan oleh profesor dari Jepangdenganpenelitiannyatentangairyangakanberubah tekstur dan kristalnya sesuai kondisi pemakainya.Karena itugunakanlahkekuat-an postif air dengan menggunakannya de-ngan penuh kasih sayang.
Rini Utami AzisSolo, Jawa Tengah.
Liberalisasi Air Semakin Memprihatinkan
Gelombang liberalisasi tampaknya su-dah tak terbendung lagi. Semua aspek hidup kita terpaksa harus tunduk pada kesepakat-an-kesepakatan internasional yang hanya memperhatikanpemilikmodalbesar.
Telah tampak adanya diskriminasi karena privatisasiair.Kebijakanyangtidakprodenganrakyatketikaairadalahbisnis,makaiakemudi-antaksekedarbergerakmencarikeuntungan,tetapi juga bagaimana dapat mengikat dan lalu memperdaya orang sehingga mau tunduk ter-hadapnya,terhadapkekuasaanyangmengua-sainya.Pengelolaanairtidaklagimempertim-bangkan bagaimana melakukan pengelolaan air dalam suatu sistem yang sanggup memberi pelayananairkepadamasyarakat secaraadil,merata dan terjangkau.
Air adalah kebutuhan dasar manusia,sebab itu air tak boleh dikomersialisasikan sebagai kebutuhandasarmasyarakat, telahdijamindalamkonstitusinegarapadapasal33UUD1945.ContohnyadiBatam,daerahpemukimanelitmenjadiprioritasutama,se-mentara daerah-daerah perkampungan dan kumuhtidak tersentuh, seperti Teluk Leng-gung, Pungur yang masih mengkonsumsiairsumursampaisaatini,padahalmenuruthasilujilaboratoriumDinasKesehatanairdiwilayahtersebuttidaklayakkonsumsikare-namengandungbakteripositiftinggidanpHdi bawah batas syarat. Sementara beberapa meter dari pemukiman warga berdiri insta-lasi pengelolaan air (IPA).
Banyaknya bunuh diri yang sekarang sedang merajalela karena merasa tekanan hidupyangtinggi, yang sulituntukdijalani.Masihkanpemerintahtidakmemperhatikanhak-hak dasar seperti air, pendidikan dankesehatan? Bukankah rakyat tidak pernahmenuntut sesuatu yang berlebihan? Mereka hanya membutuhkan terpenuhinya hak-hak mereka. Untuk menangis meratapi nasib pun kita akan berpikir karena kita akan me-ngeluarkan“airmata”.Sekalilagi,kitaperluberhati-hatidenganmasalahair,sekalisalahlangkah,bukannyawasajayangtergadaikan,tetapi juga masa depan anak cucu.
Maftuhah Menteng, Jakarta.
Jangan Gunakan Botol Plastik Berulang
Botol dan gelas air minum dalam ke-masan (AMDK) sering kembali digunakan.Bahkan, botol atau gelas itu dipakai beru-lang-ulang. Padahal sebenarnya, kemasantersebut hanya untuk sekali pakai. Ada stan-dar kesehatan yang harus dipenuhi produsen AMDK.Standarinibertujuanmeminimalkanbakteri yang ada di dalam kemasan.
Kalausegelnyasudahdibuka,hendaknyabotoltidakdipakailagi.Sebab,AMDKdibuatdari bahan polyethylene terephthalate atau PET yang mengandung karsinogen (penyebab kanker). Zat itu membahayakan kesehatan tubuh bila terminum. Melalui serangkaian standarsterilisasibotol,saatmasihtersegel,zattersebutbersifattidakaktif.Jumlahbak-teri yang ada dalam AMDK pun dipastikantak melampaui ambang batas toleransi.
Namun jangan salah botol air minum bukan hanya bisa dibuat dengan PET, tapijuga dengan PVC (Poly Vinyl Chloride), danini jauh lebih berbahaya karena bisa menim-bulkan hujan asam bila dibakar. Bahkan PVC berpotensiberbahayauntukginjal,hatidanberat badan. Perubahan penggunaan PVC ke PET sebenarnya sudah dimulai tahun 1988. Semogasajasekarangtidakadalagiperusa-haan yang menggunakan PVC.
PenggunaanbotolataugelasAMDKber-ulang membuat karsinogen tersebut larut dalam air yang kita minum. Terutama bila dilakukan dalam jangka panjang. Jika me-mang terpaksa menggunakan lagi botol atau gelas minuman kemasan perlu dicuci dengan sabun yang mengandung disninfektan atau antikuman.Sabuncuciuntukperabotrumahtangga sudah memenuhi standar ini.
Wahyu, Surabaya
SuaraAnda
5
Edisi III, 2010LaporanUtama
Awal bulan Septem-ber lalu, masyarakat dunia, khususnya prak-tisi, pegiat lingkungan hidup dan kesehatan
masyarakat serta aktivis dibidang Air Minum dan Penyehatan Lingkun-gan dibuat terkejut dengan terbitnya Reso lusi Majelis Umum PBB yang menegaskan bahwa akses memper-oleh air minum dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari hak asa-si manusia. Jelasnya, resolusi Majelis Umum PBB tersebut bertajuk: “Hak untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang bersih dan aman meru-pakan bagian dari hak asasi manusia, dan merupakan elemen penting un-tuk menikmati hak atas hidup secara menyeluruh.”
Dalam resolusi tersebut Maje-lis Umum PBB mendesak seluruh masyarakat internasional dan Negara yang menandatangani resolusi untuk meningkatkan usaha menyediakan air dan sanitasi yang aman, bersih, dan mudah untuk dijangkau bagi selu-ruh manusia.” “Keterbatasan akses ke air minum membunuh lebih banyak anak-anak dibandingkan jumlah anak yang meninggal dunia akibat AIDS, malaria, dan campak,” kata Ketua Dewan HAM PBB dari Bolivia, Pablo Solon dalam situs resmi PBB.
Data Program Lingkungan Hidup PBB memperkirakan 884 juta pen-duduk dunia tidak memiliki akses untuk mendapatkan air minum yang aman dan 2,6 milyar orang memiliki akses terbatas untuk fasilitas sanitasi
yang layak. Kesulitan akses tersebut menyebabkan antara lain 1,5 juta ba-lita meninggal dunia akibat penyakit yang terkait dengan air minum dan sanitasi yang layak.
Resolusi Hak Atas Air minum tersebut disahkan melalui voting yang diikuti 163 negara anggota PBB. Tidak ada negara yang menolak resolusi ini. Terdapat 122 negara termasuk China, Rusia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Brazil mendukung resolusi tersebut. Sementara 41 negara, seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Botswana menyatakan abstain.
Sebagian negara yang abstain me-nyatakan, resolusi tersebut tidak menjelaskan cakupan hak atas air minum dan kewa-jiban yang
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi
Hak Asasi Atas Air
6
harus dilakukan untuk memenuhi hak tersebut. Menyikapi resolusi terse-but, pakar AMPL, Hening Darpito menga takan pada awalnya ada kekha-watiran bahwa resolusi hak atas air dan sanitasi ini prematur, ternyata sebaliknya dalam voting, resolusi ini malah memperoleh tanggapan positif oleh hampir semua peserta sidang.
Jalan Panjang Diawali pada tahun 1948 ketika
Deklarasi Universal Hak Asasi Ma-nusia (DUHAM) diumumkan dan dilanjutkan pada tahun 1966 ketika International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), air tidak disebut eksplisit sebagai hak asasi tetapi disebutkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak un-
tuk kesehatan, hak untuk perumahan dan hak untuk makanan. Setelah itu barulah disebutkan secara lebih eks-plisit walaupun masih sebagai bagian dari suatu konvensi dengan tema lain seperti misalnya yang tertuang dalam pasal 14 ayat (2) huruf h The Conven-tion on the Elimination all of Forms Dis-crimination Against Women-(CEDAW 1979), bahwa negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang ter-ukur untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perem-puan, khususnya menjamin hak-hak perempuan untuk menikmati standar kehidupan yang layak atas sanitasi dan air minum yang sehat. Demikian juga dalam pasal 24 The Convention on The Right of The Child-CRC 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka setiap anak memiliki hak atas air minum yang bersih.
Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dan himbauan melalui Deklarasi Millenium yang mence-tuskan proyek MDGs (Millenium Development Goals), yang merupa-kan komitmen para kepala negara/pemerintahan anggota PBB untuk memerangi kemiskinan global antara 2000-2015 menyerukan kepada pe-merintah agar “menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang saat ini belum bisa menikmatinya”.
Tetapi pernyataan yang eksplisit dan secara khusus menyebut air baru terjadi pada tahun 2002, ketika Komite Hak Ekonomi Sosial dan Bu-daya PBB dalam komentar umum No-mor 15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya, yaitu air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (right to water) adalah hak asasi manusia. ” The human
Laporan Utama
Water Right dan Right to Water
PemahamanataspengertianWater Right dan Right to Waterseringkabur,keduaistilahituseringdiartikansamadalamBahasaIndonesiayaituHakatas Air. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pemahaman yang
berbeda. Kekuasaan untuk mengambil air dari alam sering disebut sebagaiWater Right yangmengandungpengertiansebagaiberikut:
l Mengambil atau mengalihkan dan menggunakan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah
l Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempatsepertibendunganataustrukturlainnyaatau
l Menggunakan air di sumber alaminya. Water Right merupakan suatu alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai
institusiyangmenguasaiairkepadaperseoranganataubadanusahayangsecarahukum disebut sebagai ‘licences’, ‘permissions’, ‘authorisations’, ‘consents’ and ‘concessions’ untuk memanfaatkan air. Water right dalam terminologi ekonomi dipakai sebagai alat untuk menarik restribusi atas air yang dimanfaatkan.
PengertiantersebutjelassangatberbedadenganRight to Watersepertiyangdipahami dalam kajian Hak Asasi Manusia. Hukum yang mengatur Water Right memilikiasumsibahwaairadalahkomoditiyangmembutuhkanperlindunganhukum bagi pihak-pihak yang menguasainya. Water Rightdapatlebihdiartikansebagai Hak Memiliki Air. Perbedaannya adalah air sebagai sebuah kebutuhan (untuk dimiliki) dan air sebagai sebuah hak. The Right to Water (air sebagai sebuah hak) lebih ditekankan pada air sebagai bagian yang tak terpisahkan darikehidupanmanusiayangbermartabat,olehkarenaituHakAtasAiradalahsesuatu yang mutlak dan telah memunculkan kewajiban bagi Negara untuk mengakuinya.
ISTIMEWA
7
Edisi III, 2010
right to water entitles everyone to suf-ficient, affordable, physically accessible, safe and acceptable water for personal and domestic uses.” Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air. Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehat an. Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak semata-mata sebagai barang ekonomi.
Dalam Komentar Umum Perseri-katan Bangsa-Bangsa (United Na-tions General Comments) pada Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) Nomor 15, hak asasi manusia atas air terdiri dan dua kom-ponen penting, yaitu kebebasan (free-dom) dan pengakuan (entitlements). Kebebasan dimaksudkan tidak adanya intervensi yang bisa menyebabkan ter-
cerabutnya hak asasi manusia atas air, misalnya terkontaminasinya air yang dikonsumsi. Pengakuan adalah hak atas sistem dan manajemen air yang memungkinkan setiap orang mempu-nyai kesempatan dan akses yang sama atas air.
Upaya Pemerintah Sebagaimana hak asasi manusia
lainnya posisi negara dalam hubung-annya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (to respect) yaitu mengharuskan negara mencegah terganggunya langsung/tidak lang-sung pemenuhan hak atas air, melin-dungi (to protect) yaitu mengharuskan negara mencegah keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuh-an hak atas air, dan memenuhinya (to fulfill) yaitu mengharuskan negara mengambil langkah untuk mencapai pemenuh an hak atas air sepenuhnya. Dalam konteks menghormati, peme-rintah Indonesia telah meratifikasi
kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 sehingga ne-gara harus memenuhi hak masyarakat termasuk kebutuhan akan air mi-num.
Upaya pemerintah pun terlihat serius dengan keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dalam pasal 5 menyatakan bahwa negera menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Lebih lan-jut penjabaran hak atas air yang tertu-ang dalam UU menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk (i) memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air; (ii) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pe-ngelolaan sumber daya air; (iii) memperoleh manfaat atas pengelo-
8
laan sumber daya air; (iv) menyatakan keberatan terhadap rencana pengelo-laan sumberdaya air yang sudah diu-mumkan dalam jangka waktu terten-tu sesuai dengan kondisi setempat; (v) mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air; dan/atau (vi) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumberdaya air yang merugikan ke-hidupannya.
Sementara hak masyarakat diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan UU No-mor 7 Tahun 2004, yang dalam hal ini adalah pelanggan yaitu (i) mem-peroleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; (ii) mendapatkan informasi tentang struktur dan be-saran tarif serta tagihan; (iii) meng-ajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan; (iv) mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; dan (v) memperoleh pelayanan pem-
buangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.
Bahkan secara teknis kualitas air minum telah diatur tersendiri dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengen-dalian Pencemaran Air untuk memas-tikan kepentingan masyarakat terlin-dungi.
Walaupun demikian, pemerintah dianggap telah gagal memenuhi hak masyarakat tersebut. “Upaya peme-rintah Indonesia untuk melindungi dan menghormati hak atas air mi-num masih terlalu jauh dari harapan masyarakat,” kata Koordinator Na-sional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha) Hamong Santono. “La-poran yang disusun oleh UNESCAP, ADB, dan UNDP, juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang lambat dalam pemenuh-an target air minum dan sanitasi da-lam MDGs,” tuturnya.
Salah satu pemicu rendahnya akses masyarakat terhadap air mi-num itu adalah kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Tahun 2005 lalu, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp.500 miliar dan tahun 2010 Rp.3 triliun. Padahal, kebutuhan ang-garan untuk pembangunan air mi-num dan sanitasi berkisar 2 sampai 3 kalinya. “Perlu komitmen dan agenda politik yang lebih jelas soal hak atas air masyarakat. Kita jangan asal ikut menandatangani resolusi namun tidak tahu setelah itu akan kemana perso-alan air minum dan sanitasi dasar masyarakat bergerak,” ujar Hamong,
Namun kembali kepada salah satu prinsip pemenuhan hak asasi manu-sia, bahwa prosesnya harus memper-hatikan kemampuan dari masing-masing pemerintah. Terpenting dari semuanya adalah adanya keinginan yang kuat dari pemerintah mencapai target pemenuhan hak atas air. Hal ini sudah terlihat jelas jika memban-
Laporan Utama
POKJA
9
Edisi III, 2010
dingkan kenaikan alokasi anggaran air minum dan penyehatan lingkunng-an naik hampir enam kali lipat pada kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014) dibanding kurun waktu lima tahun sebelumnya (2005-2009).
Pemerintah Daerah sebagai Ujung TombakSeringkali aktor utama dari pem-
bangunan air minum dan penyehatan lingkungan terlupakan. Berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah daerah lah yang saat ini menjadi pihak yang bertanggungjawab menyediakan air minum. Menjadi pertanyaan penting, sejauh mana konsep hak atas air seba-gai hak asasi manusia telah dipahami oleh pengambil keputusan di daerah. Jika itu saja belum terlaksana, jangan berharap banyak bahwa resolusi PBB tersebut akan berdampak bagi pe-ningkatan akses air minum di Indone-sia. Kalapun telah dipahami, menjadi langkah berikutnya untuk mengeta-hui sejauhmana pemahaman tersebut telah terinternalisasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, semisal rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh (RPJMD). Demiki-an selanjutnya sampai teralokasikan dana yang terfokus pada kelompok marjinal.
Menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah propinsi menjadikan pemahaman hak atas air sebagai hak asasi manusia menjadi bagian dari arus utama pembangunan air mi-num dan penyehatan lingkungan di daerah. Dibutuhkan upaya advokasi baik ke pihak eksekutif maupun legis-latif, dilanjutkan dengan internalisasi melalui peninjauan kembali doku-men RPJMD, sehingga terlihat jelas peningkatan dramatis dari alokasi anggaran AMPL khususnya bagi me-reka yang termarjinalkan. Sepertinya dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan terdapat
sekitar 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Tugas BersamaJadi dibutuhkan tentunya sedikit
kesabaran bagi kita semua untuk da-pat melihat hasil dari upaya pemerin-tah. Tentunya kerjasama dari semua pihak, dan ini juga merupakan salah satu prinsip pemenuhan hak asasi yaitu saling ketergantungan, men-
jadi suatu keniscayaan. Pemenuhan hak atas air sebagai hak asasi manu-sia tidak akan tercapai jika pemerin-tah dibiarkan berjuang sendiri. Mari kita bekerjasama. Masih sekitar 100 juta saudara kita belum memperoleh akses terhadap air minum. Sebagian terbesar dari mereka berasal dari kelompok yang termarjinalkan (OM)
Dirjen HAM, Harkristuti Harkrisnowo:Sejumlah Masalah di Sektor Air Jadi
Perhatian PemerintahDalam Lokakarya Hak Atas Air yang diselenggarakan oleh Pokja AMPL di Bogor beberapawaktulalu,DirekturJenderalHakAsasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowodalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Direktur Kerjasama HAM, DimasSamuderaRummenegaskan,airmerupakanbenda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan mahluk hidup. Tanpa air mahluk hiduptidakakanmampumempertahankan
kehidupannya. Namun dalam kenyataannya dunia mengalami permasalahandenganairyangdisebabkanberbagai faktor,antaralainlajupertumbuhanpendudukduniayangcepat,sertapengelolaanairyangtidakberkelanjutanyangsaatinidilaksanakan.
Disampaikan pula bahwa dalam sambutan tersebut sejumlah kebijakan internasional terkait hak atas air seperti CEDAW(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), CRC (Convention on the Rights of the Child) dan ICESCR (International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Termasuk juga ECOSOCDECLARATION(DeklarasiEkonomi,Sosial,danBudaya)PBBpada bulan November 2002.
Sementara Indonesia sendiri mencantumkan pengakuan atas hak dasar tersebut sejak awal di dalam Undang-Undang Dasar 1945Pasal33yangmenyatakan“Bumi,airdankekayaanalamyangterkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian,negara bertanggung jawab menjamin penyediaan air yang bagi setiapindividuwarganegara.
ISTIMEWA
10
Laporan Utama
Air dalam sejarah kehidupan ma-nusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan ke-
berlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup sesesorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan ter-hadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositif-kan hak atas air menjadi hak yang ter-tinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.
Pentingnya Hak Atas Air sebagai Hak AsasiTanpa disadari sebenarnya banyak
manfaat dari ditetapkannya hak atas air sebagai hak asasi. Seperti misalnya (i) air menjadi hak yang legal, lebih dari pada sekedar layanan yang diberikan berdasar belas kasihan; (ii) pencapaian akses dasar harus dipercepat; (iii) mereka yang tera-baikan menjadi lebih diperhatikan se-
hingga kesen jangan da pat
berkurang; (iv) masyarakat dan warga yang termarjinalkan akan diberdayakan untuk berperan dalam proses peng ambil-an keputusan; (v) negara menjadi lebih fokus pada pemenuhan kewajibannya karena dipantau secara internasional.
Siapa Paling TerdampakBerbicara tentang hak atas air seba-
gai hak asasi manusia, terdapat bebe-rapa kelompok yang sangat terdampak oleh perubahan yang akan terjadi. Me-reka terdampak terutama karena selama ini terabaikan haknya dan menjadi ke-lompok yang dengan berbagai alasan normatif dan legal tidak menjadi target penyedia layanan air minum.
Kaum miskin. Daintara kelompok yang terdampak, kaum miskin lah yang paling menderita. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan 80 persen dari yang tidak mempunyai akses air minum adalah kaum miskin, terutama miskin perdesaan.
Perempuan. Perempuan di ba-nyak komunitas mendapat status yang lebih rendah dibanding pria. Mereka mendapat tugas mengumpulkan atau mencari air untuk kebutuhan rumah tangga. Data menunjukkan 70 persen dari 1,3 miliar penduduk yang sangat miskin adalah wanita (WHO, 2001).
Riset menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga di Afrika menghabiskan 26 persen waktunya untuk mengum-pulkan air, dan umumnya wanita lah yang menjalankan tugas ini (DFID, 2001). Kondisi ini menghalangi wanita be kerja, bahkan bersekolah.
Anak-Anak. Kondisi air yang tidak memadai meningkatkan peluang anak-anak menderita penyakit. Sistem kekebalan mereka belum sepenuhnya terbangun. Anak-anak juga seringkali berbagi tugas dengan kaum perempuan sebagai pengumpul air. Akibatnya, di banyak negara anak-anak banyak yang tidak bersekolah.
Masyarakat Asli. Sebenarnya masyarakat asli inilah yang meman-faatkan sumber air tradisional. Namun dengan berkembangnya suatu daerah, sumber air tersebut kemudian banyak yang tercemar atau dimanfaatkan me-lebihi kapasitasnya. Kondisi ini kemu-dian menjadikan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan air.
Prinsip Utama Prinsip utama hak asasi manu-
sia terkait pembangunan air minum dan sanitasi diantaranya adalah (i) ke-setaraan dan tanpa diskriminasi. Kedua prinsip ini merupakan paling utama
Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia
Hak Atas AirPOKJA
11
Edisi III, 2010
diantara prinsip dasar kerangka hak asasi manusia. Menyatukan prinsip ini kedalam kebijakan pembangunan AMPL memerlukan upaya khusus untuk mengidentifikasi individu dan ke lompok yang paling marjinal dan rawan terkait ketersediaan akses air mi-num dan sanitasi. Selain juga memer-lukan tindakan proaktif untuk memas-tikan individu dan kelompok marjinal termasuk dalam sasaran dan menjadi fokus intervensi. Kelompok ini dian-taranya wanita, anak-anak, penduduk pedesaan, permukiman kumuh, mis-kin, penduduk yang sering berpindah, pengungsi, orang tua, masyarakat ter-asing, orang cacad, dan penduduk dae-rah rawan air. Mengembangkan data terpadu terkait kelompok ini menjadi suatu keniscayaan. Isu utama yang se-ring dibicarakan adalah keterjangkauan (affordability) tanpa membedakan penyedianya oleh swasta atau peme-rintah. Pemerintah bertanggungjawab memastikan bahwa air terjangkau oleh seluruh kalangan bahkan mereka yang tidak mampu membayar. Bentuk upaya tersebut diantaranya berupa penyedia-an sejumlah tertentu air secara gratis, sistem blok tarif, mekanisme susidi silang dan subsidi langsung. (ii) aman dan dapat diterima. Air harus aman un-tuk penggunaan domestik, dan jumlah minimum harus tersedia untuk air mi-num; (iii) layanan terjangkau. Apa yang disebut terjangkau itu?. Pembayaran dianggap tak terjangkau ketika mengu-rangi kemampuan seseorang membeli barang kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, rumah, kesehatan dan pen-didikan. Tidak dianjurkan bagi rumah tangga mengeluarkan dana untuk air minum lebih besar dari 3% pendapa-tannya; (iv) layanan dapat di akses. Ka-pan layanan dianggap dapat di akses?. Pemerintah harus memastikan akses terhadap air tersedia di dalam atau dekat rumah, sekolah atau tempat kerja. Jika tidak memungkinkan, maka kondisi
yang dapat ditolerir adalah waktu yang dibutuhkan ke sumber air maksimal 30 menit. Keamanan ketika mengambil air juga dipertimbangkan; (v) air yang memadai. Berapa banyak kebutuhan air per orang dianggap sebagai kebutuh-an minimum?. PBB mengindikasikan bahwa air harus memadai untuk kebu-tuhan minum, sanitasi, cuci pakaian, dan masak. Dibutuhkan setidaknya 20 liter per orang per hari. Jika sumber air memadai maka jumlah minimum sebaiknya menjadi 100 liter; (vi) infor-masi yang mudah di akses. Hak atas air sebagai hak asasi memungkinkan terse-dianya akses terhadap informasi tentang strategi dan kebijakan pemerintah, dan memungkinkan masyarakat berpartisi-pasi.
Hak Atas Air sebagai Prasyarat Hak Asasi LainnyaHak atas air menjadi prasyarat pe-
menuhan hak asasi lainnya. Sebagai ilus-trasi (i) Hak atas makanan. Konsumsi air tidak aman menghambat upaya pe-menuhan nutrisi dasar dan selanjutnya hak aatas makanan; (ii) hak atas kehi-dupan dan hak atas kesehatan. Keku-rangan air yang aman menjadi penyebab utama kematian bayi di seluruh dunia; (iii) hak atas pendidikan. Mengambil air di banyak negara merupakan tugas anak perempuan dan wanita. Padahal waktu dan jarak tempuh kadang-kadang mem-butuhkan lebih dari 2 jam perjalanan se-hingga menghalangi me reka untuk ha-dir di sekolah. Termasuk ketidakhadiran karena sakit akibat diare; (iv) hak atas perumahan. Ketersediaan air minum menjadi persyaratan sebuah rumah yang layak huni.
Kewajiban NegaraIsu yang timbul kemudian adalah
bagaimana posisi negara dalam hubung-annya dengan air sebagai benda publik atau benda sosial yang bahkan telah di-akui sebagai bagian dari hak asasi ma-
nusia. Berdasar komentar umum No-mor 15 dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa hak atas air sebagaimana hak asasi lain-nya menghasilkan tiga tipe kewajiban bagi negara yaitu kewajiban menghar-gai (to respect), kewajiban melindungi (to protect), dan kewajiban memenuhi (to fulfil).
Kewajiban menghormati: meme-lihara akses yang ada. Kewajiban ini mengharuskan negara tidak meng-ganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas air. Ke-wajiban termasuk misalnya tidak mem-batasi akses kepada siapapun.
Kewajiban melindungi: mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini mengharus-kan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apa pun keberadaan hak atas air. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusa-haan dan institusi yang dibawah ken-dali pemerintah. Kewajiban termasuk mengadopsi regulasi yang efektif.
Kewajiban memenuhi: fasilitasi, pro-mosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas air.
Bagaimana dengan pemerintah daerah? Sebenarnya penentu utama ter-capainya hak atas air sebagai hak asasi manusia berada ditangan pemerintah daerah. Komentar Umum PBB No-mor 15 menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memastikan bahwa pe-merintah daerah mempunyai kapasitas baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia untuk menyedia-
Kesalahpahaman terhadap Hak Atas Air
Air sebagai Hak Asasi tidak berarti....l..bahwa air disediakan secara gratis
kepada semua. l..bahwa setiap rumah harus
dilayani melalui sambungan langsung bahkan jika tidak layak secara finansial
l..bahwa pemerintah sendiri yang harus menyediakan layanan dan tidak boleh mendelegasikan ke pihak non pemerintah.
12
kan layanan air minum. Ditambahkan juga bahwa layanan tersebut harus me-menuhi prinsip hak asasi manusia.
Indikator Pemenuhan Hak Atas AirKecukupan air sebagai prasyarat
pemenuhan hak atas air, dalam setiap keadaan apa pun harus memenuhi fak-tor berikut (i) ketersediaan. Suplai air untuk setiap orang harus mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan in-dividu dan rumah tangganya; (ii) kuali-tas. Air untuk setiap orang atau rumah tangga harus aman, bebas dari orga-nisme mikro, unsur kimia dan radiologi yang berbahaya yang mengancam kese-hatan manusia; (iii) mudah diakses. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Kemudahan akses ditandai oleh (a) mudah diakses secara fisik. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat dijangkau secara fisik bagi selu-ruh golongan yang ada di dalam suatu populasi; (b) terjangkau secara ekono-mi. Air dan fasilitas air dan pelayanan-nya harus terjangkau untuk semuanya.
Biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dan biaya lain yang berhubungan dengan air harus terjangkau; (c) non-diskriminasi. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat diakses oleh semua, termasuk ke-lompok rentan atau marjinal, dalam hu-kum maupun keadaan nyata lapangan tanpa diskriminasi; (d) akses informasi. Akses atas air juga termasuk hak untuk mencari, menerima dan bagian dari in-formasi sehubungan dengan air.
Mewujudkan Air sebagai Hak AsasiPada kenyataannya, sejumlah faktor
dibutuhkan untuk memastikan air seba-gai hak asasi. Pertama, pemerintah ha-rus memiliki regulasi dan intitusi yang efektif, termasuk otoritas publik yang mempunyai mandat jelas yang dibekali sumber dana dan sumber daya manusia memadai. Kedua, informasi dan pen-didikan. Ini dibutuhkan untuk memas-tikan pengelolaan air yang transparan dan bertanggungjawab. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hak mereka. Tentunya sebaliknya juga
mereka harus tahu kewajibannya. Di lain pihak, otoritas publik juga harus mengetahui kewajibannya. Ketiga, dia-log multi pihak. Dialog ini melibatkan berbagai pihak mulai dari swasta, LSM, masyarakat miskin, yang dapat berkon-tribusi dalam proses perencanaan, pem-bangunan dan pengelolaan layanan air minum. Hal ini dapat menjadikan otoritas publik lebih bertanggungjawab dan transparan. Keempat, mekanisme solidaritas berbagi biaya. Sebagai con-toh, sistem tarif dapat menggunakan sistem subsidi silang, yang kaya mem-bayar lebih besar.
Sementara itu, hak atas air tidak hanya berlaku bagi perusahaan pu blik tetapi juga swasta. Sebagai ilustrasi, the International Federation of Private Water Operators AquaFed, yang me-wakili berbagai perusahaan layanan air minum dari yang kecil sampai perusa-haan internasional, telah memasukkan isu hak asasi air dalam aturan perusa-haan. Terdapat tiga elemen dibutuhkan agar operator melaksanakan konsep hak atas air yaitu (i) kontrak yang jelas yang mencakup peran dan tanggung-jawab operator; (ii) keberadaan subsidi atau tarif rendah bagi masyarakat mis-kin; (iii) keberadaan mekanisme sosial berkelanjutan terhadap layanan bagi kelompok yang terpinggirkan (miskin, tuna wisma, dan lainnya).
Laporan Utama
Praktek UnggulanBelgia. Dana sosial diperkenalkan
dan dibiayai melalui sumber iuran air. Pendapatan dari dana sosial diguna-kan oleh lembaga sosial untuk menu-tup biaya layanan bagi masyarakat termiskin. Selain itu diterapkan kon-sumsi air gratis maksimal 15 m3 per keluarga.
Porto Alegre, Brazil. Perusahaan publik penyedia air minum menerap-kan proses perencanaan anggaran partisipatif. Dalam pertemuan publik, setiap warga bebas berbicara tentang prioritas anggaran. Model ini meng-hasilkan pertambahan dramatis da-lam akses air minum bagi komunitas miskin.
Afrika Selatan. Setiap institusi layanan air minum harus mempunyai unit layanan konsumen yang akan menerima setiap keluhan. Kemente-rian Urusan Air dipersyaratkan mem-punyai sistem informasi nasional yang dapat di akses oleh masyarakat.
Pertanyaan yang Sering Mengemuka•Apakah20literperkapitaperharisudahmemadaisebagaipemenuhanhakasasi?.TIDAK.20li-
ter per kapita per hari kebutuhan paling minimum tetapi masih belum dapat mencukupi kebutu-hanterkaitaspekkesehatan.Untukitu,kebutuhanminimumyangsebaiknyadipenuhiberkisarantara 50 sampai 100 liter per kapita per hari.
•Apakahbiayauntukmencapaiterpenuhinyakebutuhanairmenjadipenghalang.?.TIDAK.Me-mangbetulbahwabiayayangdibutuhkanbesar.Namun,terbuktibahwabiayayangdikeluarkansebagaiakibattidakterpenuhinyakebutuhanairminumbahkanjauhlebihbesar,dalambentukmenurunnyakualitaskesehatanmasyarakat,kehilanganwaktuproduktifdanketidakhadirandisekolah.Selainitu,kebutuhantersebuttidakharusdipenuhidalamwaktusekejap,tetapidise-suaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah.
•Apakahsetiaporangbahkanyangtinggaldidaerahterpencildipersyaratkanmendapataksesairminummelaluisistemperpipaan?TIDAK.Pemerintahhanyaharusmemastikansetiaporangmempunyaiaksesyangmemenuhistandar(ketersediaan,akses,terjangkau,kualitas),namuntentunyasetiapdaerahmemerlukanbentuklayananyangberbedadisesuaikankebutuhanma-sing-masing.
•Apakahpemerintahharusmenyediakanlayananairminumsecaragratis?TIDAK..Hakasasima-nusiahanyamenjaminbahwaairminumharusterjangkaudantidakmenghambattercapainyahakasasilainnyasepertimakanan,rumahdankesehatan.
•Apakahhakasasimelarangketerlibatanswastadalampenyediaanlayananairminum?TIDAK.Hakasasitidakmenyebutkanbentuk tertentu layananairminum.Namun,pemerintahharusmemastikan,melaluiregulasi,pemantauan,prosedurpelaporan,bahwasemuapenyedia(pub-likdanswasta)tidakmelanggarhakasasimanusia.
•Apakahpengakuanair sebagaihakasasimendorongpemenuhankebutuhanairminum?YA.Diantarabanyakfaktorlainnya,hakasasimemantapkankerangkahukum,yangmenggambarkanhakdankewajiban,danmendorongperhatianlebihpadayangmiskin,danlayananyangtidakdiskriminatif.Hakasasiinimendorongmasyarakatmenjadiaktifterlibat.
13
Edisi III, 2010
Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAMHAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh
manusia, sesuai dengan kodratnya, yang diberikanlangsung oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan maka manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sementara secara resmi dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagaimakhlukTuhanYangMahaEsadanmerupakananugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah dan setiaporang, demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia”
Berdasarkan beberapa rumusanHAMdiatas,dapatditarikkesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu (i) HAMtidakperludiberikan,dibeliataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;(ii)HAMberlakuuntuksemua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,pandangan politik atau asal-usulsosialdanbangsa;(iii)HAMtidakbisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupunsebuahnegaramembuathukumyangtidakmelindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih,2003).
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hakdasaryangpalingfundamental,ialahhakpersamaandan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa keduahakdasar ini,hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.
Perkembangan Pemikiran HAMPerkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari
MagnaChartapadatahun1215diInggris,yangantaralain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan
hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukumyang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya danmulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum (Mansyur Effendi,1994). Lahirnya MagnaCharta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yanglebihkonkret,dengan lahirnyaBill of Rights di Inggris padatahun1689.Padamasaitumulaitimbuladagiumyang intinya adalah bahwa manusia sama di mukahukum (equality before the law). Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham
Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehinggatidaklahlogisbilasesudahlahiriaharus dibelenggu.
Selanjutnya,padatahun1789lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimanaketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak bolehada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,artinya orang-orang yangditangkap,kemudianditahandandituduh,berhakdinyatakantidakbersalah, sampai ada keputusanpengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam French Declaration sudahtercakupsemuahak,meliputihak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya. Selain itu juga dikenal Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkanpadatanggal6Januari1941.
Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifatuniversal,yangkemudiandikenaldenganThe Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.
Sekilas Hak Asasi Manusia (HAM)
ISTIMEWA
14
Regulasi
Sampai sejauh ini hak asasi manusia sudah menjadi pembicaraan yang lazim di kalangan awam. Walau-pun demikian tentunya tidak banyak yang tahu se-
cara pasti yang dimaksud. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di-lindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia-baikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
Sementara itu untuk menunjukkan penghargaan bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk men-junjung tinggi dan melaksanakan Dek1arasi Universal ten-tang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikat an Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lain-nya mengenai hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia secara sadar bahkan telah mengeluarkan Ketetapan Ma-jelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-un-dangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan ber-bagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam undang-undang ini secara gamblang hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang me lekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tu-han Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin dungi oleh nega-ra, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan
kepadanya kemampuan untuk
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan mem-bimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam men-jalani kehidupannya.
Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk
bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itu-lah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati seba-gai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kema-nusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organi-sasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan ke-hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia dicip-takan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosi-alitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan meng-hormati hak asasi orang lain.
Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. De-ngan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warganegara dan penduduknya tan-pa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manu-sia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan keduduk-an warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan ber-serikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta
dengan segala isinya;b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struk-
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
15
Edisi III, 2010
tur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidup-nya;
c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkat-kan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan per-lindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, se-hingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa-pun dan dalam keadaan apapun;
f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilin-dungi, dan ditegakkan, dan untukitu pemerintah, apara-tur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai ke-wajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan pene gakan hak asasi manusia.Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak
asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada De-klarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai Instrumen internasional lain yang mengatur me-ngenai hak asasi manusia.
Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pe-merintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.
Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang parti-sipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi ma-nusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah
merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-un-dangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelang-garan baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau ad-ministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Namun pasal yang terkait langsung dengan pemenuhan ke-butuhan rumah, air dan penyehatan lingkungan tercantum pada a. Pasal 9 yang menyatakan (1) Setiap orang berhak untuk
hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Se-tiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
b. Pasal ll yang menyatakan setiap orang berhak atas pe-menuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
c. Pasal 40 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, So-cial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya)
Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kove-nan terdiri dari pembukaan dan pasal pasal yang mencakup 31 pasal.
Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memaju-kan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat ter-capai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.
Dari 31 pasal yang terdapat dalam undang-undang ini, pasal mengatur ketersediaan air minum dan penyehat-an lingkungan mengacu pada pasal 11 yaitu hak atas standar kehidupan yang memadai. (OM)
16
Agenda
POKJA
Tanggal 17 Oktober setiap tahun masyarakat dunia memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia (The International Day for the Eradication
of Poverty). Kemiskinan bagi negara berkembang seperti Indonesia misalnya menjadi catatan tersendiri. Sulitnya penduduk dunia memperoleh layanan dasar sanitasi dan memperoleh air minum secara layak, jelas merupakan indikator dari kemiskinan. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut terbatasnya 95 persen akses penduduk miskin akan air bersih membuat belenggu kemiskinan menjerat 1,2 milliar penduduk dunia.
Seperti diketahui , pada tanggal 17 Oktober tahun 1987, lebih dari seratus ribu orang berdemonstrasi di Trocadéro di Kota Paris, Perancis, tepat di tempat penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, untuk mengajak seluruh warga dunia merenungkan kembali nasib para korban kemiskinan ekstrim, kekerasan, kelaparan, sulitnya memperoleh air minum dan buruknya sanitasi dihampir seluruh pelosok dunia.
Kemudian, demi menghormati momen bersejarah tersebut, PBB
berinisiatif untuk mengeluarkan resolusi Nomor 47/196 tertanggal 22 Desember 1992, yang menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Anti Kemiskinan Sedunia (International Day of Eradication for Poverty)- yang diperingati oleh warga dunia hingga saat ini. Pada tahun 2010 ini kampanye global yang dimobilisasi aliansi dunia bernama Global Call Against to Poverty (GCAP) terus dilakukan.
Pada September tahun 2000, perwakilan dari 189 negara di dunia telah berkumpul di New York dalam acara KTT Millenium yang digagas PBB. Hasilnya adalah ditandatanganinya sebuah deklarasi (Millenium Declaration) yang berisi 8 poin proyek bersama sasaran pembangunan yang harus dicapai negara-negara peserta sebelum tahun 2015. Ke delapan proyek itu meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim (dengan standar penghasilan di bawah 1,25 USD/hari), pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap penyakit khususnya HIV AIDS dan malaria, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, penjaminan daya dukung lingkungan dan membangun kemitraan
Hari Anti Kemiskinan Internasional
Sulitnya Akses Air Minum dan SanitasiIndikator Kemiskinan
17
Edisi III, 2010
global untuk pembangunan. Jika dicermati, semua proyek itu bermuara pada satu target, yakni eliminasi problem besar bernama “kemiskinan”.
Berbicara tentang cara pemberantasan kemiskinan versi PBB, tentu tak bisa lepas juga dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Millenium/Millenium Development Goal’s disingkat MDG’s – yang juga merupakan produk PBB pada tahun 2000 demi menciptakan dunia tanpa kemiskinan pada tahun 2015. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia sendiri ikut menerapkan program MDG’s sejak tahun 2004. Di dalam MDG’s sendiri, kita tahu, ada sekitar delapan program yang muluk-muluk di bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kesetaraan gender.
“Namun,terus terang, kami sangat meragukan keberhasilan program MDG’s di Indonesia. Karena praktis, kemiskinan -dan proses pemiskinan- tidak berkurang sama sekali. Kita masih mendengar terjadinya wabah kelaparan di berbagai tempat di tanah air, yang artinya masih terdapat kemiskinan ekstrim. Kesehatan rakyat juga semakin buruk saja. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih cukup tinggi, sejumlah besar masyarakat masih sulit memperoleh layanan air minum dan sanitasi mereka masih sangat buruk,” ujar Ketua Yayasan Perlundungan Konsumen Kesehatan, dr Marius Wijayarta kepada Percik.
Pendidikan, kesehatan, sulitnya memperoleh air minum dan rendahnya sanitasi dasar jelas bagian dari kemiskinan. Belum lagi masalah kesetaraan gender pun seperti masih mimpi, karena praktik penjualan anak dan perempuan masih marak di mana-mana. Target di bidang lingkungan hidup pun tidak terlihat karena setiap harinya kita terus disuguhkan fakta tentang dampak kerusakan lingkungan di sekitar kita, seperti banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi fakta yang membuat kita ragu akan bukti keberhasilan MDG’s.
Para aktivis kemanusian, pegiat lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kekerasan terhadap hak asasi manusia, sehingga mereka menuntut agar masyarakat di seluruh dunia menghormati
hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, serta masyarakat dunia merayakan ‘Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia’ dengan berbagai acara.
Di Indonesia Aksi memperingati Hari anti-pemiskinan juga
terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti Lampung, Mataram, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Purwekerto. Di Bandar lampung, sekitar 50-an massa SRMI berjalan dari tugu adipura menuju kantor Pemerintah Kota setempat. Mereka mendesak agar walikota yang baru terpilih untuk merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye, terutama dalam pemberantasan kemiskinan.
Atas desakan tersebut, walikota Bandar Lampung Herman HN bersedia menerima dan berdialog dengan
perwakilan aktivis SRMI. Pihak Walikota menjanjikan akan menuntaskan sejumlah persoalan yang dituntut SRMI, diantaranya, persoalan pendidikan, kesehatan, dan dokumen warga (KTP/KK/akta kelahiran), akan diwujudkan pada tahun 2011.
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, puluhan aktivis SRMI menggelar aksinya di kantor pemerintah kabupaten, dan
menuntut pengesahan Ranperda mengenai perlindungan Pedagang Kaki Lima (PKL). Massa juga mempersoalkan minimnya anggaran kesehatan, yang sebagian besarnya merupakan bantuan Pemprov Jabar.
Aksi juga dilakukan di kabupaten Garut, Jawa Barat, dimana puluhan demonstran menolak pembangunan Alfamart yang dianggap akan menyingkirkan ekonomi rakyat, khususnya pedagang kecil. Di Cianjur, Jawa Barat, massa yang berjumlah 300 orang anggota SRMI mendatangi kantor DPRD setempat. Massa mempersoalkan minimnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, sementara biaya untuk kendaraan dinas Pemda terus membengkak.
Disamping itu, ratusan massa itu juga mendesak agar Pemkab Cianjur segera menaikkan jumlah anggaran untuk pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. (Eko/Infid.org)
ISTIMEWA
ISTIMEWA
(Tulisan Pertama)
Wacana
Dr Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.
T he International Covenant on Economical and Social Rights (untuk selanjutnya disingkat CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (The International
Bill of Rights) dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan,
rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” dapat tercukupi (adequately)
dan tersedia (available) bagi setiap orang. Selaras dengan tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen HAM Internasional untuk memberikan perlindungan baik kepada individu atau kelompok tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR 1966. CESCR secara garis besar memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya, dan seterusnya. Hak atas penghidupan yang layak yang akan ditelaah dalam tulisan ini akan difokuskan pada hak atas rumah dan air minum. Dibandingkan dengan hak sipil dan politik termuat dalam CCPR, seringkali hak ekonomi, sosial dan budaya dipandang sebagai hak generasi kedua dimana pemenuhannya tidak dapat dipaksakan (unforceable),
18
Edisi III, 2010
tidak dapat dituntut di muka pengadilan (non-justiciable), dan hanya dapat dipenuhi oleh negara secara bertahap (to be fulfilled progresively). Namun demikian, seiring dengan diakuinya sistem Hukum HAM secara global yang ditandai dengan penerimaan DUHAM 1948, maka negara-negara di dunia secara berulang-ulang menegaskan melalui Konferensi Dunia tentang HAM Tahun 1993 dengan menyatakan bahwa kedua bidang HAM yaitu CCPR dan CESCR tersebut memiliki kedudukan yang sama penting. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 32/130 pada Desember 1977 menyatakan bahwa:
“(a) All human rights and fundamental freedoms are invisilbe and interdependent; equal attention and urgent consideration should be given to the implementation, promotion, and protection of both civil and political, and economical, social and cultural rights; (b) The full realization of civil and political rights without the enjoyment of economic, social and cultural rights is impossible; the achievement of lasting progress in the implementation of human rights is dependent upon sound and effective national and international policies of economic and social development, as recognized by the Proclamation of Teheran of 1968”.
Pada Tahun 2002 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the Committee on Economic, Social and Cultural Rights) dalam Pandangan Umum (General Comment) Nomor 15, secara tegas memberikan penafsiran tentang pasal 11 dan pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), bahwa hak atas air adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam argumentasinya, Komite ini menunjukkan bahwa banyak hak asasi manusia lainnya tidak dapat didapatkan oleh manusia jika sebelumnya tidak dikenal adanya hak atas air. Hak Hidup (the right to life), hak untuk mendapatkan makanan (the right to food), hak untuk mempertahankan kesehatan (the right to maintain health level) adalah hak-hak yang dalam upaya untuk memenuhinya membutuhkan hak atas air (the right to water) – sebagai prasyaratnya.
Disebutkan bahwa air tidak saja dibutuhkan untuk minum tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari proses pengolahan makanan, atau penciptaan kondisi perumahan yang sehat dan kebutuhan manusia lainnya
akan kehidupan. Lebih jauh bahkan ditegaskan bahwa komite tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin adanya hak atas air bagi setiap warga negaranya.
Dengan demikian, jelas bahwa baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki sifat saling ketergantungan dan keduanya memerlukan perhatian yang sama dari negara baik dalam hal penerapannya, sosialisasinya maupun perlindungannya. Hal ini mengingat bahwa pemenuhan hak sipil dan politik saja tanpa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seseorang sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya dibutuhkan dukungan baik dari kebijakan nasional atau internasional.
Dengan demikian, segala bentuk penyangkalan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang didukung oleh pendapat yang masih menempatkan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak yang tidak nyata, hak yang tidak membutuhkan keterlibatan negara, atau hak yang dapat dipenuhi secara bertahap, hanyalah sebagai pandangan yang tidak relevan lagi. Terlebih ketika CESCR telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200 A (XXI) pada Desember 1966 dan telah dilaksanakan sejak 3 Januari 1976. Bahkan saat ini karena jumlah penerimaan CESCR oleh negara-negara sudah sangat besar yaitu 143 negara meratifikasi, maka CESCR sudah mengalami perubahan karakter yang semula hanya
merupakan perjanjian multirateral berubah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law), artinya ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi.
II. Menilai Jaminan Hak Atas Rumah dan Air Dalam Hukum PositifDalam membahas persoalan tentang jaminan hukum
hak rakyat atas rumah dan air perlu kiranya melihat sejauh mana hukum di Indonesia memberikan jaminan yang cukup atas hak tersebut. Dalam melihat aspek jaminan hukum, tentunya tidak sebatas pada bagaimana kualitas substansi hukum yang mengatur persoalan ini dalam setiap Hukum Nasional, namun juga harus memperhatikan sejuah mana ketaatan Indonesia sebagai bagian dari
19
Edisi II, 2010
......bahwa hak atas air
adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari
hak-hak asasi manusia lainnya.
20
masyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif negara kita. Hal ini perlu ditegaskan mengingat masih banyak pandangan dan praktek yang mengatakan bahwa Hukum Nasional dan Hukum Internasional terpisah satu sama lainnya. Sehingga pembuat UU, penegak hukum atau bahkan pembuat kebijakan sering kali menanggalkan sifat mengikat dari Hukum Internasional yang dimaksud dan tindakan ini sering berimplikasi pada terampasnya hak-hak rakyat yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang-kurangi oleh siapapun tak terkecuali oleh negara kecuali dalam hal-hal tertentu yang itupun harus diatur secara jelas dan tegas melalui UU.
Terkait dengan obyek pembahasan dalam tulisan ini yaitu tentang jaminan hak rakyat atas kehidupan yang layak khususnya rumah dan air minum, maka implikasi yuridis dari penerimaan Indonesia terhadap suatu Perjanjian Internasional adalah sesegera mungkin melakukan pembentukan UU baru jika belum punya, singkronisasi/perubahan jika terjadi pertentangan atau bahkan pencabutan apabila memang peraturan tersebut dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan hak-hak rakyat. Dalam kaitannya dengan hak rakyat atas penghidupan yang layak, dimana hal ini masuk dalam ruang lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Indonesia secara resmi menjadi peserta dari The Internasional International Convenant on Economical, Social and Cultural Rights (CESCR) 1966 melalui sebuah
ratifikasi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan demikian, sejak tahun 2005 ada kewajiban hukum yang diemban oleh negara Indonesia untuk segera menyesuaikan diri terhadap setiap produk perUUan yang terkait dengan isi kovenan tersebut. Hal ini tentunya dengan maksud dan tujuan agar jaminan pemenuhan hak rakyat atas hak ekonomi, sosial dan budaya semakin kuat.
Lalu dalam konteks jaminan hak rakyat atas penghidupan yang layak khususnya rumah dan air, bagaimana CESCR membebani negara peserta untuk segera mengambil langkah-langkah tindakan penting guna mengakui hak tersebut? Dalam hal ini Pasal 11 Ayat (1) CESCR menyatakan bahwa:
The States Parties of the present Covenant recognize the right of everyone to an adaquate standard of living
for himlself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continous improvement of living conditions. The State Parties will take appropiate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect essential importannce of international co-operation based on free consent.
Artinya: negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, pakaian, perumahan yang layak dan atas perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan perwjuduan hak ini, dengan mengakui, untuk maksud ini, sangat pentingnya
arti kerjasama internasional yang didasarkan pada perbaikan yang sukarela.
Implikasi dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR di atas adalah bahwa bagi setiap negara yang menjadi peserta atau meratifikasi kovenant ini (termasuk Indonesia), memiliki kewajiban untuk mengakui hak setiap warga negara atas standar hidup yang layak yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan perumahan serta senantiasa meningkatkan perbaikan kondisi penghidupan secara terus-menerus. Bahwa kata “recognize” atau mengakui atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan standar hidup yang layak baik kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan tersebut memiliki makna membebani kewajiban kepada negara yaitu “the obligation to respect” (kewajiban negara untuk menghormati), “the obligation to protect” (kewajiban untuk melindungi), “the obligation to promote (kewajiban
Wacana
ISTIMEWA
21
Edisi III, 2010
untuk mensosialisasikan), “the obligation to fullfill” (kewajiban untuk memenuhi) hak-hak yang terkandung dalam kovenant CESCR melalui langkah-langkah yang nyata sesuai dengan prinsip-prinsip Limburg 1986 dan Prinsip-prinsip Maastricht 1997, termasuk tindakan-tindakan legislatif untuk menyesuaikan atau merubah segala peraturan PerUUan di Indonesia baik di tingkat pusat sampai daerah yang dinilai bertentangan dengan isi kovenan.
1. Peluang Regulasi Pelaksana Yang Mengabaikan Rakyat Atas RumahPertama, tidak dapat dipungkiri bahwa keberanian
Indonesia meratifikasi CESCR adalah salah satu bentuk Indonesia memberikan pengakuan hak atas ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya yang di dalamnya terdapat hak atas rumah dan air minum. Namun demikian, dengan ratifikasi saja tidaklah cukup. Untuk melihat sejuah mana Indonesia sebagai negara peserta CESCR telah memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya yang menyangkut hak atas rumah dan air minum setiap warga negaranya adalah dengan melihat segala bentuk PerUUan baik dalam hirarki tertinggi (UUD 1945) sampai herarki terendah atau PerUUan di tingkat pusat dan daerahsubstansinya telah diselaraskan atau disesuaikan dengan substansi CESCR atau secara lebih ekstrim dilakukan langkah-langkah kongkrit dimana ketentuan perUUan yang sudah tidak sesuai atau isinya bertentang dengan substansi CESCR segera dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.
Jika kita menelaah substansi UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, setelah mengalami empat kali perubahan, khususnya pada Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, terdapat beberapa Pasal terkait HAM yang mengalami perubahan dan penambahan. UUD 1945 dinilai lebih rinci dalam mengatur dan menjamin perlindungan HAM dibanding Pasal 28 sebelum perubahan. Tentunya hal ini patut diapresiasi. Namun sudahkah ketentuan Pasal 28 yang dinilai lebih rinci tersebut telah selaras dengan isi CESCR yang baru diratifikasi Indonesia tahun 2005, tentunya perlu ditelaah lebih lanjut.
Terkiat dengan hak atas rumah, UUD 1945 khususnya Pasal 28H Ayat (1) dikatakan bahwa :”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bahwa penggunaan istilah “pengakuan hak atas penghidupan yang layak” pada Pasal 11 Ayat (1) CESCR mengandung makna kehidupan yang layak meliputi kecukupan makanan, pakaian dan rumah, sedangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) sedikit berbeda dengan yang
dipakai dalam Pasal 28H yang memilih menggunakan istilah lain yaitu ”hak hidup sejahtera lahir dan batin”.
Dalam kalimat berikutnya yang dimaksud dengan hidup sejahtera lahir dan batin hanya meliputi ”hak bertempat tinggal” dan ”hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat”. Dalam hemat Penulis, “hak bertempat tinggal” berkonotasi lebih luas dibanding “hak atas perumahan”, dimana seseorang dapat saja memiliki tempat tinggal meskipun
dia tidak memiliki rumah. Sedangkan seseorang yang memiliki rumah secara otomatis memiliki tempat tinggal. Dalam kondisi sosial masyarakat yang komunal seperti di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hampir setiap orang memiliki tempat tinggal meskipun tidak setiap orang yang memiliki tempat tinggal memiliki rumah, sebab mereka dapat tinggal bersama dengan keluarga, anak atau orang tua.
Sedangkan hak lain sebagai wujud kehidupan sejahtera adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Di dalam UUD 1945, hak untuk mendapatkan
Tidak dapat dipungkuri bahwa keberanian
Indonesia meratifikasi CESCR adalah salah
satu upaya Indonesia memberikan pengakuan hak atas ekonomi, sosial
dan budaya warga negaranya..
ISTIMEWA
22
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak secara langsung memiliki makna pada hak untuk mendapatkan kecukupan makanan. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikehendaki dalam CESCR yang secara tegas memberikan pengakuan dan membebani setiap negara peserta untuk menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan kecukupan makanan.
Dengan demikian, Indonesia sebagai negaranya yang meratifikasi CESCR belum berhasil menjamin dalam konstitusinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang didalamnya meliputi hak untuk mendapatkan pakaian yang cukup, makanan yang cukup (termasuk air minum) dan rumah yang memadai. Konsep yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28H tersebut di atas hanya mengulang ketentuan yang ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memang lebih dulu dibuat (satu tahun sebelum amandemen Pasal 28 dilakukan). Dalam Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa:(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai,
bahagia sejahtera, lahir dan batin(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat.Jika yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan
taraf hidup” dimaknai sama dengan ”hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak” sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR, maka hak untuk meningkatkan taraf hidup ini harus diterjemahkan sebagai hak untuk mendapatkan makanan yang cukup, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, setelah ditelusuri pada Bagian Penjelasan dari UU ini, tidak ada satupun penjelasan yang memberikan definisi lebih lanjut yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan taraf hidup”. Dengan demikian, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai UU HAM di Indonesia yang diharapkan menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 justru memberikan pengaturan yang sangat lemah atas hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, atau tidak ada jaminan yang secara eksplisit
atas pengakuan terhadap ”hak untuk
mendapatkan kecukupan makanan, pakaian dan perumahan”.
Sesungguhnya Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) UU HAM lebih diarahkan pada pengakuan ”hak hidup” sebagai bagian dari hak sipil dan politik dan bukan pada konteks pengakuan hak ekonomi sosial dan budaya. Dengan kata lain, penghormatan negara terhadap hak setiap orang atas penghidupan yang layak yang didalamnya mencakup hak atas rumah, baik UUD 1945 maupun UU HAM masih belum selaras dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR. Sementara keberadaan peraturan pelaksana di bawahnya semakin berpotensi lahirnya ketentuan yang melanggar hak atas rumah namun tidak pernah dicabut atau masih terus berlaku hingga sekarang.
2. Upaya Negara Melepaskan Tanggungjawab Pemenuhan Hak Atas AirTerkait dengan hak atas air, Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” yang berdasarkan pada konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, termasuk pula pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan,
Wacana
POKJA
23
Edisi III, 2010
pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut penguasaan negara atas air sebagai bagian dari kebutuhan yang paling mendasar dan hak asasi manusia semakin dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal di pasal Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa ”perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Permasalahannya tidak dijelaskan secara lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai kemakmuran rakyat, sehingga dimensi inilah yang didalam prkatek sering diterjemahkan terlalu luas atau terlalu sempit oleh pembuat kebijakan, sehingga rentan menimbulkan konflik.
Hal lain yang sangat mendasar adalah masalah penyelenggaraan penyediaan kebutuhan air bagi masyarakat oleh swasta yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Sebagai sebuah layanan publik yang sangat mendasar penyediaan air bagi masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Jika penyediaan sumberdaya air diserahkan kepada swasta
(privatisasi), maka penguasaan negara terhadap air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat akan hilang. Secara teoritis, ada banyak definisi tentang privatisasi.
Definisi privatisasi menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 angka 12 adalah penjualan saham persero, baik sebagian mau pun seluruhnya, kepada pihak lain dalam
rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi menurut peraturan perundangan ini hanya merupakan salah satu bentuk privatisasi menurut banyak ahli. Sebagai contohnya Diana Carney dan John Farrington (1998) menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secara luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektor privat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanya sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti contracting out dan internal markets). Dengan definisi seperti ini memang yang dimaksud dengan privatisasi tidak semata-mata diartikan sebagai penjualan saham. Privatisasi juga mencakup model dimana kepemilikan tetap di tangan pemerintah/negara tetapi pengelolaan, pemeliharaan dan
investasi dilakukan oleh pihak swasta (dengan model (BOT, management contract, konsesi dan sebagainya).
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, penyeleng-garaan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belum ada BUMN/BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya.(bersambung...)
Penulis: Direktur Pusat Studi HAM (satuHAM) Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. email: [email protected]
. . . penyediaan air bagi masyarakat harus
menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara,
sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
Tidak ada yang meragukan ataupun membantah bahwa air me-rupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manu-sia yang fundamental. Pengakuan air sebagai hak asasi manu-sia secara tegas tertuang dalam pasal 14 The Convention on the
Elimination all of Forms Discrimination Against Women-CEDAW 1979), yang menyatakan bahwa perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air sebagai hak perempuan, demikian juga dalam pasal 24 The
Convention on The Right of The Child-CRC 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka set-iap anak memiliki hak atas air minum yang bersih.
Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum No.15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dengan air sebagai hak asasi manusia, menjadikan penyediaan layanan air dikategorikan sebagai es-sential services. Essential services merupakan pusat dari kontrak
sosial antara pemerintah dan masyarakat.Dengan kata lain jaminan terhadap hak atas air bagi
masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak atas air secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dimana negara
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan
produktif. Pada sisi yang lain, seiring dengan meningkatnya konsumsi air, variasi musim, kerusakan lingkungan dan pencemaran me-
nyebabkan air menjadi langka baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 meter ku-bik per tahun per kapita. Namun ketersediaan terse-but tidak merata di setiap
pulau. Sebagai contoh pulau Jawa ketersediaan air per kapita per
tahun hanya 1750 m3, masih di bawah standar kecukupan yang sebesar 2000 m3 per kapita per tahun dan kon-
disi ini diperkirakan akan semakin parah di tahun 2020 dimana keterse-
diaan hanya 1200 per kapita per tahun2.
Kondisi ini juga semakin diper-parah dengan rusaknya daerah aliran sungai (DAS), yang dari mening kat dari tahun ke tahun. Kelangkaan air ini kemudian diperparah dengan ke-tersediaan infrastruktur air yang bu-ruk.
Selama lebih dari 30 tahun pem-bangunan infrastruktur sumberdaya air yang berfokus pada pembangunan jaringan irigasi, tidak serta merta men-jadikan kondisi jaringan irigasi lebih baik. Sampai dengan tahun 2002 ja-ringan irigasi yang sebagian besar be-rada di Jawa (48,32%) dan Sumatra (27,13%), 22,4% diantaranya menga-lami kerusakan. Dengan alokasi ang-garan yang terfokus pada pembangun-an irigasi, pada akhirnya juga mem-perkecil anggaran untuk infrastruktur air lainnya termasuk air bersih dan sanitasi. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai total asset infrastruktur air yang sampai akhir tahun 2002 adalah sebe-sar Rp 346,49 triliun yang terdiri Rp 273,46 triliun (78,92%) untuk iriga-si, Rp 63,48 triliun (18,32%) untuk bendungan, bendung karet, dan em-bung, Rp 9,21 triliun (2,66%) untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan Rp 0,34 triliun (0,1%) un-tuk air baku.
Privatisasi sebagai solusi sampai awal dekade 90-an terus menjadi perdebatan. Model perencanaan yang sentralistik dan kepemilikan badan usaha sebagai bagian dari upaya aku-mulasi modal dan mendorong in-vestasi masih mendominasi kebijakan ekonomi di negara-negara berkem-bang. Kepercayaan terhadap inter-vensi negara dalam pembangunan ekonomi mulai menurun pada akhir 70-an akibat ekonomi negara-negara berkembang menderita akibat kejut-an-kejutan eksternal antara lain me-lonjaknya harga minyak, menurunnya harga komoditas ekspor sedangkan harga barang impor meningkat.
Dampaknya adalah krisis utang luar negeri di berbagai negara berkem-bang dan terjadinya defisit anggaran. Karena negara mendominasi aktifitas ekonomi di negara-negara berkem-bang tersebut, perhatian pun tertuju kepada kinerja dari berbagai sektor publik (khususnya badan usaha mi-lik negara) dalam rangka mengatasi kemerosotan ekonomi. Krisis juga mengakibatkan negara-negara terse-but menjadi sangat bergantung pada du-kungan keuangan dari donor dan kreditor internasional yang ke-mudian juga mening-kat pengaruhnya da-lam penyusunan kebi-jakan (Bayliss 2006). Berbagai hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk memper-tanyakan dominasi negara dalam aktifitas
ekonomi dan juga mempertanyakan kepemilikan pemerintah.
Padahal sejumlah badan usaha, sektor publik dikelola dengan bu-ruk, beroperasi tidak efisien sehing-ga mengakibatkan defisit anggaran (budget deficits), dimana pelayanan yang diberikan tidak handal (unreli-able) dan menyebabkan orang miskin tersisihkan (Kessler 2004). Dalam konteks inilah kemudian privatisasi dipandang sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang. Kebijakan pri-
vatisasi yang dimulai di Inggris dan AS kemudian diterapkan di banyak negara dan didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, ter-masuk Bank Dunia melalui Structural Adjustment Program (SAP).
Upaya untuk melakukan privatisa-si juga dilakukan di sektor sumberda-ya air. Dalam konferensi air dan ling-kungan internasional yang diselengga-rakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, melahirkan The Dublin Statement on Water and Sustainable Development (yang lebih dikenal de ngan Dublin Principles). Dublin Principles berisi
empat prinsip yang ha-rus dikedepankan dalam kebijakan dan pem ba-ngunan di sektor sum-berdaya air. Salah satu dari prinsip tersebut adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an eco-nomic good”.
Lahirnya the Dublin Principles, menyebabkan banyak lembaga-lembaga
internasional mereposisi kebijakan mereka di sektor sumberdaya termasuk Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dalam mengembangkan dan mem-promosikan pendekatan-pendekatan baru yang konsisten dengan Dublin Principles terutama memberlakukan air sebagai barang ekonomi. Dalam prakteknya lembaga keuangan in-ternasional menempatkan reformasi sumberdaya air yang memberlakukan air sebagai barang ekonomi dalam satu paket kebijakan neo liberal yang lebih luas dan kebanyakan melalui structural adjustment program.
Selain itu agen pembangun-an bilateral (se perti DFID dan USAID) juga mendorong private sec-
Negara Harus Menjamin Hak Rakyat Atas Air
water has an economic value
in all its competing uses
and should be recognized
as an economic good
24
Wacana
25
Edisi III, 2010
Tidak ada yang meragukan ataupun membantah bahwa air me-rupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manu-sia yang fundamental. Pengakuan air sebagai hak asasi manu-sia secara tegas tertuang dalam pasal 14 The Convention on the
Elimination all of Forms Discrimination Against Women-CEDAW 1979), yang menyatakan bahwa perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air sebagai hak perempuan, demikian juga dalam pasal 24 The
Convention on The Right of The Child-CRC 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka set-iap anak memiliki hak atas air minum yang bersih.
Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum No.15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dengan air sebagai hak asasi manusia, menjadikan penyediaan layanan air dikategorikan sebagai es-sential services. Essential services merupakan pusat dari kontrak
sosial antara pemerintah dan masyarakat.Dengan kata lain jaminan terhadap hak atas air bagi
masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak atas air secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dimana negara
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan
produktif. Pada sisi yang lain, seiring dengan meningkatnya konsumsi air, variasi musim, kerusakan lingkungan dan pencemaran me-
nyebabkan air menjadi langka baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 meter ku-bik per tahun per kapita. Namun ketersediaan terse-but tidak merata di setiap
pulau. Sebagai contoh pulau Jawa ketersediaan air per kapita per
tahun hanya 1750 m3, masih di bawah standar kecukupan yang sebesar 2000 m3 per kapita per tahun dan kon-
disi ini diperkirakan akan semakin parah di tahun 2020 dimana keterse-
diaan hanya 1200 per kapita per tahun2.
Kondisi ini juga semakin diper-parah dengan rusaknya daerah aliran sungai (DAS), yang dari mening kat dari tahun ke tahun. Kelangkaan air ini kemudian diperparah dengan ke-tersediaan infrastruktur air yang bu-ruk.
Selama lebih dari 30 tahun pem-bangunan infrastruktur sumberdaya air yang berfokus pada pembangunan jaringan irigasi, tidak serta merta men-jadikan kondisi jaringan irigasi lebih baik. Sampai dengan tahun 2002 ja-ringan irigasi yang sebagian besar be-rada di Jawa (48,32%) dan Sumatra (27,13%), 22,4% diantaranya menga-lami kerusakan. Dengan alokasi ang-garan yang terfokus pada pembangun-an irigasi, pada akhirnya juga mem-perkecil anggaran untuk infrastruktur air lainnya termasuk air bersih dan sanitasi. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai total asset infrastruktur air yang sampai akhir tahun 2002 adalah sebe-sar Rp 346,49 triliun yang terdiri Rp 273,46 triliun (78,92%) untuk iriga-si, Rp 63,48 triliun (18,32%) untuk bendungan, bendung karet, dan em-bung, Rp 9,21 triliun (2,66%) untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan Rp 0,34 triliun (0,1%) un-tuk air baku.
Privatisasi sebagai solusi sampai awal dekade 90-an terus menjadi perdebatan. Model perencanaan yang sentralistik dan kepemilikan badan usaha sebagai bagian dari upaya aku-mulasi modal dan mendorong in-vestasi masih mendominasi kebijakan ekonomi di negara-negara berkem-bang. Kepercayaan terhadap inter-vensi negara dalam pembangunan ekonomi mulai menurun pada akhir 70-an akibat ekonomi negara-negara berkembang menderita akibat kejut-an-kejutan eksternal antara lain me-lonjaknya harga minyak, menurunnya harga komoditas ekspor sedangkan harga barang impor meningkat.
Dampaknya adalah krisis utang luar negeri di berbagai negara berkem-bang dan terjadinya defisit anggaran. Karena negara mendominasi aktifitas ekonomi di negara-negara berkem-bang tersebut, perhatian pun tertuju kepada kinerja dari berbagai sektor publik (khususnya badan usaha mi-lik negara) dalam rangka mengatasi kemerosotan ekonomi. Krisis juga mengakibatkan negara-negara terse-but menjadi sangat bergantung pada du-kungan keuangan dari donor dan kreditor internasional yang ke-mudian juga mening-kat pengaruhnya da-lam penyusunan kebi-jakan (Bayliss 2006). Berbagai hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk memper-tanyakan dominasi negara dalam aktifitas
ekonomi dan juga mempertanyakan kepemilikan pemerintah.
Padahal sejumlah badan usaha, sektor publik dikelola dengan bu-ruk, beroperasi tidak efisien sehing-ga mengakibatkan defisit anggaran (budget deficits), dimana pelayanan yang diberikan tidak handal (unreli-able) dan menyebabkan orang miskin tersisihkan (Kessler 2004). Dalam konteks inilah kemudian privatisasi dipandang sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang. Kebijakan pri-
vatisasi yang dimulai di Inggris dan AS kemudian diterapkan di banyak negara dan didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, ter-masuk Bank Dunia melalui Structural Adjustment Program (SAP).
Upaya untuk melakukan privatisa-si juga dilakukan di sektor sumberda-ya air. Dalam konferensi air dan ling-kungan internasional yang diselengga-rakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, melahirkan The Dublin Statement on Water and Sustainable Development (yang lebih dikenal de ngan Dublin Principles). Dublin Principles berisi
empat prinsip yang ha-rus dikedepankan dalam kebijakan dan pem ba-ngunan di sektor sum-berdaya air. Salah satu dari prinsip tersebut adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an eco-nomic good”.
Lahirnya the Dublin Principles, menyebabkan banyak lembaga-lembaga
internasional mereposisi kebijakan mereka di sektor sumberdaya termasuk Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dalam mengembangkan dan mem-promosikan pendekatan-pendekatan baru yang konsisten dengan Dublin Principles terutama memberlakukan air sebagai barang ekonomi. Dalam prakteknya lembaga keuangan in-ternasional menempatkan reformasi sumberdaya air yang memberlakukan air sebagai barang ekonomi dalam satu paket kebijakan neo liberal yang lebih luas dan kebanyakan melalui structural adjustment program.
Selain itu agen pembangun-an bilateral (se perti DFID dan USAID) juga mendorong private sec-
Negara Harus Menjamin Hak Rakyat Atas Air
water has an economic value
in all its competing uses
and should be recognized
as an economic good
24
Wacana
ISTIMEWA
26
tor participation kepada negara-negara pe ne rima bantuan me reka. Da-lam konteks Indonesia, tekanan glo bal untuk melakukan privatisasi ter masuk di sektor sum-berdaya air, semakin mendapat legitimasi dengan kondisi penyediaan layanan air di Indonesia. Dari 41% total pen-duduk Indonesia yang tinggal di daer-ah perkotaan, hanya 51,7% atau 20 % dari total populasi yang memiliki akses terhadap layanan PDAM, dan hanya 8 % masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan memiliki akses ter-hadap air perpipaan yang disediakan oleh Unit Pengelola Sarana (UPS).
Bahkan sampai dengan tahun 2005 hanya 21 PDAM yang bera-da dalam kondisi sehat, 68 PDAM kurang sehat, 117 PDAM tidak sehat, dan 11 PDAM dalam kondisi kritis.
Pada tahun 1993 World Bank menge luarkan kebijakan di sektor sumberdaya air (Water Resources Ma-nagement Policy), dan menurut World Bank kebijakan ini merefleksikan Rio Earth Summit 1992 dan Dublin Prin-ciples. Pada tahun 1998 Bank Dunia melakukan evaluasi terhadap kebi-jakan mereka di sektor sumberdaya air yang dituangkan dalam dokumen yang berjudul “Bridging Troubled Wa-ter: Assessing the World Bank’s Water Resources Strategy” yang dipulikasika tahun 2002. Sebagai respon dari lapo-ran evaluasi tersebut pada tahun 2003 Bank Dunia membuat strategi baru di sektor sumberdaya air (Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement).
Buruknya kualitas layanan, dan keterbatasan anggaran untuk menca-pai target MDGs menjadikan peliba-tan sektor swasta (privatisasi) sebagai
bagian yang tidak ter-pisahkan
dalam kebijakan pe-nyediaan air bersih saat ini. Paling tidak ada dua alasan de ngan pe libatan sektor swasta dalam penyedia an air bersih, pertama ada-lah peningkatan kua-litas layanan dan yang kedua adanya investasi untuk menutupi ke-terbatasan anggaran
yang dimiliki oleh pemerintah. Di-lihat dari sejarahnya pelibatan sektor swasta dalam penyediaan air minum bisa dibedakan atas dua model yaitu model privatisasi Inggris dan model privatisasi Perancis.
Model Inggris merupakan model dimana sektor privat menguasai penuh penyediaan air bersih dan sanitasi. Se-dangkan model Perancis merupakan model dimana kepemilikan aset tetap berada pada publik sedangkan tan-
gung jawab penyediaan layanan ber-ada di tangan swasta. Model Pe rancis inilah kemudian yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional se perti Bank Dunia dan ADB dan banyak diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia de ngan istilah Private Sector Participation (PSP). Beberapa bentuk partisipasi sektor swasta dalam penyediaan air bersih dan sanitasi antara lain adalah service contract, management contract, conces-sion dan sebagainya.
Kebijakan Peme rintah Dalam Penyediaan Layanan Air Bersih
Dengan berbagai persoalan yang di-hadapi dalam penyediaan layanan air, kebijakan yang diambil oleh peme-rintah Indonesia saat ini memang dia rahkan untuk melibatkan sektor swasta ataupun mendorong masuknya sektor swasta dalam penyediaan layan-an air. Beberapa kebijakan tersebut
Tahun 2005 hanya 21 PDAM yang berada
dalam kondisi sehat, 68 PDAM kurang
sehat, 117 PDAM tidak sehat, dan 11 PDAM
dalam kondisi kritis.
Wacana
POKJA
27
Edisi III, 2010
antara lain adalah private sector parti-cipation (PSP), korporatisasi PDAM, regio nalisasi PDAM. Private Sector Participation (PSP) Seperti diuraikan di atas, menjadi bagian yang tidak ter-pisahkan dalam kebijakan penyediaan air bersih saat ini. Kebijakan ini secara tegas tertuang dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, PP No.16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Peraturan Menteri PU No.294/PRT/M2005 tentang Badan Pendu-kung Sistem Penyediaan Air Minum. Kebijakan PSP juga tertuang dalam Urban Water Supply Policy Framework yang disusun oleh Bank Dunia be-kerjasama dengan BAPPENAS tahun 1997. Salah satu alasan yang men-dasari munculnya kebijakan PSP ini adalah kebutuhan investasi yang besar dalam upaya meningkatkan pelayan-an PDAM. Kebutuhan investasi yang besar tersebut juga tidak terlepas dari buruknya kinerja keuangan PDAM yang disinyalir akibat tarif rata-rata yang dibawah biaya produksi. Ber-dasarkan kondisi yang ada, kebutuhan atas sumber-sumber pembi-ayaan alternatif sangat diperlukan.
Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai sumber pembiayaan tersebut adalah (1) Penghapusan hutang PDAM, hutang PDAM sampai dengan tahun 2009 masih triliunan rupiah. (2) Enterprise fund, dalam konteks penyediaan air bersih, ada dua sumber pembiayaan utama yaitu dari pemerintah dan user fee. Enterprise fund merupakan dana yang berasal dari user fee. Dengan demikian dana yang berasal dari user fee harus digunakan sepenuhnya untuk ke-pentingan PDAM. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata
kelola layanan. Upaya ini harus diawali dengan
perubahan cara pandang dimana pe-nyediaan air bersih harus dipahami se-bagai bagian dari kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Se-hingga ada kewajiban hukum peme-rintah untuk menyediakan dan me-menuhi kebutuhan air masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan ka-rena asumsi-asumsi yang digunakan oleh pemerintah untuk melibatkan
sektor swasta dalam penyediaan layanan air tidak semuanya benar. Bahwa sebagian besar tarif PDAM berada di bawah biaya produksi dan kenyataan bahwa kebanyakan PDAM beroperasi dengan jum-
lah koneksi di bawah skala ekonomi. Namun dengan kondisi tersebut
bukan berarti bahwa semua PDAM beroperasi secara tidak sehat. Meski-pun sangat sedikit sekali PDAM yang beroperasi dengan sehat, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pada dasarnya sektor publik mampu menyediakan air bagi
masyarakat. Dengan demikian yang dibutuhkan bukan hanya upaya un-tuk meningkatkan kualitas dan perlu-asan layanan dengan mengedepankan partisipasi sektor swasta, tetapi juga upaya-upaya peningkatan kualitas dan perluasan layanan yang didasar-kan atas peningkatan kemampuan dan kapasitas dari penyedia layanan itu sendiri. Dengan perubahan cara pandang tersebut diharapkan ada per-ubahan terhadap bagaimana utilitas
layanan air harus dikelola. Banyak model terhadap pengelolaan penyedia-an layanan air, salah satunya adalah memisahkan antara kepemilikan de-ngan manajemen (korporatisasi). Na-mun sekali lagi, tanpa ada perubahan cara pandang terhadap penyediaan air bersih maka korporatisasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Korpo-ratisasi juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat. Penyediaan air di Brazil merupakan salah satu con-toh dari korporatisasi yang juga diim-bangi dengan partisipasi masyarakat. (Hamong Santono)
Korporatisasi juga harus diimbangi
dengan partisipasi masyarakat.
POKJA
28
Oleh Nugroho Tri Utomo
Sanitasi di Indonesia belum bisa dibanggakan. Untuk cakupan layanan air limbah domestik sebesar 51,9 persen penduduk pada 2010, di kawasan Asia Indonesia cuma lebih baik dari Laos dan Timor Leste. Kondisi
pengelolaan persampahan juga masih buram. Dari lebih 400 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada, kurang dari 10 yang sudah ramah lingkungan - umumnya menggunakan sanitary landfill. Sisanya masih menggunakan pembuangan terbuka (open dumping).
Padahal UU18/2008 tentang Pengelolaan Sampah memandatkan batas waktu 2013 untuk tidak lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka ini. Untuk meningkatkan sistem drainase lingkungan juga masih perlu kerja keras. Masih 22.500 hektare kawasan strategis di 100 perkotaan yang sering tergenang bila hujan yang harus ditangani sampai 2014.
Kondisi di atas tidak lepas dari sejarah panjang rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan sanitasi di negeri ini. Anggapan bahwa
sanitasi adalah masalah pribadi - sehingga masyarakat pasti akan
mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya - telah membuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan sanitasi tidak sehebat sektor lainnya.
Selama 1970-1999, total investasi pemerintah pusat dan daerah untuk sanitasi hanya mencapai Rp. 200 per kapita per tahun. Angka ini memang meningkat selama 2000-2004 menjadi Rp. 2.000. Kita bersyukur lima tahun terakhir investasi per kapita sanitasi ini terus ditingkatkan menjadi Rp. 5000 per tahun. Namun ini masih cukup jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp. 47.000 per kapita per tahun (studi Bappenas, 2008).
Angka investasi di atas memang baru yang berasal dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Padahal sanitasi seharusnya bukan hanya urusan pemerintah saja. Sanitasi urusan sehari-hari. Tidak seorang pun yang tidak melakukan aktifitas sanitasi setiap harinya, mulai dari membuang limbah manusia, menghasilkan dan membuang sampah, serta melengkapi rumah atau huniannya dengan saluran air hujan atau drainase - betapapun sederhananya.
Faktanya, setiap harinya masih ada 70 juta orang di Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (Riskesdas 2009). Akibatnya sekitar 14.000 ton tinja (lebih berat dari 4.500 gajah Sumatera) dan
Peduli Rakyat? PikirkanAir Minum dan Sanitasi!
Wacana
POKJA
29
Edisi III, 2010
176.000 meter kubik air seni (setara dengan 70 kolam renang ukuran olimpiade) setiap harinya mencemari saluran air, sungai, pantai, danau, tanah kosong, dan lain-lain. Tidak heran seluruh sungai di Jawa dan 70 persen di Indonesia kualitas airnya tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk digunakan sebagai sumber air minum. Akibatnya PDAM di Indonesia harus mengeluarkan biaya ekstra sampai 25 persen untuk mengolahnya menjadi air yang layak minum.
Tidak heran pula kalau berbagai penelitian telah menemukan bakteri e-coli pada sekitar 75 persen air sumur dangkal di kota-kota besar di Indonesia. Artinya sudah tercemar oleh air tinja manusia. Bisa karena rembesan tangki septik, baik karena letaknya terlalu dekat ke sumur atau karena memang bocor. Tidak heran jika kasus diare saat ini masih mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010).
Daftar sebab akibat di atas bisa lebih panjang lagi. Rendahnya pelayanan sampah dan buruknya PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat) menyebabkan tumpukan sampah yang dipenuhi lalat, yang bukan hanya buruk secara estetik tapi juga menambah resiko penyebaran penyakit. Belum lagi kalau menyumbat saluran drainase. Banjir dan genangan akan lebih sering terjadi dan pastinya kerugian ekonomi cukup tinggi.
Ringkasnya, untuk urusan sanitasi setiap orang berbuat, terlibat, dan terkena akibat. Jadi perlu bersepakat.
Kita perlu bersepakat bahwa Sanitasi adalah urusan bersama. Kebutuhan pembangunan sanitasi 5 tahun kedepan mencapai Rp. 56 triliun. Alokasi pemerintah pusat baru mencapai Rp. 14,6 triliun. Masih jauh dari mencukupi. Untuk pemerintah daerah, sekalipun sudah menjadi salah satu urusan wajibnya, umumnya baru mengalokasikan kurang dari 1 persen APBD-nya untuk pembangunan sanitasi. Kelompok masyarakat, dunia usaha, bahkan rumah tangga sendiri juga perlu untuk dimobilisasi perannya dalam pembagunan sanitasi.
Semua pihak perlu diajak untuk meningkatkan investasi sanitasinya. Mengapa? Karena investasi sanitasi itu penting dan sangat menguntungkan. Berikut beberapa alasan:
Pertama: Menghindari pertumbuhan ekonomi semu. Studi yang dilakukan WSP bersama Bappenas (2008) menyimpulkan bahwa akibat sanitasi buruk, kerugian ekonomi negeri ini mencapai Rp58 triliun setiap tahunnya. Ini setara dengan 2,1 persen Produk Domestik Regional Bruto saat itu yang kalau mau dihitung
betul harusnya akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Ironis memang kalau kita harus kehilangan Rp58 triliun per tahun karena kita memilih untuk tidak mengalokasikan Rp11,2 triliun per tahun.
Kedua: Efek luar biasa peningkatan sanitasi pada kesehatan, pendidikan dan produktifitas. WHO memperkirakan bahwa kondisi dan perilaku sanitasi yang baik dan perbaikan kualitas air minum dapat menurunkan kasus diare sampai 94 persen. Artinya jumlah hari tidak masuk sekolah bisa berkurang 8 hari pertahun yang tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan pengajaran dan pendidikan. Jumlah hari produktif dapat meningkat sampai dengan 17 persen yang berarti tambahan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan juga.
Ketiga: Membantu menurunkan kemiskinan. Akibat buruknya sanitasi, rata-rata keluarga di Indonesia harus menanggung Rp1,25 juta setiap tahunnya. Suatu jumlah yang akan sangat berarti bagi keluarga miskin. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya berobat, biaya perawatan rumah sakit, hilangnya opportunity cost ataupun pendapatan harian akibat menderita sakit atau harus menunggui dan merawat anggota keluarga yang sakit. Semakin sehat dan produktif seseorang, semakin besar kemungkinan untuk terbebas dari kemiskinan.
Keempat: Manfaat yang berlipat. Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa leverage factor untuk investasi sanitasi mencapai 8 sampai 11. Artinya setiap Rp. 1 investasi sanitasi akan mendatangkan manfaat sebesar Rp. 8 sampai Rp. 11. Pengalaman pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di
POKJA
30
Jawa Timur selama 2008-2010 bahkan menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 yang dikeluarkan untuk memicu dan memampukan masyarakat telah berhasil menggerakkan investasi sanitasi dari masyarakat sendiri sampai sebesar Rp. 35. Makin jelas bahwa pembangunan sanitasi itu investasi, bukannya membebani.
Kelima: Mencegah selalu lebih murah dari mengobati. Bank Pembangunan Asia (2009) menyatakan bahwa kalau kita gagal menginvestasikan US$ 1 untuk menangani sanitasi sehingga sungai kita tercemar, untuk memulihkannya akan dibutuhkan biaya sebesar US$36. Sanitasi adalah upaya pencegahan masalahan kesehatan dan kerugian ekonomi yang sangat efektif. Beberapa Kota/Kab. di Indonesia juga telah membuktikan bahwa investasi sanitasi diwilayahnya ternyata bisa menghasilkan penghematan pengeluaran dana pengobatan masyarakat dan asuransi kesehatan keluarga miskin yang lebih besar lagi.
Keenam: Percepatan pembangunan sanitasi sedang menjadi tren. Pemerintah telah mencanangkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. Hingga saat ini 63 Kota/Kab. telah mengikuti program tersebut. Yang menarik, para
Walikota dan Bupati yang terlibat telah membentuk suatu Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan secara aktif mempromosikan kepada masyarakat dan kepala daerah lain akan pentingnya pembangunan sanitasi. Investasi sanitasi Kota/Kab. yang telah terlibat dalam PPSP juga telah meningkat 2,5 - 10 kali lipat seperti tercantum pada anggaran sanitasi di APBD mereka. Minat untuk bergabung dengan PPSP juga terus meningkat. Hingga 2014, diharapkan paling tidak 330 Kota/Kab. akan bergabung.
Ketujuh: Peduli sanitasi, dicintai masyarakat. Di era politik seperti sekarang, dimana setiap pemilih punya satu suara, jangan dikira perhatian terhadap sanitasi tidak punya nilai politis. Sanitasi adalah urusan keseharian masyarakat. Memperhatikan sanitasi berarti memperhatikan hajat hidup masyarakat, Tanyakan saja pada Walikota Payakumbuh atau mantan Walikota Blitar yang pernah dengan bangga bercerita:” Saya ini terpilih untuk untuk kedua kalinya karena sanitasi!”
Penulis adalah Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas. Artikel ini merupakan opini pribadi dan telah dimuat di Harian Jurnal Nasional beberapa waktu lalu.
Wacana
POKJA
31
Edisi III, 2010
Air minum sangat berhubungan dengan hak hidup manusia. Sehingga masalah memperoleh air tentunya tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak dasar atau asasi manusia. Pengakuan air sebagai
hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.
Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan sebuah resolusi tentang Hak Atas Air. Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo memberikan kesempatan wawancara wartawan Percik, Eko B Harsono
P: Sebelumnya atas nama majalah Percik kami mengucapkan selamat kepada bapak atas amanah tugas yang
baru, semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Seperti kita ketahui Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu telah mengeluarkan Resolusi bahwa Air dan Sanitasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut bapak apa yang bisa dimaknai dari terbitnya resolusi tersebut oleh pemerintah Indonesia? Apakah konsep ini merupakan hal yang baru bagi kita?
J: Kita tentunya menyambut baik terbitnya Resolusi tersebut yang merupakan pengakuan para pemimpin dunia bahwa air dan sanitasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam diri manusia sehingga menjadi hak asasi manusia. Kita sangat menyadari air dan sanitasi menjadi kebutuhan paling dasar manusia. Kita menyebut sebagai hak atas air tetapi lebih kepada air sebagai kebutuhan dasar air minum yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sebelumnya tertuang dalam PP No 16 sebagai turunan dari UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jadi sesungguhnya kita sedang merecognize bahwa air sebagai kebutuhan dasar tentunya harus dipenuhi oleh Negara. Memaknainya tentunya sama, satu pihak menyebut hal itu sebagai Hak Atas Air sedangkan kami menyebut sebagai Kebutuhan Dasar Air Minum jadi tanggung jawab pemerintah.
P: Dapat bapak jelaskan bagaimana UU No 7 Tahun 2004 telah menjadi payung hukum bahwa
persoalan air minum yang merupakan kebutuhan paling dasar manusia menjadi tanggungjawab pemerintah atau negara? Jika sudah
Wawancara
DirekturPermukimandanPerumahanBappenas, Nugroho Tri Utomo
“Air Minum SebagaiKebutuhanDasar Jadi Tanggungjawab
Pemerintah”FOTO-FOTOWAJAH:POKJA
32
diadopsi sebenarnya sejauh mana pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep ini dalam konteks pembangunan AMPL?
J: Dalam UU No 7 Tahun 2004 jelas tercantum bahwa pemanfaatan air prioritas utama ditujukan untuk air minum yang merupakan kebutuhan paling dasar masyarakat Indonesia. Jika kemudian terjadi perselisihan akibat sumber daya air atau sebagainya, maka pertama-tama yang menjadi fokus atau prioritas pemerintah adalah air minum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Negara. Selain air sebagai kebutuhan dasar, ada yang sifatnya air menjadi kebutuhan sekunder atau menjadi penunjang kegiatan perekonomian, atau air yang kemudian digunakan untuk kebutuhan rekreasional, gaya hidup atau stylelistik itu tidak bisa lagi dikategorikan air sebagai hak. Pemerintah secara tegas bersikap bahwa karakteristik kebutuhan air seperti itu harus diperoleh sesuai dengan nilai ekonomis airnya.
P: Air sebagai anugerah Tuhan untuk manusia. Apakah dengan membuat karakteristik yang berbeda akan kebutuhan air tersebut tidak menjadi persoalan akan hak atas air?
J: Kita sadar dan sangat setuju bahwa air minum itu merupakan anugerah berharga yang diberikan Tuhan kepada manusia secara gratis. Namun hendaknya dimengerti bahwa untuk mengalirkan atau servicenya tersebut tidak dapat gratis. Bahkan didalam undang-undang Sumber Daya Air secara tegas disebutkan sumber daya air itu pada prinsipnya, bisa atau boleh didapat secara gratis selama pertama dia tidak merubah peruntukan dan membahayakan peruntukan bagi masyarakat dengan prioritas air minum. Dan kedua tidak digunakan untuk komersial. Jadi untuk kebutuhan
sendiri jelas Undang Undang menyebutkan semua orang Indonesia berhak mendapat sumber daya air dari manapun dengan gratis. Akan tetapi begitu sumber daya air disalurkan melalui pipa PDAM dan sebagainya itu yang dibayar adalah service atau pelayan. Dan pengejewantahan
air sebagai kebutuhan dasar ditanggung pemerintah dalam pengertian hak atas air itu diwujudkan dengan yang namanya tarif dasar. Dimana tarif dasar itu disebutkan misalnya sampai 5 meter kubik perbulan untuk setiap rumah tangga itu oleh pemerintah diterapkan tarif yang sangat murah. Jadi tetap juga tidak bisa gratis karena ada unsur pelayanan disitu. Kecuali datang sendiri kemata air tidak menjadi masalah.
P: Saat ini mengemuka upaya privatisasi sebagai salah satu pilihan pemenuhan akses air bagi penduduk. Dilain pihak banyak yang menganggap, khususnya LSM yang menilai privatisasi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Bagaimana pemerintah melihat persoalan ini?
J: Dalam Undang Undang N0 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jelas disebutkan bahwa siapa pun untuk dapat menggunakan sumber daya air dia harus memiliki Surat Izin Pemanfataan Air (SIPA) yang turunan pemerintahnya diatur lagi baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Surat izin ini berpayung hukum UU SDA tadi itu. Untuk kepentingan lingkup provinsi maka yang menerbitkan adalah provinsi, untuk lingkup pemerintah tingkat II Kabupeten atau Kota tentunya Walikota atau Bupati yang menerbitkan. Sedangkan untuk kepentingan nasional yang menerbitkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam menerbitkan SIPA ini tentunya pemerintah baik pusat dan daerah menyadari bahwa di dalamnya diatur tegas bagaimana air minum sebegai kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi dan dijamin. Yang saya coba mengerti teman-teman LSM itu melihat beberapa kasus terkesan air minum dikuasai oleh swasta sehingga sebagai air minum tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini merupakan kasuistis. Namun kita harus melihat persoalan secara jernih juga. Kalau sebuah perusahaan memiliki sumber daya air di wilayahnya, sesungguhnya saat dia ingin memanfaatkan sendiri dia harus memiliki SIPA. Dan pada saat mengeluarkan SIPA teorinya pemerintah daerah harus melihat apakah sumber daya air yang ada
Wawancara
33
Edisi III, 2010
diwilayah swasta itu dapat dimanfaat terlebih dahulu untuk air minum atau tidak. Bahkan dalam SIPA tersebut dikatakan apabila dikemudian hari air yang ada dalam wilayah perusahaan tersebut dibutuhkan untuk kebetuhan yang lebih prioritas yaitu air minum maka secara otomatis dapat diambil oleh pemerintah.
SIPA ini merupakan surat izin pemanfaatan air bagi siapa pun. Misalnya saya sudah punya izin untuk memanfaatkan air untuk air botol, namun suatu saat pemerintah daerah tempat usaha itu beroperasi melihat ada sebuah kebutuhan air minum yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas, dan satu-satunya sumber daya air yang dapat digunakan adalah sumber air di tempat saya. Maka secara otomatis pemerintah daerah dapat meninjau kembali izin yang telah diberikan kepada saya, dan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat akan air minum. Dan sisanya kemudian bisa dimanfaatkan oleh perusahaan saya itu. Jadi jika dilihat peraturannya jelas terlihat kita sudah sangat merecognize apa yang diistilahkan PBB tersebut sebagai Hak Atas Air. Namun jika kemudian disana-sini masih terdapat sejumlah kekurangan, harus diakui kita masih sangat membutuhkan teman-teman LSM untuk membantu memberikan feedback atau informasi.
P: Apakah konsep hak asasi manusia ini juga telah mewarnai RPJMN 2010-2014? Dan terakhir mungkin bapak memiliki pesan khusus kepada pemerintah daerah untuk merespon soal air minum yang kemungkinan
besar akan lebih rumit, apa yang harus dicermati terkait air sebagai sebuah hak dan kebutuhan dasar warganya?
J: Dalam RPJMN 2014 jelas kita sudah mengadopsi air sebagai sebuah kebutuhan dasar manusia Indonesia yang harus dipenuhi oleh Negara. RPJM kita jelas bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan pengertiannya seperti sudah saya jelaskan diatas tadi tentunya. Yang harus dicermati peme rintah daerah dimanapun pertama harus punya gam-
baran yang sangat jelas tentang kebutuhan air untuk masyarakatnya. Sesuai dengan bahasa MDGS, pemerintah daerah harus paham akases sumber air berkualitas untuk masya ra kat nya (improve water). Meski masyarakat pu-nya sumber air alternatif pemerintah daerah harus tahu apakah itu sudah menjadi sumber air minum yang layak. Yang menjadi masalah adalah yang tahu mengenai kuali-tas air seperti apa adalah pemerintah daerah, sedangkan masyarakat biasanya tenang-tenang saja apakah sumber airnya itu layak atau tidak untuk dikonsumsi. Masyarakat sering tidak tahu bahwa sejumlah penyakit banyak ber-sumber dari air yang mereka minum. Inilah pentingnya pemerintah daerah untuk mengedukasi warganya. De-ngan semakin sulit nya kondisi sumber daya air ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan apa yang sudah kita punya dan kedua mencari sumber air alternatif. Dan yang kedua ini lebih mahal tentunya. Yang kedua ini tentunya tidak terhindarkan karena pertambahan penduduk . Dan untuk menjaga sumber daya air tentunya sanitasi harus diperhatikan dan dijaga secara baik.
ISTIMEWA
Beberapa waktu lalu, Majelis Umum PBB menerbitkan sebuah resolusi yang menyatakan akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia. Dengan suara 122 mendukung dan tidak
satu pun negera menentang. Pada kesempatan itu para tokoh dunia menegaskan hak atas air minum yang aman dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi negara.
Dengan mendukung resolusi PBB, penandatangan berkomitmen untuk memainkan peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan untuk akses yang memadai, aman dan terjangkau untuk air. Indonesia memilih mendukung dengan beberapa catatan. Salah satu dasar terbitnya resolusi tersebut, PBB menyatakan “keprihatinan mendalam” bahwa sekitar 884.000.000 orang tanpa akses ke air minum yang aman dan lebih dari 2,6 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar.
Ketika menerbitkan resolusi tersebut Majelis Umum PBB mengungkapkan sejumlah fakta bahwa 1,5 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap tahun akibat penyakit air dan sanitasi yang buruk. “Saya melihat resolusi yang ditanda-tangani pemerintah Indonesia itu dapat berubah menjadi buah simalakama. Tidak dilaksanakan melanggar komitmen, namun disisi lain sejumlah persoalan menyangkut air mengemuka dengan kuat ditengah masyarakat,” ujar Koordinator Hak Atas Air, Hamong Santono kepada Percik di Jakarta.
Menurut Hamong, meskipun secara luas diakui bahwa air akan menjadi sumber utama konflik di masa mendatang, Indonesia belum memasukkan isu-isu sumber daya air di antara prioritas utama pembangunan. Hal ini dapat digambarkan oleh banyak sungai yang telah mengalami kerusakan yang luas dari polusi di negara kita. Pada 1970-an, ada 22 sungai rusak parah. Menjelang akhir 1990-an, angka itu meningkat menjadi 62. Tahun lalu, angka itu berdiri di 64. Tragisnya, selama tiga dekade terakhir, belum ada usaha serius untuk mengembalikan sungai tersebut. Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa laju deforestasi (penggundulan hutan, red.) tahunan masih terus berkembang.
Dari tahun 2000 hingga 2005, deforestasi di seluruh negeri mencapai rata-rata 1.089.560 hektar per tahun. Walaupun Indonesia masih memiliki surplus air, deforestasi pasti akan mempengaruhi ketersediaan air di beberapa provinsi, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi.
Ditegaskan oleh Hamong, ancaman ini diperburuk oleh kondisi infrastruktur sumber daya air di negeri ini, yang tidak lagi mampu menyediakan air bersih untuk masyarakat baik melalui operator swasta atau air pasokan Perusahaan Daerah Air Minum. Pada 2009, PDAM hanya mencakup 24 persen dari rumah tangga nasional dan banyak kantor cabang yang kekurangan uang tunai.
Hamong Santono:
Wawancara
34
35
Edisi III, 2010
Alokasi anggaran negara untuk air bersih dan sanitasi, senilai sekitar Rp. 3 triliun menjadi Rp. 4 triliun ($ 340 juta menjadi $ 450 juta) per tahun, yang lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pemerintah untuk subsidi listrik, yang bernilai sekitar Rp. 40 triliun per tahun
Mengamankan hak rakyat untuk memperoleh air minum membutuhkan peran negara untuk memainkan peran yang lebih besar. Kesediaan Indonesia untuk mematuhi resolusi PBB yang baru, tentu saja berdampak positif pada pengembangan sumber daya air di seluruh negeri.
Sejumlah LangkahHamong menegaskan, sebagai langkah pertama,
pemerintah harus memiliki kemauan politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi. Ini harus mengadakan diskusi publik dan debat mengenai aspek teknis dari masalah sumber daya air dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Perdebatan tentang masa depan sumber daya
air kita harus melibatkan semua sektor masyarakat karena merupakan masalah keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil yang sangat membutuhkan akses terhadap air bersih yang terjangkau.
Debat sehat ditambah dengan komitmen pemerintah
bisa membuka jalan bagi inisiatif kebijakan utama pada sumber daya air bersih. Hal ini tidak hanya merupakan cara untuk mengembangkan infrastruktur sumber daya air, tetapi juga menjawab pertanyaan tentang masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan air rakyatnya. Afrika Selatan, misalnya, melakukan survei mengenai harapan rakyatnya untuk pemerintah baru segera setelah berakhirnya apartheid. Hasil survei menunjukkan bahwa orang-orang ingin negara yang menyediakan lapangan kerja, membangun perumahan yang layak dan segera menyediakan air
bersih dan sanitasi.Berdasarkan survei, pemerintah Afrika Selatan
menyiapkan rencana induk untuk mencapai target tersebut. Akibatnya, akses publik terhadap air bersih mencapai 100 persen di daerah perkotaan dan 80 persen di daerah pedesaan, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia 2008.
Di Uruguay, pemerintah bahkan mengubah Konstitusi pada tahun 2004, memberikan prioritas kepada pertimbangan sosial dalam mengeluarkan kebijakan terhadap air dan sanitasi. Dalam contoh lain, kota Porto Alegre Brasil memperkenalkan sistem anggaran partisipatif yang termasuk dalam pengembangan pasokan air bersih. Negara-negara ini telah menunjukkan bahwa air, sebagai komoditas publik, harus dikelola dengan baik dan dilindungi, dan masalah sumber daya air yang selalu harus ditangani secara demokratis.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki peran penting dalam mengatasi masalah air di Indonesia. Kita semua menonton dan menunggu. Selama sisa masa jabatan yang kedua dan terakhir di
kantor, Yudhoyono tidak memiliki pilihan selain untuk memasukkan air dan masalah sanitasi di antara prioritas pembangunan bangsa. Masa depan kita tergantung padanya.
Negara-negara ini telah menunjukkan bahwa air, sebagai komoditas publik,
harus dikelola dengan baik dan dilindungi, dan
masalah sumber daya air yang selalu harus
ditangani secara demokratis.
FOTO-FOTO:DOKPRI.
36
Ditegakkannya Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi amanat reformasi yang digulirkan pada 1998. Tetapi sepanjang rentang 1998 sampai sekarang ada banyak catatan yang menilai perjuangan
menegakkan HAM, hukum dan pemberantasan korupsi masih berjalan di tempat. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) A. Patra M. Zen, nama yang cukup dikenal praktisi hukum mencoba menjawab sejumlah persoalan menyangkut Hak Azasi Manusia (HAM) terkait dengan terbitnya resolusi PBB tentang Hak Atas Air beberapa waktu lalu.
Patra M Zen secara tegas menyebutkan penegakan hukum di Indonesia masih terbatas manis di bibir, sehingga yang terjadi surplus janji, defisit bukti. Artinya, lebih banyak janji-janji penegakan hukum daripada bukti. Karena itu banyak menteri yang mendapat nilai
merah dalam penegakan hukum dan HAM. “Karena itu, saya sangat berharap pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangani resolusi tersebut secara konsistem melaksanakannya. Jangan menjadikan hak asasi atas air sebuah jargon yang manis di bibir pejabat,” ujar Patra.
Menurut Patra, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ekosob) PBB dalam komentar umum Nomor 15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air.
Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan. Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak
A Patra M Zen, Direktur YLBHI:
Hak Asasi Atas Air Jangan Sekedar Jargon Manis di bibir
Wawancara
ISTIMEWA
37
Edisi III, 2010
semata-mata sebagai barang ekonomi. Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air, dalam setiap keadaan apa pun harus sesuai dengan faktor-faktor berikut :
1. Ketersediaan. Artinya, pasokan air untuk setiap orang harus mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan individu dan rumah tangganya. Kuantitas ketersediaan air untuk setiap orang harus mengacu pada pedoman yang ada di WHO.
2. Kualitas. Maksudnya, air minum untuk setiap orang atau rumah tangga harus aman, bebas dari organisme mikro, unsur kimia dan radiologi yang berbahaya yang mengancam kesehatan manusia.
3. Mudah diakses. Yaitu air minum dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi.
Dikatakan Patra, untuk memantau hak tersebut, saat ini diperlukan pemaksimalan sumberdaya advokat, PBH dan sukarelawan YLBHI – LBH untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekosob di negeri ini. Setidaknya, ada tiga hal yang perlu terus dikembangkan. Pertama, promosi tentang prinsip-prinsip, features dan batas lingkup, termasuk definisi hak-hak ekosob. Hal ini diperlukan, dalam praktik, untuk memberikan kerangka kebijakan dan praktik pemenuhan hak-hak ekosob rakyat;
Kedua, di lingkup kompetensi utama YLBHI – LBH, perlu dikembangkan terus peluang-peluang menggunakan sistem peradilan – disamping mekanisme administrasi dan politik – dalam rangka pemenuhan hak-hak ekosob. Dengan kata lain, sebaiknya terus mendorong hak-hak ekosob sebagai hak konstitusional menjadi hak hukum masyarakat, terutama berkaitan justisiabilitas hak-hak ini.
Ketiga, secara terus menerus sebaiknya kita menghidupi sebuah tradisi yang positif: memproduksi gagasan dan ide-ide maju tentang sistem negara demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia dan secara umum gagasan tentang masyarakat dan kemanusiaan. Aktivitas ini bertujuan untuk menopang keseluruhan aktivitas advokasi dimana YLBHI – LBH selain menjadi lembaga advokasi, juga menjadi prominent critical and criticism centre.
Sasaran advokasi ini, tentu saja tidak hanya dapat didorong oleh advokat, PBH atau sukarelawan LBH, melainkan juga para alumni LBH yang saat ini
memegang dan duduk dalam posisi kunci dan strategis dalam lembaga-lembaga negara, dalam menjalankan obligasi untuk mempromosikan, melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak ekosob di Indonesia.
Menurut Patra pula, YLBHI sejak awal telah merekomendasikan sejumlah program aksi yang secara substantif dan signifikan akan membawa perubahan besar dalam kehidupan hukum dan HAM, utamanya bagi masyarakat miskin, marjinal dan para keluarga korban pelanggaran HAM. “Program 100 hari seperti apa yang diharapkan masyarakat dengan ukuran tersebut di atas, dapatlah kami contohkan. Pertama, di bidang perluasan dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Program pemberian bantuan hukum dan pembangunan sistem bantuan hukum nasional semestinya menjadi program prioritas kementerian ini,” paparnya.
Kedua, di bidang hak asasi manusia, (antara lain) seperti mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin, menerbitkan regulasi penyelesaian
problem yang dialami korban lumpur pa-nas Lapindo, penyelesaian kekerasan buruh migran, termasuk meratifikasi konvensi perlindungan buruh migran dan pemberian bantuan hukum bagi buruh migran di luar negeri, kemudian meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, serta menyu sun dan menerbitkan Keppres Pengadilan HAM ad hoc kasus Orang Hi-lang.
Beberapa rekomendasi lainnya yang disebutkan Patra, termasuk juga
menerbitkan Perpres Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), merekomendasikan pencabutan izin HPH dan HTI, pertambangan dan migas, serta perkebunan besar yang telah menyebabkan konflik sosial dan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup, hingga penerbitan regulasi pelembagaan permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota. Pemerintah menurut Patra pula, juga bisa memperkuat regulasi dan kebijakan pemberantasan korupsi, (membuat) moratorium penggusuran paksa perumahan kaum miskin perkotaan, mengupayakan pengembalian lahan-lahan yang dikuasai BUMN kepada masyarakat yang diperoleh dengan cara melawan hukum di masa lalu, serta penerbitan regulasi yang menjamin pemenuhan hak dan hajat hidup orang banyak (air, pendidikan dan kesehatan).
Kecukupan air sebagai prasyarat
pemenuhan hak atas air, dalam
setiap keadaan apa pun . . .
38
Inovasi
BELAKANGANiniramaiorangmembicarakanakankrisisairbersih,namunpembicaraanorangselaluterkisarantarahukum,kebijakan dan manajemennya saja. Bagaimana dengan teknologi untuk
mengatasi krisis ini?SeorangpakardanpenelitiLembagaIlmu
PengetahuanIndonesia,DrAntoTriSugiatomemperkenalkan teknologi oksidasi beserta penggunaannyasebagaisolusialternatifmengatasikrisis air minum. Teknologi ini bukanlah teknologi baru,namunperkembangannyaakhir-akhirinisangatpesat. Belakangan ini teknologi oksidasi mulai dikenal dengan nama teknologi Advanced Oxidation Processes. Teknologi ini sendiri mulai banyak dikembangkan serta diterapkan di berbagai negara maju.
Krisis air bersihDiIndonesiadewasaini,salahsatumasalah
lingkungan yang cukup meresahkan adalah krisis air bersih.Krisisairbolehdikatakanmasalahpalingutamaselainmasalahlingkunganlainsepertipolusiudara,kerusakan dan juga kebakaran hutan.
Permasalahan air bersih sebenarnya ada pada pembuangan limbah cair yang dilakukan secara sembarangan dari hasil kegiatan industri serta limbah domestikperkotaan.Ditambahlagidengankurangnyausaha untuk mengolah limbah cair secara benar.
Selainakibatmasalahlimbahcair,krisisairbersihdiIndonesia juga diakibatkan karena eksploitasi langsung air tanah sebagai sumber air untuk berbagai bidang industri termasuk di antaranya industri air minum dalam kemasan tadi.
Limbah cairDalam proses produksi sebuah industri pada
umumnya dipergunakan berbagai bahan material dari berbagaijenisdanbentuk.Namun,dalampelaksanaansistem pengolahan limbah cair pada umumnya dilakukan secara bersamaan tanpa adanya pembagian atau pemisahan jenis dan bentuk bahan material berdasarkan proses yang dilalui. Akibat dari penerapan sistempengolahanlimbahsepertiini,kitaakanmembutuhkansuatuteknologitinggi,sehinggaakanmembutuhkan dana serta energi yang sangat besar.
Selainitu,sistempengolahanlimbahcairyangadasekarang umumnya mempergunakan cara kombinasi
Teknologi Oksidasi untuk Air Bersih
DOK.PRI.
39
Edisi III, 2010
antara pemakaian chlorine serta sistemkondensasi,sedimentasi,danfiltrasi.Sedangkanpengolahanlimbahorganiknya banyak mempergunakan mikrobiologi,karbonaktifsertamembrane filtration. Sedangkan akhir-akhir ini limbah organik yang dibuang semakin banyak mengandung senyawa organik yang sulit untuk diuraikan hanya dengan mikrobiologi serta membrane filtration,sertasangatmembahayakan keselamatan makhluk hidup.
Dariketerangansingkatdiatas,dapat kita simpulkan bahwa sistem pengolahan limbah cair yang ada sekarang sangatlah tidakefektif.Untukitukitaperlumemilihsertamemilah teknologi pengolahan limbah cair yang ada agar kita dapat menerapkan suatu teknologi secara tepat dan benar sesuai dengan kadar kebutuhannya.
Untuk itu kita perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut,(1)unsur-unsuryangterkandungdarilimbahcairtersebut,(2)akibatdariunsur-unsurtersebutketikaairlimbahtersebarkelingkungan,(3)perubahanserta kekuatan/ketahanan dari unsur tersebut dalam proses pengolahan (treatment),(4)metode/teknologiyangdapatmembersihkanataumemodifikasiunsuryangterdapatpadalimbahcairtersebut,(5)metode/teknologi yang tepat guna serta dapat membersihkan/memodifikasizatpadathasildariprosespengolahan,(6)demikianpulahalnyakarakteristikdariteknologipengolahanlimbahcairyangadaseperti,jenismaterialapayangdapatdiuraikan,kualitasairbagaimanayangdiharapkan,bagaimanabiayapemeliharaannya,bagaimana biaya pembangunan dan lain-lain.
Teknologi OksidasiSaat ini penggunaan teknologi oksidasi atau yang
sekarang kita kenal dengan Advanced Oxidation Processes(AOPs)mendapatperhatiancukupbesar.Karena,teknologiinidapatmenguraikansertamembersihkan senyawa-senyawa organik yang selama inisulitatautidakdapatdiuraikandenganmetodemikrobiologi atau membrane filtration.Selainitu,teknologiinidapatdiaplikasikantidakhanyauntukmengolahlimbahcairhasilindustri,namundapatjugadipergunakan untuk mengolah air minum atau air bersih.
Teknologi AOPs adalah satu atau kombinasi dari
beberapaprosessepertiozone, hydrogen peroxide, ultraviolet light, titanium oxide, photo catalyst, sonolysis, electron beam, electrical discharges (plasma) serta beberapa proses lainnya untuk menghasilkan hydroxyl radical(OH).OHadalahspesiesaktifyangdikenalmemilikioksidasipotensialtinggi2.8Vmelebihi ozone yang memiliki oksidasi potensial hanya 2.07 V. Hal ini membuat OH sangat mudah bereaksi dengan senyawa-senyawa lain yang ada di sekitarnya.
Saatini,metodekombinasidariozone, hydrogen peroxide, dan ultraviolet light merupakan metode yang palingbanyakditelitisertadicobauntukmengolahberbagaijenislimbahcair.Diikutiselanjutnyadenganmetode titanium oxide dan fenton reaction. Sedangkan metodelainsepertisonolysis, electron beam juga electrical discharges,kebanyakanmasihdalamtahapprosespenelitian.
KarakteristikdariOH,OHsesuaidengannamanyaadalahspesiesaktifyangmemilikisifatradikal,dimana mudah bereaksi dengan senyawa apa saja tanpa terkecuali. Di dalam air OH bereaksi dengan senyawa yang ada di sekitarnya.
ReaksiOHdenganOH,sepertipenjelasandiatas,OHsangatmudahbereaksidenganapasaja,termasukdenganOHitusendiri,darireaksiinididapatkanhydrogen peroxide. Jangka waktu dari OH tergantung kepadakonsentrasinya.Sebagaicontoh,untukOHberkonsentrasi1µM,jangkawaktunyaadalahsekitar200 µs.
Aplikasi dari AOPsBerikut beberapa contoh pemakaian teknologi
AOPs. Di mana selain penjelasan di atas masihbanyaklagipenelitian
40
yang membahas tentang metode AOPs ini.DiJepang,sejakditerapkannyaperundangan
tentang dioxindansejenisnya(Januari2001),pengolahan limbah cair terpusat pada limbah cair daritempatpembakaransampah(domestikdanindustri). Di mana dioxin banyak dihasilkan dari akibat pembakaransampah(terutamasampahjenisplastik)yangtidaksempurna.Perlukitaketahuibahwahampirdari 70 persen sampah di Jepang diproses dengan caradibakar(KementerianLingkunganHidup,1996).Untuk menguraikan dioxin ini metode AOPs banyak dipergunakan,diantaranyaO3/UVdanO3/H2O2.DenganmempergunakanO3/UV,kandungandioxin dapat diuraikan hingga 90 persen di mana sebagai sumber ultraviolet light-nya dipergunakan lampu dari merkuri rendah voltase yangdidapatilebihefektifdibandingkandenganlampumerkurivoltasetinggi(Daito,2000).Darihasilpenelitiandiketahuibahwaperbandingan penggunaan dari O3/UV dan O3/H2O2 adalah,O3/UVlebihefektifuntukmenguraikanjenissenyawa dioxin yang mengandung unsur Cl lebih banyak.SedangkanO3/H2O2efektifuntukjenissenyawa dioxin yang mengandung unsur Cl lebih sedikit.
Contoh lain adalah limbah cair dari berbagai industritekstilyangbanyakmengandungdye (zat pewarna),disinibanyakdipergunakanUV/H2O2,
MetodaFenton,O3/UV,sertaTiO2/UV(Sugimoto,2000).UV/
H2O2didapatkanpalingefektifuntukmenguraikan/menghilangkan zat pewarna ini. Sedangkan untuk limbah cair industri lainnya selain zat pewarna dipergunakanmetodeUV/H2O2,MetodeFentondanO3/H2O2. Untuk menguraikan p-hydroxyphenilacetic acid yang banyak didapatkan dari limbah industri agrokultur,kombinasidariMetodeFentondanultravioletadalahpalingefektif(Sarria,2001).
Untuk limbah cair dari penggunaan obat-obatan di bidangpertanian,metodeAOPsdidapatisangatefektif,di antaranya untuk penguraian senyawa atrazine dipergunakanO3/H2O2,O3/UVdanUV/H2O2.DisiniO3/H2O2didapatilebihefektifdibandingkandenganyangmetodelainnya(Acero,2001).Untukpenguraiansenyawa 2-4 dichlorophenoxyacetic acid dipergunakan UV/H2O2(Alfano,2001)Simazine(Kruithof,2000),dan Tricholoethylene(Shiotani,2001)dapatdiuraikanmendekati100persendenganmempergunakanO3/H2O2 atau UV/H2O2. Sedangkan untuk menguraikan mono dan trichloroacetic acid dalam air minum dipergunakan kombinasi dari serat TiO2 dan sinar matahari(Sun,2000).
Untuk limbah cair ini baru metode kombinasi dari ozone dan hydrogen peroxide saja yang dipergunakan (Fuchigami,2000).Metodeinididapatiefektifdipergunakan untuk menguraikan humic acid, endocrine-disrupting chemicals serta senyawa organik lainnya,yangdidapatitidakdapatdiuraikandenganproses activated sludge.( Eko/LIPI.org)
Inovasi
ISTIMEWA
41
Edisi III, 2010
Yuliansa Effendy,Peneliti Program Pascasarjana Teknik Universitas Gajah Mada
Dalamaktivitassehari-harimanusiasangatmembutuhkan air baik untuk konsumsi maupun aktivitaslainnyayangmemerlukanairseperti
mandi,cuci,pertanian,industridanlainsebagainya.Dalam buku Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun2008,berdasarkandatadariStatistikIndonesiatahun 2007 secara nasional kebutuhan air di Indonesia mencapai9,03milyarM³,adapunsumber-sumberairyang dimanfaatkan masyarakat antara lain air ledeng (PAM)sebesar16,19%,airtanah(denganpompa)sebesar57,97%,airkemasan7,18%,mataair12,64%,airsungai3,04%,airhujan2,58%danlainnya0,40%.
Usaha-usaha pemerintah melalui Perusahaan Air Minum (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di Indonesia ternyata belumdapatmenjangkauseluruhlapisanmasyarakat,terutama masyarakat pedesaan yang terletak jauh dari instalasi pelayanan pengelolaan air bersih. Sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di lingkungansekitarnyasepertimemanfaatkanairsungai,airsumur,airdanau,airhujansertamataair.
Namun mutu air yang digunakan belum tentu memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan sebagaiairbersih(PermenkesRINo.416/Menkes/SK/IX/1990),mutuairdapatdipengaruhiolehpencemaran,baikpencemaralamimaupunpencemarakibataktivitasmanusia atau makhluk hidup lainnya. Salah satu sumber air yang memiliki mutu yang kurang baik sebagai air bersihadalahairgambut,padahalbiladitinjaudarisegikuantitasairgambutmerupakanpotensialyangberlimpah khususnya terdapat pada wilayah yang mempunyaikarakteristiksebagailahangambut.
KecamatanGambutmerupakansalahsatukecamatan yang berada di kabupaten Banjar dengan luas129,30hektarmempunyailuaspotensiallahangambut,dimanapendudukyangberadadipelosokhanya memanfaatkan air hujan dan air permukaan.
HasilujidikecamatanGambut,kabupatenBanjarpropinsiKalimantanSelatanmenunjukkankarakteristikair gambut mempunyai kadar yang melebihi ambang
Tanah Liat Media Efektif Menjernihkan Keruhnya Air Gambut
DOK.FT-UGM
42
batasairbersihyangdiperbolehkan,yaitudenganpH3,9,warna570PtCo,kekeruhan13NTUmg/lt,SO₄60mg/lt,Fe2,37mg/lt,Mn0,07mg/lt,Zn0,31mg/lt,zatorganik280mg/ltKMnO₄,kesadahan21mg/ltCaCO₃danCl11mg/lt.Danbiladibandingkan dengan standar baku mutu air bersih (Permenkes RI No. 416/Menkes/SK/IX/1990)denganparameter yang sama air bersih harusmempunyaipH6.5–9.0,warna50TCU,kekeruhan25NTU,SO₄400mg/lt,Na10mg/lt,Fe1.0mg/lt,Mn0.5mg/lt,Zn15mg/lt,zatorganik10mg/ltKMnO₄,kesadahan500mg/ltCaCO₃,Cl600mg/lt.Denganperbandingantersebut,tentuairgambutbelumdapat dipakai sebagai air bersih.
Untukdapatmemanfaatkanairgambut,makadiperlukan adanya upaya pengolahan air gambut untukmemperbaikikualitassifat-sifatfisikdankimiaair sehingga memenuhi syarat air bersih. Teknologi yangmurah,aplikatifdanpemanfaatanbahanlokalsangat diharapkan dalam pengolahan air bersih ini. Denganmetodekoagulasi-flokulasi-filtrasidenganbahankoagulanlokalsepertitanahliatpodsolikdandiharapkan merupakan teknologi sederhana yang efektifdapatdiadopsiolehmasyarakatsetempat.Secara
keseluruhan pemberian tanah liat podsolik dapat memperbaiki kualitas
air gambut. Walaupun pemberian tanah liat podsolik sebagai koagulan memperlihatkan korelasi atau hubunganyangtidaklinier.Padaproses koagulasi pemberian tanah liatpodsolikdengandosis7,5g/lmemperlihatkan hasil yang paling baik.
Tahapan ProsesPenelitiandilakukandikota
Banjarmasin antara bulan Desember 2009 sampai bulan Januari 2010. Analisis air di Laboratorium Balai
TeknikKesehatanLingkungan(BBTKL)KalimantanSelatandiBanjarbarudandiLaboratoriumKesehatanPropinsiKalimantanSelatandiBanjarmasin.Penelitiandilakukandalambeberapatahappelaksanaanyaitu:
Analisis laboratorium pendahuluan terhadap air gambutsebelumdiolahdenganalatpengolahairbersih,sebagai data dasar air gambut sebelum diolah dianalisis meliputiparameterWarna,Kekeruhan,ZatOrganik,Fe,Mn dan pH.
Perancangan dan pembuatan alat pengolah air gambut skala individu.
Tanah liat podsolik diambil pada kedalaman 1- 2 meterataupadasolumB-CdikelurahanSeiUlinKotaBanjarbaruPropinsiKalimantanSelatan.Tanahliatdianginkan agar kering udara dan disaring dengan ukuran0.002–0,2mm.
Inovasi
43
Edisi III, 2010
Pengolahan Air Gambut dengan Menggunakan Alat Pengolah Air Bersih.Lantassepertiapaprosespengolahanairgambut
dengan pemberian tanah liat podsolik terjadi proses koagulasi-flokulasiyangmembuatdestabilisasidanadsorpsi pada koloid organik sehingga terjadi perubahan padapenurunannilaiwarna,kenaikankekeruhan,penurunankandunganzatorganik,penurunankandungan Fe dan Mn serta meningkatkan pH. Posisi Ca2+ dan Al3+ sebagai pengikat. Hal ini dapat dilihat melalui proses yang terjadi sebagai berikut.
Warna air gambut sebelum perlakuan mempunyai nilaisebesar1460TCU,setelahdiberitanahliatpadaberbagaidosis,parameterwarnainiterjadipenurunanmenjadi410TCU,212TCU,108TCU,133TCUdan216TCU.PenurunanwarnaairgambutinidisebabkanadanyamuatanpositifAl3+yanglepasdarijerapanpermukaanliatdanbebas,bereaksidenganmengikatkoloid asam humat sebagai penyebab warna pada airgambut,kemudiangabunganpartikeliniakanmengendap karena masanya bertambah berat bersama-samapartikelliat,sehinggapadatahappengolahaniniwarna air sudah tereduksi.
Padatahapanlanjutanberupafiltrasipenurunanwarnacukupbaik,initerlihatpadaperbandingannilaikekeruhansebelumfiltrasidansetelahfiltrasi.Setelahfiltrasikekeruhanmasing-masingditunjukkandengannilai247TCU,169TCU,21TCU,22TCUdan137TCU.Mediasaringdengankerikildanpasirsertaarangaktifdapatmengendapkandanmenjerap(adsorpsi)partikel-partikelyangmasihmelayang.
Dari seluruh tahap proses pengolahan air gambut dengankoagulantanahliatpodsolik,yangdapatmemenuhistandarwarnaairbersihpadapemberian2,5g/ltanahliatpodsolikpadatahapfiltrasiyaitu43TCUsedangkan standar warna air bersih 50 TCU.
Kekeruhanawalairgambutsebesar8,02NTU,masihtermasukdalamsyaratairbersih,perlakuanpemberiantanahliatpodsolikdengandosis0g/l,2,5g/l,5g/l,7,5g/l dan 10 g/l ke dalam air gambut justru menambah pengotor,initerlihatnyapeningkatankekeruhanmenjadi9,42NTU,11,65NTU,16,07NTU,24,37NTUdan46,57NTU. Semakin banyak tanah liat diberikan maka semakin banyakpulapartikel-partikelliatyangmasihmelayangdalamairdanbelumterendapkan.Padaprosesfiltrasipartikel-partikelyangmasihmelayangdalamairiniakanmemasukipori-poriyangkecil,sehinggapartikelyang lebih besar dari pori akan tertahan sedangkan bila partikellebihkecilakanterussampaipadaairkeluar
penyaringan. Ini terlihat pada nilai kekeruhan air gambut yangsudahpadatahapfiltrasipadamasing-masingdosis0g/l,2,5g/l,5g/l,7,5g/ldan10g/lyaitu2,36NTU,0,9NTU,1,28NTU,1,79NTUdan2,96NTU.
Untuk kekeruhan pada proses pengolahan air gambutdengankoagulantanahliatpodsolik,yangdapat memenuhi standar kekeruhan air bersih pada pemberian2,5g/ltanahliatpodsolikpadatahapfiltrasiyaitu0,9NTUsedangkanstandarkekeruhanairbersih 25 TCU. Zat Organik yang terdapat dalam air gambutsebelumperlakuansebesar338,1mg/lKMnO4dan setelah pemberian tanah liat terjadi penurunan kandunganzatorganikmasing-masingsebesar145,4mg/luntukdosis0gr/ltanahliatpodsolik,26,5mg/l
untukdosis2,5gr/ltanahliatpodsolik,13,3mg/luntukdosis5gr/ltanahliatpodsolik,9,2mg/luntukdosis7,5gr/ltanahliatpodsolikdan4,1mg/luntukdosis 10 gr/l tanah liat podsolik. Zat organik yang ada dalam air gambut tersebut melayang dalam air berupa koloidorganik,denganadanyapemberiankapurdantanah liat maka terjadi pengikatan oleh Al3+ dan Ca2+ denganbutiran-butiranliatyangjugabersifatkoloid,penggabungan tersebut akan menghasilkan massa yanglebihbesardanberat,kemudianakanterendapkan akibat pengaruh gravitasi bumi. Melewatimediasaringzat
ILLUSTRASIDOK.FT-UGM
44
organik ini lebih tertahan untuk memasuki pori-pori yanglebihkecilsertaakanterjerappadaarangaktifsehingga pada proses ini terlihat kandungan zat organik sebesar27,2mg/luntukdosis0gr/ltanahliatpodsolik,76,0mg/luntukdosis2,5gr/ltanahliatpodsolik,15,5mg/luntukdosis5gr/ltanahliatpodsolik,24,3mg/luntukdosis7,5gr/ltanahliatpodsolikdan23,7mg/luntuk dosis 10 gr/l tanah liat podsolik.
Dari seluruh tahap proses pengolahan air gambut dengankoagulantanahliatpodsolik,yangdapatmemenuhi standar kandungan zat organik air bersih padapemberian2,5g/ltanahliatpodsolikpadatahapfiltrasiyaitu7,6mg/lKMnO4sedangkanstandarzatorganikairbersih10mg/lKMnO4.
Parameter pH merupakan faktor penentu dalam
menentukanterhadapparameter-parameterlain,pHairgambutsangatrendahpadapenelitianinipHawalairgambutsebagaiairgambutadalah3,62.Pemberiankapursebagai variabel tetap sebesar 250 mg/l dan ditambahkan pulapemberiantanahliatpodsolik0g/l,2,5g/l,5g/l,7,5g/ldan10g/ldapatmeningkatkanpHairgambutmenjadi8,93,7,68,7,1,6,99dan7,2.Selainkapur(CaO)yang diberikan bersifat basa juga adanya kandungan Al3+ pada tanah liat podsolik akan membantu menetralkan air gambut dari pengaruh asam humat dan fulvat. Pada prosesfiltrasisesuaidengandosispemberiantanahliatpodsolik0g/l,2,5g/l,5g/l,7,5g/ldan10g/lmenjadi8,62,7,26,7,85,8,67dan7,29.NilaipHhasilakhirpengolahanairgambutsemua,masukdalamstandarpHairbersihyangmempunyairentang6,5–9.
Deskripsi alat pengolah air gambut skala rumah tangga sebagaiberikut:A. Nama alat:AlatPengolahAirGambut Skala Rumah tanggaB. Fungsi alat: Menjernihkan air gambut denganmetodekoagulasi-filtrasi skala kecil (rumah tangga).C.Bahan:1.Bakairplastikkapasitas50literdengankeran penguras endapan.2. Motor listrik (sewing machine) kapasitas50/60Hz,100wattsebagaipengaduk.3. Pompa air kecil (skala aquarium) daya tarik 3 meter.4. Botol galon air isi ulang kapasitas 19 liter.5. Pipa ukuran Ø 4 inci panjang 100 cm untuk saringan (daridasarpipakerikil30cm,spons2,5cm,pasir60cm dansponsfilter2,5cm).Dilengkapidengan clean out Ø 2 inci terletak di bagian atas dan bawah serta plug pembuangan kotoran Ø ½ inci.6.PipaukuranØ3incipanjang80cmyangberisiarang aktifsetinggi70cmdansponsfilterdibagianatas. Dilengkapi dengan clean out Ø 2 inci terletak di bagian atas dan bawah.7.Asesorislainnyakeran1buah,dopØ4incidanØ3inci,stopkeran1buah,dratluardandratdalam,pipa½ inci sebagai penghubung aliran air.8.Rangkabajasikupenopangalatsetinggi173cm.
D. Cara Kerja :Pengolahan air gambut dengan menggunakan alat pengolah air bersih. Tutup semua keran (keran 1 dan 2) dan plug pembuangan clean out (CO)(1,2,3,4,dan5).Masukkan air gambut sebanyak 50 liter ke dalam bak koagulasi kemudian dicampurkan kapur dengan dosis 250 mg/liter kemu-dian ditambahkan liat
masing-masingperlakuandengandosis0g/l,2,5g/l,5g/l,7,5g/ldan10g/l.Dilanjutkandenganpengadukandengan baling-baling yang digerakkan oleh motor listrik pada bak koagulasi selama 10 menit setelah itu larutan dibiarkanselama45menituntukmengendapkanflok-flokyang terbentuk. Buka plug pembuangan 1 (CO1) untuk membuangendapandantutupkembali,pompakanairkebotol galon setelah penuh buka stop keran yang meng-hubungkanantaragallondenganpipapenyaring(filter-ing),tunggudalam10menitkeran2dapatdibukadanairbersih dihasilkan. Ulangi kerja tersebut untuk menambah volume.Untuktiapkalipergantianperlakuanairgambutmaka keran 1 dapat dibuka untuk mengeluarkan endapan padapipafiltrasi(pipa1).
Inovasi
DESKRIPSI ALAT
45
Edisi III, 2010
Tidak dapat dipungkiri saat ini, krisis air bersih tengah mengancam peradaban manusia. Perubahan iklim akibat pemanasan global telah membuat ketersediaan air di seantero dunia kian
menyusut. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan, sekitar 1,9 miliar warga Asia dan Afrika dalam beberapa dekade mendatang bakal mengalami krisis air. Itu berarti kehidupan umat manusia berada dalam ancaman.
Krisis air merupakan puncak dari semua krisis sosial dan alam. Betapa tidak, air adalah hal yang paling utama bagi kehidupan manusia di planet bumi. “Ketersediaan air telah menurun secara drastis pada tingkat tidak berkesinambungan,” ujar Dirjen UNESCO, Koichiro Matsuura, dalam sebuah kesempatan, akhir April lalu.
Dua dekade mendatang, ketersediaan air akan menurun hingga sepertiga dari saat ini. Kerusakan lingkungan yang kian meluas membuat semua negara di dunia berada dalam ancaman. Tak akan ada bagian dari bumi ini yang terbebas dari krisis air. Ketahanan pangan dunia pun terancam.
Di tengah ancaman krisis air dunia itu, berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dunia. Syariat Islam ternyata mampu menjadi salah satu solusi penting bagi penyediaan air bersih. Adalah sebuah perusahaan konsorsium berbendera Inggris dan Swiss yang mencoba menjadikan syariat Islam
sebagai jawaban atas krisis air tersebut. Untuk pertama kalinya, konsorsium itu meluncurkan dana investasi penyediaan air bersih yang menerapkan prinsip syariat Islam.
Proyek itu diluncurkan di tengah tingginya kebutuhan air bersih di dunia. ‘’Bergabung dengan Gatehouse Bank--bank Islam yang berbasis di Inggris--kami menjadi mitra yang kompeten dan telah dikenal untuk meluncurkan Islamic Finance Water Strategy,” tutur Sander van Eijkern, CEO Sustainable Assets Management (SAM)).
Dana investasi itu menawarkan pinjaman jangka panjang bagi investor yang bergerak di bidang industri air. Yang menarik, dana pinjaman tak menggunakan sistem bunga, namun lewat bagi hasil. Islam memang mengharamkan riba. Karena itu, tak memberlakukan sistem bunga dalam pemberian pinjaman. Selain itu, sistem keuangan dan perbankan syariah juga tak akan memberikan pinjaman untuk investasi di industri yang diharamkan agama Islam, seperti alkohol, perjudian, pornografi, serta hal yang berkaitan dengan babi.
“Dana investasi syariah merupakan strategi untuk menarik minat investor di bidang indutri air bersih yang berorientasi jangka panjang dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah,’’ papar Eijkern seperti dikutip Islamonline.net. Lembaga ini akan membidik investor dari lembaga-lembaga Islam. Menurut dia, SAM yang telah mengelola 1,5 miliar dana investasi air akan menjadi pengelola aset.
Sedangkan, Gatehouse akan menjadi perusahaan pelapis yang menjamin kesepakatan investasi
dikelola dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kolaborasi Islamic Finance Water Strategy itu mendorong perusahaan-perusahaan untuk bergerak dalam bidang penyediaan air bersih melalui teknologi, produk, dan pelayanan bagi penyediaan air bersih yang sesuai dengan syariat.
Dana investasi ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan krisis air yang dialami negara-negara di dunia. Berdasarkan data badan kesehatan dunia, saat ini sekitar 1,1 miliar penduduk dunia hidup tanpa dukungan air bersih. Dana investasi air yang sesuai syariat merupakan gabungan dari manajemen keuangan dengan ekonomi syariat. (eko)
Sisi Lain
Syariat Islam sebagai Solusi
46
Reportase
Sebuah dialog publik bertajuk Waspadai Konflik Air Minum digelar di Fakultas Tehnik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, akhir September lalu.
Sejumlah pakar yang hadir pada dialog digelar di Ruang Serba Guna Masjid Salman ITB tersebut menilai peme-rintah daerah perlu mengantisipasi terjadinya konflik yang disebabkan oleh air minum karena krisis air akan terjadi semakin luas dalam beberapa tahun kedepan di Indonesia.
Pembicara dalam acara itu, Indrayanto Susilo dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan persoalan air minum dimasa depan perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan konflik vertikal dan horisontal. Pembangunan berbasis hak merupakan kerangka kerja konseptual untuk pem-bangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di daerah yang berdasar pada standar interna-sional hak asasi manusia dan dalam pelaksanaannya mem-promosikan dan melindungi hak asasi manusia.
Menurut Indrayanto, pemerintah daerah perlu lebih
melihat pendekatan berbasis hak atas air minum sebagai sebuah hak asasi manusia yang terintegrasi dengan nor-ma, standar dan prinsip yang ada dalam sistem hukum nasional dan internasional hak asasi manusia kedalam pe-rencanaan, kebijakan dan proses pembangunan di daerah. Pembangunan berbasis hak juga meliputi persamaan dan keadilan, akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi.
Kondisi Indonesia Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga Indonesia sudah mempunyai kewajiban secara formal untuk me-nerapkan kovenan tersebut berserta seluruh dokumen pen-dukungnya. Berkaitan dengan hak atas air, sesuai de ngan komentar umum PBB Nomor 15, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air. Sedangkan kebijakan yang khusus mengatur tentang sumberdaya air adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 tentang Sumberdaya Air. Pasal 5 UU Nomor 7 tentang Sumberdaya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok mini-mal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Re-publik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas air ternyata dibatasi
Dialog Publik Waspadai Konflik Air
Konflik Air Minum Perlu Diantisipasi Pemerintah Daerah
ISTIMEWA
47
Edisi III, 2010
hanya terbatas pada kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air. Pembatasan jaminan peme nuhan hak tersebut ber-tentangan dengan komentar umum PBB Nomor 15 yang menyatakan bahwa kecukupan hak atas air tidak bisa diterje-mahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi.
Selanjutnya pada pasal 6 dinyatakan sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut sehu-bungan dengan hak atas air dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memper-oleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sum-ber daya air.
Selain itu, masyarakat juga berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air; dan berani menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
“Disamping itu, masyarakat dapat mengajukan laporan dan pengaduan ke-pada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya ,”tukas Indrayanto.
Sedangkan pembicara lain dalam dialog tersebut, Imran Hasibuan mengatakan air berhubungan dengan hak hidup sesesorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air meru-pakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup ma-nusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air beserta seluruh peraturan pelak-sananya merupakan penjabaran lebih lanjut atas konsepsi hak atas air di tingkat nasional. Walaupun pada tataran normatif sudah cu-kup lengkap tetapi konflik-konflik atas sumberdaya air di masyarakat masih merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri.
Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keber-langsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang ke-beradaannya merupakan amanat
dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga se-harusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama.
Air berhubungan dengan hak hidup sesesorang se-hingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerang-ka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.
Demi perlindungan tersebut perlu di-positifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda
publik atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.
“Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus meng-hormati (to respect ), melindungi (to protect ), dan memenuhinya (to fulfill),” ujar Imran Hasudungan dari Green Peace Indonesia. (eko)
Air berhubungan dengan hak hidup
sesesorang sehingga air tidak
bisa dilepaskan dalam kerangka
hak asasi manusia.
ISTIMEWA
48
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tersirat mengamanatkan bahwa sektor pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan salah satu urusan wajib daerah (Pasal 14 ayat (1)). Selanjutnya Pemerintah Indonesia menetapkan sasaran Pembangunan Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2004-2009 yang dalam kenyataannya belum bisa tercapai dan tetap ditargetkan dalam RPJMN tahun 2010-2014, diantaranya yaitu tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014 (perpipaan 32% dan non-perpipaan 38%), terciptanya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tahun 2014, tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga, menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.
Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target tersebut, berikut ini beberapa program AMPL yang telah dan sedang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah diantaranya PAMSIMAS, Sanimas, DAK Air Minum dan DAK Sanitasi, Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), STBM (Plan Indonesia) serta program-program yang dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten.
Oleh karena itu, diperlukan upaya konsolidasi dan sinergi untuk memastikan seluruh program tersebut berada dalam satu arah dan berkontribusi terhadap kinerja pembangunan AMPL dalam rangka pencapaian target nasional. Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga koordinasi pembangunan AMPL diharapkan dapat mengambil peran dalam upaya sinergi
antar program AMPL.
Pada tanggal 19 – 21 Oktober 2010 bertempat di Gumaya Tower Hotel Semarang telah diselenggarakan Lokakarya Konsolidasi dan Sinergi Pembangunan AMPL Provinsi Jawa Tengah. Acara ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari unsur Pokja AMPL Provinsi, Pokja AMPL Kab/Kota, proyek terkait AMPL (PAMSIMAS, PPSP, PNPM), LSM (Plan Indonesia) dan unsur legislatif provinsi yang relevan.
Dalam sambutannya, Maraita Listyasari mewakili Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas menjelaskan bahwa lokakarya seperti ini sangat penting
juga bagi Pemerintah Pusat seiring dengan pencapaian dari tujuan MDG’s. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat terkait dengan AMPL. Beberapa upaya yang dilakukan, baik fisik maupun non-fisik diharapkan dapat bersinergi sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Berbicara mengenai AMPL masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum dan sanitasi dasar guna memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan sehingga hal tersebut jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Fakta lain menunjukkan masih ada masyarakat yang menderita penyakit yang disebabkan oleh buruknya akses sanitasi, seperti diare, malaria. Kondisi ini sangat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penyakit diare sebenarnya dapat ditekan sedemikian rupa, salah satu caranya dengan pelayanan air minum dan sanitasi dasar. Data yang ada sekarang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang membuang hajat di sungai, atau sumber-sumber drainase yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Masih dijumpai pula sarana air minum dan sanitasi yang belum difungsikan seoptimal mungkin. Kurangnya akses air minum dan sanitasi akan mempengaruhi aspek lainnya. Begitu pula terkait dengan peran gender akan semakin memperberat tugas dari perempuan.
Demikian besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh air minum dan sanitasi dasar yang terkait juga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Jawa Tengah bersama-sama berupaya untuk mengatasi masalah tersebut.
Lokakarya Konsolidasi dan Sinergi Pembangunan AMPL Provinsi Jawa Tengah
Reportase
POKJA
49
Edisi III, 2010
Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir merupakan salah satu butir dari pe-rilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang
dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Upaya mudah dan murah ini akan menghindarkan ma-nusia dari sejumlah penyakit menular yang dapat secara langsung terpapar pada tubuh manusia seperti kolera, tifus, hingga flu burung.
“Sayangnya baru tiga persen penduduk Indonesia menyadari hal ini dan membiasakan diri mencuci tangan meggunakan sabun,” ujar Direktur Pemberantasan Penya-kit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Dr HM Subuh, MPPM ketika membuka seminar dan workshop dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ke 3.
Berbicara dalam seminar tersebut Kepala Pusat Pro-mosi Kesehatan, dr Lily S Sulistyowati, Direktur Penye-hatan Lingkungan, drh Wilfried Hasiholan Purba dan Ketua Komnas Perlindungan Anak dan psikolog, Dr Seto Mulyadi. Acara dipandu dr Lula Kamal yang juga se-orang artis. Seminar diikuti oleh 100 guru Sekolah Dasar
dan Madrasah di DKI Jakarta. Dalam paparannya, dr Lily S Sulistyowati menyebut-
kan berdasarkan hasil penelitian global menunjukkan, cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan angka ke-jadian diare hingga 47 persen. Ini penting karena setiap tahun masih ada kejadian luar biasa diare atau muntaber yang menelan korban jiwa. Unicef melaporkan, setiap detik satu anak meninggal karena diare.
Survei Health Service Program (2006) menunjuk-kan, sabun telah ada di hampir setiap rumah tangga Indonesia. Namun, baru tiga persen yang mengguna-kan sabun untuk mencuci tangan.
Dari semua responden, hanya 12 persen yang mencuci tangan setelah buang air besar, 9 persen se-telah membersihkan kotoran bayi, 14 persen sebelum makan, 7 persen sebelum memberi makan bayi, dan 6 persen sebelum memasak.
Upaya untuk mengampanyekan pentingnya cuci tangan dengan sabun terus digalakkan. Tahun ini, di-pastikan pada 15 Oktober 2010, lebih dari 70 negara mengadakan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Peringatan ini berawal dari seruan yang di-sampaikan PBB untuk meningkatkan praktik higienitas dan sanitasi kepada semua penduduk di seantero dunia.
Sedangkan psikolog Anak, Seto Mulyadi pada ke-sempatan tersebut menegaskan bahwa membiasakan diri untuk mencuci tangan memakai sabun berarti
mengajarkan anak-anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini. Pola hidup bersih dan sehat akan tertanam kuat dalam diri pribadi anak-anak dan anggota keluarga lainnya.
Mengingat kegiatan ini merupakan upaya pember-dayaan masyarakat untuk hidup sehat, sudah sepatutnya mendapat perhatian dan dukungan. Karena itu, di-harapkan partisipasi aktif masyarakat untuk menerapkan langkah kecil mempraktikkan PHBS agar anak Indonesia dapat hidup lebih sehat.
Sementara itu, Penelitian Cochrane Library Jour-nal 2007 menyebutkan, cuci tangan dengan sabun merupakan cara seder-
Workshop HCTPS Bagi Guru SD DKI Jakarta
Baru Tiga Persen Masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun
POKJA
50
Reportase
hana dan murah untuk menahan virus ISPA dan pan-demi flu. Kajian terhadap 51 riset di Inggris yang dipub-likasikan dalam British Medical Journal 2007 menguatkan hal tersebut. Disebutkan bahwa cuci tangan lebih efektif dibanding obat dan vaksin untuk menghentikan flu.
Meski mencuci tangan dengan sabun telah dilaku-kan banyak orang, namun baru sedikit yang melakukan aktivitas tersebut pada saat-saat penting, seperti setelah menggunakan toilet, setelah membersihkan kotoran anak, dan sebelum menangani makanan.
“Mencuci tangan dengan air dan sabun terutama pada saat-saat penting, yaitu setelah buang air dan sebelum memegang makanan membantu mengurangi risiko terke-na diare lebih dari 40 persen dan infeksi saluran perna-pasan hampir 25 persen,” ujar Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia, Angela Kearney.
Menurut laporan Situasi Anak-anak Dunia tahun
2009 yang dikeluarkan Unicef, hanya separuh penduduk Indonesia memiliki akses kepada sanitasi yang memadai di pedesaan. Bahkan hanya sekitar sepertiganya – se-hingga mereka rentan terhadap diare dan penyakit yang ditularkan melalui air. Berbagai survei juga menemukan bahwa kebiasaan cuci tangan pakai sabun masyarakat In-donesia masih rendah.
Indonesia merupakan salah satu dari 85 negara di dunia yang melakukan cuci tangan pakai sabun secara serentak hari ini. Dengan tema “Tangan Bersih Selamat-kan Kehidupan”. Menurut rencana akan digelar berbagai acara kampanye peringatan HCTPS dengan memobilisasi ribuan anak di seluruh Indonesia. Anak-anak dinilai seba-gai agen perubahan yang sangat penting di Indonesia.
Selain lebih terbuka pada ide-ide baru, anak-anak juga dapat menjadi pembawa pesan yang efektif kepada kelu-arga serta lingkungan di sekitarnya. EK0
Krisis air minum, kini sedang terjadi. Di sebagian daerah, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air minum. Sebagai gantinya,
menggunakan air yang tak layak konsumsi menjadi pilihan terakhir. Diperkirakan masalah seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada upaya serius untuk mengatasinya. Pertanyaannya, akankah masalah ini semakin parah seiring dengan perjalanan waktu?
Peringatan akan bahaya krisis air minum bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Sebelumnya, para ahli sudah memperkirakan bahwa dunia saat ini sudah masuk pada tahap genting dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum. Dunia mengalami krisis air minum. Bahkan diperkirakan satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapat sarana
sanitasi yang layak. Sepanjang tahun 2010 ini
diprediksi sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah.
Air minum merupakan salah satu kebutuhan terpenting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Karena itu, masalah ini sudah sewajarnya mendapatkan suatu proteksi yang harus memadai bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. Dunia harus serius dalam mengatasinya.
“Indonesia tidak terlepas dari masalah yang sama. Bahkan diperkirakan sebagian provinsi akan mengalami krisis air minum yang sangat hebat pada tahun 2015. Penyebabnya adalah sumber air minum semakin berkurang. Kemudian kualitas yang semakin menurun. Masalah tersebut akan semakin berat jika tidak ditangani sedini mungkin,” ujar Hamong Santono dari Koalisi Masyarakat Hak Atas Air yang diselenggarakan oleh Harian Sinar Harapan di Jakarta, awal Oktober lalu.Sekali lagi masalah yang berhubungan
“Politik Air” Harus Jadi Perhatian Pemerintah Daerah
. . . manajemen pengelolaan
air minum oleh pemerintah daerah
harus matang membangun
“politik air” yang sehat di Indonesia.
51
Edisi III, 2010
dengan hajat hidup orang banyak hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah dalam setiap kebijakannya. Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Artinya, air menjadi komponen utama untuk memenuhi hajat hidup manusia. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan air merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, kecukupan dan keterjangkauan air minum mencakup pemerataan distribusi dan mutu yang terjamin.
Dalam konteks itulah, lanjut Hamong masyarakat menaruh harapan pada pemerintah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah ini agar dengan jeli mengurusi penyediaan air minum bagi masyarakat. Namun, tentunya tugas ini tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah berikut instansi terkaitnya. Kita semua turut berperan didalamnya.
Pemerintah perlu menata regulasi yang membuat manajemen pengelolaan air minum bisa tertata dengan rapi. Disaat yang sama juga harus ada proteksi terhadap sumber-sumber air minum. Jalur distribusi harus dijaga dan ditata dengan baik.
Untuk itulah manajemen pengelolaan air minum oleh pemerintah daerah harus matang membangun “politik air” yang sehat di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana politik air tersebut bisa diimplementasikan dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia. Misalnya soal penebangan hutan yang berakibat pada berkurangnya volume sumber mata air. Demikian juga dengan kampanye penghematan pemakaian air minum yang
mesti digalakkan lagi.Berkaitan dengan itu, kebijakan makro dan kebijakan
operasional pengelolaan kebutuhan air minum dipadukan dengan pengembangan sistem produksi dan distribusi air minum, menjadi hal yang mutlak dikerjakan. Kemampuan untuk memproduksi air minum terutama melalui peningkatan kualitas produk yang didukung oleh teknologi canggih dan kelembagaan yang bermutu, yang kesemuanya harus diperhatikan dengan seksama.
Peningkatan dalam jumlah dan jenis air minum yang dibutuhkan, baik karena pengaruh pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran kesehatan, dan pengaruh globalisasi akan menjadi mata rantai yang tak pernah putus dalam kehidupan manusia. Pada saat yang sama kompetisi penggunaan lahan sumber air dan prinsip keunggulan komparatif semakin terbatas dan terpusat. “Hal ini menjadikan penyelesaian masalah ketersediaan air minum tidak dapat lagi ditunda. Kita harus bangkit. Gerakan cepat harus dilakukan guna menyelamatkan hantaman krisis air minum tersebut,” kata Hamong.
MDGs dan Akses Air minumSementara itu, dosen senior lingkungan ITB, Dr TP
Damanhuri menegaskan sesuai agenda utama MDGs, penandatanganan Deklarasi Milenium merupakan bentuk penegasan dan komitmen pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi kemiskinan masalah air minum termasuk persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dari
ISTIMEWA
52
delapan tujuan Deklarasi Milenium, yang terkait erat dengan tema HAD tahun ini adalah tujuan ketujuh, yaitu menjamin adanya daya dukung lingkungan hidup.
Terdapat tiga target utama dari tujuan ketujuh. Pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Kedua, mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat pada 2015. Ketiga, mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh pada 2020. Masalah pengurangan emisi juga menjadi agenda yang harus diatasi dalam tujuan ketujuh ini.
“Masalahnya, apakah target yang menyangkut penyediaan akses terhadap air minum yang sehat dapat dicapai? Tentu bukan hal yang mudah untuk menjawabnya. Walaupun telah berkomitmen terhadap tujuan MDGs, pencapaian untuk mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak mempunyai akses terhadap air minum yang layak dan sanitasi pada 2015 tampaknya masih sulit untuk diwujudkan” tukasnya. Meskipun ada kemajuan dalam pencapaian target, sebagian besar dari populasi manusia yang ada masih belum terjangkau dengan air minum. Sebanyak 1,1 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses terhadap persediaan air yang terlindungi dan lebih dari 2,6 miliar tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.
Untuk Indonesia, kondisinya juga setali tiga uang. Pasalnya, yang terjadi selama ini, perusakan lingkungan jauh lebih cepat dan lebih sering terjadi dibandingkan upaya rehabilitasinya. Kita membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, sementara hampir setiap jam terjadi pembalakan dan penebangan hutan.
Pencemaran air sungai akibat limbah rumah tangga dan limbah industri juga lebih sering terjadi. Setiap harinya, dua juta ton sampah dan limbah lainnya mengalir ke perairan dunia. Belum lagi, intensitas urbanisasi yang lebih tinggi daripada kemampuan kota-kota menampung para pendatang. Akibatnya, muncul daerah-daerah kumuh yang tidak bisa segera diatasi.
Akses terhadap air minum sering juga terhambat oleh kondisi infrastruktur jalan yang kurang
baik. Kita sering lupa, upaya
pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda utama MDGs sering kali tidak dikaitkan dengan keberadaan infrastruktur. Padahal, keduanya sangat terkait erat. Jika pembangunan infrastruktur lambat, pencapaian agenda MDGs, juga menjadi lambat. Banyak orang tentu tidak bisa ke puskesmas jika jalannya rusak. Upaya mengurangi tingkat kematian ibu dan anak juga akan sulit tercapai bila tidak didukung oleh sanitasi yang baik dan akses terhadap air minum.
Harmonisasi kewenanganAir merupakan sumber kehidupan di dunia ini. Kuali-
tas kehidupan manusia sangat tergantung dari kualitas air. Kualitas air yang baik dapat mendukung ekosistem yang sehat dan akhirnya mengarah pada peningkatan kese hatan manusia. Sebaliknya, kualitas air yang buruk juga akan sangat memengaruhi lingkungan hidup dan ke-sehatan manusia. Karena itulah, seiring dengan semakin terancamnya kualitas air, sejak tahun 1992 PBB mene-
tapkan peringatan Hari Air Dunia (HAD) setiap tanggal 22 Maret. Penetapan HAD tentu bertujuan untuk mendorong dan me-ningkatkan kesadaran serta kepedulian akan perlunya upaya bersama dari seluruh kom-ponen bangsa, bahkan dunia untuk bersama-sama memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air (SDA) secara berkelanjutan.
Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, peringatan HAD tentu harus dijadikan mo-mentum yang tepat untuk meningkatkan penyediaan akses air minum bagi masyarakat. Untuk hal tersebut, belakangan ini apa yang
dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum telah menunjuk-kan arah perbaikan. Contohnya, soal pengelolaan sungai yang tidak lagi dilakukan sepotong-sepotong, tapi sudah lebih integral dan komprehensif. Kini, Kementerian Peker-jaan Umum tidak hanya mengurus badan sungai, tapi juga sudah fokus pada bantaran aliran sungai yang didiami masyarakat. Bahkan, Ditjen Cipta Karya juga telah intensif memfasilitasi usaha-usaha masyarakat yang ingin berparti-sipasi dalam penyediaan akses terhadap air minum.
Namun, hal itu saja tentu belum cukup. Kementerian Pekerjaan Umum harus menjadi kementerian terde-pan dalam hal mengembangkan kebijakan manajemen air yang berkelanjutan. Untuk hal tersebut, salah satu langkah mendesak yang harus dilakukan adalah upaya harmonisasi kewenangan beberapa instansi pemerintah, seper ti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Da-lam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas.(Eko)
1,1 miliar orang di seluruh
dunia masih tidak memiliki
akses terhadap persediaan air.
Reportase
53
Edisi III, 2010
Pada hari Senin 4 Oktober 2010 dilaksanakan Pertemuan Dialog antara Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan Jejaring AMPL di Ruang
SS-1 Bappenas dengan tema Diskusi Sinergi Program Je-jaring AMPL dengan GBCI. Pada kesempatan ini diskusi dibuka oleh Syarif Puradimadja , perwakilan dari Jejaring AMPL dan Ibu Nani perwakilan dari GBCI. Kegiatan ini dilakukan melalui presentasi dari beberapa narasumber sebagai stakeholder di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
Kesempatan pertama untuk presentasi diberikan kepada Ir.Ignesjz Kemalawarta MBA selaku Direktur PT Bumi Serpong Damai/Ketua Badan Pendidikan – Pelati-han DPP REI dengan topik “Green Property Develop-ment Mengacu Pada Greenship Rating GBCI dan Kaitan dengan Air Bersih dan Sanitasi”. Beliau menjelaskan bahwa penerapan konsep “green building” dalam pengembangan properti melalui tahapan merancang, membangun dan mengoperasikan bangunan/lingkungan akan ikut berperan dalam mengurangi pemanasan global/mengurangi kerusakan bumi. Beberapa perhatian yang perlu dicatat dari sektor properti antara lain:
* Kontribusi emisi CO2 di sektor bangunan terbesar dibanding industri dan transportasi.
* Konsumsi energi dalam bangunan 30-40%.* Harus ada effort di sektor bangunan/ properti untuk
mengurangi pemanasan global dan menghindari kerusa-kan bumi dimasa datang.
Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma di dalam pengembangan properti dari yang lama yaitu Qual-ity – Time – Cost (Pola Tiga) menjadi pola baru yaitu Quality – Time – Cost - Healthy And Save - Environment/Sustainable (Pola Lima). Salah satu cara untuk menca-pai hal tersebut adalah dengan menerapkan 8 (delapan) “greenship rating” sebagai acuan pengembangan dengan konsep green building yaitu: pemilihan dan design site; desain bangunan; spesifikasi bangunan; design mekanikal-elektrikal; spesifikasi mekanikal elektrikal; rencana kerja dan syarat kontraktor; property/estate management; serta additional effort (new building-existing building-gedung terhuni-kawasan perumahan).
Topik berikutnya yang menarik untuk dibahas yaitu
mengenai Prinsip Dasar dan Teknis Rapergub (Rancang-an Peraturan Gubernur) Bangunan Ramah Lingkungan yang dibawakan oleh perwakilan dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan - DKI Jakarta. Pada dasarnya tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai “Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan”. Namun demikian, terdapat beberapa kriteria yang diadopsi dalam Rapergud ini baik itu untuk bangunan eksisting ataupun bangunan baru (rencana). Kriteria tersebut antara lain: pengelolaan bangunan masa konstruksi, penggunaan lahan, pemanfaatan energi listrik, pemanfaatan dan konservasi air, serta kualitas udara dan kenyamanan ru-angan bagi bangunan baru. Sementara untuk bangunan eksisting, kriteria yang dipilih antara lain: pengelolaan
bangunan masa operasional, pemanfaatan energi listrik, pemanfaatan dan konservasi air, serta kualitas udara dan kenyamanan ruangan.
Beliau menjelaskan bahwa hubungan antara perizinan di pemerintah dengan sertifikat green building yaitu pera-turan gubernur ini kelak menjadi mandatory yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang diaturnya, sementara sertifikat green building bersifat voluntary.
Sasaran untuk pemberlakuan Pergub tersebut akan disesuaikan dengan kriteria berupa luas lantai dan jumlah bangunan yang akan menjadi objek pemberlakuan Per-gub. Hingga saat ini, masih dilakukan pembahasan untuk mematangkan Rapergub tersebut.
Pembahasan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dari perwakilan PT.Surya Toto Indonesia seba-gai wakil dari dunia usaha. Inovasi terus dilakukan dari tahun ketahun oleh dunia usaha agar konsumsi air untuk toilet flush menggunakan sedikit air. Hal ini juga dilakukan untuk produk-produk lain seperti faucets (kran), shower (pancuran), dan shower spray.
(Adhit)
Sinergi Program Jejaring AMPL dengan GBCI
POKJA
54
Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru,karenaairmenutupi3/4permukaanbumi.Tetapitidakjarangpulakitamengalamikesu-litanmendapatkanairbersih,terutamasaat
musim kemarau disaat air umur mulai berubah warna atau berbau.Ironismemang,tapiitulahkenyataannya.Yangpastikitaharusselaluoptimis.Sekalipunairsumuratausumberairlainnyayangkitamilikimulaimenjadikeruh,kotoratau-punberbau,selamakuantitasnyamasihbanyakkitamasihdapat berupaya merubah/menjernihkan air keruh/kotor tersebut menjadi air bersih yang layak pakai.
Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakanuntukmendapatkanairbersih,dancarayangpalingmudah dan paling umum digunakan adalah dengan mem-buatsaringanair,danbagikitamungkinyangpalingtepatadalah membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Perludiperhatikan,bahwaairbersihyangdihasilkandariprosespenyaringanairsecarasederhanatersebuttidakdapat menghilangkan sepenuhnya garam yang terlarut di dalamair.Gunakandestilasisederhanauntukmenghasilkanairyangtidakmengandunggaram.Saransaya,sebelumandamembeli alat/mesin penjernih air yang harganya ratusan ribusampaijutaanrupiah,andamencobaterlebihdahulubeberapaalternatifcarasederhanadanmudahgunamenda-patkan air bersih dengan cara mem-pergunakanfilterair/penyaringanair:
1. Saringan Kain Katun.Pembuatan saringan air dengan
menggunakan kain katun merupa-kan teknik penyaringan yang paling sederhana/mudah. Air keruh disa-ring dengan menggunakan kain ka-tun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Air hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kain
yang digunakan.
2. Saringan KapasTeknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih
baikdaritekniksebelumnya.Sepertihalnyapenyaringandengankainkatun,penyaringandengankapasjugadapatmembersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada
dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kera-patan kapas yang digunakan.
3. AerasiAerasi merupakan proses pen-
jernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikan-
nyaoksigenkedalamairmakazat-zatsepertikarbondiok-sidasertahidrogensulfidadanmetanayangmempengaruhirasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itupartikelmineralyangterlarutdalamairsepertibesidanmangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisanendapanyangnantinyadapatdihilangkanmelaluiprosessedimentasiataufiltrasi.
4. Saringan Pasir Lambat (SPL)Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang
dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan denganjalanmenyaringairbakumelewatilapisanpasirter-lebihdahulubarukemudianmelewatilapisankerikil.UntukketeranganlebihlanjutdapattemukanpadaartikelSaringanPasir Lambat (SPL).
5. Saringan Pasir Cepat (SPC)Saringanpasircepatsepertihalnyasaringanpasirlam-
bat,terdiriataslapisanpasirpadabagianatasdankerikilpada bagian bawah. Tetapi arah penyaringan air terbalik bila dibandingkandenganSaringanPasirLambat,yaknidaribawahke atas (up flow). Air bersih didapatkan dengan jalan menya-ringairbakumelewatilapisankerikilterlebihdahulubaruke-mudianmelewatilapisanpasir.UntukketeranganlebihlanjutdapattemukanpadaartikelSaringanPasirCepat(SPC).
6. Gravity-Fed Filtering SystemGravity-Fed Filtering System merupakan gabung-
an dari Saringan Pasir Cepat (SPC) dan Saringan Pasir Lambat (SPL). Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama-tama air disaring menggunakan Saringan Pasir Cepat (SPC). Air hasil penyaringan tersebut kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan Saringan Pasir Lambat. Dengan dua kali penyaringan tersebut diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebihbaik.Untukmengantisipasidebitairhasil penyaringan yang keluar dari Saring-
anPasirCepat,dapatdigu-nakanbeberapa/multiSaringan Pasir Lambat.
Panduan
Sejumlah Teknologi Mendapatkan Air Bersih
55
Edisi III, 2010Info CD
Kebutuhan Air Bersih: Solusi Pendanaan Melalui Mikro KreditVCDinidibuatolehImajiBumiProductio,tahun2010yangditerbitkanolehESPUsAid.DVDfilmdokumenterkreditmikroiniterdiridari3versi.Pertama,versitoolkitKMSA,berdurasi20menit,ditujukanuntukpromosiKMSAdansekaligusmenginspirasimerekatermasukpada kelompok stakeholderpembuatkebijakansepertiPDAM,PerusahaanSwastaPengelolaAirMinum,Bank,LembagaPembiayaan,LembagaKeuanganMikro(LKM)danjajaranPemerintahDaerahsepertiWalikota,Bupati,DPRD.Kedua,bersimasyarakatKMSA,berdurasi20menit,ditujukanuntukpromosidanmenginspirasiparamasyarakat pengguna air terutama golongan masyarakat
berpenghasilan rendah yang mendapat pelayanan air PDAM. Danketigaversitriller,durasi 5 menit adalah kumpulan cuplikan dari kedua versi tersebut diatas. DVD filmdokumentermikrokredit ini juga dapat didownload melalui websiteESP:www.esp.or.id.
Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia.Dalam rangka pelaksanaan Regional Initiative on Environment and Health di Indonesia adalah mengidentifikasibeberapakegiatanbest practices. Kegiatanbest practices yang dimaksud khususnya yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah berbasis
masyarakat untuk skala rumahtangga,lingkungan
maupun kota. Beberapa kegiatan yang berhasil tersebutantaralain:pengolahan sampah didesaSukunan,kabupaten Sleman,pemilahansampah di kabupatenSragen,
pengomposan sampah
dikelurahanCibangkong,Bandungdanpengelolaansampah terpadu di SMAN 13 Jakarta serta beberapa lainnya. VCD ini merupakan bentuk softcopy dari buku KisahSuksesPengelolaanPersampahanDiBerbagaiWilayahIndonesia:Best Practices of Solid Waste Management in Indonesia. Dibuat oleh Ditjen Cipta Karyatahun2010.
Video Promosi Strategi Sanitasi Kota. DVDiniberisimengenaiStrategiSanitasiKotadikotaDenpasar,Yogyakarta,Blitar,Payakumbuh,Medan,dan Bali. Dibuat tahun 2010 oleh TTPS (Tim Teknis PembangunanSanitasi),berdurasi37menit.Dalamdvd ini diceritakan kota yang bersih dan sehat adalah dambaansetiaporang,namunbelumsemuakotamampu mewujudkannya. Sebagian memilih membuang sampah sembarangan,buangair besar ditempat terbuka atau di jamban yang tidakmemenuhisyaratkesehatan,sehingga pencemaran tersebar kemana-mana.
VCD, kelestarian alam, lagu, penyuluhan lingkungan, album tembang lingkungan berisi 12 lagu bertema air. Airsumberpenghidupan,hijaukanhutandanjangandicemari adalah sejumlah lagu yang dikemas dengan aransemen popular dan sangat enak didengar. Pesan dari penyuluhan adalah hargai air yang telah diberikan Tuhan yang merupakan salah satu bait dalam lagu di
Album Tembang Lingkungan Vol.2 terbitan Perum Jasa Tirta I Malang. VCD ini sekaligus sebagai program penyuluhan lingkungan dan diedarkan untuk kalangan sendiri.
56
Info Buku
Buku Saku Monitoring dan Evaluasi PAMRT (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)Penerbit USAID, Jakarta, Tahun 2010. Tebal 25 halaman
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam sebuah program untuk mem-beri masukan mengenai perubahan yang terjadi,sepertiketidaksesuaianrencanaprogram dengan keadaan lapangan atau bila terjadi beberapa perubahan di lapang-an. Memang rencana program adalah pedo-manpelaksanaandilapangan,tetapibukanberartitidakbisadisesuaikandikemudianhari bila diperlukan. Monitoring dan evalu-asi adalah cara untuk mendeteksi apakah rencanaprogramperludimodifikasi.Moni-toring dan evaluasi (monev) bukan solusi masalahprogram,melainkanalatyangbisa dimanfaatkan untuk mencari solusi. Monitoring adalah pengumpulan dan anali-sis data secara berkala selama program berjalan,untukmeningkatkanefisiensidankeefektifansebuahprogram,berdasarkantargetdanaktifitasyangdirencanakan,sedangkan evaluasi merupakan pemban-dingan antara pencapaian program dengan rencana.Kegiatanmonevdiawalidenganpenjabarantujuanprogram–untukapaprogram dirancang dan apa yang akan di-capai–menjadipencapaianprogram.Bukusakuiniberisihal-halpentingterkaitmoni-toringdanevaluasiPAMRT,meliputilatarbelakang,pengertian,konsep,prosedur,alat,matrikshinggacontohlembarmoni-toring dan evaluasi untuk perilaku pengelo-
laan air minum dalam rumah tangga.
Best Practices NUSSP Mendorong Keber-dayaan Mengatasi Kumuh Perkotaan: Menuju Kota Tanpa Kekumuhan. Penulis Hendarko Rudi Susanto, Penerbit NMC (National Management Consultant) - NUSSP, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Tahun 2009 Tebal 81 halaman
Mengemban amanah yang besar dari para pemangku kepen-tingan,NUSSPtelahmenerapkan sejum-lah program sebagai upaya nyata men-jawab berbagai per-masalahan yang ada. Sedikitnyaadatigakomponen kegiat-
an yang menjadi landasan utama gerak langkahNUSSP.Kesemuanyaberujungpadapemberdayaan dan perubahan paradigma masyarakat guna mencapai kondisi kehidup-an masyarakat yang lebih sejahtera.
Buku ini adalah sepenggal “kisah sukses”programNUSSPdipelbagaidaerah.Beberapa diantaranya berkisah tentang kesuksesan pemberdayaan wanita dalam “kantung”kesetaraangenderyangmasihtebal. Sementara kisah lainnya menceri-takan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang berdampak nyata terhadap pening-katan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar serta kampanye publik untuk perubahan perilaku masyarakat ter-hadap lingkungan perumahan layak huni.
Etika Lingkungan HidupPenulis : A Sonny Keraf, Penerbit: Kompas Gramedia, Jakarta, Tahun 2010. Tebal 425 halaman
LINGKUNGANHIDUP meru-pakan tang-gung jawab semua pen-duduk di bumi ini. Tetapi
mengapa masih banyak pihak-pihak ter-tentu yang mengabaikan bahkan merusak alam ini? Berbagai kasus pencemaran dan kerusakanlaut,hutan,atmosfer,air,tanah,terus bertambah. Ini merupakan perilaku manusiayangtidakbertanggungjawab.Manusia adalah penyebab utama kerusak-an dan pencemaran lingkungan.
Pada dasarnya lingkungan hidup bukan sematasoalteknis,tetapipraktiknyaperludidasarietikadanmoralitasuntukmengatasinya.Untukitulahperlunyaetikaling kungan hidup yang membentengi moral manusia. Buku ini membeberkan persoalanetikalingkunganhidup,termasukmembahaskonsepantroposentrisme,bio-sentrisme,ekosentrisme,hakasasialam,termasuk kaitannya dengan kearifan tradisi-onal dalam mengelola lingkungan hidup.
Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Mi-num dan Sanitasi Berkualitas – PamsimasPengarang : S. Bellafolijani Adimihardja Tahun Terbit : Th. 2009 Penerbit : Jakarta, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2009, 60 ha
Pamsimas adalah kegiatan di bi-dang air minum dan sanitasi yang ditujukan bagi masyarakat ber-penghasilan ren-dah di perdesaan dan pinggiran
perkotaan (peri-urban) dan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.
Implementasi Program Pamsimas telah dimulai pada pertengahan tahun 2008. Saat ini pelaksanaan program Pamsimas telah memasuki tahun kedua. Hasil kegiatan Pam-simas berupa tambahan akses terhadap air minumtelahdapatdinikmatiolehsebagiananggota masyarakat di desa/ kelurahan yang menjadi sasaran program. Seiring dengan hasil yang telah dicapai melalui programPamsimas,makadirasaperluuntuk melakukan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan Pamsimas. Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mendokumentasikan dan merekam hasil-hasil kegiatan Pamsimas.
Buku ini menyajikan informasi umum berupa latar belakang dan gambaran umum Program Pamsimas. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang merupakan hasil kegiatan yang telahdilakukanselamaini,sehinggatampillebih menarik. Buku ini bisa dijadikan seba-gai media kits,diharapkandapatmenjadipanduan informasi umum bagi para pihak yang ingin mengetahui kegiatan Pamsimas.
57
Edisi III, 2010
Woman Human Right Net (WHRNet) www.whrnet.org/docs/issue-water.html
Di dalam situs ini pengunjung dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perempuan dan Privatisasi air. Secara jelas tertulis latar belakang dari dibuatnya tulisan mengenai hal
tersebut, hubungannya dengan hak azasi manusia dan tambahan berbagai alamat-alamat website lain yang dapat mendukung informasi berkaitan dengan tulisan tersebut. Situs ini milik WHRnet yaitu suatu proyek yang dikelola oleh Association for Women’s Rights in Development (AWID).
The Water Quality Information Center (WQIC) www.nal.usda.gov/wqic
Di dalam situs ini terda-pat electronic publications database yang berisikan 1.800 online dokumen seputar masalah air dan pertanian. Disini tersedia CEAP Bibliographies, yaitu bibliografi yang
terdiri atas empat edisi berisikan sekitar 2.400 kutipan. CEAP Bibliografi merupakan program untuk mendu-kung Conservation Effects Assesment Project satu proyek yang mempelajari efek dari konservasi lingkungan da-lam berbagai program konservasi yang dilakukan oleh The United State Department of Agriculture’s (USDA). Resource guide mengenai wetland juga dapat ditemukan dalam situs ini. The Water Quality Information Center (WQIC yang didirikan pada tahun 1990 dibuat untuk mendukung rencana-rencana The United State Depart-ment of Agriculture’s (USDA) dalam memperhatikan masalah kualitas air. WQIC yang memiliki fungsi pen-ting bagi pihak USDA bertugas untuk mengumpulkan, mengorganisasikan dan mengkomunikasikan penemuan ilmiah, metodologi pendidikan dan kebijakan publik seputar sumber daya air dan pertanian.
N- Secretary General’s Advisory Board on Water and Sanitation www.unsgab.org
Di dalam situs ini pengunjung dapat memperoleh berbagai macam publikasi dalam jumlah yang cukup banyak yang berkaitan dengan air dan sanitasi
dalam bentuk PDF, Words. Situs ini merupakan milik UNSG Advisory Board yaitu merupakan suatu badan independen yang berfungsi untuk: •Memberikan saran pada sekretaris jenderal PBB •Memberikan masukan dalam proses dialog global •Meningkatkan kesadaran global melaui media massa •Mempengaruhi dan bekerja di tingkat global, regional, institusi nasional di tingkat tertinggi •Membuat langkah-langkah dalam rangka MDGs.
UN-Water www.un.org/waterforlifedecade
Situs ini dibuat untuk menjadi penanda telah berlangsungnya program pengadaan air bagi masyarakat dunia oleh PBB selama
satu dekade. Di sini pengunjung dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan air dan sanitasi. Selain itu terdapat pula situs bagi para pelajar mengenai water management dalam link Education and Youth. UN-Water merupakan suatu lintas organisasi yang mempromosikan koherensi, dan koordinasi dari PBB yang bertujuan dalam mengimplementasikan agenda dari Millenium Declaration dan The World Summit on Sustainable Development yang memiliki hubungan dengan lingkup kerja UN-Water.
Info Situs
58
Laporan Laporan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN2004-2009:Bersama Menata Perubahan. Diterbitkan olehKementerianPerencanaan Pembangunan Nasional Tahun2010tebal607halaman.
Studi StudiKasus:SanitasiBerbasis Masyarakat di KotaBatu,JawaTimur,Tahun 2010.
Cerita Tentang Sabun dan KisahToilet(Soap Stories and Toilet Tales) Tahun 2010
PanduanBukuPanduanPelatihanTenaga Fasilitator Lapangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Dana AlokasiKhususTahun2010 Tingkat Regional Kalimantan
Buku Pegangan 2010 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Penguatan Ekonomi Daerah:LangkahMenghadapiKrisisKeuanganGlobal
Petunjuk Rencana Strategis AMPL-BM Tahun 2010 - 2015 KabupatenBangka
Majalah Majalah Air Minum Agustus 2010 Diperlukan Cara Pandang CerdasHadapiDefisitAir
PercikEdisiI,2010Membidani PIN AMPL
BuletinDewanSumberDaya Air Edisi Maret - Mei 2010
News Letter NewsletterAMPL(AirMinum dan Penyehatan Lingkungan) Edisi JuLi 2010
GaungRWSiagaPlus+Edisi 1/ Juni 2010 ”SelamatDatangDiRWSiaga Plus+!“/ Welcome to RW Siaga Plus+!
Leaflet Bina Ekonomi Sosial Terpadu(BEST/Institutefor Integrated Economic and Social Development) Tahun 2010
6CaraMudahuntukMendapatkan Air Minum SehatuntukKeluarga.Dibuat tahun 2010 oleh UsAiddanKementrianKesehatan.
Poster Hemat Air + Hemat Energi = Hidup Lebih Baik
PustakaAMPL
59
Edisi III, 2010Fakta
Untukmencegah,atausetidaknyame-ngurangi,kemungkinanterjadinyaben-canaairdunia,diperkirakandiperlukaninvestasi yang luar biasa besar untuk perbaikanpengelolaanair,pengelolaan
sanitasidanuntukirigasi.Setiaptahundibutuhkankuranglebih100–150milliarUSdollarinvestasiuntukmencegah krisis air yang parah di 2050. Jumlah ini bisa semakin besar bila upaya nyata untuk mengatasi krisis terlambat dilakukan.
SebuahlaporanPBBsetebal348halaman,mem-berikan gambaran yang suram tentang kondisi ling-kungan khususnya ketersediaan air pada tahun 2050. Laporanitudisiapkanolehsebuahtimberdasarkankompilasi dari 24 lembaga/badan organisasi PBB. Negara-negara miskin digambarkan akan menghadapi masalahyangsangatmengkhawatirkan.Berbagaikrisisyangsaatinimelanda,menambahbebannegara-nega-ra berkembang menjadi semakin sengsara.
Krisisairsangateratkaitannyadengankrisisper-ubahaniklim,krisisenerji,krisispangan,pertumbuhanpenduduk,dankrisisfinansialglobal,demikianlaporanPBBitu.Bilamasyarakatduniatidakmelakukantindak-ansignifikan,makakrisisitusemakinmultidimensisampaikepadakrisispolitik.Bukantidakmungkinpula,bahwa krisis itu bisa menjadi krisis teritorial antarnega-ra.Sengketaperebutanair,adalahsuatuancamanyangbisatimbul,terutamabaginegara-negarayangmemi-likibadanairyangdigunakansecarabersama,sepertidiAfrika,Asia,Eropa,atauAmerikaLatin.
Pertumbuhanpenduduk,adalahsalahsatufaktoryangsangatmengkhawatirkan.Padatahun2000,jumlahpendudukduniamencapai6miliyarjiwa.Jumlahitusudahmenjadi6,5milyarjiwapadasaatini.Padatahun2050,jumlahpendudukduniadiperkirakanmenjadi9milyar jiwa. Populasi penduduk dan pertum buhan paling besar justru berada di negara-negara miskin.
BerdasarkanlaporanPBBitu,pertumbuhanpen-
dudukyangtinggimemberikantekananyangsangatbesarpadasumber-sumberair,khususnyadinegara-negara berkembang. Penduduk dunia bertambah hampir80jutaorangsetiaptahun,dan90persendiataranya (sekitar 72 juta) berada di negara-negara berkembang.Kebutuhanairduniabertumbuhseba-
nyak64milyarjutameterkubikpertahun. Jumlah ini setara dengan kebutuhan seluruh ne-gara Mesir selama setahun.
Selama50tahunterakhir,pemanfaatanairdarisungai,danaudanairtanahsudahnaik3kalilipat,untukmemenuhikebutuhanpertambahanpenduduk.Secararata-rata,70persenair tersebut dimanfaatkan untuk pertanian. Di negara-negara berkembang kebutuhan air untuk pertanian bahkan bisa mencapai 90 persen.
Kerusakanlingkunganyangtimbulakibatpertum-buhan penduduk yang sangat besar mencapai milyaran dolarAmerika.KerusakanlingkungandiAfrikaUtaradanTimurTengah,sebagaikawasanyangpalingparah
dalamkerusakanlingkungan,nilainyasudahmencapai9 milliar dolar per tahun. Jumlah ini hampir mencapai 2,1-2,7persendariProdukDomestikBruto(PDB)ka-wasan itu. Angka ini adalah suatu angka yang luar biasa besar.
Krisisairsemakindiperparaholehperubahaniklim.Kecenderungankerusakanyangdemikianbesar,makakemungkinanterjadinyakonflikairbisaterjadisecaraluas.Ancamankonflikregionaldaninternasionalkare-nakrisisairbukanlahsekedarwacana,tapihalitubenar-benar ancaman yang semakin nyata. Akibat pe-rubahaniklim,akanterjadisuatu“gegarhidrolo-gis”(hydrogical shock) yang akan bisa terjadi dalamwaktuyangtidakterlalulama(eko/kruga.org)
Perlu Investasi 150 Milliar US$ Cegah Krisis Air Dunia
ISTIMEWA