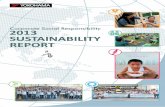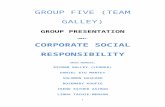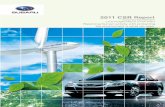MENYINGKAP SELUBUNG IDEOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA (Analisa Teori...
-
Upload
universitasnegerimalang -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of MENYINGKAP SELUBUNG IDEOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA (Analisa Teori...
MENYINGKAP SELUBUNG IDEOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA
(Analisa Teori Kritis Terhadap Keberpihakan CSR di Indonesia)
SKRIPSI
Disusun Oleh :
ABDUL KODIR 070710004
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Semester Ganjil Tahun 2011/2012
ii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan
tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila
dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas
Airlangga.
Surabaya, 7 Desember 2011
NIM 070710004
Abdul Kodir
iii
MENYINGKAP SELUBUNG IDEOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA
(Analisa Teori Kritis Terhadap Keberpihakan CSR di Indonesia)
SKRIPSI
Dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
Disusun oleh
070710004 Abdul Kodir
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Semester Ganjil Tahun 2011/2012
iv
MENYINGKAP SELUBUNG IDEOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA
(Analisa Teori Kritis Terhadap Keberpihakan CSR di Indonesia)
Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan
Surabaya, 7 Desember 2011
Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Musta’in Mashud, Msi NIP 196001201986041001
v
Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji
Program Studi Sosiologi
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Pada hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2012
Pukul : 13.00 WIB
Komisi Penguji terdiri dari:
Ketua Penguji
Drs. Herwanto, MA.
NIP 195110051079011002
Anggota Anggota
Prof. Dr. Musta’in Mashud, Msi Drs. Edy HerryP, M.Si
NIP 195110051079011002 NIP 196403131991111001
vi
Halaman Motto
“kini tak ada waktu untuk berpikir tentang apa yang tak kau miliki, berpikirlah tentang apa yang bisa kau lakukan dengan apa yang ada”
— Ernest Hemingway
Halaman Persembahan
vii
Skripsi ini dipersembahkan untuk:
“Someone who i love & Loves me”
ABSTRAK
Fenomena munculnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazim disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan sebuah respon msyarakat global terhadap proses industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi MNC/TNC yang secara nyata menyebabkan masalah ekologi, HAM, dan permasalahan sosial lainya yang perlu untuk segera ditangani. Fakta-fakta
viii
kerusakan ekologi pada tingkat planet yang jelas. Ada banyak ciri-ciri kerusakan seperti: lahan pertanian, hutan hujan dan berhutan daerah, padang rumput dan sumber air tawar semua berisiko. Pada tingkat global, lautan, sungai dan ekosistem air lainnya mengalami kerusakan. Seiring dengan perkembangannya, CSR ini dianggap sebagai anak dari korporasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat global, sehingga bisa melakukan proses produksi tanpa henti.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana CSR sebagai sebuah strategi pembangunan di Indonesia dalam perspektif teori yang digunakan dan bagaimana ideologi atau keberpihakan CSR itu sendiri. Rumusan masalah ini dianalisa dengan menggunakan teori kritis dengan metode kritik ideologi atau kritik atas metodologi positivisme dengan menggunakan langkah subversif atau keluar dari common sense dan historis
Dalam penelitian ini ditemukan adanya inkonsistensi dalam regulasi di tubuh CSR itu sendiri sehingga menyebabkan multitafsir, belum terbentuknya PP sebagai sebagai pelaksanaan teknis CSR, diperburuk dengan kenyataan program CSR yang hanya bersifat brand image dan juga CSR itu sendiri membuat masyarakat semakin terbelenggu karena mulai menggantungkan CSR sebagai suatu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. CSR juga menganut ideologi investasi dimana para pemodal akan terus melaju kepada perusahaan yang melakukan program CSR dikarenakan citra positif yang dibangun kepada masyarakat.
Kata kunci: CSR, Korporasi, Ideologi, Kritik Ideologi, Teori Kritis
ABSTRACT
The phenomenon of the emergence of corporate social responsibility, or commonly known as Corporate Social Responsibility (CSR which is a global society response to the industrialization process undertaken by the coporation (MNC / TNC) which brings on ecological issues, human rights and other social issues that need to be handled. The fact on the planet’s ecological damage is obvisius. There are a lot of damage characteristic such as agricultural land, rain
ix
forest and wood areas, grasslands and freshwater sources are al that risk. At the global level, the oceans, rivers and other aquatic ecosystems damaged. Along with its development, CSR is regarded as subsidiary of the corporation to maintain its presence in the global society, so they can do without stopping the production process.
Problems in this study how CSR as strategy of development in Indonesia in the pespective of the theory used and how the ideology or partisanship CSR it self. Formulation of the problem is analyzed using the methods of critical theory of ideology critique or criticism of the methodology of positivism by using subversive or step out of common sense and historical.
In the present study found no inconsistency in the regulation of CSR in the body itself, causing multiple interpretations, not the formation of PP as the technical implementation of CSR, exacerbated by the fact that CSR programs are just brand image and CSR itself makes people begin to rely increasingly tied by CSR as an alternative solution to overcome the existing problems. CSR also embraced the ideology of investment where the investors would go to companies that perform CSR program which is built due to a positive image to the public
.
Key Words: CSR, Corporate, Ideology, Ideology Critique,
Critical Theory
KATA PENGANTAR
Akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan dengan usaha yang tidak sedikit.
Skripsi berjudul ‘Menyikap Selubung Ideologi CSR (Analisa Teori Kritis Terhadap
Keberpihakan CSR di Indonesia)’ ini penulis angkat berdasarkan fenomena wacana
x
CSR yang muncul karena banyak menjadi perhatian khusus di kalangan bisnis
maupun para pengamat sosial. Namun kemunculan CSR itu sediri banyak pihak
yang pro dan kontra dalam menanggapi kemunculan CSR itu sendiri.
Berkat usaha peneliti, serta bantuan yang tidak bisa dikatakan sedikit dari
banyak pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Diharapkan, selain sebagai
syarat kelulusan program studi S1 Sosiologi, skripsi ini juga dapat membuka ruang
diskusi bagi studi-studi dengan tema serupa, serta memberikan pijakan bagi
terbukanya alat analisis baru, di luar alat analisis mainstream dalam melihat
persoalan. Kritik dan masukan peneliti terima, dalam rangka membuka ruang
diskusi sebagaimana peneliti inginkan. Semoga skripsi ini dapat membuka
imajinasi sosiologis pembaca sampai titik yang paling jauh.
Penulis sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini tentu dengan dukungan
dan bantuan dari banyak pihak. Pada gilirannya, pada skripsi inilah terekam jejak-
jejak memori penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan terima
kasih kepada :
1. Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada
penulis, sungguh kuasa Engkau tiada satupun dapat menandinginya.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kepada
seluruh umatnya.
3. Kedua Orang Tua penulis, (alm) abah dan mamak, untuk segenap kasih
sayang yang diberikan sepanjang masa dan tetesan air matanya dalam do’a
yang tak akan pernah bisa terbayarkan dengan apapun. Untuk kakak-kakak
xi
ku yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat dalam bentuk moril
maupun materiil yang menghendaki penulis untuk melanjutkan pendidikan
lebih tinggi dan untuk adik-adikku tercinta agar senantiasa selalu berusaha
membuat mamak kalian bangga…
4. (Alm) H. Muhammad Nur & Hj. Mudrikah dan Bpk Ismail Sekeluarga, Mas
Eddy yang telah banyak membantu keluarga penulis. KH. Abdul Muchid
Djaelani dan segenap keluarga Besar Muhammadiyah Jombang, atas segala
kesabarannya mendidik penulis.
5. Pak Pandu Hendrawan & Ibu Andriana Ocnova, mbak Mariska Yostina atas
segala kasih sayang, perhatian, kepercayaan serta dukungannya kepada
penulis, Eugenia Amanda (Dekyang) yang telah mencurahkan segenap
perhatian, kasih sayang, luapan emosi dalam setiap duka dan suka, yang
selalu setia dan sabar menemani penulis. Terima Kasih. GBU.
6. Keluarga Besar Departemen Sosiologi Fisip Unair ; Prof. Musta’in Mashud
yang senantiasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang
dan bimbinganya hingga menyelesaikan penulisan akhir skripsi, Prof. I.B
Wirawan yang menjadi dosen wali penulis selama menjadi mahasiswa, Pak
Herwanto selaku Ketua Departemen Sosiologi. Prof. Hotman Siahaan, Prof.
Soetandjo, Dr. Daniel T. Sparringa, Ibu Sutinah, Pak Doddy, Pak Novri,
Bapak Eddy Hery, Pak Karnaji, Pak Sudarso, dan semua dosen departemen
Sosiologi lainnya yang telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus
belajar.
xii
7. Segenap kawan-kawan Sosiologi 07 (Gumbul’07) yang telah membuka
awalan sebuah cerita di bangku kuliah, Bima, Dida, Bobby, Tresye,
Adith’Gebleh’, Nora, Dimaz, terima kasih untuk celoteh-celoteh yang tak
pernah ada habisnya. Denis’Negro’, Yunita’Shep2’, Alfan, Yoga’gepeng’,
Indra’Jabriks’, Adi’Pay’ untuk canda tawa yang tak pernah putus. Sabrina,
Noni’si cantik’, Mirmor, Uli’, Mbak Siska, Sarah, Amanda,
Mukhlisin’Sammy’, Jaya, Citra, Ika, Ayu, (Alm) Tina.. semoga engkau
tenang disisi-Nya, Robby, Rima. Iik Nindy’Nyo2, Nia, senang telah
mengawali sebuah tali pertemanan dengan kalian . Untuk Yogi, Adit’Kak
Fu’ yang terima kasih karena telah banyak meluagkan waktunya untuk
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Cak Kirun, Cak War, Mas
Proy, Era’, Mbak Titis, Mbak Anik, Cak Bolot, Bayu, Dhana dan segenap
Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Proud Become Sociolog !
8. Keluarga Besar GMNI Komisariat FISIP UNAIR, Untuk para terdahulu
Mas Ambon, Cak Ek, Mas Reno, Mas Ximen, Mas Mujib, Mas Hari, Bung
Koala, Mas Agus (Bogang), Mas Joko, Mas Rambak, Mbak Nila Mbak
Riska (Mamake), Skie, Mbak Nimas, Yosevin, Bowo, Mas Ozy, Rangga,
Aswin, Piere, Ken, Teddy’Ateng’, Amanu, Mbak Sundari, Gabriel’Botak’,
Frans’Jinggo’ terima kasih untuk segenap pelajaran yang telah diberikan.
Kawan2 Kader 2007, Nizen, Ayu Irene’Emon’, Ijal, Didit, Nora, Iis’Nduty’,
Fitrah’Petruk’, Bundin, Aditya’embek’ Femy’Amoy’, Dika, Intan,
Hubert’Ute’ thanks untuk berbagi cinta, cita dan harapan kalian. Adik-
adikku Haryo, Nato, Dimas’Frocky’, Edwin, Ben, Zakky, Yerry, Lexy,
xiii
Ardian’Mimen’, Eggy’Pak dhe’, Vanny, Otit’Alay’, Ardina, Mirza’Pak Kus
’Andhika’Besek’, Imas, Titi, Ifa, Jodi, Karim, Yuni, Jatayu, Ambon, Yoga,
Dira, Meteor, Jadilah Kayu Bakar dalam setiap Api Perjuangan. Sungguh
teramat bangga sekali menjadi bagian Keluarga Besar GMNI FISIP Unair,
sebuah ruang yang tak akan pernah terlupakan dalam setiap detik yang telah
terlewati. Pemikir-Pejuang, Pejuang-Pemikir. MERDEKA!! GMNI
DJAYA! MARHAEN MENANG!
9. Kelurga Besar FISIP Unair, Pak I Basis Soesilo (Dekan Fisip), Pak Dugis,
Pak Djodi yang telah banyak Mas Yunus, Mas Joko, Pak Bambang atas
waktu yang diberikan untuk ruang-ruang diskusi dan selalu memberikan
pengetahuan baru. Dan segenap jajaran Dekanat, Dosen & Karyawan FISIP
UNAIR yang telah banyak mendukung dan berkontribusi untuk aktifitas
kemahasiswaan. Dan tetap menjadikan Kampus FISIP UNAIR sebagai
miniatur Indonesia dengan segala dinamikanya.
10. Segenap Jajaran Pengurus BEM FISIP UNAIR 2009-2010 yang tetap
konsisten menghidupkan kampus dengan segala kegiatannya. Seluruh Tim
Sumber Redjo, yang harus berjuang lebih keras lagi untuk menjuarai Fisip
Super League. Teman2 Fisip, Dhani’Cepot’ sahabat yang tak lekang oleh
waktu, thanks banyak menjadi ruang curahan hati dan kegilaanya, ayie yang
kini telah menghilang. Sita adek kecil, Mas Praja, Meylysania’Cece’ untuk
wawasan keilmuan Hubungan Intenasional. Vita makasih untuk jalan-jalan
kelililng Lombok. CSku Gopok, Diaz, Tomi, Niko, Adhit seng woles yo
cak. Kerabat Antropologi dengan segala canda gurau nya dan selalu
xiv
menhidupkan suasana kampus. Teman2 HMI, KAMMI, PMII ynag telah
memberi di kampus kita.
11. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebut, rasa terima kasih takkan
cukup untuk ditumpahkan di atas kertas kosong ini.
Penulis
DAFTAR ISI
BAGIAN AWAL Halaman Judul Dalam ........................................................................................ i Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat ................................................. ii Halaman Pengungkapan Maksud Penulisan Skripsi ........................................ iii Halaman Persetujuan Pembimbing .................................................................. iv Halaman Pengesahan Panitia Penguji ............................................................... v
xv
Halaman Motto .................................................................................................. vi Halaman Persembahan .................................................................................... vii Abstrak ........................................................................................................... viii Kata Pengantar .................................................................................................. x Daftar Isi ........................................................................................................... xv Daftar Tabel .................................................................................................. xvii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I. 1 I.1. Latar Belakang ................................................................................ I. 1 I.1.1 Diskursus CSR ............................................................................. I. 2 I.1.2 CSR di Indonesia ....................................................................... I. 11 I.2. Rumusan Masalah ......................................................................... I. 19 I.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... I. 21 I.4. Manfaat Penelitian ........................................................................ I. 22 I.5. Kajian Teoritik .............................................................................. I. 22 I.5.1 Positivisme .................................................................................... I. 22 I.5.1.1 Normatif ......................................................................................I. 22 I.5.1.2 Linier ......................................................................................... I. 24 I.5.1.3 Natural ....................................................................................... I. 25 I.5.2 Teori Kritis .................................................................................... I. 26 I.5.2.1 Historis ....................................................................................... I. 26 I.5.2.2 Dialektis ...................................................................................... I. 26 I.5.2.3 Dominasi .................................................................................... I. 27 I.6 Metode Penelitian .......................................................................... I. 27 I.6.1 Positivisme ................................................................................ I. 28 I.6.2 Teori Kritis ................................................................................ I. 30 I.6.2.1 Subversif ................................................................................. I. 36 I.6.2.2 Historis .................................................................................... I. 37 I.6.3 Kontekstualisasi Metode ............................................................... I. 38 I.6.3.1 Jenis Penelitian ............................................................................ I. 38 I.6.3.2 Isu – isu Penelitian ...................................................................... I. 39 I.6.3.2.1 Agenda CSR ............................................................................I. 40 I.6.3.2.1 Ideologi ....................................................................................I. 41 I.6.3.3 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... I. 42 I.6.3.4 Jenis Data .................................................................................... I. 42 I.6.3.5 Teknik analisis Data ................................................................... I. 43 BAB II Sejarah dan Perkembangan CSR ................................................ II. 1 II.1 Sejarah CSR ...................................................................................... II. 3 II.1.1 Sejarah CSR Di Tingkat Internasional ........................................... II. 4 II.2 Definisi CSR ................................................................................. II. 11 II.3 Regulasi CSR di tingkat Global .................................................... II. 17 II.4 CSR di Indonesia .......................................................................... II. 26 II.4.1 Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia .......................... II. 40
xvi
II.4.2 Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia ............................... II. 45 BAB III Analisis Data ................................................................................ III. 1 III.1 Pengertian “Kritik” Dalam Tradisi Madzhab Kritis ...................... III. 1 III.1.1 Kritik Dalam Arti Kantian .......................................................... III. 6 III.1.2 Kritik dalam arti Hegelian ........................................................... III. 7 III.1.3 Kritik dalam arti Marxian ........................................................... III. 9 III.1.4 Kritik dalam arti Freudian ............................................................ III. 12 III.2 Kritik Madzhab kritis Atas CSR di Indonesia ........................... III. 14 III.2.1 CSR menjadi Strategi Pembangunan di Indonesia .................. III. 14 III.2.1.1 Fakta Lemahnya Implementasi CSR di Indonesia...................III. 29 III.2.2 Proses Pelaksanaan dan Hasil .................................................. III. 34 III.3 Ideologi CSR di Indonesia ........................................................... III. 40 BAB IV Penutup ............................................................................................ IV. 1 IV.1 Kesimpulan .................................................................................... IV. 1 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xvii
DAFTAR TABEL Tabel I. 1. Peta Paradigma Positivisme dan Kritis .............................................. I. 40
I. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Peter Drucker, 2004.
I.1. Latar Belakang Masalah
Corporate social responsibility is a dangerous distortion of business principles. If you find an executive who wants to take on social responsibilities, fire him. Fast.
1
Fenomena munculnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazim
disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
perkembangan dari sistem ekonomi politik global. Dan juga merupakan kewajiban
untuk perusahaan multinasional untuk menunjukkan tanggung jawab lebih besar
dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekitar
perusahaannya. Para pemilik perusahaan, mengibaratkan CSR sebagai sumber
baru yang potensial dari pemerintahan global, yaitu mekanisme untuk mencapai
keputusan bersama untuk menangani masalah pembangunan yang dilakukan oleh
perusahaan asing dengan atau tanpa partisipasi pemerintah. Studi berikut ini akan
membahas tentang fenomena CSR di dunia yang sampai saat ini menuai pro dan
kontra. Bagi pihak yang mendukung adanya CSR itu berpendapat perlunya
pembangunan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap
lingkungan sekitarnya. Namun bagi pihak yang menolak adannya CSR tersebut
dikarenakan CSR mempunyai agenda terselubung dan syarat akan kepentingan
dari para pemilik perusahaan.
1 Peter Drucker dalam S. B. Banerjee, A Critical Perspective On Corporate Social Responsibilty : Toward A Global Governance Framwork. Hal 2.
I. 2
I.1.1 Diskursus CSR
Sejumlah faktor munculnya CSR di arena internasional salah satunya
adalah dengan kekuatan dan pengaruh perusahaan multinasional, khususnya
dampaknya di negara-negara berkembang tentang hak asasi manusia, lingkungan,
dan pekerjaan. Keprihatinan ini telah datang di tahun 1970-an, tetapi mereda pada
tahun 1980. Sampai saat ini LSM, NGO atau masyarakat Internasional mengakui
bahwa operasi produksi perusahaan multinasional besar memiliki dampak kritis
pada tekanan lingkungan, praktek pasar tenaga kerja, pembangunan ekonomi
regional, dan budaya yang lebih luas. Perusahaan multinasional sering terlihat
sebagai kendaraan dari proses globalisasi yang, di satu sisi, ditandai dengan
integrasi ekonomi dan konvergensi, dan di lain pihak dengan ketegangan sosial,
pembangunan yang tidak merata, dan kesenjangan sosial. Ketika jaringan
produksi global mereka membuatdi bidng ekonomi jembatan ekonomi, dan politik
memberikan dampak terhadap dengan memperburuk perbedaan spasial dalam
hidup dan standar perburuhan, kesehatan, dan hak-hak individu. Bersamaan
dengan itu, mereka menginduksi proses hibridisasi budaya dan difusi yang
mengancam identitas lokal. Perusahaan multinasional dapat dengan mudah, oleh
karena itu, menjadi simbol dari sebuah zaman baru eksploitasi, imperialisme, dan
kolonialisme.2
Perusahaan multinasional secara de facto, menjadi bagian dari struktur
pemerintahan global. Di bawah kedok "corporate citizenship", perusahaan besar
yang menggusur negara sebagai penyedia dan pelindung hak-hak sipil dan politik.
2 Levy, D. L., & Newell, P, Multinationals in global governance. In S. Vachani (Ed.), Transformations in global governance: Implications for multinationals and other stakeholders, Edward Elgar: London, 2006. Hal 56.
I. 3
Perusahaan multinasional, dalam peran mereka sebagai investor, inovator, ahli,
produsen, pelobi, dan pengusaha, memainkan peran kunci dalam masyarakat, dari
media dan hiburan untuk lingkungan dan kondisi kerja. Sebagai contoh, keputusan
penelitian dan pemasaran perusahaan farmasi menentukan siapa yang memiliki
akses terhadap perawatan yang penyakit dan penentuan harga .3
Sementara itu perluasan kekuasaan korporasi secara lebih luas dipandang
sebagai permasalahan baru di dunia berkembang, pengakuan yang ada sampai saat
ini bahwa kekuasaan korporasi disertai eksploitasi alam yang tanpa hentinya
untuk mengeruk sumber daya alam dengan tujuan profit semata tanpa melihat
dampak lingkungan yang akan terjadi.
Akibat dari dampak lingkungan maupun sosial yang terjadi menciptakan
permintaan yang lebih besar untuk merespon masyarakat dunia dan LSM/NGO
untuk meminta pertanggung jawaban terhadap persahaan akibat proses produksi
yang telah dilakukan.
Meskipun kebutuhan nyata untuk peningkatan koordinasi di tatanan
internasional atau yang lazim disebut global governance, namun negara-negara
cenderung untuk membatasi peran mereka, karena kecenderungan koordinasi di
tatanan internasional ialah menuju deregulasi dan privatisasi, sehingga dapat
memperburuk keadaan karena kurangnya peran pemerintahan. Adanya kordinasi
internsional membuat peraturan kekuasaan negara semakin diarahkan penataan
pasar dengan cara meningkatkan pasar berdasarkan bentuk alokasi sumber daya
yang ada pada setiap negara terutama negara berkembang
3 Sell, S. K., & Prakash, A, Using ideas strategically: The contest between business and NGO networks in intellectual property rights. International Studies Quarterly, 2004, 48(1): hal 143.
.
I. 4
Kerangka hukum internasional dan lembaga-lembaga yang berkaitan
dengan dampak sosial dan lingkungan menganggap isu ini menjadi sangat
penting. Upaya pada 1970-an oleh PBB yang merupakan Pusat Korporasi
Transnasional untuk membuat kode etik untuk mengikat perusahaan-perusahaan
multinasional (MNC) berakhir dengan kegagalan. Ketidakcukupan lembaga yang
ada telah menerima pemberitahuan tertentu di bidang lingkungan hidup, di mana
eksternalitas seperti hujan asam dan emisi gas rumah kaca yang starkly jelas.
Lingkungan hanya menerima perhatian yang sedikit dalam perdagangan
internasional dan perjanjian investasi, sementara organisasi yang berdedikasi
seperti Program Lingkungan PBB “sekarang di bawah didanai, kelebihan beban
dan remote. Untuk pasang ‘kesenjangan pemerintahan’, beberapa telah membuat
argumen yang bersemangat untuk Organisasi Lingkungan Global, setara dalam
ruang lingkup Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sementara yang lain
panggilan untuk memperkuat sistem muncul dari "longgar, desentralisasi ,
jaringan padat lembaga-lembaga dan aktor.4
Keterlibatan bisnis dengan isu-isu tanggung jawab sosial pada umumnya
ada dua motivasi yakni, keuntugan dan kepentingan politik. Penghargaan CSR
telah digunakan secara mendalam di bidang lingkungan hidup pada sisi
permintaan, ada kesempatan pasar yang menarik, sementara di sisi produksi , ada
peluang untuk mengurangi biaya energi, bahan, dan pembuangan limbah. Lebih
luas, CSR dapat menghasilkan citra pasar yang positif, meningkatkan moral
karyawan, dan mengurangi biaya kewajiban, asuransi dan kepatuhan hukum
4 Bierman, F. The emerging debate on the need for a World Environment Organization. Global Environmental Politics, 1(1), 2001, hal 45.
.
I. 5
Vogel (2005) berpendapat bahwa perusahaan multinasional, khususnya,
bisa mendapatkan keuntungan dari mendukung pertumbuhan dan ekspansi pasar
di negara berkembang dan dari standarisasi pelaporan lintas negara. Meskipun
banyak bukti anekdot yang mendukung klaim ini, studi empiris yang lebih ketat
umumnya menemukan hubungan yang lemah atau tidak signifikan antara tindakan
tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Permintaan pasar untuk CSR
terbatas pada segmen niche sempit, sementara sulit untuk menyadari nilai moneter
yang berasal dari 'memasok CSR' stakeholder kepada selain konsumen.5
Kelemahan argumen ekonomi untuk CSR menunjukkan karakter
politiknya. Utting (2000: 27) mengutip mantan eksekutif dari sebuah perusahaan
minyak besar yang berkomentar dalam sebuah lokakarya yang disponsori oleh
PBB bahwa jika argumen menang-menang begitu menarik, eksekutif "maka kita
tidak akan duduk mengelilingi meja ini." mengingatkan peserta bahwa LSM dan
tekanan konsumen yang telah mengubah perilaku perusahaan. Untuk itu CSR
"mencerminkan perubahan yang terjadi dalam keseimbangan kekuatan-kekuatan
sosial - terutama pertumbuhan LSM dan tekanan konsumen." Perusahaan
memiliki motivasi politik untuk terlibat secara proaktif dengan tekanan
masyarakat, untuk "memungkinkan bisnis untuk tidak hanya membelokkan atau
encer tekanan tertentu, tetapi juga di kursi pengemudi untuk memastikan
perubahan yang terjadi yang menguntungkan bisnis ".6
5 D. J Vogel, The market for virtue: the potential and limits of corporate social responsibility, Brookings Institution Press: Washington DC, 2005. hal 13. 6 P Utting, Business responsibility for sustainable development.United Nations Research Institute for Social Development: Geneva, 2000, hal.27.
I. 6
Dalam hal yang sama, Levy (1997: 132) berpendapat bahwa pengelolaan
lingkungan perusahaan sebagai upaya untuk menjaga "keberlanjutan politik"
dalam menghadapi tantangan sosial dan peraturan. Dalam pandangan ini, CSR
merupakan sarana untuk mengakomodasi tekanan, membangun perusahaan
sebagai agen moral mengurangi ancaman regulasi, dan meminggirkan para aktivis
yang lebih radikal. Demikian juga, Shamir (2004) berpendapat bahwa perusahaan
multinasional telah berusaha untuk membentuk makna CSR dengan cara yang
bias potensial radikal, dengan menekankan kesukarelaan daripada kewajiban
hukum atau akuntabilitas publik.7
Multinational Corporation (MNC) menghadapi tantangan khususnya
dalam mempertahankan legitimasi mereka, karena mereka memberikan peluang
bagi para aktivis untuk menyoroti sangat kontras di daerah dalam pola konsumsi
dan kondisi kerja. Di negara berkembang, perusahaan multinasional sering
membawa beban kebencian rakyat terhadap sejarah kolonialis dan kesenjangan
global kontemporer, sementara pemerintah lokal mungkin memiliki alasan untuk
mendorong kebencian tersebut. Di negara-negara industri, perusahaan
multinasional besar seperti Nike, Starbucks, dan Wal-Mart telah datang untuk
melambangkan ketidakpuasan dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi
dari kekuatan-kekuatan ekonomi global. MNC telah dimasukkan ke dalam sorotan
oleh pertemuan munculnya wacana CSR dikombinasikan dengan pertumbuhan
7 D. L. Levy, Environmental management as political sustainability. Organization and Environment, 1997, 10(2): hal 126.
I. 7
ngerakan sosial dengan kapasitas untuk memantau dan mempublikasikan operasi
MNC.8
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai multi aktor dan multi-
tingkat sistem aturan, standar, norma, dan harapan, mencontohkan konsepsi
pemerintahan global yang luas. Dalam hal organisasi, CSR merupakan suatu
lembaga, yang didefinisikan sebagai "konstruksi sosial, rutin-ulang program atau
sistem aturan" 9
Berpendapat Doh dan Guay (2006) bahwa legitimasi CSR dikondisikan
oleh konteks nasional, sehingga "kesadaran yang relatif lebih maju dan dukungan
untuk CSR di Eropa," berbeda dengan Amerika Serikat, "menyediakan
lingkungan yang lebih responsif untuk mempengaruhi LSM dalam sejumlah
kebijakan publik kontemporer isu-daerah, seperti pemanasan global, perdagangan
GMO, dan harga obat-obatan anti-virus di negara-negara berkembang "global
Compact., sebuah inisiatif CSR yang disponsori oleh PBB, dirancang untuk
meningkatkan tekanan institusional dalam rangka untuk menyebarkan praktik
terbaik CSR dalam sebuah 'jaringan belajar' dari perusahaan multinasional besar
.10
Pemerintahan global yang juga dapat dilihat sebagai mode kekuasaan
yang berasal dari efek konstitutif dan disiplin wacana CSR, dalam kerangka kerja
8 M. E. Keck & K. Sikkink, Transnational advocacy networks in international politics: introduction In M. E. Keck, & K. Sikkink (Eds.), Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics, Cornell University Press: Ithaca, 1998.hal 57. 9 R. L. Jepperson, Institutions, institutional effects, and institutionalism. In W. W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organizational analysis, University of Chicago Press: Chicago, 1991, hal 143. 10 J. P Doh, & T. R Guay, Corporate social responsibility, public policy, and NGO activism in Europe and the United States: An institutional-stakeholder perspective. Journal of Management Studies, 43(1), 2006, hal 47.
I. 8
ini, merupakan serangkaian teks diskursif dan praktik yang membangun
subjektivitas perusahaan dan bidang di mana operasi perusahaan berlangsung
sebagai domain aksi tanggung jawab sosial. Praktek audit sosial dan pelaporan
merupakan bentuk disiplin yang berfungsi untuk standarisasi, pangkat dan
mengkategorikan kinerja CSR. Pengawasan kegiatan perusahaan sehingga
menerjemahkan CSR dari sebuah set abstrak norma dan harapan "menjadi
instrumen audit yang diukur dan standar yang cocok untuk pengukuran yang
objektif dan konsisten".11
.
Namun CSR jelas bukan satu-satunya struktur pemerintahan ekonomi
global dengan legitimasi diskursif. Memang, CSR mungkin bertentangan dengan
apa (1995) Gill istilah "disiplin neo-liberalisme." Perusahaan, pekerja dan
konsumen menyatakan tunduk pada sistem pemerintahan yang menggabungkan
kekuatan ekonomi persaingan dengan ideologi konsumerisme, pasar bebas, dan
disiplin diskursif peringkat kredit dan akuntansi keuangan.12
Ketegangan yang melekat dalam koeksistensi CSR dan neoliberalisme
menyoroti medan diperebutkan pemerintahan global. Pada bagian berikut kami
menunjuk dua perspektif yang berbeda tentang CSR, sebagai bentuk yang lebih
sosial-tertanam dan demokratis pemerintahan yang berasal dari masyarakat sipil,
atau sebagai alternatif, sebagai sistem privatisasi tata kelola perusahaan yang tidak
memiliki akuntabilitas publik.13
11 P. Sethi, Corporate codes of conduct and the success of globalization. Ethics & International Affairs, 16(1), 2002, hal. 89. 12 S. Gill, Globalisation, market civilisation, and disciplinary neoliberalism. Millenium. Journal of International Studies, 24(3), 1995, hal 399. 13 W. K. Carroll, & C. Carson, The network of global corporations and policy groups: A structure for transnational capitalist class formation?, Global Networks, 3(1), 2003, hal 29.
I. 9
Murphy dan Bendell (1999) berpendapat bahwa "Kami percaya bahwa
sipil organisasi-organisasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam
mempromosikan pengelolaan lingkungan dan sosial. Bukti anti-logging, anti-
minyak dan anti-pekerja anak protes menggambarkan bahwa LSM semakin
menetapkan agenda politik di mana bisnis harus bekerja . Fenomena CSR tidak
harus dirayakan sebagai ungkapan altruisme perusahaan atau penemuan peluang
menang-menang, melainkan, mereka mengakui bahwa CSR adalah respon politik
dengan bisnis untuk tekanan sosial. Daripada melihat ini sebagai keterbatasan
fundamental, bagaimanapun, mereka menemukan ruang untuk optimisme dalam
menemukan sumber agen dan otoritas dalam organisasi-organisasi masyarakat
sipil, mengklaim bahwa "Oleh karena itu tantangannya adalah untuk merebut
kesempatan yang diberikan oleh politik lingkungan perusahaan, tidak meratapi
nya eksistensi.14
Mencari CSR sebagai bagian dari tren menuju privatisasi pemerintahan
memberikan perspektif yang lebih kritis bahwa pandangan lokus kekuasaan dalam
sektor korporasi bukan dalam unsur-unsur masyarakat sipil. Kritikus berpendapat
bahwa istilah-istilah seperti CSR, corporate citizenship, dan pembangunan yang
berkelanjutan mencerminkan perusahaan-ekonomi daripada rasionalitas sosial
atau ekologis .15
Cutler (1999: 3) mengamati bahwa "Tingkat signifikan tatanan global
disediakan oleh perusahaan-perusahaan individu yang sepakat
14 D. F. Murphy, & J. Bendell, Partners in time? Business, NGOs, and sustainable development, United Nations Reserach Institute for Social Development: Geneva, 1999. hal 67. 15 S. B. Banerjee. Who sustains whose development? Sustainable development and the reinvention of nature, Organization Studies, 24(2), 2003, hal. 143.
untuk bekerja
I. 10
sama, baik secara formal maupun informal, dalam membangun kerangka kerja
internasional untuk kegiatan ekonomi mereka" Dalam kaitannya dengan CSR,
kerangka kerja ini mungkin terdiri Kode perilaku seperti kode industri 4C untuk
kopi, standar untuk pelaporan dan audit sosial seperti global Reporting Initiative,
atau standar pelabelan produk seperti Kehutanan Stewardship Council . Konsep
pemerintahan meluas ke norma-norma dan struktur otoritas di mana perjanjian ini
tertanam. Sebuah kompleks terintegrasi dari lembaga formal dan informal yang
merupakan sumber pemerintahan untuk wilayah masalah ekonomi secara
keseluruhan" menggunakan "rezim swasta" istilah untuk menyebut Meskipun
mereka mengakui bahwa otoritas pribadi pada akhirnya berasal sanksi dan
legitimasi dari negara dan masyarakat, mereka mengungkapkan keprihatinan
dengan kaburnya batas antara negara dan otoritas pribadi. gema titik ini dalam
menekankan karakter, masyarakat politik CSR tapi kurangnya akuntabilitas
demokratis: "Ketika perusahaan-perusahaan terlibat dalam upaya sukarela, mereka
membuat keputusan tentang alokasi sumber daya menakut-nakuti untuk
kepentingan publik."16
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada dasarnya mengharuskan
perusahaan untuk melakukan bisnis di luar kepatuhan dengan hukum dan
melampaui pemegang saham untuk maksimalisasi kekayaan. Ini menunjukkan
bahwa perusahaan harus melakukan lebih dari mereka wajib lakukan berdasarkan
hukum yang berlaku yang mengatur keamanan produk, perlindungan lingkungan ,
hak buruh, hak asasi manusia, pengembangan masyarakat,
16 C. A. Cutler, V. Haufler, & Porter, T. (Eds.), Private authority and international affairs, Albany, SUNY Press: NY, 1999. hal 39.
korupsi, dan
I. 11
sebagainya, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan harus
mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pemegang saham tetapi juga
stakeholder lainnya misalnya, karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat
lokal.
CSR mengharuskan perusahaan untuk memberikan tidak hanya jumlah
barang, jasa, dan pekerjaan tetapi juga kualitas hidup orang-orang yang
kepentingannya terkena dampak kegiatan perusahaan. Konsep abstrak CSR telah
berubah menjadi daftar panjang praktek-praktek perusahaan , namun tidak
terbatas pada, sistem manajemen lingkungan, ramah lingkungan dan aman
produk, tindakan perlindungan tenaga kerja dan rencana kesejahteraan, filantropi
perusahaan dan masyarakat proyek-proyek pembangunan, dan perusahaan sosial
dan lingkungan pengungkapan kinerja .17
Di antara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia
masih tergolong rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang
memberikan laporan mengenai aktivitas sosial yang dilaksanakannya. Ikatan
Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005
mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Secara umum
ISRA bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada
perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan
yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan
I.1.2 CSR di Indonesia
17 Carroll Archie B, A History Corporate Social Responsibility, dalam A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J.Moon and D. Siegeleds, The Oxford Handbook Of Corporate Social Responsibility, 2008, hal.2.
I. 12
yang diberikan adalah Best Social and Environmental Report Award, Best Social
Reporting Award, Best Environmental Reporting Award, dan Best Website.18
Pada Tahun 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best
Sustainability ReportsAward, Best Social and Environmental Report Award, Best
Social Reporting Award,Best Website, Impressive Sustainability Report Award,
Progressive Social Responsibility Award, dan Impressive Website Award. Pada
Tahun 2007 kategori diubah dengan menghilangkan kategori impressive dan
progressive dan menambah penghargaan khusus berupa Commendation for
Sustainability Reporting: First Time Sutainability Report. Sampai dengan ISRA
2007 perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi keikutsertaan
dalam ISRA. Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari sejarah
perkembangan PKBL.
19
Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan
Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan
Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan
sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan
No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman
Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik
Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5%
18 Diakses dari http://www.csrindonesia.com pada tanggal 13 oktober 2011 pukul 20.30 wib 19 Ibid
I. 13
dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program
Pegelkop.20
Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan
Usaha Keciln dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan
Usaha Milik Negara. Memperhatikan perkembangann ekonomi dan kebutuhan
masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami
penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/MPBUMN/ 1999 tanggal
28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN,
Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-
05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
21
Keberadaan CSR itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari keberadaan
industri korporasi, yang nantinya CSR inilah yang menjadi tema pokok penelitian
ini. CSR dalam pandangan common sense adalah sebuah bentuk tanggung jawab
sebuah perusahaan terhdap masyarakat sekitarnya.. Keberadaan CSR sendiri
sering diartikan sebagai representasi dari peran serta pembangunan yang dilakukan
20 Diakses dari http://www.csrindonesia.com pada tanggal 13 oktober 2011 pukul 20.30 wib 21 Ibid
I. 14
oleh pihak swasta . Pada tataran masyarakat, kehadiran CSR dianggap mewakili
masyarakat guna membantu peran serta pemerintah dalam mulakukan upaya
pembangunan. Dalam pandangan common sense, posisi atau kedudukan CSR
tersebut bersifat netral dan normatif.
Pandangan common sense terhadap CSR berbeda dengan pandangan teori
kritis atau teori frankfurt. Teori kritis memandang bahwa posisi CSR bersifat
ideologis atau menyatakan keberpihakan dan pandangan teori kritis bersifat
historis. Secara historis, CSR lahir atas respon msyarakat global terhadap proses
industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi MNC/TNC yang secara nyata
menyebabkan masalah ekologi yang serius dan bahwa ini perlu ditangani. Fakta-
fakta stres ekologi pada tingkat planet yang jelas, meskipun penting mereka tidak
universal disepakati. Ada banyak indikator stres seperti: lahan pertanian, hutan
hujan dan berhutan daerah, padang rumput dan sumber air tawar semua berisiko.
Pada tingkat global, lautan, sungai dan ekosistem air lainnya menderita parah
ekologi tertekan. Sementara rincian dari ekologi yang akan datang krisis masih
diperdebatkan, kebanyakan orang tampaknya lebih sadar manusia dampak
terhadap lingkungan daripada sebelumnya. Sebagian besar perusahaan sekarang
mengeluarkan laporan dampak lingkungan.
Eksistensi CSR itu sendiri mengalami problematik di tengah masyarakat,
banyak terjadi kesalahan baik dalam teori maupun praktek, di Indonesia sendiri
terjadi beberapa permasalahan di tubuh CSR itu sendiri, antara lain :
1. Sebagai sebuah tanggung jawab moral-sosial, UU ini telah mengabaikan
sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR
I. 15
tersebut. Sonny Keraf (Etika Bisnis, 1998) menyebut tiga prasyarat
dimaksud: sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan
bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus
sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat
mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.Dalam ranah norma
kehidupan manusia modern, kita dilingkupi dan sekaligus menjalankan
sejumlah norma yang berbeda: norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa
mengabaikan kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya, pada
domain lain perusahaan juga terikat pada norma moral-sosial sebagai
bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli CSR
sesungguhnya hendak bergerak dalam kerangka tersebut, di mana
perusahaan secara sadar memaknai aneka prasyarat tadi dan sekaligus
masyarakat bisa menakar komitmen pelaksanaannya.22
2. Dengan kewajiban semacam itu CSR lalu bermakna parsial sebatas upaya
pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari
kehadiran perusahaan. Dengan demikian, bentuk-bentuk program CSR
hanya terkait langsung dengan core business perusahaan, dengan wilayah
jangkauan sebatas stakeholders langsung (masyarakat sekitar) semata.
Padahal praktik yang berlangsung di banyak perusahaan selama ini, ada
atau tidaknya aktivitas terkait dampak lingkungan dan sosial tersebut,
perusahaan menjalankan program sosial langsung (seperti lingkungan
hidup) dan tak langsung (bukan core business) seperti rumah sakit,
22 Diakses dari Suara Pembaharuan, 31 Juli 2007.
I. 16
sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi hilangnya aneka
program tak langsung tersebut.
Peliknya permasalahan yang akan dibahas ini membuat penulis
membutuhkan perangkat analisis yang secara konseptual memiliki keseragaman
konsentrasi. Dalam penelitian sosial humaniora, paling tidak ada empat
paradigma pengetahuan yang memiliki konsentrasi pada tema sosial humaniora,
antara lain: paradigma positivisme, teori kritis, strukturalisme, dan anti essensialis
posmodernisme.
Sebagai perintis Positivisme, August Comte pada abad ke-19
memperkenalkan fisika sosial, yang sekarang bernama Sosiologi. Jika pada
Rasionalisme dan Empirisme pengetahuan masih direfleksikan maka dalam
Positivisme dirubah dengan metodologi ilmu alam. Hal ini membuat penelitiannya
berporos pada observasi dan pembuktian empiris. Secara praktis gunanya untuk
mengetahui hukum-hukum apa yang mengatur masyarakat sehingga dapat
melakukan rekayasa, social engineering melalui Sosiologi. Positivisme memang
sesuai jika di terapkan dalam ilmu alam namun menjadi bermasalah ketika
diterapkan pada ilmu sosial karena obyek ilmu sosial yaitu manusia tidak dapat
diprediksi dan dikuasai secara teknis.23
Berbeda dengan aliran positivis, teori kritis menganggap positivisme
sebagai pengetahuan yang pro status quo, anti demokrasi, tidak humanis, dan
sebagai pengetahuan yang teramat dangkal karena klaim-klaim positivis yang
justru menjatuhkan semangat ilmu pengetahuan itu sendiri dengan kebeperihakan
23 Teddy, G, Tahappary. 2009. Menyingkap Selubung Ideologi Industri Musik Indonesia: Analisa Teori Kritis Mengenai Keberpihakan Industri Musik Di Indonesia. hal 19
I. 17
terhadap nilai-nilai dominatif. Secara umum ilmu sosial teori kritis adalah ilmu
yang secara terus menerus malakukan proses kritik terhadap ilusi yang didapati di
permukaan yang menutupi realitas sesungguhnya dari struktur dalam dunia nyata
yang berfungsi untuk merubah kondisi dan membangun dunia yang lebih baik
untuk kehidupan manusia itu sendiri.24
Klaim positivisme tentang pengetahuan berawal dari realitas yang natural
menjadi titik awal teori kritis untuk menyerang positivisme. Teori kritis
beranggapan bahwa sejak awal tidak ada realitas yang sifatnya natural, karena
sejak awal relitas sosial selalu timpang. Hal ini dikarenakan sejak awal klaim
bahwa realitas sosial bersifat natural justru terlihat sangat tidak natural karena
sebelum melakukan penelitian lebih lanjut kaum positivis sudah mendudukkan
Oleh karena itu, penulis memilih untuk menggunakan perangkat analisis
teori kritis generasi pertama dengan Max Horkheimmer dan Theodore W. Adorno
sebagai pelatak dasar awalnya dan bukan menggukan tokoh perseorangan
dikarenakan analisis tersebut tidak menkritisi subjek yang mungkin
kedudukannya ialah korporasi, melainkan yang menjadi persoalan adalah
normatifitas CSR yang berkedudukan sebagai objek dan menkritik metodologi.
Teori kritis ini lahir di Jerman yang terkenal dengan Frankfurt School
pada tahun 1930an. Teori kritis yang dimotori oleh Max Horkheimmer dan
Theodore W. Adorno pada awalnya ini secara terang-terangan mengkritisi
positivisme dan kedudukan keilmiahan yang sebelumnya selalu menjadi klaim
positivisme.
24 Ibid
I. 18
dulu posisi realitas natural sebagai sebuah kealamian, padahal sejatinya dengan
mengambil proposisi tersebut saja positivis sudah melakukan kesengajaan untuk
mengistimewakan realitas soaial terlebih dahulu, Yang berarti realitas sosial ini
tidak bersifat netral. Hal ini yang menjadikan asumasi dasar teori kritis untuk
menjelaskan bahwa sebenarnya sejak awal klaim positivis tentang realitas sosial
yang bersifat natural sudah gagal.
Dengan kata lain teori kritis menyepakati bagian tertentu dari kritik
interpretatif terhadap positivisme. Peneliti kritis mempelajari masa lalu untuk
melihat perubahan dengan tujuan mendapatkan cara alternatif untuk mengatur
kehidupan sosial yang baru dan lebih baik. Ilmu sosial kritis tertarik pada
pembangunan hubungan sosial yang baru, evolusi institusi sosial atau masyarakat
dan penyebab utama perubahan sosial. Peneliti kritis mencatatkan bahwa
perubahan sosial dan konflik tidak selalu nyata dan dapat diamati, terjadinya hal
tersebut karena realitas sosial penuh dengan ilusi, mitos dan terdistorsi.
Pengamatan dunia merupakan pengamatan sebagian saja karena keterbatasan rasa
manusia begitu juga ilmu pengetahuan.
Teori kritis menolak skeptisisme diatas dengan tetap memertahankan
kaitan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis
menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan
klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara
tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap memertahankan penekanan
terhadap normativitas dalam tradisi filsafat, teori kritis mendasarkan cara bacanya
I. 19
dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu, yang digunakan untuk
memahami klaim normatif itu dalam konteks kekinian
Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa penulis menggunakan alat
analisis teori kritis, dikarenakan teori kritis lah yang mendekati kesamaan
konsentrasi dengan tema yang diangkat oleh penulis dan dianggap oleh penulis
relevan untuk digunakan membahas tema ini. Pertama, keyakinan penulis bahwa
fakta-fakta yang ada bukanlah sesuatu hal yang bersifat natural, alami, atau terjadi
begitu saja. Tapi semua itu merupakan suatu rancangan atau by design, dalam
artian terdapat faktor-faktor yang mendorong dan mendukung terjadinya fakta
tersebut atau terdapat keberpihakan.
Hal tersebut sesuai dengan kritik teori kritis terhadap paradigma
positivisme yang menyatakan bahwa fakta-fakta yang terjadi merupakan suatu hal
yang alami, bersifat given dan bebas nilai. Kedua, penulis ingin membedah isu-isu
atau kepentingan yang diusung oleh CSR di Indonesia dan menyingkap selubung
ideologi.
I.2. Rumusan Masalah
Kelahiran CSR yang merupakan sebuah respon msyarakat global terhadap
proses industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi MNC/TNC yang secara nyata
menyebabkan masalah ekologi, HAM, dan permasalahan sosial lainya yang perlu
untuk segera ditangani. Fakta-fakta kerusakan ekologi pada tingkat planet a.l
dapat dilihat dari lahan pertanian, hutan hujan dan berhutan daerah, padang
rumput dan sumber air tawar semua berisiko. Pada tingkat global, lautan, sungai
I. 20
dan ekosistem air lainnya mengalami kerusakan. Seiring dengan
perkembangannya, CSR ini dianggap sebagai bentuk invisible hand dari
korporasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat global,
sehingga bisa melakukan proses produksi secara berkelanjutan.
CSR dinilai sebagai produk internasional, yang dalam tujuan awalnya
merupakan kerangka besar agenda pembangunan dunia yang ingin mengentaskan
permasalahan yang ada di dunia khususnya di negara-negara berkembang
terutama bertujuan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu diambilah
kebijakan oleh PBB bahwasanya pihak korporasi / nonstate harus membantu
dalam permasalahan pembangunan yakni melalui program CSR.
Namun dalam perspektif kritis, CSR itu sendiri tak lepas dari pada
ideologi yang berperan, ideologi tersebut dimaksud ialah sistem kerangka berpikir
yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang
mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok
sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.
Munculnya MDGs (Millenium Development Goals) sebagai peletak dasar
kemunculan CSR tak lepas dari ideologi yang mendominasi disana. MDGs dinilai
sangat penting karena menjadi sebuah strategi keberadaan korporasi untuk tetap
melakukan proses produksi dengan menekankan agenda-agenda terselubung yang
di praktekan melalui program CSR sebagai timbal balik dr perusahaan tersebut
terhadap masyarakat sekitar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah CSR adalah bentuk
kepedulian korporasi atau mempunyai agenda terselubung yang hanya mencari
I. 21
selamat mengenai keberadaanya di lingkungan suatu masyarakat dan juga
mengura jejak ideologi. Secara lebih rinci penelitian hendak menjawab beberapa
pertanyaan berikut:
1. Bagaimana CSR menjadi sebuah strategi pembanguan di Indonesia?
2. Apa ideologi yang beroperasi dalam pelaksanaan CSR di Indonesia ?
3. Bagaimana ideologi tersebut beroperasi dalam pelaksanaan CSR di
Indonesia ?
I.3. Tujuan Penelitian
Menimbang dari kajian teoritik yang diangkat oleh penulis, tidaklah terlalu
berlebihan apabila penelitian ini bertujuan melakukan kritik terhadap ideologi
CSR di Indonesia. Sesuai dengan paradigma yang digunakan, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengembalikan keberpihakan industri. Membongkar klaim-klaim
obyektif atas ideologi CSR yang sebenarnya melindungi dan melegitimasikan
kepentingan-kepentingan dominasi.
Selain itu penulis berekeinginan untuk membuktikan apa yang dibicarakan
oleh kaum liberal yang bersembunyi di balik implementasi CSR itu membangun
masyarakat, tidak ada politik, ideologi, kepentingan apapun didalamnya selain
kepentingan membangun ataupun memberdayakan masyarkat yang berlaku pada
konteks di Indonesia saat ini.
I. 22
I.4. Manfaat Penelitian
Bagi penulis:
• Sebagai media aktualisasi diri, dimana karya penulisan ini menjadi media
pembelajaran untuk mengetahui sampai sejauh manakah penulis memahami
studi yang digeluti oleh penulis.
• Selain sebagai media pembelajaran dan media aktualisasi diri, karya
penulisan ini juga bermanfaat sebagai pemuas hasrat intelektual penulis.
Bagi kampus:
• Memberikan kontribusi baru bagi studi-studi Sosiologi.
• Menawarkan alternatif yang berpotensi sebagai alat analisis dalam studi-
studi Sosiologi
Bagi masyarakat:
• Diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat tentang selubung
ideologi yang selama ini dianggap natural, given, dan bebas nilai.
I.5. Kajian Teoritik
I.5.1 Positivisme
I.5.1.1 Normatif
Masyarakat ideal menurut Comte adalah masyarakat yang menjunjung
tinggi cinta dan pengabdian pada kemanusiaan. Sifat Altruis ini tertanam dalam
proses evolusi masyarakat yang linier dari masyarakat teologis hingga yang paling
paripurna yaitu masyarakat positivis. Pada awalnya, masyarakat tidak mengetahui
apa-apa, maka kehendak mereka didasari ketidaktahuan tersebut. Adalah tugas
I. 23
para filsuf positivistis dan para ilmuwan untuk mengawal dan mengorganisasikan
masyarakat menuju terwujudnya “agama kemanusiaan”. Gerak progresif
masyarakat menurut hemat Comte, ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
Secara kontras, dua pemikir lain yaitu Hobbes dan Locke, memiliki
pandangan berbeda dibanding masyarakat altruis Comte. John Locke menyatakan
bahwa secara alami masyarakat dikaruniai akal oleh Tuhan untuk dapat
membedakan antara yang benar dan yang salah25
Masyarakat menurut Hobbes memiliki kecenderungan untuk mengingkari
consensus. Sehingga manusia menjadi serigala untuk manusia lainnya (homo
homini lupus). Untuk menjaga hak-hak alami manusia, akhirnya tercapai
konsensus untuk membentuk Negara. Hobbes menggambarkan Negara sebagai
makhluk besar yang kejam bernama Leviathan. Kesediaan masyarakat untuk
menyerahkan kedaulatannya didasari oleh kesadaran yang dibentuk oleh represi
sang penguasa.
. Selain itu manusia juga
memiliki hak alami yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan mendapatkan hak
milik. Masyarakat awal diatur oleh hukum-hukum alam dan tanpa Tuhan pun hak-
hak ini dapat terpenuhi. Namun karena munculnya kriminalitas, perselisihan, dan
masalah-masalah lainnya, masyarakat membuat kontrak sosial guna menciptakan
pemerintahan yang bias melindungi hak-hak alami mereka.
Perbedaan mendasar ketiganya terletak pada peran masyarakat
menentukan dirinya. Locke dan Hobbes menggunakan entitas di luar masyarakat
(Negara/penguasa) untuk mengatur masyarakat, sedangkan Comte percaya bahwa
25 Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir. Penerbit Qalam: Yogyakarta, 2004, hal 22.
I. 24
masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri lewat evolusi
pengetahuannya.
I.5.1.2 Linier
Runtuhnya tatanan feodal dan dogmatika gereja tradisional serta sistem
metafisika, membuat para pemikir abad ke-19 mencoba untuk menemukan sistem
integrasi baru. Salah satunya adalah membuat sebuah rekonstrusi histories tentang
sistem pengetahuan dan tahapan-tahapannya. Asumsinya adalah perkembangan
pengetahuan seperti pada perkembangan ilmu-ilmu alam yang berjalan progresif,
niscaya, dan linear. Ilmuwan yang berhasil menemukan bentuk yang
komprehensif adalah August Comte.
Menurut Comte, sejarah pengetahuan berkembang melalui tiga tahap,
yaitu “tahap teologis”, “tahap metafisis”, dan “tahap positivis”. Pada tahap
teologis, manusia menempatkan kekuatan adimanusiawi untuk mencari penjelasan
atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Tahap metafisis ditandai dengan
diubahnya kekuatan adimanusiawi menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Dan
akhirnya, manusia mencapai kedewasaan mental pada tahapan metafisis. Pada
tahap ini, manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab diluar fakta yang teramati.
Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, tetapi juga bersifat pasti
dan berguna.
I. 25
I.5.1.3 Natural
Oleh Comte Sosiologi di bagi dua, yaitu statika sosial dan dinamika sosial.
Masyarakat adalah kenyataan yang tertata rapi juga berubah. Statika sosial
mempelajari tatanan sosial itu dengan segala hukum yang mengaturnya. Dinamika
sosial mempelajari hukum-hukum perubahan dan kemajuan sosial. Keduanya
berkaitan erat, sebab perubahan tanpa tatanan melahirkan anarki dan tatanan tanpa
perubahan adalah stagnasi Dengan mengetahui tatanan (statika sosial), sosiologi
dapat mengarahkan perkembangan masyarakat ke sebuah susunan yang lebih baik
(dinamika sosial).
Di dalam pembahasan tentang masyarakat, Comte menerima premis
bahwa “masyarakat adalah laksana organisme hidup”26. Walau dia tidak benar-
benar berusaha mengembangkan tesis ini, Herbert Spencer membahas berbagai
perbedaan dan persamaan yang khusus antara sistem biologis dan sistem sosial
berdasarkan premis tersebut. Inti pemikirannya sebagai berikut27
26 Margaret M, Poloma, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press: Jakarta, 2007, hal 23. 27 Ibid. hal 24.
: Pertama,
masyarakat dan organisme sama-sama mengalami pertumbuhan. Kedua, karena
pertumbuhannya, maka struktur tubuh-sosial (social body) itu mengalami
pertambahan pula. Ketiga ,tiap bagian tubuh sosial tersebut memiliki fungsi dan
tujuan. Keempat, perubahan pada satu bagian sistem akan berpengaruh pada
bagian sitem yang lain. Sosiolog Perancis Emile Durkheim menambahkan, sistem
masyarakat memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi yang mana jika tidak
terpenuhi atau tidak berjalan fungsinya, akan dianggap sebagai patologi.
I. 26
Namun ilmuan positivis tetap menganggap bahwa masyarakat berjalan
dengan alamiah. Semua perubahan terjadi secara perlahan dan dapat
diperhitungkan. Hal ini diperkuat oleh argumen Talcott Parson yang menyebutkan
bahwa sistem sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan dan stabilitas.
Dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem. Bilamana terjadi
kekacauan norma-norma, maka sistem akan mengadakan penyesuaian kembali
mencapai keadaan normal28
I.5.2 Teori Kritis
.
I.5.2.1 Historis
Sebagaimana telah dirumuskan kembali oleh Juergen Habermas, teori
kritis bukanlah suatu teori ‘ilmiah sebagaimana dinenal secara luas dikenal di
kalangan publik akademis dalam masyarakat kita. Teori kritis tidak berhenti pada
fakta objektif seperti yang dianut oleh teori-teori positivis. Teori kritis hendak
menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi-
kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutub
ilmu pengetahuan dimaksudkan teori kritis juga bersifat historis dan tidak
meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual.
I.5.2.2 Dialektis
Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat
transendental dan yang bersifat empiris. Karena sifat dialektis itu teori kritis
28 Ibid. Hal 172
I. 27
dimungkinkan untuk melakukan dua macam kritik. Di satu pihak melakukan
kritik transendental dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan
pengetahuan dalam diri subjek sendiri.
Di lain pihak melakukan kritik imanen dengan menemukan kondisi-
kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan
manusia. Dengan kata lain, teori kritis merupakan kritik ideologi bila pengetahuan
manusia jatuh pada salah satu kutub, entah transedental entah empiris.
I.5.2.3 Dominasi
Teori kritis mengemban misi untuk mengungkap ‘kedok’ ideologi
positivisme, bukan hanya pandangannya sebagai ilmu pengetahuan, melainkan
juga sebagai cara berpikir yang menjangkiti kesadaran masyarakat industri maju.
Oleh teori kritis, fakta selalu dilihat dalam posisi yang timpang. Selalu ada salah
satu pihak yang mendominasi pihak lain. Karena itulah teori kritis ingin
mengembalikan posisi ilmu pengetahuan untuk berpihak pada kepentingan
masyarakat yang didominasi ini.
I.6 Metode Penelitian
Sebagai sebuah pengetahuan, baik positivisme maupun teori kritis
memiliki metode yang konsisten sesuai dengan refleksi dan kritik yang diberikan
terhadap pengetahuan sebelumnya. Dan pada subbab metode ini, peneliti sengaja
menghadirkan metode kedua teori tersebut agar nantinya dapat diketahui bahwa
I. 28
teori kritis memberikan kritik terhadap positivisme hingga pada tingkatan
metodologi.
I.6.1 Positivisme
Positivisme mendedahkan dirinya sebagai satu-satunya pengetahuan yang
memiliki metode yang valid untuk menemukan hukum-hukum yang melandasi
perkembangan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, positivisme yang
menyediakan seperangkat metodologi yang merupakan gabungan dari
pengetahuan sebelumnya, yakni rasionalisme dan empirisme. Metodologi terdiri
dari korelasi dua variable, hipotesis, populasi, instrumen penelitian, dan skala
statistik.
Sebagai ilmu alam yang memperlakukan objeknya sebagai kategori yang
fix, begitu juga dengan positivisme yang mereduksi manusia beserta relasinya
yang unik. Hal ini dilakukan agar positivisme mampu mengkontrol dan
menghasilkan hukum-hukum universal. Semangat semacam ini yang nantinya
akan dikritik oleh teori kritis.
Filasafat modern berkembang melalui dua aliran, pertama dibidani oleh
plato yang mengutamakan kekuatan rasio manusia, yaitu pengetahuan murni
dianggap dapat diperoleh melalui rasio itu sendiri (apriori). Kedua adalah
Aristoteles yang memerhatikan peranan empiris terhadap objek pengetahuan
(aposteoritis). Selanjutnya masing-masing melahirkan penerus, rasio didukung
oleh Rene Descartes, Malebrace, Spinoza, Leibnies, dan Wolf. Filsafat empirisme
berkembang di tangan Hobbes, Locke, Barkley, dan Hume (Hardiman,1990). Ilmu
I. 29
alam berkembang melalui empirisme dan rasionalisme yang memisahkan
kepentingan dan teori.29
Empirisme dan rasionalisme ilmu alam bisa dikembangkan sebagai
metode ilmu sosial menurut keyakinan para tokoh-tokoh terdahulu ilmu sosial.
Sehingga kedua metode tersebut melahirkan filsafat positifisme dalam ilmu sosial.
Sosiologi Comte menandai positivisme awal dalam ilmu sosial, mengadopsi
saintisme ilmu alam yang menggunakan prosedur-prosedur metodologis ilmu
alam dengan mengabaikan subyektivitas .Subjek peneliti dalam Paradigma
Positivisme diharuskan untuk taat prosedur, untuk mendapatkan hasil penelitian
yang valid, ilmiah dan berlaku universal. Positivisme menggunakan metode ilmu
alam dalam penelitiannya, sehingga menuntut peneliti untuk mendapatkan data
yang tidak dinodai oleh interpretasi dan pemberian makna, baik oleh objek
maupun subjek peneliti.
30
Positivisme ilmu sosial mencita-citakan ilmu yang bebas nilai, objektif,
terlepas dari perasaan subjektif seperti moralitas dan kepentingan. Semangat ini
menyajikan pengetahuan yang universal yang terlepas dari konteks dan sejarah.
Pengatahuan yang terlepas dari ruang dan waktu. Positivisme merupakan usaha
membersihkan pengetahuan dari kepentingan untuk melahirkan teori yang bebas
nilai dari subyektivitas manusia.
31
Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta obyektif sebagai
pengetahuan yang sahih. Dengan klaim semangat ilmiah, ia melakukan penolakan
29 Novri Susan, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Kencana: Jakarta, 2009, Hal.12. 30 John D Brewer, Ethnography, Open University Press: Buckingham, 2005, Hal 31 31 Novri Susan, Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Kencana: Jakarta, 2009, Hal.12.
I. 30
terhadap mode pengetahuan yang melampaui fakta atau dengan kata lain,
menghindarkan diri dari spekulasi metafisika. Positivisme sebagai metodologi
yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme merupakan puncak
pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita ntuk
memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari
praxis hidup manusia.32
I.6.2 Teori Kritis
Berikut beberapa pengandaian dari paradigma positivisme. Pertama,
bahwa prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung
diterapkan pada ilmu-ilmu sosial. Kedua, hasil-hasil penelitian itu dapat
dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga,
ilmu-ilmu sosial bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat
instrumental murni. Pengetahuan itu harus dapat dipakai untuk keperluan apa saja
sehingga tidak bersifat etis dan juga tidak terkait pada dimensi politis manusia.
Ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu-ilmu alam, bersifat netral dan bebas nilai.
Istilah teori kritis pertama kali ditemukan Max Horkheimer pada tahun 30-
an. Pada mulanya teori kritis berarti pemaknaan kembali ideal-ideal modernitas
tentang nalar dan kebebasan, dengan mengungkap deviasi dari idealideal itu
dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri kebudayaan, dan institusi politik
borjuis.
32 F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, Kanisius: Yogyakarta, 2003, hal. 9.
I. 31
Untuk memahami pendekatan teori kritis, ia harus ditempatkan dalam
konteks Idealisme Jerman dan kelanjutannya. Karl Marx dan generasinya
menganggap Hegel sebagai orang terakhir dalam tradisi besar pemikiran filosofis
yang mampu ”mengamankan” pengetahuan tentang manusia dan sejarah. Namun,
karena beberapa hal, pemikiran Marx mampu menggantikan filsafat teoritis Hegel,
yang hal ini, menurut Marx, terjadi dengan membuat filsafat sebagai hal yang
praktis; yakni merubah praktik-praktik yang dengannya masyarakat mewujudkan
idealnya. Dengan menjadikan nalar sebagai sesuatu yang ’sosial’ dan menyejarah,
skeptisisme historis akan muncul untuk merelatifkan klaim klaim filosofis tentang
norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya kehidupan.
Teori kritis menolak skeptisisme diatas dengan tetap memertahankan
kaitan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis
menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan
klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara
tradisional merupakan bahasan filsafat. Dengan tetap memertahankan penekanan
terhadap normativitas dalam tradisi filsafat, teori kritis mendasarkan cara bacanya
dalam konteks jenis penelitian sosial empiris tertentu, yang digunakan untuk
memahami klaim normatif itu dalam konteks kekinian.
Di zaman modern, filsafat secara ketat dibedakan dari sains. Locke
menyebut filsafat sebagai ’pekerja kasar’. Bagi Kant, filsafat, khususnya filsafat
transenden, memiliki dua peran. Pertama, sebagai ”hakim” yang dengannya sains
dinilai. Kedua, sebagai wilayah untuk memunculkan pertanyaan normatif. Untuk
I. 32
menjawab pertanyaan-pertanyaan normatif, dalam perspektif Kantian, sains tidak
dibutuhkan, karena hal itu dijawab melalui analisis transenden.
Teori kritis yang berorientasi emansipasi berusaha mengkontekstualisasi
klaim-klaim filosofi tentang kebenaran dan universalitas moral tanpa
mereduksinya menjadi sekedar kondisi sosial yang menyejarah. Teori kritis
berusaha menghindari hilangnya kebenaran yang telah dicapai oleh pengetahuan
masa lalu. Tentang hal ini Horkheimer menyatakan ”Bahwa semua pemikiran,
benar atau salah, tergantung pada keadaan yang berubah sama sekali tidak
berpengaruh pada validitas sains”.
Teori kritis memungkinkan kita membaca produksi budaya dan
komunikasi dalam perspektif yang luas dan beragam. Ia bertujuan untuk
melakukan eksplorasi refleksif terhadap pengalaman yang kita alami dan cara kita
mendefinisikan diri sendiri, budaya kita, dan dunia. Hal ini didorong oleh
kesadaran bahwa makna bukanlah sesuatu yang alamiah dan langsung. Bahasa
bukanlah media transparan yang dapat menyampaikan ide-ide tanpa dominasi,
sebaliknya ia adalah seperangkat kesepakatan yang berpengaruh dan menentukan
jenis-jenis ide dan pengalaman manusia. Dengan berusaha memahami proses
dimana teks, objek, dan manusia diasosiasikan dengan makna-makna tertentu,
teori kritis memertanyakan legitimasi anggapan umum tentang pengalaman,
pengetahuan, dan kebenaran.
Dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain dan alam, dalam kepala
seseorang selalu menyimpan seperangkat kepercayaan dan asumsi yang terbentuk
dari pengalaman dalam arti luas dan berpengaruh pada cara pandang seseorang,
I. 33
yang sering tidak tampak. Teori kritis berusaha mengungkap dan
mempertanyakan asumsi dan praduga itu. Dalam usahanya, teori kritis
menggunakan ide-ide dari bidang lain untuk memahami pola-pola dimana teks
dan cara baca berinteraksi dengan dunia.
Hal ini mendorong munculnya model pembacaan baru. Karenanya, salah
satu ciri khas teori kritis adalah pembacaan kritis dari dari berbagai segi dan luas.
Teori kritis adalah perangkat nalar yang, jika diposisikan dengan tepat dalam
sejarah, mampu merubah dunia. Pemikiran ini dapat dilacak dalam asumsi Marx
terkenal yang menyatakan ”Filosof selalu menafsirkan dunia, tujuannya untuk
merubahnya”. Ide ini berasal dari Hegel yang, dalam Phenomenology of Spirit,
mengembangkan konsep tentang objek bergerak yang, melalui proses refleksi-diri,
mengetahui dirinya pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi.Hegel
menggabungkan filsafat tindakan dengan filsafat refleksi sedemikian rupa
sehingga aktivitas atau tindakan menjadi momen niscaya dalam proses refleksi.
Hal ini memunculkan diskursus dalam filsafat Jerman tentang hubungan
antara teori dan praktis, yakni bahwa aktivitas praktis manusia dapat merubah
teori. Teori kritis, dengan demikian, adalah pembacaan filosofis dalam arti
tradisional yang disertai kesadaran terhadap pengaruh yang mungkin ada dalam
bangunan ilmu, termasuk didalamnya pengaruh kepentingan. Teori kritis, dalam
konteks perdebatan metode antara ilmu pengetahuan dan filsafat, memiliki
kehendak untuk menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk
menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data
empiris.
I. 34
Dengan kutub ilmu penegetahuan dimaksudkan bahwa teori kritis juga
bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman
kontekstual. Dengan demikian, Teori Kritis tidak hendak jatuh pada metafisika.
Teori Kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental
dan yang bersifat empiris. Karena sifat dialektis itu, Teori Kritis dimungkinkan
untuk melakukan dua macam kritik. Di satu pihak melakukan kritik transendental
dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri
subyek sendiri. Di lain pihak melakukan kritik imanen dengan menemukan
kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi
pengetahuan manusia.
Pada taraf teori pengetahuan, Teori Kritis berusaha mengatasi pemahaman
saintisme atau positivisme. Pemahaman positivistis atas ilmu-ilmu sosial
mengandung relevansi politik yang sama beratnya dengan klaim-klaim politis
lain, karena pemahaman itu berfungsi dalam melanggengkan status quo
masyarakat. Sebaliknya, interaksi sosial sendiri diarahkan oleh cara berpikir
teknokratis dan positivistis yang pada prinsipnya adalah rasio instrumental atau
rasionalita teknologis ke dalam situasi ideologis itulah Teori Kritis membawa misi
emansipatoris untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang lebih
rasional melalui refleksi diri. Seperti yang dikatakan oleh Hardiman bahwa “Teori
kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk
menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data
empiris. Teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang
I. 35
diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian, teori kritis merupakan
dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan empiris”.33
Sebaliknya, interaksi sosial sendiri diarahkan oleh cara berpikir
teknokratis dan positivistis yang pada prinsipnya adalah rasio instrumental atau
rasionalita teknologis. Ke dalam situasi ideologis itulah Teori Kritis membawa
misi emansipatoris untuk mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yanglebih
rasional melalui refleksi diri. Seperti yang dikatakan oleh Hardiman bahwa“Teori
kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis, untuk
menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data
empiris. Teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang
diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian, teori kritis merupakan
dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan empiris”.
34
Konsistensi dari teori kritis untuk melakukan kritik terhadap positivisme
terus berlanjut yaitu ketika positivis menjelaskan tentang posisi ilmu pengetahuan
yang seharusnya bebas nilai. Teori kritis mengkritisi bahwa dengan membiarkan
ilmu pengetahuan yang bebas nilai justru akan membuka ruang luas bagi nilai
yang dianggap melakukan dominasi terhadap yang lain, sehingga teori kritis
menganggap bahwa posisi tawar yang diajukan oleh positivis justru memiliki
potensi untuk pro status quo, dimana posisi bebas nilai yang berarti tidak bersikap
ini justru menguntungkan bagi nilai-nilai dominatif (termasuk pengetahuan itu
sendiri) yang pada akhirnya menegasikan peran manusia dan semangat
humanisme ilmu pengetahuan itu sendiri. Teori kritis melalui beberap tokohnya
33 Budi Hardiman, Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas, Kanisius: Yogyakarta, 2009, hal. 16 34 Ibid.hal.16
I. 36
yang terkenal seperti Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, Fromm, serta
Habermas mangajukan tawaran dimana seharusnya ilmu pengetahuan itu
berpihak kepada kemanusiaan yaitu dengan membela nilai-nilai kemanusiaan itu
sendiri tanpa harus tunduk dengan nilai dominatif yang ada termasuk ilmu
pengetahuan itu sendiri.
Ilmu sosial berparadigma kritis mengkritik positivisme terlalu
mengutamakan realitas mempengaruhi cara berpikir manusia dan juga
mengabaikan konteks sosial. Dengan demikian secara umum ilmu sosial kritis
dapat dikatakan sebagai suatu proses kritis untuk membongkar sesuatu yang tak
terlihat yang menutupi struktur masyarakat yang menindasnya dalam usaha untuk
merubah kehidupan dunia yang lebih baik. Ilmu sosial kritis sepakat dengan
sebagian kritik intepretatif pada positivisme. Ilmu sosial kritis mengkritik
intepretatif dan positivisme karena mengalami kemandekan anti demokrasi dan
anti humanis pada tataran praksis. selain itu ilmu sosial kritis memandang setiap
sudut dari realitas sebagai hal yang sama penting.
I.6.2.1 Subversif
Pada dasarnya cara kerja pengetahuan kritis (Hardiman, 2007) dalam
membedah realitas berprinsip pada kecurigaan atas kebenaran umum (common
sense). Bagi teori kritis kebenaran umum yang selalu diapit oleh dominasi negara,
agama, pengetahuan dan investasi, ujungnya berpihak pada superioritas klas, klan,
ras, sex/gender. Maka setiap bentuk kebenaran yang megendap maupun yang
I. 37
dilestarikan di masyarakat haruslah ditakar menurut semangat equality (kesamaan
derajat).
Bila seluruh kebenaran wajib ditakar derajat ketimpangannya. Dan
susahnya dari berbagai pembuktian atas keadaan sosial yang telah dijalani oleh
teori kritis ternyata selubung keberpihakan yang paling bermasalah adalah alur
nalar dari setiap personal. Dan mereka dicurigai terinfeksi oleh karakteristik
berfikir modern yang rasis, sexis. Agar tidak terlalu berjarak penulis akan
memberikan contoh: safari ritual seperti Haji, ziarah ke Yerusalem, sungai gangga
dst. seluruh bentuk ziarah agama tidak lain adalah upaya negara tujuan dalam
melestarikan semangat monopoli yang dikandung dalam rahim Kapitalis.
Di sisi lain semangat monopoli yang mengendap pada ritual keagamaan
hanya akan berujung pada sikap antagonis antar penganutnya, dimana penganut
satu ditegakkan dengan menggerus yang lain. Akhirnya hanya menanam benih
pertikaian antar umat beragama. Maka korelasi antara ritual ziarah dengan pahala
menjadi mentah. Yang ada adalah bibit pertikaian dengan supremasi klas.
I.6.2.2 Historis
Teori kritis menghindarkan diri dari model berpikir kausalitas (sebab-
akibat) sebagaimana yang telah dilakukan oleh perspektif-perspektif yang
mengadopsi ilmu alam. Karena dengan alur seperti ini, perspektif berbasis ilmu
alam tersebut justru mengabaikan dan mereduksi subyek yang unik dan spesifik
serta lepas dari historisitasnya.
I. 38
Maka dari itu, teori kritis menawarkan metode baru yang keluar dari
common sense, yakni dengan penelusuran historis. Yang harus diperhatikan untuk
masuk ke dalam pemikiran teori kritis adalah memahami alurnya ketika
digunakan sebagai alat baca. Alur teori kritis adalah sebagai berikut: keluar dari
common sense (kebenaran umum), melakukan pelacakan historis, menemukan
keberpihakan, dan memberikan tawaran.
1.6.3 Kontekstualisasi Metode
1.6.3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan Analisis Wacana. Analisis Wacana sebagai
pendekatan metodologis tertentu yang menjadi dasar Teori Kritis, Psikologi
Sosial, dan Cultural Studies.35 Wacana bukan hanya koleksi dari kata atau
kalimat: Sebuah wacana dalam integrasi dari kalimat yang menghasilkan makna
global yang lebih dari itu terkandung dalam kalimat yang dilihat secara
independen.36
35 Raymond A. Morrow. Critical Theory and Methodology. Vol 3. California : Sage Publications. 1994. hal 259. 36 Ibid hal 261
Penelitian ini menjelaskan mengenai CSR baik berupa teks maupun
pemikiran secara historis dari diskursus CSR yang timbul sebagai jargon
MNC/TNC yang berkampanye tentang penyelematan bumi akibat kerusakan yang
dilakukan oleh proses produksi.
I. 39
I.6.3.2 Isu – isu Penelitian
Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk membedakan pokok masalah
yang akan dibahas nantinya. Penulis membedakan definisi konseptual ideologi,
industri dan CSR dengan menggunakan alat baca positivisme dan teori kritis.
Konsep yang dimaksud dengan menggunakan alat baca positivisme sengaja
dihadirkan oleh penulis, hal tersebut dikarenakan penulis menggunakan alat baca
teori kritis yang kehadirannya bermaksud merefleksi dan sebagai kritik atas
kehadiran positivisme.
Tabel I. 1. Tabel Paradigma Positivisme dan Kritis
Pokok Masalah
Paradigma Positivisme Paradigma Kritis
Industri Pembangunan Eksploitasi
Ideologi Pilihan hidup Metodologi
CSR Pemberdayaan Masyarakat Berpihak kepada korporasi
Dalam apa yang penulis kodifikasikan pada tabel diatas, terdapat
perbedaan antara paradigma positivisme dengan paradigma kritis dalam
memandang ideologi, dan Industri. Pandangan positivisme yang melihat fakta itu
bersifat natural dan netral, memberikan pandangan bahwa ideologi menjadi
pilihan hidup yang diterima begitu saja. Industri yang merupakan manifestasi dari
I. 40
tahapan masyarakat positivis yang paling maju bertindak sebagai infrastruktur
yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan publik (produksi massal).
Paradigma kritis memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan
positivisme terhadap ideologi. Ideologi yang dimaksud dalam pandangan teori
kritis adalah metodologi. Industri sendiri dipandang oleh teori kritis sebagai
infrastruktur yang eksploitatif.
I.6.3.2.1 Agenda CSR
Agenda Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki hubungan yang
ambigu dengan pembangunan internasional. Hal ini dianggap oleh sebagian orang
pihak sektor swasta dapat berkontribusi dalam proses pembangunan yang
nantinya dapat berpengaruh pada pengurangan kemiskinan dan tujuan sosial
lainnya, yang tidak akan dicapai oleh pemerintah jika bertindak sendiri. Namun
agenda juga menarik kritik karena tidak peka terhadap prioritas-prioritas lokal dan
berpotensi merugikan prospek berkelanjutan mata pencaharian pada masyarkat
sekitar akibat pembebasan lahan atau dampak ekologi yang diciptakan dari proses
produksi.
Selain itu, masyarakat sipil semakin frustrasi dengan keterbatasan agenda
yang sering mendefinisikan CSR sebagai kegiatan sukarela. Jika keresahan ini
mengarah ke penarikan dari agenda bisa dibilang bahwa sektor swasta yang telah
banyak berperan konstruktif untuk bermain dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan di semua bidang. Adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui
I. 41
dan membentuk kembali agenda-agenda dalam pelaksanaan CSR yang nantinya
akan berjalan sesuai dengan kebutuhan korporasi.
I.6.3.2.1 Ideologi
Pengertian ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan
asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat
dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat
dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala
masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran
metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.
Namun yang dimaksud ideologi dalam isu penelitian ini ialah ideologi
menurut teori kritis, yang artinya ideologi dimaknai sebagai yaitu sebagai
kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial.
Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan
pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat
sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk
melegitimasikan kekuasaannya. Ideologi dipandang sebagai keberpihakan, yang
nantinya dalam penelitian ini mencoba mencari ideologi yang berperan dalam
pelaksanaan CSR di Indonesia.
I. 42
1.6.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu literatur yang
berhubungan dengan pembentukan konsep CSR. Yang penulis maksud dengan
teks adalah literatur-literatur yang diterima dan dipraktekkan dalam pelaksanaan
CSR di Indonesia. Penulis percaya, kedudukan teks tidak pernah netral dan
obyektif. Ia selalu dibarengi dan lahir dari satu konteks sejarah yang
melingkupinya. Hal ini berpengaruh dalam soal bagaimana kita membaca dan
menafsirkan teks tersebut. Data yang didapat dari media cetak berkala yang
berskala nasional maupun internasional, buku, antologi, jurnal ilmiah dalam dan
luar negeri. Sebagai pendukung juga dilibatkan karya-karya penelitian terdahulu,
makalah-makalah yang relevan, serta literature lain yang mendukung penulisan
skripsi
1.6.3.4 Jenis Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data berupa tulisan
(essay, buku, makalah, jurnal ilmiah, media cetak berkala-seperti majalah,
bulletin, blog internet) tentang kecenderungan-kecenderungan pewacanaan CSR
di Indonesia. Data-data pendukung juga disertakan yang berupa karya-karya
tentang model analisa terhadap fenomena-fenomena pemikiran mengenai wacana
CSR, serta analisa melalui perangkat teori dan mekanisme teori kritis terhadap
perkembangan wacana CSR itu sendiri.
I. 43
1.6.3.5 Teknik analisis Data
Berdasarkan data-data yang berupa teks-teks pemikiran atau tulisan
dengan tema besar diskursus CSR, diskursus yang terdapat dalam tulisan itu
kemudian dikelompokkan, dan diklasifikasi berdasarkan persamaan atau
perbedaan kecenderungan yang dimunculkan, untuk selanjutnya memperoleh
gambaran tentang main reference dan ontologi CSR itu sendiri. Dalam tahapan
ini, akan mencoba membedah mengenai agenda-agenda yang terselubung dalam
pelaksanaan CSR di Indonesia, setelah itu nantinya dapat mengetahui ideologi
yang beroperasi dalam pelaksanaan CSR di Indonesia.
II. 1
BAB II
CSR dan Perkembangannya
Lester Thurow, tahun 1966 dalam bukunya “The Future of Capitalism”,
sudah memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, kapitalisme akan berjalan
kencang tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan, musuh utamanya, sosialisme dan
komunisme telah lenyap. Pemikiran Thurow ini menggaris bawahi bahwa
kapitalisme tak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga
memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau
yang kemudian disebut sustainable society. Pada jamannya, pemikiran Thurow
tersebut sulit diaplikasikan, hal ini ia tuliskan seperti there is no social ‘must’ in
capitalism.1
Karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar Professor
of Public Polecy and Business Responsibility dari Universitas
Columbia.Pemikiran para ilmuwan sosial di era itu masih banyakmendapatkan
tentangan, hingga akhirnya muncul buku yang menghebohkandunia hasil
Jaman pun berlalu, tahun 1962, Rachel Calson lewat bukunya
“TheSilent Spring”, memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan
dankehidupan yang diakibatkan oleh racun peptisida yang mematikan. Paparan
yang disampaikan dalam buku “Silent Spring” tersebut menggugah kesadaran
banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju
kehancuran bersama. Dari sini CSR (Corporate Social Responsibility) pun mulai
digaungkan. Tepatnya di era 1970-an. Banyak professor menulis bukutentang
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, di samping kegiatan mengeruk
untung. Buku-buku tersebut antara lain; “Beyond the Bottom Line”
1 AB Susanto, A Strategic Management Approach, CSR, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hlm.21
II. 2
pemikiran para intelektual dari Club of Roma, bertajuk “The Limits to Growt”.
Buku ini mengingatkan bahwa, disatu sisi bumi memilikiketerbatasan daya
dukung (carrying capacity), sementara di sisi lain populasimanusia bertumbuh
secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber dayaalam mesti dilakukan
secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.Era 1980 – 1990, pemikiran
dan perbincangan tentang issu ini terus berkembang, kesadaran dalam berbagi
keuntungan untuk tanggungjawab sosial, dan dikenal sebagai community
development. Hasil menggembirakandatang dari KTT Bumi di Rio de Jenerio
Tahun 1992 yang menegaskan bahwakonsep pembangunan berkelanjutan menjadi
hal yang harus diperhatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan
korporasi yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme di masa mendatang. Dari
sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai
bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya Built toLast: Successful
Habits of Visionary Companies (1994), menyampaikan bukti bahwa perusahaan
yang terus hidup adalah yang tidak semata mencetak limpahan uang saja, tetapi
perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungansosial dan turut andil dalam
menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.2
Konsep dan pemikiran senada juga ditawarkan oleh John Elkington lewat
bukunya yang berjudul “Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line ofTwentieth
Century Business. Dalam bukunya ini, Elkington menawarkan solusi bagi
peusahaan untuk berkembang di masa mendatang, di mana mereka harus
memperhatikan 3P, bukan sekedar keuntungan (Profit), juga harus terlibat dalam
pemenuhan kesejahteraan rakyat (People) dan berperan aktif dalam menjaga
2Ibid, hlm.35
II. 3
kelestarian lingkungan (Planet).3
3diakses dari
Agenda World Summit di Johannesburg (2002),
menekankan pentingnya tanggung jawab social perusahaan. Dari situ program
CSR mulai terus berjalan dan berkembang dengan berbagai konsep dan definisi.
Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi trend global,
terutamaproduk-produk yang ramah lingkungan yang diproduksi dengan
memperhatikan kaidah social dan hak asasi manusia.
Di pasar modal globalpun, CSR juga menjadi faktor yang diperhitungkan.
Misalnya New York Stock Exchange (NYSE) saat ini menerapkan program Dow
Jones Sustainable Index (DJSI) untuk sahamperusahaan yang dikategorikan
memiliki Social Responsible Investment (SRI). Kemudian Index and Financial
Times Stock Exchange (FTSE) menerapkanFTSE4 Good sejak 2001. Konsekuensi
dari adanya index-index tersebutmemacu investor global seperti perusahaan dana
pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan investasinya di perusahaan-
perusahaan yang sudahmasuk dalam index tersebut.
II.1 SEJARAH CSR
Sejarah merupakan torehan kejadian masa lampau yang mengungkapkan
fenomenarealitas sosial yang bisa menjadi kajian menarik dan bermanfaat di masa
kini danmendatang. Dengan memahami sejarah tentang obyek kajian akan
bermakna bagipengungkapan realitas sosial yang lebih obyektif.Corporate Social
Responsibility (CSR) telah ada sejak Abad 17 dan mengalamiperkembangan
kajian yang mencerminkan dinamika implementatif yang terusmengalami
perubahan. Berikut disajikan sejarah singkat CSR dari masa ke masa.
http://www.csrindonesia.com pada tanggal 13 september 2011 pukul 20.50
II. 4
II.1.1 Sejarah CSR Di Tingkat Internasional
Tahun 1700-an SMTanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social
Responsibility) telah menjadipemikiran para pembuat kebijakan sejak lama.
Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah
memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalaidalam menjaga kenyamanan warga
atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya.Dalam Kode Hammurabi
disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orangorangyang
menyalahgunakan ijin penjualan minuman, pelayanan yang buruk danmelakukan
pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematianorang
lain.Perhatian para pembuat kebijakan tentang CSR menunjukkan telah adanya
kesadaranbahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari kegiatan usaha.
Dampak buruktersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak
membahayakankemaslahatan masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim
usaha.
Tahun 1940-an: Pengembangan Masyarakat
(Community Development)Secara resmi istilah Comdev dipergunakan di
Inggris 1948, untuk mengganti istilahmass education (pendidikan massa).
Menurut Hodge, akar munculnya model pengembangan masyarakat (Community
Development) terkait dengan disiplin ilmupendidikan (education). Di Amerika
Serikat pengembangan masyarakat juga berakardari disiplin pendidikan di tingkat
pedesaan (rural extension program), sedangkan diperkotaan mereka
mengembangkan organisasi komunitas (community organization)yang bersumber
dari ilmu kesejahteraan Sosial yang diawali pada tahun 1873.
II. 5
Pengembangan masyarakat merupakan pembangunan alternatif yang
komprehensifdan berbasis komunitas yang dapat melibatkan baik oleh
Pemerintah, Swasta, ataupunoleh lembagalembaga non pemerintah. Dari segi
tujuan bisa bersifat spesifik, tidakselalu multi-tujuan. Beberapa alternatif
pendekatan yang pernah terjadi di AmerikaSerikat terkait dengan pengembangan
masyarakat ini, antara lain: (1) pendekatankomunitas, (2) pendekatan pemecahan
masalah, (3) pendekatan eksperimental, (4)pendekatan konflik kekuatan, (5)
pengelolaan sumberdaya alam, dan (6) perbaikanlingkungan komunitas
masyarakat perkotaan.Pendekatan komunitas merupakan pendekatan yang paling
sering dipergunakan dalampengembangan masyarakat. Pendekatan ini mempunyai
tiga ciri utama (1) basispartisipasi masyarakat yang luas, (2) fokus pada kebutuhan
sebagian besar wargakomunitas, dan (3) bersifat holistik. Pendekatan ini menaruh
perhatian padakepentingan hampir semua warga. Keunggulan pendekatan ini
adalah adanyapartisipasi yang tinggi dari warga dan pihak terkait dalam
pengambilan keputusan(perencanaan) dan pelaksanaan, serta dalam evaluasi dan
menikmati hasil kegiatanbersama warga komunitas.Comdev semakin menjadi
kebutuhan tidak saja bagi masyarakat, tetapi jugaperusahaan. Perusahaan bukan
lagi merupakan kesatuan yang independen danterisolasi, sehingga manajer tidak
hanya bertanggung jawab kepada pemilik tetapijuga kepada kepentingan yang
lebih luas yang membentuk dan mendukungnya darilingkungan sekitarnya. Dalam
mengejar tujuan ekonomisnya, perusahaanmenimbulkan berbagai konsekuensi
sosial lainnya, baik kemanfaatan (keamanan,kenyamanan, dan kemakmuran bagi
masyarakat) maupun biaya sosial (degradasipotensi sumberdaya lingkungan,
limbah dan pencemaran). Perkembangan lebih lanjut,konsep Comdev ini
mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap CSR.
II. 6
Tahun 1950-an: CSR MODERN
Literatur-literatur awal yang membahas CSR pada tahun 1950-an
menyebut CSRsebagai Social Responsibility (SR bukan CSR). Tidak
disebutkannya kata corporatedalam istilah tersebut kemungkinan besar disebabkan
pengaruh dan dominasikorporasi modern belum terjadi atau belum disadari.
Menurut Howard R. Bowendalam bukunya: “Social Responsibility of The
Businessman” dapat dianggap sebagaitonggak bagi CSR modern. Dalam buku itu
Bowen (1953:6) memberikan definisi awaldari CSR sebagai: “… obligation of
businessman to pursue those policies, to makethose decision or to follow those
line of action wich are desirable in term of theobjectives and values of our
society.”Walaupun judul dan isi buku Bowen bias gender (hanya menyebutkan
businessmantanpa mencantumkan businesswoman), sejak penerbitan buku
tersebut definisi CSRyang diberikan Bowen memberikan pengaruh besar kepada
literatur-literatur CSR yangterbit setelahnya. Sumbangsih besar pada peletakan
fondasi CSR tersebut membuatBowen pantas disebut sebagai Bapak CSR.
Tahun 1960-an
Pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan
formalisasi definisiCSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu
adalah Keith Davis. Davisdikenal karena berhasil memberikan pandangan yang
mendalam atas hubungan antaraCSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan
“Iron Law of Responsibility” yangmenyatakan bahwa tanggung jawab sosial
pengusaha sama dengan kedudukan sosialyang mereka miliki (social
responsibilities of businessmen need to be commensuratewith their social power).
II. 7
Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang tidakmenggunakan kekuasaan
dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapanmasyarakat akan kehilangan
kekuasaan yang mereka miliki sekarang.Kata corporate mulai dicantumkan pada
masa ini. Hal ini bisa jadi dikarenakansumbangsih Davis yang telah menunjukkan
adanya hubungan yang kuat antaratanggung jawab sosial dengan korporasi.Tahun
1962, Rachel Carlson menulis buku yang berjudul “Silent Spring”. Bukutersebut
dianggap memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam.
Bukutersebut berisi efek buruk penggunaan DDT sebagai pestisida terhadap
kelestarianalam, khususnya burung. DDT menyebabkan cangkang telur menjadi
tipis danmenyebabkan gangguan reproduksi dan kematian pada burung. Silent
Spring jugamenjadi pendorong dari pelarangan penggunaan DDT pada tahun
1972. Selainpenghargaan Silent Spring juga menuai banyak kritik dan dinobatkan
sebagai salahsatu ”buku paling berbahaya abad ke-19 dan ke-20” versi majalah
Human Events.Tahun 1963, Joseph W. McGuire (1963:144) memperkenalkan
istilah CorporateCitizenship. McGuire menyatakan bahwa: “The idea of social
responsibilities supposesthat the corporation has not only economic and legal
obligations but also certainresponsibilities to society which extend beyond these
obligations”. McGuire kemudianmenjelaskan lebih lanjut kata “beyond” dengan
menyatakan bahwa korporasi harusmemperhatikan masalah politik, kesejahteraan
masyarakat, pendidikan,“kebahagiaan” karyawan dan seluruh permasalahan sosial
kemasyarakatan lainnya.Oleh karena itu korporasi harus bertindak “baik,” sebagai
mana warga negara(citizen) yang baik.
II. 8
Tahun 1970-an
Tahun 1971, Committee for Economic Development (CED) menerbitkan
SocialResponsibilities of Business Corporations. Penerbitan yang dapat dianggap
sebagaicode of conduct bisnis tersebut dipicu adanya anggapan bahwa kegiatan
usahamemiliki tujuan dasar untuk memberikan pelayanan yang konstruktif untuk
memenuhikebutuhan dan kepuasan masyarakat.CED merumuskan CSR dengan
menggambarkannya dalam lingkaran konsentris.Lingkaran dalam merupakan
tanggungjawab dasar dari korporasi untuk penerapankebijakan yang efektif atas
pertimbangan ekonomi (profit dan pertumbuhan);Lingkaran tengah
menggambarkan tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitifterhadap nilai-nilai
dan prioritas sosial yang berlaku dalam menentukan kebijakanmana yang akan
diambil; Lingkaran luar menggambarkan tanggung jawab yangmungkin akan
muncul seiring dengan meningkatnya peran serta korporasi dalammenjaga
lingkungan dan masyarakat.
Tahun 1970-an juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. Dalam
artikel yangberjudul “Dimensions of Corporate Social Performance”, S. Prakash
Sethi memberikanpenjelasan atas perilaku korporasi yang dikenal dengan social
obligation, socialresponsibility, dan social responsiveness. Menurut Sethi, social
obligation adalahperilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan
pertimbanganpertimbanganhukum. Dalam hal ini social obligatioan hanya
menekankan pada aspekekonomi dan hukum saja. Social responsibility
merupakan perilaku korporasi yangtidak hanya menekankan pada aspek ekonomi
dan hukum saja tetapi menyelaraskansocial obligation dengan norma, nilai dan
harapan kinerja yang dimiliki olehlingkungan sosial. Social responsivenes
merupakan perilaku korporasi yang secararesponsif dapat mengadaptasi
II. 9
kepentingan sosial masyarakat. Social responsivenessmerupakan tindakan
antisipasi dan preventif.Dari pemaparan Sethi dapat disimpulkan bahwa social
obligation bersifat wajib, socialresponsibility bersifat anjuran dan social
responsivenes bersifat preventif. Dimensidimensikinerja sosial (social
performance) yang dipaparkan Sethi juga mirip dengankonsep lingkaran
konsentris yang dipaparkan oleh CED.
Tahun 1980-an
Era ini ditandai dengan usaha-usaha yang lebih terarah untuk lebih
mengartikulasikansecara tepat apa sebenarnya corporate responsibility. Walaupun
telah menyinggungmasalah CSR pada 1954 , Empu teori manajemen Peter F.
Drucker baru mulaimembahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984 ,
Drucker (1984:62)berpendapat: ”But the proper ‘social responsibility’ of business
is to tame thedragon, that is to turn a social problem into economic opportunity
and economicbenefit, into productive capacity, into human competence, into well-
paid jobs, andinto wealth”.Dalam hal ini, Drucker telah melangkah lebih lanjut
dengan memberikan ide baru agarkorporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang
dilakukannya dengan sedemikian rupasehingga tetap akan menjadi peluang bisnis
yang menguntungkan.Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World
Commission on Environment andDevelopment (WECD) menerbitkan laporan yang
berjudul “Our Common Future” –juga dikenal sebagai Brundtland Report untuk
menghormati Gro Harlem Brundtlandyang menjadi ketua WECD waktu itu.
Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungansebagai agenda politik yang pada
akhirnya bertujuan mendorong pengambilankebijakan pembangunan yang lebih
II. 10
sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan inimenjadi dasar kerjasama multilateral
dalam rangka melakukan pembangunanberkelanjutan (sustainable development).
Tahun 1990-an
Gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama duapuluh tahun
terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil
danjaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah
perilakukorporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang
tidak fair dantidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan
sebagai kejahatankorporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat
merasakan jatuhnyareputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.
Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya
KTT Bumidi Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development
(pembangunanberkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh
negara, tapi terlebiholeh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin
menggurita. Tekanan KTT Rio,terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry
Porras meluncurkan Built To Last;Succesful Habits of Visionary Companies di
tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan,mereka menunjukkan bahwa perusahaan-
perusahaan yang terus hidup bukanlahperusahaan yang hanya mencetak
keuntungan semata.Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth
Summit) di Rio deJaneiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma
pembangunan, daripertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi
pembangunan yang berkelanjutan(sustainable development). Dalam perspektif
perusahaan, di mana keberlanjutandimaksud merupakan suatu program sebagai
dampak dari usaha-usaha yang telahdirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan
II. 11
rekanan dari masing-masing stakeholder.Ada lima elemen sehingga konsep
keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;(1) ketersediaan dana, (2)
misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4)terimplementasi dalam kebijakan
(masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5)mempunyai nilai
keuntungan/manfaat.4
Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin
duniamemunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep
sebelumnyayaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini
menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
(Corporate SocialResponsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di
Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian
media dari berbagai penjuru dunia.Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan
untuk menunjukkan tanggung jawab danperilaku bisnis yang sehat yang dikenal
dengan corporate social responsibility.
5
World Business Council for Sustainable Development: Komitmen
berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi
kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan
II.2 Definisi CSR
Definisi CSR sangat menentukan pendekatan audit program CSR. Sayangnya,
belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga.
Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR
menurut berbagai organisasi :
4Dhaniri, Mas Achmad. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hal 3. 5Ibid
II. 12
karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada
umumnya.
International Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberi
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan
karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk
meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun
pembangunan.
Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jaminan bahwa
organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi
masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham
(shareholders) mereka.
Canadian Government: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi,
lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan
operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk
menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
European Commission: Sebuah konsep dengan mana perusahaan
mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis
mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
berdasarkan prinsip kesukarelaan.
CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan
berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan
beragam kepentingan para stakeholders. 6
Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility juga
memberikan definisi CSR. Meskipun pedoman CSR standard internasional ini baru
6Diakses dari http://www.wikipedia.com , pada tanggal 15 september 2011 pukul 12.30wib.
II. 13
akan ditetapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO
26000, CSR adalah:
Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-
keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang
diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan
pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan
harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan
norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara
menyeluruh.
Jika dipetakan, menurut saya, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah
dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan
mengembangkan konsep Tripple Bottom Lines (Elkington, 1998) dan
menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni procedure. Dengan demikian,
CSR adalah:
Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya
(profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan
(planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat
dan profesional.
Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam
ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek the environment. Konsep
people di dalamnya bisa merujuk pada konsep social development dan human rights
yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian
modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial
(semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dan pendididikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial
dan kearifan lokal). Sedangkan konsep procedur bisa mencakup konsep
II. 14
organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer
issues.7
Pendukung konsep tanggungjawab sosial (social responsibility) memberi
argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiaban terhadap
masyarakat selain mencari keuntungan. Ada berapa definisi tentang definisi CSR,
yang pada dasarnya adalah etika dan tindakan untuk turut berperan dalam
keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Hopkin (1998)
memberikan definisi CSR sebagai etika memperlakukan stakeholders dan bumi.
The Conadin Business for Social Responsibility-CSR (2001).
8The European
Commission menebutkan CSR adalah konsep perusahaan yang mengintergrasikan
kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam oprasi bisnis serta interaksinya dengan
stakeholders secara suka rela (Fenwick, T, 2004).9
Menurut WBCD (2005), CSR adalah komitmen perusahaan yang
berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan pekerja
dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas guna meningkatkan
kualitas hidupnya. Departemen Sosial (2005) mendefinisikan CSR sebagai
komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakankewajiban sosial
terhadap lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekelilingnya. Definisi dari Corporate
Social Responcibility (CSR) itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar.
Diantaranya adalah definisiyang dikembangkan oleh Magnan & Ferrel (2004)
yang mendefinisikan CSR sebagai ”A business acts in socially responsible manner
7lihat http://www.csrindonesia.com , diakses pada tanggal 27 oktober 2011 pukul 15.00wib 8Hardiansyah,CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah disampaikan pada Seminar & Talk Show CSR 2007,“Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”, 10 Agustus 2007. 9Hardiansyah, ibid.
II. 15
when its decisionandaccount for and balance diverse stake holder interest ”10
Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung
jawab sosial (social responcibility) pada lingkungannya. Tanggungjawab sosial
seorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada
lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat.
Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi
kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satuunsur kecerdasan spiritual.11
Sementara dalam konteks perusahaan, tanggungjawab sosial itu disebut
tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responcibility—CSR).
Howard Rothmann Bowen menggagas istilah CSR pada tahun 1953 dalam
tulisanya berjudul Social Responcibility of the Businesman. CSRberakar dari etika
yang berlaku di perusahaan dan di masyarakat. Etika yang dianut oleh perusahaan
merupkan bagian dari budaya perusahaan (corporateculture); dan etika yang
dianut oleh masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat.
12
Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri telah
dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan
oleh Magnan dan Ferrel yang mendefinisikan CSR sebagai “ Abusiness acts in
socially responsible manner when its decision and accaundfor and balance
diverse stake holder interest”.
13
10A.B. Susanto,Corporate Greening,Majalah Ozon, Edisi No.2 Oktober 2002 11A B. Susanto,Ibid, hal.21 12Hardiansyah,CSR dan Model Sosial Untuk membangun Sinergi Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah disampaikan pada Seminar & TalkShow CSR 2007“Kalimantan 2015:Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”. 10 Agustus 2007. 13Ibid
Definisi ini menekankan kepada perlunya
memberikan perintah secara seimbang terhadap kepentingan berbagai
stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang ambil oleh
para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara socialbertanggungjawab.
II. 16
Sedangkan komisi eropa membuat definisi yang lebih praktis, yang pada galibnya
bagaimana perusahaan secara sukarela member kontribusi bagi terbentuknya
masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sedangkan
Elkington (1997) mengemukakan bahwa sebuahperusahhan yang menunjukan
tanggungjawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas
perusahaan (profit); masyarakat, khususnya sekitar (people); serta lingkungan
hidup (planet bumi).14 Dalam UU PM, yang digunakan sebagai rujukan pewajiban
CSRdalam RUU PT, di penjelasan Pasal 15 huruf b, CSR didefinisikan sebagai
“tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetapmenciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.” Dalam teks Pasal 74 RUU PT sendiri CSR tidak
didefinisikan, namun dalam dokumen kerja Tim Perumus terdapat definisi
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Definisi ini telah
disetujui Tim Perumus pada tanggal 3 Juli 2007. Ada banyak masalah dalam
definisi yang tertera dalam dokumen kerjaRUU PT. Pertama, penyebutan
tanggung jawab sosial dan lingkungan tidaklah lazim. Penjelasan yang sangat
komprehensif paling mutakhir tentang definisi misalnya diberikan oleh Michael
Hopkins (2007) dalam Corporate Social Responsibility and International
Development.15
14Ibid 15Hopkins, M, 2007,Corporate Social Responsibility and International Development. Is Business the Solution?,Earthscan, hlm.22
Di situ dijelaskan bahwa kata “social” di tengah CSR memang
kerap menyasarkan orang pada sangkaan bahwa CSR hanya berisikan kegiatan
pada ranah sosial. Namun demikian, menghilangkan kata tersebut juga
II. 17
problematic karena tidak memberikan penekanan terhadap sebuah bentuk
tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak/kurang begitu dikenal (kalau tadinya
hanya ada tanggung jawab pada ranah ekonomi terhadap pemilik modal—
maksimisasi keuntungan— kini tanggung jawab itu disadari menjadi dalam tiga
ranah: ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada ranah ekonomi juga ditekankan
bahwa yang harus menikmati bukan saja pemilik modal,melainkan juga pemangku
kepentingan lainnya). Ia juga menekankan bahwa “social” dalam CSR memang
sah dan lazim untuk mewakili tiga ranah tersebut dengan mencontohkan banyak
kejadian serupa (misalnya di dunia akademik). CSR sudah jelas mencakup tiga
ranah—bukan dua, sepertidalam penyebutan RUU PT—dan karenanya kerap
disandingkan dengan konsep triple bottom line.16
• AccountAbility’s (AA1000) standard, yang berdasar pada prinsip “Triple
Bottom Line” (Profit, People, Planet) yang digagas oleh John Elkington
II.3 Regulasi CSR di tingkat Global
Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR
di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga
keuangan internasional. Untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung
jawab, di level internasional perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai
standard CSR seperti :
• Global Reporting Initiative’s (GRI) – panduan pelaporan perusahaan
untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh
PBB lewat Coalition for Environmentally Responsible Economies
(CERES) dan UNEP pada tahun 1997
16Op CitHAM Hardiansyah.
II. 18
• Social Accountability International’s SA8000 standard
• ISO 14000 environmental management standard
• Kemudian, ISO 26000.17
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi
tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global
terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan
memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia
(HAM). Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman
hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai
contoh, bank-bank Eropa hanyamemberikan pinjaman pada perusahaan-
perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut,
yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar
hutan.
Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah
penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah
mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang
dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya
adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki Socially
Responsible Investment (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE)
yang memiliki FTSE4Good sejak 2001.
Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di
Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari
17Yanuar Nugroho, “Commodum Totti Topulo: The Benefit is for the Whole Society”, 20 Maret 2007, diakses dari http://www.audentis.wordpress.com pada tanggal 25 oktober 2-11 pukul 21.30wib
II. 19
adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana
pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-
perusahaan yang sudah masuk dalam indeks. Menghadapi tren global dan
resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan
memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari setiap
aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap tahunnya kepada
stakeholdernya. Laporan bersifat non financial yang dapat digunakan sebagai
acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungannya.
Di Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2007, Parlemen Uni Eropa
mengeluarkan resolusi berjudul “Corporate Social Responsibility: A new
partnership” yang mendesak Komisi Eropa untuk meningkatkan kewajiban yang
terkait dengan persoalan akuntabilitas perusahaan seperti tugas direktur (directors’
duties), kewajiban langsung luar negeri (foreign direct liabilities) dan pelaporan
kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (environmental and social
reporting).Banyak pihak menyambut gembira perkembangan ini. Semakin lama
semakin disadari bahwa walaupun perusahaan (sektor bisnis) selama ini sudah
berkontribusi sangat positif terhadap pembangunan dunia, pada saat yang sama
perusahaan harus diminta semakin bertanggung jawab. Karena, upaya memupuk
laba cenderung (meski tidak selalu) mengabaikan tanggung jawab sosial.
Di Inggris, sudah lama perusahaan diikat dengan kode etik usaha. Dan
karena sudah ada banyak aturan dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis
di Inggris, maka tidak diperlukan UU khusus CSR. Sekedar diketahui, perusahaan
di Inggris ini tidak lepas dari pengamatan publik (masyarakat dan negara) karena
harus transparan dalam praktik bisnisnya. Publik bisa protes terbuka ke
perusahaan jika perusahaan merugikan masyarakat/konsumen/buruh/lingkungan.
II. 20
Melihat perkembangan ini, tahun lalu, disahkan Companies Act 2006 yang
mewajibkan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek untuk melaporkan
bukan saja kinerja perusahaan (kinerja ekonomi dan financial) melainkan kinerja
sosial dan lingkungan. Laporan ini harus terbuka untukdiakses publik dan
dipertanyakan. Dengan demikian, perusahaan didesak agar semakinbertanggung
jawab.
Mac Oliver – EA Marshal (Company Law Handbook Series, 1991)
berpendapat, perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri diharuskan
melaksanakan Sullivan Principal dalam rangka melaksanakan Corporate Social
Responsibilty, yaitu:
Tidak ada pemisahan ras (non separation of races) dalam makan, bantuan
hidup dan fasilitas kerja.
Sama dan adil dalam melaksanakan pekerjaan (equal and fair
employment process).
Pembayaran upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding (equal
payment compansable work).
Program training untuk mempersiapkan kulit hitam dan non kulit putih
lain sebagai supervisi, administrasi , klerk, teknisi dalam jumlah yang
substansial.
Memperbanyak kulit hitam dan non kulit putih lain dalam profesi
manajemen dan supervisi.
Memperbaiki tempat hidup pekerja di luar lingkungan kerja seperti
perumahan,transportasi, kesehatan, sekolah dan rekreasi.18
18M. Yahya Harahap,“Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Makalah Seminardisampaikan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, 20 November 2007, dikutip dari MC Oliver – EAMarshal, "Company Law Handbook Series”, 1991, Hal.321.
II. 21
Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk
menjadi contoh penerapan CSR. Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda,
Inggris, dan Amerika Serikat telah mengadopsi code of conduct CSR yang
meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak
asasi manusia (HAM). Berbasis pada aspek itu, mereka mengembangkan regulasi
guna mengatur CSR. Australia, misalnya, mewajibkan perusahaan membuat
laporan tahunan CSR dan mengatur standardisasi lingkungan hidup, hubungan
industrial, dan HAM. Sementara itu, Kanadamengatur CSR dalam aspek
kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan, danpenyelesaian masalah
sosial.
Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit
diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja
perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan--apalagi aspek
ekonomi--memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang
menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan
perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan
berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan.
Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi
evaluasi yang digunakan.
Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar "pemanis
bibir" (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari
perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan
semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya,
kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan.
II. 22
Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya.
CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan
(corporate value)yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja.
Tapi tanggung jawabperusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini
bottom lines lainnya selainfinansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena
kondisi keuangan saja tidak cukupmenjamin nilai perusahaan tumbuh secara
berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutanperusahaan hanya akan terjamin
apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial danlingkungan hidup. Sudah
menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, diberbagai tempat dan
waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggaptidak
memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.
Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for
Standardization)sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif
mengundang berbagaipihak untuk membentuk tim (working group) yang
membidani lahirnya panduan danstandarisasi untuk tanggung jawab sosial yang
diberi nama ISO 26000: GuidanceStandard on Social Responsibility.Pengaturan
untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak padapemahaman umum
bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi.Pemahaman
tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth Summit on theEnvironment”
tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)”tahun
2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.19
19AchmadDaniri,Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal 3.
II. 23
Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO
memintaISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan
standar CorporateSocial Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut
mengadopsi laporan COPOLCOmengenai pembentukan “Strategic Advisory
Group on Social Responsibility pada tahun2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan
pre-conference dan conference bagi negaranegaraberkembang, selanjutnya di
tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposalatau NWIP diedarkan kepada
seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting padabulan Januari 2005,
dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak.Dalam hal ini
terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atauCorporate Social
Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahanini, menurut
komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO
26000diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk
organisasi, baikswasta maupun publik.ISO 26000 menyediakan standar pedoman
yang bersifat sukarela mengenaitanggung tanggung jawab sosial suatu institusi
yang mencakup semua sektor badanpublik ataupun badan privat baik di negara
berkembang maupun negara maju. DenganIso 26000 ini akan memberikan
tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosialyang berkembang saat ini
dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadappengertian tanggung
jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentangpenterjemahan prinsip-
prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilahpraktek-praktek
terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikankomunitas atau
masyarakat internasional.20
20Ibid. hal 4
II. 24
Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli
yangmenggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang
secara konsistenmengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan
mencakup 7 isu pokokyaitu:
1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organizational Governance (governance organisasi)
ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab
suatuorganisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat
danlingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:
Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat;
Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma
internasional;
Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi
baik kegiatan, produk maupun jasa.
Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility
hendaknyaterintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok
II. 25
diatas. Dengandemikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu
saja, misalnya suatuperusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun
perusahaan tersebut masihmengiklankan penerimaan pegawai dengan
menyebutkan secara khusus kebutuhanpegawai sesuai dengan gender tertentu,
maka sesuai dengan konsep ISO 26000perusahaan tersebut sesungguhnya belum
melaksanakan tanggung jawab sosialnyasecara utuh.
Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar
bagipelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan
keputusan dankegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:
Kepatuhan kepada hukum
Menghormati instrumen/badan-badan internasional
Menghormati stakeholders dan kepentingannya
Akuntabilitas
Transparansi
Perilaku yang beretika
Melakukan tindakan pencegahan
Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia
Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga
tahun2008, diantaranya adalah menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006,
penyusunandraf ISO 26000 hingga Desember 2007, finalisasi draf akhir ISO
26000 diperkirakanpada bulan September 2008 dan seluruh tugas tersebut
diperkirakan rampung padatahun 2009.Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal
15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orangdari 55 negara dan 26 organisasi
internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 inihanya memuat panduan
(guidelines) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratankarena ISO 26000 ini
II. 26
memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dantidak digunakan
sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya.Adanya
ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkanadanya
kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri
dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan
CSR dimanca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline)
ataudijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum,
sekaligusmenjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.21
Di Indonesia, kini kita menyaksikan perbincangan yang terus berlanjut
seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada persetujuan dan pula pertentangan.
Terlebih pihak pemerintah secara khusus membuatkan UU tentang tanggung
jawab sosial ini, yakni dalam UU Perseroan Terbatas Pasal74. Terlepas dari itu,
isu tentang Corporate Social Responsibility (CSR) memang kian hangat.
Persoalannya bukan lagi melulu dari aspek sosial, tetapi sudah jauh merasuk ke
aspek bisnis dan penyehatan orporasi. Lama-kelamaan, CSR tidak lagi dipandang
sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang semula dianggap
sebagai cost, kini mulai diposisikan sebagai investasi. Dalam sebuah ulasan di
Majalah Marketing (edisi 11/2007) menegaskan tentang mengapa pula perusahaan
harus berinvestasi pada kegiatan CSR? Apakah lantaran moralitas semata atau dia
sudah menjadi marketing tools yang efisien? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan
manajemen dan divisi marketing sewaktu mempersiapkan strategi CSR. Akan
tetapi, perdebatan paling baru tentang CSR adalah soal imbas program tersebut
II.4 CSR di Indonesia
21Ibid. hal 5
II. 27
pada profit perusahaan. Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan program yang
mampu mendukung sustainability perusahaan dan aktivitas CSR itu sendiri.
Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti responsif terhadap kondisi-
kondisiyang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global, tren baru di pasar,
dan kebutuhan stakeholders yang belum terpenuhi.22 Berkaitan dengan masalah
imbas tadi, Global CSR Survey paling tidak bisa memperlihatkan betapa
pentingnya CSR. Bayangkan, dalam survey di 10 negara tersebut, mayoritas
konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta
merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang
dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya,sebanyak 61% dari mereka sudah
memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya tanggung jawab sosial. CSR
kini bukan lagi sekadar program charity yang tak berbekas. Melainkan telah
menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang (CSR for
profit). Karena itu,hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan
dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung core business
perusahaan.23
Philip Kotler, dalam buku CSR: Doing the Most Good for Your Company
and Your Cause, membeberkan beberapa alasan tentang perlunyaperusahaan
menggelar aktivitas itu. Disebutkannya, CSR bisa membangunpositioning merek,
mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar,meningkatkan loyalitas
karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik korporat
di mata investor.
24
22Majalah Marketing. Edisi 11/2007. 23Ibid 24Philip Kotler.2007. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause.New York, Thomas Dunne Books.hal.33.
Menurut Godo Tjahjono, Chief Consulting Officer Prentis,
CSR memang punya beberapa manfaat yang bisa dikategorikan dalam empat
II. 28
aspek, yaitu: license to operate, sumber daya manusia, retensi, dan produktivitas
karyawan. Dari sisi marketing, CSR jugabisa menjadi bagian dari brand
differentiation.25
Kini kita menyaksikan dan mengharap gairah perusahaanperusahaan
raksasa dunia untuk menerapkan program kepedulian sosial. Semoga ini tak hanya
jadi sekedar angin segar ditengah kekosongan issu saja, melainkan mampu
menjadi virus baik yang menyebar cepat di Indonesia.
26
Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya
kegiatan perusahaan membawa dampak (for better or worse), bagi kondisi
lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan
beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholdersatau
para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an.
Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social
Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai
CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan
bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan
lingkungan. Melalui konsep investasi social perusahaan “seat belt”, sejak tahun
2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam
mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai
perusahaan nasional.
27
25Majalah Marketing, Edisi 11/2007 26Di sarikan dari berbagai sumber – Cikeas Magazine ”CSR dari mana datangnya”, Vol 1 No4/07, Majalah Marketing, ”CSR for Profit”, edisi 11/2007, dan Societa, “Sejarah Panjang Konsep CSR”, 12/2006. 27A.B.Susanto, Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997, hlm.55
Stakeholders dapat mencakup
karyawan dan keluarganya,pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan,
II. 29
lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku
regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan
dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.
Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan
masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya.
Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti
Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering
diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang
mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan social dan
pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensimasyarakat
lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain
dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga
kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra
sebagai perusahaan yang ramah dan pedulilingkungan. Selain itu, akan tumbuh
rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari
masyarakat sehingga masyarakatmerasakan bahwa kehadiran perusahaan di
daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di
negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban
semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan muncul pada saat pembahasan ditingkat Panja dan Pansus DPR. Pada
konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat
II. 30
dengar pendapat dengan Kadin danpara pemangku kepentingan lain, materi pasal
74 ini pun belum ada. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan
Apindo, keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR
membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan
lingkungan dalam RUU PT.
Substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tentang
Perseroan Terbatas mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan
lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan
anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dankewajiban melaporkannya.
Mengikuti perkembangan berita di media massa yang menyangkut pembahasan
pasal 74, sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan cukup
lumayan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Tadinya, tanggung jawab
sosial dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di
bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua
perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, baru berdiri, atau
masihdalam kondisi merugi.
Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR
dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga
internasional (The World Bank, ISO 26000 dan sebagainya) serta praktek yang
telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional.Lalu
sebenarnya seperti apa best practice mengenai CSR ini? Saat ini ISO
(International Organization for Standardization), tengah menggodok konsep
standar CSR yang diperkirakan rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal
dengan nama ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Dengan standar ini,
II. 31
pada akhir 2009 hanya akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal banyak
konsep mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan
para pakar. Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses
interaksisosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan
biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat.
Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha,
pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh
masing-masing perusahaan. Dengan demikian adalah tidak mungkin untuk
mengukur pelaksanaan CSR.Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari
good corporate governance yang mestinya didorong melalui pendekatan etika
maupun pendekatan pasar (insentif). Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan
untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam kaitan untuk
menyamakan level of playing field pelaku ekonomi. Sebagai contoh, UU dapat
mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, bukan hanya aspek keuangan,
tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan
masyarakat. Tak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya perusahaan dan
masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan
antaraperusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan
kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared value), yaitu
pilihan-pilihan harus memberi manfaat kedua belah pihak. Lebih menarik lagi
ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta penjelasan
pasal 74 itu sendiri. Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
II. 32
Perseroan Terbatas memuat “… komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan
serta”, sedangkan pasal 74 ayat 1 “… wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan”. Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat
sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat.
Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban
TJSL pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya
pada pasal 74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan kepada peraturan
perundang-undangan lain yang terkait.
Demikian juga pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung
jawab sosial dan lingkungan, dibatasi namun dalam penjelasannya dapat diketahui
bahwa semua perseroan terkena kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan,
karena penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat
dilihat pada bunyi pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan pada penjelasan
pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan
kegitan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan
usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang
dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber
daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan
sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya
alam. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak
berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.
II. 33
Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah konsep
dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan
itu adalah diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam
peraturan perundangan formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan
dan standar lingkungan hidup.Mereka berpendapat, jika diatur, selain
bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada
dunia usaha. CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut
pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses
interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan
CSR bisa karena tuntutankomunitas atau karena pertimbangannya sendiri.
Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.
Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi
pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang
diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk
orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan
yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan
adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para
aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus
melalui dialog bersama para pemangkukepentingan, seperti pelaku usaha,
kelompok masyarakat yang akan terkena dampak,dan organisasi pelaksana.Semua
proses ini tidak mudah. Itu sebabnya di negara-negara Eropa yang secara
institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia, proses regulasi yang
menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. European Union
II. 34
sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR, telah
menyatakan sikapnya, CSR bukan sesuatu yang akan diatur.28
Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal
dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bias
menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR
mengalami distorsi serius. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini
telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna
dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan
bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus
ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat
pemaknaannya dalam praktik.
29
Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna parsial
sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan
dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya
terkait langsung dengan core business perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat
sekitar. Padahal praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan
terkait dampak social dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program
Dalam ranah norma kehidupan modern, kita dilingkupi dengan sejumlah
norma yakni norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa mengabaikan kewajiban dan
pertanggungjawaban hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat pada
norma sosial sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli
CSR sesungguhnya bergerak dalam kerangka ini, di mana perusahaan secara sadar
memaknai aneka prasyarat tadi dan masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen
pelaksanaannya.
28Meuthia Ganie Rochman, “Meregulasi Gagasan CSR”, Kompas 10 Agustus 2007. 29Robert Endi Jaweng, “Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT”, Suara Pembaruan 31 Juli 2007.
II. 35
langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung (bukan core business) seperti
rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan
aneka program tak langsung tersebut.
Ketiga, tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab
setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan
akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap
dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan
setiap perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan menempatkan kewajiban
proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini
cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal
menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru
bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial
(menurut UU PT) dan secara hukum (UUlingkungan hidup).Keempat, dari sisi
keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan
sebagai pelaku dan penangung jawab tunggal program CSR.30
30Ibid
Di sini masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya
menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi
mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang
terjadi.Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan
mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha social
kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat secara sosial
dan ekonomi. Namun pewajiban dalam suatu Undang-undang dapat memunculkan
multi tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai.
II. 36
Di antara permasalahan yang harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja
yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin
dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan
dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab
sosial.Pewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan
tidaklah tepat. Hal ini karena:
• Pemerintah telah mengatur tentang LH, Perlindungan Konsumen, Hak
Asasi Manusia, Perburuhan dan sebagainya pada masing-masing UU
tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UUPT.
• Kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar (Dunia
Usaha, Pemerintah dan Masyarakat), berkaitan dengan 7 masalah pokok,
melebihi kewajiban dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat
sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika.
• Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas
dilakukan oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia.
• Pemerintah & masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani
masalah sosial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh
Dunia Usaha.
Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi
masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama
Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini
justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan
pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program
semua stakeholders pembangunan.
II. 37
Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu
yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan
program pemda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia,
pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum,
dan jaminan ketertiban sosial.
Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan
regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan
kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus
berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa
menetapkan bidang-bidangpenanganan yang menjadi fokus, dengan masukan
pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan
memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar
ini. Pemerintah juga dapatmengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan
kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan
menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini
amat diperlukan, terutama di daerah.
Di antara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia
masihtergolong rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang
memberikan laporanmengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya.Ikatan
Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun
2005mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). Secara umum
ISRAbertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada
perusahaan diIndonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan
yang membuatlaporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan
yang diberikan adalahBest Social and Environmental Report Award, Best Social
II. 38
Reporting Award, BestEnvironmental Reporting Award, dan Best Website.Pada
Tahun 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best Sustainability
ReportsAward, Best Social and Environmental Report Award, Best Social
Reporting Award,Best Website, Impressive Sustainability Report Award,
Progressive SocialResponsibility Award, dan Impressive Website Award. Pada
Tahun 2007 kategoridiubah dengan menghilangkan kategori impressive dan
progressive dan menambahpenghargaan khusus berupa Commendation for
Sustainability Reporting: First TimeSutainability Report. Sampai dengan ISRA
2007 perusahaan tambang, otomotif danBUMN mendominasi keikutsertaan dalam
ISRA.
Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari sejarah
perkembangan PKBL.Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak
terbitnya Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan
dan pengawasan PerusahaanJawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Perseroan (Persero).Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil
dibebankan sebagai biaya perusahaan.Dengan terbitnya keputusan Menteri
Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11Nopember 1989 tentang Pedoman
Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik
Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihansebagian laba sebesar 1%-5%
dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebihdikenal dengan Program
Pegelkop.Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha
Kecil dan Koperasi(Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.:316/KMK.016/1994tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha
Keciln dan Koperasi melaluiPemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha
Milik Negara. Memperhatikanperkembangann ekonomi dan kebutuhan
II. 39
masyarakat, pedoman pembinaan usaha keciltersebut beberapa kali mengalami
penyesuaian, yaitu melalui Keputusan MenteriNegara Pendayagunaan
BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/MPBUMN/1999 tanggal
28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan BinaLingkungan BUMN,
Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni2003 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan,
dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007
tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan UsahaKecil
dan Program Bina Lingkungan.Pembinaan usaha kecil yang dilakukan BUMN ini
tidak terlepas dari beberapaperaturan perundang-undangan lainnya, yaitu sebagai
berikut.
a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan
danPengembangan Usaha Kecil.Penjelasan Pasal 16; Lembaga
pembiayaan menyediakan dukungan modal untukpembinaan dan
pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal,modal
bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja
usahakecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan
Usaha MilikNegara, anjak piutang dan kredit lainnya.
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.Pasal 2: Salah
satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikanbimbingan dan
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi,
danmasyarakat.Pasal 88 ayat (1): BUMN dapat menyisihkan sebagian laba
bersihnya untukkeperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta
pembinaan masyarakat sekitarBUMN.
II. 40
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah(lihat uraian di bawah).
II.4.1 Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia
1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:
o Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
sertamencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6:1).
o Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
memberikaninformasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan
hidup (Pasal 6:2).
o Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan
limbahhasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16:1).
o Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan
bahanberbahaya dan beracun (Pasal 17:1).
2.UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung
jawabperusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan
untukmenumbuhkan kesadaran corporate tentang pentingnya kejujuran dan
tanggung jawabdalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah
larangan-laranganpelaku usaha, pencantuman klausula baku dan tanggung jawab
pelaku usaha.
II. 41
3. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut.
o Setiap penanam modal berkewajiban (Pasal 15):
_ melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
_ menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman modal;
_ Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah
tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk
tetapmenciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan,nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (penjelasan pasal 15
Huruf b).
o Setiap penanam modal bertanggung jawab (Pasal 16)
_ menjaga kelestarian lingkungan hidup;
_ menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan
pekerja; … Pasal 34:
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
yang tidakmemenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat
dikenai sanksiadministratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
instansi ataulembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
II. 42
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat
dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, kewajiban dan tanggung
jawabperusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada
karyawandan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan
hidup.
4. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus
2007.Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan.
o Bagi BUMN yang sudah melakukan alokasi biaya untuk bina wilayah atau
yangsejenis sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT),
makadalam pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi
denganmemperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
o Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan bina lingkungan
(PKBL)-nyaberasal dari penyisishan laba, maka tetap melaksanakan PKBL sesuai
dengan alokasi dana yang disetujui RUPS.
o Bagi BUMN yang sumber dana program kemitraan dan/atau bina lingkungan
(PKBL)-nya dibebankan/menjadi biaya perusahaan sebagai pelaksanaan Pasal 74
UUPT,maka dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada peraturan
menteriNegara BUMN No: Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih
lanjut darimenteri Negara BUMN.Selengkapnya tentang Pasal 74 UU No. 40
tahun 2007 tersebut adalah sebagai berikut:
II. 43
Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pasal 74:
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber dayaalam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajibanPerseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaannyadilakukan dengan memperhitungkan
kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan PeraturanPemerintah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Bunyi Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008:…..Badan Usaha Milik Negara
dapatmenyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang
dialokasikankepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah,dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program
Pembinaan Usaha Kecil danpemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN
melalui pemanfaatan dana dari bagianlaba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk
pendanaan program maksimal sebesar 2%(dua persen) dari laba bersih untuk
Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)dari laba bersih untuk Program
II. 44
Bina Lingkungan (CSR). Ketentuan UU inilah yangdijadikan dasar bagi penataan
tentang pemanfaatan CSR di Indonesia.
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 15 April 2009
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya 15 April 2009 menolak gugatan
ujimaterial oleh Kadin terhadap pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial
danLingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya
alam. Karenaputusan MK bersifat final dan mengikat, maka lebih baik kita
melihat dari sisipositifnya, yaitu sinergi antara pasal PJSL dengan UU Pajak
Penghasilan 36/2008 (UUPPh) pasal 6 ayat 1 huruf a yang sekarang
memberlakukan beberapa jenis sumbangansosil sebagai biaya, yaitu.
• Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
• Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah;
• Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
• Biaya pembangunan infrasrtuktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
• Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah:dan
• Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan
untukmembangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak
II. 45
yangterkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial
dimanaperusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan
usahanya secaraberkelanjutan.Sayangnya, masih ada perusahaan yang
mempersepsi CSR sebagai bagian dari biayaatau tindakan reaktif untuk
mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan.Beberapa perusahaan
memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang lebihtinggi dengan
menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand building danpeningkatan
corporate image. Namun upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yangdijadikan
sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan.
Masyarakat kini telah semakin well informed, dan kritis serta mampu
melakukanfilterisasi terhadap dunia usaha yangg tengah berkembang. Hal ini
menuntut parapengusaha untuk menjalankan usahanya dengan semakin
bertanggung-jawab.Pengusaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh capital
gain atau profit darikegiatan usahanya, melainkan mereka juga diminta utk
memberikan kontribusi baikmateriil maupun spirituil kepada masyarakat dan
pemerintah sejalan dengan aturan.
II.4.2Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia
Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan
kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut
pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, masyarakat
adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan
macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan mereka,
pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat
tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan resiko. Jalan keluar
II. 46
yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan
menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepentingannya.
Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok lemah.
Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme untuk
berkomunikasidengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingan-
kepentingan mereka.
Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat
berpartisipasi dengan benar. Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi
semacam prinsip yang dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam
masyarakat. CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia
usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.
Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond
compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia,
sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai
peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan
risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan usahanya. Penerapan
kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan
dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat
yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada
yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam
mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
II. 47
Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil
kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertama adalah
keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial
lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Kedua adalah
sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktivitas sosial
lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.
Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah
mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang
sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya
finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.Akibat kebijakan tersebut
aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal
yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna
dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan
bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus
ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat
pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSRakan
bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan perusahaan
di lingkungan sekitarnya (bergantung pada core business-nya masing-masing)
padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia semakin
memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa tujuan
pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi
II. 48
seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan
terkesan basa-basi.31
Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan pemangku
kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua decade
belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh dan lingkungan,
telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun, tanggapan
positif terhadapnya memang baru terjadi belakangan. Di masa lampau, hampir
selalu keluhan pada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan akan membuat
mereka yang menyatakannya berhadapan dengan aparat keamanan. Walaupun kini
hal tersebutbelum menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah
lebih banyak terdengar. Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja
buruk kini telah banyak tersedia. Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan
tekanan kepada perusahaan berkinerja buruk. Payahnya, banyak perusahaan juga
yang mulai menyadari pentingnya meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan
ternyata tidak mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai pemangku
kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak berubah malah
menjadi sasaran tembak. Karena dianggap "melunak", perusahaan tersebut kerap
dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai
cara.
32
Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain
berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah
kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan
industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini
cukup menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah
31Roby Akbar, “Benang Kusut Regulasi CSR”, 3 Desember 2007, diakses dari http://www.roryakbar.wordpress.com diakses pada tanggal 20 september 2011 pukul 13.00wib. 32Jalal, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, Koran Tempo, 26 September 2006.
II. 49
atas potensi kemitraan pembangunan dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat
kekhawatiran bahwa pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke
perusahaan. Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban
baru bagi perusahaan, alih-alihmenjadi insentif bagi mereka yang hendak
meningkatkan kinerja CSR-nya.
Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah
seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat
beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi
yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi
perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah
mencapainya. Di luar itu, pemerintah bias pula membantu perusahaan yang
sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya
dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan
pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang
sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk
bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.
Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu
diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan
menggunakan pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability Reporting. Dari
sisi ekonomi, pesnggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi
sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan
dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.33
33Makalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, “Proper Sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan”, 23 Agustus 2006.
II. 50
Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR,
yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan
(internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya
regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah
memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan).
Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen
dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggung
jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community
development responsibility). Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan
denganmengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat
tumbuh danberkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif
dari masyarakatluas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap
kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia
(human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan
pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan
mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).34
Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan
oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan Strategic CSR. Agenda sosial
perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang
untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju penemuan jalan untuk
34Muhammad Arief Effendi, “Implementasi GCG Melalui CSR”, 7 November 2007, diakses dari http://www.muhariefeffendi.wordpress.com diakses pada tanggal 1 september 2011 pukul 20.30wib.
II. 51
mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda
sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan.
Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga
kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi
secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan
perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial
value chain, yakni isu social yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas
normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu
sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi
kemampuan berkompetisi perusahaan.
Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga
kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian
menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk
dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.
Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas atau
masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran
terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut.
Perubahan orientasi social politik di tanah air dapat memunculkan kembali
apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif dalam upaya
menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber daya yang ada di
wilayahnya.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan
masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling
ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan
masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus
II. 52
mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan
kedua belah pihak. Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan
masyarakat memilikidua bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa perusahaan
memiliki dampak terhadapmasyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal.
Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas
produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran,
penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. Kedua, outside-in-linkages, di mana
kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau
lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber
daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur
kompetisi-seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaanintelektual, menjamin
transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas
permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat,
seperti penyedia jasa dan produsen mesin.35
35Mas Achmad Daniri dan Maria Dian Nurani, “Menuju Standarisasi CSR”, telahdimuat di Harian Bisnis Indonesia, 19 Juli 2007.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat
membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji
(good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis
sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis
serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku
dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita
sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai
yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri
adalah:
II. 53
• Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk
mengambilkeputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang
apa yangdianggapnya baik untuk dilakukan.
• Prinsip kejujuran.
• Prinsip keadilan.
• Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).
• Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam
diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan
tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun
perusahaannya.
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja,
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan
mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat
adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan
budaya lokal tersebut. Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang
aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan
perannya yaitu:
a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak
sejalandengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun
institusi yang terkait dengan CSR
c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen
dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan
meningkatkan kualitas penerapan CSR
II. 54
Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua
stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus
punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang
lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan
ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk
pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini.
Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat
di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.
Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-
organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan ‘practical
guidances’ yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial;
identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan
klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil
performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan
atas konsumen dan ‘stakeholders’ lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak
berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak
bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab
sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam
lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai
tanggung jawab sosial.36
ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang
diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility,
memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi
trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh–
36Indonesia Business Links, “Integrating CSR a Business Strategy: How to adopt CEO values into CSRPolicies”, Hotel Nikko, Jakarta 2 Mei 2007.
II. 55
sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha di Indonesia. ISO 26000 ini bisa
dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip
pelaksanaan CSR di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk
membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair.
Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa dibarengi dengan upaya pemerintah
memberikan bantuan/asistensi pada perusahaan yang belum/menjadi perusahaan
publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO.
Misalnya dengan menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih
bottom-up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk
menerima produk Indonesia. Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi
masa depan bagi perusahaan.
Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang
telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan
CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan
hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.
Pada tahun 2001, ISO-suatu lembaga internasional dalam perumusan
standar atau pedoman, menggagaskan perlunya standar tanggungjawab sosial
perusahaan (CSR standard). Setelah mengalami diskusi panjang selama hampir 4
tahun tentang gagasan ini, akhirnya Dewan managemenISO menetapkan bahwa
yang diperlukan adalah Standar Tanggungjawab Sosial atau Social Responcibility
Standard (ISO, 2005). CSR merupakan salah satu bagian dari SR. Tidak hanya
perusahaan yang perlu terpanggil melakukan SR tetapi semua organisasi,
termasuk pemerintah dan LSM.37
37A.B. Susanto, CSR dalam Perspektif Ganda, Harian Bisnis Indonesia, 2 September
II. 56
Sejak januari 2005 dibentuk kelompok kerja ISO 26000 untuk
merumuskan draf Standar SR. Definisi tanggungjawab Sosial—Social
Responsibility (SR), berdasarkan dokumen draf dokumen ISO 26000, adalah etika
dan tindakan terkait tanggungjawab organisasi yang mempertimbangkan dampak
aktivitas organisasi pada berbagai pihak dengan cara-cara yang konsisten dengan
kebutuhan masyarakat. Social Responcibility (SR) merupakan kepedulian dan
tindakan managemen organisasi pada masyarakat dan lingkungan, disamping
harus mentaati aspel legal yang berlaku. ISO 26000memberikan prinsip-prinsip
dasar, isu-isu universal dan kerangka pikir yang menjadi landasan umum bagi
penyelenggaraan SR oleh setiap organisasi, tanpa membedakan ukuran dan jenis
organisasi. ISO 26000 tidak dimaksudkan untuk menjadi standar sistem
managemen dan tidak untuksertifikasi perusahaan. ISO 26000 juga tidak
dimaksudkan untuk menggantikan consensus internasional yang sudah ada, tetapi
untuk melengkapi dan memperkuat berbagai konsensus internasional, misalnya
tentang lingkungan, hak azazi manusia, pelindungan pekerja, MDGs, danlain
sebagainya.38
Prinsip Penyelenggaraan SR antara lain terkait dengan pembangungan
berkelanjutan, penentuan dan pelipatan stakeholders; komunikasi kebijakan
kinerja SR; penghargaan terhadap nilai-nilai universal, pengintegrasian SR dalam
kegiatan normal organisasi. Olehkarena itu, ada tujuh isu utama dalam perumusan
ISO 26000 yaitu 1) isu lingkungan, 2) isu hak asasi manusia, 3) isu praktek
ketenaga-kerjaan, 4) isu pengelolaan organisasi, 5) isu praktik beroperasi yang
adil, 6) isu hak dan perlindunagn konsumen, dan 7) isu partisipasi masyarakat,
Dokumen FinalISO 26000 dipublikasi pada awal tahun 2009. Diharapkan
2007. 38Ibid
II. 57
keberadaan ISO 26000 akan berdampak positif pada upaya percepatan
penanggulangan masalah kemiskinan, masalah pangan dan gizi, masalah
kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah kesejahteraan sosial. Penerapan CSR
di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan
menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor,
pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih mendukung
perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan
peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu,
perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik
serta keuntungan dan pertumbuhanyang meningkat. Memang saat ini belum
tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik CSR terhadap
keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap
skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena
mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang
mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang
sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktek CSR yang
berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan ijin operasional
darimasyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan
berkelanjutan.
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering
diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang
mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan
pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensimasyarakat
lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain
dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga
II. 58
kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra
sebagai perusahaan yang ramah dan pedulilingkungan. Selain itu, akan tumbuh
rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari
masyarakat sehingga masyarakatmerasakan bahwa kehadiran perusahaan di
daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.39
Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat
luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan
posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan
bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar
kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan
keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya
terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk
lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat
keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal
dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku
kepentinganinternal.
40
Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus
merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi
usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya
wajar bila perusahaan memperhatikankepentingan masyarakat. Kedua, kalangan
bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis
mutualisme. Ketiga, kegiatantanggung jawab sosial merupakan salah satu cara
untuk meredam atau bahkan menghindari konflik social.
41
39Ibid 40A.B. Susanto, Membumikan Gerakan Hijau, Majalah Ozon, Edisi No.5 Februari 2003. 41Ibid
II. 59
Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan
tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:42
Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau
kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Program
pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:
a. Public Relations
Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentangkegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Strategi defensif
Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negative komunitas
yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan
serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah
untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya
dengan yang baru yang bersifat positif.
c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan
43
Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau
kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada
1. Community Relation
Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembanganBkesepahaman melalui
komunikasi dan informasi kepada para pihak yangterkait. Dalam kategori ini,
program lebih cenderung mengarah pada bentukbentuk kedermawanan (charity)
perusahaan.
2. Community Services
42Himawan Wijanarko, Reputasi, Majalah Trust, 4-10 Juli 2005. 43Ibid
II. 60
di masyarakat dan pemecahan masalahdilakukan oleh masyarakat sendiri
sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah
tersebut.
3. Community Empowering
Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih
luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan
usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah
mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaanmemberikan akses kepada
pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran
utama adalah kemandirian komunitas.
Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan
nilaitambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap
tenagakerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya
substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan
perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder
yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program
pengembangan masyarakat sekitarnya.
Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang
umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan
globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin
besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajibanbaru standar
bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada
akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000on Social Responsibility,
sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program
CSR dijalankan oleh perusahaan apabilamenginginkan keberlanjutan dari
II. 61
perusahaan tersebut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam
perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan
kesetiaanmerek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan
menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para
pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk
membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan
merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR
adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan
tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation)
– konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun
mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan
masyarakat secara tidak langsung.
Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak
korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan
misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi,
besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar.
Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan
kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi)
serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar
kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan
lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ideal
bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang
penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan
foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah
direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program
II. 62
CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari
semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR.
Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk
bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisikehidupan umat manusia di
masa datang. Sebagai contoh, terdapat sebuah perusahaan di Indonesia yang
menjalankan strategi bisnis dengan konsep 3 P yaitu Profit, memastikan bahwa
tetap mampu memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah
sebagai sebuah perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua yaitu
Planet, memastikan bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman
hayati dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan.Konsep ketiga People
dengan meyediakan kesempatan untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan
serta menjadi tempat untuk pilihan pekerjaan. Perusahaan tersebut memiliki 6
konsep srategi pelaksanaan CSR yaitu environment, community empowerment,
improving workplace,volunterism, stakeholders engagement dan transparency.44
Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa melaksanakan bisnis di
Indonesia memiliki tantangan yang besar terutama untuk perusahaan extractive.
Penerapan CSR dimulai pada tahun 1993 dimana pelaksanaan program CD
dijalankan oleh Public Relations dengan kegiatan yang bersifat insidental dan
kedermawanan. Pada 1999 July 2005 kegiatan CD lebih mengarah ke penguatan
komunitas di bawah Departemen Community Development yang kemudian
didirikan Community Development Foundation. Pada November 2005 CSR
Department terbentuk dan pada tahun 2007 dibentuk Sustainability Director dan
menandatangani TheGlobal Compact untuk mendukung terwujudnya tujuan-
tujuan MilleniumDevelopment Goals (MDGs).
44Diakses dari http://www.csrindonesia.com pada tanggal 20 september 2011 pukul 13.00 wib
II. 63
Bisnis bukan hanya dilaksanakan beyond compliance tapi harus juga melibatkan
stakeholder (stakeholders engagement) . Perusahaantersebut berkomitmen untuk
menjalankan usaha dengan mengutamakan prinsip-prinsip sustainable
management, Socio-economic contribution danconservation and environmental
responsibility. CSR sebagai core competency dilakukan sebagai sebuah nilai yang
dilakukan oleh semua. Salah satu yang dilakukan perusahaan tersebut adalah
melakukan collaborative effort dengan LSM sebagai usaha untuk mengelola
konflik danisu sosial serta ekonomi yang merupakan tiket untuk melakukan bisnis
sehingga bisa menjanjikan bisnis yang berkelanjutan. Secara singkat CSR dapat
diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR
adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial
secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan
seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan community development
merupakan bagian dari pelaksanaan CSR.45
45Himawan Wijanarko, Filantrofi bukan Deterjen, Majalah Trust, 11-17 September 2006.
Dalam praktiknya, memang charity dan community development dikenal
lebih dahulu terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Serta,
kebutuhan perusahaan untuk lebih dapat diterima masyarakat. Sementara itu, lebih
jauh CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan
memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku, bukan saja
pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih
luas. Tidak hanya itu, CSR dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif
terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya
kesejahteraan.
II. 64
Memang ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap ketentuan dan\
pelaksanaan CSR. Dari sisi pendekatan, misalnya, ada community based
development project yang lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan
kemampuan kelompok masyarakat. Ada pula yang fokus padapenyediaan
kebutuhan sarana. Dan, yang paling umum adalah memberikan bantuan sosial
secara langsung maupun tidak langsung guna membantu perbaikan kesejahteraan
masyarakat, baik karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan sendiri maupun
yang bertujuan sebagai sumbangan social semata.
Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan
kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut
pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, masyarakat
adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan pembangunan
macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, demikian menurut pandangan mereka,
pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat
tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan resiko. Jalan keluar
yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan
menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepentingannya.
Kata kuncinya transparansi, partisipasi, dan penguatan kelompok lemah.
Pemerintah dan perusahaan dituntut membuat mekanisme untuk berkomunikasi
dengan lebih banyak pihak dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka.
Terakhir, harus ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat
berpartisipasi dengan benar.
Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi semacam prinsip yang
dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat. CSR secara
umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan
II. 65
berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan
lingkungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada
pada tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat
termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan
dansosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian
dari pengelolaan risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan
usahanya.
Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000,
walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun
1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti
donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi
perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan melalui Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah
memasukkan pengaturan Tanggung JawabSosial dan Lingkungan kedalam
Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya ada beberapa hal yang
mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial
dan lingkungan Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi
yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di
pihak masyarakat. Kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam
penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks
nasional maupun lokal.46
Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah
mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang
sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk memenuhi
46A.B. Susanto, Paradigma Baru - Community Development, Harian Kompas, 22 Mei2001.
II. 66
kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSRhanya sebatas sumber daya
finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.47
Di masa lampau, hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan
lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadapan
dengan aparat keamanan. Walaupun kini hal tersebut belum menghilang
sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak terdengar. Kiranya,
Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan
akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang
memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan
sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR,apa pun
alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut
kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.
Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan
dan dampak negatif keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung
pada core business-nya masing-masing) padahal melihat perkembangan aktivitas
CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR
dengan beberapa tujuan pemerintah.
Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas CSR dengan regulasi
seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan
terkesan basa-basi. Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan
pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam dua
dekade belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruhdan
lingkungan, telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak dulu. Namun,
tanggapan positif terhadapnya memang baru terjadi belakangan.
47Ibid
II. 67
disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini telah banyak tersedia.
Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan tekanankepada perusahaan
berkinerja buruk. Payahnya, banyak perusahaan juga yang mulai menyadari
pentingnya meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan ternyata tidak
mendapatkan insentif yang memadai dari berbagaipemangku kepentingan. Bahkan
mereka yang secara fundamental hendakberubah malah menjadi sasaran tembak.
Karena dianggap “melunak”, perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber
uang yang bisa diambil kapan saja melalui berbagai cara. Di antara berbagai
pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. Selain berbagai perangkat yang
diciptakan di tingkat pusat, beberapa pemerintah kabupaten telah membuat
berbagai macam forum CSR. Regulasi hubungan industrial juga telah dibuat di
beberapa provinsi. Di satu sisi, perkembangan ini cukup menggembirakan karena
menunjukkan tumbuhnya pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan
pembangunan dengan perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa
pemerintah sedang memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan.
Berbagai regulasi yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi
perusahaan, alihalih menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan
kinerja CSRnya.
Secara teoritis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah
seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat
beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi
yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerjaminimal bagi
perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah
mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa pula membantu perusahaan yang
sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya
II. 68
dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan
pemangku kepentingan lain, meningkatkankepedulian pihak lain atas upaya yang
sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk
bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan. Mengingat CSR sulit terlihat
dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan yang dicapai. Olehkarena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk
menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line
atau SustainabilityReporting. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam
dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran
danpenghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi
lingkungan.
Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR,
yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan
(internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya
regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenaidampak lingkungan
(Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah
memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan).
Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen
dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggung
jawab perusahaan untuk membangunmasyarakat sekitar (community development
responsibility). Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan
mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuhdan
berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari
masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap
kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia
II. 69
(human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan
pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan
mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).48
Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga
kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian
menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama biasmasuk
dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.
Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas atau
masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran
Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan
oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan Strategic CSR. Agenda sosial
perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang
untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungansecara bersamaan.
Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju penemuan jalan untuk
mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda
sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan.
Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga
kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi
secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak memengaruhi kemampuan
perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua,dampak sosial value
chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal
perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di
lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi
kemampuan berkompetisi perusahaan.
48Diakses dari http://www.csrindonesia.com pada tanggal 20 september 2011 pukul 13.00 wib.
II. 70
terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawabsosial tersebut.
Perubahan orientasi sosial politik di tanah air dapat memunculkan kembali
apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif dalam upaya
menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber daya yang ada di
wilayahnya. Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan
kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki
saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan
masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan social harus
mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan
kedua belah pihak. Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan
masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa perusahaan
memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secaranormal.
Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua
aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran,
penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya.Kedua, outside-in-linkages, di mana
kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau
lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber
daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur
kompetisiseperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin
transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas
permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat,
seperti penyedia jasa dan produsen mesin.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat
membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji
(good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis
II. 71
sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yangberada dalam kelompok bisnis
serta kelompok yang terkait lainnya. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku
dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita
sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai
yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri
adalah:49
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilaitambah
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja,
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan
mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat
adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan
budaya lokal tersebut. Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang
aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan
perannya yaitu:
1) Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil
keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang
dianggapnya baik untuk dilakukan.
2) Prinsip kejujuran.
3) Prinsip keadilan.
4) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).
5) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam
diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap
menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.
50
a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak
49Majalah Bisnis Dan CSR, Oktober 2007. 50Ibid.
II. 72
sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan
membangun institusi yang terkait dengan CSR
c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai
elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan
dan meningkatkan kualitas penerapan CSR
Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua
stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus
punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bias melindungi kepentingan yang
lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan
ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk
pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini.
Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat
di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik. Cakupan dari
ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasiorganisasi menjalankan
tanggung jawab sosialnya; memberikan “practicalguidances” yang berhubungan
dengan operasionalisasi tanggung jawab sosial; identifikasi dan pemilihan
stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai
tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan
peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan
˜stakeholders lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan
traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi
otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu
organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung
II. 73
jawab social dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab
sosial.51
ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang
diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility,
memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi
trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan
sungguh–sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha di Indonesia. ISO
26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan
pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus
bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa
masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini
bisa dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/asistensi pada
perusahaan yangbelum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-nya juga
diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan
menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau
insentif tertentu yang bias meyakinkan pasar internasional untuk menerima
produk Indonesia.
Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi
perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan
yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak
menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangunkomunikasi yang efektif
dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.
51A.B. Susanto, Manajemen Aktual, Jakarta, Grasindo, 1997, hlm.53.
III. 1
BAB III
Analisis Data
“Masa depan kemanusiaan tergantung pada adanya sikap kritis dewasa ini”.
-Max Horkheimer-
Inti dari madzhab kritis dalah kebencian terhadap sistem filosofis yang
tertutup. Menyajikan hal ini sedemikian rupa akan medistorsi kandungannya yang
tak terbatas dan memancing rasa ingin tahu. Bukan suatu kebetuan kalau
Hokheimer memilih megartikulasikan ide-ide nya dalam beberapa essai dan
aforisme daripada dalam beberapa bacaan jilid berat yang menjadi ciri filsafat
Jerman. Meski Adorno dan Mercuse tidak terlalu antusias berbicara melalui
buku-buku yang utuh, mereka pun mengekang dorongan untuk menjadian buku
tersebut melalaui prnyataan-pernyataan filosofis yang bernada positif yang
tersusun secara sistematis. Justru Madzhab kritis, sebagaimana namanya,
diekspresikan melalui serangkaian kritik terhadap pemikir dan tradisi-tradaisi
filsafata lain. Perkembangan kemudian berlangsung melalui dialog, kelahiranya
berkarakter diaektis sebagaimana metode yang inigin diterapkan kepada
fenomena sosial. Hanya dengan menkonfrontirnya dengan gagasan-gagasan
sendiri, sebagai suatu virus bagi sistem yang lain, barulah dia dapat dipahami
sepenuhnya.1
“Hendaklah anda berani berpikir sendiri!”Semboyan ini bergema keras di
abad delapan belas, yang dalam sejarah barat dikenal sebagai jaman Aufklärung,
jaman ketika manusia gandrung dengan akal budinya sendiri.Aufklärung sendiri
1Martin Jay, Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teri Kritis, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2005, hal. 57-58.
III. 2
berarti pencerahan.Nama tadi diberikan pada jaman ini karena manusia mencari
cahaya dalam akal budinya.2
Immanuel Kant telah mengetengahkan semacam definisi. Katanya,
dengan Aufklärung dimaksudkan bahwa manusia keluar dari keadaan tidak akil
baligh, yang dengannya sendiri ia bersalah. Bersalah, karena ia tidak
menggunakan kemungkinan yang ada padanya, yakni akal budinya. Kini tiba
saatnya manusia benar-benar harus menggunakan akal budinya.
3
Tetapi sesungguhnya Aufklärung bukan hanya milik abad delapan belas.
Sejak dua ribu lima ratus tahun yang lalu manusia sudah senantiasa berusaha
untuk mencapai pengertian rasional tentang dirinya dalam alam lingkungannya.
Le miracle Grec (keajaiban yunani) adalah awal dari Aufklärung sendiri.
Maksudnya aneh bin ajaib dalam usia semuda itu dan dalam keadaan seprimitif
itu, manusia sudah tahu betapa agung akal budinya. Bagaikan suatu keajaiban
pada saat suasana masih diliputimitos dan tahyul, filsuf-filsuf pertama Yunani
dari Yonia sudah bisa mencoba memberikan pengertian rasional tentang asal
muasal alam semesta.
4
Aufklärung melaju terus, Plato atau Aristoteles dengan ontologinya, abad
pertengahan dengan metafisiknya, masa modern dengan rasionalismenya.Dan
masa kini dengan empirisme atau positivismenya.Ini semua merupakan usaha
manusia untuk mencapai pengertian rasional tentang dirinya dalam alam
lingkungannya.
5
2 Sindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Gramedia: Jakarta, 1982, hal.68. 3 Lih.K.Bertens, Ringkasan Sejarah Filasafat,Kanisius: Yogyakarta, 1976, hal.51. 4 Sindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Gramedia: Jakarta, 1982, hal.69. 5Ibid, Hal.70.
III. 3
Dalam pengertian ini, terselip makna emansipatoris dari Aufklärung,
yakni pembebasan manusia dari kekuatan diluar dirinya demi kedaulatan
dirinya.Sesungguhnya Aufklärung dapat diartikan sebagai usaha manusia
rasional.Sebab dengan pembebasan itulah, manusia mempunyai otonomi atas
dirinya sendiri, dan dengan demikian juga manjadi rasional. Horkheimer sindiri
juga memakai Aufklärung bukan dalam arti yang biasa digunakan yakni “gerakan
abad delapan bales” (masa Aufklärung), melainkan Aufklärung dalam artinya
yang luas yakni:”arti yang paling utama dari pemikiran progresif…yang
bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketakutan dan membangun
kedaulatan dirinya”.6
Selanjutnya kami juga akan menggunakan istilah usaha manusia rasional
dalam pengertian Aufklärung dalam artinya yang luas tersebut. Jadi istilah usaha
manusia rasional itu tidak membatasi diri pada Aufklärung abad delapan belas,
melainkan Aufklärung pada umumnya, yang berarti usaha manusia untuk
mencapai pengertian rasional yang emansipatoris.Seluruh tahapan madzhab kritis
Horkheimer dengan demikian juga termasuk dalam usaha manusia rasional.Sebab
madzhab kritis juga hendak mengemansipasikan manusia dari keadaan irasional
masyarakat jaman ini.
7
Disini Horkheimer berbicara sebagai seorang marxis, ini mengandaikan
bahwa orang tidak perlu terlebih dulu menanyakan apa sesungguhnya
keirasionalan masyarakat itu. Sebab bagi kalangan marxis, keirasionalan
6Max Horkheimer dan Theodore W. Adorno.Dialectic of Enlightment, translated by John Cumming. Allen Lane: London, 1973Hal. 3. Bdk Leszek Kolakowski, Main Current of Marxism, Vol. II:The Breakdown, Oxford: Clarendon Press, 1978, hal. 372-373. 7 Sindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional, Gramedia: Jakarta, hal.71.
III. 4
masyarakat itu sudah terang dan jelas dengan sendirinya dan diandaikan begitu
saja dalam pemikiran mereka.Seperti rekannya, persoalan pokok Horkheimer
hanyalah bagaimana membangun teori yang bisa membedol keirasionalan
masyarakat itu.8
Dalam artikelnya ini Horkheimer memperlihatkan bahwa pandangan yang
sudah umum berlaku sejak Descartes sampai saat ini (teori tradisional) gagal
menjadi teori emansipatoris. Maka ia mencoba menyodorkan pandangannya yang
baru (Madzhab kritis), yang pada hematnya bakal banar-benar menjadi teori
emansipatoris.
9
Kata kritik sebenarnya sudah dipakai sejak masa Renaissance (1350-
1600). Dalam masa itu, masyarakat Eropa membangkitkan kembali
III.1 Pengertian “Kritik” Dalam Tradisi Madzhab Kritis
Kritik merupakan konsep kunci untuk memahami madzhab
kritis.Kritik juga merupakan suatu program bagi Mazhab Frankfurt untuk
merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris atas kebudayaan dan
masyarakat modern. Kritik mereka diarahkan pada berbagai bidang kehidupan
masyarakat modern, seperti seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik dan
kebudayaan pada umumnya yang telah menjadi rancu karena diselubungi oleh
ideologi yang menguntungkan pihak tertentu sekaligus mengasingkan
manusia individual dari masyarakatnya.
8 Ibid. 9 Uraian Horkheimer tentang teori Tradisional dan teori Kritis seluruhnya terdapat dalam Max Horkheimer, Critical Theory, Selected Essays, translated by Matthew J. O’Connel cs., New York: Seabury Press, 1972, hal.188-252.
III. 5
kebudayaan Yunani dan Romawi dan karena banyak inspirasi rasional digali
darinya, kecenderungan berpikir pada masa ini telah mulai mengusir
kegelapan dogmatis abad pertengahan (600-1400) yang dikuasai cara berpikir
gaya gereja, dimana faktor iman dan kepatuhan kepada otoritas gereja
mendapat porsi besar. Dalam masa Renaissance, para sarjana dan seniman
menyibukkan diri dengan teks sastra dari zaman Yunani-Romawi termasuk
Kitab Suci.Mereka mencoba memberi penjelasan dan penilaian atas teks
tersebut.
Sebagaimana lazimnya waktu itu, penjelasan semacam itu juga
dipergunakan untuk menyerang atau mempertahankan ajaran iman
tertentu.Seni menilai dan menjelaskan teks ini menjadi awal hermeneutika
Kitab Suci dan akhirnya menjadi seni kritik yang lepas dari kegiatan
pengetahuan yang dilatarbelakangi iman.Lambat laun kritik sastra ini menjadi
seni kritik yang cenderung untuk selalu rasional.Jika madzhab kritis
mempergunakan konsep kritik, hal itu terutama dihubungkan dengan konsep
kritik yang dikembangkan pada masa setelah Renaissance, yaitu masa
Aufklarung (abad ke-17 dan 18) dan abad ke-19.
Pada masa itu muncul filsuf-filsuf seperti Kant, Hegel, dan Marx yang
oleh Mazhab Frankfurt dipandang sebagai filsuf-filsuf kritis.Pada akhir abad
sebelumnya dan permulaan abad ini, muncul seorang pemikir yang kendati
bukan seorang filsuf namun bagi Mazhab Frankfurt dipandang sebagai
pemikir kritis, pemikir kritis itu adalah Sigmund Freud.Jika madzhab kritis
mempergunakan kata “kritik”, hal tersebut langsung dikaitkan pada keempat
III. 6
pemikir kritis tersebut.Dengan demikian, kritik dipahami dalam arti Kantian,
Hegelian, Marxian, dan Freudian.
III.1.1 Kritik Dalam Arti Kantian
Menurut madzhab kritis, Imannuel Kant adalah seorang pemikir kritis
karena ia mempertanyakan the condition of possibility dari pengetahuan kita
sendiri. Para filsuf sebelum Kant menyibukkan diri dalam diskusi yang tidak
kunjung selesai mengenai isi pengetahuan. Misalnya mereka berpretensi untuk
mengetahui apa itu kebebasan dan kekekalan jiwa lalu berusaha
merumuskannya secara ontologis, Kant tidak ingin mempersoalkan semua itu
melainkan mengarahkan diri pada rasio kita sendiri yang menjadi alat untuk
menyelidiki perkara metafisis tersebut.
Kant menyelidiki kemampuan dan batas rasio dengan tujuan untuk
menunjukkan sampai sejauh mana klaim rasio kita tersebut dapat dianggap
benar.Jalan yang ditempuh oleh Kant ini disebutnya sebagai kritisisme dalam
perlawanannya dengan jalan yang ditempuh para filsuf sebelumnya yang
disebut dogmatisme. Kant menulis,
“Kritik saya … ditujukan pada dogmatisme saja, yaitu pengandaian bahwa mungkinkah membuat suatu kemajuan dengan pengetahuan murni (filosofis) yang terdiri atas konsep dan yang diarahkan oleh prinsip, seperti yang telah lama dijalankan oleh rasio, tanpa terlebih dahulu menyelidiki dengan cara apa dan dengan hak apa rasio sampai memiliki konsep dan prinsip itu. Karena itu, dogmatisme adalah jalan yang dipakai oleh rasio murni tanpa kritik lebih dahulu atas kemampuannya sendiri”10
Dengan mempertanyakan syarat kemungkinan pengetahuan, Kant
menguji sahih tidaknya bentuk pengetahuan, seperti fisika dan metafisika. Di
.
10 ImannuelKant, Critique of Pure Reason, New York, Doubleday & Company Inc, 1996, Hlm. xiii.
III. 7
sini Kant dengan epistemologinya ingin menunjukkan bahwa rasio dapat
menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi “pengadilan
tinggi” terhadap hasil refleksinya sendiri, yaitu ilmu pengetahuan dan
metafisika. Kritik dalam pengertian Kantian lalu berarti kegiatan menguji
sahih atau tidaknya klaim pengetahuan dengan tanpa prasangka dan kegiatan
ini dilakukan oleh rasio belaka.
III.1.2 Kritik dalam arti Hegelian
Menurut madzhab kritis, Hegel mengembangkan konsep kritik dengan
cara yang berbeda dari Kant, bahkan Hegel mengkritik epistemologi Kant.
Kritik Kant bersifat transendental dan dengan cara itu ia ingin meletakkan
rasio yang kritis itu di atas suatu dasar yang pasti dan tak tergoyahkan. Rasio
semacam ini tidak mengenal waktu, netral, dan ahistoris. Hegel yang kritis
terhadap kritisisme Kant ini menempatkan kegiatan pengetahuan kita dan
rasio di dalam konteks proses perkembangan pengetahuan dalam proses
sejarah. Dalam istilah Hegel, rasio ditempatkan di dalam rangka proses
pembentukan diri (Bildungsprozess)11
Dalam pandangan Hegel, rasio bersifat kritis tidak dengan cara
transendental dan ahistoris, seakan-akan rasio tersebut telah sempurna pada
dirinya. Rasio menjadi kritis justru kalau menyadari asal-usul
pembentukannya sendiri. Rasio bukanlah kesadaran lengkap yang bebas dari
rintangan-rintangan dalam sejarah umat manusia dan alam, melainkan
dari rasio.
11 Yang dimaksud dengan Bildungsprozess atau Self-formative process adalah proses sejarah kebudayaan atau proses pembudayaan manusia. Kata Bildung berarti pendidikan kepribadian.
III. 8
merupakan proses menjadi semakin sadar justru di dalam rintangan-rintangan
tersebut.
Jika rasio menyadari rintangan-rintangan mana yang menghalanginya
untuk menjadi semakin rasional dan semakin sadar, rasio melangkah ke
kualitas rasionalitas yang lebih tinggi. Menyadari adanya rintangan tersebut,
dalam pandangan Hegel sama dengan menyadari asal-usul kesadaran. Dengan
kata lain, kesadaran rasional kita akan sesuatu yang terbentuk justru setelah
kita merefleksikan rintangan tersebut dan dengan terbentuknya kesadaran itu
kita dapat membebaskan diri dari rintangan itu untuk menjadi semakin
rasional. Proses rasio menjadi semakin rasional dalam sejarah ini
digambarkan oleh Hegel dalam suatu ilustrasi yang terkenal, yaitu “dialektika
tuan dan budak”12
Dalam konflik dan kontradiksi serta rintangan yang menuntut korban
ini, manusia berusaha memahami siapa dirinya yang sebenarnya atau dengan
kata lain rasio berjuang untuk menyadari dirinya dan menjadi semakin
rasional dan bebas. Contohnya adalah proses penyadaran rasio yang diperoleh
.
Untuk menggambarkan maksudnya, Hegel menunjuk beberapa contoh
di dalam sejarah bagaimana rasio dan proses kesadaran manusia menjadi
makin rasional. Bagi Hegel, sejarah tak lain dari pergumulan rasio
merefleksikan dan membebaskan dirinya dari rintangan untuk menjadi
semakin sadar. Dalam sejarah, zaman yang satu berperang melawan zaman
yang lain, bangsa melawan bangsa, dan kebudayaan melawan kebudayaan.
12 G.W.F Hegel, Phenomenology of Spirit, Clarendon Press: Oxford, 1977, Hlm. 111-119
III. 9
dalam revolusi Prancis, msekipun revolusi ini menghasilkan korban yang
tidak sedikit, berkat pertentangan inilah warga Negara memperoleh
kebebasannya dari kekuasaan monarki absolut. Kesadaran demokratis yang
diperoleh dalam revolusi Prancis tak lain dari hasil refleksi dan perjuangan
rasio sendiri untuk menyadari adanya rintangan untuk menjadi semakin bebas
dan sadar. Proses sejarah manusia dalam memahami siapa dirinya, apa itu
masyarakat, kebudayaan dan alam semesta adalah proses pembentukan diri
rasio.
Dengan demikian, kita sampai pada kritik arti Hegelian. Kritik tidak
lain dari refleksi atau refleksi diri atas rintangan, tekanan, dan kontradiksi
yang menghambat proses pembentukan diri dari rasio dalam sejarah. Dengan
kata lain, kritik juga berarti refleksi atas proses menjadi sadar atau refleksi
atas asal-usul kesadaran. Secara singkat, kritik berarti negasi atau dialektika
karena bagi Hegel kesadaran timbul melalui rintangan yaitu dengan cara
menegasi atau mengingkari rintangan tersebut.
III.1.3 Kritik dalam arti Marxian
Jika Hegel mengembangkan konsep kritik dalam konteks filsafat
idealismenya, Marx mengembangkan konsep ini dalam rangka
materialismenya.Dalam pandangan Marx, kritik dalam filsafat Hegel masih
kabur dan membingungkan karena Hegel memahami sejarah secara
abstrak.Sejarah bukanlah sejarah konkret dari manusia yang berdarah daging,
melainkan sejarah kesadaran atau sejarah rasio. Dengan cara idealistis tersebut
III. 10
seperti juga dengan cara transendental, kritik tidak menghasilkan apa-apa bagi
praxis karena sasaran pragmatisnya tidak jelas.
Marx mendaratkan idealisme Hegel ini menjadi materialisme sejarah
yang bersifat praktis emasipatoris dan kebersamaan dengan itu konsep kritik
diterapkan dalam sejarah konkret dari masyarakat yang nyata13
13KarlMarx, Early Writings, Penguin Books: London, I981, Hlm. 384-385.
. Dalam
pandangan Marx, apa yang terjadi dalam masyarakat dan sejarah adalah orang
yang bekerja dengan alat kerja untuk mengolah alam. Dalam masyarakat, alat
kerja, pekerja, dan pengalaman kerja merupakan kekuatan produksi
masyarakat, sedangkan hubungan antarpekerja dalam proses produksi tersebut
merupakan hubungan produksi. Jika kekuatan produksi berkembang,
hubungan produksi juga turut berubah. Misalnya, sistem gotong royong di
antara petani tradisional dalam mengerjakan sawahnya akan berubah jika
teknologi pertanian baru ditetapkan dalam masyarakat petani tersebut.
Menurut Marx, sejarah tak lain dari sejarah perkembangan tenaga
produksi dan hubungan produksi, atau dengan kata lain sejarah ekonomi,
proses produksi dalam masyarakat. Dalam praktik, hubungan produksi ini
adalah hubungan kekuasaan antara pemilik modal di satu pihak dan kaum
buruh di pihak lain. Untuk menumpuk keuntungan dan memenangkan
persaingan pasar, para pemilik modal memeras kaum buruh dengan pekerjaan
yang harus mereka lakukan demi menyambung hidup.Akan tetapi, pekerjaan
di dalam pabrik kaum kapitalis terebut adalah pekerjaan yang tidak manusiawi
dan mengasingkan kaum buruh.
III. 11
Hubungan hak milik dan penguasaan ini bersifat konservatif dan ingin
dipertahankan terus karena menguntungkan pihak pemilik modal.Hal
sebaliknya terjadi pada kekuatan produksi, kekuatan produksi diperbaiki,
dirasionalisasikan, ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya.Karena perbedaan
sifat antara hubungan produksi yang konservatif dan kekuatan produksi yang
progresif, terjadilah kontradiksi secara terus menerus di masyarakat.Dalam
pengertian inilah Marx mendaratkan dialektika Hegel ke dalam masyarakat
nyata.
Dalam pandangan Marx, kontradiksi dalam masyarakat tersebut juga
mencerminkan pertentangan kepentingan antara kaum kapitalis dan kelas
buruh atau kaum proletariat. Kelas kapitalis ingin melestarikan kekuasaannya
sementara kaum proletar ingin membebaskan diri dari penindasan tersebut
dengan cara menghapus hak milik pribadi atas alat produksi. Ketika
kontradiksi makin menghebat, perjuangan kelas proletariat untuk
mengemansipasikan diri melalui revolusi sosial tidak dapat dicegah lagi.
Menurut Marx setelah revolusi terjadi, sistem ekonomi masyarakat
berubah dan bersamaan dengan itu bentuk kesadaran sosial juga berubah
sebab perubahan pada basis ekonomi mau tak mau menentukan perubahan
pada suprastruktur kesadaran.
“pada tahap tertentu perkembangannya, kekuatan produksi material masyarakat bertegangan dengan hubungan produksi yang ada … di dalamnya keduanya sampai sekarang bergerak. Dari bentuk perkembangan kekuatan produksi ini, hubungan ini sekarang berubah menjadi belenggunya, mulailah suatu tahap revolusi sosial. Dengan
III. 12
perubahan basis ekonomi, seluruh suprastruktur raksasa itu dijungkirbalikkan ….”14
Freud memberi pengertian yang lebih lengkap terhadap konsep kritik
meskipun ia sendiri tidak secara eksplisit menyebut konsep ini. Madzhab
kritis berupaya mengintegrasikan konsep kritis dari Freud mengenai gangguan
psikis dan naluri ke dalam kritik ideologi Marx. Dengan cara demikian, suatu
. Dari sini dapat kita lihat bahwa dalam pandangan Marx, pengetahuan atau
rasio kita ditentukan oleh faktor ekonomis masyarakat dan kesadaran baru
yang timbul hanyalah akibat langsung dari penataan baru atas proses produksi
sosial.
Menurut madzhab kritis, kritik dalam konteks materialisme sejarah ini
berarti praksis revolusioner yang dilakukan kaum proletariat atau perjuangan
kelas.Kritik berarti usaha mengemansipasikan diri dari penindasan dan
alienasi yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan di masyarakat. Akan tetapi
sebagaimana tampak dari teori Marx yang membuka kesadaran akan adanya
mekanisme obyektif hubungan penindasan dan menunjukkan cara
pemecahannya, kritik dalam arti Marxian juga berarti teori dengan tujuan
emansipatoris. Dengan menyingkapkan kenyataan sejarah dan masyarakat
lewat analisisnya tersebut, Marx tidak sekadar melukiskan masyarakat
melainkan juga hendak membebaskannya.Kritik sebagai teori dan praksis
emansipatoris inilah pengertian kritik dalam arti Marxian.
III.1.4 Kritik dalam arti Freudian
14KarlMarx, “Preface of a Contribution to the Critique of Political Economy”. Dalam Marx and Engels.Selected Works. Vol.1. Foreign Languages Publishing House: Moscow, 1962, Hlm. 363.
III. 13
kritik yang bersifat kemasyarakatan mendapat pendasaran psikologisnya. Para
pendiri madzhab kritis generasi pertama yang melakukan integrasi ini adalah
Horkheimer, dan khususnya Herbert Marcuse.Erich Fromm, meskipun tidak
dapat dimasukkan ke dalam generasi pertama madzhab kritis juga turut
menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pengintegrasian psikoanalisis
Freud ke dalam materialisme sejarah Marx.
Sebagai seorang psikoanalis, Freud menghadapi pasien yang
mengalami gangguan kejiwaan seperti histeria, fobia, neurosis, dan berbagai
macam penyakit psikopatologis lainnya.Subyek dari psikoanalisis Freud
tersebut adalah manusia yang menipu diri tentang dirinya sendiri karena
adanya mekanisme tak sadar dalam dirinya berupa tekanan psikis.Konflik
psikis ini muncul sebagai akibat represi terhadap naluri yang penyalurannya
dilarang di masyarakat.Karena konflik internal ini, pasien membuat ilusi dan
delusi serta mekanisme pertahanan diri tak sadar.
Dengan menciptakan gambaran palsu, ilusi, delusi, dan melakukan
mekanisme pertahanan diri, subyek merasa seolah-olah memperdamaikan
konfliknya, akan tetapi sesungguhnya hal tersebut hanya penipuan diri belaka
dan penindasan diri oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, subyek
psikoanalisis Freud seperti juga kaum proletariat pada teori Marx berada
dalam situasi ketidakbebasan. Hanya saja pada pasien Freud, ketidakbebasan
subyek itu adalah ketidakbebasan psikis.
Situasi represi, ketertindasan psikis, penipuan diri, gambaran-
gambaran palsu yang terbentuk ini oleh generasi pertama madzhab
III. 14
kritisditerapkan ke dalam kenyataan sosial, khususnya pada ideologi dan
hubungan kekuasaan.Apa yang terjadi pada taraf individual diterapkan pada
taraf sosial. Dalam arti Freudian, kritik adalah refleksi baik dari pihak
individu maupun masyarakat atas konflik psikis yang menghasilkan represi
dan ketidakbebasan internal sehingga dengan cara refleksi tersebut masyarakat
dan individu dapat membebaskan diri dari kekuatan asing yang mengacaukan
kesadarannya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kritik tak lain dari
ketidaksadaran menjadi kesadaran.
Keempat arti kritik tersebut yang dimaksudkan oleh para pendiri
madzhab kritis jika mereka menganalisis kenyataan ideologis dari masyarakat
zaman sekarang. Dengan sebutan yang lazim diberikan pada keempat macam
kritik tersebut dapat dikatakan bahwa mereka melontarkan apa yang disebut
kritik ideologi, karena mereka terutama memusatkan diri pada kenyataan
ideologis dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan kenyataan material
masyarakat.
III.2 Kritik Madzhab kritis Atas CSR di Indonesia
III.2.1 CSR Menjadi Strategi Pembangunan di Indonesia
Di Indonesia, kini kita menyaksikan perbincangan yang terus berlanjut
seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada persetujuan dan pula
pertentangan.Terlebih pihak pemerintah secara khusus membuatkan UU tentang
tanggung jawab sosial ini, yakni dalam UU Perseroan Terbatas Pasal74.Terlepas
dari itu, isu tentang Corporate Social Responsibility (CSR) memang kian hangat.
III. 15
Persoalannya bukan lagi melulu dari aspek sosial, tetapi sudah jauh
merasuk ke aspek bisnis dan penyehatan orporasi.Lama-kelamaan, CSR tidak lagi
dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang semula
dianggap sebagai cost, kini mulai diposisikan sebagai investasi. Dalam sebuah
ulasan di Majalah Marketing (edisi 11/2007) menegaskan tentang mengapa pula
perusahaan harus berinvestasi pada kegiatan CSR?Apakah lantaran moralitas
semata atau dia sudah menjadi marketing tools yang efisien?Pertanyaan ini
menjadi pertanyaan manajemen dan divisi marketing sewaktu mempersiapkan
strategi CSR.Akan tetapi, perdebatan paling baru tentang CSR adalah soal imbas
program tersebut pada profit perusahaan.Para pelaku dituntut untuk ikut
memikirkan program yang mampu mendukung sustainability perusahaan dan
aktivitas CSR itu sendiri.
Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti responsif terhadap kondisi-
kondisiyang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global, tren baru di pasar,
dan kebutuhan stakeholdersyang belum terpenuhi.15
15 Majalah Marketing. Edisi 11/2007.
Berkaitan dengan masalah
imbas tadi, Global CSR Survey paling tidak bisa memperlihatkan betapa
pentingnya CSR.Bayangkan, dalam survey di 10 negara tersebut, mayoritas
konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta
merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang
dilakukan perusahaan tersebut.Sebaliknya,sebanyak 61% dari mereka sudah
memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya tanggung jawab sosial.CSR
kini bukan lagi sekadar program charity yang tak berbekas. Melainkan telah
III. 16
menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang (CSR for
profit). Karena itu,hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan
dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung core business
perusahaan.16
Philip Kotler, dalam buku CSR: Doing the Most Good for Your Company
and Your Cause, membeberkan beberapa alasan tentang perlunyaperusahaan
menggelar aktivitas itu. Disebutkannya, CSR bisa membangunpositioning merek,
mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar,meningkatkan loyalitas
karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik korporat
di mata investor.
17 Menurut Godo Tjahjono, Chief Consulting Officer Prentis,
CSR memang punya beberapa manfaat yang bisa dikategorikan dalam empat
aspek, yaitu: license to operate, sumber daya manusia, retensi, dan produktivitas
karyawan. Dari sisi marketing, CSR jugabisa menjadi bagian dari brand
differentiation.18
Kini kita menyaksikan dan mengharap gairah perusahaanperusahaan
raksasa dunia untuk menerapkan program kepedulian sosial. Semoga ini tak hanya
jadi sekedar angin segar ditengah kekosongan issu saja, melainkan mampu
menjadi virus baik yang menyebar cepat di Indonesia.
19
Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an.
Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social
16 Ibid 17 Philip Kotler. 2007. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York, Thomas Dunne Books.hal. 33. 18 Majalah Marketing, Edisi 11/2007 19Di sarikan dari berbagai sumber – Cikeas Magazine ”CSR dari mana datangnya”, Vol 1 No4/07, Majalah Marketing, ”CSR for Profit”, edisi 11/2007, dan Societa, “Sejarah Panjang Konsep CSR”, 12/2006.
III. 17
Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai
CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan
bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan
lingkungan. Melalui konsep investasi social perusahaan “seat belt”, sejak tahun
2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam
mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai
perusahaan nasional.
Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya
kegiatan perusahaan membawa dampak (for better or worse), bagi kondisi
lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan
beroperasi.Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholdersatau
para pemegang saham.Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.20
20 A.B.Susanto, Budaya Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997, hlm.55
Stakeholders dapat mencakup
karyawan dan keluarganya,pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan,
lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku
regulator. Jenis dan prioritas stakeholdersrelatif berbeda antara satu perusahaan
dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.
Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan
masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholdersdalam skala prioritasnya.
Sementara itu, stakeholdersdalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti
Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.
III. 18
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering
diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang
mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan social dan
pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensimasyarakat
lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain
dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga
kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra
sebagai perusahaan yang ramah dan pedulilingkungan. Selain itu, akan tumbuh
rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari
masyarakat sehingga masyarakatmerasakan bahwa kehadiran perusahaan di
daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di
negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban
semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan muncul pada saat pembahasan ditingkat Panja dan Pansus DPR.Pada
konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat
dengar pendapat dengan Kadin danpara pemangku kepentingan lain, materi pasal
74 ini pun belum ada. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan
Apindo, keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR
membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan
lingkungan dalam RUU PT.
III. 19
Substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tentang
Perseroan Terbatas mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan
lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan
anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dankewajiban melaporkannya.
Mengikuti perkembangan berita di media massa yang menyangkut pembahasan
pasal 74, sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan cukup
lumayan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Tadinya, tanggung jawab
sosial dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di
bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua
perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, baru berdiri, atau
masihdalam kondisi merugi.
Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR
dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga
internasional (The World Bank, ISO 26000 dan sebagainya) serta praktek yang
telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional.Lalu
sebenarnya seperti apa best practice mengenai CSR ini? Saat ini ISO
(International Organization for Standardization), tengah menggodok konsep
standar CSR yang diperkirakan rampung pada akhir 2009. Standar itu dikenal
dengan nama ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Dengan standar ini,
pada akhir 2009 hanya akan dikenal satu konsep CSR. Selama ini dikenal banyak
konsep mengenai CSR yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan
para pakar. Pada dasarnya kegiatan CSR sangat beragam bergantung pada proses
III. 20
interaksisosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan
biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-
undangan.
Oleh karena itu, didalam praktek, penerapan CSR selalu disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan
masyarakat.Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni
dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat dan kemudian dilaksanakan
sendiri oleh masing-masing perusahaan.Dengan demikian adalah tidak mungkin
untuk mengukur pelaksanaan CSR.Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian
dari good corporate governance yang mestinya didorong melalui pendekatan etika
maupun pendekatan pasar (insentif).Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan
untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam kaitan untuk
menyamakan level of playing field pelaku ekonomi.Sebagai contoh, UU dapat
mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, bukan hanya aspek keuangan,
tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan
masyarakat.Tak banyak yang menyadari bahwa sesungguhnya perusahaan dan
masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi.Saling ketergantungan
antaraperusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan
kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (shared value), yaitu
pilihan-pilihan harus memberi manfaat kedua belah pihak.Lebih menarik lagi
ternyata terdapat inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta penjelasan
pasal 74 itu sendiri.Pada pasal 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
III. 21
Perseroan Terbatas memuat “… komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan
serta”, sedangkan pasal 74 ayat 1 “… wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan”.Pada pasal 1 mengandung makna pelaksanaan CSR
bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan
masyarakat.Sedangkan pasal 74 ayat 1 bermakna suatu kewajiban.Lebih jauh lagi
kewajiban TJSL pada pasal 74 ayat 1 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan
sanksinya pada pasal 74 ayat 3.Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan tidak diatur dalam UU PT tetapi digantungkan
kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Demikian juga pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung
jawab sosial dan lingkungan, dibatasi namun dalam penjelasannya dapat diketahui
bahwa semua perseroan terkena kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan,
karena penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat
dilihat pada bunyi pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan pada penjelasan
pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan
kegitan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan
usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang
dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber
daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan
sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya
III. 22
alam.Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak
berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.
Kritik yang muncul dari kalangan pebisnis bahwa CSR adalah konsep
dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.Kegiatan-kegiatan
itu adalah diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam
peraturan perundangan formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan
dan standar lingkungan hidup.Mereka berpendapat, jika diatur, selain
bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada
dunia usaha. CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut
pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses
interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan
CSR bisa karena tuntutankomunitas atau karena pertimbangannya
sendiri.Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.
Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi
pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang
diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk
orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan
yang melakukan penetapan dan penilaian standar.Yang juga harus diperhitungkan
adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para
aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus
melalui dialog bersama para pemangkukepentingan, seperti pelaku usaha,
kelompok masyarakat yang akan terkena dampak,dan organisasi pelaksana.
III. 23
Semua proses ini tidak mudah. Itu sebabnya di negara-negara Eropa yang
secara institusional jauh lebih matang dari pada Indonesia, proses regulasi yang
menyangkut kewajiban perusahaan berjalan lama dan hati-hati. European Union
sebagai kumpulan negara yang paling menaruh perhatian terhadap CSR, telah
menyatakan sikapnya, CSR bukan sesuatu yang akan diatur.21
Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal
dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bias
menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR
mengalami distorsi serius. Pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini
telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna
dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan
bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus
ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat
pemaknaannya dalam praktik.
22
21 Meuthia Ganie Rochman, “Meregulasi Gagasan CSR”, Kompas 10 Agustus 2007. 22 Robert Endi Jaweng, “Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT”, Suara Pembaruan 31 Juli 2007.
Dalam ranah norma kehidupan modern, kita dilingkupi dengan sejumlah
norma yakni norma hukum, moral, dan sosial. Tanpa mengabaikan kewajiban dan
pertanggungjawaban hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat pada
norma sosial sebagai bagian integral kehidupan masyarakat setempat. Konsep asli
CSR sesungguhnya bergerak dalam kerangka ini, dimana perusahaan secara sadar
memaknai aneka prasyarat tadi dan masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen
pelaksanaannya.
III. 24
Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna parsial
sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan
dari kehadiran sebuah perusahaan.Dengan demikian, bentuk program CSR hanya
terkait langsung dengan core business perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat
sekitar.Padahal praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan
terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program
langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung (bukan core business) seperti
rumah sakit, sekolah, dan beasiswa.Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan
aneka program tak langsung tersebut.
Ketiga, tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab
setiap subyek hukum, termasuk perusahaan.Jika terjadi kerusakan lingkungan
akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum.Setiap
dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan
setiap perusahaan harus bertanggung jawab.Dengan menempatkan kewajiban
proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini
cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal
menjadi sekadar pilihan tanggung jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru
bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial
(menurut UU PT) dan secara hukum (UUlingkungan hidup).Keempat, dari sisi
keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan
sebagai pelaku dan penangung jawab tunggal program CSR.23
23 Ibid
III. 25
Di sini masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya
menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi
mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang
terjadi.Tanggung jawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan
mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha social
kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat secara sosial
dan ekonomi.Namun pewajiban dalam suatu Undang-undang dapat memunculkan
multi tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai.
Maka dengan demikian wujud tanggung jawab sosial perusahaan pada
dasarnya telah tercermin dari pajak yang dipungut oleh negara, salah satunya
alokasi dana diperuntukan demi kepentingan pembangunan kesejahteraan
masyarakat atau tanggung jawab sosial yang seharusnya dikelola oleh pihak
pemerintah.Bahkan pihak KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)
termasuk tidak setuju atau secara terbuka menentang keras adanya kewajiban CSR
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang tertuang dalam pasal 74, yaitu
alasannya disatu sisi CSR merupakan tanggung jawab sukarela, tetapi disisi
lainnya bersifat Mandatoris atau memaksa (kewajiban) bagi setiap perusahaan
untuk melaksanakan program CSR tersebut (Media Indonesia, 04/02/2009), maka
Kadin, termasuk Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
dan Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) telah bersama-sama mengajukan
permohonan uji material pasal 74 tersebut kepada MK (Mahkamah
Konstitusi) yang menyangkut UU N0. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas,
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilakukan korporat
III. 26
tersebut harus dicabut, kata Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Kebijakan Publik,
Perpajakan dan Kepabeaan Sistem Fiskal dan Moneter, Haryadi B. Sukamdani.
Menurut alasan Hariyadi, pengaturan program CSR tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum, bersifat diskriminatif, dan membuat iklim usaha menjadi
tidak efisien serta tidak adil, artinya pasal 74, UU No. 40/2007 tersebut
merupakan materi hukum materiil yang mengatur kewajiban perseroan dan dapat
memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya dan hal-hal yang memberatkan
inilah perlu dilakukan uji material untuk mencabutnya dari UU perseroan baru
tersebut. "Kewajiban perusahaan adalah berusaha semaksimal untuk mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya, dan kemudian berkewajiban membayar pajak
kepada pemerintah. “Dengan membayar uang pajak tersebut dipergunakan untuk
mensejahterakan masyarakat, dan hal pelaksanaan CSR tersebut sudah menjadi
kewajiban pemerintah, bukan digeser ke setiap perusahaan,” tegas
Haryadi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan referensi pihak Kadin, tidak ada
satu negara di dunia-pun kecuali pemerintah Indonesia yang memasukan
kewajiban pelaksanaan program CSR bagi perusahaan, alasan keberatan Haryadi
dalam sidang Pleno pertama uji material pasal 74, UU No. 40/2007 di Gedung
MK, Jakarta (03/02/09).
Namun pada akhir MK tetap menolak Uji Material (Judical Review)
mengenai pasal 74, ayat 1, 2 dan 3 yang mewajibkan pelaksanaan Program
CSR bagi perusahaan, khususnya bergerak dibidang sumber daya alam yang telah
diajukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin tersebut (Koran Tempo, 16 April 2009),
karena program CSR tidak bertentangan dengan pasal 33, UUD '45 dan "Majelis
III. 27
melindungi hak konstitusional warga yang berada dilingkungan perusahaan
dengan mewajibkan perusahaan yang diuntungkan untuk membagi kekayaannya
untuk kemakmuran rakyat," ujar Mahfud MD di Jakarta.
Kemudian yang Kedua, dampak buruk dari demi komersialisasi atau
keserakahan dari prilaku dunia usaha yang berkelakuan tidak etis tersebut telah
banyak merusak kehidupan sosial atau mencemari lingkungan alam sekitarnya,
bahwa kini kesadaran sosial-masyakat tersebut berbalik menuntut dunia usaha
yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab moral dan sosial. Jika
kenyataannya banyak dilanggar oleh perusahaan raksasa bersangkutan dan
dampaknya banyak yang gulung tikar sebagai akibat telah mengabaikan kekuatan
sosial yang menghukumnya, dengan seringnya terjadi demonstrasi publik yang
memprotes prilaku negatif perusahaan baik secara internal atau eksternal, dan
produknya akan disabotase atau diblokir publiknya karena melakukan
pencemaran, menggunakan bahan kimia berbahaya atau polusi udara. Sebagai
akibatnya akan menimbulkan ketidakpuasan pekerjanya terhadap lingkungan
pekerjaan yang tidak nyaman serta iklim bekerja kurang kondusif, dan dampaknya
dapat menjerumuskan terjadinya kebankrutan perusahaan atau pemailitan usaha.
Ketiga, bentuk proses evolusi perusahaan dari tahapan kepemilikan pribadi
yang berubah menjadi milik publik, artinya secara tidak langsung perusahaan
tidak lagi sekedar institusi bisnis belaka, tetapi telah berubah menjadi institusi
sosial, dan konsekuensinya perubahan perusahaan tersebut sebagai institusi sosial
tidak lagi selalu berorientasi mencari keuntungan secara sepihak, dan secara
berimbang bahwa perusahaan yang bersangkutan untuk dituntut harus mampu
III. 28
memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya sebagai kegiatan prioritas utama
dalam rencana investasi perusahaan. Sesuai dengan konsep mainstream mengenai
pelaksanaan CSR yang diajukan oleh World Bank Group yang menyatakan,
bahwa pengertian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan
komitmen bisnis untuk dapat memberikan konstribusi bagi pembangunan
ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan karyawan serta pewakilannya,
keluarga karyawan, komuniti setempat dan hingga masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas hidup, dengan cara pihak perusahaan yang bermanfaat baik
dari aspek bisnisnya maupun demi kepentingan sosial dan pembangunan
perekonomian yang berkelanjutan (sustainability economic development).
Namun permasalahan mengenai regulasi tidak hanya berhenti disitu,
mengenai inkonsistensi terhadap pasal 74, UU No. 40/2007 yang akibatnya
menjadi multitafsir sendiri bagi para pihak penguaha dan pengamat sosial.
Terhitung sampai sekarang setelah diputuskannya UU oleh DPR belum ada tindak
lanjut dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP).Sebetulnya, kegiatan
CSR sudah berjalan tanpa adanya PP, bahkan sebelum adanya undang-undang
yang mengatur perseroan terbatas.Namun, dengan adanya PP tersebut kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih punya landasan.Ketiadaan PP
membuat sebagian perusahaan masih kebingungan dalam mengimplementasikan
program tanggung-jawab sosialnya. Yakni mengenai hal apa saja yang bisa
diperhitungkan sebagai CSR, dan bagaimana sistem auditnya itu masih belum
dijelaskan.
III. 29
Jadi dapat diartikan bahwasanya peliknya permsalahan CSR sampai
sekarang pun belum selesai, hal ini bisa dikatakan bahwasanya terjadi
inkonsistensi dalam regulasi mengenai CSR di Indonesia.
III.2.1.1 Fakta Lemahnya Implementasi CSR di Indonesia
Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi,
dan kesejahteraan sosial masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab
perusahaan besar saja, meskipun pada dasarnya mayoritas perusahaan yang
melakukan CSR adalah perusahaan besar. Dengan perkataan lain, perusahaan
kecil pun harus bertanggung jawab melakukan CSR. Di Indonesia, pelaksanaan
CSR sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan Chief Executive Officer (CEO)
sehingga kebijakan CSR tidak secara otomatis akan sesuai dengan visi dan misi
perusahaan. Hal ini memberikan makna bahwa jika CEO memiliki kesadaran akan
tanggung jawab sosial yang tinggi, maka kemungkinan besar CSR akan dapat
dilaksanakan dengan baik, sebaliknya jika CEO tidak memiliki kesadaran tentang
hal tersebut pelaksanaan CSR hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan
mendongkrak citra perusahaan di mata karyawan dan di mata masyarakat.
Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR di
Indonesia mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi dan
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang ada. Sebagai contoh UU Nomor
23 tahun 1997 Pasal 41 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan
“Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam
III. 30
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima
ratus juta rupiah.”
Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsung mengikat
sebagai tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan jera bagi para
pelaku tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan
lingkungan.Kasus kerusakan di lingkungan lokasi penambangan timah
inkonvensional di Pulau Bangka-Belitung dan tidak dapat ditentukan siapakah
pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi atas kegiatan
penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat yang tak berijin yang mengejar
setoran pada PT. Timah.Tbk. Sebagai akibat penambangan inkonvensional
tersebut terjadi pencemaran air laut dan perairan umum.Lahan menjadi tandus,
terjadi abrasi dan kerusakan laut.
Contoh lain adalah konflik antara PT Freeport Indonesia dengan rakyat
Papua. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan
hidup, penghancuran perekonomian, dan pengikaran eksistensi penduduk
Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diteima rakyat Papua akibat
keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Bencana kerusakan
lingkungan hidup dan komunitas lain yang ditimbulkan adalah jebolnya Danau
Wanagon hingga tiga kali (20 Juni 1998; 20-21 Maret 2000; 4 Mei 2000) akibat
pembuangan limbah yang sangat besar kapasitasnya dan tidak sesuai dengan daya
dukung lingkungan.
Kedua contoh tersebut hanya merupakan sebagian kecil gambaran
fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia, dan masih banyak lagi
III. 31
contoh kasus seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya, kasus Lumpur panas
Sidoarjo yang diakibatkan kelalaian PT Lapindo Brantas, kasus perusahaan
tambang minyak dan gas bumi, Unicoal (perusahaan Amerika Serikat), kasus PT
Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus suku Dayak dengan
perusahaan tambang emas milik Australia (Aurora Gold), dan kasus pencemaran
air raksa yang mengancam kehidupan 1,8juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah
yang merupakan kasus suku Dayak vs “Minamata.”
Hal terpenting yang harus dilakukan adalah membangkitkan kesadaran
perusahaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Hal ini
menuntut perlunya perhatian stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha dalam membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama antara
pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai keefektifan program CSR. Tidak dapat
dipungkiri peran UU sebagai bentuk legalitas untuk mengatur pelaksanaan CSR
sangat diperlukan.
Disamping itu, untuk meningkatkan keseriusan perhatian dan tingkat
kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat, diperlukan adanya suatu alat evaluasi untuk menilai tingkat
keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program CSR. Hasil dari penilaian
yang dilakukan oleh lembaga penilai independen dapat dijadikan sebagai dasar
untuk pemberian penghargaan dalam bentuk award atas peran serta perusahaan
terhadap komunitas sekitar. Pada bagian selanjutnya akan dibahas beberapa kisah
sukses implementasi CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan domestik dan
III. 32
bentuk-bentuk partisipasi perusahaan tersebut dalam pengembangan masyarakat,
ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Di antara permasalahan yang harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja
yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin
dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan
dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggung jawab
sosial.Pewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan
tidaklah tepat. Hal ini karena:
• Pemerintah telah mengatur tentang LH, Perlindungan Konsumen, Hak
Asasi Manusia, Perburuhan dan sebagainya pada masing-masing UU
tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UUPT.
• Kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar (Dunia
Usaha, Pemerintah dan Masyarakat), berkaitan dengan 7 masalah pokok,
melebihi kewajiban dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat
sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika.
• Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas
dilakukan oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia.
• Pemerintah & masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani
masalah sosial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh
Dunia Usaha.
Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi
masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama
Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini
III. 33
justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan
pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program
semua stakeholders pembangunan.
Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu
yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan
program pemda dalam kerangka pembangunan regional.Untuk Indonesia,
pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum,
dan jaminan ketertiban sosial.
Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan
regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini.Di tengah persoalan
kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus
berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa
menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan
pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan
memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar
ini. Pemerintah juga dapatmengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan
kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan
menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir
ini amat diperlukan, terutama di daerah.
Motif dasar dari semua konsep itu hanyalah strategi kaum neoliberal untuk
tetap bisa melanggengkan hegemoni kapitalisme. CSR hanyalah alat penaklukan
dalam kerangka sosial dan lingkungan dengan motif dasar yang tidak berubah,
yaitu motif utama pengusahaan keuntungan sebesar mungkin dan akumulasi
III. 34
kapital. Hal ini mendapat dukungan fakta empiris dari terus berlanjutnya proses
pemiskinan dan marginalisasi kelompok-kelompok masyarakat rentan (a.l.:
masyarakat adat, kaum buruh, kaum miskin kota; anak-anak dan perempuan) serta
degradasi lingkungan termasuk punahnya berbagai spesies hingga kehancuran
lapisan ozon yang disebabkan oleh eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan
raksasa.
CSR merupakan sebagai tujuan dari kerangka besar kapitalisme, dimana
CSR itu sendiri sebagai alat untuk mempermudah keberadaan korporasi itu di
tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat pun mengakui keberadaan
korporasi dengan agenda CSR yang dijalankan.
III.2.1.2 Proses Pelaksanaan dan Hasil
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering
diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang
mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan
pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensimasyarakat
lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain
dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga
kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra
sebagai perusahaan yang ramah dan pedulilingkungan. Selain itu, akan tumbuh
rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari
III. 35
masyarakat sehingga masyarakatmerasakan bahwa kehadiran perusahaan di
daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.24
Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat
luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan
posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya
kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.CSR adalah bukan hanya
sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam
pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan
akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan,
termasuk lingkungan hidup.Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat
keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal
dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku
kepentinganinternal.
25
Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus
merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi
usahanya.Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya
wajar bila perusahaan memperhatikankepentingan masyarakat.Kedua, kalangan
bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis
mutualisme.Ketiga, kegiatantanggung jawab sosial merupakan salah satu cara
untuk meredam atau bahkan menghindari konflik social.
26
24Ibid 25A.B. Susanto, Membumikan Gerakan Hijau, Majalah Ozon, Edisi No.5 Februari 2003 26Ibid
III. 36
Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan
tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:27
Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau
kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Program
pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:
a. Public Relations
Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas
tentangkegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Strategi defensif
Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negative
komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk
melawan serangan negatif dari anggapan komunitas.Usaha CSR yang dilakukan
adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan
menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.
c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan
28
1. Community Relation
Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangankesepahaman melalui
komunikasi dan informasi kepada para pihak yangterkait.Dalam kategori ini,
program lebih cenderung mengarah pada bentukbentuk kedermawanan (charity)
perusahaan.
27Himawan Wijanarko, Reputasi, Majalah Trust, 4-10 Juli 2005 28Ibid
III. 37
2. Community Services
Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau
kepentingan umum.Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada
di masyarakat dan pemecahan masalahdilakukan oleh masyarakat sendiri
sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah
tersebut.
3. Community Empowering
Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih
luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan
usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah
mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaanmemberikan akses kepada
pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut.Dalam kategori ini, sasaran
utama adalah kemandirian komunitas.
Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan
nilaitambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap
tenagakerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya
substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan
perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder
yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program
pengembangan masyarakat sekitarnya.
Pada saat ini di Indonesia, praktek CSRbelum menjadi perilaku yang
umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan
globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin
III. 38
besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSRmenjadi kewajibanbaru standar
bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada
akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000on Social Responsibility,
sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program
CSR dijalankan oleh perusahaan apabilamenginginkan keberlanjutan dari
perusahaan tersebut. CSRakan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam
perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan
kesetiaanmerek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan
menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para
pesaing.
Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk
membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan
merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan
CSRadalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian
akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win
situation) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan,
produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan
dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.
Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak
korporasi.Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan
misi korporasi.Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi,
besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang
benar.Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan
III. 39
kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi)
serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar
kosmetik.
Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan
lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ideal
bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang
penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan
foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah
direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program
CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari
semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR.
Keraguan akan kesungguhan implementasi CSR harus diakui juga
diperburuk oleh kinerja CSR yang dilakukan oleh berbagai korporasi sejauh ini.
Di tataran praktik, implementasi CSR masih kerap menunjukkan kecenderungan
sebagai kegiatan kosmetik.Ia menjadi sekedar fungsi kepentingan public relations,
citra korporasi atau reputasi dan kepentingan perusahaan untuk mendongkrak nilai
di bursa saham. CSR hanya dilakukan sebagai pemenuhan kecenderungan global
tanpa substansi distribusi kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.
Praktek CSR di indonesia menjatuhkan CSR pada praktek pembangunan
brand image belaka sehingga terkesan imagesentris dan mendahulukan program-
program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategi komunikasi) dibandingkan
melihat kedalam perusahaan yang pada dasarnya memiliki posisi yang sama
III. 40
didalam stakeholder CSR, yaitu buruh. Di satu sisi mengklaim telah
meningkatkan standar sosial dan lingkungan pada proses operasi atau di
perusahaan intinya, akan tetapi secara bersamaan menutup mata pada pelanggaran
standar perburuhan atau lingkungan.
III.3 Ideologi CSR di Indonesia
Lester Thurow, tahun 1966 dalam bukunya “The Future of Capitalism”,
sudah memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, kapitalisme akan berjalan
kencang tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan, musuh utamanya, sosialisme dan
komunisme telah lenyap.Pemikiran Thurow ini menggaris bawahi bahwa
kapitalisme tak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga
memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau
yang kemudian disebut sustainable society. Pada jamannya, pemikiran Thurow
tersebut sulit diaplikasikan, hal ini ia tuliskan seperti there is no social ‘must’ in
capitalism.29
29 AB Susanto, A Strategic Management Approach, CSR, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hlm.21
Jaman pun berlalu, tahun 1962, Rachel Calson lewat bukunya
“TheSilent Spring”, memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan
dankehidupan yang diakibatkan oleh racun peptisida yang mematikan.Paparan
yang disampaikan dalam buku “Silent Spring” tersebut menggugah kesadaran
banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju
kehancuran bersama.Dari sini CSR (Corporate Social Responsibility) pun mulai
digaungkan.Tepatnya di era 1970-an. Banyak professor menulis bukutentang
III. 41
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, di samping kegiatan mengeruk
untung. Buku-buku tersebut antara lain; “Beyond the Bottom Line”
Karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar Professor
of Public Polecy and Business Responsibility dari Universitas
Columbia.Pemikiran para ilmuwan sosial di era itu masih banyakmendapatkan
tentangan, hingga akhirnya muncul buku yang menghebohkandunia hasil
pemikiran para intelektual dari Club of Roma, bertajuk “The Limits to Growt”.
Buku ini mengingatkan bahwa, disatu sisi bumi memilikiketerbatasan daya
dukung (carrying capacity), sementara di sisi lain populasimanusia bertumbuh
secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber dayaalam mesti dilakukan
secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.Era 1980 – 1990, pemikiran
dan perbincangan tentang issu ini terus berkembang, kesadaran dalam berbagi
keuntungan untuk tanggungjawab sosial, dan dikenal sebagai community
development.
Dari sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam
berbagai bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya Built toLast:
Successful Habits of Visionary Companies (1994), menyampaikan bukti bahwa
perusahaan yang terus hidup adalah yang tidak semata mencetak limpahan uang
saja, tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungansosial dan turut
andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.30
30 Ibid, hlm.35
III. 42
Konsep dan pemikiran senada juga ditawarkan oleh John Elkington lewat
bukunya yang berjudul “Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line ofTwentieth
Century Business. Dalam bukunya ini, Elkington menawarkan solusi bagi
peusahaan untuk berkembang di masa mendatang, di mana mereka harus
memperhatikan 3P, bukan sekedar keuntungan (Profit), juga harus terlibat dalam
pemenuhan kesejahteraan rakyat (People) dan berperan aktif dalam menjaga
kelestarian lingkungan (Planet).31
Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya
KTT Bumidi Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development
(pembangunanberkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh
negara, tapi terlebiholeh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin
menggurita. Tekanan KTT Rio,terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry
Porras meluncurkan Built To Last;Succesful Habits of Visionary Companies di
tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan,mereka menunjukkan bahwa perusahaan-
Gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama duapuluh tahun
terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil
danjaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah
perilakukorporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang
tidak fair dantidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan
sebagai kejahatankorporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat
merasakan jatuhnyareputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.
31 diakses dari http://www.csrindonesia.com pada tanggal 13 september 2011 pukul 20.50
III. 43
perusahaan yang terus hidup bukanlahperusahaan yang hanya mencetak
keuntungan semata.Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth
Summit) di Rio deJaneiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma
pembangunan, daripertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi
pembangunan yang berkelanjutan(sustainable development).Dalam perspektif
perusahaan, di mana keberlanjutandimaksud merupakan suatu program sebagai
dampak dari usaha-usaha yang telahdirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan
rekanan dari masing-masing stakeholder.Ada lima elemen sehingga konsep
keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;(1) ketersediaan dana, (2)
misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4)terimplementasi dalam kebijakan
(masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5)mempunyai nilai
keuntungan/manfaat.32
Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin
duniamemunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep
sebelumnyayaitu economic dan environment sustainability.Ketiga konsep ini
menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
(Corporate SocialResponsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di
Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian
media dari berbagai penjuru dunia.Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan
untuk menunjukkan tanggung jawab danperilaku bisnis yang sehat yang dikenal
dengan corporate social responsibility.
33
32 Dhaniri, Mas Achmad. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hal 3. 33 Ibid
III. 44
Teori kritis menyatakan bahwa sejak lahir subyek (manusia/masyarakat)
telah berhadapan dengan entitas-entitas di sekelilingnya. Entitas-entitas tersebut
adalah negara, agama, pengetahuan, dan investasi.Dapat diprediksi bahwa
kesibukan dari subyek adalah melakukan kompromi atau resisten. Kompromi
berarti subyek mengafirmasi seluruh entitas-entitas tersebut dan resisten berarti
subyek beroposisi terhadap satu entitas dan di sisi lain berkompromi dengan
entitas lainnya pada saat yang sama.
Berdasarkan pada karakterisasi yang penulis temukan, dapat disebutkan
bahwa CSR Indonesia menganut ideologi atau berpihak pada investasi.ideologi,
nalar kerja, serta logika yang dianut oleh CSR di Indonesia juga dianut oleh CSR
dibelahan dunia.
Investasidilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau
keuntungan di kemudian hari.Investasi meryupakan salah satu plihan langkah
untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di kemudian hari. Yang harus
diperhatikan dalam melakukan investasi adalah: kita harus memiliki ketersediaan
dana maupun aset, serta komitmen mengikatkan aset tersebut pada saat sekarang.
CSR merupakan sebuah langkah investasiguna dengan tujuan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dapat kita lihat
pertumbuhan atau perkembangan CSR yang menjadi respon internasional dan
selalu berkembang hingga lahirnya ISO 26000 sebagai standarisasi pelaksanaan
CSR.
Keberadaan CSR itu sendiri di tengah masyarakat Indonesia sudahlah
tampak jelas, bahwasanya keberadaan CSR merupakan win-win solution agar
III. 45
nantinya masyarakat lah mengakui keberadaan korporasi. Diamana nantinya
masyarakat akan dipertemukan dengan permasalahan akibat proses produksi yang
dilakukan oleh korporasi, tentang kerusakan lingkungan, pecemaran udara dll, dan
menjadikan CSR ini sebagai suatu alternatif penyelesaian dari permasalahn yang
dihadapi, sehingga tanpa disadari masyarakat akan menggantngkan kehidupanya
terhadap CSR dari perusahaan tersebut.
Meskipun pada akhirnya, sebagian besar korporasi memberikan kebebasan
kepada masyarakat dalam menentukan aktifitas CSR itu sendiri dengan
mengedepankan bentuk community development namun yang terjadi ialah
kebebasan itu sendiri bukan lahir atas inisiatif masyarakat di sekitar korporasi
akan tetapi merupakan sebuah kebebsan yang terberi dari korporasi, sehingga
yang terjadi keberadaan korporasi itu harus mereka terima walaupun pada proses
jalanya produksi korporasi akan mengeksploitasi habis sumber daya alam di
lngkngan mereka dan menyebabkan proses perusakan ingkungan akibat proses
produksi.
Dengan Ideologi invesatasi yang dianut oleh CSR di Indonesia, dapat
ditarik sebuah benang merah bahwasanya system ekonomi yang di Indonesia ialah
memihak dengan pasar atau TNC/MNC dengan melihat keberadaan CSR yang
semakin kuat yang ditandai dengan penetapan regulasi oleh pemerintah atau
negara.
IV. 1
BAB IV
PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
Berangkat dari analisis dan temuan dalam uraian bab sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR Indonesia terdapat inkonsistensi, hal ini
ditunjukan dengan carut marut nya regulasi yang megatur pelaksnaan CSR itu
sendiri dikarenakan setelah diputuskannya pasal 74 dalam UU PT tidak ada
pengawalan lebih lanjut mengenai PP yang harusnya ada untuk mengatur apa
yang disebut CSR itu sendiri dan bagaimana proses pelaksanaanya.
CSR merupakan sebuah tawaran kepada masyarakat dengan tujuan
menolong keberadaan korporasi untuk tetap melakukan proses produksi
dengan menekankan melalui program CSR sebagai timbal balik dr perusahaan
tersebut terhadap masyarakat sekitar.
Meskipun korporasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
memlakukan program terhadap aktifitas CSR nya, namun kebebasan yag
diberikan hanyalah bersifat semu, karena apapun kebebesan yang telah dipilh
oleh masyarakat itu sendiri merupakan kebebasan yang terberi oleh pihak
korporasi.
Ideologi CSR di Indonesia adalah ideologi investasi, karena CSR itu
sendiri merupakan investasi jangka panjang selain modal yang bersifat sosial
dalam kedudukannya di masyarakat. Dengan program CSR yang diberikan,
diharapkan masyarakat akan menerima CSR sebagai solusi mengenai
IV. 2
permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan CSR itu sebagai jalan
keluar.
Selain itu, karena desakan Internasional. Negara pun akhirnya
memberikan jalan terbuka lebar kepada pihak korporasi menginvestasikan
modalnya dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam melalui regulasi
untuk menetapkan CSR sebagai suatu hal yang diwajibkan meskipun sampai
sekarang masih menjadi kontroversi. Dengan ideologi investasi yang dianut
oleh CSR di Indonesia, dapat kita tarik suatu benang merah bahwa perilaku
sistem ekonomi yang ada pada CSR di Indonesia adalah sistem ekonomi
kapitalistik yang jelas karena keberpihakannya dengan korporasi. Hal tersebut
semakin mengukuhkan kekuasaan dari pengusaha industri dalam mengelola
sumber daya yang ada di Indonesia hanya demi kepentingan pribadi bukan
demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal ini jelas
bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33, karena pada hakekatnya Negara lah
yang harus mengelola aset-aset strategis yang berhubungan dengan
kelangsungan hajat hidup orang banyak.
IV.2 Saran
Dari hasil penelitian ini, penulis hendak meberikan saran atau rekomendasi
yang nantinya dapat bermanfaat mengenai permasalahan CSR yang ada, saran
tersebut ialah pemerintah hendaknya segera membuat regulasi yang tepat
dalam mengatur CSR itu sendiri melalui PP (Peraturan Pemerintah), PP ini
DP-1
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Vogel, D. J. 2005. The market for virtue: the potential and limits of corporate
social responsibility. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Keck, M. E., & Sikkink, K. 1998. Transnational advocacy networks in
international politics: introduction. In M. E. Keck, & K. Sikkink (Eds.),
Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics.
Ithaca: Cornell University Press.
Jepperson, R. L. 1991. Institutions, institutional effects, and institutionalism. In W.
W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in
organizational analysis: Chicago: University of Chicago Press.
Cutler, C. A., Haufler, V., & Porter, T. (Eds.). 1999. Private authority and
international affairs. Albany, NY: SUNY Press.
Archie B. Carroll, A History Corporate Social Responsibility, THE OXFORD
HANDBOOK OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, A. Crane,
A. McWilliams, D. Matten, J.Moon and D. Siegeleds, 2008.
Adams, Ian. 2004. Ideologi Politik Mutakhir. Yogyakarta. Penerbit Qalam
Poloma, Margaret M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. Rajawali Press.
Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta:
Kencana.
Brewer, John D. 2005. Ethnography. Buckingham. Open University Press.
DP-2
Hardiman, F. Budi. 2003. Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan
Kepentingan. Yogyakarta:Kanisius.
AB Susanto. 2007. A Strategic Management Approach, CSR. The Jakarta
Consulting Group: Jakarta.
Kotler, Philip. 2007. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause.,
Thomas Dunne Books: New York.
Susanto, A.B. 1997. Budaya Perusahaan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Kant, Imannuel, 1996, Critique of Pure Reason, New York, Doubleday &
Company Inc. Hlm. xiii.
Hegel, G.W.F.1977. Phenomenology of Spirit. Oxford. Clarendon Press.
Marx, Karl. I981. Early Writings. London. Penguin Books.
Marx, Karl. 1962. “Preface of a Contribution to the Critique of Political
Economy”. Dalam Marx and Engels. Selected Works. Vol.1. Moscow.
Foreign Languages Publishing House.
Horkheimer, Max dan Theodore W. Adorno. 1973. Dialectic of Enlightment.
London: Allen Lane.
Kolakowski, Bdk Leszek. 1978. Main Current of Marxism Vol. II: The
Breakdown. Oxford: Clarendon Press.
Lih.K.Bertens, (1976), Ringkasan Sejarah Filasafat, Yogyakarta:Kanisius.
Sindunata. 1982. Dilema Usaha Manusia Rasional. Jakarta: Gramedia.
Jay, Martin. 2005. Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam
Perkembangan Teri Kritis. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
Susanto, A.B. 1997. Manajemen Aktual. Jakarta: Grasindo.
DP-3
Jurnal
Levy, D. L., & Newell, P. 2006. Multinationals in global governance. In S.
Vachani (Ed.), Transformations in global governance: Implications for
multinationals and other stakeholders. London: Edward Elgar
Sell, S. K., & Prakash, A. 2004. Using ideas strategically: The contest between
business and NGO networks in intellectual property rights. International
Studies Quarterly, 48(1)
Bierman, F. 2001. The emerging debate on the need for a World Environment
Organization. Global Environmental Politics, 1(1)
Utting, P. 2000. Business responsibility for sustainable development. Geneva:
United Nations Research Institute for Social Development.
Levy, D. L. 1997. Environmental management as political sustainability.
Organization and Environment, 10(2)
Doh, J. P., & Guay, T. R. 2006. Corporate social responsibility, public policy,
and NGO activism in Europe and the United States: An institutional-
stakeholder perspective. Journal of Management Studies, 43(1)
Sethi, P. 2002. Corporate codes of conduct and the success of globalization.
Ethics & International Affairs, 16(1)
Gill, S. 1995. Globalisation, market civilisation, and disciplinary neoliberalism.
Millenium: Journal of International Studies, 24(3)
Carroll, W. K., & Carson, C. 2003. The network of global corporations and policy
groups: A structure for transnational capitalist class formation? Global
Networks, 3(1)
DP-4
Murphy, D. F., & Bendell, J. 1999. Partners in time? Business, NGOs, and
sustainable development. Geneva: United Nations Reserach Institute for
Social Development.
Banerjee, S. B. 2003. Who sustains whose development? Sustainable development
and the reinvention of nature. Organization Studies, 24(2)
Dhaniri, Mas Achmad. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
HAM Hardiansyah. 2007. CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi,
Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan.
Hopkins, M. 2007. Corporate Social Responsibility and International
Development. Is Business the Solution?. Earthscan.
Yanuar Nugroho. 2007. “Commodum Totti Topulo: The Benefit is for the Whole
Society”.
Harahap, Yahya M. 2007. Sinopsis UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Akbar, Roby. 2007. “Benang Kusut Regulasi CSR”.
Makalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2006. “Proper Sebagai
Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan”.
Indonesia Business Links. 2007. “Integrating CSR a Business Strategy: How to
adopt CEO values into CSR Policies”. Jakarta.
Koran & Majalah
Rochman, Meuthia Ganie. “Meregulasi Gagasan CSR”. Kompas 10 Agustus
2007.
DP-5
Jaweng, Robert Endi. “Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT”. Suara Pembaruan
31 Juli 2007.
Jalal. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”. Koran Tempo, 26
September 2006.
Susanto, A.B. Paradigma Baru “Community Development”. Harian Kompas, 22
Mei 2001.
Mas Achmad, Daniri & Maria Dian Nurani. “Menuju Standarisasi CSR”. Harian
Bisnis Indonesia, 19 Juli 2007.
Susanto, A.B. CSR dalam Perspektif Ganda. Harian Bisnis Indonesia, 2
September 2007.
Susanto, A.B. Membumikan Gerakan Hijau, Majalah Ozon, Edisi No.5 Februari
2003.
Wijanarko, Himawan. Filantrofi bukan Deterjen, Majalah Trust, 11-17 September
2006.
Wijanarko, Himawan. Reputasi. Majalah Trust. 4-10 Juli 2005
Internet
http://www.csrindonesia.com
http://www.wikipedia.com
Nugroho, Yanuar. 2007. “Commodum Totti Topulo: The Benefit is for the Whole
Society”. diakses dari http://www.audentis.wordpress.com pada tanggal 25
oktober 2-11 puku 21.30 wib
DP-6
Akbar, Roby. 2007. “Benang Kusut Regulasi CSR”, diakses dari
http://www.roryakbar.wordpress.com pada tanggal 20 september 2011
pukul 13.00 wib
Effendi, Muhammad Arief. 2007. “Implementasi GCG Melalui CSR”, diakses
dari http://www.muhariefeffendi.wordpress.com diakses pada tanggal 1
september 2011 pukul 20.30 wib