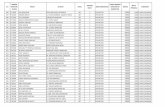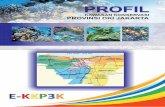Media Konservasi Volume X/Nomor 1, Juni 2005
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Media Konservasi Volume X/Nomor 1, Juni 2005
Media
KONSERVASI Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan
ISSN 0251-1677 Volume X/Nomor 1, Juni 2005
Artikel KETERSEDIAAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DI DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO (Agricultures Labour Availability in the Bufferzone of Gunung Gede Pangrango National Park) Sambas Basuni dan Tatang Kurniawan ..........................................................................................................................
1 PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TATA RUANG KEPULAUAN
SERIBU (Conservation of Local Vegetation in the Space Development of Kepulauan Seribu) Nyoto Santoso .................................................................................................................................................................
7 PENYEBARAN DAN KARAKTERISTIK SARANG BERBIAK KOMODO (Varanus komodoensis Ouwens, 1912)
DI LOH LIANG PULAU KOMODO TAMAN NASIONAL KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR M. Muslich dan Agus Priyono .........................................................................................................................................
13 PENCEMARAN INSEKTISIDA PADA TIGA SPESIES BURUNG AIR (PECUK HITAM, KUNTUL
KECIL, DAN BLEKOK SAWAH) DI AREAL PERSAWAHAN SUKAMANDI, SUBANG, JAWAB BARAT (Insecticides Pollution on the Three Water Bires Species (Little Black Cormorant, Little Egret and Javan Pond Heron) in Rice-Field at Sukamandi, Subang, West Java) Lin Nuriah Ginoga ..........................................................................................................................................................
21
EKONOMI REHABILITASI DAERAH TANGKAPAN WADUK (Rehabilitation Economic of Dam Catchment
Area) Sudarsono Soedomo .......................................................................................................................................................
27 LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT OF MINAGKABAU LAND (Perencanaan dan Pengelolaan
Lanskap Minangkabau) Nandi Kosmaryandi ........................................................................................................................................................
31
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Media
KONSERVASI
Media Konservasi diterbitkan oleh Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, merupakan jurnal ilmiah bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan lingkungan, berupa hasil penelitian maupun telaah pustaka. Redaksi menerima sumbangan artikel, dengan ketentuan penulisan artikel seperti tercantum pada halaman dalam sampul belakang.
Terakreditasi : SK Dirjen DIKTI Nomor : 118/DIKTI/Kep/2001
DEWAN REDAKSI
Pengarah : Dekan Fakultas Kehutanan IPB
Penanggung Jawab : Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB
Dewan Redaksi : Burhanuddin Masy’ud Rachmad Hermawan Agus Hikmat Abdul Haris Mustari Siti Badriyah Rushayati Resti Melani
Dewan Editor : Hadi S. Alikodra Machmud Thohari Ervizal A.M. Zuhud Ani Mardiastuti E.K.S. Harini Muntasib
Alamat Redaksi : Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, P.O. Box 168, Bogor 16001
Telepon / Fax. : (62-251) 621947 E-mail : [email protected]
Bagi para pembaca dan yang berminat untuk berlangganan, surat menyurat dan permintaan berlangganan dapat menghubungi redaksi dengan alamat di atas.
i
PENGANTAR REDAKSI
Penerbitan jurnal ilmiah Media Konservasi Vol. X No. 1 Juni 2005 ini menyajikan lima penting baik yang terkait dengan satwalira (wildlife), taman nasional, pencemaran maupun ekonomi sumberdaya alam serta perencanaan dan pengelolaan lansekap.
Seperti diketahui keberadaan taman nasional dan pelestariannya tidak dapat dilepaspisahkan dari keberadaan
masyarakat sekitarnya, khususnya yang terkait dengan tenaga kerja. Untuk memberikan gambaran terkait dengan hal ini, disajikan artikel tentang ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga taman nasional. Selain itu juga disajikan tulisan yang terkait dengan ekonomi rehabilitasi daerah tangkapan waduk, pelestarian vegetasi lokal dalam kaitan dengan pengembangan tata ruang di Kepulauan Seribu, penyebaran dan karakteristik sarang berbiak komodo, pencemaran insektisida pada tiga spesies burung, serta perencanaan dan manajemen lansekap Minangkabau.
Kita percaya tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam ikut memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan dan teknologi khususnya yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan lingkungan hidup.
Selamat menyimak, semoga bermanfaat.
Redaksi
UCAPAN TERIMA KASIH
Media Konservasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang seting-tinggi tingginya kepada para pakar yang telah menelaah tulisan/karya tulis yang dimuat pada edisi ini. Dr Ir Rinekso Soekmadi, MSc.F., Studio Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan
dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Yeni A. Mulyani, MSc., Laboratorium Ekologi Satwa Liar, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Agus Hikmat, MSc.F., Laboratorium Konservasi Tumbuhan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Lilik B. Prasetyo, Laboratorium Analisis dan Spasial Lingkungan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5
1
KETERSEDIAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DI DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
(Agricultures Labour Availability in the Bufferzone of Gunung Gede Pangrango National Park)
SAMBAS BASUNI1 DAN TATANG KURNIAWAN2)
1)Pengajar Studio Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, PO Box 168, Bogor 16001
2)Alumni Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Po Box 168, Bogor 16001
ABSTRACT
Ability of buffer zone in protecting conservation area depends very much on development of economic opportunity of the buffer zone area itself. The objective of this research was to provide description on economic condition of the buffer zone of Gunung Gede – Pangrango National Park (TNGP) based on economic indicators, particularly the availability of labor in agriculture sector. Method of Location Quotient (LQ) was applied to describe whether the agriculture labor in buffer zone constituted the base sector or not. Employment Surplus Index (ESI) was used to calculate surplus of agriculture labor while Shift Share Analysis (SSA) was used to show shift in labor availability in agriculture sector. Research results showed that agriculture sector labor in buffer zone of TNGP constituted the base sector and implied that agriculture sector possessed extra labor. In general, villages in buffer zone of TNGP showed very dynamic shift of labor availability in agriculture sector. Excess labors were considered as labors that serve export market. Considering that ratio of agriculture land size to number of inhabitants in buffer zone of TNGP was very small, accompanied by low level of education and skill of the inhabitants whose livelihood was limited on skill based on land and natural resources, it can be predicted that export of excess labors in buffer zone villages will go to TNGP area in the form of forest area disturbance. Therefore, one of the attempts to overcome the problem of agriculture labor surplus was seeking potency and development of farmer ability in non agriculture job.
Key words : bufferzone, agriculture labor availability, economic indicators
PENDAHULUAN
Terjadinya gangguan kawasan konservasi yang berasal dari penduduk yang tinggal di daerah penyangganya sangat sering terjadi, termasuk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP). Permasalahan konservasi kawasan TNGP adalah rendahnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan TNGP (Sensudi, 2000). Sebanyak 78,28% penduduk di daerah penyangga TNGP adalah petani, 41% dari total penduduknya adalah buruh tani. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduknya kurang dari 0,25 ha. Dilihat dari struktur kepemilikan luas lahannya, 74,08% penduduk sekitar TNGP memiliki lahan kurang dari 0,5 ha (Basuni, 2003). Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan garapan yang sempit dan banyaknya penduduk yang berstatus sebagai buruh tani akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat di daerah penyangga TNGP dan terjadinya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian. Oleh karena itu, rendahnya pendapatan petani dan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ini harus menjadi faktor pertimbangan dalam konservasi kawasan, khususnya dalam pembinaan daerah penyangga, karena secara aktual maupun potensial akan
mengarah pada terjadinya tekanan kawasan TNGP yang lebih besar.
Selama periode 1998-1999, sekitar 17,88 ha kawasan TNGP telah dirambah penduduk untuk dijadikan lahan pertanian (Kusnoto, 2000). Bentuk gangguan terhadap kawasan TNGP lainnya adalah pencurian hasil hutan baik tumbuhan maupun satwaliar. Ganggaun terhadap TNGP terjadi di hampir seluruh Resort Polisi Hutan dan sepanjang tahun. Basuni (2003) menyatakan bahwa kejadian pencurian hasil hutan di kawasan TNGP cenderung tinggi pada musim kemarau (bulan Maret-Juli). Musim kemarau merupakan waktu “menganggur” bagi penduduk di daerah penyangga TNGP karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tani. Pada musim kemarau, waktu dan tenaga yang dimiliki penduduk akan lebih banyak digunakan untuk melakukan kegiatan lain di luar kegiatan bercocok tanam. Mencari dan mengambil hasil hutan dari kawasan hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari merupakan salah satu kemungkinan kegiatan yang dipilih oleh penduduk sekitar kawasan TNGP. Secara kuantitas, gangguan terbesar terjadi di kawasan TNGP wilayah Kabupaten Bogor, kemudian wilayah Sukabumi, dan terendah di wilayah Kabupaten Cianjur.
Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
2
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian wilayah daerah penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) berdasarkan indikator tenaga kerja sektor pertanian dengan menggunakan pendekatan teori basis ekonomi (Bendavid, 1974). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen TNGP dan pemerintah daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di lima desa daerah penyangga TNGP, pada bulan Juni-Juli 2003. Desa contoh diambil secara purposive berdasarkan prinsip keterwakilan dan besarnya gangguan terhadap TNGP, yaitu Desa Bojong Murni dan Desa Sukagalih (Kabupaten Bogor), Desa Cihanjawar dan Desa Sukamulya (Kabupaten Sukabumi), dan Desa Ciputri (Kabupaten Cianjur). Data yang dikumpulkan adalah data tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total tingkat desa dan kecamatan. Data bersumber dari berbagai dokumen yang relevan yang tersedia di desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk menghitung besarnya peranan tenaga kerja sektor pertanian terhadap perekonomian daerah penyangga, data dianalisis dengan menggunakan metode LQ (Location Quotient), untuk menghitung besarnya kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian digunakan ESI (Employment Surplus Index), dan untuk menunjukkan performance tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP digunakan metode SSA (Shift Share Analysis). Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:
1. Location Quotient (LQ)
LQ = Xij/Xit
Xtj/Xtt
Keterangan :
LQ = Location Quotient Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah
desa ke-i Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor
produksi di wilayah desa ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di
wilayah kecamatan Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor
produksi di wilayah kecamatan 2. Employment Surplus Index (ESI)
2.1. ESIa = Xij – (Xit/Xtt)Xtj (Keterangan : ESIa = ESI model absolut)
2.2. ESIr = [Xij – (Xit/Xtt) Xtj] / Xit x 100 % (Keterangan : ESIr = ESI model relatif)
3. Shift Share Analysis (SSA)
SSA = (Xtt(1) /Xtt(0) – 1) + (Xtj(1) /Xtj(0) – Xtt(1) /Xtt(0) ) + (Xij(1) /Xij(0) – Xtj(1) /Xtj(0))
a b c
Keterangan :
SSA = Shift Share Analysis
a = komponen share (menyatakan laju pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjuk-kan dinamika)
b = komponen proportional shift (menyatakan pertum-buhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah
c = komponen differential shift (menjelaskan bagaimana daya kompetisi suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan total sektor atau aktivitas dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keung-gulan atau ketidakunggulan) suatu sektor atau aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di wilayah lain.
Xij(1) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah desa ke-i pada tahun akhir
Xij(0) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah desa ke-i pada tahun awal
Xtj(1) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah kecamatan pada tahun akhir
Xtj(0) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah kecamatan pada tahun awal
Xtt(1) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kecamatan pada tahun akhir
Xtt(0) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kecamatan pada tahun awal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Data tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total yang berhasil dikumpulkan dari lima desa contoh disajkan pada Tabel 1. Rentang waktu awal dan akhir berkisar antara 3 – 8 tahun tergantung pada ketersedian data di masing-masing desa dan kecamatannya.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5
3
Tabel 1. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total tingkat desa dan kecamatan
No. Desa/Kecamatan Tahun
Awal/ Akhir Tenaga Kerja Sektor Pertanian
(orang) Tenaga Kerja Total
(orang)
1 Desa Bojong Murni
1998 543 1406 2001 683 1700
Kec. Ciawi 1998 7479 24317 2001 8624 28884
2 Desa Sukagalih
1996 778 1503 2002 767 1718
Kec. Megamendung 1996 5156 23096 2002 5170 23160
3 Desa Cihanjawar
1996 1608 1775 2003 2250 2479
Kec. Nagrak 1996 12662 31624 2003 16725 36731
4 Desa Sukamulya
1996 3420 3995 2003 4403 4851
Kec. Caringin 1996 5383 15030 2003 5932 16559
5 Desa Ciputri
1996 2183 3456 2002 2927 4646
Kec. Pacet 1996 35983 77274 2002 35191 83341
Sumber : BPS Kabupaten, Monografi Kecamatan, danProfil Desa yang bersangkutan (diolah) Peranan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Hasil pengolahan terhadap data dalam Tabel 1, diperoleh nilai LQ dan ESI seperti tertera dalam Tabel 2. Tabel 2. Nilai LQ (Location Quitient) dan nilai ESI (Emloyment Surplus Index) desa-desa daerah penyangga TNG
No. Desa LQ ESIa (orang) ESIr (%) 1 Bojong Murni 1,346 175 10,32 2 Sukagalih 1,999 383 22,32 3 Cihanjawar 1,993 1121 45,22 4 Sukamulya 2,533 2665 54,94 5 Ciputri 1,492 965 20,78
Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
4
Tabel 2 menunjukkan bahwa kelima desa contoh memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu (LQ > 1). Ini berarti bahwa tenaga kerja sektor pertanian di lima desa contoh tergolong sektor basis. Kegiatan basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (prime removable). Bertambah banyaknya sektor basis di suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa, dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan, turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Secara lokalitas wilayah, sektor pertanian memiliki tenaga kerja ekstra yang berarti akan menghasilkan surplus barang dan jasa yang kemudian mengekspornya. Jumlah pekerja yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swasembada wilayah (LQ=1) dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor (Glasson, 1977).
Kelebihan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Besarnya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dapat dilihat dari hasil perhitungan ESI. Desa yang mempunyai
kelebihan tenaga kerja terbesar adalah Desa Sukamulya yaitu sebanyak 2665 orang (54,94%) dan terendah adalah Desa Bojong Murni yaitu sebanyak 175 orang (10,32%). Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di daerah penyangga TNGP yang sangat kecil ditambah dengan tingkat pendikan dan keterampilan hidup penduduknya yang rendah yaitu terbatas pada keterampilan hidup yang berbasis lahan dan sumberdaya alam, dapat diduga bahwa ekspor kelebihan tenaga kerja desa-desa daerah penyangga adalah ke kawasan TNGP dalam bentuk gangguan kawasan.
Performance Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Shift-Share Analysis menjelaskan performance sektor pertanian di suatu desa dan membandingkannya dengan performance di dalam wilayah kecamatannya. Performnace sektor pertanian di daerah penyangga dijelaskan dengan tiga komponen analisis, yaitu laju pertumbuhan total (share component), komponen pergeseran proporsional (propor-tional shift component), dan komponen pergeseran diferential (differential shift component). Hasil analisis Shift-Share Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Lima Desa Contoh disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil analisis shift-share tenaga kerja sektor pertanian di lima desa contoh
No. Desa Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pergeseran Proporsional
Pergeseran Diferensial Total
1 Bojong Murni 0,1878 -0,0347 0,1047 0,2578 2 Sukagalih 0,0028 -0,0001 -0,0169 -0,0141 3 Cihanjawar 0,1615 0,1594 0,0784 0,3993 4 Sukamulya 0,1017 0,0003 0,1854 0,2874 5 Ciputri 0,0785 -0,1005 0,3628 0,3408
Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa laju
pertumbuhan total tenaga kerja sektor pertanian tertinggi adalah di Kecamatan Ciawi (0,1878) dan terendah di Kecamatan Megamendung (0,0028). Dilihat dari komponen pergeseran proporsional, laju pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian di Desa Bojong Murni, Sukagalih, dan Ciputri lebih rendah dari kecamatannya, dua desa lainnya lebih tinggi dari kecamatannya. Namun demikian, dilihat dari komponen pergeseran diferensialnya, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian di Desa Bojong Murni, Cihanjawar, Sukamulya, dan Ciputri lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatannya. Komponen pergeseran diferensial menunjukkan daya kompetisi sektor pertanian di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan di kecamatannya. Oleh karena itu, di di Desa Bojong Murni, Cihanjawar, Sukamulya, dan Ciputri sektor pertanian memiliki keunggulan kompetitif yang
relatif besar. Secara umum, pergeseran tenaga kerja sektor pertanian di desa contoh, kecuali di Desa Sukagalih, lebih dinamis dibandingkan dengan di kecamatannya.
KESIMPULAN
Tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP merupakan sektor basis. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian telah melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swasembada wilayah (LQ=1). Kelebihan tenaga kerja ini dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor. Secara umum, pergeseran tenaga kerja sektor pertanian di desa daerah penyangga TNGP lebih dinamis dibandingkan dengan di kecamatannya. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di daerah penyangga TNGP sangat kecil (< 0,5 ha), sekitar 85% penduduknya memiliki latar belakang pendidikan
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5
5
rendah, ditambah dengan keterampilan hidup penduduknya yang rendah, dapat diduga bahwa ekspor kelebihan tenaga kerja desa-desa daerah penyangga adalah ke kawasan TNGP dalam bentuk gangguan kawasan. Oleh karena itu, salah satu penangulangan kelebihan tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP adalah penggalian potensi dan pengembangan kemampuan petani dalam lapangan kerja non pertanian.
DAFTAR PUSTAKA
Basuni, S. 2003. Inovasi institusi untuk meningkatkan kinerja daerah penyangga kawasan konservasi (studi kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat). Disertasi, Program Pascasarjana IPB, Bogor.
Bendavid, A. 1974. Regional economic analysis for practitioners. Praeger Publishers, Inc, New York.
Glasson, J. 1977. Introduction to pegional planning. P. Sihotang, Penerjemah : pengantar perencanaan regional. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Jakarta.
Kusnoto, K. 2000. Bentuk-bentuk dan intensitas gangguan manusia pada derah tepi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Studi Kasus di Resort Bodogol, Cimande, Goalpara, dan Selabintana). Skripsi. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. Tidak dipublikasikan.
Sensudi, E. 2000. Gangguan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Buletin Edelweis Vol. VII No. 71, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11
7
PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TATA RUANG KEPULAUAN SERIBU
(Conservation of Local Vegetation in the Space Development of Kepulauan Seribu)
NYOTO SANTOSO
Pengajar Laboratorium Ekologi Satwaliar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
Fakultas Kehutanan IPB
ABSTRACT
Condition of vegetation land in Kepulaun Seribu is very needed as a life supporting system, particularly water balance and freshwater resource for local community. Beside that, it is very important for habitat of wildlife and water biota. Conservation and management of vegetation land or green space reserve in Kepulauan Seribu is not denied by decision maker. Keywords : Local vegetation, conservation area, wildlife, community, Kepulauan Seribu
KONDISI DAN STATUS VEGETASI LOKAL
Kepulauan Seribu yang merupakan gugusan pulau-pulau yang telah dihuni dan belum dihuni dengan total wilayah daratan seluas 855,97 ha, pada saat ini termasuk wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Keberadaan vegetasi lokal di wilayah Kepulauan Seribu terdapat pada beberapa pulau dengan status Kawasan Lindung (Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional Laut, sempadan pantai) dan sebagian tidak termasuk kawasan lindung.
Tipe dan Komposisi Jenis Vegetasi Lokal
Vegetasi lokal diartikan sebagai jenis-jenis tumbuhan asli setempat, alami, serta bukan merupakan jenis tumbuhan yang dimasukkan dari luar Kepulauan Seribu. Mengingat tempat hidup tumbuhan tersebut berupa pulau-pulau kecil, dataran rendah dengan sebagian areal dipengaruhi pasang surut dan sebagian berupa daratan, maka tipe vegetasi lokal
yang terdapat di Kepulauan Seribu terdiri atas : vegetasi mangrove dan vegetasi pantai.
1. Vegetasi Mangrove
Ciri dari komunitas vegetasi mangrove antara lain : dipengaruhi pasang surut air laut, berair payau (salinitas > 1 o/oo), substrat lumpur berpasir dengan variasinya, vegetasi dicirikan dengan akar napas (pneumatofora). Jenis tumbuhan yang menduduki antara lain : bakau (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata), pidada (Sonneratia alba), api-api (Avicennia marina) (Tabel 1).
Kondisi vegetasi mangrove saat ini telah banyak mengalami perubahan, akibat terkena abrasi, pencemaran minyak dan sampah padat. Hampir pada semua lokasi yang terdapat vegetasi mangrove, telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu pelestarian vegetasi mangrove di masa mendatang perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan secara terus menerus.
Tabel 1. Luas Vegetasi Mangrove Di Kawasan Lindung Kepulauan Seribu
No. Lokasi Luas (ha) Jumlah Jenis Nama Jenis 1. SM.Pulau Rambut 27,00 9 R.stylosa, R.mucronata, S.alba, B.gymnorrhiza, A.marina, L.
racemosa, C.tagal, E. agallocha, X.granatum 2. CA. Pulau Bokor 25,23 2 R.mucronata, S.alba 3. Pulau Untung Jawa 31,00 2 R. ucronata, A.alba 4. P.Lancang Besar 16,50 3 R.mucronata, S.alba, A.alba 5. P.Peteloran Barat 11,30 3 R.mucronata, C.tagal, A.marina 6. CA.Penjalinan Barat 8,30 4 R.stylosa, C.tagal, S.alba, A.marina 7. CA.Penjalinan Timur 6,80 4 R.stylosa, C.tagal, S.alba, A.marina
Jumlah 126,13 Sumber : Bappedalda DKI Jakarta (2000)
Pelestarian Vegetasi Lokal dalam Rangka Pengembangan Tata Ruang
8
2. Vegetasi Pantai
Ciri dari komunitas vegetasi pantai antara lain : berada pada areal daratan yang berbatasan dengan daerah pasang surut air laut (berada di belakang vegetasi mangrove, atau berbatasan langsung dengan areal pasang surut), tidak terpengaruh pasang susut air laut, substrat daratan. Jenis tumbuhan yang menduduki antara lain : pandan (Pandanus tectorius), ketapang (Terminalia catappa), cemara laut (Casuarina equisetifolia), waru laut (Hibiscus tiliaceus), butun (Barringtonia asiatica), centigi (Pemphis acidula). Variasi komunitas vegetasi pantai antara lain : formasi Pescaprae dan Formasi Barringtonia. a. Formasi Pes-caprae
Terdapat pada batas belakang jangkauan pasang tertinggi dan memperoleh namanya dari tumbuhan berbunga ungu atau kangkung pantai (Ipomoea pes-caprae) yang merambat dan dominan. Sebagian besar tumbuhan ini merupakan perambat dengan akar-akar yang dalam sehingga dapat mengikat tanah/pasir dan memmerangkap bahan-bahan organik yang dieksploitasi oleh binatang dan tumbuhan. Jenis tanaman lain pada formasi ini antara lain : rumput angin (Spinifex littoreus), Ischaemum muticum, Euphorbia atoto. b. Formasi Barringtonia
Dinamakan menurut nama pohon Barringtonia asiatica yang sering terdapat di pantai, meskipun tidak selalu dijumpai. Jenis pohon laiin yang dijumpai antara lain : nyamplung (Calophyllum inophyllum), pandan (Pandanus tectorius), pace/mengkudu (Morinda citrifolia), kepuh (Sterculia foetida), ketapang (Terminalia catappa), pakis haji (Cycas rumphii), dadap (Erythrina variegata), waru (Hibiscus tiliaceus), waru laut (Threspesia populnea).
Luas vegetasi pantai di kawasan lindung Kepulauan Seribu lebih kurang 34 ha, yang berada di Suaka Margasatwa Pulau Rambut (18 ha) dan Cagar Alam Pulau Bokor (16,79 ha). Namun demikian diluar kawasan lindung tersebut masih terdapat areal bervegetasi lokal (terutama vegetasi pantai). Status dan Fungsi Vegetasi Lokal 1. Status Vegetasi Lokal
Berdasarkan statusnya, vegetasi lokal (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) tumbuh dan berkembang pada kawasan lindung (Suaka Margasatwa, Cagar Alam/Taman Laut, sempadan pantai) dan diluar kawasan lindung atau kawasan budidaya (pekarangan/kebun, tegalan).
Pada kawasan lindung (Suka Alam dan Cagar Alam/ Taman Laut), keberadaan vegetasi lokal (vegetasi mangrove
dan vegetasi pantai) memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk tetap dipertahankan, dan pada kawasan ini sudah seharusnya tidak terjadi perubahan status pengelolaan atau perubahan peruntukan dan fungsi ruang. Namun demikian luas vegetasi lokal pada kawasan lindung Kepulauan Seribu relatif kecil dan diperkirakan lebih kurang 160,13 ha (18,7 %). Sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan lindung (Suaka Margasatwa dan Cagar Alam), maka fungsi utama pelestarian vegetasi lokal antara lain sebagai habitat satwaliar burung (SM. Pulau Rambut, Cagar Alam Pulau Bokor), serta sebagai pelestarian eksosistem alami setempat (CA. Penyaliran Barat, CA. Penyaliran Timur, CA. Peteloran Barat, CA. Pulau Lancang).
Vegetasi lokal yang berada pada kawasan lindung (sempadan pantai), tidak semua pantai pada masing-masing pulau di Kepulauan Seribu (yang dihuni) vegetasi lokalnya dipertahankan, karena untuk keperluan tempat berlabuh perahu, sarana pelabuhan dan bahkan pemukiman penduduk umumnya sampai ke pinggir pantai. 2. Fungsi Vegetasi Lokal
Secara keseluruhan pelestarian vegetasi alami dalam suatu kawasan budidaya dan lindung atau sebagai suatu kawasan hutan (Suaka Margasatwa dan Cagar Alam) mempunyai multi fungsi antara lain : a. Sebagai habitat (tempat berlindung, berkembangbiak
dan mencari pakan) satwaliar (burung, mamalia, reptilia)
b. Sebagai penghasil biomasa yang mempunyai andil besar dalam mendukung sistem penyangga kehidupan bagi organisma lain (ikan, udang, kepiting)
c. Sebagai penahan angin dan penahan abrasi (hantaman gelombang laut), serta menjaga stabilitas pulau-pulau kecil
d. Sebagai pengatur tata air, dan turut membantu mempertahankan kualitas dan kuantitas air bersih
e. Mencegah interusi air laut f. Penghasil oksigen yang dilepas ke udara bebas g. Sarana penelitian dan pendidikan h. Sarana wisata alam terbatas i. Penghasil bahan baku obat (tumbuhan, binatang) j. Keterwakilan genetik, species, dan ekosistem asli
Kepulauan Seribu k. Penghasil kayu bangunan dan kayu bakar l. Mempertahankan kekhasan, keunikan dan keindahan.
PERMASALAHAN PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DI KEPULAUAN SERIBU
Keberadaan 110 pulau yang tersebar secara tidak teratur dalam kelompok-kelompok, dan lebih kurang 80 Km di sebelah utara Jakarta (Ibu Kota Negara) merupakan potensi sumberdaya yang sangat bagus apabila dapat
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11
9
dikembangkan dengan baik. Namun demikian kondisi vegetasi lokal yang terdapat pada Kawasan Lindung (Suaka Margasatwa, Cagar Alam/Taman Nasional, sempadan pantai) mengalami tekanan akibat aktivitas manusia di sekitarnya, baik aktivitas di darat maupun aktivitas di perairan laut. Sedangkan keberadaan vegetasi lokal pada kawasan budidaya, sulit untuk meningkatkan kualitasnya. Beberapa permasalahan yang memberikan kontribusi bagi kelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu sebagai berikut : 1. Aktivitas Kehidupan Di Darat (Pulau-Pulau Yang
Dihuni Penduduk) a. Limbah padat (Sampah rumah tangga, restoran, dsb)
Jumlah penduduk Kepulauan Seribu tahun 1999 (15.316 jiwa) diperkirakan akan menghasilkan sampah rumah tangga yang dapat menjadi permasalahan bagi pelestarian vegetasi lokal. Potensi sampah rumah tangga, saat ini juga sangat dipengaruhi oleh sampah yang berasal dari daratan DKI Jakarta, sehingga akumulasi dari 2 (dua) sumber sampah tersebut telah memberikan dampak negatif bagi keberadaan vegetasi mangrove di Pulau Rambut. Beberapa bagian vegetasi mangrove di Pulau Rambut telah mati, diperkirakan disebabkan oleh limbah padat (sampah rumah tangga, industri, restoran, dsb.) yang menahan genangan pasang surut air laut.
b. Limbah cair (minyak, detergent, dsb.)
Aktivitas penduduk (terutama dari daratan Jakarta) telah memberikan kontribusi cemaran minyak. Akumulasi cemaran minyak hasil buangan telah menimbulkan dampak negatif pada kelestarian vegetasi lokal (vegetasi mangrove Pulau Rambut). Adanya lapisan minyak yang melapisi perakaran tumbuhan mangrove, menyebabkan sistem pernapasan tumbuhan terganggu, dan pada akhirnya mendorong terjadinya kematian. Demikian pula hal ini apabila terjadi pada vegetasi pantai (formasi Pes-caprae dan formasi Barringtonia).
c. Kebutuhan kayu
Kemungkinan permasalahan yang disebabkan oleh kebutuhan kayu (kayu bakar dan kayu bangunan) sangat kecil. Namun dalam jangka panjang, ketika pasokan kayu dari luar Pulau Jawa telah menipis, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penebangan kayu dari vegetasi lokal untuk keperluan pembuatan tiang pancang, kayu bakar dan komponen bangunan rumah.
d. Kebutuhan tempat tinggal/perumahan
Pada saat ini kedudukan perumahan penduduk Kepulauan Seribu berada di pantai (dekat perairan). Dalam
hal ini kepatuhan terhadap pelestarian vegetasi lokal pada kawasan lindung (Sempadan Pantai 200 meter ke darat) sangat rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kesadaran penduduk, konsistensi kebijakan pemerintah dan implementasinya lemah.
Perkembangan penduduk Kepulauan Seribu akan semakin menekan vegetasi lokal pada sempadan pantai, apabila tidak dilakukan penataan hunian/pemukiman bagi penduduk di masa mendatang. e. Kebutuhan sarana prasarana umum/sosial (pela-
buhan/darmaga)
Sarana prasarana umum (pelabuhan/darmaga) berada di pantai, dengan sendirinya menggunakan ruang tempat tumbuh vegetasi lokal di sempadan pantai. Untuk kepentingan tersebut tidak menjadi permasalahan (Kepres nomor 32 tahun 1990). Di samping itu lokasi sandar perahu nelayan, seringkali mengganggu pertumbuhan vegetasi lokal (vegetasi mangrove), sehingga hal ini dapat merupakan penekan kelestarian vegetasi lokal. 2. Aktivitas Di Perairan Laut
Aktivitas nelayan di perairan laut dan aktivitas pelabuhan telah memberikan konstribusi pencemaran (lapisan minyak) yang tinggi terhadap vegetasi lokal, terutama vegetasi mangrove di Pulau Rambut. Kematian tumbuhan mangrove dan kebersihan pantai menjadi menurun. Sedangkan sampah nelayan juga dibuang saja ke perairan, sehingga menimbulkan penumpukan sampah pada wilayah pantai, termasuk habitat vegetasi lokal.
Di samping itu aktivitas penambangan pasir di perairan laut juga memberikan pengaruh terhadap kestabilan pulau tempat hidup vegetasi lokal. Sampai saat ini tidak kurang di Kepulauan Seribu telah terjadi kehilangan 6 buah pulau. Salah satu faktor penyebab hilangnya pulau tersebut adalah pengambilan batu karang dan penambangan pasir. 3. Kondisi Alam a. Pulau-Pulau Kecil dan Ekosistem Fragile
Gugusan pulau di Kepulauan Seribu (110 pulau) tergolong pulau kecil, dengan ukuran luas pulau terbesar adalah Pulau Kelapa (481,33 ha). Kondisi pulau yang berukuran kecil ini, terbentuk dari karang atau Pulau Karang, susbtrat dominan pasir, maka tempat tumbuh vegetasi lokal tergolong ekosistem fragile atau rentan terhadap perubahan/gangguan. Berdasarkan kondisi pulau kecil tersebut dan fungsi vegetasi lokal, maka sangat penting penetapan kebijakan pembangunan Kepulauan Seribu harus tetap mempertahankan vegetasi lokal atau Ruang Terbuka Hijau (alami dan binaan).
Pelestarian Vegetasi Lokal dalam Rangka Pengembangan Tata Ruang
10
b. Pemanasan Global dan Dampaknya
Dampak pemanasan global telah dirasakan, tidak hanya terhadap peningkatan suhu atmosfir bumi, tetapi juga peningkatan permukaan laut selama abad yang lalu kira-kira 15 cm dan perkiraan peningkatan permukaan laut pada abad mendatag (abad 21) sekitar 65 cm sampai 1 meter.
Daerah yang luas di pesisir Pulau Jawa yang ketinggiannya di bawah 1 meter, diperkirakan akan tenggelam, bahaya interusi air laut meningkat. Pada saat ini (kasus pesisir Kabupaten Demak-Jawa Tengah), luasan tambak dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan interusi air laut meningkat dan genangan air laut juga meningkat. Sehingga luas areal pertanian padi sawah menurun, sedangkan luasan tambak meningkat. Dengan kata lain telah terjadi konversi sawah menjadi tambak akibat peningkatan muka air laut dari waktu ke waktu. Bahkan kasus yang terjadi di Desa Sriwulan (Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak), telah terjadi hilangnya areal tambak dan pemukiman akibat peningkatan genangan air laut dan abrasi.
Kondisi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu secara keseluruhan merupakan pulau karang, dataran, dan tidak berbukit. Dengan peningkatan permukaan laut diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kondisi vegetasi lokal di Kepulauan Seribu, berupa meningkatnya wilayah
genangan, dan juga kemungkinan abrasi. Kondisi pulau yang rata-rata berukuran di bawah 100 ha (relatif kecil), diperkirakan akan banyak terpengaruh oleh peningkatan genangan air laut.
Menurut Pemda DKI Jakarta (1999), permasalahan pengembangan Kepulauan Seribu yang berkaitan dengan pelestarian vegetasi lokal dan menjadi isu pokok adalah : peruntukan lahan tidak sesuai fungsi, dan terbatasnya air bersih. Oleh karena itu beberapa program yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dan berkait dengan pelestarian vegetasi lokal antara lain : mendorong penghijauan pekarangan penduduk, intensifikasi pengelolaan pulau-pulau dengan peruntukan kawasan lindung, pengembangan pariwisata alam, pengelolaan sampah secara terpadu, perbaikan tanggul-tanggul pulau yang terabrasi dengan program penghijauan.
PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM PENGEMBANGAN TATA RUANG
Rencana alokasi ruang terbuka hijau (hijau lindung dan hijau binaan) yang disusun Pemda DKI Jakarta menunjukkan bahwa persentase luas hijau lindung berkisar antara 10 % sampai 40 %, sedangkan persentase luas hijau binaan berkisar antara 2 % sampai 13,9 % (Tabel 2)
Tabel 2. Rencana Alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kepulauan Seribu Sampai Tahun 2005
No
Kelurahan
Luas (Ha)
Luas RTH (Ha) Persentase RTH (%) Hijau Lindung (ha) Hijau Binaan (ha) Jumlah (ha)
1. Pulau Tidung 180,76 18,94 3,53 22 ,47 12,43 2. P.Untung Jawa 129,53 65,08 19,44 84,52 65,25 3. P.Panggang 64,35 14,47 3,00 17,47 27,15 4. P.Kelapa 491,67 192,62 68,10 260,72 53,03 Total 866,3 1 291,11 94,07 385,18 44,46
Sumber : Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 1999. Luasan dan Alokasi Ruang
Pendekatan luasan yang sesuai bagi pelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu berbeda dengan pendekatan luasan RTH di daratan (Pulau Jawa, yakni sebesar 30 %). Mengingat ekosistem pulau kecil memiliki karakteristik tersendiri, maka pendekatan luasan pelestarian vegetasi lokal perlu lebih menekankan pada kelestarian beragam fungsi pulau itu sendiri.
Luas vegetasi lokal (hijau binaan dan hijau lindung) yang telah direncanakan (44,46 %) dari luas daratan kiranya perlu ditingkatkan menjadi 60 %. Dasar usulan ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penutupan daratan agar fungsi vegetasi sebagai pengatur hidrologis, habitat hidupan liar dan sebagainya dapat ditingkatkan. Dengan
kata lain proporsi luas daratan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan budidaya/pemukiman/ perkantoran/fasilitas umum dan sosial tidak lebih dari 40 %, dan luasan vegetasi lokal (hijau binaan dan hijau lindung) dapat mencapai 60 %.
Alokasi pelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu terdapat pada Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Pemukiman. 1. Kawasan Lindung
a. Suaka Margaatwa (Pulau Rambut)
Pelestarian vegetasi lokal (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) bertujuan untuk meningkatkan kualitas habitat burung-burung air yang tinggal di Pulau Rambut. Populasi burung air di tempat ini cukup tinggi, dan aktivitas
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11
11
burung pada pagi dan sore hari merupakan atraksi yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Keberadaan vegetasi lokal pada tiap-tiap pulau di Kepulauan Seribu sAngat penting dipertahankan, agar terdapat habitat alternatif bagi burung tersebut. b. Cagar Alam (P.Penyaliran Barat, Penyaliran Timur,
P.Peteloran, P. Lancang, P. Bokor)
Pelestarian vegetasi mangrove dan vegetasi pantai bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pulau, agar fungsi penyangga kehidupan, hidroloogis, stabilitas pulau, pelestarian keanekaragaman hayati, kegiatan penelitian dan pendidikan dapat meningkat. Di samping itu keterwakilan keanekaragaman spesies dan ekosistem darat dan ekosistem rawa payau di Kepulauan Seribu dapat diselamatkan.
Menurut peraturan perundangan (UU Nomor 5/1990) pada kawasan ini tidak diperkenankan untuk kegiatan wisata, namun pada kawasan konservasi ini dapat dilakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Dalam upaya pelestarian potensi dan peningkatan kesadaran, serta meningkatkan potensi obyek wisata alam Kepulau Seribu, perlu kiranya dipikirkan peluang untuk dijadikan obyek kunjungan wisatawan secara sangat terbatas. Contoh: pengunjung/wisatawan dapat menikmati keberadaan Cagar Alam ini cukup dari Pusat Informasi saja atau dari menara pandang atau mengeliling pulau dengan perahu. Program rehabilitasi di kawasan Cagar Alam ini sangat penting dilakukan, dengan tetap mempertahankan keaslian vegetasi dan ekosistemnya. c. Sempadan Pantai
Pada 110 pulau yang berada di Kepulauan Seribu tidak semuanya dapat dimanfaatkan sebagai daerah hunian. Pulau yang dimanfaatkan sebagai daerah hunian, perlu kiranya mempertahankan sempadan pantainya dengan disiplin (200 meter dari surut terendah atau 100 meter dari titik pasang tertinggi). Kekecualian dari kondisi tersebut adalah apabila pada sempadan pantai dibangun darmaga dan pelabuhan.
Pelestarian vegetasi lokal pada sempadan pantai (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) mutlak diperlukan
agar keberadaan pulau dapat dipertahankan dari ancaman bahaya abrasi pantai, disamping itu juga untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai daerah asuhan dan pembesaran biota air (vegetasi mangrove), serta pencegah intrusi air laut, penahan air tanah dan penyangga angin. Dengan demikian alokasi ruang untuk vegetasi lokal dan daerah hunian/pemukiman, fasilitas umum/sosial perlu ditata agar tetap mempertahankan vegetasi lokal (60 %). Jenis Tumbuhan Lokal Untuk Rehabilitasi
Jenis tumbuhan lokal (vegetasi mangrove) yang sesuai untuk kegiatan rehabilitasi antara lain : api-api (Avicennia marina), bakau (Rhizophora stylosa), pidada (Sonneratia alba). Untuk kepentingan menahan abrasi dan menjerap sedimen/lumpur, maka jenis api-api dan pidada sangat baik dipergunakan. Namun pemilihan jenis ini juga harus memperhatikan lama genangan/pasang surut air laut dan kondisi substrat.
Jenis tumbuhan lokal (vegetasi pantai) yang sesuai untuk kegiatan rehabilitasi/penghijauan antara lain : cemara laut (Casuarina equisetifolia), waru (Hibiscus tiliaceus), butun (Barringtonia asiatica), ketapang (Terminalia catappa). Namun demikian pada lahan pekarangan (Kawasan Budidaya) saat ini banyak dipergunakan jenis tanaman bukan asli setempat, seperti : sukun (Arthocarpus sp.), kelapa (Cocos nucifera), jambu, dsb.
Daftar Pustaka
Whitten, T, Soeriaatmadja, R.E, Afiff, S.A. 1999. Ekologi Jawa dan Balii (Seri Ekologi Indonesia Jilid II). Dalhousie University/Canadian International Development Agency. Prenhallindo, Jakarta.
Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta. 1999. Sosialisasi RRTRW-Kecamatan, Kotamadya Jakarta Utara. Jakarta.
Bapedalda DKI Jakarta. 2000. Laporan Draft Final Koordinasi Evaluasi Kawasan Mangrove Cagar Alam Dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu DKI Jakarta.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20
13
PENYEBARAN DAN KARAKTERISTIK SARANG BERBIAK KOMODO (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) DI LOH LIANG
PULAU KOMODO TAMAN NASIONAL KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR
M. MUSLICH1) DAN AGUS PRIYONO2)
1) Alumni Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB 2) Pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB
ABSTRACT
The study on distribution and characteristic of the nest of komodo was conducted during March and April 2004 in Komodo National Park. Based on
the field observation in Loh Liang resort indicated that the distribution of the nest of komodo were mainly on the flat areas (<8 % slope), between 8-48 meters above sea level. Most of the nest was heap type, and most of them were the nest of Gosong birds. The nest usually located in ecotone areas between forest and savannah, especially near the tamarind trees. The nest was 13,8 m length; 12,3 m width; 0,98 m high and the depth was 0,97 m. Key word : komodo, nest, Loh Liang, ecotone
PENDAHULUAN
Melalui Surat Keputusan Presiden No. 4 tahun 1992, komodo ditetapkan sebagai satwa nasional sehingga keberadaannya dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan komodo juga dilakukan dengan melakukan perlindungan habitatnya dengan menetapkan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar sebagai Taman Nasional pada tahun 1980.
Banyak data ilmiah tentang komodo yang masih belum terungkap, sehingga menjadi misteri dalam ilmu pengetahuan dan menarik perhatian para peneliti. Kedudukannya dalam ilmu pengetahuan sangatlah penting karena dianggap sebagai contoh hidup sisa peninggalan reptilia purba yang dapat menghubungkan evolusi reptilia di masa lalu dan di masa kini. Namun demikian ancaman populasi komodo juga terus terjadi. Ancaman terjadi secara tidak langsung, terutama penyempitan habitat dan perburuan satwa mangsa (babi hutan, rusa) khususnya yang terjadi di luar Taman Nasional, yaitu di Pulau Flores bagian barat. Informasi mengenai jumlah populasi sangat diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen dan upaya konservasi komodo.
Sarang merupakan komponen dari habitat yang sangat terkait dengan reproduksi satwaliar. Pertumbuhan populasi komodo ditentukan oleh banyaknya telur yang dapat menetas dalam suatu sarang. Komodo tidak mengerami telur-telurnya, tetapi meletakkannya dalam sarangnya dan proses penetasannya sangat tergantung pada kondisi lingkungan, baik fisik, biologi maupun kimia. Dengan mengetahui lokasi sarang komodo, maka program pemantaun dan penelitian tahunan dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat. Lebih jauh lagi pendugaan penambahan populasi tahunan dapat dilakukan oleh pengelola. Data mengenai penyebaran dan karakteristik sarang yang tersedia dapat dijadikan sebagai pedoman pengelolan habitat dan kawasan agar kelestarian komodo dapat terjamin.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebaran sarang komodo dan karakteristiknya di Loh Liang Pulau komodo Taman Nasional Komodo.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai April 2004 di Resort Loh Liang pulau Komodo Taman Nasional Komodo Propinsi Nusa Tenggara Timur
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan selama kegiatan penelitian ini adalah : Peta kawasan, GPS, kamera, binokuler, termo-meter, refraktometer, roll meteran, worksheet dan alat tulis.
Penelitian karakteristik sarang berbiak komodo meng-gunakan teknik Purpossive sampling dalam pengambilan data di lapangan. Penggunaan teknik sampling ini adalah untuk mereduksi objek yang diteliti dari objek yang lebih luas karena pertimbangan waktu, biaya, tenaga dan per-alatan. Selain itu hasil penelitian dapat digeneralisasikan, artinya menggunakan kesimpulan-kesimpulan pada objek yang lebih luas dari keseluruhan objek penelitian.
Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo
14
Metode Pengumpulan Data
Data primer yang diperlukan adalah letak sarang yang diperoleh dengan cara observasi lapang secara langsung. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Orientasi lapangan dan inventarisasi sarang, berguna
untuk mengetahui seluk beluk kawasan yang akan dijadikan objek penelitian dan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan sarang. Titik koordinat sarang diplotkan dalam GPS.
b. Cross checking, berguna untuk mengetahui kebenaran keberadaan dan sebaran suatu lokasi sarang yang sedang dijadikan objek penelitian, informasi dasar didapatkan dari survey sarang sebelumnya dari petugas di lapangan.
c. Pemetaan, memetakan letak sarang dan sumber air di atas peta kerja
d. Pengamatan dan pengukuran, dilakukan terhadap objek penelitian berupa sarang berbiak dan kondisi lingkungan sekitarnya dengan meninjau karakteristiknya.
e. Pengambilan sampel air, dilakukan untuk menganalisis air yang terdapat di lokasi.
Data sekunder yang dikumpulkan meliputi sebaran iklim (suhu, kelembaban), sebaran vegetasi, sebaran satwa, penataan kawasan, aktivitas manusia dan sharing. Data itu didapatkan dari Studi pustaka dan wawancara dengan petugas jagawana, pihak mitra Taman Nasional (The Zoological Society of San Diego) dan mitra lainnya yang berada di Taman Nasional Komodo.
Analisis Data
Analisis sebaran geografis yaitu memetakan hasil inventarisasi dengan peta digitasi dengan program ArcView, kemudian mendeskripsikan keterkaitan sebaran sarang dengan faktor iklim (suhu dan kelembaban) dan morfologi lahan.
Analisis sebaran ekologis yaitu mendeskripsikan keterkaitan antara sebaran sarang dengan sebaran tipe vegetasi, sebaran satwaliar dan sebaran sumber air.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran Geografis Sarang Komodo (Varanus
komodoensis)
Topografi dan Elevasi Loh Liang merupakan gugusan lembah yang paling
besar di pulau Komodo. Sedikitnya terdapat 5 lembah yang membentang diantara perbukitan, diantaranya dua lembah yang luas yaitu lembah Banunggulung dan lembah Poreng.
Gugusan gunung dan perbukitan membentang mulai dari gunung Ara (510 m dpl) sampai ke gunung Satalibo (735 m dpl). Sarang komodo yang termonitor pada luasan survey 8,997 km2 berjumlah 6 sarang yang berada pada ketinggian 8 m dpl sampai dengan 78 m dpl. Dua sarang tercatat pada ketinggian 10 m dpl (LL 24 dan LL 30) dan yang lainnya berada pada ketinggian 48 m dpl (LL 64) dan 46 m dpl (LL 65). Sarang LL 05 berada pada ketinggian 8 m dpl dan sarang lubang bukit LL 103 berada pada ketinggian 78 m dpl (Gambar 1). Dua sarang masing-masing berada di lembah Banunggulung dan jalan setapak menuju pantai, sedang dua lainnya berada di lembah Poreng dan sekitar pos jaga.
Lima dari total sarang (n = 6) berada pada tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF) yang berdekatan dengan savana hutan (SWL) dengan kelerengan datar (<8 %), sedangkan satu sarang berada pada tipe vegetasi padang savana (SGL) yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka dengan kelerengan curam (35%). Penyebaran sarang komodo mengikuti penyebaran komodo. Komodo banyak ditemukan di daerah lembah yang relatif datar. Komodo lebih leluasa bergerak di lahan yang datar dan mengeluarkan energi yang tidak begitu besar. Satu sarang (LL 103) yang terdapat di lereng bukit dipilih karena keamanan dari predator. Tiga sarang aktif terletak saling berjauhan dibatasi oleh setidaknya satu bukit antar sarang terdekat dengan jarak rata-rata 2 km. Posisi untuk LL 05 yaitu 8°:34’:14”.6 BT - 119°:29’:41”.0 LS, LL 103 yaitu 8°:33’:07”.3 BT - 119°:29’:47”.7 LS dan LL 64 berada pada posisi 8°:33’:14”.1 BT - 119°:30’:38”.2 LS.
Komodo juga diketahui memanfaatkan sarang burung gosong sebagai tempat sarangnya.
Klimatis Sebesar 70% wilayah Taman Nasional Komodo
merupakan ekosistem savana. Keterbukaan lahan menye-babkan intensitas penyinaran semakin tinggi. Tingkat kelembaban sepanjang tahun sangat rendah. Hal ini dikarenakan curah hujan yang rendah selama sekitar 8 bulan. Bulan basah terjadi hanya 3-4 bulan yaitu pada bulan Desember–Maret.
Hasil pengukuran suhu harian terhadap tipe vegetasi di sekitar tiga sarang komodo aktif menunjukan perbedaan antara hutan gugur terbuka (ODF) dan savana. Suhu harian hutan di sekitar sarang LL 05 sama dengan suhu harian di savana yaitu 29,5º C, sedangkan kelembaban harian di savana sebesar 80,75%. Nilai suhu harian yang sama antara hutan dan savana di sekitar sarang LL 05 disebabkan penutupan vegetasi yang cukup terbuka, sehingga walaupun didalam hutan intensitas sinar matahari yang masuk sama dengan di savana (Tabel 1).
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20
15
Gambar 1. Peta penyebaran sarang berdasarkan kontur dan aliran sungai
Tabel 1. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban harian di dua tipe vegetasi
Sarang Hutan Suhu Savana Suhu Kelembaban savana Kelembaban (%)
LL 05
07,30 27 07,30 26.5 07,30 88
13,30 33.5 13,30 35 13,30 81
17,30 29.5 17,30 29 17,30 66
Suhu harian 29.25 29.5 Kelembaban harian 80.75
LL 103
07,30 25.5 07,30 31.5 07,30 71
13,30 32 13,30 35 13,30 68
17,30 28 17,30 28 17,30 87
Suhu harian 27.75 31.5 Kelembaban harian 74.25
LL 64
07,30 25 07,30 24 07,30 71
13,30 31.5 13,30 34.5 13,30 68
17,30 29 17,30 29.5 17,30 87
Suhu harian 27.63 28 Kelembaban harian 74.25
Ket : Suhu dalam derajat Celcius (°C)
Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo
16
LL 103 merupakan sarang yang terletak di lereng bukit. Suhu harian di savana sangat tinggi mencapai 31,5º C dengan kelembaban harian cukup rendah yaitu 74,25 %, sedangkan suhu harian di dalam hutan gugur terbuka sebesar 27,75° C. Selisih suhu di kedua tipe vegetasi tersebut sangat tinggi, karena di sekitar sarang tidak ada vegetasi peneduh yang dapat dijadikan naungan. Suhu harian hutan gugur terbuka di sekitar sarang LL 64 sebesar 27,63° C, sedangkan suhu harian di savana 28º C dengan kelembaban harian sebesar 74,25%. Selisih suhu di dua tipe vegetasi tersebut tidak terlalu signifikan.
Secara umum habitat komodo di semua tempat hampir sama, suhu rata-rata 23° - 40 C dengan kelembaban berkisar 45% - 75%. Intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam suatu tipe vegetasi dipengaruhi oleh penutupan vegetasinya. Sarang komodo sebagian besar berada di hutan gugur terbuka (ODF) yang berbatasan langsung dengan savana hutan (SWL). Hal ini terkait dengan penyebaran komodo yang lebih memilih hutan gugur terbuka sebagai habitat utamanya. Selain itu terkait dengan perilaku berjemur yang dilakukan oleh komodo setiap pagi. Mulai pukul 07.00 komodo akan beraktivitas berjalan menuju savana untuk menaikkan suhu tubuhnya dengan berjemur. Setelah pukul 10.00 atau intensitas cahaya semakin tinggi, komodo akan kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat dengan intensitas cahaya yang lebih rendah.
Sebaran Ekologis Sarang Komodo (Varanus
komodoensis)
Sumber Air Air merupakan komponen penting dari suatu habitat
dan berperan sebagai faktor pembatas dalam mempengaruhi penyebaran satwaliar. Tetapi ketersediaan air bukan merupakan faktor pembatas utama bagi komodo betina produktif dalam pemilihan tempat bersarang. Hal ini dikarenakan komodo mempunyai kemampuan fisiologi di dalam menahan haus. Dalam pemenuhan kebutuhan minumnya, komodo mendapatkannya dari satwa mangsa yang dimakannya dan embun dengan cara menjilati daun, kayu dan rumput dengan lidahnya. Selain itu komodo mempunyai kemampuan termoregulasi untuk mengatur suhu dan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sehingga walaupun terdapat banyak air dalam suatu sumber air, komodo akan menggunakannya hanya sedikit.
Taman Nasional Komodo merupakan daerah beriklim kering dengan tipe F (menurut Schmidt-Ferguson). Musim hujan terjadi hanya 3-4 bulan antara Desember-Maret. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan satwaliar sangat terbatas. Komodo betina melakukan aktivitas menjaga sarang selama 3-4 bulan atau sampai pada awal musim hujan. Setelah lapisan tanah
mengeras dan bau-bauan dari telur di dalam sarang sudah tidak dapat tercium oleh komodo lainnya, komodo betina meninggalkan sarangnya. Sungai yang terdapat di Loh Liang cukup banyak, tetapi hanya bersifat musiman. Sungai dialiri pada saat hujan saja dan itupun hanya ditempat yang relatif tinggi dengan lapisan sungai bebatuan.
Komodo betina penghuni sarang LL 103 (Nomor ID : 00-063A-309A) menggunakan sumber air untuk memenuhi kebutuhannya di genangan air pada sebuah sungai musiman (air 21, 22, 23) yang berjarak lebih dari 1 km dari sarang LL 103. Sumber air tersebut berada pada ketingian 53 m dpl. Air sungai tersebut mempunyai pH 4-4, 5 dengan salinitas 0 per mil, berada di tipe vegetasi hutan lebat tertutup (CDF) dengan vegetasi dominan kesambi dan bambu. Ketiga genangan air tersebut mempunyai ukuran rata-rata panjang 1,99 m, lebar 1,2 m, dan kedalaman 0,11 m.
Selain menggunakan air genangan di sungai musiman (air 21, 22, 23), komodo penghuni sarang LL 103 juga menggunakan sumber air yang terdapat di kolam manipulatif (air 7) dengan ukuran panjang 2,97 m, lebar 1,88 m, dan kedalaman 0,18 m. Kolam tersebut berjarak 315 m dari sarang LL 103. Pada saat penelitian kolam yang berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka kering sehingga tidak dapat diukur pH dan salitasnya. Kolam manipulatif tersebut juga terletak di dekat sarang LL 65 yang berstatus tidak aktif dengan jarak 15 m.
Air 13 merupakan kubangan yang terletak di sekitar pos jaga Loh Liang yang merupakan sumber air paling dekat dengan sarang LL 05 dengan jarak 285 m. Air kubangan ini berada di tipe vegetasi hutan pantai (CF) dengan jenis vegetasi dominan bidara (Zyzipus jujuba). Selain digunakan oleh komodo, air dengan pH 8,5 dan salinitas 0 per mil ini juga digunakan oleh rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus scrova vittatus) dan burung. Komodo penghuni sarang LL 05 (Nomor ID : 00-063A-309E) menggunakan sumber air ini untuk memenuhi kebutuhan minumnya.
Air 16 merupakan muara sungai yang menggenang dengan ukuran panjang 58,5 m, lebar 7,5 m dan kedalaman 0,9 m. Sumber air ini terletak di dekat pantai dengan ketinggian 5 m dpl dan berada di tipe vegetasi Manggrove (MF) dengan jenis vegetasi dominan Avicennia sp. Sumber air ini tidak digunakan oleh komodo karena sifat airnya yang terlalu basa dengan nilai pH 10 dan kadar garam tinggi (38 per mil). Sumber air ini hanya digunakan oleh rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus scrova vittatus) dan burung.
Kubangan yang terdapat di Loh Liang bahkan di seluruh pulau bersifat tidak permanen. Kubangan akan segera kering karena iklim yang begitu kering. Sejumlah 72,22 % (n = 13) kubangan berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF). Ukuran rata-rata kubangan dan bekas kubangan adalah panjang 5,6 m, lebar 3,38m, dan kedalaman 0,36 m.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20
17
Tipe Vegetasi Sebesar 83,33% (n = 5) lokasi sarang komodo berada
di tipe vegetasi peralihan antara hutan gugur terbuka (ODF) dan savana hutan (SWL). Pohon-pohon yang terdapat dalam hutan gugur terbuka diantaranya asam (Tamarindus indicus), jarak (Jatropha curcas), kesambi (Schleicera Oleosa), kepuh (Sterculia foetida), kedondong hutan (Spondias pinnata), dan walikukun (Schoutenia ovata). Sedangkan 16,66% (n = 1) berada di tipe vegetasi padang savana dengan jenis vegetasi rumput Heteropogon contortus yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka dengan jenis pohon dominan walikukun (Schoutenia ovata) yaitu sarang lubang bukit (LL 103).
Banyaknya sarang yang berada di peralihan dua tipe vegetasi (ekotone) memungkinkan pencahayaan dengan intensitas yang lebih tinggi dari pada di tipe vegetasi hutan lebat tertutup (CDF). Selain itu memudahkan komodo betina yang sedang menjaga sarang untuk berjemur di savana dan dengan mudah menemukan mangsanya, karena rusa banyak ditemukan di savana untuk makan rumput. Alasan lain juga karena melimpahnya sumberdaya pakan seperti kadal, tokek, burung dan sarangnya, dan serangga sebagai penyedia pakan bagi anakan komodo (hatcling) yang baru menetas.
Satu sarang berada di tipe vegetasi padang savana yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka. Posisi sarang menghadap ke timur sehingga intensitas cahaya yang masuk ke dalam sarang cukup tinggi, namun intensitas cahaya akan berkurang apabila matahari condong ke barat karena terhalangi perbukitan.
Satwaliar dan Sumberdaya Pakan Komodo merupakan karnivora sejati dan bersifat
kanibal. Pakan utama komodo dewasa yaitu rusa, kerbau liar, babi hutan, kera, telur burung gosong dan kadal. Sedangkan jenis makanan komodo yang baru menetas diantaranya serangga, kadal kecil dan telur burung. Pemilihan sarang oleh betina produktif tidak terbatas pada sumberdaya pakan yang ada.
Menurut Jessop et. al. (2003), tidak ada bukti spasial yang menunjukan bahwa pemanfaatan sarang oleh betina ditentukan oleh kebutuhan habitat tertentu terkait posisi sarang satu sama lain di lembah terbesar bagian utara pulau. Jika dianggap bahwa di pulau komodo terdapat suatu wilayah habitat spesifik, yang menyediakan sumberdaya termasuk makanan dan perkembangan habitat dan akan mendukung offspring, maka diduga seperti halnya reptil lain, bahwa kepadatan aktivitas bersarang yang tinggi akan dijumpai. Penyebaran satwaliar dalam hal ini prey komodo di Loh Liang dan seluruh pulau terkait dengan tipe vegetasi yang dapat menyediakan makanan seperti padang rumput dan tersedianya air. Pada musim kemarau dimana sumber air sangat terbatas komodo akan lebih mudah untuk
mendapatkan mangsanya, termasuk komodo betina yang sedang menjaga sarang.
Pemilihan Sarang oleh Komodo (Varanus komodoensis)
Tipe dan Ukuran sarang Total sarang komodo (n = 6) yang ditemukan, empat
diantaranya bertipe gundukan. Sarang gundukan merupakan sarang yang dibangun oleh burung gosong (Megapodius reinwardt) dan telah diambil alih oleh komodo. Ada dua sarang aktif yang bertipe gundukan yaitu LL 64 dan LL 05. LL 64 mempunyai ukuran panjang 10,7 m, lebar 9,06 m, dan tinggi 0,98 m dengan jumlah lubang 5 buah. Ukuran rata-rata panjang lubang 0,61 m, lebar 0,31 m, dan kedalaman 0,95 m. Sedangkan sarang LL 05 mempunyai ukuran panjang 15,86 m, lebar 15,6 m, dan tinggi 0,99 m dengan jumlah 18 buah. Ukuran rata-rata panjang lubang 1,38 m, lebar 0,52 m, dan kedalaman 0,98 m.
Sarang gundukan aktif yang ditemukan mempunyai rata-rata ukuran panjang 13,8 m, lebar 12,33 m, dan tinggi 0,985 m dengan jumlah lubang 11,5 ( 12) buah dan ukuran rata-rata panjang lubang 0,99 m, lebar 0,42 m, dan kedalaman 0,97 m. Sedangkan dua sarang gundukan lainnya yang berstatus tidak aktif mempunyai ukuran rata-rata yang lebih pendek yaitu panjang 7,87 m, lebar 7,09 m, dan tinggi 0,95 m, dengan rata-rata jumlah lubang 5,5 ( 6) buah.
Dua sarang lainnya bertipe lubang bukit dan lubang tanah. LL 103 merupakan sarang lubang bukit aktif dengan ukuran panjang 8,63 m, lebar 6,89 m, tinggi 2,76 m dengan jumlah lubang 6 buah, meliputi lubang horizontal dan vertikal dengan kemiringan ± 45° ukuran rata-rata panjang lubang 1,1 m, lebar 0,42 m, dan kedalaman 1,295 m. Secara umum banyaknya lubang yang terdapat pada sarang merupakan lubang kamuflase untuk menghindari predasi dari komodo lainnya. Selain itu lubang dapat digunakan sebagai tempat tidur komodo betina pada saat menjaga sarang. Sarang lubang tanah (LL 65) yang ditemukan berstatus tidak aktif. Sarang ini berukuran panjang 3,14 m, lebar 1,6 m dan terdapat satu lubang horisontal kedalam tanah dengan kedalaman 1,53 m.
Terlihat adanya pemilihan oleh biawak komodo betina dalam penggunaan sarang burung gosong belum terpakai daripada sarang permukaan tanah dan sarang di bukit. Diperkirakan pemakaian sebagian struktur sarang ini menunjukan proses pemilihan yang disengaja oleh betina, juga menunjukan bahwa alternatif bersarang di tanah atau di tebing bukit tidak terbatas oleh kompetisi atau kekurangan habitat yang ada. Tiga dari total sarang (n = 6) berstatus aktif untuk tahun 2004 yaitu LL 5, LL 103, dan LL 64. Ketiga sarang tersebut telah digunakan oleh komodo betina yang sama pada tahun yang lalu (Tabel 2).
Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo
18
Table 2. Komodo betina produktif penghuni sarang aktif 2004
Nest code Pit tag
Head length (cm)
Head wide (cm)
Dorsal TBL (cm)
ventarl TBL (cm)
Av. SVL (cm)
Tail length (cm)
Weight (gr) Blood ID
LL 64 00-063A-22BA 15.4 7.6 198 197 98.4 99 21 - LL 103 00-063A-309A 16.7 8.1 226 223.5 109.5 115.3 32.35 - LL 05 00-063A-309E 14.85 10.2 209 206 115 91 24.6 K 9
Sumber data : Zoological Society of San Diego
Komodo mempunyai kebiasan untuk menggunakan sarang yang sama untuk meletakkan telurnya untuk musim bertelur berikutnya, hal ini juga terjadi di daerah Loh Sebita. Sebelum bertelur komodo mempersiapkan dirinya dengan kondisi tubuh yang baik yaitu dengan menyimpan cadangan lemak yang cukup banyak. Komodo dapat bertelur berturut-turut dalam dua tahun apabila kondisi tubuhnya sehat dan baik. Selama menjaga sarang komodo betina mengalami penurunan berat badan. Hal ini dikarenakan komodo betina kekurangan makanan tetapi masih dapat bertahan hidup dari cadangan lemak dari tubuhnya. Monitoring terhadap komodo betina produktif tahunan masih sangat sulit dilakukan . Keberadaan betina yang menggunakan sarang LL 65, LL 24, LL 30 sudah tidak dapat dimonitoring. Salah satu penyebabnya adalah sifat kanibalisme komodo sehingga memungkinkan komodo betina tersebut telah dimangsa oleh komodo lainnya.
Penutupan Vegetasi dan Vegetasi Dominan Sekitar Sarang Komodo
Keberhasilan penetasan telur komodo sangat ditentu-kan oleh kondisi di dalam sarang diantaranya suhu. Menurut Jessop et al. (2003) telur komodo memerlukan suhu untuk inkubasi sampai pada penetasan sekitar 30°C. Apabila ada pengurangan suhu yang signifikan akan memperlambat proses penetasan, tetapi apabila ada penambahan suhu yang signifikan maka telur akan rusak dan konsekuensinya telur tidak akan menetas. Suhu di dalam sarang cenderung stabil dan dipengaruhi oleh penutupan vegetasi di sekitarnya. Lima dari total sarang (n = 6) yang ditemukan mempunyai penutupan vegetasi 0-10% dan satu sarang mempunyai penutupan vegetasi sekitar sebesar 11-25%. Hal ini memungkinkan penyinaran yang cukup terhadap sarang. Penggunaan lokasi dengan penutupan vegetasi yang terbuka karena komodo menghindari adanya penumpukan serasah di atas sarangnya. Komodo selalu membersihkan sarangnya dari serasah dan ranting. Hal ini dilakukan untuk menghindari peningkatan suhu tanah akibat proses pembusukan ranting dan serasah oleh mikrorganisme. Kandungan Carbon organik sarang komodo aktif lebih rendah dari pada sarang gosong aktif. Rata-rata Carbon organik yang terdapat pada lapisan tanah bagian atas dan bawah sarang komodo sebesar 1,38 dan
1,23. Sedangkan rata-rata Carbon organik yang terdapat pada lapisan tanah bagian atas dan bawah sarang gosong sebesar 4,12 dan 4,6. Vegetasi dominan disekitar sarang adalah asam (Tamarindus indicus), sebesar 66,66 % (n = 4), tetapi ada satu sarang dengan dominasi vegetasi sekitar kesambi (Scheleicera oleosa). Satu sarang berada di tipe vegetasi padang savana yang didominasi oleh rumput (Heteropogon contortus) dan jenis pohon walikukun (Schoutenia ovata).
Sarang Gosong Sebagai Sumberdaya Tempat Bersarang Komodo
Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Taman Nasional Komodo dan Zoological Society of San Diego (ZSSD) menunjukan di seluruh pulau, komodo lebih banyak menggunakan sarang gosong (sarang tipe gundukan) untuk meletakkan telurnya. Walaupun di beberapa tempat komodo membuat sarangnya sendiri dengan menggali tanah (tipe lubang tanah) dan menggali lubang pada tebing bukit (Tipe lubang bukit). Banyaknya sarang gosong yang digunakan komodo menunjukan bahwa gosong merupakan sumberdaya penting dalam kawasan yang menyediakan tempat bersarang bagi komodo. Betina biawak komodo secara khas memilih sarang burung gosong yang rata-rata secara signifikan lebih tersinari matahari. Diperkirakan bahwa proses pemilihan ini disebabkan karena lingkungan tersebut memiliki kondisi yang baik untuk inkubasi telur selama 180 hari hingga masa penetasan.
Di resort Loh Liang telah ditemukan sejumlah 34 sarang gosong yang masih aktif. Status aktif ditunjukan dengan adanya aktivitas penggalian (digging) baru di sarang dan sekitarnya yang biasanya dilakukan oleh sepasang burung gosong. Selain itu dapat dilihat dari jejak yang ditinggalkan di sarang dan sekitarnya. Burung gosong mempunyai kebiasaan dan aktivitas merawat sarang sehingga sarang gosong yang aktif juga ditunjukan dengan banyaknya serasah dan ranting yang ada di atas gundukan sarang. Kondisi ini berbeda dengan sarang komodo yang cenderung bersih dari serasah dan ranting-ranting di atasnya.
Ukuran rata-rata panjang sarang gosong 9,30 m, lebar 7,82 m, dan tinggi 1,25 m, dengan rata-rata jumlah lubang
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20
19
6,25 (6) buah. Ukuran dan jumlah lubang sarang burung gosong aktif mudah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya penggalian dan penambahan tanah, serasah dan ranting oleh burung gosong setiap hari.
Sarang burung gosong kebanyakan berada di dalam tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF) sebesar 79,41% (n = 27). Sarang lainnya berada di tipe vegetasi CF (hutan pantai) sebesar 14, 7% (n = 5) dan di peralihan hutan gugur terbuka dan hutan pantai sebesar 5,88% (n = 2). Sejumlah 52,90 % (n = 18) sarang burung gosong mempunyai penutupan vegetasi di sekitar sarang yang cukup rapat yaitu 76-100 %. Walaupun demikian menurut Tim Jessop sarang burung gosong mempunyai suhu sarang yang lebih tinggi daripada suhu sarang komodo sekitar 34°C. Hal ini dikarenakan telur gosong bersifat keras pada cangkangnya. Untuk memenuhi kebutuhan panas dalam proses inkubasi, maka burung gosong mengumpulkan serasah dan ranting di dalam sarangnya. Proses biologis dalam penguraian oleh mikroorganisme merupakan sumber panas yang membantu dalam meningkatkan suhu sarang. Sumber panas pada sarang burung gosong juga berasal dari sinar matahari. Bila suhunya terlalu tinggi maka burung gosong membuka gundukan tanah tersebut agar panasnya keluar sehingga suhu dalam sarang yang ideal dapat dipertahankan sekitar 34° C.
Jenis vegetasi dominan yang berada di sekitar sarang burung gosong adalah asam (Tamarindus indicus) sebesar 79, 41 % dari total sarang yang aktif. Hampir semua sarang gosong aktif berada dekat pohon yang merupakan pohon utama di dalam menaungi sarang.
Jenis interaksi yang terjadi antara sarang gosong dan beberapa satwa lainnya diantaranya adalah predasi. Aktivitas predasi banyak dilakukan oleh komodo. Komodo akan menggali sarang untuk mencari telur burung gosong. Sedangkan pada musim bersarang komodo betina produktif aktif mencari dan menggali sarang untuk meletakkan telurnya. Ini merupakan bentuk mekanisme awal pengambilalihan sarang burung gosong oleh komodo. Selain komodo, babi hutan juga sering menggali-gali sarang untuk mencari telur dan cacing. Hal ini dilakukan karena kondisi tanah yang mempunyai konsistensi ramah sehingga memudahkan dalam proses penggalian. Sejumlah 76,47 % (n = 26) sarang gosong aktif tidak mengalami ganguan oleh komodo maupun babi hutan. Dua sarang (LL 95 dan LL 31) merupakan sarang bersama (joinest) antara komodo dan burung gosong. Sarang ini dapat saja aktif untuk musim bersarang komodo tahun berikutnya. Kedua sarang tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan sarang komodo yaitu mempunyai penutupan vegetasi 0-10% dan 11-25%, dengan ukuran panjang rata-rata 11,57 m, lebar 9,39 m, tinggi 1,27 m dengan jumlah lubang 9 buah.
Menurut Sunanto (1998), aktivitas komodo yang dilakukan di sarang burung gosong meliputi aktivitas
menggali sarang untuk mencari telur burung gosong, mengawasi kegiatan burung gosong di sarang tersebut, memeriksa sarang dengan cara menjulurkan lidahnya untuk mengetahui letak telur dalam sarang, serta berjalan mengelilingi sarang untuk mencari posisi yang tepat untuk mengambil telur burung gosong. Dari hasil pengamatan belum pernah ditemukan burung gosong dimangsa oleh komodo. Hal senada juga dikatakan oleh petugas bahwa selama ini belum pernah petugas melihat komodo memakan burung gosong. Namun demikian mereka mengatakan ada peluang burung gosong dimakan komodo yaitu pada saat burung gosong bertelur.
Sarang Tidak Aktif dan Sarang Tua (oldnest)
Sarang tidak aktif merupakan sarang gosong yang sudah tidak dipakai lagi dan berpeluang menjadi sarang tua. Dalam kondisi sarang seperti ini maka burung gosong maupun komodo tidak akan menggunakannya. Ukuran sarang tidak aktif lebih kecil. Rata-rata panjangnya 7,85 m, lebar 6,98 m, dan tinggi 0,84 m, dengan rata-rata jumlah lubang 1,71 (2) buah. Lapisan tanah sangat keras, karena tanah lunaknya semakin tererosi. Beberapa sarang tidak aktif dan sarang tua ditemukan dengan lapisan tanah berbatu. Di Resort Loh Liang ditemukan 7 sarang baik yang tidak aktif maupun sarang tua. Sebesar 71,43 % (n = 5) sarang berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka dan dua lainnya ditemukan berada di savana hutan (SWL) dan peralihan antara hutan gugur terbuka dan savana hutan. Sebesar 42,86 % (n = 3) penutupan vegetasi sekitar sarang 11-25 % dengan jenis vegetasi dominan asam (Tamarindus indicus) sebesar 71,43 % (n = 5). Interaksi yang terjadi adalah penggalian oleh babi hutan terhadap sarang.
Telur dan Anakan Komodo (Hatchling)
Penggalian yang dilakukan pada sarang LL 05 dan LL 64 pada saat penelitian tidak ditemukan telur. Hal ini dikarenakan lokasi penggalian yang tidak tepat sehinga telur belum dapat ditemukan. Sampai penelitian ini selesai kedua sarang belum digali karena tidak adanya tenaga yang ahli yang dapat menggali dengan baik. Sehingga apabila dipaksakan untuk menggali dikhawatirkan akan merusak konstruksi sarang. Penggalian kemudian dilakukan di dua sarang di Loh Sebita. Dari kegiatan penggalian yang dilakukan di dua sarang di Loh Sebita di temukan telur yang masih utuh. Pada sarang LSB 01 ditemukan 29 telur, 4 diantaranya belum menetas, dan satu telur terdapat anakan yang gagal menetas. Di sarang LSB 01 juga ditemukan potongan tubuh hatcling diduga perilaku kanibalisme saat masih di dalam sarang. Sedangkan di sarang yang lain ditemukan 28 telur, empat diantaranya gagal menetas, satu terkena jamur dan dua belum menetas (Tabel 3).
Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo
20
Tabel 3. Ukuran telur komodo di Loh Sebita
No. Panjang (cm) Lebar (cm) Berat (gr) Keterangan 1 8.8 6.55 99 belum menetas 2 8.99 6.7 107 belum menetas 3 8.7 6.7 108 belum menetas 4 8.9 5.7 108 belum menetas 5 9.1 5.7 102 belum menetas
Rata-rata 8.90 6.27 104.8
Pada tahun 2003 di sarang LL 64 telah ditangkap 17
hatcling dan telah diberi ID dengan ukuran rata-rata panjang kepala 4,06 cm, lebar kepala 1,94 cm, panjang total tubuh atas 37,11 cm, rata-rata panjang tubuh 18,29 cm, panjang total tubuh bawah 41,67 cm, panjang ekor 18,8 cm dan berat badan 0,086 kg.
Tidak terdapat musim kawin yang jelas (kopulasi diamati terjadi pada hampir sepanjang tahun), namun mereka tampak menghindari musim hujan. Betinanya bertelur sekitar 15–30 butir dalam sarang yang dibuat dari pasir atau daun kering sekali setahun, bagian terbesar telur terdapat pada bulan Agustus–September. Kadang-kadang, betina bertelur di dalam sarang burung gosong. Masa gestasi sekitar 8,5 bulan dan saragnya dijaga hanya selama bulan-bulan pertama saja. Setelah menetas pada bulan Maret-April, satwa muda mandiri, kendati ukurannya kecil (rata-rata 80,3 gram dan panjang 30,4 cm) dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon untuk menghindari dimangsa oleh komodo yang dewasa, anjing liar dan babi.
Strategi ini juga memungkinkan satwa komodo muda untuk memperoleh makanan seperti telur burung, burung muda, serangga, kadal dan sebagainya tanpa perlu bersaing dengan satwa dewasa (Taman Nasional Komodo, 2002).
KESIMPULAN DAN SARAN
Di resort Loh Liang ditemukan sejumlah 6 sarang, 3 diantaranya aktif untuk tahun 2004. Dalam pemilihan sarang, komodo betina cenderung menggunakan tipe sarang gundukan (66,66%), lainnya di lubang bukit (16,66%) dan lubang tanah (16,66%). Lokasi sarang paling banyak ditemukan di daerah lembah pada ketinggian 8 mdpl – 48 m dpl dengan topografi lahan datar (< 8%), kecuali satu sarang berada di lereng bukit pada ketinggian 78 m dpl dengan topografi lahan curam (35%). Sebesar 83,33% (n = 5) sarang berada di lembah pada tipe vegetasi hutan gugur terbuka yang berdekatan dengan padang savana dengan penutupan vegetasi ≤ 25 % dengan jenis vegetasi dominan asam (Tamarindus indicus). Faktor utama pemilihan sarang oleh betina produktif yaitu penutupan vegetasi yang terkait
dengan intensitas penyinaran dan suhu serta kemudahan dalam penggalian.
Ukuran sarang komodo lebih panjang dengan jumlah lubang yang lebih banyak daripada asarang gosong. Sarang gundukan aktif yang ditemukan mempunyai rata-rata ukuran panjang 13,8 m; lebar 12,33 m; dan tinggi 0,985 m dengan jumlah lubang 12 buah dan ukuran rata-rata panjang lubang 0,99 m; lebar 0,42 m; dan kedalaman 0,97 m. Sedangkan ukuran rata-rata panjang sarang gosong 9,30 m; lebar 7,82 m dan tinggi 1,25 m dengan rata-rata jumlah lubang 6 buah. Telur komodo mempunyai ukuran rata-rata panjang 8,90 cm, lebar 6,27 cm, dan berat 104,8 gram. Secara keseluruhan ukuran rata-rata hatchling yang ditangkap selama penelitian adalah panjang kepala 4,49 cm, lebar kepala 2,06 cm, panjang tubuh atas 50,53 cm, rata-rata panjang tubuh 20,25 cm, panjang total tubuh bawah 49,93 cm, panjang ekor 29,38 cm, lingkar ekor 5,43 cm dan berat 113,13 gr.
DAFTAR PUSTAKA
Fahrudin. 1998. Pendugaan Parameter Demografi Populasi Komodo (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) di Pulau Komodo Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. [skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
Jessop, T. S., J. Sumner, H. Rudiharto, D. Purwandana, M.J. Imansyah dan J. A. Phillips. 2003. Studi Distribusi, Penggunaan dan Pemilihan Tipe Sarang oleh Biawak Komodo : Implikasi untuk Konservasi dan Manajemen. Zoological Society of San diego, The Nature Conservancy, Komodo National Park.
Sunanto. 1998. Studi Interaksi Antara Komodo (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) dengan Burung Gosong (Megapodius freycinet Gaimard, 1823) Di Pulau Komodo Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. [Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 21 – 26
21
PENCEMARAN INSEKTISIDA PADA TIGA SPESIES BURUNG AIR (PECUK HITAM, KUNTUL KECIL, DAN BLEKOK SAWAH)
DI AREAL PERSAWAHAN SUKAMANDI, SUBANG, JAWA BARAT
(Insecticides Pollution on the Three Water Birds Species (Little Black Cormorant, Little Egret and
Javan Pond Heron) in Rice-Field at Sukamandi, Subang, West Java)
LIN NURIAH GINOGA
Pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, IPB
ABSTRACT
Significant use of insecticide in rice-field by intensification program can directly endanger the environment and sustainability of birds living in the habitat. The objective of the investigation is to study negative impact of insecticide pollution on rice-field environment and on water birds. The research has been conducted on : (1) the diversity of vegetation and macrozoobenthos; (2) insecticide content in water, soil, food, eggs, and tissues of the three water birds species namely little black cormorant, little egret and javan pond heron; and (3) community utilization of insecticide. The research was carried out in Sukamandijaya Village, Ciasem district, under Subang Regency. Samples of eggs and birds were taken from the Sukamandi Rice Research Institute. Purposive sampling application was used in the survey method. The vegetation characteristics in research site include 5 species of weeds in the rice-field and 15 species of weeds in the rice-field dike are also studied. Macrozoobenthos was taken in 20 sampling location consisted of 17 types. Diversity index ranged from 0.469 to 2.689, and water quality of irrigation range from light to high levels pollution. Laboratory analysis were able to detect the presence of 9 types of insecticides consisted of 3 groups, namely : (1) organochlorine (BHC, Aldrin, Endosulfan, Dieldrin, DDT, and Endrin); (2) organophosphat (Chlorpirifos and Diazinon); and (3) Carbamat (Carbofuran). The lowest concentration of insecticide was found in the water, while highest was in the fat tissues of birds. Although the local community recently used only organochlorine (Endosulfan) and other 5 insecticide belonging to this group were detected in the samples. Another group of insecticide used by the community, pirethroid, was not detected in the samples. Results of research further indicated the occurrence of biomagnification starting from the water , soil, food, eggs, and tissues. Keywords : insecticides, pollution, water bird, rice-field
PENDAHULUAN
Persawahan selain merupakan lahan penghasil pangan bagi manusia, juga merupakan habitat, tempat beristirahat, dan mencari pakan bagi burung-burung air. Adanya program intensifikasi pertanian untuk mencapai swasem-bada pangan memerlukan teknologi penggunaan insektisida untuk mencegah dan memberantas hama. Aplikasi insektisida yang intensif dan berlebihan secara langsung maupun tidak langsung akan membahayakan lingkungan dan kelestarian burung yang hidup di areal tersebut (Carson, 1990; Mc Ewen, 1979; Brown, 1978).
Dampak negatif langsung penggunaan insektisida pada burung adalah terjadinya kematian. Sedangkan dampak tidak langsung adalah adanya dampak residu yang dapat menyebabkan peracunan terhadap rantai makanan, akumulasi, biomagnifikasi serta gangguan reproduksi (Untung, 1996; Carson, 1990; Nandika, 1986). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan insektisida dalam air, tanah, pakan, telur, jaringan burung, serta nilai biomagnifikasi yang terjadi; Menilai kualitas lingkungan persawahan dengan menggunakan vegetasi, makrozoobentos dan burung air sebagai bioindikator; serta
mengetahui pemahaman dan penggunaan insektisida oleh petani. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan kebijakan perijinan dan penggunaan pestisida, serta sebagai informasi bagi pihak yang berkaitan dengan pelestarian burung dan pelestarian plasma nutfah.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di areal persawahan Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dari bulan Agustus 1998 sampai bulan Februari 1999. Analisis makrozoobentos dilakukan di Laboratorium Limnologi LIPI Cibinong, sedangkan analisis kandungan insektisida dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Enzimatik Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan Bogor. Contoh vegetasi diambil di persawahan dan diidentifikasi langsung di lapangan. Contoh makrozoo-bentos diambil dari 20 lokasi secara purposive sampling. Contoh air, tanah, dan pakan burung yang terdiri dari makrozoobentos dan ikan diambil bersamaan dengan pengambilan contoh makrozoobentos. Contoh 3 spesies burung air yang paling dominan dijumpai yaitu pecuk hitam
Pencemaran Insektisida pada Tiga Spesies Burung Air
22
(Phalacrocorax sulcirostris Brandt) (n=5), kuntul kecil (Egretta garzetta Linnaeus) (n=6), dan blekok sawah (Ardeola speciosa Horsfield) (n=4) dengan telurnya masing-masing sebanyak 3, 4, dan 3 butir yang diambil dari tempat beristirahat dan berkembangbiak burung yang terletak di lokasi Balai Penelitian Padi Sukamandi. Contoh telur dipisahkan menjadi bagian putih, kuning dan kulit. Sedangkan burung dibedah dan diambil jaringan lemak, hati, daging, dan bulu untuk dianalisis kandungan insektisida pada masing-masing jaringan. Responden petani (n=60) dipilih secara purposive sampling untuk mengetahui persepsi, jenis insektisida, penggunaan serta pena-nganannya.
Digunakan rumus diversitas Shannon (Odum, 1971) untuk menghitung indeks keanekaragaman makrozoo-bentos. Hubungan indeks keanekaragaman dengan tingkat pencemaran perairan digunakan kriteria Wilhm (1975). Data rataan konsentrasi insektisida yang terkandung dalam air, tanah, pakan, telur dan jaringan burung dibandingkan dengan Batas Maksimum Residu (BMR) yaitu PP No. 20 tahun 1990 untuk air, McEwen 1979 untuk pakan, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian RI No. 881/MENKES/SKB/VIII/1996 – 711/ Kpts/TI.270/8/96 untuk telur dan jaringan burung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Vegetasi. Selain tanaman padi dijumpai 5 jenis gulma di persawahan yaitu Echinochloa crusgalli (jukut jajagoan), Cyperus iria (jekeng), Cyperus diformis (teki), Monochoria vaginalis (eceng lembut) dan Marsilea crenata (semanggi). Dijumpai pula 15 jenis gulma di pematang yaitu Cyperus rotundus, Cyperus pygmaeus, Mimosa pudica, Mimosa invisa, Ludwigia parviflora, Jussieua repens, Sida rhombifolia, Ageratum conyzoides, Drymaria cordata, Alternanthera philoxeroides, Saccharum spontaneum, Paspalum vaginatum, Panicum trypheron, Digitaria arhopalotricha dan Alternanthera sessilis. Jenis vegetasi yang dijumpai relatif sedikit bila dibandingkan dengan jenis gulma yang sering dijumpai di ekosistem persawahan berdasarkan Sastroutomo (1990) yaitu sebanyak 33 jenis. Hal ini kemungkinan disebabkan areal penelitian merupakan persawahan yang termasuk dalam program intensifikasi, sehingga pemberantasan gulma sebagai tanaman pengganggu dilakukan secara intensif.
Makrozoobentos. Hasil penelitian dari 20 lokasi
pengambilan contoh ditemukan 17 jenis makrozoobentos yang terdiri dari 3 Filum : (1) Filum Annelida (47.06%) meliputi spesies Branchiura sowerbyi, Tubifex sp., Phristina osborni, Ophistocysta flagellum, Amphichaeta sp., Chaetogaster diastropus dan Hirudinea sp.; (2) Filum Mollusca (41.18%) meliputi spesies Bellamya javanica, Gyraulus convexiusculus, Melanoides tuberculata, Lymnea
rubiginosa, Lymnea sp., dan Pita scutata; (3) Filum Arthropoda (11.77%) meliputi spesies Allaudomyta sp., dan Pentaneura sp. Jenis Melanoides tuberculata dan Tubifex sp. yang mendominasi areal penelitian merupakan jenis yang memiliki toleransi besar terhadap pencemaran air serta jenis yang dapat dijadikan indikator kualitas air yang rendah.
Dari 20 lokasi pengambilan contoh, pada setiap lokasi hanya dijumpai 2 sampai 7 spesies. Kecilnya jumlah spesies tersebut sangat dimungkinkan mengingat inten-sifnya penggunaan insektisida. Toksisitas insektisida sangat berpengaruh terhadap kelimpahan dan keanekaragaman bentos. Indeks keanekaragaman jenis bentos berkisar 0.469 – 2.689. Berdasarkan kriteria Wilhm (1975) nilai tersebut menunjukkan kualitas air di daerah penelitian termasuk ke dalam perairan yang tercemar ringan sampai tercemar berat.
Kandungan Insektisida. Hasil analisis insektisida
pada air, tanah, pakan, telur, dan jaringan burung menyatakan adanya 9 jenis insektisida yang terdiri dari 3 golongan yaitu : (1) klor-organik meliputi jenis BHC, Aldrin, Endosulfan, Dieldrin, DDT, dan Endrin, (2) fosfat-organik meliputi jenis Klorpirifos dan Diazinon, serta (3) Karbamat meliputi jenis Karbofuran. Berdasarkan jenis insektisida yang ditemukan, golongan klor-organik menempati peringkat pertama (66.67%), kedua golongan fosfat-organik (22.22%), dan ketiga golongan karbamat (11.11%). Bila dibandingkan dengan jenis-jenis insektisida yang digunakan responden, sebagian besar menggunakan insektisida golongan fosfat-organik dan karbamat, diduga keberadaan residu insektisida golongan klor-organik yang ditemukan dalam penelitian ini akibat penggunaan masa lalu dan karena sifatnya yang persisten sehingga sampai saat ini masih terdeteksi. Kemungkinan lain insektisida golongan klor-organik digunakan secara ilegal.
Jenis insektisida di dalam air lebih sedikit bila dibandingkan di dalam tanah dan pakan. Di dalam air hanya terdeteksi 3 jenis insektisida yaitu BHC, Endosulfan, dan Klorpirifos masing-masing sebesar 0.00737; 0.00563; dan 0.00143 ppm yang seluruhnya masih di bawah batas maksimum residu untuk air berdasarkan PP No. 20 tahun 1990. Di dalam tanah terdeteksi 5 jenis insektisida yaitu BHC, Aldrin, Endosulfan, Klorpirifos, dan Karbofuran masing-masing sebesar 0.02823; 0.00993; 0.01643; 0.05360; dan 0.00987 ppm. Hal ini dapat terjadi karena air sawah menduduki tingkat tropik terendah dari proses rantai makanan di ekosistem persawahan dan merupakan medium utama bagi transportasi insektisida yang jatuh ke dalamnya. Konsentrasi BHC, Endosulfan, dan Klorpirifos yang terdeteksi relatif rendah pada air disebabkan sifat dari insektisida terutama golongan klor-organik yang sukar larut dalam air. Penyebab lain karena insektisida yang jatuh dalam sistem perairan akan diabsorbsi oleh partikel-partikel yang ada di dalamnya, dan pada tahap selanjutnya pestisida
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 21 – 26
23
masuk dalam sistem perairan bagian bawah yang terdiri dari lempung, lumpur, dan bahan organik (Edwards, 1976). Pernyataan tersebut sejalan dengan konsentrasi insektisida pada tanah yang ditemukan lebih besar serta lebih banyak jenisnya.
Ekstraksi pada pakan burung yang terdiri dari makrozoobentos dan ikan memperlihatkan terjadinya peningkatan jenis dan konsentrasi insektisida dari air dan tanah. Dalam pakan ditemukan 9 jenis insektisida yaitu BHC, Aldrin, Endosulfan, Dieldrin, DDT, Endrin, Klorpirifos, Diazinon dan Karbofuran, dengan konsentrasi masing-masing 0.04577; 0.05207; 0.06613; 0.05217; 0.02297; 0.01967; 0.08110; 0.07063; dan 0.02830 ppm. Peningkatan dimungkinkan karena nilai insektisida dalam pakan merupakan akumulasi dari tingkat tropik di bawahnya. Peningkatan ini menunjukkan telah terjadi proses biomagnifikasi.
Jenis insektisida dalam telur burung terbanyak dijumpai dalam kuning telur (9 jenis), putih telur (7 – 8 jenis), dan kulit telur (3 – 8 jenis) (Tabel 1, 2, dan 3). Konsentrasi insektisida BHC, Aldrin, DDT, Endrin, Klorpirifos, dan Karbofuran tertinggi terdapat pada kuning telur burung pecuk hitam. Konsentrasi Endosulfan, Dieldrin dan Diazinon tertinggi terdapat pada kuning telur burung kuntul kecil. Konsentrasi insektisida Aldrin dan Klorpirifos pada kuning telur burung pecuk hitam ditemukan telah melebihi batas maksimum residu. Tingginya konsentrasi dalam kuning telur dibandingkan putih telur dan kulit telur, disebabkan sifat insektisida yang lipofilik (terdeposit dalam lemak), dan kandungan lemak tertinggi dalam telur terdapat dalam kuning telur. Konsentrasi selengkapnya tersaji dalam Tabel 1, 2 dan 3.
Tabel 1. Konsentrasi insektisida dalam telur burung pecuk hitam
Insektisida Konsentrasi (ppm) Kulit Telur Putih Telur Kuning Telur BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
ttd ttd
0.02580 ttd ttd
0.02723
0.02650 0.07650 0.03610
ttd ttd
0.03080
0.07103
0.15320** 0.06310 0.05200 0.08570 0.05253
0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
ttd
0.04100
ttd
0.02610
0.11587**
0.07660
0.1 0.5
Karbamat Karbofuran
0.03460
0.04037
0.07567
Keterangan: ttd = tidak terdeteksi; * = BMR = Batas Maksimum Residu; ** = melebihi BMR Tabel 2. Konsentrasi insektisida dalam telur burung kuntul kecil
Insektisida Konsentrasi (ppm) Kulit Telur Putih Telur Kuning Telur BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
0.01453
ttd 0.02475
ttd ttd ttd
0.02058 0.03450 0.02333 0.01723
ttd ttd
0.06225 0.05258 0.07367 0.08855 0.07879 0.03948
0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
0.02490
ttd
0.04080 0.02950
0.08058 0.09925
0.1 0.5
Karbamat Karbofuran
ttd
0.00390
0.03613
Pencemaran Insektisida pada Tiga Spesies Burung Air
24
Tabel 3. Konsentrasi insektisida dalam telur burung blekok sawah
Insektisida Konsentrasi (ppm) Kulit Telur Putih Telur Kuning Telur BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
0.02930 0.01170 0.01203 0.01597
ttd 0.01393
0.03467 0.04083 0.05240 0.02983
ttd 0.02280
0.06233 0.07480 0.06893 0.05480 0.07100 0.04917
0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
0.02670 0.01693
0.04647 0.02070
0.09853 0.08963
0.1 0.5
Karbamat Karbofuran
0.01650
0.02173
0.04300
Jenis insektisida dalam jaringan burung terbanyak
dijumpai dalam lemak, hati, dan daging burung pecuk hitam (9 jenis), kedua dalam lemak dan hati burung blekok sawah (8 jenis), ketiga dalam bulu pecuk hitam dan daging blekok
sawah (5 jenis) serta keempat dalam lemak, hati dan daging burung kuntul kecil (4 jenis). Jenis dan konsentrasi insektisida dalam jaringan burung tersaji dalam Tabel 4, 5 dan 6.
Tabel 4. Konsentrasi insektisida dalam jaringan burung pecuk hitam
Insektisida Konsentrasi (ppm) lemak Hati Dagingr Bulu BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
0.30174** 0.26442**
0.11734 0.07930 0.31260
0.14090**
0.02650 0.12156 0.09848 0.03194 0.12674 0.12870
0.04470 0.05534 0.02866 0.02160 0.04324 0.08692
0.02480 0.02014 0.02264
ttd ttd ttd
0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 1
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
0.15632 0.16938
0.09242 0.11926
0.05132 0.07046
0.04236 0.04452
0.2 0.7
Karbamat Karbofuran
0.15010**
0.08258**
0.06248**
ttd
0.005
Keterangan: ttd = tidak terdeteksi; * = BMR = Batas Maksimum Residu; ** = melebihi BMR
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 21 – 26
25
Tabel 5. Konsentrasi insektisida dalam jaringan burung kuntul kecil
Insektisida Konsentrasi (ppm) lemak Hati Dagingr Bulu BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
0.07155
0.23407** 0.13013
ttd ttd ttd
0.02935 0.15815 0.07895
ttd ttd ttd
0.02025 0.05945 0.02978
ttd ttd ttd
ttd ttd
0.02264 ttd ttd ttd
0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 1
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
0.33783**
ttd
0.27569**
ttd
0.20285**
ttd
0.06125
ttd
0.2 0.7
Karbamat Karbofuran
ttd
ttd
ttd
ttd
0.005
Tabel 6. Konsentrasi insektisida dalam jaringan burung blekok sawah
Insektisida Konsentrasi (ppm) lemak Hati Dagingr Bulu BMR*
Klor-organik BHC Aldrin Endosulfan Dieldrin DDT Endrin
0.06983 0.14900 0.09190 0.06578
ttd 0.17575**
0.03080 0.07833 0.03438 0.03920
ttd 0.08877
0.01090 0.05878 0.02240
ttd ttd ttd
0.00453 0.03900
ttd ttd ttd ttd
0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 1
Fosfat-organik Klorpirifos Diazinon
0.17118 t0.20238
0.05345 0.09988
0.02525 0.07963
0.01733
ttd
0.2 0.7
Karbamat Karbofuran
0.08663**
0.03893
ttd
ttd
0.005
Konsentrasi insektisida BHC, Aldrin, Endosulfan, Dieldrin, DDT, dan Karbofuran tertinggi terdapat dalam jaringan lemak burung pecuk hitam, Endrin dan diazinon tertinggi terdapat dalam jaringan lemak burung kuntul kecil, dan Klorpirifos tertinggi terdapat dalam jaringan burung blekok sawah. Konsentrasi BHC dan Aldrin pada lemak, Endrin pada lemak dan hati serta Karbofuran pada daging burung pecuk hitam; Aldrin pada lemak, Klorpirifos pada lemak, hati dan daging burung kuntul kecil; Endrin dan Karbofuran pada lemak burung blekok sawah ditemukan telah melebihi batas maksimum residu.
Terjadinya perbedaan jenis dan konsentrasi insektisida pada ketiga jenis burung diduga karena perbedaan habitat, wilayah jelajah, dan jenis pakan. Sesuai dengan pernyataan Brown (1978) bahwa residu insektisida di dalam tubuh burung tergantung pada habitat dan jenis makanan dari burung tersebut.
Pada ketiga jenis burung, konsentrasi insektisida tertinggi ditemukan dalam jaringan lemak. Hal tersebut dapat terjadi karena pada umumnya insektisida terakumulasi dalam lemak. Secara keseluruhan hasil analisis kandungan insektisida mulai dari air, tanah, pakan, telur sampai jaringan burung menunjukkan telah terjadinya proses biomagnifikasi insektisida.
Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan teknologi penggunaan insektisida dalam program intensifikasi telah menimbulkan pencemaran pada ekosistem persawahan dan lingkungan sekitarnya. Dampak penggunaan insektisida pada persawahan selain terkena pada burung-burung air juga meluas pada biota air lainnya. Terputusnya suatu rantai makanan akibat punahnya suatu mata rantai dapat berakibat buruk pada rantai makanan secara keseluruhan.
Pencemaran Insektisida pada Tiga Spesies Burung Air
26
Penggunaan Insektisida oleh Petani. Responden yang diwawancarai seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran umur 23 – 69 tahun. Tingkat pendidikan responden pada umumnya hanya sampai sekolah dasar (96.97%). Seluruh responden menggunakan insektisida untuk mencegah dan mengendalikan hama. Jenis-jenis insektisida yang digunakan yaitu Thiodan, Azodrin, Basudin-60 EC, Dursban, Diazinon, Furadan, Sevin, Emcida, Bastox dan Arivo.
Ditinjau dari jenis-jenis insektisida yang digunakan, 1-12 orang responden masih menggunakan 6 jenis insektisida yang telah dilarang penggunaanya untuk pertanaman padi berdasarkan INPRES No. 3 tahun 1986 yaitu Azodrin, Basudin, Dursban, Diazinon, Sevin dan Thiodan. Namun sebagian besar responden telah menggunakan insektisida dari golongan karbamat dan piretroid yang memiliki persistensi di alam relatif tidak lama serta tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Meskipun hasil wawancara terhadap responden hanya digunakan satu jenis insektisida golongan klor-organik yaitu Endosulfan, namun hasil penelitian menyatakan ada residu lima jenis insektisida golongan klor-organik lainnya yaitu BHC, Aldrin, Dieldrin, DDT, dan Endrin. Sedangkan insektisida golongan piretroid, meskipun digunakan oleh responden, namun tidak terdeteksi dalam penelitian ini.
Metode aplikasi insektisida yang digunakan sudah cukup baik seperti, menggunakan alat penyemprot khusus, menggunakan takaran untuk menetapkan konsentrasi formulasi, dan melakukan penyemprotan dengan mengikuti arah angin. Pemahaman petani terhadap bahaya insektisida masih sangat terbatas, seperti banyaknya petani yang tidak menggunakan alat pelindung selama penyemprotan, tidak menghabiskan seluruh insektisida yang digunakan dan membuang sisanya ke sungai, menyimpan insektisida di rumah, serta mencuci peralatan bekas menyemprot di sungai dan di sumur. Terbatasnya pemahaman ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan responden yang hanya sampai sekolah dasar.
KESIMPULAN
Akibat penggunaan pestisida secara intensif menyebabkan sedikitnya jenis vegetasi dan makrozoobentos yang dijumpai, dengan kualitas perairan tercemar ringan sampai tercemar berat. Telah terjadi akumulasi dan biomagnifiaksi residu insektisida mulai dari air, tanah, pakan, telur serta jaringan burung. Pemahaman petani terhadap bahaya insektisida masih sangat terbatas, serta masih ditemukan adanya penggunaan insektisida yang telah dilarang oleh pemerintah.
UCAPAN TERIMA KASIH
Disampaikan terima kasih kepada Prof Dr Ir F Gunarwan Soeratmo, MF; Prof Dr Ir M Sri Saeni, MS; serta Prof Dr Ani Mardiastuti, MSc yang telah membimbing selama pelaksanaan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA Brown, A.W.A. 1978. Ecolody of Pesticides. John Wiley
and Sons Inc. New York
Carson, R. 1990. Musim Bunga yang Bisu. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Nandika, D. 1986. Dampak insektisida terhadap burung. Media Konservasi I (2); 6 -7
McEwen, F.L. and G.R. Stephenson. 1979. the Use and Significance of Pesticides in The Environment. John Wiley and Sons Inc. New York.
Odum, E.P. 1971. Fundamental of Ecology. Third Edition. W.B. Sounders Company. Philadelphia. Toronto. London.
Sastroutomo, S.S. 1990. Ekologi Gulma. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Wilhm, J.L. 1975. Biological Indicatorof pollution. P : 375 – 402. In Whiton, B.A. (Ed). River Ecology Vol 2. Black Well Scientific Publication. Osney Mead. London.
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 27 – 30
27
EKONOMI REHABILITASI DAERAH TANGKAPAN WADUK
(Rehabilitation Economic of Dam Catchment Area)
SUDARSONO SOEDOMO
Pengajar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor
ABSTRACT
Dynamic optimization approach is employed in this paper. Moreover, in this paper it is indicated that not all crititcal lands in the catchment areas of a dam need to be rehabilitated even though opportunity for the critical lands up to the end life of the dam is available. Budget allocation for rehabilitating catchment areas need to consider this factor to avoid inefficiency. Too large catchment areas can create an inefficiency. Location selection for developing a dam needs to take into account the costs of conservation and/or rehabiltation of catchment areas.
Keywords : catchment area, dam, critical land, rehabilitation, conservation
PENDAHULUAN
Wilayah tangkapan (catchment area) adalah suatu daerah yang mengumpulkan dan melepaskan aliran di bawah dan di atas permukaan. Sebagian besar air yang terkumpul dalam wilayah tangkapan dialirkan melalui saluran air atau sistem bawah tanah menuju ke titik yang lebih rendah seperti bendungan, lahan basah, mulut sungai dan lautan. Tulisan ini akan mendiskusikan wilayah tangkapan air yang terletak di atas bendungan, khususnya bendungan yang ditujukan untuk memproduksi tenaga listrik. Dalam tulisan ini, istilah waduk dan bendungan akan digunakan secara bergantian dengan makna yang sama.
Banyak bendungan air di Indonesia mengalami pendangkalan yang terlalu cepat dibandingkan dengan rencana. Penyebabnya adalah laju sedimentasi yang jauh di atas laju sedimentasi yang diperkirakan dalam perencanaan. Beberapa bendungan harus beroperasi jauh di bawah kapasitas yang direncanakan dengan akibat lanjutan pemadaman listrik secara bergantian. Peristiwa seperti ini semakin sering timbul dengan sebaran yang juga semakin meluas.
Fenomena pendangkalan bendungan yang terlalu cepat serta kebutuhan untuk mengendalikannya menunjukkan bahwa konservasi wilayah tangkapan sebenarnya mempunyai nilai yang selama ini diabaikan. Rehabilitasi wilayah tangkapan bendungan merupakan kebutuhan mendesak, khususnya untuk bendungan yang berskala besar. Namun masih timbul pertanyaan, berapa luas dari wilayah tersebut yang perlu direhabilitasi. Perlukah seluruh wilayah tangkapan direhabilitasi demi memperpanjang umur waduk?
Tulisan ini mendiskusikan rehabilitasi wilayah tangkapan bendungan untuk menjawab pertanyaan pokok apakah seluruh wilayah tangkapan harus direhabilitasi? Pertanyaan ini dapat dinyatakan dengan cara lain, kapan kita
harus menghentikan upaya rehabilitasi wilayah tangkapan yang ditujukan untuk menyelamatkan waduk? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat digunakan dalam merancang pembangunan bendungan di masa yang akan datang sehingga terjadi optimalisasi antara kapasitas waduk dan luas wilayah tangkapannya.
Luas wilayah tangkapan akan berpengaruh pada biaya perawatan atau konservasi wilayah tangkapan tersebut. Wilayah tangkapan yang berlebihan akan menghasilkan sedimentasi tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Kelebihan air karena terlalu luasnya wilayah tangkapan dapat dibuang dengan mudah. Tidak demikian halnya dengan kelebihan sedimen. Barangkali, perbandingan antara luas wilayah tangkapan dan kapasitas waduk perlu dijadikan kriteria pemilihan lokasi pembangunan bendungan melengkapi kriteria waduk baik dan buruk yang dikemukakan oleh Ledec dan Quintero (2003).
Tulisan ini akan diorganisasi sebagai berikut. Setelah pendahuluan, seksi berikutnya adalah model rehabilitasi wilayah tangkapan. Seksi 3 mendiskusikan implikasi dari model. Seksi 4 membahas implikasi dari analisis model terhadap kebijakan publik. Seksi terakhir merupakan kesimpulan.
MODEL REHABILITASI WILAYAH TANGKAPAN
Pada waktu ke-t volume bendungan efektif adalah v(t), tenaga listrik yang dihasilkan merupakan fungsi dari volume bendungan w(v)1, harga listrik per unit adalah p, biaya konservasi per satuan luas daerah tangkapan adalah c, luas daerah tangkapan adalah a(t) dan dianggap seluruhnya merupakan lahan kritis pada awal proyek. Biaya rehabilitasi dan harga listrik dianggap konstan dari waktu ke waktu. Laju rehabilitasi adalah k(t) per unit waktu dan luas lahan yang
Ekonomi Rehabilitasi Daerah Tangkapan Waduk
28
telah terehabilitasi adalah b(t). Laju sedimentasi dianggap kombinasi linear kontribusi dari lahan yang terehabilitasi (e1b(t)) dan kontribusi dari lahan yang rusak (e2(a(t) -
b(t))),
dimana e1 dan e2 masing-masing adalah laju sedimentasi dari lahan terehabilitasi dan lahan yang rusak dalam m3
per hektar
per tahun. Tanpa program rehabilitasi, waduk akan terisi penuh
dengan sedimen pada waktu T0: v
T0 = ______ (1) e2a
Net present value dari waduk tanpa rehabilitasi (π0) adalah:
T0
π0 = e−rtpw(v)dt (2) 0
Apabila pengelola waduk mempertimbangkan apakah perlu merehabilitasi lahan wilayah tangkapan atau membiarkan lahan yang rusak apa adanya, maka pertimbangannya adalah apakah rehabilitasi lebih menguntungkan dibanding tanpa rehabilitasi wilayah tangkapan. Rehabilitasi lahan kritis wilayah tangkapan bertujuan untuk memaksimumkan net present value dari aliran keuntungan yang dirumuskan sebagai berikut :
T max π1 = e−rt[pw(v) -
ck]dt (3)
{k(t)}
dengan kendala sebagai berikut:
v˙= - e1b - e2(a -
b) (4)
b˙= k (5)
b(0) = 0, b(T ) <
a, v(T ) = 0, T bebas, k(t)
[0,k] (6)
Hamiltonian dari problem ini adalah : H =[pw(v) -
ck][e1b + e2(a -
b)] + ψk (7)
Syarat yang harus dipenuhi bagi maksimisasi
Hamiltonian adalah :
∂H – ________ + rλ =pgh + rλ = λ˙
(8) ∂v ∂H – ________ + rψ = λ[e1 –
e2]+ rψ = ψ˙ (9)
∂b pgh
λ(t) = C0e rt + ______ (10) r
1 Dalam tulisan ini akan digunakan bentuk spesifik w = vgh, dimana g
adalah gravitasi dan h adalah jarak dari muka air waduk ke turbin pembangkit tenaga. Bentuk ini adalah formula energi potensial dengan asumsi berat jenis air adalah 1.
Transversality condition H(T) = 0 (Chiang 1992). Demikian juga, pada titik terminal dimana volume waduk telah mencapai nol (v(T) = 0) tidak ada gunanya melakukan rehabilitasi lahan demi mempertahankan waduk. Dengan kata lain k(T) = 0. Karena [e1b + e2(a – b)] > 0, maka λ(T) = 0. Oleh karena itu, nilai definitif bagi C0 adalah:
pgh C0 = – e-rt ______ (11)
r
Untuk sembarang nilai t persamaan 10 menjadi
pgh λ(t) = (1 − er(t−T) ) _______ (12)
r Nilai T akan ditentukan kemudian (lihat persamaan 22).
Karena kontribusi k(t) terhadap Hamiltonian bersifat linear, maka untuk t < T nilai k(t) optimal adalah k(t)* = k jika ψ(t) -
c > 0. Dengan diketahuinya λ(t), maka ψ(t) dapat ditentukan dengan hasil sebagai berikut :
(e2 − e1)pgh er(t−T )(e2 − e1)pght ψ(t) = ________________ + ________________________ + C1ert (13) r2 r
Nilai definitif bagi C1 ditentukan dengan menggunakan transversality condition serta kondisikondisi lainnya. Dengan H(T) = 0 sebagai transversality condition serta k(T) = 0, v(T)=0 dan λ(T) = 0, maka dari Hamiltonian akan diperoleh :
ψ(T) = c (14)
Dengan demikian nilai C1 diperoleh sebesar :
(e2 − e1)pgh (e2 − e1)pghT C1 = e−rT [c __ ________________ __ ___________________ ] (15) r2 r
Substitusi persamaan 15 ke dalam persamaan 13 diperoleh :
(e2 − e1)pgh (e2 − e1)pgh(t − T) ψ(t) = cer(t−T) + (1 − er(t−T) ) _______________ + er(t−T) ______________________ r2 r
(16)
Sama dengan persamaan 12, nilai T ditentukan kemudian seperti terlihat pada persamaan 22. Persamaan 16 hanya menjamin bahwa pada waktu T nilai ψ(T) sama dengan c. Namun persamaan ini tidak menjamin bahwa sebelum waktu T nilai ψ(t) tidak pernah mencapai c. Kapanpun ψ(t) = c tercapai maka rehabilitasi wilayah tangkapan harus dihentikan. Hal ini mempunyai implikasi yang penting dalam menyusun program rehabilitasi wilayah tangkapan.
Mengingat laju luas rehabilitasi optimal adalah konstan pada k, maka dengan menggunakan persamaan 5 luas kumulatif areal yang direhabilitasi adalah :
Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 27 – 30
29
b = kt (17)
Jangka waktu rehabilitasi T1 adalah luas lahan yang membutuhkan rehabilitasi dibagi dengan laju rehabilitasi yang konstant pada k:
a T1 = ___ (18)
k
Dengan substitusi persamaan 17 dan penyusunan ulang, persamaan 4 menjadi
v˙= [e2 – e1]kt – e2a (19)
Integrasi persamaan ini akan diperoleh:
1 v(t) = ____ [e2 – e1]kt2 – e2at + v0 (20)
2
Jangka waktu hingga waduk penuh, T, dapat diperoleh dengan setting v(T) = 0 dan mencari solusi bagi T sebagai berikut : T = [k(e2 − e1)]-1(ae2 ± a2e2
2 − 2(e2 − e1)kv0) (21)
Di antara dua pilihan nilai T, tanda yang mana yang harus dipilih. Untuk memilih satu di antara dua kemungkinan tersebut, kita perlu melihat bila waduk sejak awal sudah penuh dengan sedimen, artinya v0 = 0. Bila keadaan ini terjadi, maka tidak ada tindakan rehabilitasi yang perlu dilakukan. Dengan kata lain, T haruslah bernilai nol, yang berarti masa operasi waduk adalah nol. Hal ini hanya mungkin bila kita memilih : T = [k(e2 – e1)]−1
ae2 – a
2e2 – 2(e2 – e1)kv0 (22)
Jangka waktu rehabilitasi lebih pendek dari jangka waktu penuhnya waduk dengan sedimentasi jika:
(e1 + e2) ___________ a2 < v0 (23)
2k
Apabila persamaan 23 ini tidak terpenuhi, maka tidak seluruh daerah tangkapan waduk perlu direhabilitasi. Sebaliknya, apabila persamaan 23 ini terpenuhi, belum berarti bahwa seluruh wilayah tangkapan perlu direhabilitasi. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut pada bagian diskusi.
Volume waduk yang tersisa sesaat setelah seluruh daerah tangkapan terehabilitasi adalah :
1 v(t1) = v0 – e2aT** + ___ [e2 + e1] k(T**)2
(24)
2
Sisa umur waduk t2 hingga seluruh volume waduk terisi endapan adalah :
v(T**) t2 = _______________________ (25) e2a –
(e2 –
e1)kT**
Dengan mendefinisikan bahwa T1 = T** dan T2 = T1 + t2, maka net present value (π1) dari bendungan dengan program
rehabilitasi adalah:
T1 T2
π1 = e-rt[pw(v) – ck]dt + e-rt[pw(v)]dt (26)
0 T1
Rehabilitasi layak dilakukan hanya bila:
T0 T1 T2
e-rt pw(v)dt <
e-rt[pw(v) –
ck]dt + e-rt[pw(v)]dt (27)
0 0 T1
Sebaliknya, bila persamaan ini tidak terpenuhi, rehabilitasi wilayah tangkapan bendungan tidak layak dilakukan.
DISKUSI
Bagian ini mendiskusikan implikasi dari model yang telah dibahas di muka, khususnya dalam menjawab pertanyaan apakah seluruh wilayah tangkapan harus direhabilitasi. Ada tiga peubah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu jangka waktu penuhnya waduk dengan bahan sedimen, jangka waktu rehabilitasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh wilayah tangkapan, dan jangka waktu tercapainya ψ(t) = c.
Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa rehabilitasi lahan sebesar k layak dilakukan jika ψ(t) >
c.
Jangka waktu hingga tercapainya ψ(t)= c, dicatat dengan T**, dapat lebih pendek daripada jangka waktu penuhnya waduk dengan sedimentasi ataupun jangka waktu merehabilitasi seluruh wilayah tangkapan dengan laju k per tahun. Jadi ada dua kemungkinan dimana rehabilitasi tidak perlu dilakukan pada seluruh wilayah tangkapan, yakni bila T** < T1 atau bila persamaan 23 tidak terpenuhi. Diskusi selanjutnya akan dibatasi hanya pada kasus pertama, karena masih sulit dimengerti oleh kebanyakan orang.
Apabila T** < T1 rehabilitasi lebih lanjut tidak akan meningkatkan Hamiltonian, meskipun masih tersedia lahan di wilayah tangkapan yang belum terehabilitasi dan umur waduk masih cukup panjang. Artinya, melanjutkan rehabilitasi wilayah tangkapan tidak akan meningkatkan net present value keuntungan yang diterima oleh pengelola bendungan. Hal ini tidak berarti bahwa rehabilitasi lanjutan terhadap wilayah tangkapan yang belum terehabilitasi tidak bermanfaat bagi pengelola bendungan dan lingkungan secara umum.
Rehabilitasi lanjutan dapat saja dilanjutkan dan berdampak positif pada keuntungan bendungan selama ψ(t) lebih besar dari biaya rehabilitasi yang harus ditanggung oleh pengelola bendungan, c. Bila rehabilitasi lanjutan tersebut dibiayai, sebagian atau seluruhnya, dengan anggaran pemerintah maka rehabilitasi lanjutan akan meningkatkan net present value keuntungan pengelola bendungan. Apabila rehabilitasi lanjutan ini dilakukan dengan bantuan anggaran
Ekonomi Rehabilitasi Daerah Tangkapan Waduk
30
pemerintah, maka inefisiensi terjadi pada penggunaan anggaran pemerintah tersebut. Publik harus menyadari bahwa rehabilitasi akan memperbaiki lingkungan, tetapi rehabilitasi juga membutuhkan biaya.
IMPLIKASI BAGI KEBIJAKAN PUBLIK
Beberapa implikasi bagi kebijakan publik perlu diangkat. Pertama, pengelola bendungan perlu ikut menanggung biaya konservasi dan/atau rehabilitasi wilayah tangkapan. Kedua, bila rehabilitasi perlu dan layak dilakukan, maka hendaknya rehabilitasi dilakukan dengan laju yang tinggi. Hal ini berimpllikasi pada atau ditentukan oleh anggaran yang tersedia. Ketiga, untuk menekan biaya konservasi dan/atau rehabilitasi, luas wilayah tangkapan hendaknya tidak berlebihan diukur dari kebutuhan untuk mencapai kapasitas waduk yang direncanakan. Hal ini berimplikasi pada pemilihan lokasi pembangunan bendungan.
Apabila wilayah tangkapan masih dalam keadaan baik, pengelola bendungan tidak perlu mengeluarkan biaya rehabilitasi. Jasa konservasi yang disediakan oleh wilayah tangkapan ini menjadi kurang disadari. Jasa wilayah tangkapan ini perlu mendapat penghargaan yang sepadan atas jasa konservasi yang telah dilakukan. Jasa ini harus dibayar oleh pengelola bendungan sebagai pihak yang telah menikmati jasa tersebut. Hal ini menjadi lebih jelas bila wilayah tangkapan tersebut dalam keadaan rusak atau kritis sehingga memberikan tingkat sedimentasi yang sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini, pengelola bendungan lebih mudah melihat dan merasakan perlunya wilayah tangkapan yang baik.
Rehabilitasi hendaknya dilakukan secepat mungkin. Hal ini implikasi dari penurunan nilai ψ(t) dengan waktu sebelum akhirnya menyamai biaya satuan rehabilitasi sebesar c. Apabila dana dan sumberdaya lain tersedia, rehabilitasi hendaknya dapat dituntaskan dalam jangka waktu T**, yakni pada saat ψ(t) = c. Rehabilitasi wilayah tangkapan setelah T** hingga waduk berhenti beroperasi
akan menimbulkan inefisiensi, yakni manfaat rehabilitasi lebih kecil dari biayanya.
Pemilihan lokasi pembangunan bendungan perlu mempertimbangkan optimisasi luas wilayah tangkapan dan kapasitas bendungan. Wilayah tangkapan yang terlalu luas akan menyebabkan biaya konservasi dan/atau rehabilitasi menjadi sangat tinggi. Sedimentasi dari wilayah yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi apapun terhadap supply air ke dalam waduk akan ikut memperpendek umur waduk tanpa memberi sumbangan pada terjadinya tenaga listrik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Model rehabilitasi wilayah tangkapan yang dikembangkan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak harus dilakukan di seluruh wilayah tangkapan. Rehabilitasi yang berlebihan dapat menimbulkan inefisiensi. Publik harus menyadari bahwa rehabilitasi dapat memperpanjang umur waduk. Tetapi rehabilitasi juga menimbulkan biaya yang belum tentu lebih kecil dari manfaat yang diperoleh.
Jasa konservasi wilayah tangkapan masih kurang disadari. Dalam membangun bendungan di masa mendatang perlu dibandingkan dua pilihan. Pertama, rehabilitasi wilayah tangkapan dahulu baru membangun bendungan. Kedua, rehabilitasi wilayah tangkapan dilakukan bersamaan dengan beroperasinya bendungan.
PUSTAKA
Chiang, Alpha C., Elements of Dynamic Optimization, Mc-Graw Hill, Inc, New York, NY, 1992.
Ledec, George dan Jaun David Quintero. 2004. “Good Dams and Bad Dams: Environmental Criteria for Site Selection of Hydroelectric Projects,” World Bank Working Paper (16): 20pp.
Media Konservasi Vol. IX, No. 1 Jun 2005 : 33 – 37
31
LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT OF MINANGKABAU LAND
(Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap Minangkabau)
NANDI KOSMARYANDI1)
1) Lecturer at Department of Forest Resources Conservation and Ecotourism, Faculty of Forestry, IPB
ABSTRAK
Dalam Suku Minangkabau, lahan dikelola secara komunal. Unit pengelolaan dilakukan melalui sistem nagari, dimana didalamnya diatur pola penggunaan lahan dan sistem waris. Perkembangan dalam pola penggunaan lahan, baik disebabkan oleh pertambahan populasi penduduk maupun perubahan orientasi penggunaan lahan menjadi lebih berorientasi ekonomi dapat menjadi penyebab hilangnya sistem adat dalam manyarakat Minangkabau ini. Sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai adat serta sebagai upaya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kharakteristik lingkungan setempat maka dipelukan panduan pengelolaan lansekapnya.
Kata kunci : Minangkabau, lahan, sistem adat, lansekap
THE MINANGKABAU TRADITIONAL LAND USE
Traditional land use is judicious utilizing of nature resources. This is the result of long-term experience of natural resources, natural indicators and the natural limits of human life. Thus they know how to deal with and treat the environment, where to live, which resources can be used and which resources must be preserved. They know what amount of resources can be harvested in certain time. This knowledge is passed from one generation to the next and it has become traditional wisdom.
The land system of the Minangkabau is a community property system: they allow land use in cluster patterns. They build the nagari with housing as a centre, farmland surrounds the centre on flat areas and forestlands are situated at outer part on hilly areas. This system creates simple infrastructure development in a village. Concen-tration of housing provides the communities with easier social interaction. Farmland is situated close to the housing because rice fields need intensive planting and water management. Forestland and mixed cash crop land is situated on hilly areas because it is known that the soil fertility in those areas are unsuitable for annual plants and have a high risk of soil erosion.
Farmland
Rice fields
The basic village crop is rice. Because of the high rainfall, it is possible to grow rice at two times per year. The quality of the rice field varies greatly according to the access to irrigation water. Some fields in the lower areas of the village are too wet to grow any rice at all, even without any irrigation system. A few rice fields can be irrigated for
rice cultivation twice a year. Irrigation is practiced both by rainwater and by a number of channels that bring water to the fields from springs and streams, having their source higher up in the mountain. Inefficient irrigation systems and the irregularity of the land in the mountain area result in over all insufficiency of water supplies to the sawah. The cultivation of rice on irrigated fields essentially needs constant water flow through the submerged fields.
Based on that cultivation technique, it is can understood that traditional rule allocated rice field on plain land and on wetland physical soil condition. The location of the rice fields is always close to the housing, because both need permanent water supply and the management of the rice field is more demanding than any other cultivation.
Cash Crops Area
The common commodities that planted in house hold plantations are rubber, coconut palm, palm oil, cinnamon, coffee, gambir (ingredient used in betel chewing, tanning, and dyeing), cacao, sugar cane, and clove tree. The diversification of commercial trees creates modified canopy stratification: the upper stratum consists of rubber and fruit trees, the middle stratum is dominated by cinnamon and coffee and the lower stratum covers perennial crops, i.e., chili, eggplant and galingale a plant of the ginger family.
First planting usually starts with coffee or rubber, for cover are used dadap (flowering trees of Erythrina spp.) or fruit tree. The perennial crops take advantage of the cover of the trees. However, after three years, the canopy of the trees eventually will close preventing the farmers to plant perennial crops. To compensate this, the farmers change the perennial crops to cinnamon trees (Cinamomum spec.). In some cases, farmers are forced to utilize forestland
Landscape Planning and Management of Minangkabau Land
32
through land clearing. Cultivation on this type of land can lasts two to three years only due to the intensive erosion and leaching of the soil matters.
Forestland
In former days, forest territories were decided among clans/lineage. Lineage determined the borders after a series of consultation among them. However, they had no limitation on clear cutting of the forest, which means that they could open the forest as far as they wanted.
Traditionally, forestland was allocated as a reserve area. Only the good quality trees were harvested for construction, especially for the poles of traditional houses. Based on the adat, the size and status of the forestland was not changed. These areas were inherited as hutan tinggi owned by the nagari or clan. In the meantime, the vegetation cover of these areas is changing. The more economic oriented led to the conversion of the forestland into mixed cash crop land, creating a higher risk for soil erosion. Whereas, the soil structure and soil type cannot support that changing. Most of this forestland is situated on high slope areas and the management of the mixed cash crops cultivation is quite extensive. In the meantime, some areas become secondary forests again. Nevertheless, in November 2000, there were landslides and floods in most highland areas of the west side of West Sumatra Province.
According to the physical condition and economic oriented, it is needed management based on ecological aspect combined with economic oriented that can keep forest functions. This input especial for the forestlands where were change.
Residentral Patterns
According to the traditional rule, a nagari can be built if it includes the following elements: adat house, mosque, and water source to take a bath and other household purposes and access/road (barumah gadang, bamusajik, batapian tampek mandi dan balabuah). All houses in the village are connected by a network of roads and unpaved paths, some also passable to motor traffic, other only by foot. In fact these roads and paths form the focus of housing. Most houses are strung out evenly on both sides of the roads.
Traditionally, the residential buildings (Rumah Gadang) were built stretch along from west to east, to avert the house from direct solar insulation and keep the air inside the house cool. But there is another argument, that Rumah Gadang are built look out Mt. Merapi, which is considered as a legend. Since roads are constructed, this is also affects to the position of Rumah Gadang and others houses. Many of them are built parallel to the roads.
The traditional Minangkabau house, of which only a few still remain, is a large and impressing construction, rising up to 2 m high above ground, with a characteristically sloped roof, and a communal surau nearby where the men and boys live. Because of tradition to leave homeland area, many Rumah Gadang are un-resident and that some of them are damage.
The rule about housing lay out was not found as long as research was been held. The new houses built follow the roads and can built surrounding Rumah Gadang. Adulteration of housing site in some villages was occurring. But this is based on family agreement. The sites where used for new houses are for the most part of site of rice fields, because that sites is situated close with settlement area. Scheme of village land use ca be shown in Figure 1 that created by Scholz (1997).
PRESENT SITUATION OF THE MINANGKABAU LAND USE
Up to now, the Minangkabau people keep the land use system based on traditional rules. No drastic changing of land status in a village. The allocation land accordant the traditional rule can be seen in most of villages in hearth land of Minangkabau. This is happened because of the tradition to leave home area makes the population in hearth land of Minangkabau is not rapidly increase. In Tanah Datar District as a sample, average population growth in last ten years is 0.68% per years. This condition makes low land dependence.
In village forestland, the changing that happens is land cover change. Some parts of the forestland have been changed to mixed cash crop trees, fruit trees and perennial crops. Due to only extensive cultivation systems, shrub and imperata grass is growing in some areas.
Also there is little changing in extend of housing site. All this time, the new houses built at open space near the old house or Rumah Gadang. No exact rules are found in space arrangement surrounding Rumah Gadang. But in few chases occurred houses development outside traditional housing site. The site where the new houses built is the plot of rice field, because it is close with the settlement area. This decision was happened after consensus in a family was reached.
Although land is owned communally and kaum land is cultivated by denizen together, every one can work on land for subsistence with the right of land use. The extent of the right of land use depends upon the ability to work and the availability of land. Minangkabau society has an assumption that all of land in their borough, including virgin forestland is ulayat land. Consequently, transferring ulayat land to the government always needs adat procedures. But transferring land of ulayat suku or kaum surrounding the village needs a retribution fund (Navis, 1980).
Media Konservasi Vol. IX, No. 1 Jun 2005 : 33 – 37
33
LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT FOR PRESERVATION OF LAND AND CULTURE
Landscape planning is a method for creating suitable land for living and the preservation of natural resources. The consideration of environmental conditions has become an important aspect of this. One method of knowing the rules for using natural resources is based on traditional land use that has been adapted to the environment. Traditional values (adat) provide easier solutions for managing the environment.
Taking this into consideration, the development can preserve the culture, which in fact can support sustainable development. In this study, analysis of the scientific aspects of land use confirms that traditional rules for land suitability in the highlands of West Sumatra are perfectly responsible. The Minangkabau traditional rules give land use planning basis as follows : Land allocation for protected and cultivated areas Land suitability based on degree of slope and soil
characteristics Land allocation with cluster pattern for housing,
agriculture and forest. Housing with linear pattern
Based on soil characteristics, management systems must take care with the conversion of forestland to cultivated land, which brings on cover changes takes to the high risk of soil erosion in inclined areas. Traditionally, slope areas are covered by forestland but as a consequence of population growth, economic orientation and the disappearance of the function of the nagari consultative forum, land functions have changed. Some forestland areas are planted with perennial crops based on economic orientation. But this situation has taken place spontaneously and without good planning. An example of this occurred some years ago in Sumanik Village (Tanah Datar Distric): the people planted clove trees when the market price was high, but when the time came to harvest the cloves, the price had decreased. Now the clove trees are neglected and the land has become more open. In such a situation there is a need for and input of technology for the recovery of land cover as well as a need for market research for information about marketable commodities.
In the study area, following the traditional rule most rice fields cover andosol soils from tuff volcanic and red-yellow podzol (spodosols) from alluvial genesis. Mixed cash crops and forests however cover red-yellow podzol (ultisol) and andosol soil.
Based on Twardy (1995), land evaluation of rice fields in spodosol soil areas is also needed because agricultural activity in these areas requires high input production. It is should be changed with perennial crops. Forest areas grow on ultisol and oxisol soil. It is better to maintain this
condition rather than converting the land because these soils are highly erosive and need high input production and technology for agricultural use.
The application of an agroforestry system could be possible in an area where forest has become secondary forest as a consequence of extensive use. Agroforesty is a system of land management based on the sustainability of yield increase of plants by combining forest plants and economically oriented plants and/or domesticated animals with a management system based on local culture. For this solution research is needed in order to know which agroforestry systems can be used and which kind of trees can be planted in accordance with the economic aspects and agro-climatic conditions.
Another input is needed for applying the traditional rules based on ecological aspects for sustainable development. This input is watershed management. Water bodies are important sources for human activities; therefore management of water sources and riversides is needed. It is important to maintain forestland as catchment’s areas because one forest function is hydrological arrangement. The arrangement of buffer zones along riversides reduces erosion by water flow and distils the high input of nutrients into the rivers, because the farmers use fertilizers in agricultural management. The designing of buffer zones should be done along riversides. The application of this technique needs socialization and consultation with the landowners, because buffer zone areas will use private or community lands. Based on the Presidential Decree No 32/1990, the breadth of a buffer zone for big rivers (more than 200m breadth) is 100 meters at each side of the river and 50 meter for tributaries located outside of a settlement area. For rivers located in settlement areas, riverside borders must be 10 to 15 meter or approximately enough to build inspection roads. Plant cover is made up of a combination of shrubs, bushes to trees. In this case one could choose fruit trees, bamboo, or perennial trees, which have economic significance. Based on this management, the sketch of land use management can be seen at Figure 2.
Traditionally, a nagari was decided as autonomous and self-sufficient community, accordingly the village system must return to the nagari system and re-function the nagari consultative forum in order to manage the nagari land. But some aspects of management should be introduced to improve the nagari form of management. The knowledge of the ninik mamak and penghulu about planning, organizing, actuating, and controlling should be re-introduced and improved. This is important because in the future the problem of nagari management will more complex. It is related to social and economic development, lands limit for extensive management system and the changing of the culture.
Landscape Planning and Management of Minangkabau Land
34
.
Figure 1. Village land use, an example at Rambatan Village (Source: Scholz, 1977)
Figure 2. Guidance of land use management for highland area in Minangkabau Land
Media Konservasi Vol. IX, No. 1 Jun 2005 : 33 – 37
35
REFERENCE
Navis A.A. 1980. Hak Ulayat, Landreform dan trasmigrasi di Sumatra Barat. Paper in workshop of Penataran Hukum Tanah untuk Lembaga-lembaga Swasta Pembina Swadaya Masyarakat Desa. Jakarta 1980.
Scholz, U. 1997. Minangkabau: die Agrastruktur in West Sumatra un Moglichkeiten ihrer Einwiklung. Geographic Institute. Giessen University. Germany.
Twardy, A.G. 1995. Soil quality standards for Indonesia. Environmental Management Development in Indonesia Project (EMDI), Dalhousie University Printing Centre. Canada
GLOSSARY
adat traditional prescriptive law in Indonesia tradition, customary law balai adat consultative hall in Minangkabau village hutan nagari nagari forestland kaum family, lineage musajik (masjid) mosque nagari Minangkabau village ninik mamak the grand matriarch penghulu clan chief rumah gadang big house, traditional house of Minangkabau sawah irrigated rice field suku clans surau prayer house ulayat land or territory, village land property
PETUNJUK FORMAT PENULISAN ARTIKEL UNTUK MEDIA KONSERVASI
1. Naskah berupa tulisan ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau studi pustaka. 2. Naskah diketik 2 spasi dalam kertas kuarto dengan jumlah halaman maksimum 15 halaman; sebanyak 2 eksemplar
disertai disket file naskah. Pengiriman naskah yang telah diterima disertai dengan satu disket ukuran 3.5” (disket kecil) berisi file naskah yang dikirimkan menggunakan program olah kata Word for Windows 95/98.
3. Untuk naskah/artikel asli harus disenaraikan dalam Judul, Identitas Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan (dan Saran), dan Ucapan Terima Kasih, Daftar Pustaka dan Lampiran. 3.1 Judul harus tegas dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 3.2 Identitas penulis berisi nama lengkap penulis (hindari penggunaan singkatan) dan dibubuhi angka arab secara
berurut untuk keterangan tentang penulis (bila lebih dari satu penulis). Alamat lengkap penulis berisikan laboratorium asal penulis, lembaga dan alamat lengkap dengan nomor telpon, faksimili dan e-mail yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat.
3.3 Abstrak (maksimal 300 kata) ditulis dalam Bahasa Inggris apabila naskah berbahasa Indonesia dan sebaliknya. 3.4 Kata kunci/Keywords (5 – 8 kata). 3.5 Metode Penelitian diuraikan secara rinci dan jelas. 3.6 Hasil dan Pembahasan digabungkan. Tabel dan gambar dapat digabungkan atau dipisah dengan bagian ini disertai
keterangan yang jelas. Foto berwarna atau hitam putih dapat dikirim dengan ukuran 9 x 13 cm (maksimum). Biaya untuk proses separasi foto akan dibebankan kepada penulis dan segera dikirim ke Redaksi sebelum majalah ini dicetak. Grafik yang diperoleh dari hasil pengolahan data dikirim dalam file yang terpisah dari file artikel yang disertai nama program penyusunan grafik dan disertai data dasarnya.
3.7 Daftar Pustaka disusun menurut sistem nama dan tahun. Disusun menurut abjad nama belakang penulis dengan urutan sebagai berikut: Nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap, nama publikasi/penerbitan, nomor publikasi dan halaman (untuk majalah/journal).
Contoh Pustaka: Buku Kuijt; J. 1969. The biology of parasitic flowering plants. University of California Press; Berkeley and Los Angeles.
Bab dalam Buku Lovejoy, T.E. & D.C. Oren. 1981. The minimum critical size of ecosystem, hlm. 7 – 12. Di
dalam R.L. Burges & D.M. Sharpe. 1981. Forest island dynamics in man-dominated landscapes. Springer-verlag. New York.
Majalah/Journal Meijer; W. 1985. A contribution to the taxonomy and biology of Rafflesia arnoldii in West
Sumatra. Anneles Bogoriense 3 (1):33-34.
Prosiding Turner, S. 1994. Scale, observation and measurement : critical choices for biodiversity
research, hlm. 97-111. Di dalam T.J.B. Boyle & B. Boontawee (ed.). 1995. Measuring and monitoring biodiversity in tropical and temperate forests. Proceeding of a IUFRO Symposium August 27th – September 2nd, 1994. Center for International Forestry Research. Bogor.
Website/Internet MacCracken, M.C. 1995. Climate change : The evidence mounts up. Http: //www.vsgcrp.gov/
vsgcrp/mmnature.html