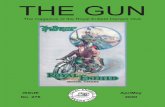276 BAB V PRAKTIK TRANSFORMASI KONSEP PEMBAGIAN ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of 276 BAB V PRAKTIK TRANSFORMASI KONSEP PEMBAGIAN ...
276
BAB V
PRAKTIK TRANSFORMASI KONSEP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
(ACCESS AND BENEFIT SHARING/ABS) SEBAGAI HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN THAILAND
SERTA PERBANDINGAN KEDUANYA
Bab ini menguraikan mengenai Praktik Transformasi Konsep ABS di
Indonesia dan Thailand. Sebagai jawaban atas rumusan masalah ketiga, uraian
diawali dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam hukum internasional
sebagai basis pengaturan dalam ABS. Seterusnya dipaparkan pengaturan ABS dan
perbandingan praktiknya di Indonesia dan Thailand serta diakhiri dengan uraian
mengenai pengembangan hukum ke depan baik yang terkait transformasi hukum
internasional secara umum maupun terkait transformasi perjanjian internasional
CBD dan Nagoya Protocol guna mewujudkan hak masyarakat hukum adat atas
pembagian keuntungan atas akses sumber daya genetiknya.
A. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (Access and
Benefit Sharing) dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
1. Pengakuan Hukum Internasional atas Hak Masyarakat Hukum Adat
Berkaitan Dengan Access and Benefit Sharing Pemanfaatan Sumber Daya
Genetik
Pengakuan hukum internasional terhadap kelompok masyarakat hukum
adat merupakan pengakuan berbasis hak asasi manusia. Hukum internasional
menyediakan sejumlah intrumen hukum guna memajukan hak-hak masyarakat
hukum adat yaitu Konvensi International Labour Organization/ILO 1989 Nomor
169 tentang Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, Konvensi
ILO Tahun 1957 Nomor 107 tentang Indigenous and Tribal Population dan yang
paling komprehensif adalah United Nation Declaration the Rights of Indigenous
277
People Tahun 2007.
Berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat atas sumber daya
alam, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 serta Pasal 15 Konvensi ILO 1989 Nomor
169 yang pada prinsipnya menentukan bahwa pemerintah harus menghormati
budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat hukum adat yang terkait dengan
hubungan mereka dengan tanah dan sumber daya alamnya, khususnya aspek
kolektif dari hubungan ini. Hak-hak kepemilikan dan penguasaan masyarakat
hukum adat atas tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Bahkan
dalam ketentuan Pasal 15 penegasan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat
juga dibarengi dengan prinsip HAM free prior informed consent (FPIC) bahwa:
(1) Hak-hak masyarakat hukum adat dan orang-orang pribumi yang
bersangkutan atas sumber daya alam serta berkaitan dengan tanah dan
wilayah mereka harus dilindungi secara khusus. Hak-hak ini termasuk hak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan
konservasi sumber daya alam.
(2) Dalam kasus dimana Negara mempertahankan kepemilikan sumber daya
alam di bawah permukaan tanah atau hak atas sumber daya lain yang
berkaitan dengan tanah, Pemerintah harus menetapkan prosedur dimana
pemerintah akan berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat, dengan
maksud untuk memastikan kepentingan masyarakat hukum adat tidak
dirugikan dan masyarakat hukum adat harus sedapat mungkin berpartisipasi
dan mendapat manfaat dan menerima kompensasi yang adil untuk setiap
kerusakan yang mungkin dialami akibat dari kegiatan tersebut.
Walaupun perjanjian-perjanjian internasional tersebut yang berbentuk
Deklarasi tidak mengikat negara-negara atau sering disebut soft law, namun
mendapat dukungan luas dari negara-negara sehingga prinsip-prinsip deklarasi dan
konvensi tersebut dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.1
1 S. James Anaya, op. cit., halaman 984, diakses pada
https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2385&context=articles.
278
Awalnya, negara-negara mengakui eksistensi masyarakat ini baik secara
resmi maupun secara informal yang direfleksikan dalam pengakuan atas kedaulatan
wilayah dan sumber daya alamnya. Dari sudut pandang hukum, aspek utama dari
masalah pengakuan kelompok masyarakat hukum adat bertalian di seputar
bagaimana mengenali suatu kelompok dengan kareakteristinya yang bersangkut
paut dengan dua dimensi mengenai pengakuan yaitu, dimensi eksternal bagaimana
pihak luar memandang dan berhubungan dengan kelompok masyarakat hukum
adat. Hal ini akan merujuk pada bagaimana sistem nilai yang dianut, apa kekuatan
dan tindakan-tindakan apa yang menjadikan mereka terikat. Kedua, dimensi
internal yaitu bagaimana anggota kelompok berhubungan dan mengelola
kelembagan serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Begitu kelompok
tersebut diberikan pengakuan formal fungsi pengakuan sesungguhnya diharapkan
memperkuat keterikatan group.2
Pada bagian lain The World Commission on the Social Dimension of
Globalization yang digagas oleh ILO pada tahun 2002 melalui progress report
dengan topik ‘A fair Globalization Creating Opportunities for All’ membahas
implikasi dari globalisasi terhadap kehidupan ekonomi dan sosial dalam rangka
menyerasikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Komisi mengakui bahwa
diperlukan dukungan dan upaya untuk melindungi dan menghormati hak-hak
masyarakat hukum adat utamanya hak atas wilayah dan sumber daya alamnya
termasuk pentingnya penerapan prinsip free and prior informed consent (FPIC).
2 J.S. Fingleton, Legal Recognation of Indigenous People, FAO, 1998, halaman 7,
diakses pada https://www.fao.org/3/bb034e/bb034e.pdf.
279
Pihak luar saat akan berkegiatan pada wilayah masyarakat hukum adat harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum kegiatan suatu proyek dimulai.3
Pemenuhan keadilan melalui pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat
atas sumber daya genetik dapat membawa dampak positif terhadap pelestarian
lingkungan karena sebagian besar pusat keanekaragaraman hayati yang di
dalamnya terdapat sumber daya genetik berada dan dijaga dalam wilayah
masyarakat hukum adat yang sangat berguna dalam menopang hidup dan
kehidupan manusia.
Pengakuan hukum internasional atas hak masyarakat hukum adat adalah
UNDRIP dan Deklarasi Amerika Serikat tentang Hak dan Kewajiban Manusia.
Dalam kasus pada The Inter-American Court of Human Right antara Saramaka
People v. Suriname yang mempersoalkan konsesi penebangan dan pertambangan
yang diberikan oleh Suriname terkait properti komunal yang secara tradisional
ditempati oleh Komunitas Saramaka telah mengancam kelangsungan hidup fisik
dan budaya mereka. Pengadilan mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) dan (2) Konvensi
Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 21 mengakui bahwa setiap
orang berhak untuk menggunakan harta miliknya dan penggunaannya sepenuhnya
tunduk pada kepentingan masyarakat.4
Deklarasi tersebut serta berbagai konvensi internasional memberikan
dukungan bagi masyarakat hukum adat dalam perjuangan mereka untuk
3 Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples)”, Padjadjaran Jurnal ilmu
Hukum, Vol. 1 (2), 2014, halaman 324. 4 Taisi Copetti, “The rights of Indigenous People under International Law”, 2019,
halaman 2, diakses pada
https://www.academia.edu/39328532/The_rights_of_indigenous_peoples_under_international_law
.
280
melestarikan kelangsungan hidup dan budaya dalam menghadapi proyek-proyek
pembangunan ekonomi yang dikenakan pada mereka yang mengancam kelestarian
lingkungan mereka. Kasus-kasus hukum internasional mengenai kelompok pribumi
atau masyarakat hukum adat ini menyiratkan bahwa masyarakat tersebut memiliki
hak menentukan identitas mereka sendiri yang diakui oleh pengadilan serta dijamin
dalam dokumen internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UNDRIP
bahwa:
(1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan identitas atau
keanggotaan mereka sesuai dengan hukum adat dan tradisi mereka. Hal ini tidak
mengurangi hak individu masyarakat hukum adat untuk memperoleh
kewarganegaraan negara tempat mereka tinggal.
(2) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan struktur dan untuk
memilih keanggotaan lembaga mereka sesuai dengan prosedur mereka.
Titik balik komitmen internasional terhadap isu-isu hak masyarakat hukum
adat adalah Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1971 yang mengesahkan
Subkomisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas,
sebuah badan penasehat ahli antar pemerintah Komisi Hak Asasi Manusia untuk
melakukan studi tentang Masalah Diskriminasi terhadap Penduduk Asli. Pelapor
khusus Jose Martines Cobo membuat serangkaian rekomendasi guna mendukung
tuntutan masyarakat hukum adat. Berdasarkan rekomendasi studi Martines Cobo
dan perwakilan dari kelompok masyarakat hukum adat, Komisi HAM PBB dan
badan induknya Dewan Ekonomi Sosial PBB pada tahun 1982 menyetujui
pembentukan kelompok kerja PBB untuk masyarakat hukum adat. Kelompok kerja
ini dibentuk sebagai bagian dari Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan
Perlindungan Minoritas dengan mandat untuk meninjau perkembangan yang
berkaitan dengan promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar masyarakat
281
hukum adat serta memberikan perhatian khusus mengenai standar hak-hak
masyarakat hukum adat.5 Seterusnya, kelompok kerja mendorong inisiatif untuk
memperkuat eksistensi masyarakat hukum adat dan mengembangkan draft
Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
Studi Martinez Cobo menjadi standar acuan dalam persiapan konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi)
tahun 1992 dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sejumlah instrumen
hukum yang diadopsi pada KTT Bumi, seperti Deklarasi Rio, Agenda 21 dan
Konvensi Keanekaragaman Hayati telah menetapkan standar hukum internasional
untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas pengetahuan dan praktik
tradisional mereka di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Hal penting
yang dicapai adalah terdapat kerangka hukum internasional yang mengakui
hubungan unik yang dimiliki masyarakat hukum adat dengan tanah, sumber daya
alam dan lingkungannya.
Masyarakat hukum internasional menyadari bahwa peran strategis
masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya genetik sangat menentukan.
Piagam Bumi Masyarakat Hukum Adat memang tidak dimasukan ke dalam
negosiasi CBD saat The Earth Summit 1992 namun pengakuan yang signifikan
tercantum dalam konsideran CBD bahwa:
Mengakui ketergantungan yang erat pada tradisi masyarakat hukum adat dan
komunitas lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional pada sumber daya
hayati, dan keinginan untuk berbagi keuntungan secara adil yang timbul dari
penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, inovasi dan
praktik yang relevan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan
pemanfaatannya secara berkelanjutan.
5 S. James Anaya, op. cit., halaman 985.
282
Pengakuan ini menyiratkan ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat
dengan sumber daya genetik yang membentuk kosmologi, budaya, dan kehidupan
spiritual yang tidak terpisahkan dari alam yang dijaga dan dikelola secara turun
temurun. Perkembangan industri bioteknologi atas pemanfaatan sumber daya
genetik yang masif dan bernilai ekonomi telah memunculkan perlawanan
masyarakat hukum adat terhadap pengambilan bebas sumber daya genetiknya.
Ketidakadilan ini karena manfaat dari sumber daya genetik tersebut sebagian besar
dimanfaatkan industri negara-negara maju yang menikmati keuntungan atas akses
dan pemanfaatan sumber daya genetik yang dianggap suatu public goods yang
bersifat common dan karenanya bisa diakses bebas tanpa izin tanpa kompensasi.
Sesuai dengan Konvensi keanekaragaman Hayati Tahun 1992 dan Nagoya
Protoccol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of
Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity
Tahun 2010 yang membentuk kesepakatan tentang serangkaian prosedur dan hak
dan kewajiban para pihak dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban para pihak
melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 8 j (1) CBD.
Kewajiban ini termasuk penghormatan oleh pengguna sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisional terkait tentang akses dalam hukum nasional dan peraturan
perundang-undangan sistem ABS. Dengan demikian negara-negara harus mengatur
atau mentransformasikan sistem pembagian keuntungan yang adil dan seimbang
atas pemanfaatan sumber daya genetik masyarakat hukum adat dalam hukum
nasionalnya
Perkembangan penting dalam pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat
283
dan hak-haknya adalah dengan dibentuknya United Nation Declaration Right of
Indigenous Peoples/UNDRIP dalam suatu sidang Majelis Umum PBB pada tanggal
13 September 2007. Di tingkat internasional, UNDRIP dapat dikatakan perjanjian
internasional soft law yang penting bagi perlindungan dan rekognisi hak-hak
masyarakat hukum adat yang membawa harapan bagi pemenuhan hak masyarakat
hukum adat.
Ketentuan Pasal UNDRIP menentukan hak masyarakat hukum adat atas
sumber daya alam bahwa:
1. Masyarakat hukum adat memiliki ha katas tanah, wilayah dan sumber daya alam
yang secara tradisional mereka miliki dan tempati.
2. Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan dan menguasai tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan
alasan kepemilikan tradisional lainnya, serta yang mereka peroleh dengan cara
lain.
3. Negara-negara harus memberikan pengakuan dann perlindungan hukum
terhadap tanah-tanah tersebut wilayah dan sumber daya alam. Pengakuan
tersebut harus dilakukan dengan menghormati hukum adat, trasdisi dan sistem
kepemilikan tanah masyarakat hukum adat.
Adapun pengakuan negara atas masyarakat Hukum Adat dalam kerangka
instrumen Hukum Nasonal terdapat dalam UUD 1945 sebelum Amademen,
khususnya pada Penjelasan Pasal 18 bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250
daerah-daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti
marga, desa, dusun dan negeri. Adapun dalam UUD 1945 hasil amademen dan
peraturan perundang-undangan, ditemukan perumusan yang sama bahwa
masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
284
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.6
Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 lengkapnya menentukan
bahwa:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum
Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
UUD 1945 tidak menentukan siapakah yang dimaksud dengan masyarakat
Hukum Adat.7 Namun, ketentuan Pasal 18B ayat (1) ditafsirkan bahwa eksistensi
masyarakat Hukum Adat diakui dan dijamin oleh Konstitusi namun pengakuan
tersebut kondisional karena terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi yaitu
“sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang diatur dalam undang-undang”.
Unsur-unsur untuk dikukuhkannya suatu komunitas sebagai masyarakat
Hukum Adat justru ditemukan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41
6 Lies Sugondo, Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional, Makalah
pada Advanced training hak-hak masyarakat adat (Indigenous peoples rights) bagi dosen pengajar
HAM di Indonesia, diselengarakan oleh Pusham UII-Noerwegian Centre for Human Rights,
Yogyakarta tanggal 21-24 Agustus 2007, halaman 4. 7 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
yang mengakui eksistensi masyarakat Hukum Adat dengan gaya perumusan yang sama, juga tidak
mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan masyarakat Hukum Adat.
285
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat
akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-
undang. Sementara unsur-unsur untuk adanya pengakuan adalah:
1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah Hukum Adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih
ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya
untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Memperhatikan unsur-unsur tersebut dan membandingkannya dengan
kondisi sekarang, sulit untuk menemukan siapa yang dimaksud dengan masyarakat
Hukum Adat. Ada beberapa komunitas adat yang sebenarnya eksis, namun tak bisa
diakui sebagai masyarakat Hukum Adat, karena tak memenuhi unsur salah satu
unsur apabila unsurnya kumulatif.
Kewenangan untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat
Hukum Adat adalah kewenangan pemerintah daerah, melalui pengukuhan dalam
peraturan daerah. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) bahwa: “Pengukuhan keberadaan dan
hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.” Penjelasan Pasal ini menjelaskan bahwa Peraturan
daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar Hukum
Adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah
286
yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Dengan demikian
pengakuan atas eksistensi masyarakat Hukum Adat menjadi tidak hanya bersyarat
tapi juga berlapis.
Menurut Maria Sumardjono, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak
ulayat dihubungkan dengan eksistensi masyarakat hukum adat adalah:8
a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai
subyek hak ulayat;
b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang
hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta
perbuatan-perbuatan hukum.
Persyaratan tersebut di atas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, hal itu
merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan
masyarakat hukum adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi
pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat hukum adat, tapi membantu
para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat hukum
adat.
Keberadaan masyarakat hukum adat umumnya ditandai dengan sejumlah
praktek usaha perladangan dan pertanian, penggembalaan ternak, pemburuan satwa
liar dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal hutan dikelola secara lestari
8 Ade Saptomo, Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 15.
287
oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber kehidupannya dengan segala
kearifannya.
Berbagai praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dikenal
dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada
masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di
Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada
masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktek tersebut menunjukan bahwa
masyarakat adat telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya
secara turun-temurun.
Praktik pengelolaan sumber daya alam telah ada sebelum lahirnya negara,
demikian juga dengan masyarakat hukum adat. Dengan demikian pengelolaan
sumber daya alam berbasis kearifan lokal atau hukum adat telah dilakukan oleh
masyarakat hukum adat mendahului kelahiran negara.9 Praktik tersebut
diformalkan melalui UUPA yang menegaskan hukum adat adalah sumber hukum
agraria. Dengan adanya sejumlah masyarakat hukum adat yang hidup di dalam dan
sekitar kawasan hutan yang dipenuhi praktik konservasi sumber daya genetik, maka
penerapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum
menjadi signifikan dampaknya kepada masyarakat hukum adat guna melindungi
hak-hak tersebut di tengah semakin besarnya kepentingan untuk memanfaatkan
sumber daya alam mereka.
Indonesia sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum
9 Ade Saptomo, ibid., halaman 13.
288
adat. Adanya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang
telah sekian lama disusun namun belum menampakkan titik terang untuk disahkan.
Berdasarkan daftar tahun 2022 RUU tersebut masuk kembali dalam dafatr program
legislasi nasional/Proglegnas10 yang diprioritaskan untuk disahkan menginggat
pentingnya bagi perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keberlanjutan
lingkungan. Berbeda di tingkat lokal pengakuan terhadap masyarakat hukum adat
telah dikukuhkan dalam beberapa peraturan daerah.11
Berdasarkan gambaran pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam
hukum internasional dan nasional dapatlah dikatakan pengakuan yang telah dijamin
dalam hukum nasional dan internasional ini tidak akan bermakna tanpa ada
pemenuhan hak mereka secara progresif di tingkat lokal.
2. Pengaturan Access and Benefit Sharing/ABS dalam Hukum Internasional
a. Perjanjian Internasional Convention on Biological Diversity/CBD
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan pada tahun 1992 di
Rio de Janerio Brazil menghasilkan Konvensi Keanekaragaman Hayati
(Convention on Biological Diversity/CBD) yang dibangun atas tiga tujuan yaitu
konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan dari
10 DPR RI, “Program Legislasi Nasional Prioritas 2022”, diakses pada
https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak
Ulayat Masyarakat Badui; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten
Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta; dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas;
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015, yaitu sebanyak 519 kasepuhan yang
terdiri dari kasepuhan inti, kokolot lembur dan gurumulan rendangan.
289
komponen-komponennya dan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas
manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.
Nagoya Protocol Tahun 2010 mengembangkan tujuan ketiga dari akses dan
pembagian manfaat (access and benefit sharing/ABS) dengan memperhitungkan
peran penting masyarakat hukum adat beserta pengetahuan tradisionalnya. Di
sepakatinya sistem ABS didorong oleh para pemangku kepentingan negara
berkembang yang mengkhawatirkan eksplotasi sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisional mereka.12
Ketentuan Pasal 8j dan Pasal 10c CBD menuntut para pihak melindungi
masyarakat hukum adat, pengetahuan tradisional, praktik dan gaya hidup yang
relevan dengan konservasi keanekaragaman hayati.
Pasal 8j
Pasal 15 ayat (7) CBD yang menegaskan bahwa:
Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya
kebijakan, dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-
lainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan
sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang
disetujui bersama.
Ketentuan pokok dalam CBD yang bersinggungan dengan ABS adalah
Pasal 15 yang meneguhkan bahwa mengakui hak kedaulatan negara atas sumber
daya alam mereka, kapasitas untuk mengatur akses ke sumber daya genetik berada
di pemerintah nasional dan tunduk pada undang-undang nasional. Ketentuan Pasal
15 ini mengandung makna bahwa negara adalah pemilik sumber daya genetik di
12 Broggiato et al, op. cit., halaman 13.
290
wilayah mereka. Negara memiliki wewenang tunggal dan eksklusif untuk mengatur
akses ke sumber daya genetik. Dengan demikian tanggung jawab untuk
menjalankan wewenang ini dilimpahkan ke pemerintah nasional.13 Kewenangan
pemerintah untuk menentukan akses ke sumber daya genetik harus diatur dan
dipastikan, sesuai dengan undang-undang nasional. Otoritas ini diakui berasal dari
hak kedaulatan Negara atas sumber daya alam mereka. Jika sumber daya genetik
termasuk dalam hak milik nasional maka itu adalah masalah yurisdiksi nasional.
Sementara itu bertalian dengan syarat dan ketentuan akses bahwa ungkapan
pertama terkait Pasal 15 adalah kata ‘tepat’ yang berhubungan dengan syarat atau
ketentuan akses ke sumber daya genetik. Akses ini dapat ditentukan oleh suatu
Pihak yang menyediakan sumber daya genetik. Referensi hak atas sumber daya
genetik memberi pertanda bahwa status hukum sumber daya genetik merupakan
pertimbangan utama Konvensi yang tunduk kepada masing-masing pihak yang
berjanji untuk mengklarifikasi dan menetapkannya dalam hukum nasionalnya.
Dalam konteks tersebut, pembagian manfaat menunjukan pertukaran antara
penyedia yang memberikan akses ke sumber daya genetik dan Users yang
memberikan manfaat atau kompensasi dari akses sumber daya genetik. Berbeda
dengan konsep warisan bersama (common heritage of mankind), dalam konsteks
sumber daya genetik negara memegang hak berdaulat atas sumber daya alam dann
negara dapat memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan untuk
memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai prinsip persetujuan atas dasar informasi
13 Grethel Aguilar, op. cit., halaman 247.
291
awal (free prior informed consent/FPIC) dan persyaratan yang disepakati bersama
(mutual agreement term/MAT).
Konsep ABS dalam pemanfaatan sumber daya genetik berasal dari CBD
yang mengakhiri era konsep warisan bersama umat manusia. Di dalam pembukaan
CBD sumber daya genetik dianggap sebagai kepentingan bersama bukan warisan
bersama umat manusia. Tahapan ini adalah konsern seluruh umat manusia untuk
melestarikan dan mempertahankan penggunaan sumber daya genetik untuk
kemanusiaan dan generasi yang akan datang. Namun catatan penting dalam relasi
ini adalah kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan sumber daya genetik
tidak berarti bahwa sumber daya tersebut adalah warisan bersama umat manusia.
Sebaliknya sumber daya genetik tersebut adalah milik negara dan masyarakat
hukum adat.
Persyaratan pembagian keuntungan diperkuat melalui serangkaian diskusi
oleh para peserta CBD yang kemudian mencapai puncaknya menjadi kerangka
kerja yang lebih tegas yang dikenal sebagai Nagoya Protocol. Protokol yang
diadopsi pada tahun 2010 ini memberikan dasar yang kuat bagi kepastian hukum
dan transparansi yang lebih besar baik bagi penyedia maupun pengguna sumber
daya genetik. Kepastian hukum dari Nagoya Protocol adalah mengharuskan negara-
negara untuk mengembangkan undang-undang untuk memastikan bahwa
penggunaan sumber daya genetik dalam yurisdiksi mereka dilakukan dengan FPIC
dan MAT serta mematuhi undang-undang pembagian keuntungan di negara lain.
Sedangkan dari aspek transparansi Nagoya Protocol mengharuskan negara-
negara industri mendirikan pos pemeriksaan untuk mengungkapan sumber daya
292
genetik apa yang telah mereka akses dimana dan untuk memantau apakah mereka
mematuhi Protokol. Konsep ABS dikaitkan dengan keadilan konservasi bahwa
mereka yang menggunakan sumber daya genetik memberikan kembali imbalan
kepada penyedia.14
Landasan filosofi dari hal ini adalah bahwa nilai intrinsik dari sumber daya
genetik perlu diimbangi dengan penghargaan yang proporsional. Hal ini beranjak
dari kekhawatiran tentang bagaimana melakukan penelitian yang etis pada negara-
negara yang kaya sumber daya genetik baik yang dikelola masyarakat hukum adat
untuk mendapatkan manfaat yang besar maka ABS dianggap sebagai salah satu
instrumen penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan diantara hubungan
tersebut. Sebagian pelaku konservasi hidup dalam kesederhanaan jauh dari akses
kesehatan adalah relevan sumber daya genetik yang diakses tersebut manfaatnya
dibagi ke penjaga konservasi. Sebaliknya secara etis adalah tidak adil bila suatu
negara atau Users tidak memberikan manfaat yang adil atas akses yang diberikan
kepadanya.
CBD mengakui peran masyarakat hukum adat dalam melakukan konservasi
sebagimana tergambar dari praktik dan gaya hidup mereka yang memiliki
pengetahuan mengenai alam. Secara normatif CBD meneguhkan sistem ABS, hak
masyarakat hukum adat atas pembagian keuntungan dan bagaimana seharusnya
negara-negara mentransformasikan nilai, prinsip dan norma ABS ini ke dalam
hukum nasionalnya. Adapun ketentuan-ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:
14 Doris Schroeder and Balakrishna Pasupati, “Ethics, Justice and the Convention on
Biological Diversity”, UNEP, 2010, halaman 13-14.
293
Pasal 8 (J) bahwa:
Tergantung perundang-undangan nasionalnya menghormati, melindungi dan
mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat
hukum adat dan komunitas lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional
sesuai dengan konservasi dan pembanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman
hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan
keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut,
mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan
sumber daya genetik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam
itu.
Seterusnya ketentuan Pasal 15 meneguhkan kembali amanah Pasal 8 (J) bahwa:
Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislative, administrative atau upaya
kebijakan yang sesuai dan menurut Pasal 16 dan 19 dan bila perlu melalui
mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21 dengan tujuan
mebagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan
dari penggunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik secara adil
dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian inin harus
didasarkan atas persayaratan yang disetujuai bersama.
Berdasarkan pengaturan dalam CBD terlihat bahwa CBD mengakui hak
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sebagai pemilik sumber daya genetik
dan pengetahuan traisional. Negara diharapkan mengambil langkah hukum untuk
mewujudkan sistem ABS tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Ketentuan
mengenai ABS dalam CBD diderivasi ke dalam Nagoya Protocol sebagai bentuk
komitmen masyarakat hukum internasional mewujudkan sistem ABS.
b. Perjanjian Internasional Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources
and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from their Utilization
to the Convention on Biological Diversity
Access and Benefit Saharing (ABS) mengacu pada cara dimana sumber
daya genetik dapat diakses dan bagaimana manfaat yang dihasilkan dari
penggunaannya dibagi antara penyedia dengan pengguna. Mengapa ABS penting,
294
penyedia sumber daya genetik adalah Negara sebagai pemegang kedaulatan atas
sumber daya alam dan masyarakat hukum adat dalam suatu negara yang
menyediakan sumber daya genetik. Ketentuan akses dan pembagian keuntungan
dari CBD dirancang untuk memastikan bahwa akses fisik ke sumber daya
difasilitasi dan manfaat yang diperoleh dari penggunaannya dibagi secara adil
dengan penyedia.
Dalam rangka memperkuat peluang pembagian keuntungan guna
mempromosikan pengunaan sumber daya genetik yang lebih adil termasuk yang
berasosiasi dengan pengetahuan tradisional Nagoya Protocol on Access to Genetic
Resources and the Fair and Equitabel Sharing Of Benefit Arising from their
Utilization to the Convention on Biological Diversity menciptakan skema ABS
untuk merealisasikan tujuan pilar ketiga CBD dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang
terkait dengan hak masyarakat hukum adat:
1. Sesuai dengan Pasal 15 (3) dan Pasal 7 Konvensi keuntungan yang timbul
dari pemanfaatan sumber daya genetik serta komersialisasinya harus dibagi
secara adil dan setara dengan pihak penyedia yang merupakan negara asal
sumber daya atau pihak yang memiliki sumber daya genetik sesuai konvensi
harus dibagi berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama.
2. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau
kebijakan yang sesuai dengan tujuan untuk menjamin bahwa keuntungan
yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal sesuai dengan undang-undang
domestik mengenai hak-hak yang telah ditetapkan dari masyarakat hukum
adat dan komunitas lokal itu atas sumber daya genetik tersebut dibagi secara
adil dan seimbang dengan masyarakat yang bersangkutan berdasarkan
kesepakatan bersama.
3. Untuk melaksanakan ayat 1, setiap pihak wajib mengambil langkah
legislatif, administratif atau langkah-langkah kebijakan yang sesuai.
4. Keuntungan dapat mencakup keuntungan moneter dan non moneter tetapi
tidak terbatas pada yang tercantum dalam lampiran.
295
5. Setiap pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau
kebijakan yang tepat agar manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber
daya genetik dibagikan secara adil dan merata dengan masyarakat hukum
adat dan komunitas lokal yang memiliki, pembagian itu harus sesuai dengan
persyaratan yang disepakati bersama.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan hak berdaulat negara atas sumber daya alam
Nagoya Protocol Pasal 6:
1. Dalam pelaksanaan hak berdaulat atas sumber daya alam pada akses domestik
dan peraturan perundang-undangan pembagian keuntungan atau peraturan
persyaratan, akses terahadap sumber daya genetik untuk pemanfaatannya harus
diinformasikan terlebih dahulu sebelum persetujuan dari pihak yang
menyediakan sumber daya.
2. Sesuai dengan hukum nasional, masing-masing pihak wajib mengambil
tindakan yang sesuai dengan tujuan untuk memastikan bahwa persetujuan dan
keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diperoleh untuk akses
ke sumber daya genetik dimana masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal
memiliki hak yang ditetapkan untuk memberikan akses ke sumber daya genetik
tersebut.
3. Sesuai dengan ayat 1 setiap pihak yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu
harus mengambil langkah-langkah legislatif, adminsitratif atau kebijakan yang
diperlukan sebagaiman mestinya untuk:
a. Memberikan kepastikan hukum, kejelasan dan trasnparansi akses dan
peraturan persyaratan pembagian keuntungan.
b. Menyediakan aturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang
dalam mengakses sumber daya genetik.
c. Memberikan informasi tentang cara mengajukan persetujuan berdasarkan
informasi sebelumnya
d. Memberikan keputusan tertulis yang jelas dan transparan oleh otoritas
nasional yang kompeten
e. Menyediakan dokumen penerbitan pada saat akes izin diberikan sebagai
bukti keputusan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu dan
penetapan syarat-syarat yang disepakati bersama dan memberitahukan
kepada Lembaga kliring akses dan pembagian hasil atau keuntungan
f. Menetapkan kriteria dan proses untuk mendapatkan persetujuan
berdasarkan informasi awal dan keterlibatan masyarakat hukum adat ke
akses sumber daya genetik
g. Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dalam menetapkan persyaratan
yang disepakati bersama. Persyaratan tersebut ditetapkan secara tertulis dan
meliputi:
296
1) Klausul penyelesaian sengketa
2) Ketentuan pembagian keuntungan termasuk yang berhubungan dengan
hak kekayaan intelektual
3) Ketentuan penggunaan oleh pihak ketiga selanjutnya bila ada
4) Ketentuan tentang perubahan kesepakatan bila diperlukan
Kemudian ketentuan Pasal 7 menegaskan kembali kewajiba negara mengatur dalam
dalam hukum nasionalnya bahwa sesuai dengan hukum nasional, masing-masing
pihak wajib mengambil kebijakan sebaimana mestinya dengan tujuan memastikan
bahwa pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang diselenggarakan
oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses melalui persetujuan yang
diinformasikan terlebih dahulu dan sesuai dengan persyaratan yang disepakati
bersama masyarakat hukum adat.
Nagoya Protocol memberikan acuan yang harus ditransformasikan ke dalam
hukum nasional yaitu:
a. Negara wajib menunjuk focal point nasional untuk akses dan pembagian
keuntungan. Focal point harus menyediakan informasi sebagai berikut:
1) Untuk Users yang mencari akses ke sumber daya genetik menyediakan
informasi tentang prosedur untuk mendapatkan persetujuan yang
diinformasikan terlebih dahulu, persyaratan kesepakatan bersama dan
pembagian keuntungan
2) Untuk Users yang mencari akses ke pengetahuan tradisional yang terkait
dengan sumber daya genetik menyediakan informasi tentang prosedur
memperoleh persetujuan yang diinformasikan terlebih dahulu dan
keterlibatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam
297
menetapkan persayaratan yang disepakati bersama dan pembagian
keuntungan.
3) Negara pihak dapat menunjuk satu entitas untuk memenuhi fungsi focal
point dan otoritas nasional
4) Setiap negara wajib selambat-lambatnya pada tanggal berlakunya Protokol
memberiahu Sekretariat tentang informasi kontak dari Focal Point
nasionalnya, informasi tersebut berisi pejabat yang bertanggung jawab atas
sumber daya genetik yang dicari.
5) Sekretariat akan membuat informasi yang diterima melalui Balai Kliring
Akses dan Pembagian Keuntunngan
6) Infoemasi tambahan bila tersedia mencakup otoritas yang kompeten dari
masyarakat hukum adat, model klausula kontraktual, metode tang
dikembangkan untu memantau sumebr daya genetik
7) Kode etik dan praktik terbaik
8) Tata cara pengoperasian Lembaga kliring akses dan pembagian keuntungan
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut negara memiliki dua kewajiban utama
yaitu menerapkan atau mentranformasikan aturan akses ke sumber daya genetik
melalui sistem ABS. Negara juga harus memastikan bahwa keuntungan yang
dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik dibagi secara adil antara
pengguna sumber daya genetik dengan penyedia sumber daya genetik. Untuk
mendapatkan akses pengguna harus terlebih dahulu mendapat izin sesuai prinsip
persetujuan berdasarkan informasi awal dari negara penyedia (Free Prior Informed
Consent/FPIC). Selain itu, pengguna dan penyedia harus merundingkan
298
kesepakatan atau yang dikenal dengan prinsip persyaratan yang disepakati bersama
(mutually agreed term/MAT) untuk berbagi keuntungan secara adil.
Melalui Protocol Nagoya negara-negara diamanahkan memformulasi dalam
hukum nasionalnya peraturan perundang-undangan nasional guna mendorong
pengguna dan penyedia memperoleh manfaat langsung dari akses sumber daya
genetik. Hal ini pada akhirnya untuk mewujudkan pemanfaat sumber daya genetik
menuju konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelnajutan
komponen-komponennya.
c. Bonn Guideline
Bonn Guideline merupakan instrumen internasional yang dibentuk untuk
memberikan pedoman negara dalam pelaksanaan ABS dalam sistem hukum
nasional. Bonn Guideline diluncurkan pada Konperensi Para Pihak pada pertemuan
CBD tahun 2002. Bonn Guideline bertujuan memandu negara-negara sebagai
penyedia maupun sebagai pengguna untuk menerapkan prosedur akses dan
pembagian keuntungan (ABS) secara efektif. Walaupun Bonn Guideline bersifat
soft law namun panduan ini diakui sebagai langkah yang penting untuk
implementasi ketentuan ABS dari CBD dan Nagoya Protocol.
Bonn Guideline membantu negara dalam pengembangan dan pelaksanaan
kerangka kerja yang memfasilitasi akses dan memastikan bahwa manfaat yang
timbul dari penggunaannya dibagi secara adil dengan dua tujuan utama:15
15 The Bonn Guidelines, diakses pada
https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-bonn-en.pdf.
299
1. Memandu negara sebagai penyedia membentuk legislasi nasional mereka
sendiri seperti merekomendasi elemen-elemen prosedur persetujuan atas dasar
informasi awal (Free Prior Informed Consent/FPIC) dan
2. Memandu penyedia dan pengguna dalam bernegosiasi terkait persyaratan yang
disepakati bersama (mutually Agreed Terms/MAT) dengan memberikan contoh
elemen apa saja yang harus dimasukan dalam perjanjian tersebut.
Langkah-langkah penting dalam proses ABS yang mencakup mengidentifikasi
elemen dasar yang diperlukan untuk FPIC dan MAT dan menguraikan peran utama
dan tanggung jawab pengguna dan penyedia serta menyertakan dafatr manfaat
keuangan dan non moneter. Prinsip dasar sistem FPIC dan MATyang efektif harus
mencakup:
1. Kepastian dan kejelasan aturan hukum
2. Akses ke sumber daya genetik harus difasilitas dengan biaya minum
3. Pembatasan akses ke sumber daya genetik harsu transparan, berdasarkan dasar
hukum dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi
4. Jenis dan kuatitas sumebr daya genetik dan wilayah geografis
5. Apakah sumber daya genetik da[at ditransfer pada pihak ketiga
Keberhasilan mekanisme ABS melalui FPIC dan MAT tergantung pada pemenuhan
syarat dan ketentuan yang disepakati bersama antara para pihak. Oleh karena itu
bila terdapat perselisihan yang timbul harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian
kontrak tentang akses dan kesepakatan pembagian keuntungan yang belum
terpenuhi dapat dipertimbangkan penggunaan sanksi berupa biaya denda. Pedoman
Bonn memberikan panduan teknis untuk penerapan ABS. Keberhasilan skema ABS
300
akan tergantung pada seberapa cepat negara pihak menginternalisasikan pedoman
ini kedalam sistem hukum nasionalnya.
Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa konsep ABS telah
mengalami evalusi dari konsep etik yang awalnya sebagai prinsip warisan bersama
umat manusia menjadi konsep pembagian keuntungan (ABS), dari prinsip
kesetaraan dimana semua negara atau semua orang berhak mendapatka akses yang
sama secara bebas menjadi prinsip keadilan terjadi pembagian keuntungan antara
yang menyediakan atau yang melakukan konservasi sumber daya genetik dengan
yang mengakses sumber daya. Hal ini disebut sebagai keadilan konservasi yaitu
suatu keadilan berdasarkan pengakuan jerih payah pihak pelaku konservasi sumber
daya hayati dalam hubungan dengan sistem ABD dalam kerangka pembanguan
berkelanjutan.
Dengan demikian konsep ABS mendapat jsutifikasi dan perlindungan karena secara
hukum internasional diabadikan dalam perjanjian yang mengikat negara-negara.
Karena itu kerangka hukum ABS dalam hukum nasional adalah penting untuk
mewujudkan sistem ABS terimplementasikan dan pembagian manfaat
terealisasikan.
Dimensi keadilan berperan besar dalam relasi antara ABS untuk sumber
daya genetik dan beban lingkungan. Keanekaragaman hayati yang terancam saat
ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari gaya hidup dan pembangunan yang
tidak berkelanjutan di belahan bumi Utara. Dengan mengacu pada prinsip keadilan
adalah beralasan bila seseorang yang diuntungkan karena memanfaatkan sumber
daya genetik yang dijaga di belahan bumi Selatan dalam konteks perubahan iklim
301
harus berbagi keuntungan. Kesadaran, pengakuan dan keadilan dapat membantu
memahami dan mengahormati negara yang kaya keanekaragaman hayati dan
masyarakat hukum adat pelaku konservasi.
B. Perbandingan Transformasi Praktik Indonesia dan Thailand Hak
Masyarakat Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (ABS)
1. Praktik Indonesia terkait Transformasi Hukum Internasional mengenai
Access and Benefit Sharing (ABS) Sumber Daya Genetik Masyarakat
Hukum Adat
Tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia merupakan perwujudan
dari tujuan negara. Berbagai perjanjian internasional baik berupa law making treaty
maupun treaty contract merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian dan
ketertiban dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional
yang kemudian menjadi hukum internasional memunculkan konsekuensi hukum
yang tidak dapat dihindari. Walaupun hukum internasional tidak menentukan
bagaimana hukum internasional akan diterapkan oleh negara-negara namun tidak
bisa tidak harus dimaknai bahwa negara yang mengikatkan diri dalam suatu
perjanjian wajib memberlakukan hukum internasional itu ke dalam sistem hukum
nasionalnya.
302
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang
Perjanjian Internasional bahwa: “A treaty enters into force in such manner and
upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree”. Perjanjian
berlaku sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini selaras dengan
ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional bahwa: “Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan
mengikat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetaokan dalam perjanjian
tersebut”. Selain itu, pada saat perjanjian berlaku maka negara-negara wajib
menerapkan dan tidak dapat mengajukan alasan hukum nasional sebaga
pembenaran atas kegagalannya melaksanakan perjanjian internasional
sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 27 bahwa: “ A party may not
invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a
treaty. This rule is without prejude to article 46”.16
CBD dan Nagoya Protokol merupakan dua perjanjian internasional yang
diikuti dan diratifikasi Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati
sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan
secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Namun kondisi sumber daya genetik terus menerus mengalami kemerosotan akibat
masifnya pengambil sumber daya genetik yang mengancam kelangsungan
kehidupan manusia. Masyarakat hukum adat telah merawat dan melestarikan
16 Negara tidak dapat menggunakan alasan ketentuan hukum nasionalnya sebagai
pembenaran atas kegagalannya untuk melaksanakan suatu perjanjian (Konvensi Wina 1969 Pasal
27)
303
sumber daya genetik selama berabad-abad yang menjadi sumber pengidupan yang
berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan.
Di tingkat komunitas internaisonal banyak pemerintah telah melakukan
upaya hukum guna menerapkan ketentuan ABS dari CBD dan Nagoya Protocol.
Namun, cara mereka mentransformasikannya bervariasi berdasarkan keadaan di
aras nasional. Sejumlah negara seperti Australia, Brazil, India dan Dafrika Selatan
telah mengadopsi langkah-langkah perumusan ABS. Australia misalnya adalah
rumah bagi sekita 10% spesies dunia dan hamper 80% spesies aslinya tidak
ditemukan di tempat lain, sebagai penyedia harus melindungi kekayaan sumber day
agenetik yang unik tersebut. Australia mengikuti kerangka kerja CBD termasuk
menerapkan prosedur untuk menyetujuai PIC dan MAT.17
Sebagi negara yang meratifikasi CBD dan NP, Indonesia yang memiliki
wilayah yang membentang sepanjang dari Sabang sampai Merauke melimpah akan
keanekaragaman hayati dan tradisi kearifan lokal yang dijaga masyarakat hukum
adat. Dengan dibentuknya ketentuan hukum lingkungan melalui Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup/UU PPLH terutama Pasal 63 ayat (1) huruf i negara wajib menetapkan
kebijakan pengelolaan sumber daya genetik Indonesia termasuk memenuhi hak
masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional. Pembentukan UU PPLH merupakan amanat
dari ketentuan Pasal 28 C yaitu hak setiap orang untuk mengembangkan diri
17 CBD Secretariat, Access and Benefit Sharing Uses of Genetic Resources Traditional
Knowledge Bonn Guidelines, 2011, halaman 21.
304
memperoleh manfaatn dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya serta
memperjuangkan haknya secara kolektif, 28 H yaitu hak asasi setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, 28 I tentang HAM yaitu
penghormatan atas hak masyarakat hukum adat, identitas budaya, serta Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang penguasaan
negara atas sumber daya alam.
Peraturan perundnag-undangan yang memiliki keterkaitan dengan
masyarakat hukum adat dan ABS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, hak penguasaan atas sumber daya alam, ada pada negara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal
33 ayat (3) telah ditetapkan beberapa peraturan perundangan tentang hak masyakat
hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya genetik yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Lebih lanjut di dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 pengakuan tersebut meliputi bahwa: “identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormatii selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”. Sejalan dengan pengakuan tersebut maka kebijakan pengelolaan
sumber daya genetik sebagai bagian dari sumber daya alam haruslah mengakui dan
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
305
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal
33 ayat (3). Berdasarkan ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa sumber daya alam
adalah elemen dari lingkungan yang mancakup sumber daya hayati dan non hayati
yang di dalamnya adalah sumber daya genetik yang mengamanahkan negara
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam hal ini termasuk
masyarakat hukum adat. Artinya, walaupun di dalam konstitusi tidak ditegaskan
secara eksplisit hubungan antara masyarakat hukum adat dan sumber daya genetik
namun dari penegasan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan pernyataan
sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapatlah
dikatan bahwa konstitusi mewadahi hak-hak masyarakat hukum adat.
b. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam bagian menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dinyatakan bahwa
pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlangsung selama
ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan
berbagai konflik. Ketentua Pasal 4 TAP MPR: “mengakui, menghormati dan
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber
daya agrarian/sumber daya alam”.
306
Dengan demikian diperlukan penataan kembali penguasaan dan
pengelolaannya secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan
mengedepankan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat
hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya
alam yang berkeadilan dengan menafsirkan secara jelas makna hak penguasaan
negara melalui instrumen hukum sumber daya alam yang berpihak pada
perwujudan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat salah satunya adalah
dengan pengaturan terkait hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alamnya.
Terlebih lagi adanya praktik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 bahwa: “Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat bukan lagi
di wilayah Negara”.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengisyaratkan pengakuan dan
penguatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang perlu ditindaklanjuti
dengan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang selama ini masih
berpegang pada kriteria “hutan adat berada di kawasan hutan negara”. Hal ini
penting untuk perumusan kebijakan ke depan agar peraturan perundang-undang
pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat eksistensi dan hak-hak
masyarakat hukum adat.
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria
(UUPA)
Sumber daya genetik adalah perwujdukan dari keanekaragaman hayati
yang merupakan bagian dari sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 atau lebih dikenal dengan UUPA meneguhkan kembali kedaulatan
307
(sovereignty) dan penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengaturan yang berkaitan dengan
masyarakat hukum adat ditemukan dalam beberapa ketentuan antara lain ketentuan
Pasal 3 bahwa: “dalam pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat diakui sepanjang sesuai dengan kepentingan
nasional dan negara”.
Selain itu, Pasal 5 UUPA juga menegaskan bahwa: “hukum agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan
lainnya”. Dengan demikian dapatlah persepsikan bahwa UUPA juga mengakui
secara tidak langsung bahwa dalam pengelolaan sumber daya genetik berdasarkan
hukum adat tetap berlaku dan dihormati dan masyarakat hukum adat memiliki hak
ulayat walaupun di dalam UUPA belum ditemukan mengenai pemanfaatan sumber
daya genetik masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pembagian
keuntungan. Hal ini mengingat pengaturan mengenai hak masyarakat hukum adat
atas sumber daya genetik baru menjadi perhatian masyarakat internasional dan
nasional pada dekade tahun 1992 saat KTT Bumi diluncurkan seiring dengan
konsepsi pembangunan berkelanjutan.
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pelestarian Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati/kehati Indonesia
mempunyai relasi dengan hukum internasional karena nilai strategis kehati bagi
kebutuhan pangan, kesehatan masyarakat dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia
308
telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Pelestarian Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang bertujuan mengatur konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.
Undang-undang ini memiliki keterkaitan yang erat dengan CBD dan
Nagoya Protocol karena mengusahakan terwujudnya kawasan konservasi
kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya tersebut. Namun, tidak ada pengaturan
mengenai hak masyarakat hukum adat yang berhubungan sumber daya genetik
termasuk peran masyarakat hukum adat dalam praktik konservasi di dalam undang-
undang ini.
Lebih lanjut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan kaitan antar
konservasi dapat dilihat sebagai salah satu pilar atau prinsip utama pembangunan
berkelanjutan dari United Nation Conference on Environment and Development
yaitu:
1. Keadilan antargenerasi (interngenerational equity)
2. Keadilan dalam satu generasi (generational equity)
3. Pencegahan dini (precautionary principle)
4. Perlindungan keanekaragaman hayati (conservation of biological diversity)
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (internalisation of
enviromental cost and incentive mechanism)
Indonesia dapat berperan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati melalui adopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bumi memiliki
sumber daya yang terbatas dan harus dilindungi untuk generasi mendatang. Itulah
309
sebabnya mengadopsi praktik pembangunan berkelanjutan penting untuk
keberhasilan kehidupan jangka Panjang.
Masyarakat hukum adat telah lama dikenal berpartisipasi melalui praktik-
praktik konservasi dalam tradisi kearifan lokal mereka. Namun terjadi kesenjangan
antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik dan dan pelestari sumber daya
genetik dengan pengguna yang mengakses dan memanfaatkan. Keuntungan yang
diperoleh pengguna yang tidak dibagi ke masyarakat hukum adat menciptakan
ketimpangan dan ketidakadilan yang berujung pada kerugian dan kemiskinan pada
masyarakat hukum adat. Karena itu, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
kebijakan ke depan perlu mengadopsi prinsip sustainable development goals
terutama tujuan 10, 15, 16, dan 17 yang pada prinsipnya tujuan-tujuan SDGs ini
untuk mengurangi kesenjangan guna mencapai keadilan. Terwujudnya keadilan
merupakan kondisi yang menjadi harapan dan cita hukum.
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB
Mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations on Convention
Biological Diversity).
Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)
1992 merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat bagi para peserta
perjanjian. Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diprakarsai oleh Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor
5 Tahun 1994 merupakan instrumen hukum pertama yang mengakui peran penting
masyarakat hukum adat atas konservasi dan pelestarian sumber daya genetik yang
berasosiasi dengan pengetahuan tradisional. Konvensi menyerahkan kepada negara
310
untuk mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya genetik termasuk mengatur
pembagian keuntungan atas pemanfaatannya oleh pihak ketiga.
Konvensi Keanekaragaman Hayati memperkenalkan sistem access and
benefit sharing/ABS terkait akses sumber daya genetik pada negara penyedia dan
masyarakat hukum adat. Melalui CBD negara-negara diamanahkan untuk
mentransformasikan prinsip, norma dan prosedur ABS yang diatur dalam CBD,
Nagoya Protocol dan Bonn Guidelines. Sumber daya genetik memiliki nilai ilmu
pengetahuan dan ekonomi yang tinggi namun masyarakat hukum adat yang
menjunjung nilai komunal tidak menyadari bahwa sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisionalnya telah disalahgunakan oleh pengguna yang kemudian
mengklaimnya dalam bentuk paten.18
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan CBD terdiri dari
dua pasal. Pasal pertama mengenai pengesahan dan pasal kedua mengenai mulai
berlakunya undang-undang ratifikasi. Apabila dicermati maka undang-undang
ratifikasi ini tidak ada kaitannya dengan telah ditransfomasinya kewajiban
Indonesia mengenai ABS ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini karena undang-
undang pengesahan bukanlah undang-undang yang membuat hukum internasional
tersebut dapat langsung menjadi hukum nasional.
Dalam hukum internasional ratifikasi adalah tindakan internasional suatu
negara pihak yang menegaskan persetujuannya untuk diikat dalam suatu perjanjian
internasional sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang
Perjanjian Internasional Pasal 2 bahwa: “ratification … mean in each case the
18 Xuanyu Chen, op. cit, halaman 164.
311
international act so named whereby a State establishes on the international plane
its consent to be bound by a treaty”. Suatu prinsip dasar yang berlaku dalam hukum
internasional bahwa negara pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional
wajib memastikan bahwa hukum nasionalnya konsisten dengan apa yang
diwajibkan dalam perjanjian internasional.
CBD dan Nagoya Protocol telah meletakkan dasar hukum bagi negara pihak
untuk mengatur dan mentransformasikan ketentuan mengenai ABS. Hal ini
dilandasi pengakuan Konvensi atas peran masyarakat hukum adat dan praktik
masyarakat hukum adat dalam konservas dan pemanfaatan yang berkelanjutan.19
Setelah CBD dan Nagoya Protocol mulai berlaku negara-negara mulai membangu
sistem hukum ABS guna melindungi kekayaan sumber daya genetiknya. Namun,
sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum tentang ABS meskipun
telah meratifikasi CBD lebih dari 25 tahun.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 8 (J) jo Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal
7 Nagoya Protocol mewajibkan negara mengambil langkah legislasi, administrasi
dan kebijakan lainnya untuk menetapkan sistem ABS. Perwujudan dari kewajiban
ini sudah tentu memerlukan transformasi hukum internasional ke dalam hukum
nasional baik secara formal maupun subtantif sebagai bentuk komitmen dan
integritas negara yang berjanji.
f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation).
19 Bram De Jonge, “What is Fair and Wquitabel Benefit Sharing?”, Journal Agric. Environ
Ethics (24), 2013, halaman 128: “the CBD declares that states have sovereign rights over their
plants genetic resources and introduces the first access and benefit sharing model in the world”.
312
World Trade Organisation (WTO) merupakan badan internasional yang
mengatur masalah perdagangan antar negara. Persetujuan pembentukan WTO
memiliki lampiran (annexes) yang sangat terkait terkait sumber daya genetik yaitu
Annex 1C yang juga lebih dikenal dengan Persetujuan Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang merupakan bagian dari
persetujuan WTO ketentuan Pasal 27 ayat (3) buruf b menentukan bahwa:
Members may also exclude from plants and animals other than micro-
organisms, and essentially biological processes for the production of plants
or animals other than non-biological and microbiological processes.
However, Members shall provide for the protection of plant varieties either
by patents or by an effective sui generis system or by any combination
thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years
after the date of entry into force of the WTO Agreement.
(Negara anggota juga dapat mengecualikan dari paten: tanaman dan hewan
selain mikro-organisme, dan pada dasarnya proses biologis untuk produksi
tanaman atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Namun,
negara anggota harus menyediakan perlindungan varietas tanaman baik
dengan paten atau dengan sistem sui generis yang efektif atau dengan
kombinasi apa pun dari padanya. Ketentuan-ketentuan dari sub-ayat ini
akan ditinjau empat tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian WTO).
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b sumber daya genetik tidak dapat
dilindungi melalui paten karena itu negara-negara harus membentuk kebijakan
perlindungan sendiri baik melalui paten maupun sistem sui generis atau kombinasi
keduanya. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang sue generis
yang mengatur tentang sumber daya genetik dan sistem ABS. Sementara itu,
melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ketentuan Pasal 26
mengatur:
(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik
dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal
sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam
deskripsi.
313
(2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang
diakui oleh pemerintah.
(3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di
bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 telah diatur mengenai invensi yang
bertalian dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional harus
disebutkan secara jelas asal sumber daya genetik dan pembagian hasil atas akses
dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional tersebut. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas akses
dan pemanfaatan sumber daya genetik. Di dalam undang-undang ini peran
masyarakat hukum adat tidak disebut dalam hubungannya dengan invensi namun
secara terbatas telah di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) hal ini dapatlah dimaknai
bahwa bila invensi harus mencantumkan asal dari sumber daya genetik dalam hal
ini tentu termasuk dari masyarakat hukum adat dan secara tidak langsung hal ini
merupakan pengakuan terhadap kontribusi masyarakat hukum adat.
g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU
HAM)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asassi Manusia
(HAM) yang mengatur mengenai mayarakat hukum adat merupakan turunan dari
Konstitusi khususnya ketentuan Pasal 18 B ayat (2) yang diteguhka kembali dalam
Pasal 6 UU HAM. “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan
314
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh
hukum. Selain itu, identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman”.
Berdasarkan pengaturan dalam UU HAM Indonesia bila ditelusuri
pengakuan atas hak sumber daya alam masyarakat hukum adat tidak disebutkan
secara eksplisit namun pengakuan yang signifikan terhadap hak tanah ulayat
merupakan bentuk dari pengakuan dan perlindungan negara terhadap sumber daya
alam masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat praktik konservasi sumber
daya genetik yang mentradisi.
h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-
Undang Kehutanan)
Penafsiran ketentuan Undang-Undang Kehutanan yang bertalian dengan
masyarakat hukum adat dan hutan perlu dikontekstualkan dengan Putusan
Mahkmah Konstitusi mengenai hutan adat tidak berada di wilayah hutan negaera.
Dengan demikian hutan adat merupakan hutan yang tunduk pada hukum adat.
Ketentuan Pasal 67 ayat (1) mengatur hak Masyarakat Hukum Adat antara lain:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-
hari dari Masyarakat Adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
315
Penjelasan Pasal 67 ayat (1) di atas menyatakan bahwa sebagai Masyarakat
Hukum Adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:
a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinschap);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih
ditaati;
e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
35/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa hutan adat bukan hutan negara maka
dapatlah dimaknai bahwa sumber daya genetik masyarakat hukum adat yang ada di
wilayah kelola masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum sebagai bagian
dari hutan masyarakat hukum adat.20 Putusan yang progresif ini dapat dikatakan
manifestasi dari ketentuan pasal 18 B ayat (2) serta merupakan tahapan penting dan
berimplikasi ke depan dalam penyelesaian dan harmonisasi hukum bertalian
dengan masalah masyarakat hukum adat khususnya berkaitan dengan klaim sumber
daya alam.
Kepastian hukum ini dapat memperjelas dan memenuhi keadilan bagi
masyarakat hukum adat terkait pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber
20 R. Yando Zakaria, “Konstitusionalitas Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2021”, Jurnal kajian Volume 19 Nomor 2, 2014,
halaman 128.
316
daya genetiknya. Kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai tindak
lanjut bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara beserta hak-hak tradisionalnyan
dalam rangka pengelolaan sumber daya genetik menjadi relevan untuk
ditindaklanjuti.
f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman (UU PVT)
Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PVT Hak Perlindungan Varietas Tanaman
adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak
Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil
pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu. Pada bagian lain ketentuan Pasal 2 (1)
Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman
yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. (2) Suatu varietas dianggap baru
apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil
panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah
diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar
negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk
tanaman tahunan. Di dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturan
mengenai sumber daya genetik masyarakat hukum adat, begitupun mengenai
pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya
genetik.
Di tingkat internasional terdapat International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture/ITPGRFA yang bertujuan mendorong negara-
317
negara melakukan konservasi dan penggunaan secara berkelanjutan semua genetic
resources untuk pangan dan pertanian serta pembagian keuntungan atas
pemanfaatan sesuai dan harmoni dengan CBD. Perbedaannya dengan sistem ABS
CBD adalah sistem ITPGRFA dikenal dengan sistem multilateral yang memberikan
setiap anggota akses ke tanaman pangan dan ternak yang tercakup dalam perjanjian.
Sistem multilateral pada prinsipnya adalah kumpulan gen global sumber daya
genetik tanaman yang dapat dibagi secara kooperatif oleh semua anggota. Adapun
mekanisme untuk memperoleh sumber daya genetik tertentu adalah melalui kontrak
yang disebut standard material transfer agreement/SMTA.
Indonesia sendiri telah meratifikasi ITPFRFA dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian ITPGRFA. Kesepakatan
penting mengenai ABS dicapai dengan menyisihkan 0,6 persen keuntungan bersih
dari penjualan produk sumber daya genetik sebagai kontribusi peserta ke
ITPGRFA. Kontribusi ABS ini mendorong setiap negara agara dapat memenuhi
keperluan sumber daya genetiknya tanpa menimbulkan sengketa karena selama ini
monopoli kepemiliki sumber daya genetik tanaman untuk pangan acap kali
membuat negara-negara mengalami perselihan karena perembutan sumber daya.
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa penangkapan dan pembudidayaan ikan harus
mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran
318
serta masyarakat. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam
termasuk sumber daya genetik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)
tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol
Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati Protocol on Biosafety to The Convention on
Biological Diversity
Pengaturan mengenai hak masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber
daya genetik tidak terdapat di dalam undang-undang ini. Organisme hasil
modifikasi genetik mengandung risiko yang menimbulkan dampak merugikan
terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sehingga untuk menjamin tingkat
keamanan hayati perlu diatur pemindahan, penanganan, dan pemanfaatannya
sebagaimana diatur dalam Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati yang
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.
i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan
tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta
hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional
yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pasal 1 angka 3 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber
daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan
319
biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut;
sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut
tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi
gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Berdasarkan pengertian ini
bertalian dengan sumber daya genetik yaitu sumber daya hayati yang meliputi ikan,
terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya hayati
pesisir ini juga merupakan sumber daya genetik yang sangat berguna untuk
menopang hidup dan kehidupan nelayan masyarakat hukum adat.
Ketentuan yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat terdapat
dalam Pasal 1 angka 33 bahwa masyarakat pesisir yang secara turun-temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum. Undang-undang ini dengan jelas mengakui eksistensi masyarakat adat
dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 bahwa:
(1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau
kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat
menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.
Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan
kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
320
j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dalam Kaitannya Dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Perkembangan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang mengalami
penyesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Namun secara esensi pengaturan yang terkait dengan kebijakan sumber daya
genetik dan masyarakat hukum adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa
aspek antara lain mengenai perizinan dan amdal sehingga Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 disesuaikan dalam UU Cipta Kerja. Pasca terbitnya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diterbitkan pula Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun di sisi lain terjadi perkembangan judisial
review UU Cipta Kerja dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional
bersayarat dan menegaskan bahwa “pembentukan UU Cipta Kerja masih tetap
berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan dalam waktu 2 dua tahun
… .”21 Dengan demikian Pemerintah perlu segera menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi agar terdapat kejelasan dan kepastian.
Sementara itu apabila dicermati terkait pengembangan kebijakan sumber
daya genetik ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (i) Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa
21 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020” , 25-11-2021. Lihat juga
Mahkamah Konstitusi, “MK: Inkonsitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam
jangka Waktu Dua Tahun” diakses pada
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
321
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan
berwenang: “menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Sumber Daya
Alam Hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, Sumber Daya Genetik, dan
keamanan hayati produk rekayasa genetik”.
Sementara itu, di dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (t) ditentukan bahwa dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan
berwenang “menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
Kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat menjadi penting karena
berimplikasi pada statusnya sebagai subyek hukum yang pada gilirannya akan
mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat
termasuk hak atas pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik.
Beberapa Peraturan Daerah telah dibentuk untuk mengakui keberadaan masyarakat
hukum adat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001
tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Badui, Peraturan Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di
Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta,
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.
Terbitnya pengaturan pengenai pengakuan masyarakat hukum adat ini
diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subyek
322
hukum. Namun, pengaturan mengenai hak-hak masyarkat hukum adat yang diatur
di dalam peraturan daerah tersebut di atas belum ada yang mengatur mengenai
pembagian keuntungan atas akses atau pemanfaatan sumber daya genetik
masyarakat hukum adat. Karena itu ke depan diperlukan penyesuaian dan
tindaklanjuti mengenai ABS.
k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya
Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing
Arising from Their Utilization to Convention on Biological diversity
Nagoya Protocol merupakan perjanjian internasional yang dibentuk untuk
mewujudkan pilar ketiga dari CBD yaitu pembagian keuntungan atas akses dan
pemanfaatan sumber daya genetik. Sistematika Protokol meliputi 36 pasa dengan 1
lampiran yang mengatur sistem ABS atas akses sumber daya genetik termasuk yang
berasosial dengan pengetahuan tradisional yang diberikan berdasaarkan
kesepakatan bersama (Mutually Agreed Terms/MAT) dan persetujuan atas dasar
informasi yang diberitahukan terlebih dahulu (Free Prior Informed Consent/FPIC).
Bertalian dengan transformasi sistem ABS sebagai pelaksanaan kewajiban
Indonesia pasca ratifikasi CBD dan Nagoya Protocol walaupun Indonesia adalah
salah satu negara paling Makmur di dunia dalam keanekaragaman hayati serta
memiliki sumber daya genetik yang berlimpah terkait pengetahuan tradisional.
Namun pada bagian lain menunjukan banyak sumber daya genetik Indonesia
dibajak oleh pengguna yang dikomersialkan secara global (biopiracy), tanpa skema
pembagian keuntungan.
Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia masih belum mampu
memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal
323
yang telah melestarikan sumber daya genetik secara turun temurun karena
Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus yang
mengatur tentang sistem ABS dan yang mengatur mengenai masyarakat hukum
adat.
Perkembangan yang cukup baik sejauh ini adalah dalam konteks akses
Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76
mengatur mengenai perizinan peneliti asing di Indonesia. Pada prinsipnya peneliti
asing tidak dapat melakukan penelitian di Indonesia tanpa izin dari Pemerintah.
Sementara itu transfer dari materi keanekaragaman hayati secara fisik harus disertai
dengan perjanjian tertulis. Pasal 76 (h): “Kelembagaan ilmu pengetahuan dan
teknologi asing/orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia wajib
membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka pemindahan
atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital”.
Masalahnya Indonesia hanya mengatur akses namun belum
memperhitungkan pengaturan pembagian keuntungan sebagai hasil dari akses.
Sejauh ini belum ada kesepakatan pembagian keuntungan yang disepakati antara
pemerintah atau masyarakat hukum adat dengan pengguna. Hal ini berdampak
merugikan Indonesia dan masyarakat hukum adat karena tidak memperoleh
manfaat dari askes. Selain itu pengakuan dan peran masyarakat hukum adat dalam
sistem ABS juga belum diatur dengan jelas sehingga belum memberikan manfaat
optimal bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
324
l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan
ditetapkan menjadi Desa Adat. Adapun persyaratan masyarakat hukum adat
menajdu Desa Adat adalah:
1. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih
hidup baik bersifat territorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional
2. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai
dengan perkembangan masyarakat; dan
3. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa
menjadi Desa Adat merupakan bentuk pengakuan status masyarakat hukum adat.
Namun sejauh ini Undang-Undang Desa tidak berkaitan atau menyinggung
mengenai masyarakat hukum adat dan ABS sehingga dapat dikatakan Undang-
Undang lebih mengarah pada pengaturan penataan masyarakat hukum adat menjadi
Desa Adat.
m. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka
5 bahwa hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur
secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada
325
di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber
kehidupan dan mata pencahariannya.
Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah
hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan
musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk
memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Hal ini
diatur dalam Pasal 12 yang dikuatkan dengan rumusan Pasal 17 bahwa pejabat yang
berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat
masyarakat hukum adat kecuali telah dicapai persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12. Perlindungan terhadap tanah masyarakat hukum adat ini
diteguhkan kembali dengan mengatur sanksi bagi orang yang secara tidak sah
mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasai tanah masyarakat hukum
adat untuk usaha perkebunan (Pasal 107).
Walaupun telah mengakui hak ulayat dan mengatur perlindungannya namun
secara khusus Undang-Undang Perkebunan tidak mengatur mengenai pemanfaatan
sumber daya genetik dan ABS. Keterkaitan masyarakat hukum adat dengan
Undang-Undang Perkebunan adalah pada usaha perkebunan hanya dapat dilakukan
bila telah disetujui masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan paparan tersebut di atas dapatlah katakan bahwa peraturan
perundan-undangan Indonesia dan praktik pengadilan Mahkamah Konstitusi
tentang masyarakat hukum adat terkait hak atas sumber daya alam telah diakui.
Namun perwujudan sistem ABS dalam peraturan perundang-undangan tersebut
326
belum ada. CBD dan Nagoya Protocol telah meletakan landasan bagi negara untuk
meformulasikan sistem ABS dalam sistem hukum nasionalnya. Pengabaian negara
dalam mentransformasikan nilai, prinsip dan norma ABS terkait hak masyarakat
hukum adat berkonsekuensi pada ketiadaan perlindungan atas hak-hak masyarakat
hukum adat atas pembagian keuntungan.
2. Praktik Thailand terkait Transformasi Hukum Internasional mengenai
Access and Benefit Sharing (ABS) Hak Masyarakat Hukum Adat dalam
Hukum Nasional
Thailand sama halnya dengan Indonesia juga memiliki keanekaragaman
hayati yang berlimpah berupa spesies, genetik, dan keanekaragaman ekosistem.
Tidak kurang dari 200.000 spesies mikroorganisme, 14.000 spesies tanaman
vaskular dan non-vaskular, 4.000, spesies vertebrata atau 8% dari semua vertebrata
di dunia, tidak kurang dari 80.000 spesies invertebrate, 2.000 spesies ikan atau 10%
dari ikan yang diidentifikasi secara global.22
Dalam ranah budaya yang beragam dan sejarah yang Panjang bangsa
Thailand dikenal telah memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk memproduksi
makanan dan obat-obatan. Nilai-nilai dan pengetahuan tradisional yang dimiliki
bangsa Thailand telah diterapkan dalam memasak, produk jamu, kosmetik, dan
perawatan kesehatan. Dengan teknologi modern, aplikasi herbal Thailand secara
bertahap mengalami peningkatan untuk obat-obatan tradisional dna suplemen
kesehatan yang menghasilkan tidak kurang dari 30.000-40.000 juta baht per tahun,
22 Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning Ministry of
Natural Resources and Environmental Thailand BE 2528-2564, 2015, halaman 7.
327
dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 10-20%, sebagai hasil kekayaan
keanekaragaman hayati Thailand.23 Dalam praktik masyarakat hukum adat
Thailand disebut sebagai Suku Bukit (Hill Tribal). Terdapat sepuluh kelompok
masyarakat yang diakui secara resmi yang dinamakan “chao khao” yang berarti
Suku Bukit. Kelompok-kelompok ini merupakan kelompok masyarakat hukum
adat yang tinggal di bagian utara, bagian utara-barat dan bagian barat Thailand.24
Mereka terdiri dari The Lua, Htin, Khamu, Meo, Yao, akha, Lahu, Lisu, Karen
dan Mlabri.25
Praktik Thailand mengenai jaminan komunitas lokal dalam melestarikan
keanekaragaman hayati dan berhak atas manfaatnya diatur dalam ketentuan
Konstitusi Thailand Tahun 2017 Pasal 57 yang menentukan bahwa Negara wajib:
(1) melestarikan, menghidupkan kembali dan mempromosikan kearifan lokal, seni,
budaya, tradisi dan kebiasaan baik di tingkat lokal dan nasional, dan
menyediakan ruang publik untuk yang relevan kegiatan termasuk
mempromosikan dan mendukung orang-orang dan komunitas lokal untuk
melaksanakan hak-hak untuk berpartisipasi;
(2) melestarikan, melindungi, memelihara, memulihkan, mengelola dan
menggunakan atau mengatur pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan
keanekaragaman hayati secara seimbang dan berkelanjutan. Masyarakat lokal
diperbolehkan berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari upaya mereka
melakukan pelestarian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
23 Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning Ministry of
Natural Resources and Environmental Thailand BE 2528-2564, 2015, halaman 7. 24 Prasert Trakansuphakon, Menjamin Kepastian Hak Melalui Pluralisme Hukum:
Pengelolaan Tanah Komunal di Kalangan Masyarakat Hukum Adat Karen di Thailand, Epistema
Institute, Jakarta, halaman 151, diakses pada
https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/divers-paths-justice-bahasa-
indonesia.pdf. 25 https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/30854.pdf,
Wanat Bhruksarsi, “Government Policy: Highland Ethnic Minorities”, halaman 6 diakses pada
tanggal 12 November 2020. Nama masyarakat hukum adat di Thailand yang disebut Suku Bukit
atau dalam Bahasa Thailand Chao Khao merupakan sebutan kolektif yang digunakan secara resmi
sejak tahun 1959 saat Pemerintah Thailand membentuk Pusat Komite Suku Bukit. Lihat juga
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.476.7011&rep=rep1&type=pdf,
Chupinit Kesmanee and Prasert Trakansuphakorn, “An Assessment of The Implementation of The
Thai Government’s International Commitments on Traditional Forest-Related Knoledge from the
Perspective of Indigenous Peoples”, halaman 6.
328
Perkembangan keberadaan masyarakat hukum adat di Thailand yang
dikenal dengan Hill Tribe terlihat pada peran mereka dalam melakukan konservasi
keanekaragaman hayati melalui cara tradisonal.26 Berbagai kelompok masyarakat
hukum adat yang menghuni dataran tinggi Thailand utara secara kolektif dikenal
sebagai Suku Bukit dan mempraktikkan berbagai teknik pertanian tradisional.27
Salah satu praktik konservasi keanekaragaman hayati dikenal dengan sebutan
‘miang’ dan ditanam tanpa menggunakan silvikultur manajemen atau cara
pertanian modern. Selain itu tercatat praktik masyarakat hukum adat Suku Hmong
di Thailand dikenal sebagai komunitas utama dalam melakukan konservasi
keanekaragaman hayati melalui .28
Keikutsertaan Thailand dalam CBD dan telah meratifikasinya namun tidak
demikian dengan Protocol Nagoya dimana Thailand belum melakukan tindakan
26 Edward Osborne Wilson, Biodiversity, National Academic of Sciences/Smithsonian,
National Academic Press, 2011, halaman 410. 27 Watana Sackchoowong and Weeyawat Joitrong, “Ant Diversity in Forest and Traditional
Hill Tribe Agricultural in Northern Thailand”, Natural Science Journal 42 (4), October 2008,
halaman 617. 28 Chandra Shekhar Silori, “From Cabbage to Conservation: Case of Community Forest
Conservation Hmong Tribe in Northern Thailand”, in Biodiversity Community and Climate
Change, edited by Chandra Prakash Kala, The Energy and Resources Institute, 2013, halaman 149.
Lihat juga Udom Charoenniyomhrai et at, Indigenous Knowledge Customary Use of Natural
Resources Sustainable Biodiversity Management: Case Study Hmong and Karen Communities in
Thailand, 2006, halaman 8 diakses pada
https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/10cthailandimpectjun06eng.pdf:
“In northern Thailand, there are a number of tribal and ethnic groups residing in highland areas.
They are referred to by the majority ethnic Thais and the Thai government as “Thai hill tribal
people” or “hill tribes.” These ethnic groups include the Karen, Hmong, Lisu, Lahu, Akha, Mien,
Lu’a, and others. The total population of “hill tribes” is around 1.2 million. These peoples have
tradition, culture, language, belief, and ways of life that are distinguished from those of the
lowland people. They have vast bodies of knowledge and local wisdom about living in their forest
environment, such as rotational swidden agriculture, managing sacred forests, taboo forests, and
religious-use forests. Many of their customs are relevant and appropriate to natural resources and
environmental management. They practice traditional regulations and conventions for controlling,
conserving and using resources in a sustainable manner”.
329
ratifikasi, kewajiban Thailand terkait sistem ABS diwujudkan dengan
mentransformasikan amanah Pasal 8, Pasal 15 CBD dan ketentuan Nagoya Protocol
dalam dua undang-undang nasionalnya yaitu Plant Variety Protection ACT 1999
dan Protection and Promotion of Traditional Thai Medecinal Intellingence ABT
B.E 2542 (1999).
Secara umum, walaupun Thailand bukan merupakan pihak dalam Nagoya
Protocol tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang
Adil dan Setara yang dihasilkan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, namun
demikian, Thailand telah memiliki persyaratan tentang akses dan pembagian
manfaat (ABS), berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan
tentang varietas tanaman, keanekaragaman hayati dan obat tradisional Thailand.
Peraturan perundang-undangan berikut memuat ketentuan yang terkait dengan ABS
yaitu:29
1. Konstitusi Thailand 2017
2. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT Act) Tahun 1999 yang
diterbitkan pada tanggal 25 November 1999.
3. Undang-Undang Perlindungan dan Promosi Pengetahuan Obat Tradisional
Thailand (Traditional Knowledge Act) yang diterbitkan pada 29 November
1999 dan mulai berlaku 180 hari kemudian.
4. Peraturan Perdana Menteri tentang Konservasi dan Pemanfaatan
Keanekaragaman Hayati (Office of Prime Minister’s Regulations on the
Conservation Utilization of Biodiversity tahun 2000)
29 Union For Ethical Bio Trade Thailand, op. cit., halaman 1-3.
330
5. Peraturan Komite Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman
Hayati secara Berkelanjutan tentang Kriteria dan Prosedur Akses terhadap
Sumber Daya Gentik dan Pembagian Manfaat (ABS Regulation) tahun 2011
6. Peraturan Komite Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman
Hayati secara Berkelanjutan tentang Kriteria dan Prosedur Akses terhadap
Sumber Daya Gentik dan Pembagian Manfaat (Peraturan ABS Tahun 2011).
Berikut dipaparkan praktik Thailland dalam membentuk peraturan perundang-
undangan nasional untuk menerapkan kewajiban dalam perjanjian
internasionalnya.
a. Plant Variety Protection Act 1999
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Thailand tahun 1999
(Protection Variety Plant Act/ PVP 1999) adalah sistem sui generis yang dibentuk
untuk melaksanakan Convention on Biological Diversity (CBD) yang berisi tiga
jenis perlindungan untuk varietas tanaman:
1. perlindungan kekayaan intelektual untuk varietas tanaman baru yang baru,
berbeda, seragam, dan stabil;
2. perlindungan kekayaan intelektual untuk varietas domestik lokal yang berbeda,
seragam dan stabil (Distinct Uniform and Stable), tetapi belum tentu baru; dan
3. perlindungan akses dan pembagian keuntungan untuk varietas tanaman
domestik umum dan varietas tanaman liar.
Pengaturan mengenai kaitan antara masyarakat hukum adat Thailand yang di dalam
Konstitusi disebut sebagai local community sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
57 Konstitusi Thailand 2017 mengenai peran masyarakat lokal dalam pelestarian
331
keanekaragaman hayati diakomodir dalam PVP Act 1999 dalam beberapa
ketentuan berikut:
Pasal 43
“Suatu varietas tanaman yang dapat mengajukan pendaftaran sebagai varietas
tanaman masyarakat lokal berdasarkan Undang-undang ini harus:
a. suatu varietas tumbuhan yang hanya ada di daerah setempat di dalam
Kerajaan
b. varietas tanaman yang belum terdaftar sebagai varietas tanaman baru.”
Pasal 44
“Seorang ahli waris yang bertempat di masyarakat lokal dan mewarisi budaya
masyarakat lokal serta berperan dalam melestarikan atau mengembangkan
varietas tanaman yang memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 43
dapat mendaftar sebagai masyarakat lokal berdasarkan Undang-undang ini
dengan meminta perwakilan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Gubernur.”
Permohonan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. varietas tanaman yang dilestarikan dan dikembangkan bersama dan cara
pelestariannya atau pengembangannya
b. nama anggota kelompok masyarakat lokal
c. lanskap dengan peta kasar yang menunjukkan masyarakat lokal dan daerah
sekitarnya.
d. Permohonan dan pertimbangannya harus sesuai dengan peraturan dan
pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang ABS.”
Pasal 45.
Suatu varietas tanaman yang hanya ada di daerah setempat dan telah dilestarikan
atau dikembangkan sendiri oleh masyarakat lokal setempat, masyarakat tersebut
berhak meminta kepada organisasi pemerintahan setempat untuk mengajukan
permohonan pendaftaran varietas tanaman atas nama masyarakat lokal.
Setelah menerima permintaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
paragraf satu, organisasi administrasi lokal harus mengajukan pendaftaran varietas
tanaman masyarakat lokal kepada Komite sejak hari semua dokumen dan informasi
yang diperlukan diserahkan.
332
Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam paragraph satu diorganisir
sebagai kelompok tani atau koperasi menurut undang-undang koperasi, kelompok
tani atau koperasi tersebut berhak untuk mengajukan pendaftaran varietas tanaman
lokal lokal atas nama masyarakat lokal.
Berdasarkan ketentuan Pasal 43, 44 dan Pasal 45 masyarakat lokal dalam
kontekstual ini adalah masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi melestariakan
sumber daya genetik secara turun temurun dan diakui oleh negara sebagai penyedia
yang memiliki hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan bila pihak pengguna
melakukan akses dan pemanfaatan.
Adapun ketentuan mengenai ABS terdapat dalam Pasal 48 PVP Act yaitu:
Pasal 48
Setiap orang yang memungut, memperoleh atau memungut suatu varietas tanaman
masyarakat lokal atau bagiannya untuk pengembangan varietas, studi, percobaan
atau penelitian untuk tujuan komersial, harus membuat perjanjian pembagian
keuntungan tentang varietas tanaman lokal.
Dalam mengizinkan setiap orang untuk mengambil tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat pertama dan dalam membuat perjanjian pembagian
keuntungan, organisasi pemerintah daerah, kelompok tani atau koperasi yang
menerima sertifikat pendaftaran varietas tanaman dalam negeri melakukan
transaksi atas nama komunitas lokal, dengan perjanjian persetujuan terlebih dahulu
dari Komite.
Pengaturan adanya sistem ABS sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal
48 seterusnya diteguhkan kembali ketentuan Pasal 49 bahwa:
Dari hasil pemberian izin kepada orang lain untuk menggunakan hak atas varietas
tanaman lokal setempat, dua puluh persen diberikan kepada orang yang memelihara
atau mengembangkan varietas itu, enam puluh persen kepada masyarakat sebagai
pendapatan bersama, dan dua puluh persen kepada pemerintah daerah, organisasi,
kelompok tani atau koperasi yang melakukan transaksi.
Pembagian keuntungan di antara orang-orang yang memelihara atau
mengembangkan varietas tanaman harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan
oleh Komite.
333
Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembagian keuntungan berdasarkan
paragraf satu, Komite memberikan keputusan akhir.
Ketentuan Pasal 52 PVP Act 1999 mengatur lebih lanjut mengenai adopsi prinsip
Free Prior Informed Consent/FPIC dan Mutually Agreed Term/MAT sebagai yang
diamanahkan dalam CDB dan Nagoya Protocol yaitu sebagai berikut:
Setiap orang yang memungut, memperoleh atau memungut varietas tanaman
domestik biasa, varietas tanaman hutan atau bagiannya untuk pengembangan
varietas, studi, percobaan atau penelitian untuk tujuan komersial,
memerlukan izin dari pejabat yang bertanggung jawab dan harus membuat
perjanjian pembagian keuntungan dimana sebagian dananya diberikan
kepada Dana Perlindungan Varietas Tanaman sesuai dengan peraturan,
pedoman, dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
Perjanjian pembagian keuntungan sekurang-kurangnya memuat:
1. tujuan pengumpulan dan pengumpulan varietas tanaman;
2. jumlah atau jumlah sampel varietas tanaman yang dibutuhkan;
3. hak dan kewajiban pengguna dan penyedia;
4. penetapan hak atas kekayaan intelektual hasil modifikasi, kajian,
percobaan, atau penelitian varietas tanaman yang disepakati;
5. menetapkan besaran, persentase, dan jangka waktu pembagian
keuntungan menurut perjanjian tentang hasil-hasil yang berasal dari
varietas tumbuhan;
6. lamanya perjanjian;
7. pencabutan perjanjian;
8. tata cara penyelesaian sengketa;
9. hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
Ketentuan mengenai adopsi prinsip Free Prior Informed Consent dan Mutually
Agreed Term dalam PVP Act tahun 1999 merupakan transformasi dari ketentuan
Pasal 8 (J) Pasal 15 CBD dan ketentuan Nagoya Protocol. Selanjutnya, Peraturan
Komite Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati yang
Berkelanjutan tentang Kriteria dan Prosedur untuk Akses ke Sumber Daya Hayati
dan Pembagian Manfaat (Peraturan ABS) mendorong lembaga pemerintah yang
memiliki yurisdiksi atas sumber daya hayati yang tidak tercakup dalam Undang-
334
Undang PVT atau Undang-Undang Pengetahuan Tradisional untuk
mengembangkan mekanisme ABS mereka sendiri. Pada tahun 2014, Thailand telah
memiliki 11 organisasi, termasuk Departemen Taman Nasional, Satwa Liar dan
Tumbuhan dan BIOTEC telah mengembangkan mekanisme untuk menerapkan
Peraturan ABS.
Menurut Peraturan ABS, akses ke sumber daya hayati untuk
pemanfaatannya memerlukan otorisasi dari pejabat negara yang berwenang atas
atas sumber daya genetik, namun setiap lembaga dapat menentukan mekanisme
ABS-nya sendiri, tetapi persyaratan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang PVP Act dan harus didasarkan pada prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan. Informasi dan komitmen yang diperlukan dari pemohon termasuk daftar
spesies, kultivar atau sumber daya hayati lainnya yang akan diakses, kegiatan
penelitian dan pengembangan khusus yang akan dilakukan, pembagian
keuntungan, pembatasan transfer ke pihak ketiga dan perubahan penggunaan, dan
cara-cara di mana setiap kekayaan intelektual hak yang timbul dari akses terhadap
sumber daya hayati akan dikelola wajib diperjanjikan dan disepakati secara
bersama.
b. The Act on Protection and Promotion of Traditional Thai Medicinal
Intelligence Tahun 1999 (UU Perlindungan dan Promosi Obat
Tradisional Thailand)
Setelah membentuk PVP Act tahun 1999 Thailand juga secara sui generis
mentransformasikan sistem ABS dan membangun peraturan perundang-undangan
yang sui generis kedua dalam menindaklanjuti kewajibannya sesuai CBD
335
membentuk sistem ABS yaitu ‘The Act on Protection and Promotion of Traditional
Thai Medicinal Intelligence Tahun 1999’ (UU Promosi Obat Tradisional
Thailand).30 UU Promosi Obat Tradisional Thailand adalah suatu peraturan tentang
keunggulan obat tradisional Thailand yang substansinya mengenai pengetahuan
dan kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengobatan tradisional berupa
prosedur pengobatan, pemeriksaan, diagnosis, terapi, pencegahan dan promosi
kesehatan termasuk penemuan obat-obatan tradisional berdasarkan pengetahuan
tradisioanl dan teks yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.
Obat tradisional Thailand berarti obat-obatan yang diperoleh langsung dari
tumbuh-tumbuhan atau berasal dari ramuan campuran, dan termasuk juga obat-
obatan tradisional Thailand menurut undang-undang tentang obat-obatan. Teks
tentang pengobatan tradisional Thailand ini berisi pengetahuan teknis yang
berkaitan dengan pengobatan tradisional Thailand yang telah ditulis atau dicatat
dalam buku-buku Thai, daun palem, batu prasasti atau bahan lain atau yang belum
dicatat tetapi diturunkan dari generasi ke generasi.31
Institut Pengobatan Tradisional Thailand bertanggung jawab untuk
mengumpulkan informasi tentang dokumen medis pengabotan tradisional Thailand
yang berkaitan dengan formula obat tradisional Thailand dan teks tentang
pengobatan tradisional Thailand dari seluruh negeri untuk didaftarkan. Ketentuan
yang berkaitan erat dengan sistem ABS dan hak kekayaan intelektual ditemui dalam
30 Gabrielle Gagne and Chutima Ratanasatien, op. cit., halaman 311-312, “the Thai Plant
Varieties Protection Act 1999 is sui generis system that contains … access and benefit sharing for
domestic plant” 31 WIPO, “Traditional Knowledge Laws: Thailand, diakses pada
https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/articles/article_0024.html.
336
beberapa Pasal 19 bahwa siapa pun yang ingin menggunakan obat tradisional
Thailand untuk pendaftaran dan izin produksi obat menurut undang-undang atau
ingin menggunakannya untuk penelitian tentang perbaikan atau pengembangan
formula obat baru untuk keuntungan komersial, atau ingin melakukan penelitian
nasional teks tentang Obat Tradisional Thailand untuk pengembangan dan
peningkatan untuk keuntungan komersial, harus mengajukan aplikasi untuk
mendapatkan manfaat dan membayar biaya dan membagi keuntungannya kepada
otoritas lisensi. Formula pribadi obat tradisional Thailand atau teks pribadi tentang
pengobatan tradisional Thailand dapat didaftarkan untuk perlindungan hak
kekayaan intelektua.
Kemudia ketentuan Pasal 34 menentukan bahwa pemegang hak memiliki
kepemilikan tunggal atas produksi obat dan memiliki hak tunggal atas penelitian,
distribusi, perbaikan atau pengembangan formula obat tradisional Thailand atau
hak kekayaan intelektual obat tradisional Thailand di bawah teks terdaftar tentang
pengobatan tradisional Thailand. Ketentuan ini lalu diperkuat oleh Pasal 46 bahwa
tidak seorangpun boleh meneliti atau mengekspor obat tradisional atau jamu atau
menjual atau mengubahnya untuk tujuan komersial, kecuali jika izin telah diperoleh
dari otoritas pemberi lisensi.
Menurut Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif, Thailand
telah ditemukan sekitar 170.602 resep obat tradisional Thailand. Menurut
ketentuan The Act on Protection and Promotion of Traditional Thai medicinal
Intelligence Tahun 1999 siapa pun yang memerlukannya mendaftarkan obat
tradisional Thailand dan meminta izin untuk memproduksi obat atau perlu
337
mempelajari obat-obatan tersebut untuk komersial, meningkatkan atau
mengembangkan menjadi resep medis baru, ia harus mengajukan izin untuk
membuat penggunaan dan harus membayar biaya layanan termasuk biaya
kompensasi atau pembagian keuntungan untuk penggunaan obat-obatan tersebut
kepada orang yang mengizinkan.32
Hal tersebut merupakan elemen ABS dalam UU Promosi Obat Tradisional
yang diatur dalam ketentuan Pasal 19. Lebih jauh, Thailand juga telah mengatur
mengenai batasan hak dan kompensasi biaya didasarkan pada peraturan, sarana,
dan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian yang berwenang untuk
pertimbangan ABS atau pembagian keuntungan yaitu:33
1. uang 3% dari penjualan di pabrik
2. ganti rugi bukan uang seperti transfer teknologi dan penyebaran hasil studi.
3. Pelatihan/bimbingan teknis
4. Pertukaran data/pengetahuan yang ditunjukkan
5. pertukaran staf
6. penciptaan jaringan kerja sama
7. investasi bersama dalam bisnis
8. asuransi jiwa untuk staf
9. bentuk lain yang disepakati bersama.
32 Nanthasak Chotichanadechawong and Somboon Sirisunhirun, The Development Policy
on Access and Sharing of Benefit from National Knowlegde of The Thail Traditional Medicine,
International Journal of Crime, Law, and Social Issue, Vol.5 (3) January-June 2018, HALAMAN
195 33 Nanthasak Chotichanadechawong and Somboon Sirisunhirun, The Development Policy
on Access and Sharing of Benefit from National Knowledge of The Thai Traditional Medicine,
International Journal of Crime, Law, and Social Issue, Vol.5 (3) January-June 2018, halaman
194.
338
Selanjutnya prosedur akses dan pembagian keuntungannya berlandaskan
pembayaran kompensasi yang ditetapkan dan disepakati bersama antara penerima
manfaat, orang yang mengizinkan, dan orang yang diizinkan dengan cara: 34
1. menunjuk komite operasi untuk mempertimbangkan kontrak atau perjanjian
kasus pembagian keuntungan dengan resep medis dan
2. mengumumkan daftar nama para ahli tersebut sebagai database untuk proposal
untuk menjadi komite operasi termasuk pembuatan kontrak untuk pembagian
keuntungan berdasarkan kasus per kasus
Dalam rangka mengimplementasikan CBD Pada tahun 2000, Thailand membentuk
badan pemerintah yang otonom yaitu Pusat Keanekaragaman Hayati Thailand yang
bertugas untu mengatur access and benefit sharing namun pada pada tahun 2002,
tugas-tugas ini dialihkan ke Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang
baru dibentuk. Titik fokus nasional tentang ABS saat ini adalah Divisi
Keanekaragaman Hayati di Kantor Sumber Daya Alam dan Kebijakan dan
Perencanaan Lingkungan. Sesuai dengan UU PVT dan UU Promosi Obat
Tradisional Thailand secara kelembagaan pelaksanaan ABS terkait dengan institusi
Departemen Pertanian untuk akses ke varietas tanaman liar dan varietas tanaman
domestik umum, masyarakat lokal, Kelompok tani, koperasi atau otoritas lokal
dengan sertifikat pendaftaran untuk akses ke lokal yang relevan varietas tanaman
domestic dan Departemen Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Alternatif
34 Nanthasak Chotichanadechawong and Somboon Sirisunhirun, ibid, halaman 195-196
339
Thailand atau Kementerian Kesehatan Masyarakat untuk akses ke formula nasional
obat tradisional Thailand.
Thailand saat ini memiliki hukum dan peraturan berikut yang terkait
administrasi, pemantauan dan konservasi sumber daya hayati yang secara tidak
langsung mendukung Thailand dalam penerapan akses dan pembagian keuntungan
sumber daya genetik yaitu:35
1. Undang-Undang Kehutanan, B.E. 2484 (1941) yang dibentuk untuk
mengendalikan dan menghentikan penebangan kayu dan mempercepat
pemulihan kondisi hutan
2. Undang-Undang Taman Nasional, B.E. 2504 (1961) yang diterbitkan guna
memastikan kondisi konservasi alam mereka yang tidak berubah dan tidak
rusak
3. Undang-Undang Konservasi dan Perlindungan Satwa Liar, B.E. 2535 (1992)
yang mengatur jenis tindakan terkait yang diizinkan dan dilarang oleh regulas
ini yang menekankan konservasi dan perlindungan;
4. Peraturan Dewan Riset Nasional tentang izin bagi peneliti asing untuk
melakukan pekerjaan penelitian di Thailand, B.E. 2550 (2007)
5. Undang-Undang Hutan Lindung Nasional The National Reserved Forest Act
(No.4), B.E. 2559 (No.4), B.E. 2559 (2016) yang mengatur kebijakan dan
langkah-langkah dalam melindungi, mencegah dan melestarikan sumber daya
alam dan pemanfaatan cadangan hutan nasional.
35 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/th-nr-06-en.pdf Thailand Sixth National Report on
the Implementation on Convention Biological Diversity, June 2019, halaman 80.
340
Selain itu, telah ada pengembangan baru pada Community-Access and
Benefit Sharing (C-ABS), yang bertalian dengan berbagai komunitas sebagai
pemegang sumber daya genetik yang dapat mengklaim pembagian keuntungan
dalam bentuk uang tunai dan barang, dengan demikian skema yang diterapkan
sesuai prinsip distribusi pembagian keuntungan yang adil.36 Dalam beberapa tahun
terakhir telah ada dua perkembangan hukum dalam kaitannya dengan akses dan
pembagian keuntungan yang mencakup sumber daya genetik dan kebijakan
endemik terkait. Perkembangan ini termasuk rancangan undang-undang Promosi
dan Konservasi Hewan Endemik, yang terkait dengan akses dan pembagian
keuntungan yang tercakup dalam jenis sumber daya hewan, dan Peraturan
Rekayasa Genetika dan Bioteknologi terkait dengan akses dan pembagian
keuntungan dari sumber daya biologis.
Thailand juga melakukan pengembangan mekanisme untuk mengakses
sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil terutama didasarkan
pada akses sumber daya hayati dan pembagian manfaat, yaitu, melalui mekasnime
Prior Informed Consent (PIC) pemberitahuan sebelumnya, perjanjian tentang
pembagian keuntungan yang adil.37
Berdasarkan praktik Thailand dapatlah dipahami bahwa persyaratan ABS
dalam UU PVT, UU Promosi Obat Tradisional Thailand, dan Peraturan ABS
apabila dicermati semuanya memuat berbagai pengaturan dan persyaratan serta
referensi tentang pembagian keuntungan dan manfaat. PVT Act menyatakan bahwa
36 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/th-nr-06-en.pdf Thailand Sixth National Report on
the Implemention on Convention Biological Diversity, June 2019, halaman 64 dan 80. 37 https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/th-nr-06-en.pdf Thailand Sixth National Report on
the Implemention on Convention Biological Diversity, June 2019, HALAMAN 80
341
akses ke varietas tanaman masyarakat lokal dan liar tunduk pada pembagian
keuntungan yang adil dan merata (ABS system), termasuk melalui Dana
Perlindungan Varietas Tanaman. Perjanjian pembagian keuntungan harus
mencakup ketentuan tentang hak kekayaan intelektual dan jumlah atau persentase
tertentu dari manfaat keuntungan yang akan dibagikan, serta durasi kewajiban
pembagian keuntungan.
Demikian pula Undang-Undang Pengetahuan Tradisional mengacu pada
peraturan yang memberikan kondisi untuk pembagian keuntungan dalam kaitannya
dengan formula obat. Sedangkan berdasarkan Peraturan ABS telah ditetapkan
beberap parameter tertentu tentang jenis keuntungan yang akan dibagikan yaitu
perjanjian pembagian keuntungan antara pengguna dan penyedia serta lembaga
negara yang mengeluarkan izin harus memperkirakan manfaat moneter dan non-
moneter. Pembagian manfaat non-moneter mencakup partisipasi peneliti atau
ilmuwan Thailand dalam proyek pembagian keuntungan moneter mencakup
manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya hayati dan penerapan
selanjutnya dari produk, proses, dan informasi yang dihasilkan.
Berdasarkan paparan praktik Thailand mentransformasikan sisten access
and benefit sharing/ABS CBD dan Nagoya Protocol ke dalamm sistem hukum
nasionalnya yang sui generis yang meliputi sumber daya genetik tanaman dalam
PVP Act tahun 1999 dan pengetahuan obat tradisional masyarakat lokal yang
diturunkan dari generasi ke generasi dalam The Act on Protection and Promotion
of Traditional Thai medicinal Intelligence Tahun 1999 dapatlah dipahami bahwa
Thailand menyikapi perjanjian internasional dengan menganut doktrin dualisme.
342
Transformasi tersebut berarti hukum internasional diberlakukan dalam
hukum nasional melalui pengubahan bentuk secara formal dan substansi dengan
mentransformasikan kewajiban CBD dan Nagoya Protocol yang mengamanahkan
mengambil langkah hukum dan upaya kebijakan lainya yang ditentukan dalam
perjanjian internasional ke dalam undang-undang nasional. Dengan transformasi
hukum internasional ke dalam hukum nasional ini menunjukan bahwa Thailand
berkomitmen menjalankan perjanjian internasional sekaligus melindungi kekayaan
keaneakaragaman hayati dan pengetahuan obat tradisional yang telah diturunkan
dari generasi ke generasi melalui sistem ABS.
C. Pengembangan Hukum ke Depan Terkait Transformasi Access and
Benefit Sharing Hak Masyarakat Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional
1. Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
(the 17 of Sustainable Development Goals)
Pada Rio Earth Summit 1992 delegasi masyarakat hukum adat
mendeklarasikan Indigenous Peoples Earth Charter yang menegaskan beberapa hal
penting yaitu: 1) hak asasi manusia masyarakat hukum adat dan hukum
internasional; 2) tanah dan wilayah; 3) keanekaragaman hayati dan konservasi; 4)
strategi pembangunan berbasis kearifan lokal; dan 5) budaya, ilmu pengetahuan,
dan kekayaan intelektual.
Bagi masyarakat hukum adat konservasi sumber daya genetik dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan bukanlah hal baru, sebaliknya bagian dari
budaya, sejarah dan spritualitas yang mentradisi. Indigenous Peoples Earth Charter
menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat hukum adat yang masih tinggal di
343
wilayah mereka menjaga dan melanjutkan adat istiadat leluhur. Mereka adalah
aktor kunci dalam pelestarian alam karena ikatan yang kuat dengan tanah,
keanekaragaman hayati, satwa liar, dan semua elemen api, air bulan dan bintang.
Keterkaitan masyarakat hukum adat dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan karena memiliki ciri khusus yang ditandai dengan praktik konservasi
keanekaragaman hayati, sumber daya alam baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir
dan laut. Praktik dan kearifan lokal yang turun temurun diwariskan dari generasi ke
generasi bahkan dianggap dan terbukti lebih baik dati bentuk-bentuk konservasi
dan pelestarian lingkungan yang dibuatt oleh negara, swasta atau pengajur
konservasi dan pelestarian lingkungan lainnya.38
Salah satu contoh kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam penggunaan
tanah dalam kaitannya dengan konservasi dan pembangunan berkelanjutan adalah
misalnya Masyarakat Hukum Adat Dayak Bentian di Kalimantan Timur dikenal
dengan praktik konservasi tanah dengan membudidayakan rotan. Rotan yang
ditanam pada lahan merupakan bagian dari usaha gilir bilik. Usaha ini dikenal dapat
mempercepat waktu panen dengan tumbuhan pionir sekaligus mempertahankan
fungsi kesuburan tanah. Praktik-praktik ini telah dilakukan oleh Masyarakat
Hukum Adat Dayak Bentian keturunan Jato Rampangan di wilayah adatnya sejak
tahun 1813 yang dipimpin oleh Kepala Adatnya.39
Dalam hubungannya dengan konservasi dan konsep ABS dalam
pemanfaatan sumber daya genetik berasal dari CBD yang mengakhiri era konsep
38 Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Hak Asasi Manusia,
Komnas HAM, 2016, halaman 24. 39 Ibid., halaman 26-27
344
warisan bersama umat manusia terdapat keselarasan praktik-praktik konservasi
tersebut dengan the 17 Goals of Sustainable Development/SDGs.40 Hal ini
mengingat bahwa pencanangan SDGs tidak terlepas dari kesepakatan KTT Bumi
di Rio 1992. Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang
menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. SDGs merupakan
komitmen global dan nasional dengan the 17 Goals of Sustainable Development
yang meliputi: 1) No Poverty, 2) Zero Hunger, 3) Good Health and Well Being, 4)
Quality Education, 5) Gender Quality, 6) Clean Water and Sanitation, 7)
Affordable and Clean Energy, 8) Decent Work and Economic Growth, 9) Industry,
Innovation and Infrastructure, 10) Reduce Inequalities, 11) Sustainable Cities and
Communities, 12) Responsible Consumption and Production, 13) Climate Change,
14) Life Below Water, 15) Life on Land, 16) Peace, Justice and Strong Institutions,
and 17) Partnership for the Goals.
Terkait dengan penelitian ini, konservasi dan pemanfaatan secara
berkelanjutan sumber daya genetik merupakan kepentingan yang menentukan
untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi
penduduk dunia yang selalu berkembang. Sumber daya genetik menyediakan
kebutuhan dasar dari semua proses produksi pangan dan kunci untuk
40
345
keberlangsungan kehidupan manusia termasuk saat perubahan iklim dan perubahan
lingkungan lainnya,41 dan berhubungan erat dengan aspek ketahanan pangan,
ekonomi, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.42
Pemanfaatan sumber daya genetik dewasa ini semakin digemari seiring
dengan gaya hidup kembali ke alam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Penemuan rekombinan DNA di tahun 1953,43 yang mengarah pada
kemajuan-kemajuan genetik yang diikuti dengan kelahiran industri yang dikenal
saat ini hingga menyebabkan kebutuhan akan sumber daya genetik yang berasal
dari tanaman, hewan, dan mikro organisme meningkat tajam untuk dipakai sebagai
materi atau bahan (valuable raw materials) di berbagai bidang kehidupan.
Akibatnya, industri bioteknologi bermunculan pada sektor-sektor industri
pertanian, produksi makanan, kesehatan, biofarmasi, dan kosmetik.
Berdasarkan pemasaran produk-produk tersebut di berbagai sektor, estimasi
omzet dari penjualan produk-produk yang berbasis sumber daya genetik
diperkirakan sebesar 500-800 milyar USD per tahun.44 Gambaran nilai ekonomi ini
terus meningkat dari bioprospecting sumber daya genetik yang mencakup sektor
obat-obatan, produk pertanian, tanaman hias, kosmetik dan berbagai produk
bioteknologi lainnya.45
41 Stephen Brush, op. cit. 42 Efridani Lubis, op. cit., halaman 1. 43 Sarah L Elrod dan William D Stansfield, Shaum’s Outside of Theory and Problem of
Genetic, Fourth Edition, 2007, Erlangga, halaman 270. 44 Sudarmono Ahmad Tahir, Potensi Sumber Daya Genetik Indonesia dalam
Komersialisasi Produk Bioteknologi, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tt, halaman 3. 45 https://kolom.tempo.co/read/1330389/virus-corona-dan-sumber-daya-genetik-
indonesia, Roni Megawanto, “Corona dan Sumber Daya Genetik Indonesia”.
346
Nilai ekonomi, pengetahuan dan teknologi yang besar dalam sumber daya
genetik yang pada umumnya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat ini
diekplotasi dan diakses oleh tanpa pembagian keuntungan karena awalnya
dianggap benda bebas. Secara historis, perkembangan pembangunan berkelanjutan
dalam hukum internasional menunjukan bahwa konsep Common Heritage of
Mankind (CHM) sumber daya genetik sebagai benda bebas tidak ada pemiliknya
yang bila diakses siapapun telah menguntungkan satu pihak saja yaitu negara-
negara maju dengan perusahaan besarnya dan para penelti yang memiliki dukungan
dana untuk diinvestasikan atas pengembangan sumber daya genetik. Akibatnya
negara-negara kaya sumber daya genetik dan masyarakat hukum adat tidak
mendapat pembagian manfaat atas nilai ekonomi yang dinikmati negara-negara
maju dan perusahaan farmasi yang secara kenyataan miskin akan sumber daya.46
Sementara itu, di tingkat nasional juga memperlihatkan bahwa beberapa
kasus di Indonesia mengambarkan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur,
pemerintah sering mengalami konflik dengan masyarakat hukum adat. Sepanjang
tahun 2018 terdapat 326 konflik sumber daya alam dan agraria yang melibatkan
areal seluas 2.101.858 hektar dengan korban total mencapai 186.631 jiwa dari total
korban itu, 176.637 di antaranya berasal dari masyarakat hukum adat. Data tersebut
menjadikan masyarakat hukum adat sebagai salah satu pihak yang paling rentan
dalam masalah konflik tanah dan sumber daya alam. 47
46 Anna Deplazes Zemp, “Commutative Justice and Access and Benefit Sharing for Genetic
Resources”, 2018, Ethics, Policy Environment, Volume 21 No. 1, halaman 19, diakses pada
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/160847/1/Deplazes-Zemp_2018_Commutative_justice.pdf
tanggal 24 Desember 2020. 47 Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan
Hak Asasi Manusia terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Sasi Vol. 26 No. 3 2020,
347
Sebagian kebijakan dilakukan tanpa menghormati hak-hak mereka.48
Dalam banyak kasus49, kebijakan sudah dijalankan ketika izin-izin dari pemerintah
sudah diperoleh, sementara konsultasi tidak dilakukan dan persetujuan masyarakat
hukum adat belum diperoleh. Masyarakat hukum adat akhirnya melihat bahwa
hutannya telah ditebang, tanahnya ditambang, lembahnya dibanjiri, tempat
berburunya dipagari, ladang-ladangnya ditempati. Hal tersebut terjadi tanpa bisa
mengatakan apa-apa dan seringkali terjadi tanpa mendapatkan keuntungan
apapun.50
Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan sumber daya alam yang mengakui
hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam berdasarkan kebijakan
pengakuan bersyarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Kebijakan pengakuan tersebut ditambah lagi dengan kebijakan harus melalui
pengukuhan dalam suatu peraturan daerah.51 Terlebih lagi dengan adanya Putusan
hlm. 381. Lihat juga Nisa Istiqomah Nidasari, “Peluang Penerapan FPIC sebagai Instrumen Hukum
Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Usaha Tambang dan
Minyak Bumi”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017, halaman 52, diakses pada
https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/15, tanggal 12 Maret 2021 48 Renee V Hagen and Tessa Minter, “Displacement in the Name of Development How
Indigenous Right Legislation Fails to Protect Philippine Hunter Gatherer”, Vol. 33 Issue 2, 2020, P.
66, diakses pada https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941920.2019.1677970 49 Deti Mega Purnamasari, “Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga
Kriminalisasi”, Harian Kompas, diakses pada
: https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-
terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all: “… “: “ketika investasi atau proyek
pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin
tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah. Mereka mengalami perampasan
wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi.” 50 Emil Kleden, “Konsep Free Prior Informed Consent”, Kertas Kerja dalam Pelatihan
Impact Elsam 23 Pebruari 2017, halaman 9, diakses pada
https://referensi.elsam.or.id/2017/06/konsep-prinsip-free-prior-informed-consent 51 Unsur-unsur untuk dikukuhkannya suatu komunitas sebagai masyarakat Hukum Adat
diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
menegaskan bahwa masyarakat Hukum Adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
348
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memutuskan hutan adat
bukanlah hutan negara melainkan hutan adat adalah bagian dari wilayah adat yang
merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut persoalan mengenai hutan adat dapat dikatakan memiliki
kepastian hukum yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pengakuan dan
pengukuhan masyarakat hukum adat agar keberadaan masyarakat hukum adat
beserta hak-haknya terkait tanah dan sumber daya alam dapat terlindungi.
Indonesia sejatinya memiliki landasan yang kuat untuk mengakui dan
melindungi hak masyarakat hukum adat ketentuan Pasal 18B ayat 2 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip
negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”
Selanjutnya ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang. Sementara unsur-unsur untuk adanya pengakuan adalah:
1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah Hukum Adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari.
Kewenangan untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat Hukum Adat adalah
kewenangan pemerintah daerah, melalui pengukuhan dalam peraturan daerah. Ketentuan Pasal 67
ayat (2) bahwa: ”Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Penjelasan Pasal ini menjelaskan
bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum
adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Dengan demikian pengakuan atas eksistensi
masyarakat hukum adat menjadi tidak hanya bersyarat tapi juga berlapis.
349
bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban”. 52
Terkait kepemilikan sumber daya genetik, CBD dan Nagoya Protocol
menentukan sumber daya genetik merupakan hak kedaulatan negara serta
mengakui kontribusi masyarakat hukum adat dalam melakukan konservasi sumber
daya genetik. CBD dan Nagoya Protocol dapat dikatakan merupakan ketentuan
yang melindungi kepentingan masyarakat hukum adat sebagai pemilik sumber daya
genetik yang berada di wilayah kelola masyarakat hukum adat dan memberikan
harapan baru dalam pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan.
Dengan demikian kepemilikan dalam memelihara sumber daya genetik
berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Pemberlakuan ABS dalam hukum
internasional dan mewajibkan negara mengaturnya ke dalam hukum nasional
nasional akan menciptakan insentif untuk melestarikan keragaman hayati secara
umum dan pengetahuan tradisional terkait. Kondisi ini merupakan kesempatan
untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dimana nilai sumber daya
genetik masyarakat hukum adat benar-benar diakui.53
Pembagian keuntungan (Access and Benefit Sharing) merupakan konsep
dasar pembangunan berkelanjutan yaitu prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip
keadilan ini menuntut bahwa mereka yang melestarikan sumber daya genetik
mendapatkan pembagian keuntungan dari akses dan pemanfaatannya oleh pihak
52 Muazin, op. cit.
53 Stellina Jolly, “Access and Benefit Sharing under Nagoya Protocol and Sustainable
Development A Critical Analysis”, Juridical Science, Volume 9 No. 3, 2015, halaman 43, diakses
https://www.researchgate.net/publication/318852649_Access_and_Benefit_Sharing_under_Nagoy
a_Protocol_and_Sustainable_Development-A_Critical_Analysis.
350
pengguna. Apa yang merupakan pembagian keuntungan yang adil harus ditentukan
dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan peran masyarakat hukum adat
dalam memelihara keanekaragaman hayati. Karena adanya hak atas pembagian
keuntungan akses sumber daya genetik ini maka diperlukan hukum untuk menjaga
kelangsungan eksistensi hak dalam kehidupan bernegara itulah sebabnya pasca
ratifikasi CBD dan Nagoya Protocol mendesak dibangun rezim hukum ABS.
Lebih jauh, di dalam pembukaan CBD sumber daya genetik dianggap
sebagai kepentingan bersama bukan warisan bersama umat manusia. Tahapan ini
adalah konsern seluruh umat manusia untuk pembangunan berkelanjutan guna
melestarikan dan mempertahankan penggunaan sumber daya genetik untuk
kemanusiaan dan generasi yang akan datang. Namun catatan penting dalam relasi
ini adalah kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan sumber daya genetik
tidak berarti bahwa sumber daya tersebut adalah warisan bersama umat manusia.
Sebaliknya sumber daya genetik tersebut adalah milik masyarakat hukum adat.
CBD dan Nagoya Protokol merupakan perjanjian internasional yang
termasuk dalam law making treaty dan governed by international law.
Terbentuknya CBD dan Nagoya Protokol untuk mengatasi ancaman kepunahan
sumber daya hayati dengan mengatur hubungan yang lebih adil antara penguna dan
penyedia termasuk masyarakat hukum adat selaku pengkonservasi yang selama ini
dirugikan dengan praktik pencurian sumber daya genetik atau biopiracy.
Konsep ABS dikaitkan dengan kontribusi konservasi bahwa mereka yang
menggunakan sumber daya genetik memberikan kembali imbalan kepada
351
penyedia.54 Hubungan ini mengambarkan keadilan dan kesetaraan dimana
penghormatan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di satu sisi dan
hak pengguna di lain sehingga terwujud keadilan yang berperikemanusiaan dan
berkeadilan sosial.
Landasan filosofi dari hal ini adalah bahwa nilai intrinsik dari sumber daya
genetik perlu diimbangi dengan penghargaan yang proporsional. Hal ini beranjak
dari kekhawatiran tentang bagaimana melakukan penelitian yang etis oleh Users
pada negara-negara yang kaya sumber daya genetik baik yang dikelola masyarakat
hukum adat untuk mendapatkan manfaat yang besar maka ABS dianggap sebagai
salah satu instrumen penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan diantara
hubungan tersebut. Sebagian pelaku konservasi hidup dalam kesederhanaan jauh
dari akses kesehatan adalah relevan sumber daya genetik yang diakses tersebut
manfaatnya dibagi ke penjaga konservasi. Sebaliknya secara etis adalah tidak adil
bila suatu negara atau Users tidak memberikan manfaat yang adil atas akses yang
diberikan kepadanya.
Seturut dengan hal tersebut, tujuan perjanjian internasional CBD dan
Nagoya Protokol serta SDGs sesuai dengan tujuan atau the 17 Goals of Sustainable
Development, utamanya tujuan ke 11, 15, 16 dan 17 yaitu Reduce Inequalities, Life
on Land, Peace, Justice and Strong Institutions, and Partnership for the Goals tidak
akan dapat diwujudkan bila masyarakat hukum adat hidup dalam kesenjangan dan
ketidakadilan sebagai akibat eksplotasi sumber daya genetiknya tanpa izin dan
54 Doris Schroeder and Balakrishna Pasupati, “Ethics, Justice and the Convention on
Biological Diversity”, UNEP, 2010, halaman 13-14.
352
tanpa pembagian keuntungan atas nilai ekonomi sumber daya genetik yang
sesungguhnya berasal dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat telah
dirugikan dan menderita ketidakadilan sebagai akibat dari perampasan tanah,
wilayah, dan sumber daya alam mereka atas nama proyek pembangunan.55
Sebagian kebijakan dilakukan tanpa menghormati hak-hak mereka.56
Dalam banyak kasus57, kebijakan sudah dijalankan ketika izin-izin dari pemerintah
sudah diperoleh, sementara konsultasi tidak dilakukan dan persetujuan masyarakat
hukum adat belum diperoleh. Masyarakat hukum adat akhirnya melihat bahwa
hutannya telah ditebang, tanahnya ditambang, lembahnya dibanjiri, tempat
berburunya dipagari, ladang-ladangnya ditempati. Hal tersebut terjadi tanpa bisa
mengatakan apa-apa dan seringkali terjadi tanpa mendapatkan keuntungan
apapun.58Kesemuanya menyebabkan berkurangnya wilayah kelola masyarakat
55 Deti Mega Purnamasari, “Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga
Kriminalisasi”, Harian Kompas, diakses pada
: https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-
terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all: “… “ketika investasi atau proyek
pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin
tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah. Mereka mengalami perampasan
wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi.” 56 Renee V Hagen and Tessa Minter, “Displacement in the Name of Development How
Indigenous Right Legislation Fails to Protect Philippine Hunter Gatherer”, Vol. 33 Issue 2, 2020,
P. 66, diakses pada https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08941920.2019.1677970 57 Deti Mega Purnamasari, “Nasib Masyarakat Adat yang Terancam Investasi Hingga
Kriminalisasi”, Harian Kompas, diakses pada
: https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-
terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all: “… “ketika investasi atau proyek
pembangunan pemerintah masuk, misalnya pembangunan jalan, irigasi, hingga izin-izin
tambang, masyarakat adat mengalami berbagai masalah. Mereka mengalami perampasan
wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi.” 58 Emil Kleden, “Konsep Free Prior Informed Consent”, Kertas Kerja dalam Pelatihan
IMPACT ELSAM 23 Pebruari 2017, halaman. 9, diakses pada
https://referensi.elsam.or.id/2017/06/konsep-prinsip-free-prior-informed-consent
353
hukum adat atas tanah dan sumber daya alamnya serta hilangnya keanekaragaman
hayati.59
Instrumen hukum internasional UNDRIP khususnya Pasal 32 terkait dengan
tujuan SDGs ke 11 pengurangan kesenjangan, tujuan ke 15 kehidupan, tanah, tujuan
ke 16 keadilan dan kelembagaan serta ke 17 kemitraan bahwa:
1. “Indigenous peoples have the right to determine and develop sriorities and
strategies for the development or use of their lands or territories and other
resources.”
2. “States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous
peoples concerned through their own representative institutions in order to
obtain their free and informed consent prior to the approval of any project
affecting their lands or territories and other resources, particularly in
connection with the development, utilization or exploitation of mineral,
water or other resources.”
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terlihat bahwa SDGs merupakan penjabaran
operasional dari berbagai norma pembangunan berkelanjutan termasuk
keselarasannya dengan Pasal 32 UNDRIP tersebut. Seiring dengan UNDRIP,
ketentuan Pasal CBD dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 mengamanahkan bahwa
masyarakat hukum adat tidak boleh disingkirkan dari tanah, wilayah dan sumber
daya alam yang mereka tempati. Bila mana pemindahan masyarakat hukum adat
ke tempat lain dianggap perlu sebagai suatu langkah pengecualian maka
pemindahan hanya bisa dilakukan dengan keinginan dan persetujuan mereka
setelah diinformasikan terlebih dahulu akibat-akibatnya.
59 E Cohen-Schacham et al,”Nature Based Solution to Address Global Societal
Challenges”, UNDP, Norad German, 2016, p. 2, diakses pada
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-036.pdf
60 Sopia R. Hirakuri and Brendan Michael Tobin, “Free Prior Informed Consent and Access
to Genetic Resources and Benefit Sharing”, Work in Progress, Vol. 17 No. 2, 2005, p.13, diakses
pada https://www.researchgate.net/publication/42766394
354
Bila ketidakadilan yang dirasakan masyarakat hukum adat terus
berlangsung karena ketiadaan perlindungan hukum maka kerugian tidak hanya
diderita masyarakat hukum adat namun lingkungan dan keanekaragaman hayati
secara keseluruhan karena peran mereka yang besar dalam konservasi tidak
dihargai termasuk terkait dengan sumber daya genetik masyarakat hukum adat. Bila
tidak ada hukum yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat berhak atas
pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetiknya belum dibangun
dalam sistem hukum nasional maka bukan hanya masyarakat hukum adat yang
dirugikan namun Indonesia secara keseluruhan karena membiarkan potensi sumber
daya genetiknya dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian status sehingga rentan
dicuri. Padahal pasca ratifikasi CBD dan Nagoya Protokol Indonesia memiliki
kesempatan besar untuk melindungi sekaligus menjadikan potensi sumber daya
genetiknya sebagai sumber daya pembangunan pembangunan hukum rezim ABS.
2. Pengembangan Hukum ke Depan Terkait Pengakuan Hak Masyarakat
Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (Access and Benefit
Sharing/ABS)
Pembahasan mengenai kesetaraan dan hak dalam wacana konservasi global
antara negara yang kaya keanekaragaman hayati dengan negara yang kaya ilmu
pengetahuan dan teknologi secara hitoris telah dimulai sejak tahun 1970-an yang
dilanjutkan dengan gagasan tentang kesetaraan antar generasi yang menjadi dasar
bagi pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam KTT Bumi pertama
pada tahun 1992.
Negara yang memegang hak berdaulat atas sumber daya genetik dapat
memberikan akses kepada mereka yang memerlukan atau pengguna melalui
355
prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dan prinsip kesepakatan bersama
Mutually Agreed Terms (MAT). Hal ini menyiratkan bahwa negara-negara
berkembang harus melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dengan
membangun hukumnya untuk menentukan hak dan kewajiban dari berbagai pihak
yang terlibat. Ketika akses ke sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
menjadi masalah maka seperangkat aturan yang jelas dan telah ditetapkan negara
yang makmur sumber daya hayati akan memenuhi kebutuhan kepastian,
kemanfaatan dan keadilan semua pihak yang terlibat yaitu negara, masyarakat
hukum adat, penyedia dan pengguna.
Setiap negara berkepentingan untuk melakukan konservasi penggunaan
keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan distribusi keuntungan yang adil
yang dihasilkan dari sumber daya genetik berdasarkan hak kedaulatan negara
sebagaimana diteguhkan dalam Pasal 15 CBD.61
Ketentuan Pasal 15
1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the
authority to determine access to genetic resources rests with the national
governments and is subject to national legislation.
2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate
access to genetic resources for environmentally sound uses by other
Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the
objectives of this Convention.
3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided by
a Contracting Party, as referred to in this Article and Articles 16 and 19,
are only those that are provided by Contracting Parties that are countries
of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic
resources in accordance with this Convention.
4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the
provisions of this Article.
61 Grethel Aguilar, op. cit., halaman 243.
356
5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the
Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined
by that Party.
6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific
research based on genetic resources provided by other Contracting Parties
with the full participation of, and where possible in, such Contracting
Parties.
7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy
measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and,
where necessary, through the financial mechanism established by Articles
20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of
research and development and the benefits arising from the commercial and
other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing
such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.
Referensi hak atas sumber daya genetik sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 15 ayat (1) memberi pertanda bahwa status hukum sumber daya genetik
merupakan pertimbangan utama Konvensi yang tunduk kepada rezim masing-
masing negara pihak yang berjanji untuk mengambil langkah mengatur dan
menetapkannya dalam hukum nasionalnya. Selain itu, hal penting yang dapat
dicermati dalam ketentuan Pasal 15 CBD adalah frasa sesuai/tepat (as appropriate).
Kata sesuai atau tepat terkait erat dengan syarat atau ketentuan akses ke sumber
daya genetik. Persyaratan tersebut harus ditentukan oleh Pihak yang menyediakan
sumber daya genetik.
Ketika suatu langkah hukum dikembangkan untuk mengimplementasikan
CBD dan Nagoya Protocol utamanya sistem ABS sesuai amanat Pasal 15 CBD
maka ketentuan lain yang relevan juga perlu diperhatikan bahwa tujuan utama
Konvensi, dan dasar Pasal 15 adalah untuk memastikan pembagian yang adil atas
357
akses dan pemanfaatan sumber daya genetik dengan Para Pihak yang
menyediakannya. Ketentuan lain tersebut adalah Pasal 8 (J) bahwa:
Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan
mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat
hukum adat dan masyarakat lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri
tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan
keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan
persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-
praktek tersebut, mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan
dari pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan
praktek-praktek semacam itu.
Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 8 (j) terlihat beberapa elemen dasar
yang perlu ditindaklanjuti yaitu Pasal 8 (J) memberikan rujukan ke istilah ‘dengan
persetujuan’ dan ‘keterlibatan’ masyarakat hukum adat. Dalam kerangka hukum
internasional makna ‘persetujuan’ dan ‘keterlibatn’ ini dipahami sebagai prinsip
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan atau yang lebih dikenal dalam
Free Prior Informed Consent/FPIC.62 Adapun makna ‘keterlibatan’ secara lebih
substantif digambarkan sebagai ‘partisipasi penuh dan efektif’. Penafsiran ini
diperkuat oleh Pasal 6 (3) (f) Nagoya Protocol bahwa
1. Dalam pelaksanaan hak berdaulat atas sumber daya alam pada akses domestik
dan peraturan perundang-undangan pembagian keuntungan atau peraturan
persyaratan, akses terahadap sumber daya genetik untuk pemanfaatannya harus
diinformasikan terlebih dahulu sebelum persetujuan dari pihak yang
menyediakan sumber daya.
2. Sesuai dengan hukum nasional, masing-masing pihak wajib mengambil
tindakan yang sesuai dengan tujuan untuk memastikan bahwa persetujuan dan
keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diperoleh untuk akses
ke sumber daya genetik dimana masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal
memiliki hak yang ditetapkan untuk memberikan akses ke sumber daya genetik
tersebut.
62 Free Prior Informed Consent/PFIC adalah hak masyarakat hukum adat untuk
memberikan persetujuan sebelum proses pembangunan atau kegiatan dimulai di wilayah sumber
daya alamnya atau yang memegaruhi kehidupan mereka sekaligus menghormati budaya masyarakat
hukum adat. FPIC dijamin dalam hukum internasional UNDRIP.
358
3. Sesuai dengan ayat 1 setiap pihak yang memerlukan persetujuan terlebih
dahulu harus mengambil langkah-langkah legislatif, adminsitratif atau
kebijakan yang diperlukan sebagaiman mestinya untuk:
a. Memberikan kepastikan hukum, kejelasan dan trasnparansi akses dan
peraturan persyaratan pembagian keuntungan.
b. Menyediakan aturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang
dalam mengakses sumber daya genetik.
c. Memberikan informasi tentang cara mengajukan persetujuan berdasarkan
informasi sebelumnya
d. Memberikan keputusan tertulis yang jelas dan transparan oleh otoritas
nasional yang kompeten
e. Menyediakan dokumen penerbitan pada saat akes izin diberikan sebagai
bukti keputusan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu dan
penetapan syarat-syarat yang disepakati bersama dan memberitahukan
kepada Lembaga kliring akses dan pembagian hasil atau keuntungan
f. Menetapkan kriteria dan proses untuk mendapatkan persetujuan
berdasarkan informasi awal dan keterlibatan masyarakat hukum adat
ke akses sumber daya genetik
g. Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dalam menetapkan persyaratan
yang disepakati bersama. Persyaratan tersebut ditetapkan secara tertulis dan
meliputi:
1) Klausul penyelesaian sengketa
2) Ketentuan pembagian keuntungan termasuk yang berhubungan dengan
hak kekayaan intelektual
3) Ketentuan penggunaan oleh pihak ketiga selanjutnya bila ada
4) Ketentuan tentang perubahan kesepakatan bila diperlukan
Dengan demikian pengembangan hukum ke depan perlu mengadopsi
dimana proses akses dan pemanfaatan sumber daya genetik masyarakat hukum adat
dan pengetahuan tradisionalnya secara penuh mengikutkan masyarakat hukum
adat. Dengan demikian berdasarkan kandungan makna prinsip FPIC maka
keputusan untuk mengizinkan atau tidak atas akses dan pemanfaatan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisionalnya harus tetap berada pada masyarakat hukum
adat.
359
3. Pengembangan Hukum ke Depan terkait Transformasi Hukum
Internasional ke dalam Hukum Nasional
Sejak awal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hingga sekarang belum terdapat konsepsi, doktrin, praktik
dan aturan untuk mengkonstruksikan perjanjian internasional ke dalam sistem
hukum nasional sehingga diperoleh kepastian kedudukan hukum internasional
dalam hukum nasional,63 Pengaturan perjanjian internasional dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 11 tidak
menentukan secar tegas posisi perjanjian internasional dalam hukum nasional.
Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, kedudukan perjanjian internasional belum dianggap bagian dari
hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercermin dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 dimana tidak ditemukan perjanjian internasional
dalam hierarki tersebut. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional tidak menentukan secara pasti pilihan doktrin
yang dianut Indonesia akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ditegaskan
perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi melalui undang-undang bila
berkenan dengan:
a. masalah politik, perdamaian dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
c. kedaulatan dan hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaedah hukum baru; dan
f. pinjaman dan/hibah luar negeri
63 Damos Dumali Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik,
op. cit., halaman 56.
360
Kedudukan undang-undang hasil ratifikasi tidak disebutkan secara jelas dalam
ketentuan tersebut di atas. Bertalian dengan Pasal 10, terdapat perkembangan
yudisial review atas undang-undang perjanjian internasional berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 13/PUU-XVI/2018, MK memutuskan
bahwa:
“ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian
sebagaimana disebut dalam huruf a sampai huruf f dalam Pasal 10 itulah yang
mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian
tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.”64
Walaupun bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-
undang, namun perjanjian internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum
tata negara Indonesia dalam arti formal.65 Di samping sebagai sumber hukum utama
dalam hukum internasional,66 perjanjian internasional adalah sumber hukum
penting bagi hukum nasional. Perjanjian internasional, walaupun termasuk dalam
bidang hukum internasional, merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum
tata negara sepanjang perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang
hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya.67
Mengapa kedudukan hukum internasional penting dalam hukum nasional?
Pada fase awal kemerdekaan hal ini tidak dipermasalahkan dalam hukum nasional,
64 https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/12/13_PUU-XVI_2018.pdf. “Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI Tahun 2018”, halaman 266. 65 Ni’matul Huda, op. cit. 66 ICJ Statute Article 38 (1): “ The Court, whose function is to dicide in accordance with
international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions,
whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states …
.” 67 Moh. Kusniadi dan Harmaily Ibrahim, op. cit.
361
salah satunya dikarenakan perjanjian internasional belum menjadi studi yang luas
dan dipermasalahankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan
studi hukum tata negara yang berkembang pesat pasca kemerdekaan. Selain itu,
doktrin mengenai status perjanjian internasional dalam hukum nasional dapat
dikatakan terbatas dan belum sebesar perhatian terhadap hukum tata negara. Lagi
pula perjanjian internasional yang diikuti Indonesia dahulu belum seintensif
sekarang.
Dengan semakin banyaknya Indonesia mengikatkan diri dalam suatu
perjanjian internasional kebutuhan untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan
hukumnya semakin luas terutama bila menyangkut perjanjian internasional yang
berdampak luas kepada kehidupan bernegara dan keuangan negara, hak-hak warga
negara. Hal ini tentu bertalian dengan bagaimana ke depan hakim merespon
instrumen hukum internasional sebagai suatu sumber hukum dalam putusannya
atau warga negara yang menuntut haknya yang dijamin dalam hukum internasional
namun status perjanjian internasional belum jelas dalam sistem hukum nasional
Selama ini berkembang dua pemikiran mengenai kedudukan perjanjian
internasional yaitu pemikiran pertama yang beranggapan bahwa perjanjian
internasional yang telah diratifikasi sebagai bagian dari hukum nasional. Di sisi lain
pemikiran kedua yang menganggap harus adanya legislasi nasional tersendiri untuk
menerapkan atau menjabarkan hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam
hukum nasional. Munculnya kedua pemikiran tersebut di Indonesia secara teoretis
dan praktik berakar dari ketidakjelasan doktrin mana yang digunakan oleh
Indonesia.
362
Persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong perjanjian
internasional yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui
setelah berkonsultasi dengan DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Perjanjian Internasional maka rumusan norma dalam Pasal 10
tersebut telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian
internasional yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 yang tergolong perjanjian
yang demikian.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memperluas kriteria
perjanjian internasional yang tidak hanya terbatas sebagaimana ditentukan pada
Pasal 10 namun meliputi perjanjian yang mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang yaitu perjanjian yang mempunyai akibat yang luas
dan mendasar bagi rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.68 Dengan
demikian Undang-Undang Perjanjian Internasional memerlukan perubahan guna
menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepastian hukum. Perubahan
Undang-Undang Perjanjian Internasional saat ini termasuk dalam prioritas
Proglegnas.
Berdasarkan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam
ASEAN menegaskan bahwa persetujuan DPR lebih baik tidak dibuat dalam bentuk
undang-undang namun persetujuan tersebut cukup berbentuk lisan karena semata-
mata merupakan persetujuan formal DPR sebaimana tercantum dalam Pasal 11
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian.69 Konstruksi hukum undang-
68 Ibid. 69 Yudisial Review UU Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the
Association of Southeast Asian Nations, Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: PUU-XX/2020
halaman diakses
363
undang ratifikasi dengan demikian dianggap perwujudan formal persetujuan DPR
yang memperlihatkan pengesahan Piagam ASEAN.70 Sesuai dengan Pasal 2 (b)
Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian internasional bahwa Ratifikasi merupakan
tindakan internasional suatu negara pihak dalam meneguhkan persetujuannya untuk
diikat oleh suatu perjanjian internasional.71
Apabila dicermati peraturan perundang-udangan Indonesia juga tidak ada
yang memberi pedoman bahwa undang-undang ratifikasi adalah transformasi
perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional. Karena itu, undang-
undang ratifikasi tidak dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum untuk pelaksanaan
pemenuhan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Hal ini menimbulkan
persoalan dalam penerapan perjanjian internasional.
Selama kemederkaannya Indonesia telah menjalin kerja sama dan
menandatangani sampai tahun 2009 sekitar lebih dari 4000 perjanjian internasional,
namun implikasi atau konsekuensi hukumnya yang diharapkan yaitu sejauh mana
perjanjian internasional yang merupakan hukum internasional mengikat lembaga
negara, warga negara maupun pejabat atau penegak hukum terutama hakim di
pengadilan belum menampakan wujudnya.72
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_33%20PUU%202011_A
SEANcharter_telah_baca_26Feb2013%20final.pdf pada tanggal 28 Desember 2020 70 “Pada prinsipnya lembaga ratifikasi berasal dari konsepsi hukum perjanjian internasional
untuk menandai tindakan konfirmasi dari negara pihak atas perbuatan hukum pejabatnya yang
menandatangani suatu perjanjian. Pengesahan ini dimaknai mulai mengikatnya perjanjian tersebut
kepada negara pihak. Dari sisi hukum pengesahan adalah konfirmasi atas suatu fakta hukum yang
mendahuluinya yaitu penandatanganan atau penerimaan teks perjanjian.” Lihat Damos Dumoli
Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, op. cit., halaman 71. 71 “Ratification, acceptance, approval and accession mean in each case the international
act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by
treaty” Vienna Convention 1969 on International Treaties. 72 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, op. cit., halaman 1.
364
Bagaimana hakim menggunakan hukum internasional dalam putusannya,
praktik pengadilan Indonesia juga memperlihatkan ketidakkonsitenan. Di satu sisi
hakim menerapkan hukum internasional secara langsung (ciri monisme) dalam
putusannya namun di sisi lain sebaliknya hakim menolak untuk menggunakan
hukum internasional tanpa transformasi hukum internasional menjadi hukum
nasional (ciri dualisme). Gambaran inventarisir praktik pengadilan Indonesia
disusun pada tabel 11
Tabel 11
Praktik Pengadilan Indonesia dan Kecenderungan Doktrin
dalam Putusan Hakim
No Kasus/Yudisi Review Pengadilan/Instrumen Hukum
Doktrin
1. Kasus tanah Kedubes
Saudi Arabia tahun
2006
MA merujuk langsung Pasal 31 Konvensi
Wina 1961 sementara Indonesia tidak
meratifikasi.73
Monisme
2. PT. Nizwar melawan
Navigation Maritime
Bulgare,
MA menolak menerapkan Putusan
Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards
1958/New York Convention sebelum New
York Convention ditransformasikan ke
dalam hukum nasional
Dualisme
3. Kasus E.D. &F. Man
Sugar Ltd melawan
Yani Haryanto
MA menolak eksekusi putusan arbitrase
London.74 Mahkamah Agung merasa
perlu menunggu suatu peraturan
pelaksanaan bilamana suatu putusan
arbitrase asing diterima di Indonesia.75
Dualisme
73 Eddy Pratomo, op. cit., Lihat juga Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian
Internasional dalam Hukum Nasional”, op. cit. 74 S. Gautama, op. cit. 75 Sulaiman Batubara. op. cit.
365
4 Yudisial Review UU
No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan
HAM
Mahkamah Konstitusi merujuk langsung
International Covenant on Civil and
Political Rights/ICCPR.76
Monisme
5 Yudisial Review
KUHP tentang
Penghinaan kepada
Presiden dan Wakil
Presiden.77
Mahkamah Konstitusi merujuk langsung
International Covenant on Civil and
Political Rights/ICCPR
Monisme
6 Yudisial Review UU
No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi
Elektronik/UU ITE.78
Mahkamah Konstitusi merujuk langsung
International Covenant on Civil and
Political Rights/ICCPR. Sementara
Indonesia baru meratifikasi ICCPR pada
tahun 2005 dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005.
Monisme
7 Yudisial Review UU
No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika,79
Putusan MK Mahkamah Konstitusi
mempertimbangkan bahwa kejahatan
narkotika adalah ‘the most serious crime’
yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
International Covenant on Civil and
Political Rights/ICCPR.
Monisme
8 Yudisial Review UU
Nomor 16 Tahun
2003 tentang Perpu
Nomor 2 Tahun 2002
tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Terorisme.
MK memutus peristiwa Bom Bali tanggal
12 Oktober 2002 dengan langsung
menggunakan:
- Pasal 11 dan Pasal 15 ICCPR
sementara Indonesia belum menjadi
negara pihak dalam Covenant
tersebut.80
- MK juga menggunakan:
a. DUHAM
b. European Convention for the
Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and Its
Eight Protocols
c. Rome Statute of the
International Criminal
Court/1998
d. International Convention for the
Suppression of Terrorist
Bombing/1997
e. International Convention for
the Suppression of the
Financing of Terrorism/1999.
Monisme
76 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004,
halaman 56, diakses pada
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/PutusanNo065PUUII2004tgl030305.pdf 77 Adhya Satya Bangsawan, op. cit. 78 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. 79 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007”, diakses pada
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%202-
3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf. 80 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-I/2003”,
halaman 68, diakses pada https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/
putusan_sidang_Putusan013PUUI2003 tangggal 28 Desember 2020.
366
9 Yudisial Review UU
Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan
Anak
MK dalam Putusan Nomor 1/PUU-
VII/2010 menegaskan bahwa:
“perjanjian-perjanjian internasional
tentang Hak Anak dapat digunakan MK
sebagai alat perbandingan, namun dalam
hal ini perjanjian-perjanjian internasional
itu tidak dapat menentukan batas umur
anak secara konstitusional”.81
Monisme
10 Permintaan beberapa
anggota DPR kepada
Mahkamah Konstitusi
untuk memberikan
putusan bahwa
Product Sharing
Contract (PSC)
merupakan perjanjian
internasional sesuai
dengan Pasal 11 UUD
1945, sehingga harus
mendapat persetujuan
DPR.
Dalam kaitan ini Mahkamah Konstitusi
telah menyandarkan putusannya langsung
kepada Konvensi Wina tahun 1969
tentang hukum perjanjian internasional
yang kemudian memutuskan bahwa PSC
bukan merupakan perjanjian
internasional.82
Monisme
11 PK terpidana
pelanggaran HAM
berat Timor Timur
Eurico Guterres
MA merujuk langsung pada instrumen
hukum internasional:
- Rome Statute 1998 terkait Pasal 7
Butir 3 Elements of Crimes dari
Rome Statute International Criminal
Court.
- Hakim juga mendasarkan pada
argumentasi hukum yang digunakan
dalam kasus Bagilishema yang
diputus International Criminal
Tribunal for Rwanda/ICTR, Trial
Chamber tanggal 7 Juni 2001 yang
mengartikan bahwa tanggung jawab
komandan termasuk orang sipil yang
punya pengaruh untuk memobilisasi
massa.83
Monisme
12 Yudisial Review UU
No.1/PNPS/1965
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan
Agama
Hakim meneguhkan bahwa Pasal 18
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia/DUHAM dan International
Covenant on Civil and Political
Rights/ICCPR telah transformasikan baik
langsung maupun tidak langsung melalui
Dualisme
81 Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010”.
halama 82 Ibnu Sina Chandranegara, “Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-
besarnya Kemakmuran Rakyat”, Jurnal Konstitusi Vol 14 Nomor 1, 2017, halaman 62, diakses pada
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1413. 83 Komariah Emong Sapardjaja, op. cit.
367
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.84
13 Ratifikasi UNCLOS
1982 dengan UU No.
17 Tahun 1985
UU No.17 Tahun 1985 bukan UU
Substantif hanya prosedural sehingga
dibutuhkan UU yang
mentransformasikan UNCLOS ke dalam
hukum nasional maka dibentuklah UU
No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia
Dualisme
Berdasarkan tabel 10 mengenai praktik tersebut dapatlah dikatakan bahwa
sebagian besar hakim mengadopsi hukum internasional secara langsung namun di
sisi lain untuk berlaku di sistem hukum nasional hukum internasional harus benar-
benar menjadi hukum nasional terlebih dahulu dengan mentransformasikannya ke
dalam undang-undang nasional.
Pada beberapa dekade terakhir dunia menyaksikan peningkatan yang tajam
dalam pembentukan perjanjian internasional yang berdampak pada hukum
domestik yang berhubungan pula dengan pengadilan nasional.85Perkembangan
tersebut menandakan bahwa tidak hanya semata-mata negara yang berperan dalam
pengembangan hukum internasional dalam sistem hukum nasional pengadilan
nasional memiliki potensi dan berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan
hukum internasional.
Bagaimana Indonesia sebagai negara peserta aktif dalam perjanjian
internasional belum memiliki pengaturan yang jelas untuk penegak hukum dan
warganya sendiri tentang hak dan kewajiban yang timbul ketika Indonesia
menandatangani perjanjian internasional dan mengikatkan diri sebagai negara
84 Melda Kami Ariadno, op. cit., Lihat juga Damos Dumali Agusman, Hukum Perjanjian
Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, op. cit., halaman 109. 85 Paul Gralg, International Law in Domestic Legal Orders, Legal Monism, Law and
Philosophy and Politics, Oxford University Press, UK, 2018, halaman viii.
368
pihak. Pada negara-negara maju doktrin mengenai hubungan hukum nasional dan
hukum internasional terkait kedudukan dan status hukum dari perjanjian
internasional dalam hukum nasional diatur secara jelas di dalam Konstitusinya.86
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pengadilan
tersebut dapatlah dikatakan bahwa Indonesia belum menentukan secara tegas
pilihan doktrin apakah monism atau dualisme atau keduanya. Praktik ini dapat
memunculkan ketidakpastian mengingat Pemerintah Indonesia telah mengikuti
perjanjian internasional di sisi lain masyarakat Internasional percaya bahwa
perjanjian yang diratifikasi oleh Indonesia telah otomatis dapat langsung
dilaksanakan dalam sistem hukum nasional namun praktik menunjukan sebaliknya.
Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia menolak menjalankan
kewajiban internasionalnya yang diatur dalam perjanjian internasional sementara
perjanjian itu tidak memiliki efek dalam hukum Indonesia.87
Bagaimana menempatkan perjanjian internasional dalam kerangka hukum
nasional. Ketidakjelasan hubungan hubungan hukum internasional dan hukum
nasional menyiratkan tergantung arah dan orientasi rezim yang berkuasa sehingga
banyaknya ratifikasi perjanjian internasional lebih bersifat politik dari pada
kepastian hukum. Sebagaimana pandangan Gernor Biehler bahwa: “Something it is
questioned whether international law is really law and not just a branch of power
86 Netherland Council of State, “Hierarchy of Norms in Ducth Legislation”: “The
Netherland has a partly monist system, based on article 93 and 94 The Ductch Constitution”,
ACA-Europe Seminar, 18 Desember 2013, diakses pada https://www.aca-
europe.eu/seminars/Paris2013bis/Pays-Bas.pdf. 87 Lihat Gernot Biehler, Procedures in International Law, Springer, 2008, halaman 189:
“Something it is questioned whether international law is really law and not just a branch of power
politics. This recurring concern is related to its deep roots in state practice and politic … .”
369
politics. This recurring concern is related to its deep roots in state practice and
politic … .”
Apakah Indonesia menandatangani sebuah perjanjian internasional, apakah
perjanjian itu secara otomatis berlaku dalam hukum atau apakah memerlukan
transformasi? Pertanyaan ini masih belum terjawab di Indonesia, yang merupakan
dapat dikatakan mungkin satu-satunya negara-negara di dunia yang tidak
menentukan dalam Konstitusi atau lainnya hukum lain, atau melalui praktik
peradilan, status hukum internasional yang tepat dalam sistem hukum
domestiknya.88
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas sesuai prinsip lain dalam hukum
internasional yaitu soveriegnity atau paham kedaulatan negara menjamin
kedaulatan negara dalam menentukan bagaimana hukum internasional berlaku
dalam suatu negara. Namun di sisi lain sesuai ketentuan Pasal 27 VCLT bahwa: “
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its
failure to perform a treaty. This rule is without prejude to article 46”.89 Negara
tidak dapat mengajukan alasan hukum nasionalnya untuk menghindar dari
kewajiban internasionalnya yang sudah ia sepakati.
Indonesia berdasarkan penelaahan dari konstitusi dan peraturan perundang-
undangan serta praktik pengadilan menunjukan tidak membuat pilihan jelas dan
tegas bagaimana hukum internasional berlaku dan memiliki validitas dalam sistem
88 Simon Butt, “Review of Treaties Under Indonesia Law: A Comparative Study”,
Opinio Juris, Volume 17 Januari 2015, halaman 55. 89 Negara tidak dapat menggunakan alasan ketentuan hukum nasionalnya sebagai
pembenaran atas kegagalannya untuk melaksanakan suatu perjanjian (Konvensi Wina 1969 Pasal
27)
370
hukum nasional. Hal ini merupakan masalah mendasar karena sebagaimana
dikemukakan oleh Cassese bahwa hukum internasional tidak dapat tegak sendiri
tanpa bantuan dan fasilitasi dari hukum nasional:
“International law can’t stand on its own feet without its “crutches”, that is
international law cannot work without the constant help, cooperation, and
support of national legal system. As the German jurist Triepel observed in
1923, the international law is like a field marshal who can only give orders to
general. It is solely through the generals that his orders can reach the troops.
If the general don’t transmit them to the soldiers in the field, he will lose the
battle”.90
Dengan demikian selama ini praktik bagaimana hukum internasional
berlaku dalam hukum nasional terkait teori monism dan dualime direfleksikan
melalui relasi hubungan hukum nasional dan hukum internasional yang diikuti dan
diratifikasi oleh Indonesia. Situasi ini akan menjadi sulit pada saat Indonesia
dihadapkan untuk menentukan doktrin monisme atau dualisme yang akan
diterapkan secara konsisten. Bertalian dengan hal ini Dioniso Anzilloti dan
Fitzmaurice mengemukakan jalan tengah melalui teori harmonisasi yang
difungsikan sebagai konsep pilihan dalam menyembatani problem teoretik ini
sebagai berikut:
“the entire monist-dualist controversy is un real, artificial and strictly
beside the point because it assumes something that has to exist for there to
be any controversy at all, and which in fact does not exist, namely a common
field in which the two legal orders under discussion both simultaneously
have their spheres of activity”.91
90 Simon Butt, Ibid., “Hukum internasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa penopangnya.
Hukum internasional tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari sistem hukum nasional. Sebagaimana
dikemukakan Triepel hukum internasional layaknya Marshal lapangan yang hanya bisa memberi
perintah kepada jenderal. Hanya melalui para jendera perintahnya dapat mencapai pasukan. Jika
jenderal tidak mengirimkan perintahnya kepada prajurit di lapangan maka dia akan kalah dalam
pertempuran” (terjemahan penulis). 91 Ducan B Hollis et al, op. cit., halaman 771.
371
Teori harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional menghindari
terjadinya superioritas atau keunggulan diantara kedua hukum dengan menekankan
pada pendekatan koordinasi. Pengemuka teori harmonisasi menganggap bahwa
tidak ada konflik antar sistem hukum nasional dan hukum internasional sehingga
terhadap keduanya perlu dilakukan harmonisasi. Sementara itu kecenderungan
paham dualisme lebih pada pemisahan yang tegas antara ke dua sistem hukum
tersebut yang bertumpu dan berdasar pada subjek, sumber hukum dan struktur
kelembagaan yang berbeda.
Interpretasi dan praktik yang tidak konsisten mengenai hubungan antara
hukum perjanjian internasional dengan hukum nasional Indonesia memunculkan
ketidakpastian tentang konsekuensi dari perjanjian internasional dalam hukum
Indonesia. Pada akhirnya perjanjian internasional digunakan oleh pengadilan
internasional dalam menyelesaikan kasus di antara Negara. Pada sisi lain perjanjian
juga seharusnya diterapkan oleh hakim di pengadilan nasional untuk menyelesaikan
kasus sehubungan dengan hak dan kewajiban individu. Cara negara menerapkan
hukum internasional dalam hukum domestiknya tidak seragam, tergantung praktik
negara-negara, namun negara harus menerapkan hukum internasional yang telah
disepakati dan dijanjikannya sebagai pemenuhan kewajibannya itu dalam hukum
nasional. Apapun pilihan doktrin suatu negara selama negara dapat mematuhi
hukum internasional termasuk dengan cara selain monim dan dualism atau
gabungan monisme dan dualisme adalah sangat penting agar kewajiban hukum
internasional tersebut dapat dijalankan.
372
Pilihan doktrin yang dibuat oleh suatu negara ketika menerapkan hukum
internasional memiliki implikasi yang signifikan baik dari validitas perjanjian
internasional92 maupun legitimasi hukum internasional itu sendiri. Ada anggapan
bahwa pilihan yang mendukung penerimaan perjanjian tanpa perlu
ditransformasikan dulu ke dalam hukum nasional menampakan keunggulan
hierarki hukum internasional dalam sistem hukum nasional sebagaimana
pandangan Hans Kelsen. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas komitmen suatu
negara dan mengefektifkan rezim hukum internasional. Namun, di sisi lain
pengadopsian secara langsung perjanjian-perjanjian internasional tanpa melakukan
adaptasi dengan hukum nasional juga menunjukan bahwa kesempatan lembaga-
lembaga nasional dalam suatu negara untuk memastikan dan memeriksa kesesuaian
dan keselarasan perjanjian internasional terutama dengan Konstitusinya menjadi
terbatas.
Sementara itu negara-negara yang menganut sistem dualisme menerapkan
hukum internasional melalui proses pengubahan ke dalam hukum nasional.
Kekuatan sistem ini lembaga negara yang bertugas memeriksa kesesuaian
perjanjian internasional dengan hukum nasional dapat menjalankan fungsinya
dengan berpedamon pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.
Namun, di sisi lain sistem ini juga menunjukan banyak negara pihak terlibat dalam
suatu perjanjian internasional tidak mentransormasikannya ke dalam hukum
nasional sehingga efektifitas dan validitas perjanjian internasional menjadi tidak
92 Dinah L. Shelton, International Law and Domestic Legal System: In Corporation,
Transformation and Persuasion“, Oxford University Press, 2011, halaman 5: “In general, the place
of international law in the domestic legal system depends on the source of the international law in
question: whether it is a treaty … .”.
373
pasti karena hakim tidak memiliki pedoman untuk memutus perkara dengan
mengunakan hukum internasional melainkan hukum nasional.
Indonesia ke depan harus membangun rezim hukum perjanjian
internasional dengan mendudukan status hukum internasional yang sudah
seharusnya ditentukan berdasarkan konstitusi dengan pilihan doktrin yang jelas.
Kejelasan ini dapat dirunut berdasarkan kategori perjanjian internasional.
Perjanjian internasional yang bersifat implementatif yaitu treaty contract misal
perjanjian garis landas kontinen anatar RI dan Thailand yang ditandatangani di
Bangkok tahun 1971 dan diratifikasi dengan Keppres 21 Tahun 1972 dan Perjanjian
Indonesia dengan Singapore tentang Penetapan Batas Laut Wilayah d Bagian Timur
Selat Singapore tahun 2014 diratifikasi dengan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun
2017 dapat mengacu pada doktrin monisme. Artinya untuk posisi perjanjian treaty
contract langsung berlaku tidak memerlukan transformasi ke dalam hukum
nasional mengingat perjanjian ini tidak menciptakan kaidah hukum baru dan
terbatas diantara dua atau tiga negara saja, sebagaimana dikemuka oleh Starke: “ a
treaty between two or only a few states, dealing with a special matter concerning
these states exclusively”.93
Klasifikasi kedua adalah law making treaty yaitu perjanjian internasional
yang menciptakan kaidah hukum baru dimana negara-negara pihak diharapkan
berperilaku tertentu yang dalam konsep Starke diilustrasikan sebagai: “lay down
rule of universal or general application”. Sementara itu Gerald Fitzmaurice
93 Hikmahanto Juwana, “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian
Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum
Nasional”, op. cit., halaman 17.
374
mengemukakan bahwa dalam perjanjian yang law making treaty ada kewajiban
integral yang menciptakan norma untuk mewujudkan suatu rezim hukum yang
berlaku terhadap semua negara. Karakter integral inilah yang akan dipergunakan
oleh International Court of Justice/ICJ ketika mempertimbangkan suatu ketentuan
dalam hukum internasional.94
CBD dan Nagoya Protocol yang diikuti oleh Indonesia merupakan contoh
dari perjanjian internasional yang law making treaty yang mewajibkan negara
berperilaku tertentu yaitu melindungi sumber daya genetiknya dan mengakui hak
masyarakat hukum adat atas ABS melalui langkah hukum membangun rezim
perundang-undang nasional guna mewujudkan pembagian keuntungan bagi
penyedia sumber daya genetik.
Indonesia dapat melihat praktik negara-negara dalam membangun rezim
hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yang dimulai dari
penetapan status perjanjian internasional dalam Konstitusi. Pilihan yang relevan
bila Indonesia menganut doktrin monisme untuk perjanjian internasional yang
berkarekter treaty contract dan menggunakan doktrin transformasi untuk perjanjian
internasional yang law making treaty. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mewadahi langkah ini dengan
mengintegarsikan penambahan ayat yang menentukan bahwa perjanjian
internasional yang menciptakan kaidah hukum baru berlaku setelah
94 Catherine Brolmann, “Law Making treaties: From and Function in International Law”
Nordic Journal of International Law 74, 2005, halaman 384.
375
ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui pembentukan atau
perubahan undang-undang.
Pilihan ini lebih memungkinkan Indonesia untuk menyelaraskan substansi
perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi sekaligus memastikan
Indonesia tidak lalai dalam mentransformasikan perjanjian internasional yang telah
diratifikasi. Langkah hukum ini juga akan sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan nasional. Hal ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan hukum
internasional dalam hukum nasional Indonesia termasuk bagi hakim dan individu.
4. Pengembangan Hukum ke Depan Terkait Perwujudan Hak Masyarakat
Hukum Adat atas Access and Benefit Sharing/ABS
Banyak negara mengatur akses ke sumber daya genetik, baik dalam undang-
undang eksplisit tentang akses dan pembagian keuntungan yang diperkenalkan
secara nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap CBD dan perlindungan
sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya. Pengaturan negara-negara
dalam hukum nasionalnya merupakan tindakan hukum baru yang diperkenalkan
sejak CBD antara lain di negara Filipina (Executive Order 245 tahun 1995)95 dan
Thailand (PVP tahun 1999 dan UU Promosi Obat Tradisional). Ketentuan yang
mengatur aspek akses dan pembagian keuntungan untuk turunan dari sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional juga diakomodir India melalui Biological
Diversity Act tahun 2002, Bangladesh (Biodiversity Act, tahun 2017) termasuk di
95 Smagadi Aprodhite, “National Meusures on Access to Genetic Resources and Benefit
Sharing: The Cases of Philippines” Lead Journal 2005 Volume 1, diakses pada
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/17513.
376
Australia, Brazil96. Colombia mengaturnya dalam Res 620 1997 tentang Penetapan
Proses ABS, Afrika Selatan (Bio-Prospecting, Access and Benefit-Sharing (BABS)
2015),97 Vietnam (Law and Biodiversity tahun 2008), China (Regulation of Access
to Genetic Resources and Benefit Sharing tahun 2017). 98
Meskipun Indonesia telah meratifikasi CBD dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1995 dan Nagoya Protocol dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2013, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang ABS untuk
sumber daya genetiknya.99 Indonesia perlu mewadahi kewajiban yang ditetapkan
oleh CBD dan Nagoya Protocol,100 tentang sistem Access and Benefit Sharing
96 Daniella Guaras et al, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: a Review of
Existing Frameworks, Unites Nation Environment World Conservation Monitoring Centre, 2019,
halaman 12, Diakses pada https://www.unep-
wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/579/original/ “Law 13.123, adopted in 2015, and
its regulating Decree 8772 of 2016, are the main legal instruments regulating access and benefit-
sharing in Brazil. The emphasis of the legislation is on access to genetic heritage and associated
traditional knowledge; with the aim of ensuring benefits arising out of their economic exploitation
are shared in a fair and equitable way.” 97 Ibid., halaman 161: “South Africa is a Party to the Nagoya Protocol since its entry into
force in 2014. However, its ABS system precedes the existence of the Protocol. Access and benefit-
sharing in South Africa is regulated through a series of instruments, the main two being the National
Environmental Management Biodiversity Act (NEMBA) 2004 (and its subsequent amendments), and
Regulations on Bio-Prospecting, Access and Benefit-Sharing (BABS) 2015. Even though these two
instruments are at the cornerstone of the South African ABS framework” 98 Aathira Perinchery, “Bioresources Access and Benefit Sharing: How Far We Have Come
in India”, “After India ratified the CBD, there was no looking back. In 2002, India became one of
the first countries to enact a law, the Biological Diversity Act, to implement the treaty”, 2020,
halaman 2, diakses pada https://india.mongabay.com/2020/04/india-bioresource-access-and-
benefit-sharing-how-far-have-we-come/ tanggal 29 Januari 2021: “National Biodiversity Authority
(NBA) yang memastikan pembagian keuntungan yang adil diimplementasikan. Dewan
keanekaragaman hayati negara bagian memberi nasihat kepada pemerintah negara bagian tentang
hal-hal yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan
dan komite pengelolaan keanekaragaman hayati melaksanakan konservasi di akar rumput dan
menyiapkan daftar keanekaragaman hayati masyarakat, atau daftar semua keanekaragaman hayati
di wilayah mereka, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. Manfaat dari
jaringan ini adalah uang mulai mengalir pada awal tahun 2007. Misalnya, PepsiCo India Holdings
Private Limited membayar Dewan Keanekaragaman Hayati Tamil Nadu 3,7 juta Rupee untuk
mengakses spesies rumput laut eksotis Kappaphycus alvarezii yang dibudidayakan oleh masyarakat
hukum adat di Tamil Nadu selatan.” 99 Diakses pada https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12532 100 Efridani Lubis, op. cit., halaman 452.
377
dalam kaitannya dengan hak masyarakat hukum adat atas pembagian keuntungan.
Setelah CBD berlaku beberapa negara menetapkan aturan ABS dalam wilayahnya.
Namun sampai sekarang Indonesia belum memiliki kerangka hukum ABS
walaupun telah meratifikasi CBD lebih dari 25 tahun yang lalu.101
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
pemanfaatan keanekaragaman hayatinya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Namun undang-
undang ini belum mengacu pada CBD dan Nagoya Protocol. Terdapat Peraturan
perundang-undang yang mendukung ABS yaitu mengenai izin peneliti
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearipan Lokal dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup namun masih terbatas dan
bersifat sektoral.
Formulasi ke depan terkait dengan perwujudan hak masyarakat hukum adat
atas ABS bertalian erat dengan perjanjian internasional yang termasuk dalam
pengertian ‘governed by international law’ merupakan suatu instrumen
internasional yang bertujuan untuk menciptakan kewajiban internasional yaitu
CBD dan Nagoya Protocol. Berdasarkan pendapat Fiztmaurice yang dimaksud
dengan governed by international law tidak hanya berarti menciptakan hak dan
kewajiban berdasarkan hukum internasional tetapi juga menciptakan hubungan
101 Nurul Bazirah, “Access and Benefit Sharing of Biodiversity for Enpowering Local
Community: Case Studies in Selected Countries”, Journal Review of International Geographical
Education Volume 11 (4) 2021, halaman 191, diakses pada https://rigeo.org/submit-a-
menuscript/index.php/submission/article/view/407.
378
internasional yang berdasarkan hukum internasional. 102
CBD dan Nagoya Protokol merupakan perjanjian internasional yang
termasuk dalam law making treaty dan governed by international law.
Terbentuknya CBD dan Nagoya Protokol untuk mengatasi ancaman kepunahan
sumber daya hayati dengan mengatur hubungan yang lebih adil antara penguna dan
penyedia termasuk masyarakat hukum adat selaku pengkonservasi yang selama ini
dirugikan dengan praktik biopiracy.
Perlindungan hukum sumber daya genetik masyarakat hukum adat pada
hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban yang harus
dilakukan oleh negara yang telah meratifikasi. Tujuan nasional Negara Republik
Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati
sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan
secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Namun kondisi sumber daya genetik terus menerus mengalami kemerosotan akibat
masifnya pengambil sumber daya genetik yang mengancam kelangsungan
kehidupan manusia. Masyarakat hukum adat telah merawat dan melestarikan
102 Anthony Aust, op. cit., halaman 18.
379
sumber daya genetik selama berabad-abad yang menjadi sumber pengidupan yang
berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum untuk
menjamin haknya.
Sebuah negara seperti halnya Indonesia sebagai suatu entitas bagian dari
masyarakat hukum internasional yang ikut serta dalam suatu perjanjian wajib
melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Pengaitan sumber daya genetik
dengan hak atas pembagian keuntungan bertujuan setiap akses dan
pemanfaatannya yang dilakukan pihak ketiga berkontribusi bagi pelestariannya
dengan membagi keuntungan yang diperoleh para pihak.
Transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional ini terkait
dengan bagaimana kedudukan dan status hukum internasional dalam sistem hukum
nasional. Kewajiban negara pascapenandatangan perjanjian internasional adalah
mentransformasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional. CBD
merupakan titik awal konsep ABS untuk hak atau kepentingan hukum yang dapat
dimiliki atas sumber daya genetik yang tidak dikenal sebelumnya. Dalam
pengertian ini ABS adalah salah satu konsep hukum baru dan inovatif yang
diperkenalkan dalam hukum internasional.
Relasi ini mengacu pada prinsip-prinsip dan cara-cara dimana sumber daya
genetik dapat diakses dan bagaimana pembagian keuntungan disepakati antara yang
menggunakan sumber daya dan penyedia, yang diatur dalam persetujuan atas
informasi awal (Free Prior Informed Consent/PFIC) dan kesepakatan transfer
keuntungan/manfaat (Mutually Agreed Transfer/MAT). Lebih lanjut di dalam
konsep tersebut terkandung dua nilai fundamental yaitu keadilan dan kesetaraan.
380
Keadilan direfleksikan dengan kebijakan pengakuan kontribusi masyarakat hukum
adat dalam konservasi sumber daya genetik dan peran dunia industri untuk
mengakses dan mengembangkan sumber daya genetik menjadi produk yang
bernilai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanfaatan umat manusia yang
lebih luas. Sedangkan kesetaraan merupakan makna relasi yang seimbang antara
kepentingan hukum dari masyarakat hukum adat dan penguna. Penguna berhak
mengakses dan memanfaatkan sumber daya genetik untuk tujuan komersial dan
masyarakat hukum adat berhak atas pembagian keuntungannya.
Berdasarkan paparan tersebut di atas maka pengembangan hak baru
masyarakat hukum adat berbasis hak atas sumber daya alam sebagaimana dijamin
dalam instrumen hukum internasional UNDRIP dan diamanahkan oleh CBD dan
Nagoya Protocol untuk diatur lebih lanjut dalam sistem hukum nasional perlu
ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan membentuk kerangka hukum baru sistem
ABS Indonesia sendiri.
Implementasi ABS yang didefinisikan dengan jelas dan diatur dalam
instrumen hukum nasional yang relevan merupakan langkah hukum yang perlu
ditempuh Indonesia. Kerangka hukum awal yang dapat ditempuh ke depan adalah
dengan memunculkan dan memformulasikan hak baru dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat dengan menambah satu pasal setelah
Pasal 28 dengan rumusan: (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas pembagian
keuntungan atas akses dan pemanfaatan sumber daya genetiknya; (2) Pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip
FPIC dan MAT, (3) besaran pembagian keuntungan yang diperoleh oleh penguna
381
disepakati bersama dalam suatu perjanjian pembagian keuntungan.
Pengintergrasian sistem ABS sebagai hak baru masyarakat hukum adat dalam RUU
Masyarakat Hukum Adat seterusnya perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang
lebih luas dengan membangun rezim ABS Indonesia secara komprehensif.
Pilihan kedua dapat ditempuh dengan membangun sistem ABS secara yang
sui generis. Kerangka hukum tersebut mencakup dan saling melengkapi yaitu
sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana negara-negara kaya
sumber daya genetik lainnya. Upaya membangun sistem ABS ini termasuk
membangun kelembangaan yang berwenang dalam mengelola sistem ABS di
Indonesia, memastikan hak dan kewajiban para pihak
Hadirnya negara nasional di seluruh belahan bumi tidak lain karena latar
belakang sejarah, sosial, politik, hukum, dan budaya yang berbeda hingga
membentuk suatu identitas yang menjadi perekat sebagai satu bangsa sekaligus
pembeda dengan negara bangsa lainnya. Indonesia berkepentingan untuk
terciptanya tata hukum internasional yang tertib dan diterima negara-negara karena
hal ini merupakan amanat dan tujuan pembentukan negara. Betapapun berlainan
wujudnya hukum positif yang berlaku di masing-maisng negara terdapat pula unsur
keterkaitan dan pengikat hukum yaitu asas kesamaan hukum antar negara-negara.
Pada saat Indonesia mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian internasional
berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan good faith namun abai melaksanakan
kewajiban perjanjian maka hukum internasional menjadi tidak bermakna dan
terjadi ketidakpastian.
382
Kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam suatu perjanjian
internasional dapat dipenuhi dengan baik apabila Indonesia membangun rezim
relasi hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dengan tertib dan
konsisten. Hal ini penting agar dapat dipedomani oleh para penegak hukum, seluruh
warga negara dan terciptanya tata hukum internasional kredibel. Penerimaan negara
dengan mentransformasikan norma perjanjian internasional memberikan peluang
bagi hukum internasional untuk diterima dan menjangkau setiap sudut dunia.
Hukum internasional dapat dipergunakan untuk mencapai standar umum negara-
negara dan mengubah tata dunia yang lebih baik untuk semua negara dalam
perlindungan keanekargaman hayati dan pemenuhan keadilan dalam konteks rezim
ABS dan hak masyarakat hukum adat.
Transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional Rezim ABS
tidak akan berfungsi kecuali para pihak memberlakukan kebijakan hukum untuk
memenuhi kewajiban perjanjian internasional (CBD dan Nagoya Protokol) di
tingkat nasional dan membangun kapasitas untuk mengimplementasikan langkah-
langkah mewujudkan rezim ABS. Langkah-langkah transformasi tersebut memuat
pengaturan amanah CBD dan Nagoya Protocol yang mencakup sebagai berikut:
a. Mengambil langkah-langkah legislatif, adminsitratif atau kebijakan yang
diperlukan untuk memastikan masyarakat hukum adat memperoleh pembagian
keuntungan atas akses dan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisionalnya melalui kebijakan pengakuan hak.
383
b. Mengatur akses yang tepat ke sumber daya genetik dengan memperhitungkan
semua hak yang terkait atas akses sumber daya genetik tersebut pengguna dan
penyedia.
c. Membangun kelembagaan yang kompeten untuk melaksanakan akses ke
sumber daya genetik.
d. Mengatur transfer teknologi yang relevan dengan mempertimbangkan semua
hak atas sumber daya genetik antara pengguna dan penyedia.
e. Memberikan kepastikan hukum, kejelasan dan trasnparansi akses dan peraturan
persyaratan pembagian keuntungan.
f. Menyediakan aturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam
mengakses sumber daya genetik.
g. Memberikan informasi tentang cara mengajukan persetujuan berdasarkan
informasi sebelumnya.
h. Memberikan keputusan tertulis yang jelas dan transparan yang dilakukan oleh
otoritas yang kompeten terkait akses dan pembagian keuntungan.
i. Menyediakan dokumen penerbitan pada saat akes izin diberikan sebagai bukti
keputusan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu dan penetapan syarat-
syarat yang disepakati bersama serta memberitahukan kepada lembaga kliring
akses dan pembagian hasil atau keuntungan
j. Menetapkan kriteria dan proses untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan
informasi awal dan keterlibatan masyarakat hukum adat ke akses sumber daya
genetik.
384
k. Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dalam menetapkan persyaratan
yang disepakati bersama. Persyaratan tersebut ditetapkan secara tertulis dan
meliputi:
1) Klausul penyelesaian sengketa;
2) Ketentuan pembagian keuntungan termasuk yang berhubungan dengan hak
kekayaan intelektual bila disepakati;
3) Ketentuan penggunaan oleh pihak ketiga selanjutnya bila disepakati; dan
4) Ketentuan tentang perubahan kesepakatan bila diperlukan.
Bagi Indonesia rezim ABS ke depan perlu dibangun berdasarkan prinsip-
prinsip yang diamanahkan oleh CBD dan Nagoya Protocol berbasis keadilan sosial
Pancasila. Keadilan Pancasila merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan
pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaultan rakyat. Di satu sisi
perwujudan keadilan sosial itu tercermin imperatif etis pada keempat sila lainnya.
Di sisi lain, otensitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan
keadilan sosial dalam perikehidupan kemanusiaan berkebangsaan. Kesungguhan
negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia bisa
dinilai dari upaya nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk kepada
masyarakat hukum adat yang memiliki kepenting besar untuk mendapat keadilan
dalam konteks ini.103
Perlindungan hak masyarakat hukum adat dan sumber daya genetiknya
terkait ABS menuntut negara berupaya melaksanakan secara aktif kebijakan yang
telah disepakatinya dalam perjanjian internasional CBD dan Nagoya Protokol agar
103 Yudi Latif, “Reaktualisasi Pancasila”, MKRI, Pusdik, Jakarta, halaman 26.
385
keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat khususnya dan rakyat Indonesia
umumnya dapat direalisasikan. Keadilan Pancasila menegaskan hak individu dan
hak kelompok merupakan konsekuensi dari keberadaan manusia Indonesia dalam
perspektif Pancasila termasuk melindungi hak masyarakat hukum adat untuk
mendapatkan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetiknya.
Dalam kaitan dengan Pancasila sebagai Grundnorm serta dalam
hubungannya dengan hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan
perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia yang dalam penelitian ini
adalah CBD dan Nagoya Protocol terdapat relasi keduanya. Menurut Hans Kelsen
interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dilihat bahwa
seluruh negara di dunia terikat pada norma yang disebut basic norm. Norma
tersebut menciptakan hubungan timbal balik antar negara dan seterusnya
menciptakan kebiasaan internasional dan hukum internasional. Tindakan resiprokal
antar negara tersebut dikatakan Hans Kelsen sebagai law creating material fact
bahwa: “The basic norm of international law, then, and thus of state legal system,
to, whose power is delegate to them by international law, must be a norm that
establishes custom the reciprocal behaviour of states as law creating material
fact.104
Indonesia mempunyai Pancasila yang mendasari law making material fact
bagi pembentukan hukum nasional dan hukum internasional yang dibentuk oleh
tindakan resiprokal Indonesia dengan negara lain yang menciptakan suatu hukum
104 Garry Gumilar Pratama, Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum
Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945, Pustaka Unpad, 2015,
halaman 5.
386
internasional. Proklamasi merupakan gerbang untuk mengantarkan Indonesia pada
kemerdekaan sebagai negara berdaulat yang sejajar dengan bangsa lain sedangkan
Pancasila meletakkan dasar-dasar, nilai dan asas pembentukan hukum dalam sistem
hukum nasional.
Dalam kerangka perjanjian internasional CBD dan Nagoya Protocol
kepentingan Indonesia adalah melindungi sumber daya genetiknya yang berlimpah
yang umumnya diperlihara dan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat
hukum adat. Sumber daya ini bernilai ekonomi tinggi dan perlu dikelola dan diatur
pemanfaatannya secara berkelanjutan. Karena itu akses dan pemanfaatn sumber
daya genetik masyarakat hukum adat harus memberikan keuntungan yang adil
terhadap usaha dan jerih payah mereka dalam melakukan konservasi.
Kepentingan Indonesia yang lebih luas adalah memajukan kesejahteraan
umum dan mewujudkan keadilan sosial. Hukum adalah sesuatu yang mengikat dan
bila ikatan itu dikaitkan dengan setiap orang atau kelompok orang (masyarakat
hukum adat) maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian
pengaturan konsep Access and Benefit Sharing ke depan dibangun di atas prinsip-
prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila selain tentu saja mengacu pada
prinsip-prinsip ABS yang diatur dalam CBD dan Nagoya Protocol.
Seturut dengan hal tersebut bahwa salah satu prinsip fundamental dalam
hukum internasional adalah setiap negara dalam melaksanakan perjanjian
internasional sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Indonesia terikat untuk
melaksanakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Pembukaan alenia ke
empat yaitu ikut serta menjaga ketertiban dunia. Amanat Konstitusi untuk ikut
387
menjaga ketertiban dunia hanya dapat terwujud bila ada tata hukum internasional
yang kredibel dan diterima negara-negara.105
Pilar utama dari tata hukum internasional yang kredibel dan tertib hanya
dapat diwujudkan bila negara-negara mentaati dan menerima asas pacta sunt
servanda. Pengingkaran terhadap asas pacta sunt servanda ini dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam hubungan antar negara dengan menggunakan alasan
hukum nasional suatu negara tidak melaksanakan kewajiban internasionalnya.
Karena itu, ketaatan negara dalam menjalankan kewajiban perjanjian internasional
dalam hukum nasionalnya bagi Indonesia sesungguhnya dapat dimaknai sebagai
pelaksanaan kewajiban konstitusionalnya yang tercantum dalam Pembukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai perwujudan
tujuan negara.106
Dalam cita hukum Pancasila terkandung tujuan hukum yang diidealkan
yaitu keadilan Pancasila. Dengan kedudukannya yang demikian maka Pancasila
adalah kaidah bangsa yang menjadi panduan bagi terbentuknya hukum nasional.
Dalam sistem hukum Pancasila, hukum harus berdimensi dan berorientasi keadilan
yang penuh dengan sentuhan moral dan nurani yang diharapkan menjadi esensi
pembangunan hukum. Kelalaian Indonesia dalam mentransformasikan konsep
ABS ke dalam sistem hukum nasionalnya dapat berujung pada ketidakadilan bagi
masyarakat hukum adat karena ketiadaan aturan yang mewadahi kepentingan dan
haknya.
105 MKRI, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011, halaman 131. 106 Ibid.