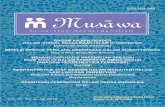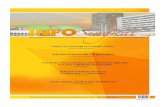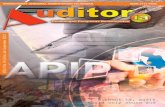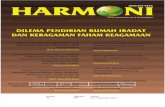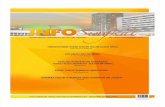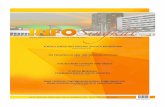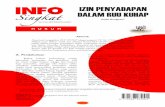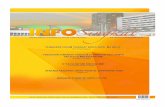Vol. VII No.13 I P3DI Juli 2015
-
Upload
infosingkat -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of Vol. VII No.13 I P3DI Juli 2015
-
- 1 -
Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351
Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015H U K U M
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
REVISI UU KPK: PEMBENAHAN HUKUM PENYADAPAN KPK
Prianter Jaya Hairi*)
Abstrak
Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.
PendahuluanRevisi Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Revisi UU KPK pada awalnya bukan merupakan RUU prioritas pada tahun 2015 akhirnya menjadi prioritas tahun 2015 setelah pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengajukan permohonan pengagendaan tersebut dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg), 16 Juni 2015. Kesepakatan untuk menetapkan revisi terhadap UU KPK sebagai prioritas, dilakukan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-33 tanggal 23 Juni 2015.
Pro-kontra terkait revisi UU KPK kini mulai lagi ramai dibicarakan. Polemik
rencana revisi UU KPK sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Rencana pengajuannya saja sudah menimbulkan pro dan kontra sejak lama, yang terakhir yakni pada tahun 2012 lalu. Bedanya, pada saat itu seluruh fraksi menolak revisi, sementara itu sekarang seluruh fraksi menyetujui untuk direvisi. Pro dan kontra tidak hanya muncul di gedung DPR, melainkan juga oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya akademisi dan masyarakat.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril misalnya, berpandangan bahwa penolakan revisi bukan hanya karena ingin agar RUU KPK tidak diubah, tetapi karena kenyataan bahwa parlemen yang secara terang-terangan akan mereduksi kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan. Jika itu terealisasi, keberadaan
*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: [email protected]
-
- 2 -
KPK bisa dipastikan akan mati dan tidak berguna lagi. Sebaliknya pandangan berbeda disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menegaskan bahwa revisi UU KPK bukan berarti upaya memperlemah KPK. Sebaliknya, revisi itu justru malah bisa memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum. Sebagai contoh, pengaturan kembali kewenangan penyadapan KPK menurutnya bukan untuk mengurangi kewenangan KPK karena melalui revisi tersebut, prosedur penyadapan akan diperketat pengaturannya.
Sejauh ini belum ada draf dan naskah akademik (NA) yang secara resmi diajukan. Namun demikian, beberapa wacana perubahan substansi sudah mengemuka dan menjadi perdebatan luas, termasuk dalam konteks tulisan ini terkait dengan soal aturan penyadapan (interception). Tulisan ini tidak bermaksud mengesampingkan keperluan revisi beberapa substansi lainnya yang tidak kalah penting dalam revisi UU KPK tersebut. Menkumham menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat lima isu krusial yang diwacanakan akan dimasukan dalam NA RUU KPK, yaitu (1) kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses "pro-justisia"; (2) peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung; (3) perlu dibentuknya Dewan Pengawas; (4) pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan; dan (5) penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.
Pembenahan Dasar Hukum Penyadapan KPK
Sudah bukan rahasia umum bahwa salah satu substansi paling krusial dalam rencana revisi UU KPK berkenaan dengan aturan penyadapan oleh KPK. Pembenahan aturan penyadapan menjadi isu sensitif karena selalu dicurigai hanya akan memperlemah kewenangan KPK. Padahal pembahasan substansi belum dimulai sama sekali bahkan pengajuan draf dan NA RUU KPK tersebut belum disiapkan.
Dalam pengaturan yang ada saat ini, tepatnya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, pada intinya hanya diatur bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Sedangkan soal mekanisme penyadapan belum diatur sama sekali. Selama ini KPK hanya menggunakan aturan Standard Operating Procedures (SOP) tentang teknis penyadapan yang dibuat oleh KPK sendiri.
Lemahnya dasar hukum KPK dalam melakukan kewenangannya tersebut sudah menjadi perhatian banyak pemerhati hukum, termasuk dari KPK sendiri. Amien Sunaryadi, ketika menjadi Komisioner KPK, bahkan sempat mengusulkan agar DPR membentuk UU Penyadapan. Amien menyadari betapa lemahnya dasar hukum tindakan penyadapan yang dijalankan KPK, khususnya berkaitan dengan aspek teknis. Dalam kenyataannya, jenis kewenangan KPK ini memang beberapa kali dipersoalkan di pengadilan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pembenahan dasar hukum penyadapan KPK sebenarnya sangat dibutuhkan.
Penyadapan memang merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidak-tidaknya menurut pandangan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Meskipun di sisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk melanggar hak asasi manusia (HAM). Juru bicara KPK, Johan Budi, dalam suatu acara diskusi, menyebutkan bahwa 30% kasus yang ditangani KPK terutama pada saat tertangkap tangan, merupakan hasil dari metode penyadapan.
Sebenarnya efektifitas penyadapan ini sudah disadari oleh pembentuk undang-undang jauh hari sebelum KPK pamer tentang keberhasilannya dalam mengungkap korupsi dengan alat sadap. Banyak peraturan hukum lain yang sudah terlebih dahulu memberikan wewenang penyadapan ke berbagai lembaga negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak lembaga negara yang kemudian memiliki wewenang menyadap, dan uniknya proses serta mekanismenya pun berbeda. Hal yang kemudian menimbulkan masalah adalah isu ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan aturan penyadapan di Indonesia.
Mengenai kebutuhan akan pengaturan ulang aturan penyadapan KPK, sudah sejak lama menjadi perhatian. Terdapat
-
- 3 -
tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan penyadapan ini. Ketiga putusan tersebut pada akhirnya menolak permohonan pemohon. Meskipun demikian, ada beberapa amanat para hakim MK yang harus diperhatikan, yakni terkait erat dengan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk soal aturan penyadapan KPK.
Pertama, Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004. Dalam putusannya, meskipun menolak permohonan pemohon, untuk membatalkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, di dalam pertimbangan hukum putusannya, MK memberikan penjelasan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut MK menyatakan, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman MK berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud.
Kedua, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Dalam putusannya, MK kembali menolak permohonan pembatalan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan memerintahkan untuk menuangkan pengaturan mengenai penyadapan dalam Undang-undang (UU). UU dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.
Ketiga, Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011. Secara umum, dalam ratio decidendi putusan perkara No. 5/PUU-VIII/2010,
MK menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar HAM. Meskipun begitu, untuk kepentingan nasional yang lebih luas, seperti halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpangi dengan pembatasan. Mempertimbangkan bahwa penyadapan merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM seseorang, maka pengaturannya harus dilakukan dengan UU. Menurut MK, pengaturan dengan menggunakan UU akan memastikan adanya keterbukaan dan legalitas dari penyadapan itu sendiri.
Dengan ketiga putusan MK tersebut, pembentukan suatu perangkat peraturan setingkat UU yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman memang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM seseorang. Termasuk pula dalam konteks ini, yakni keperluan merevisi UU KPK terkait penyadapan.
Pembentukan pengaturan terkait penyadapan setingkat UU tersebut sebenarnya lebih tepat ketika RUU KUHAP dibahas di DPR. Namun demikian, sayangnya substansi penyadapan yang diatur dalam KUHAP masih cukup terbatas, hanya terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 83 dan Pasal 84. Secara umum RUU KUHAP hanya mengatur berkenaan dengan jenis tindak pidana yang boleh disadap, yakni yang tergolong tindak pidana serius. Selain itu, diatur pula bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atas perintah atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan. Sementara itu, soal kategori subjek hukum yang berwenang menyadap, tata cara penyadapan, pengawasan, dan penggunaan hasil penyadapan belum diatur.
Jika merujuk keterangan saksi ahli, Ifdhal Kasim, dalam sidang MK Perkara No. 5/PUU-VIII/2010, maka diketahui beberapa substansi yang seharusnya diatur dalam UU, di antaranya penyadapan hanya dibolehkan bilamana memenuhi beberapa pra-syarat berikut: (1) adanya otoritas resmi yang ditunjuk oleh UU untuk memberikan izin penyadapan (biasanya Ketua Pengadilan); (2) adanya jaminan kepastian jangka waktu penyadapan; (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat
-
- 4 -
mengakses penyadapan.Sementara itu, menurut pendapat
ahli Fajrul Falaakh tentang tata cara penyadapan, seperti pada instrumen dan praktik di negara lain, bahwa UU mengenai penyadapan harus mengatur: (1) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan; (2) tujuan penyadapan secara spesifik; (3) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; (4) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan; (5) tata cara penyadapan,; (6) waktu penyadapan; (7) pengawasan terhadap penyadapan; dan (8) penggunaan hasil penyadapan.
Dalam konteks pembenahan aturan penyadapan dalam revisi UU KPK, pembentuk UU perlu memperhatikan substansi-substansi penting terkait penyadapan tersebut. Sistem pemantauan dan pengawasan pun harus dibentuk. Selain itu, mekanisme keluhan, termasuk di dalamnya soal aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan pun demikian.
Supriyadi W. Eddyono dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menulis bahwa pengaturan penggunaan materi hasil penyadapan mencakup berberapa hal yang pada intinya, yakni: (1) adanya pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan dan jangka waktu penyimpanan hasil penyadapan; (2) prosedur penyadapan; (3) mengatur mengenai materi penyadapan yang relevan; (4) prosedur menjadikan materi penyadapan sebagai alat bukti di pengadilan; dan (5) menghancurkan hasil penyadapan yang sudah tidak relevan demi kepentingan umum dan hak privasi warga negara
PenutupPengaturan yang ada saat ini hanya
mengatur pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanismenya belum diatur sama sekali. Selama ini KPK hanya menggunakan aturan SOP tentang teknis penyadapan yang ditetapkan oleh KPK sendiri. Lemahnya dasar hukum KPK dalam melakukan kewenangannya tersebut sudah lama menjadi perhatian banyak pemerhati hukum.
MK dalam tiga putusan uji materinya tahun 2003, 2006, dan 2010 pada intinya
telah mengamanatkan kebutuhan suatu perangkat peraturan setingkat UU yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM sesorang. Dalam konteks tersebut, maka pembenahan aturan penyadapan KPK dalam UU KPK menjadi penting.
Dalam merevisi UU KPK, pembentuk UU perlu memperhatikan substansi-substansi penting terkait penyadapan. Termasuk soal sistem pemantauan dan pengawasan, mekanisme keluhan, serta aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan. Selain revisi UU KPK, pembenahan pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP semestinya menjadi dasar hukum bagi seluruh tindakan penyadapan oleh penegak hukum yang berwenang.
ReferensiUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan KorupsiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/
PUU-I/2003Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-
016-019/PUU-IV/2006Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/
PUU-VIII/2010Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana IndonesiaICW Ingatkan Presiden Untuk Tolak Revisi
UU KPK, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558cdc90301d4/icw-ingatkan-presiden-untuk-tolak-revisi-uu-kpk, diakses 2 Juli 2015.
Kalla: Revisi UU Bukan Berarti Untuk Memperlemah KPK, h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2015/06/17/17112361/Kalla.Revisi.UU.Bukan.Berarti.untuk.Memperlemah.KPK, diakses 2 Juli 2015.
Erasmus A. T. Napitupulu, Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia, http://icjr.or.id/mendamaikan-pengaturan-hukum-penyadapan-di-indonesia/, diakses 2 Juli 2015.
Supriyadi W. Eddyono, Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2012.
-
- 5 -
Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351
Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015HUBUNGAN INTERNASIONAL
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL MELAWAN ISIS
Sita Hidriyah*)
Abstrak
Tiga serangan terorisme telah terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis terjadi tanggal 26 Juni 2015. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku berada di balik serangan tersebut. Serangan ini kembali menunjukkan bahwa ancaman teror ISIS semakin tidak mengenal batas wilayah. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil sehingga menuai reaksi keras masyarakat internasional. Indonesia mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi terorisme.
PendahuluanSerangan teroris dengan korban
penduduk sipil kembali terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis pada 26 Juni 2015. Kelompok ISIS mengklaim mereka berada di balik setiap serangan tersebut dan menyatakan pelaku adalah anggota mereka. Seorang anggota kelompok Islam fanatik bernama Seifeddine Rezgui menggunakan senjata Kalashnikov melakukan serangan brutal di sebuah hotel wisata di pantai El Kantaouim di kota pantai Sousse, Tunisia. Serangan terhadap kawasan yang tengah dipadati wisatawan dari berbagai negara tersebut mengakibatkan korban sipil yang tidak sedikit. Hingga 1 Juli 2015 telah teridetifikasi 39 korban jiwa, sementara masih banyak korban jiwa lainnya yang belum teridentifikasi secara positif.
Bagi Tunisia, serangan tersebut merupakan serangan terbesar kedua dalam tahun ini. Tunisia telah mengalami serangan serupa pada Maret lalu ketika sekelompok militan bersenjata menyerang Museum Bordo di Ibukota Tunis.
Serangan lain terjadi di Kuwait dan dilakukan terhadap umat Islam Syiah yang sedang melakukan shalat Jumat di Masjid Imam Al-Sadeq dengan metode bom bunuh diri. Kejadian ini menyebabkan 27 orang tewas dan 202 orang lainnya luka-luka.
Aksi serupa terjadi pula di tenggara negara Perancis yaitu Lyon, dimana seorang pria yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok radikal Islam menabrak mobil ke sebuah pabrik gas hingga membuat ledakan yang menyebabkan 1 korban meninggal dan dua orang lain terluka. Yang lebih
*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: [email protected]
-
- 6 -
mengerikan adalah ketika pihak berwenang menemukan adanya pemenggalan kepala kepada salah satu korban.
Kekerasan yang masih terus terjadi belumlah menunjukkan tanda akan berhenti. Sementara, publik semakin khawatir dengan meningkatnya serangan terorisme yang menimbulkan korban sipil. Publik juga mempertanyakan upaya yang telah dilakukan masyarakat internasional melalui berbagai bentuk kerjasama dalam memerangi terorisme.
Tujuan Aksi TerorismeDalam beberapa waktu terakhir,
masyarakat internasional telah menyaksikan meningkatnya kembali aksi-aksi teror yang mengakibatkan korban sipil yang tidak sedikit, termasuk wanita dan anak-anak.
Berdasarkan kasus-kasus terorisme yang terjadi selama ini, tampak jelas bahwa aksi teror dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, ditujukan kepada seseorang atau sekelompok tertentu untuk membalas dendam. Sasaran dari dendam tersebut dapat seseorang, sekelompok, atau negara tertentu. Kedua, upaya untuk hanya menimbulkan rasa ketakutan suatu kelompok atau negara tertentu.
Untuk yang pertama, sasaran dari kekerasan berdarah itu jelas, yakni seseorang, sekelompok, atau negara tertentu. Walaupun sulit bagi masyarakat awam untuk menerimanya, alasannya masih dianggap masuk akal. Sebagai contoh dari pilihan pertama yaitu balas dendam adalah saat Jaksa Agung Mesir Hisham Barakat tewas pada 29 Juni 2015 dalam serangan bom mobil di Distrik Heliopolis, Kairo. Serangan tersebut dilakukan oleh Gerakan Perlawanan Rakyat yang diketahui sebagai loyalis Ikhwanul Muslimin (IM). Aksi itu dilakukan sebagai balasan mereka terhadap keputusan vonis hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada para aktivis dan tokoh oposisi, termasuk mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi.
Yang lebih mengerikan adalah pilihan yang kedua, kekerasan berdarah itu dilakukan hanya untuk menimbulkan rasa gentar pada suatu kelompok atau negara tertentu karena sasarannya bisa siapa saja. Sering kali kita lihat bahwa
yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang sama sekali tidak terkait dengan orang atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan berdarah itu. Aksi teror semacam ini masih menjadi pilihan kelompok-kelompok radikal dalam menjalankan perjuangannya.
Upaya Internasional Memerangi Terorisme
Perang global melawan terorisme di satu sisi terus berhadapan dengan peningkatan aksi-aksi terorisme internasional yang terutama ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara-negara pendukungnya. Ancaman-ancaman terhadap agresi ISIS akan dihadapi dengan kekerasan dan aksi teror. Aksi ISIS di Tunisia, Kuwait serta Perancis ditengarai merupakan balas dendam karena mendukung perang terhadap kelompoknya. Perancis telah memberikan dukungan, baik secara finansial dan maupun militer, terhadap serangan ke basis ISIS di Suriah. Pemerintah Kuwait dan lembaga-lembaga swasta negara tersebut memberi pasokan uang tunai dan bahan makanan. Sementara Tunisia pernah mengadakan pertemuan dengan Turki dan negara-negara Teluk Persia Arab serta mengirim 4.000 pemuda Tunisia untuk bergabung melawan ISIS di Suriah. Dengan demikian, yang dapat dilihat jika gelombang terbaru dari serangan teroris di Tunisia, Kuwait dan Perancis adalah aksi balas dendam atas dukungan ketiga negara tersebut dalam penyerangan kepada ISIS.
Serangan teror yang terjadi di tiga negara berbeda mengejutkan banyak pihak karena sasaran yang dituju berada di wilayah yang tidak terduga. Bukan hanya oleh kebrutalan aksi dan jumlah korban, melainkan juga oleh kenyataan bahwa bagaimana pelaku kekerasan yang terlihat normal dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba berubah menjadi milisi garis keras yang mampu membunuh banyak warga sipil.
Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku, motif di balik terorisme, dan akar permasalahan yang mendasarinya. Motivasi tentang mengapa
-
- 7 -
individu-individu bergabung dengan sebuah kelompok teroris sering sekali sangat kompleks dan bervariasi. Mayoritas individu bergabung dengan kelompok teroris karena berbagai alasan sosial, politik, ekonomi dan pribadi. Motivasi politik yang paling perlu mendapat sorotan adalah disebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara lain, imperialism budaya, sokongan negara bagi pihak yang didefinisikan sebagai musuh, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak disetujui, dan penindasan terhadap kelompok identitas. Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat menjelaskan motivasi dari semua individu tersebut.
Masyarakat internasional mengutuk aksi kekerasan terorisme ISIS tersebut. Terorisme melalui kekerasan merupakan hal yang melanggar kemanusiaan. Membunuh orang yang tidak berdosa, terutama perempuan dan anak-anak yang pasti tidak bersenjata merupakan tindakan yang tidak beradab. Kekerasan yang masih terus terjadi belumlah menunjukkan tanda akan berhenti. Publik semakin khawatir dengan meningkatnya serangan terorisme ISIS yang menimbulkan korban sipil. Publik juga mempertanyakan upaya yang telah dilakukan masyarakat internasional melalui berbagai bentuk kerja sama dalam memerangi terorisme.
Aksi teror yang tidak berhasil ditangani secara efektif akan makin meningkatkan intensitas dan frekuensi aksi-aksi tersebut. Peningkatan kerja sama internasional harus terus dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme, baik dalam kerangka multilateral (PBB) maupun regional, serta bilateral, khususnya dalam bentuk peningkatan kapasitas, penegakan hukum, perbaikan legislasi/kerangka hukum, pertukaran informasi dan berbagi pengalaman, pengiriman pakar dan pemberian advis kepakaran, dan kerja sama teknis lainnya. Termasuk dalam hal ini, berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui pendekatan/strategi soft power, yakni melalui upaya kerja sama untuk mengatasi penyebab dasar terjadinya terorisme (underlying causes of terrorisme). Selain itu, berbagai inisiatif untuk mendorong interfaith dialogue yang
bertujuan membangun saling pengertian dan hubungan yang harmonis antar-umat beragama dan kepercayaan berbagai negara juga perlu dilakukan.
Penutup Serangan teror di Tunisia, Kuwait dan
Perancis pada hari yang sama menunjukan bahwa ancaman teror tidak mengenal batas wilayah. Terorisme terus menjadi ancaman serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan internasional, namun juga berdampak kepada perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara di berbagai kawasan.
Aksi teror ISIS adalah ancaman besar untuk dunia. Dalam jangka panjang, apabila tidak dikelola secara tepat, terorisme dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus mampu merencanakan dan melakukan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang dapat mengantisipasi dan mencegah aksi-aksi terorisme yang meliputi deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
Serangan kekerasan tidak boleh melemahkan tekad masyarakat internasional untuk memerangi ISIS. Hal ini justru harus lebih memperkuat komitmen untuk mengalahkan mereka. Negara-negara dunia tidak bisa membiarkan tindakan-tindakan seperti itu terus terjadi, tanpa ada satu pihak pun yang berusaha atau bertekad menghentikannya. Penuntasan yang menjadi kunci atas tragedi ini adalah kerja sama internasional untuk menghentikan ISIS, melalui kelanjutan kerja sama kontra-terorisme baik secara bilateral maupun multilateral dalam melawan terorisme. Termasuk dalam hal ini kemungkinan pelaksanaan usul kerjasama langsung AS dan sekutu Barat dengan Presiden Suriah Assad yang selama ini ditolak.
Indonesia berkomitmen untuk memerangi terorisme bersama masyarakat internasional. DPR RI dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif mendukung upaya bersama masyarakat internasional untuk memerangi berbagai kelompok gerakan radikal. Pemerintah Indonesia juga perlu kembali mengingatkan para warga negara Indonesia (WNI)
-
- 8 -
yang berada di luar negeri untuk terus meningkatkan kewaspadaan, menjaga diri, menghindari tempat-tempat yang dapat menjadi target teror, dan tidak terlibat dengan kelompok-kelompok radikal.
ReferensiIS Klaim Penembakan di Pantai Tunisia,
Media Indonesia, 28 Juni 2015. Presiden Hollande: Penyerangan Pabrik
adalah Serangan Teroris, Kompas, 26 Juni 2015.
Radikalisasi Anak Muda Tunisia, Kompas, 1 Juli 2015.
Mereka Memilih Cara Kekerasan, Kompas, 29 Juni 2015.
Korban Tewas Asal Inggris Bertambah, Media Indonesia, 1 Juli 2015.
Tunisia Tangkap 12 Tersangka Sousse, Republika, 3 Juli 2015.
Penembakan di Pantai Tunisia, Setidaknya 27 Orang Tewas, http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150626203636-127-62698/p e n e m b a k a n - d i - p a n t a i - t u n i s i a -setidaknya-27-orang-tewas/, diakses tanggal 1 Juli 2015.
Obama dan Sekjen PBB Kecam Aksi Teror di Tiga Negara, http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/27/nqklar-obama-dan-sekjen-pbb-kecam-aksi-teror-di-tiga-negara, diakses tanggal 1 Juli 2015.
Serangan di Tunisia Tewaskan 39 Orang, h t t p : / / w w w . b b c . c o m / i n d o n e s i a /dunia/2015/06/150627_dunia_tunisia_korban, diakses tanggal 1 Juli 2015.
PM Tunisia Perintahkan Penutupan Puluhan Masjid, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150627_dunia_tunisia_masjid, diakses tanggal 1 Juli 2015.
Indonesia Kecam Serangan Teroris Di Kuwait-Tunisia-Perancis, http://www.antaranews.com/berita/503826/indonesia-kecam-serangan-teroris-di-kuwait-tunisia-prancis, diakses tanggal 2 Juli 2015.
-
- 9 -
Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351
Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
ANcAMAN EL NINO 2015Anih Sri Suryani*)
Abstrak
Fenomena cuaca El Nino, yang salah satunya ditandai dengan musim kemarau yang panjang, diperkirakan melanda Indonesia mulai Juni-November 2015. Dampak dari kemarau yang panjang ini di antaranya adalah gagal panen bagi para petani dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan. Perlu strategi yang tepat dalam mengantisipasi hal ini agar fenomena cuaca El Nino tidak berdampak pada ketahanan pangan. Pada sektor pertanian, ketersediaan pasokan air bagi irigasi menjadi perhatian utama selain penyesuaian pola tanam yang perlu mengadaptasi pergeseran musim. Sedangkan pada sektor perikanan, penyediaan sistem informasi kelautan yang terpadu dan dapat diakses oleh nelayan merupakan upaya adaptasi yang dapat dilakukan.
PendahuluanBadan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG) memperkirakan gelombang panas El Nino akan menyerang wilayah Indonesia dari mulai awal Juni sampai November 2015. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, perkembangan El Nino sampai Juni menunjukkan bahwa El Nino masih berada pada level moderat atau sedang, namun berpeluang untuk menguat.
Dampak El Nino berbeda-beda untuk tiap wilayah tergantung pada letak geografisnya. Dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia diperkirakan adalah mundurnya awal musim hujan tahun 2015/2016. Hal ini dapat memicu kekeringan, penurunan jumlah tangkapan ikan, atau bahkan kebakaran hutan.
Pusat prakiraan iklim Amerika (Climate Prediction Center) mencatat bahwa sejak
tahun 1950 telah terjadi setidaknya 22 kali fenomena El Nino. Enam kejadian di antaranya berlangsung dengan intensitas kuat, yaitu pada periode tahun 1957/1958, 1965/1966, 1972/1973, 1982/1983, 1987/1988, dan 1997/1998. Sebagian besar kejadian-kejadian El Nino berlangsung pada akhir musim hujan atau awal hingga pertengahan musim kemarau, yaitu Bulan Mei, Juni, dan Juli. El Nino tahun 1982/1983 dan tahun 1997/1998 adalah dua kejadian El Nino terhebat yang pernah terjadi di era modern dengan dampak yang dirasakan secara global. Disebut berdampak global karena pengaruhnya melanda banyak kawasan di dunia. Amerika dan Eropa mengalami peningkatan curah hujan sehingga memicu bencana banjir besar sedangkan Indonesia, India, Australia, Afrika mengalami
*) Peneliti Muda Kesehatan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI. E-mail: [email protected]
-
- 10 -
pengurangan curah hujan yang menyebabkan kemarau panjang.
Di Indonesia, El nino terakhir mengakibatkan bencana kekeringan yang luas, yaitu pada tahun 1997. Banyak wilayah sentra pertanian mengalami gagal panen serta kebakaran hutan dengan kabut asap yang menyebar sampai dengan negara tetangga. Beratnya pengaruh El Nino terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman yang harus dicarikan jalan keluarnya.
Apa Itu El Nino?El Nino adalah peristiwa memanasnya
suhu air permukaan laut di pantai barat Peru Ekuador (Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global). Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya up-welling (arus dari dasar laut menuju permukaan). Ketika terjadi peningkatan air di Peru dan Ekuador, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang.
Fenomena El Nino bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Proses perubahan suhu permukaaan laut yang biasanya dingin kemudian menghangat bisa memakan waktu dalam hitungan minggu hingga bulan. Oleh karena itu, El Nino dapat diperkirakan dengan melakukan pengamatan terhadap perubahan suhu muka laut.
Masing-masing kejadian El Nino adalah unik dalam hal kekuatannya sebagaimana dampaknya pada pola turunnya hujan maupun panjang durasinya (berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut). Berdasarkan intensitasnya El Nino dikategorikan sebagai El Nino lemah(Weak El Nino), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator +0.5 C s/d +1,0C; El Nino sedang (Moderate El Nino), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator +1,1 C s/d 1,5C; dan El Nino kuat (Strong El Nino), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator >1,5C.
Dampak El Nino di IndonesiaFenomena El Nino menyebabkan curah
hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang, tingkat berkurangnya curah hujan ini sangat tergantung dari intensitas El Nino tersebut. Berbagai publikasi ilmiah menunjukkan bahwa dampak El Nino terhadap iklim di Indonesia akan terasa kuat jika terjadi bersamaan dengan musim kemarau dan sebaliknya akan berkurang (atau bahkan tidak terasa) jika terjadi bersamaan dengan musim penghujan.
Pada kasus El Nino dengan intensitas lemah-sedang, El Nino diperkirakan akan berdampak pada pengurangan curah hujan dengan kisaran 40-80 persen (dibanding normalnya) untuk bulan Juli-Agustus. Hal ini terutama dirasakan di sebagian Sumatera, Jatim-Bali-NTB-NTT, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Sementara pada bulan September-Oktober, dampak El Nino diperkirakan akan semakin parah dimana semakin banyak area yang mengalami pengurangan curah hujan, meliputi seluruh Sumatera kecuali Aceh, seluruh Jawa, Bali-NTB-NTT, sebagian besar Kalimantan, seluruh Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Papua. Pada daerah NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara bahkan curah hujan bisa berkurang hingga 20-40 persen dari normalnya.
Sementara pada kejadian El Nino kuat, kejadian curah hujan di bawah normal diperkirakan akan melanda wilayah yang lebih luas. Wilayah-wilayah yang tidak terdampak oleh El Nino lemah-sedang seperti Sumbar, Bengkulu dan Kalbar, akan terkena pengaruh El Nino kuat. Di beberapa wilayah seperti Sumsel, Babel, Lampung, Jateng, Jatim, Bali-NTB-NTT, Kalsel, Sulsel, Sultra, Maluku dan sebagian Papua bahkan curah hujan hanya turun dalam kisaran 10-30 persen dibanding normalnya, terutama pada bulan September dan Oktober.
Munculnya El Nino level kuat pada musim kemarau dapat menimbulkan kekeringan panjang di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada potensi gagal panen sehingga mempengaruhi pasokan pangan. Untuk El Nino periode ini, daerah yang berpotensi kekeringan adalah kawasan di Selatan Indonesia. Kondisi anomali cuaca itu akan mencapai puncaknya Oktober nanti dan berakhir Februari 2016. Risiko akibat terpaan badai El Nino dan kemarau panjang kali ini diperkirakan tidak masif, karena siklus panen di Indonesia terjadi pada Februari-Maret dan Mei-Juni. Akan tetapi, diperkirakan 11.14 ton padi akan gagal panen dari 222.847 hektar lahan sawah nusantara, dengan estimasi 1 hektar menghasilkan kurang dari 5 ton.
El Nino juga menyebabkan kritisnya kondisi beberapa daerah aliran sungai (DAS), khususnya di Jawa. Berdasarkan analisis terhadap data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang tersebar di Indonesia terlihat bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi untuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Misalnya penurunan debit sungai Bengawan Solo telah menyebabkan 248,2 hektar sawah di Jatim mengalami puso (gagal panen) hingga Juni
-
- 11 -
2015. Sungai di Indonesia memang reaktif terhadap adanya penyimpangan iklim dalam bentuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal, dimana akan langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan hidrologis).
Di sektor perikanan dan kelautan, hasil tangkapan ikan pada tahun-tahun El Nino juga dilaporkan menurun. Hal ini dikarenakan pada kondisi tersebut ketersediaan pakan bagi ikan (plankton) juga berkurang. Selain itu banyak terumbu karang yang mengalami keputihan (coral bleaching) akibat terbatasnya alga yang merupakan sumber makanan dari terumbu karang karena tidak mampu beradaptasi dengan peningkatan suhu air laut. Memanasnya air laut juga akan menggangu kehidupan jenis ikan tertentu yang sensitif terhadap naiknya suhu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya migrasi ikan ke perairan lain yang lebih dingin.
Pada tahun-tahun normal, air laut dalam yang bersuhu rendah dan kaya akan nutrisi bergerak naik ke permukaan di wilayah dekat pantai. Kondisi ini dikenal dengan up-welling. Up-welling ini menyebabkan daerah tersebut sebagai tempat berkumpulnya jutaan plankton dan ikan. Ketika terjadi El Nino up-welling menjadi melemah dan air hangat dengan kandungan nutrisi yang rendah menyebar di sepanjang pantai sehingga panen para nelayan berkurang. Perubahan lokasi potensial penangkapan ikan akibat El Nino, memicu pemborosan waktu melaut dan bahan bakar nelayan tradisional.
Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya penyimpangan cuaca dapat memberi dampak yang positif bagi sektor perikanan. Karena pada masa itu terjadi migrasi ikan tuna ke wilayah Indonesia. Perairan barat Pasifik selama ini diketahui merupakan kawasan yang memiliki kelimpahan ikan tuna tertinggi, mencapai 70 persen stok ikan tuna dunia. Ketika terjadi El Nino, ikan tuna di Pasifik bergerak ke timur. Namun, ikan yang berada di Samudera Hindia bergerak masuk ke selatan Indonesia. Hal itu karena perairan di timur samudera ini mendingin, sedangkan yang berada di barat Sumatera dan selatan Jawa menghangat.
Upaya AntisipasiEl Nino datang hampir bersamaan
dengan masa tanam kering atau musim kemarau, yakni Juni-November, sehingga perlu menyiapkan upaya khusus guna mengantisipasi ancaman dampak gelombang panas El Nino terhadap budi daya pertanian.
Ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan petani dan nelayan sebelum El Nino melanda. Pertama, diversifikasi tanaman. Untuk mengantisipasi kekeringan, sebaiknya petani menyiapkan lahan untuk tanaman umur pendek agar tidak kehabisan air dan cepat panen. Jenis tanaman padi misalnya INPARI 19 yang jenjang umurnya 94 hari sangat dianjurkan untuk ditanam petani karena tergolong varietas umur pendek.
Untuk nelayan dapat melakukan diversifikasi kegiatan usaha dengan beralih menjadi petani garam sementara. Tingkat evaporasi yang tinggi selama El Nino menyebabkan panen garam melimpah. Peluang ini bisa menjadi altenatif bagi nelayan tradisional yang selama periode El Nino tidak bisa melaut untuk beralih sementara menjadi petani garam. Namun hal yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan lahan/tambak sebagai tempat pembuatan lahan, dan juga penambahan keterampilan bagi para nelayan untuk dapat menjadi petani garam.
Kedua, pemanfaatan sumber air alternatif. Ketika air hujan sedikit, maka petani dapat memanfaatkan embung, yakni cadangan air di area persawahan untuk menampung air hujan.
Peran PemerintahPemerintah memegang peranan penting
dalam membantu membimbing petani dan nelayan melewati masa sulit El Nino. Di sini dituntut peran aktif kementerian terkait dalam hal Pertama, informasi, yaitu sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk petani dan nelayan yang melakukan diversifikasi usaha agar tetap dapat produktif. Untuk nelayan yang ingin melaut, maka Pemerintah membantu mengkomunikasikan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) penting bagi nelayan untuk menemukan ikan di tempat yang potensial. Dalam hal antisipasi dampak El Nino, tepat kiranya pemerintah memberikan informasi kepada nelayan lokal mengenai wilayah perairan baik yang minus ikan, dan terutama yang surplus ikan dengan membangun sistem informasi kerakyatan. Berdasarkan hasil pemantauan pakar kelautan, wilayah yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan adalah perairan barat Sumatera, selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, dan Utara Papua.
Pemerintah juga perlu mendorong berbagai lembaga penelitian untuk meningkatkan pemantauan gejala El Nino misalnya dengan pemasangan pelampung pemantauan (buoy) di beberapa titik. Di samping itu, Pemerintah juga perlu membuat
-
- 12 -
peta rawan dampak El dalam mengantisipasi fenomena El Nino yang diprakirakan sudah terjadi ini ini.
Kedua, penyediaan sarana dan prasarana, Pemerintah setempat hendaknya mengatur tata penggunaan air, irigasi, termasuk ketersediaan air di waduk-waduk, serta membangun sejumlah embung. Pada kondisi yang lebih kritis, penggunaan pompa air untuk mengalirkan air guna menyiram tanaman yang terancam puso sangat diperlukan. Namun, mengingat tingginya biaya operasional terutama untuk membeli bahan bakar, alternatif pembiayaan dengan mekanisme subsidi pemerintah baik untuk pembelian pompanya maupun untuk biaya bahan bakar nampaknya diperlukan.
Pada sektor perikanan, Pemerintah perlu membantu meningkatkan jumlah kapal laut penangkap ikan, membangun sistem pendingin serta mendorong swasta mengolah hasil perikanan. Peluang itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan serta mengoptimalkan hasil tangkapan ikan dan produksi garam.
PenutupFenomena El Nino yang berdampak
terutama pada sektor pertanian dan perikanan perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat (terutama kementerian/lembaga terkait) maupun pemerintah daerah yang selama ini dapat memantau langsung kondisi pertanian dan perikanan di wilayahnya.
Koordinasi antarlembaga/ kementerian terkait mutlak dilakukan, yaitu antara BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), termasuk juga lembaga penelitian di perguruan tinggi sebagai sumber data, dengan kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Maritim, dll, untuk kemudian dapat disusun strategi nasional dalam mengantisipasi EL Nino ini. Strategi dan program pemerintah pusat tersebut selanjutnya dapat diimplementasikan di Pemerintah Tingkat I dan kemudian Tingkat II.
DPR RI juga turut berperan dalam fungsi pengawasan untuk memastikan ketersediaan pangan dan kondisi para petani serta nelayan
tidak terganggu selama periode El Nino ini. Dalam hal ini khususnya Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan pemerintah yang membidangi pertanian dan perikanan. DPR perlu memastikan bahwa pemerintah sudah menyusun peta rawan kekeringan terutama di sentra produksi pangan Jawa, Lampung dan Sulawesi Selatan. Strategi dan program pemerintah dalam mengantisipasi El Nino juga perlu diawasi, termasuk program percepatan tanam daerah rawan kekeringan dan pemilihan komoditas yang berumur genjah dan tahan kekeringan. Dengan antisipasi dan upaya pencegahan sedini mungkin, diharapkan dampak negatif El Nino dapat diminimalisir.
ReferensiEl Nino Ancam Kehidupan Nelayan, http://
www.merdeka.com/teknologi/el-nino- ancam-kehidupan-nelayan.html, diakses tanggal 5 Juli 2015.
El Nino, http://idkf.bogor.net/yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/Fenomena.Alam/ElNino /materi2.html, diakses tanggal 3 Juli 2015.
Garam Berkah di Kala Musim Kering,http://www.indosiar.com/ragam/garam-berkah-di-kala-musim-kering_42787.html, diakses tanggal 7 Juli 2015.
Gejala El Nino Menguat, Harian Umum Kompas 9 Juli 2015.
Jateng dan Jatim Alami Puso, Harian Umum Republika 7 Juli 2015.
Sejarah Dampah El Nino di Indonesia, http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/lain lain/ artikel /Sejarah_Dampak_El_Nino_di_Indonesia.bmkg#ixzz3f2JdQnsR, diakses tanggal 3 Juli 2015.
Tindaklanjut Ekspose BMKG dan Lapan dalam Antisipasi El Nino, http://sipongi.menlhk.go.id/home/read/8/tindaklanjut-e k s p o s e - b m k g - d a n - l a p a n - d a l a m -antisipasi-el-nino, diakses tanggal 5 Juli 2015.
"El Nino Diklaim Undang Berkah Buat Lahan Rawa", http://www.republika.co.id/b e r i t a / e k o n o m i / m a k r o / 1 5 / 0 6 / 3 0 /nqrk28-el-nino-diklaim-undang-berkah-buat-lahan-rawa, diakses tanggal 9 Juli 2015.
Rafi'i, Suryatna. 1995. Meteorologi dan Klimatologi. Jakarta: Angkasa.
Tjasyono HK, Bayong. 2004. Klimatologi. Bandung: Penerbit ITB.
Wiratmo, Joko. 1998. La Nina dan El Nino. Bandung: Penerbit ITB.
-
- 13 -
Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351
Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
KRISIS YUNANI DAN TURBULENSI EKONOMI INDONESIA
Achmad Wirabrata*)
Abstrak
Krisis ekonomi yang dialami Yunani dikarenakan kegagalan negara itu membayar utang (default) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 pada International Monetary Fund (IMF), sebesar 1,5 miliar euro. Akibatnya, Yunani bangkrut dan saat ini hidup dari sisa uang pinjaman. Di saat yang sama Indonesia mengalami turbulensi ekonomi. Namun demikian, karena Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, dilihat dari utang luar negeri, tingkat inflasi, dan tren penguatan rupiah, potensi pengaruhnya terhadap turbulensi ekonomi secara nasional sangat kecil.
Pendahuluan Perhatian dunia saat ini sedang tertuju
pada krisis ekonomi yang dialami Yunani. Krisis terjadi akibat kegagalan membayar utang (default) sebesar 1,5 miliar euro atau sekitar Rp22 triliun pada International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah utang luar negeri Yunani yang diperkirakan sekitar 243 miliar Euro. Akibat gagal bayar tersebut, Yunani bangkrut dan kini hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu.
Konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah Yunani adalah memperketat pengendalian modal. Bank ditutup untuk mencegah rush atau arus keluar uang tunai. Rakyat Yunani tidak dapat menarik uang tabungan dalam jumlah besar, bahkan uang pensiun yang menjadi hak para pensiunan pun juga tidak bisa ditarik.
Daya beli masyarakatnya menurun drastis, situasi yang tentu saja akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran dalam waktu dekat.
Krisis Yunani semakin diperparah dengan hutang terhadap PDB yang semakin besar, yaitu sebesar 177 persen (Gambar 1). Pertumbuhan PDB yang hanya sebesar 0,2%, tentu berdampak pada risiko kegagalan dalam membayar hutang.
Gambar 1. Perbandingan Hutang dan PDB Yunani
sumber:www.tradingeconomics.com
*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: [email protected]
100 106.1105.4
112.9
129.7
146
171.3
156.9
175 177.1
1/1/2006 1/1/2008 1/1/2010 1/1/2012 1/1/2014
-
- 14 -
Default yang terjadi saat ini bukan yang terakhir, mengingat jatuh tempo hutang yang harus dibayar pada bulan Juli 2015 sebesar 8,03 miliar euro, termasuk pembayaran bunga sebesar 910 juta euro (Tabel 1).
Yunani menjadi negara (maju) pertama di Eropa yang bangkrut akibat tidak bisa membayar utang. Banyak negara yang berada di ambang kebangkrutan yang sama tetapi akhirnya bisa lolos dari jeratan, misalnya Argentina dan Puerto Rico. Meskipun belum keluar dari krisis finansial, tetapi setidak-tidaknya mereka bisa membayar utang-utangnya.
Ketika Yunani mengalami krisis saat ini, di saat yang sama Indonesia juga tengah mengalami turbulensi ekonomi. Situasi ini ditandai dengan semakin lemahnya rupiah dibandingkan dengan dolar AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta utang luar negeri triwulan pertama tahun 2015 yang telah mencapai 298,1 miliar dolar AS. Semua ini merupakan faktor yang tidak bisa dianggap remeh.
Namun demikian, krisis di Yunani memberikan dampak yang tidak terlalu relevan secara langsung kepada ekonomi Indonesia. Andil ekspor Indonesia ke benua Eropa terhadap PDB relatif kecil, yaitu sekitar 2,5 persen dan ke Yunani hanya sebesar 0,1 persen. Mari kita bandingkan korelasi ini dalam konteks kekuatan ekonomi kedua negara masing-masing.
Kondisi Keuangan YunaniKondisi perekonomian Yunani
masih tetap terpuruk, walaupun sudah mendapatkan bantuan sebesar 240 miliar euro pada tahun 2010. Di tahun yang sama, sebenearnya beberapa negara di Eropa juga mengalami krisis tetapi saat ini kondisinya mulai membaik dan pertumbuhan
ekonominya bergerak positif.Setelah bergabung dengan zona
mata uang Euro (Eurozone) pada 1 Januari 2001, Yunani yang memiliki banyak utang, langsung menjadi korban pertama krisis finansial global yang muncul pada 2007-2008. Imbas krisis finansial global ini tidak hanya dirasakan Yunani namun juga membebani 19 negara zona Euro lainnya karena harus ikut membantu membenahi perekonomian negeri itu.
Perlahan-lahan krisis finansial Yunani semakin memburuk. Utang negara mencapai 107 persen dari penghasilan nasional pada 2007 menjadi 177 persen pada tahun lalu. Angka ini jauh di atas batas yang ditetapkan Uni Eropa, yaitu 60 persen. Data Badan Pengelolaan Utang Yunani, per Maret 2015, menunjukkan beban utang negara itu mencapai 312,7 miliar Euro atau sekitar Rp4.600 triliun alias 174,7 persen di atas GDP.
Kekacauan politik dan ekonomi di Yunani, mengakibatkan deflasi dalam 2 tahun terakhir. Saat ini, deflasi Yunani tercatat sebesar 2,1 persen dan deflasi terendah dalam 3 tahun terakhir tercatat sebesar 2,9 persen pada bulan Februari. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Angka pengangguran di Yunani sebesar 25,6 persen atau sekitar 1,3 juta orang penduduk.
Kondisi Ekonomi Indonesia Satrio Utomo, Kepala Riset Universal
Broker Indonesia, menyatakan krisis Yunani diperkirakan dapat menggangu tren naik jangka pendek yang sedang terjadi pada IHSG. IHSG Fluktuatif bergerak naik dan turun secara tajam merespons perkembangan penanganan krisis Eropa. Data positif soal deflasi Indonesia ternyata tidak cukup untuk memberikan sentimen
Tabel 1. Jangka Waktu Jatuh Tempo Utang YunaniTanggal Jenis Utang Nilai Utang (Juta Euro)
10 Juli 6-month t-bill 200013 Juli Utang IMF 450
14 Juli Surat Utang Pemerintah 85
17 Juli 3-months t-bill 100020 Juli Surat utang yang dipegang ECB 3490
29 Juli Utang ECB 100 Sumber: Bisnis Indonesia
-
- 15 -
positif. Mengawali perdagangan, IHSG langsung melemah dan pelemahan itu terjadi semakin tajam pada hari berikutnya (Tabel 2). Sentimen utamanya adalah anjloknya bursa global merespons hasil referendum Perdana Menteri Yunani.
Tabel 2. Pergerakan IHSGTanggal Penutupan Posisi
7 Juli 2015 4,906.0500 -10
6 Juli 2015 4,916.7410 -66.16
3 Juli 2015 4,982.9100 38.13
2 Juli 2015 4,944.7810 40.72
1 Juli 2015 4,904.0630 6.59sumber: www.duniainvestasi.com
Sementara itu, Alfiansyah, Head Research Valbury Asia Securities, menyatakan pergerakan IHSG yang negatif disebabkan oleh adanya sentimen terhadap kebangkrutan Yunani yang menolak bantuan menjadi faktor utama aksi jual investor. Indonesia memang tidak memiliki hubungan ekonomi langsung yang besar terhadap Yunani. Meskipun begitu, jika krisis tersebut tidak menunjukkan arah perkembangan positif, krisis Yunani dapat memicu krisis di negara-negara di kawasan Eropa lainnya, sehingga sentimen pengaruhnya terhadap keuangan global dapat saja terjadi.
Sebagai gambaran, posisi mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS pasca-referendum mengalami fluktuasi. Sebaliknya, mata uang rupiah justru mengalami penguatan terhadap Euro. Kondisi ini dinilai patut diapresiasi, karena rupiah mampu memperbaiki posisinya di tengah-tengah anjloknya Euro. Namun demikian, menurut Eric Alexander Sugandhi, ekonom senior dari Standard Chartered Bank Indonesia, efek krisis Yunani berdampak temporer dan tidak akan berlangsung lama.
Sedangkan tingkat inflasi sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia sebelumnya, di mana tingkat inflasi pada triwulan I-2015 berada dalam tren menurun. Pada akhir triwulan I-2015, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara triwulanan mencatat deflasi sebesar -0,44% (qtq) atau secara tahunan mencatat inflasi sebesar 6,38% (yoy), menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya yang sebesar 8,36%
(yoy). Dibandingkan triwulan sebelumnya, kelompok volatile food mencatat deflasi pada triwulan I-2015 sejalan dengan meningkatnya pasokan beberapa komoditas pangan. Kelompok administered prices juga mengalami deflasi terutama karena didorong oleh koreksi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta dampak lanjutannya terhadap tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, tekanan inflasi inti terkendali sejalan dengan koreksi harga komoditas global dan perlambatan ekonomi domestik.
Gambar 2. Perkembangan Inflasi Tahunan
Sumber: Bank Indonesia
Dari aspek hutang luar negeri, Laporan
BI menyatakan kondisi Indonesia dalam hal utang luar negeri (ULN) terhadap PDB sebesar 33,5 persen pada triwulan pertama tahun 2014 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 32,96 persen bisa dilihat (Tabel 3). Akhir Maret 2015, posisi ULN terdiri dari ULN sektor publik sebesar 132,8 miliar dolar AS (44,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar 165,3 miliar dolar AS (55,5% dari total ULN). Posisi ULN sektor publik tersebut mengalami kenaikan 2,3% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar 129,7 miliar dolar AS. Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami kenaikan 1,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan IV-2014 yang sebesar 163,4 miliar dolar AS.
-
- 16 -
Tabel 3. Kondisi Utang Luar Negeri terhadap PDB
Tahun Rasio ULN terhadap PDB
2010 26.55
2011 25.03
2012 27.41
2013 29.05
2014 32.96
2015* 33.5Ket: * perkiraan sementarasumber: Bank Indonesia
Mohammad Ikhsan, analisa Ekonom Universitas Indonesia, menyatakan pemerintah harus mewaspadai dampak krisis Yunani di tengah penolakan Yunani terhadap rencana bailout dari sejumlah negara. Hal ini bisa memperparah keadaan ekonomi yang Indonesia yang saat ini sedang menderita krisis kecil. Dampak langsung yang dirasakan bisa minimal, tetapi dampak tidak langsung akan terasa karena investor di seluruh dunia bakal me-review untuk memindahkan asetnya.
Pemerintah juga harus berusaha menahan tingkat inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah jangan sampai menyentuh level Rp14.000 per dolar AS. Langkah ini perlu dilakukan agar dampak krisis eropa khususnya yang dialami Yunani saat ini tidak berdampak besar bagi ekonomi nasional. Pada kenyataannya, ekonomi nasional saat ini sedang dalam kondisi yang rentan. Jika Pemerintah tidak merespons dengan cepat, maka imbas Yunani akan dirasakan oleh Indonesia. Sebab, Indonesia di masa normal saja ekonominya tidak menentu, apalagi ditambah dengan dampak dari dari krisis Yunani.
PenutupKondisi perekonomian Yunani saat ini
banyak dipengaruhi oleh ketidak hati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan. Tingginya utang luar negeri, deflasi, dan nilai tukar uang yang bergerak fluktuatif tetapi dengan kecenderungan menurun, mengakibatkan turunnya kepercayaan pasar. Hal tersebut semakin memberatkan Yunani untuk kembali menjadi negara yang diperhitungkan di kancah percaturan ekonomi di kawasan Eropa.
Kondisi perekonomian Indonesia diyakini lebih baik dan jauh berbeda
dengan kondisi Yunani saat ini. Namun demikian, pemerintah harus belajar dari kondisi krisis yang dihadapi Yunani saat ini. Sebagai contoh, pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk dapat merevisi tingkat pertumbuhan ekonomi ke angka yang lebih realistis dalam rangka menjaga kepercayaan pasar Selain itu, DPR RI dan pemerintah pun harus bersinergi untuk dapat lebih menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Sebaliknya, dalam mengawal momentum ini, DPR RI bisa segera mengesahkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai dasar hukum mitigasi krisis. Dengan demikian, upaya menjaga momentum ketahanan ekonomi nasional akan semakin kuat.
ReferensiEfek Yunani Sudah Diantisipasi, Bisnis
Indonesia, 7 Juli 2015.Dampak Yunani Jangka Pendek, Kompas,
7 Juli 2015.Meski Indonesia Belum Seperti Yunani,
Rupiah Merosot Ancam Perekonomian, Neraca, 6 Juli 2015.
Yanis Varoufakis Mundur, Media Indonesia, 7 Juli 2015.
Krisis Yunani Bikin Panik Investor Pasar Modal, Neraca, 7 Juli 2015.
Indonesia Jauh Beda Dengan Yunani, https://suaratiga.com/2015/07/rasio-utang-indonesia-jauh-beda-dengan-yunani/, diakses 6 Juli 2015.
Lain Yunani Lain Indonesia, h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m /read/2015/07/06/144191/lain-yunani-lain-indonesia, diakses 6 Juli 2015.
Krisis Yunani Ekonomi Indonesia Lebih Sehat Ini Sebabnya, h t t p : / / b i s n i s . t e m p o . c o / r e a d /news/2015/07/06/092681344/krisis-yunani-ekonomi-indonesia-lebih-sehat-ini-sebabnya, diakses 7 Juli 2015.
Goverment Debt to GDP, http://www.t r a d i n g e c o n o m i c s . c o m / g r e e c e /government-debt-to-gdp, diakses 7 Juli 2015.
Euro Tertekan Jelang Rapat Eurogrup, h t t p : / / w w w . s e p u t a r f o r e x .c o m / b e r i t a / f o r e x / d e t a i l .php?nid=239135&title=euro_tertekan_jelang_rapat_eurogroup
-
- 17 -
Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351
Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis
POLITIK RESHUFFLE KABINET DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL
Prayudi*)
Abstrak
Isu politik reshuffle kabinet tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap Presiden terpilih dalam ketika menjalankan pemerintahannya. Ruang keterlibatan publik yang luas dalam menyokong kesuksesan setiap pasangan capres dan cawapres, bahkan lintas partai dan organisasi non-kepartaian, memaksa presiden terpilih mempertimbangkan untuk mengakomodasi banyak kalangan dalam tahap proses penyusunan dan pengoperasian mesin kabinet, hingga ketika memasuki tahap evaluasi atas capaian kinerjanya. Tuntutan yang sedemikian tinggi menyebabkan pertimbangan atas penguatan basis politik partai sebagai seleksi kader calon pemimpin dan penuntasan agenda RUU tentang kepresidenan menjadi semakin penting bagi substansi penguatan sistem presidensial.
PendahuluanIsu politik reshuffle kabinet selalu
membayangi pemerintahan sekarang yang tidak saja dikaitkan dengan ukuran obyektif mengenai kinerja kabinet tetapi juga sangat berkaitan dengan masalah subyektif politik bagi-bagi kekuasaan. Interaksi antar-kedua sisi isu politik reshuffle tersebut semakin memanas, setelah Mendagri Tjahjo Kumulo menuding adanya menteri yang tidak loyal pada presiden setelah beredarnya transkrip ucapan salah satu menteri yang dituding tidak loyal dimaksud. Isu politik ini selalu bersifat dinamis, sebagaimana ditunjukkan dengan rencana reshuffle kabinet yang semula diisyaratkan sebelum lebaran, ternyata akan dilakukan setelah lebaran. Isu
reshuffle selalu diletakkan dalam harapan publik agar kinerja kabinet lebih baik. Jajak pendapat merupakan salah satu tekanan dari keinginan publik tersebut.
Isu politik reshuffle kabinet telah memantik perdebatan tentang penguatan sistem presidensial. Artinya, dasar-dasar pertimbangan untuk melakukan langkah reshuffle atau tidak harus sesuai dengan kewenangan prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 di Pasal 17 mengenai keberadaan status para menteri sebagai pembantu presiden, yang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di bawah kewenangan prerogratif presiden.
*) Peneliti Utama Politik Pemerintahan Indonesia, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E mail: [email protected].
-
- 18 -
Penegasan atas posisi kewenangan prerogatif presiden ini juga dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan begitu, reshuffle kabinet dalam sistem presidensial, semakin tampak makna politiknya yaitu pada konteks pengisian dan penggantian personel kabinet tersebut. Meskipun dalam hal perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian tertentu sesuai pembidangan urusannya, parlemen memiliki kewenangan pula untuk mempengaruhinya. Hal ini melalui klausul adanya pertimbangan DPR sebelum presiden melakukan pengubahan dan pembubaran suatu kementerian.
Penguatan Sistem PresidensialSebagai pemerintahan hasil pemilu
presiden 2014, Kabinet Kerja Jokowi-JK merupakan kombinasi antara unsur profesional (zaken cabinet) dengan kalangan politisi. Meskipun disadari bahwa kombinasi tersebut tidak berada dalam sekat yang kaku karena masing-masing unsur sebenarnya berlaku interaksi tertentu yang dapat bersifat cair. Isu politik reshuffle kabinet pun ketika awal meluncur tidak saja menerpa unsur profesional yang minim (bukan nir sama sekali) secara politik, tetapi juga menerpa kalangan partisan politik partai. Konsekuensi atas terpaan isu politik reshuffle dianggap dapat tertuju pada kapasitas figur presiden secara personal dalam mengelola desakan untuk mengganti atau sekedar menggeser menterinya ke posisi lain di pemerintahan. Konsekuensi demikian sangat terkait dengan keperluan untuk melakukan penguatan sistem presidensial yang tidak lagi terlampau dominan oleh cita rasa parlementer secara berlebihan. Itu sebabnya, dapat dipahami ketika muncul isu tuduhan atas keraguan loyalitas menteri tertentu, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengingatkan pihak lain untuk tidak mencoba mengusik para menterinya dalam bekerja.
Arend Lipjhart menyebutkan karakteristik dan sekaligus perbedaan utamanya dengan kabinet parlementer bahwa kabinet presidensial, ketika dirinya hanya membutuhkan dukungan mayoritas pihak legislatif hanya terkait usulan kebijakannya, dipilih untuk
memiliki kurun waktu masa jabatan yang pasti dan tidak tergantung pada (mosi) kepercayaan dari parlemen dalam menjalankan kekuasaannya. Hal lain yang berbeda adalah, kabinet presidensial lebih mengacu pada presiden secara tunggal (one person executive), atau bukan merupakan kabinet bersifat kolegial (collegial cabinet) yang dianut oleh sistem parlementer. Beberapa karakteristik sistem presidensial ini jelas menegaskan bahwa kemampuan presiden secara personal dalam mengelola kabinet akan sangat penting bagi pembentukan sistem pemerintahan yang stabil. Masalahnya, di Indonesia, cottail effect pemilih yang tidak sejalan saat pilpres dan pileg dari partai politik yang didukungnya, membuka ruang bagi terjadinya paradoks karakter partai atau gabungan partai pendukung pasangan kandidat pilpres dengan sang presiden. Karakter ini dibandingkan dengan hasil pileg yang menghasilkan pembelahan parlemen berdasarkan kubu partai pemerintah dan partai oposisi yang relatif jelas. Padahal, J. Mark Pye, dkk (2002) menekankan pentingnya kesejalanan cottail effect antara dukungan partai saat pemilu sangat berdampak pada kemampuan memerintah (democratic governability) pada saat kabinet sudah terbentuk.
Realitas Politik Kepartaian dan Penerapan Ukuran Kinerja
Realitas politik komposisi kekuatan partai di parlemen memiliki arti penting bagi penilaian presiden terhadap kabinetnya. Apalagi dengan konstelasi politik awal hasil pemilu 2014 di DPR yang sempat terbelah antara dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di satu sisi dan Koalisi Merah Putih (KMP) di sisi lain, maka penilaian atas kabinet jelas memperhitungkan konstelasi parlemen dimaksud. Penilaian ini tetap menjadi dasar, meskipun pro-kontra selalu menyertai keperluan presiden bagi perlu tidaknya menggerakkan perluasan spektrum dukungan politik partai bagi kabinetnya. Apalagi, penilaian itu sejalan dengan kesadaran mengenai kelemahan sistem presidensial yang berhadapan dengan sistem kepartaian yang plural, tampaknya semakin menghinggapi publik. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, perolehan kursi partai-partai di DPR 2014-2019, cenderung tidak terdapat
-
- 19 -
partai dengan kekuatan mayoritas, tetapi cenderung mendorong pada arah koalisi antar-mereka dalam menyikapi isu atau rencana kebijakan yang dibahas.
Tabel 1. Peta Politik DPR Hasil Pemilu 2014
No Partai Politik Jumlah kursi %
1 PDI Perjuangan 109 19,52 Partai Golkar 91 16,33 Partai Gerindra 73 13,04 Partai Demokrat 61 10,95 Partai Amanat Nasional 49 8,86 PKB 47 8,47 Partai Keadilan Sejahtera 40 7,18 PPP 39 7,09 Partai Nasdem 35 6,3
10 Partai Hanura 16 2,9Sumber: SK Nomor 416/kpts/KPU/2014 tentang
Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu 2014.
Kesadaran dukungan politik subjektif partai bagi presiden terpillih hasil pemilu, dituntut seimbang ketika ukuran kinerja kabinet secara obyektif juga penting diterapkan. Masalahnya, penerapan ukuran obyektif kinerja demikian belum tentu berjalan paralel dengan proses penyusunan komposisi kabinet itu ketika awal penyusunannya. Situasi awalnya sempat dinilai tidak baik walaupun pada akhirnya presiden menetapkan RPJMN 2015-2020. Bagaimana mencerna dan menjabarkan RPJMN yang diharapkan sebagai pengejawantahan Nawacita dalam program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu di sinilah persoalannya. Dikhawatirkan hal itu belum dikuasai, terutama oleh beberapa atau bahkan kebanyakan menteri kabinet. Diduga, bukannya beranjak dari tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan terlebih dahulu, melainkan dari organisasi. Sehingga, organisasi dengan pilihan orang-orang yang sebagian besar bahkan belum mengenali apa tujuan, sasaran, dan kerja yang harus mereka lakukan. Meskipun asumsi ini bisa dibantah dalam batas tertentu, karena beberapa di antaranya adalah anggota tim sukses sang presiden saat pemilu. Artinya, keterlibatan aktifnya menyusun platform
kampanye saat pemilu, mereka sudah pasti paham betul apa visi dan misi yang akan dibawakan sang presiden. Model bantahan terbatas ini belum dipertimbangkan variabel eksternal tekanan global.
Penerapan ukuran kinerja kabinet mengalami situasi yang klise saat transisi pemerintahan terjadi, meskipun Indonesia tidak mengenal politik eksekutif lame duck, sebagai konsekuensi politik aji umpung mengejar target sektoral. Situasi klise ini terjadi pada saat politik rezim berubah dengan segala visi, misi dan program pemerintahannya. Hingga saat ini serapan anggaran di beberapa kementerian masih rendah, akibat terhambat oleh perubahan nomenklatur dan persoalan administratif. Penyerapan anggaran kementerian dan lembaga hingga Juni 2015 mencapai 35 persen atau Rp640 triliun. Padahal, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang digunakan presiden dalam menilai kinerja menteri dan kementerian. Kasus rendahnya serapan anggaran di Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal sangat jelas mencerminkan kendala transisi organisasi kabinet dan birokrasi pemerintahan itu. Dorongan kinerja dengan segala evaluasi yang dilakukan pemerintah melalui kelembagaan ekstra sekalipun sebagaimana ditawarkan melalui kementerian super ala Kantor Staf Presiden, tidak sejalan dengan kendala teknis kementerian dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masa transisi politik rezim. Fungsi-fungsi ekstra kabinet yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana dimuat di Perpres No. 6 Tahun 2015 sebatas menjadi masukan bagi presiden atas realisasi program prioritas nasional. Langkahnya tidak menjangkau eksekusi dalam rangka mengurangi bottleneck atau bahkan dapat terjebak perangkap duplikasi otoritas.
Kasus Jokowi dengan isu reshuffle kabinetnya, berada pada dilema persaingan internal dan antar-pihak, yaitu di tim sukses relawan di satu sisi dengan kalangan partai pendukung di pihak lain. Masing-masing pihak seperti warna faksi-faksinya. Dua aspek keseimbangan kabinet yang belum dicapai sebelum satu tahun kabinet, menyebabkan isu politik reshuffle selalu menghantui pemerintah. Parahnya, sering
-
- 20 -
sejarah kelam hantu isu reshuffle juga dikait-kaitkan dengan ancaman mosi tidak percaya DPR melalui hak menyatakan pendapat dan memorandum MPR yang justru bertentangan dengan karakteristik fix term eksekutif sistem presidensial. Konstruksi kepartaian yang belum tertata rapi sebagai basis seleksi kader secara demokratis, juga menjadi faktor pemicu lahirnya paradoks sikap partai pendukung presiden terpilih dibandingkan kalangan partai oposisi saat pemerintahan hasil pemilu mulai berjalan. Rangkaian irasionalitas pengaitan isu reshuffle semacam tadi memperoleh ruang luas, karena detail kelembagaan kepresidenan tidak diatur dalam UU tersendiri. Padahal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi jelas memerlukan penjabaran lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban personal, struktur organisasi beserta relasi kewenangan presiden dengan kelembagaan negara lainnya dalam aturan setingkat UU.
Draf RUU Kepresidenan sendiri pernah disusun di awal tugas masa DPR 1999-2004. Bahkan, catatan draf RUU Kepresidenan yang kemudian bermetamorfosis menjadi RUU Lembaga Kepresidenan di masing-masing era pemerintahan presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Sukarnoputeri, menunjukkan bahwa RUU tersebut tidak pernah dibahas, walaupun sempat masuk daftar Prolegnas. Fenomena politik tarik-menarik kepentingan dan perdebatan substansi yang perlu di atur di dalamnya, menjadi kendala tersendiri. Padahal, UU Kepresidenan penting bagi penguatan sistem presidensial, dan nilainya tidak kalah strategis dibandingkan langkah kompleks pengaturannya di tingkat kebijakan UU Pemilu terkait agenda pemilu serentak.
PenutupIsu politik reshuffle kabinet
tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap presiden terpilih sekaligus berpotensi mengganggu sistem presidensial selama ini. Karena itu, penguatan sistem presidensial perlu ditegaskan kembali pada dua aras politik yang saling berkaitan basis politiknya. Pertama, membenahi basis kepartaian sebagai instrumen demokrasi dalam seleksi para kader dan
calon pemimpinnya. Kedua, pengagendaan penuntasan RUU Kepresidenan sebagai UU yang isinya disinergikan dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara guna penguatan sistem kabinet secara presidensial. Terlepas dari gagasan pemilu serentak, melalui kedua aras politik ini yang perlu diagendakan segera sebagai langkah pembenahan politik sistem presidensial. Dengan demikian, keperluan untuk melakukan penguatan sistem presidensial yang tidak lagi terlampau didominasi gaya sistem parlementer dapat menjadi lebih mudah dilakukan.
ReferensiReshuffle Fokus ke Menteri Ekonomi,
Media Indonesia, 30 Juni 2015.Presiden Isyaratkan Reshuffle, Kompas, 30
Juni 2015.Bambang Kesowo, Efektivitas Perombakan
Kabinet, Kompas, 2 Juli 2015.Arend Lipjhart, Pattern of Democracy:
Government Form and Performance in Thirty Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, 1999, h. 104.
J. Mark Pyne, et.al (2002), Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, John Hopkins University Press, Washington DC, h. 65-66.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Rapor Merah Karena Serapan Rendah, Koran Tempo, 3 Juli 2015.
RUU Lembaga Kepresidenan: Tiga Presiden Tak Juga Selesai, http:/www.unisosdem.org., diunduh 6 Juli 2015.