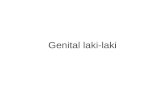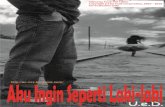UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM ...repository.usd.ac.id/31726/2/144114016_full.pdfHampatokng :...
Transcript of UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM ...repository.usd.ac.id/31726/2/144114016_full.pdfHampatokng :...

UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM NOVEL NGAYAU
KARYA MASRI SAREB PUTRA
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
Maria Fransiska
NIM: 144114016
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Juni 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i
UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM NOVEL NGAYAU
KARYA MASRI SAREB PUTRA
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
Maria Fransiska
NIM: 144114016
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Juni 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

iv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

v
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

vi
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk
Bapak Antonius Pendi
Ibu Sesilia
Abang Trudis Joni
Kakek Silvanus Lorensius Anyim (Alm), Tumenggung Panco Benuo
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

vii
MOTO
Jika Anda menyerah satu kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jangan
pernah menyerah! (Michael Jordan)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

viii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Unsur Budaya Dayak dan Tionghoa dalam Novel Ngayau karya Masri Sareb
Putra” ini dengan lancar.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak
yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima
kasih kepada beberapa pihak.
Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yoseph Yapi
Taum, M.Hum sebagai pembimbing I dan S. E Peni Adji, S.S., M.Hum sebagai
pembimbing II yang telah membantu dalam penulis skripsi ini. Dorongan dan
semangat yang disampaikan sangat memotivasi agar skripsi ini dapat selesai tepat
waktu.
Kedua, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen Sastra
Indonesia, Universitas Sanata Dharma (USD), terutama kepada Prof. Dr.
Praptomo Baryadi, M. Hum yang menjadi Dosen Pembimbing Akademik
Angkatan 2014. Terima kasih atas waktu dan tenaga yeng telah diberikan kepada
penulis. Nasihat dan dukungan yang selalu mendorong penulis supaya bekerja
keras. Terima kasih juga kepada Sony Christian Sudarsono, S.S., M.A. selaku
Wakil Program Studi Sastra Indonesia USD, Drs. B. Rahmanto, M.Hum., dan
Maria Magdalena Sinta Wardani, S.S., M.A., yang telah bersedia membagi
ilmunya selama saya menjalani studi di Program Studi Sastra Indonesia; juga
kepada Staf Sekretariat Fakultas Sastra khususnya Program Studi Sastra Indonesia
atas pelayanan yang baik selama ini.
Ketiga, ucapan terima kasih untuk kedua orang tua, Bapak Antonius Pendi
dan Ibu Sesilia yang selalu memberi dukungan dalam segi finansial maupun
psikologis. Terima kasih juga kepada Kakek Silvanus Lorensius Anyim (alm),
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ix
Tumenggung Panco Benuo yang semasa hidupnya selalu memotivasi dan selalu
mengingatkan kepada anak dan cucunya agar menjaga adat istiadat suku Dayak di
mana pun berada.
Keempat, kepada seluruh rekan-rekan Program Studi Sastra Indonesia
Angkatan 2014. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama kita menjadi
mahasiswa di USD.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
memberikan dukungan, sumbangan, dan bantuan dalam bentuk apapun kepada
penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penelitian ini dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini
dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu Sastra Indonesia.
Yogyakarta, 19 Juni 2018
Penulis
Maria Fransiska
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

x
ABSTRAK
Fransiska, Maria. 2018. Unsur Budaya Dayak dan Tionghoa dalam Novel
Ngayau Karya Masri Sareb Putra. Skripsi. Yogyakarta: Sastra
Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini menganalisis unsur Budaya Dayak dan Tionghoa dalam
Novel Ngayau karya Masri Sareb Putra”. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mendeskripsikan struktur pembangun cerita yang mencakup tentang tokoh,
penokohan, dan latar dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra dan (2)
mendeskripsikan unsur budaya Dayak dan Tionghoa yang terdapat dalam novel
Ngayau karya Masri Sareb Putra.
Dalam menganalisis struktur pembangun cerita, menggunakan kajian
struktural. Analisis unsur budaya menggunakan teori unsur kebudayaan menurut
Koentjaraningrat. Penelitian ini menggunakan paradigma M.H Abrams yaitu
pendekatan objektif dan pendekatan mimetik. Dalam penelitian ini, metode
pengumpulan data yang dipakai adalah metode studi pustaka, metode analisis data
menggunakan metode analisis konten/isi, dan metode penyajian analisis data
menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil analisis struktur pembangun cerita novel Ngayau karya Masri Sareb
Putra. Tokoh utama adalah Lansau dan Siat Mei. Sedangkan, tokoh tambahan
terdiri dari A pa Mei, A kong Mei, Ahong, Sinfu, Sin Sang, Kek Longa, Domia,
dan Domamakng Bunso. Dalam menganalisis latar, peneliti membagi unsur latar
menjadi tiga bagian yaitu, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Latar
waktu yang dominan adalah tahun 1967 saat Peristiwa Mangkok Merah dan
tahun 1999 saat kerusuhan antaretnis pendatang di Kalimantan Barat. Latar tempat
yang paling dominan adalah negeri Poromuan. Latar sosial budaya yang meliputi
cara hidup, makanan, dan bahasa. Dalam penelitian ini ditemukan enam unsur-
unsur budaya Dayak yaitu: (1) Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Dayak
Kanayatn dan Bahasa Dayak Djongkang (Djo). (2) Sistem pengetahuan yang
meliputi membaca musim, pengetahuan pengetahuan alam flora, dan sistem
pengetahuan adat-istiadat. (3) Sistem peralatan dan teknologi yang meliputi
senjata, tempat berlindung, perumahan, alat produksi, dan makanan. (4) Sistem
mata pencaharian hidup yang meliputi berburu, berladang, dan kerja tambang. (5)
Sistem religi yang meliputi kepercayaan animisme dan dinamisme, dan (6)
kesenian yang meliputi benda lama yang masih digunakan, kesusteraan berupa
mantra-mantra, cerita rakyat dan lagu daerah. Sedangkan, unsur-unsur budaya
Tionghoa terdapat empat unsur yaitu: (1) Bahasa yang meliputi bahasa Tio Ciu,
dialek hakka. (2) Sistem pengetahuan ruang dan waktu yaitu menentukan tanggal
perayaan Ceng Beng. (3) Sistem peralatan dan teknologi yang meliputi makanan
khas Tionghoa yaitu Kwee Cap. (4) Sistem mata pencaharian hidup etnis
Tionghoa yang meliputi berkebun, pasar terapung, berdagang, dan kerja tambang,
dan (4) Sistem religi Tionghoa yaitu konfusianisme.
Kata Kunci : Unsur, Budaya, Dayak, Tionghoa, Ngayau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xi
ABSTRACT
Fransiska, Maria. 2018. Cultural Elements Dayak and Tionghoa in Novel
Ngayau written by Masri Sareb Putra. An Undergraduate Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Literature Study Program, Department of
Indonesian Letters, Faculty of Letters, Sanata Dharma University.
This study is based on the elements of Dayak Culture and Tionghoa in
Ngayau written by Masri Sareb Putra. This study aims to (1) describing the
structure constructing the story including characters, characterizations, and setting
in Ngayau written by Masri Sareb Putra, and (2) describing the Dayak and
Tionghoa’s Cultural elements in Ngayau written by Masri Sareb Putra.
In analyzing the structure constructing the story, structural study was
used. Analysis of cultural elements using the theory of cultural elements based on
Koentjaraningrat. The paradigm of this study is based on M.H Abrams, which is
objective and mimetic approach. In this study, the research applied data collection
method as literature study method, data analysis method using content analysis
method/content, and method of data analysis using qualitative description method.
The result of structure constructing analysis the story analysis in Ngayau
by written by Masri Sareb Putra. The main characters are Lansau and Siat Mei.
While, the additional characters were A pa Mei, A kong Mei, Ahong, Sinfu, Sin
Sang, Kek Longa, Domia, and Domamakng Bunso. In analyzing the background,
the writer classified the elements of setting into three parts, which were setting of
time, setting of place, and socio-cultural setting. The setting of time dominant
was in 1967 during the RedBowl Flood and in 1999 during interracial inter-ethnic
riots in West Kalimantan. The setting of place dominant is Poromuan country.
Socio-cultural background that includes way of life, food, and language. In this
study found six elements of Dayak culture are: (1) The language used is Dayak
Kanayatn and Dayak Djongkang (Djo). (2) A system of knowledge which
includes season reading, knowledge of natural flora knowledge, and knowledge
systems of customs. (3) Equipment and technology systems including weapons,
shelter, housing, production equipment, and food. (4) Livelihood systems that
include hunting, farming, and mine work. (5) Religious systems that include
animism and dynamism, and (6) art that includes old objects still used, literature
of mantras, folklore and regional songs. Meanwhile, the elements of Tionghoa
culture there are four elements: (1) Languages that include the language Tio Ciu,
hakka dialect. (2) The system of knowledge of space and time is to determine the
date of celebration of Ceng Beng. (3) Equipment and technology system that
includes typical Tionghoa food that is Kwee Cap. (4) The livelihood system of
Tionghoa life that includes gardening, floating market, trading, and mining work,
and (4) Tionghoa religious system is Confucianism.
Keywords: Cultural Elements, Dayak, Tionghoa, Ngayau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xii
DAFTAR ISTILAH
Abuh : Perapian tempat memasak
A kong : Kakek
A me : Ibu
A moi : Sapaan anak perempuan
A pa : Bapak
Atok : Takdir
Babae : Manusia yang sudah bosan hidup di bumi.
Baju : orang yang mempunyai ilmu atau kekebalan untuk melindungi
diri
Belantik : perangkap
Bikas : Busur yang terlepas
Bolopas : Melahirkan bayi
Bopacu : memberikan bekal atau nasihat kepada kedua mempelai
Boraupm : Berkumpul dan melakukan musyawarah saat akan me-ngayau dan
mendirikan betang
Bubu : Perangkap ikan terbuat dari bambu
Chang Fu : Istri
Ceng Beng : Sembahyang kubur
Hampatokng : Patung kayu
Jubata : Tuhan
Ka kon : Mertua laki-laki
Kasikng : Berupa duri, pecahan bambu, kayu, atau benda apa saja yang bisa
melukai dan tertinggal di badan seseorang.
Kolayak : Tikar terbuat dari anyaman rotan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xiii
Ku chong : Paman
Lawakng : Pintu
Lo pho : Istri
Lo thai sim : Abang ipar
Lotos : Pelita
Moici : Anak perempuan
Ngabas Poya : Melihat atau mengamati lahan atau tanah yang akan
menjadi area perladangan
Ngadoh : Membantu persalinan seorang ibu yang melahirkan
Ngayau : Tradisi memenggal kepala
Ngansu : Sumpit
Ngimpak : Senjata laras
Nugal : Menanam padi
Pantak : Patung dari kayu
Polopas : Tradisi menyentuh makanan dengan ujung jari
Pongamik : Bentuknya seperti ransel, terbuat dari anyaman rotan dan
kulit kayu. Talinya dari kulit kayu yang kuat.
Pongaretn : pemakaman umum yang sudah tidak terpakai lagi.
Puaka : Sesuatu, benda, atau peninggalan berharga milik bersama
yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara.
Saor : jaring kecil
Tajau : wadah untuk menyimpan pati tuak.
Tajor : Mata kail
Tariu : Upacara memanggil ruh leluhur
Tepekong : Kuil
Thaiko : abang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xiv
Tikak : Semacam tas pinggang yang terbuat dari kulit kayu,
tempat menyimpan alat-alat perlengkapan berburu.
Tonok : Bambu muda
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .........................................................Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .............Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .......................Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..........................Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ................ Error!
Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................... Error! Bookmark not defined.i
MOTO .................................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ................................................................................................... viii
ABSTRAK ........................................................................................................................ x
ABSTRACT ........................................................................................................................ xi
DAFTAR ISTILAH ........................................................................................................ xii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 5
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 6
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................ 6
1.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................................ 6
1.4.2 Manfaat Praktis ......................................................................... 6
1.5 Tinjauan Pustaka .............................................................................. 6
1.6 Kerangka Teori ................................................................................. 7
1.6.1 Pendekatan Objektif dan Kajian Struktural .............................. 9
1.6.1.1 Tokoh ................................................................................... 10
1.6.1.2 Tokoh Berdasarkan Peranan ................................................ 10
(1) Tokoh Utama .............................................................................. 10
(2) Tokoh Tambahan ....................................................................... 11
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xvi
1.6.1.3 Penokohan ............................................................................ 11
1.6.1.4 Latar ..................................................................................... 11
(1) Latar Tempat .............................................................................. 12
(2) Latar Waktu ................................................................................ 13
(3) Latar Sosial-Budaya ................................................................... 13
1.6.2 Pendekatan Mimetik ............................................................... 14
1.6.3 Sosiologi Sastra ....................................................................... 14
1.6.4 Teori Unsur-Unsur Kebudayaan Menurut Koentjaraningrat .. 16
1.6.4.1 Bahasa .................................................................................. 17
1.6.4.2 Sistem Pengetahuan ............................................................. 18
1.6.4.3 Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan ............................... 19
1.6.4.4 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi ............................... 20
1.6.4.5 Sistem Mata Pencaharian Hidup .......................................... 20
1.6.4.6 Sistem Religi ........................................................................ 20
1.6.4.7 Kesenian ............................................................................... 21
1.7 Metode Penelitian ........................................................................... 21
1.7.1 Jenis Penelitian ....................................................................... 22
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 23
1.7.3 Teknik Analisis Data .............................................................. 23
1.7.4 Teknik Penyajian Analisis Data .............................................. 24
1.8 Sistematika Penyajian ..................................................................... 25
BAB II STRUKTUR CERITA DALAM NOVEL NGAYAU KARYA
MASRI SAREB PUTRA
2.1 Pengantar ........................................................................................ 26
2.2 Tokoh dan Penokohan .................................................................... 26
2.2.1 Tokoh Utama .......................................................................... 27
2.2.1.1 Lansau .................................................................................. 27
2.2.1.2 Siat Mei ................................................................................ 30
2.2.2 Tokoh Tambahan .................................................................... 32
2.2.2.1 A pa Mei ............................................................................... 33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xvii
2.2.2.3 Ben Teng .............................................................................. 34
2.2.2.5 A kong Mei ........................................................................... 35
2.2.2.4 Ahong ................................................................................... 35
2.2.2.6 Sinfu ..................................................................................... 37
2.2.2.7 Sin Sang ............................................................................... 38
2.2.2.8 Kek Longa ............................................................................ 39
2.2.2.9 Domia ................................................................................... 40
2.2.2.10 Domamakng Bunso ............................................................ 41
2.3 Latar ................................................................................................ 42
2.3.1 Latar Waktu ............................................................................ 42
2.3.1.1 Tahun 1967 .......................................................................... 43
2.3.1.2 Tahun 1999 .......................................................................... 44
2.3.2 Latar Tempat ........................................................................... 45
(1) Negeri Poromuan ....................................................................... 45
(2) Rumah Mei ................................................................................. 46
(3) Hutan .......................................................................................... 47
2.3.3 Latar Sosial-Budaya ................................................................ 47
2.4 Rangkuman ..................................................................................... 49
BAB III UNSUR-UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM
NOVEL NGAYAU KARYA MASRI SAREB PUTRA
3.1 Pengantar ........................................................................................ 51
3.2 Unsur-Unsur Budaya Dayak dalam novel Ngayau Karya Masri
Sareb Putra..................................................................................... 51
3.2.1 Bahasa ..................................................................................... 52
3.2.2 Sistem Pengetahuan ...................................................................... 58
3.2.2.1 Membaca Musim ....................................................................... 58
3.2.2.2 Sistem Pengetahuan Alam Flora ............................................. 59
(1) Daun Sabang Merah ......................................................................... 59
3.2.2.3 Sistem Pengetahuan Adat-istiadat ........................................... 60
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xviii
3.2.3 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi ..................................... 62
3.2.3.1 Senjata ......................................................................................... 62
3.2.3.2 Tempat Berlindung .................................................................... 63
3.2.3.3 Perumahan .................................................................................. 64
3.2.3.4 Alat Produksi ............................................................................. 65
3.2.3.5 Makanan ..................................................................................... 66
3.2.4. Sistem Mata Pencaharian Hidup ............................................... 67
(1) Berburu .............................................................................................. 67
(2) Berladang .......................................................................................... 67
(3) Kerja Tambang ................................................................................. 70
3.2.5 Sistem Religi ................................................................................. 70
3.2.6 Kesenian ......................................................................................... 71
3.2.6.1 Benda-benda Lama yang Masih Digunakan .......................... 72
3.2.6.2 Kesusasteraan............................................................................ 72
(1) Mantra saat Tariu ............................................................................. 72
(2) Mantra Nosu Minu (Menyerukan semangat/jiwa) ........................ 73
(3) Mantra Sokutuk Sokutokng .............................................................. 74
3.2.6.3 Cerita Rakyat ............................................................................. 74
3.2.6.4 Kisah Asal Usul Padi versi suku Dayak ................................. 75
3.2.6.5 Seni Musik .................................................................................. 76
3.2.6.6 Seni Rupa ................................................................................... 77
3.3 Unsur-unsur Budaya Tionghoa dalam novel Ngayau karya Masri
Sareb Putra ....................................................................................... 78
3.3.1 Bahasa ..................................................................................... 78
3.3.1.1 Sapaan Kekerabatan ............................................................. 79
(1) A kong ......................................................................................... 80
(2) Lo Pho ........................................................................................ 80
(3) A moi .......................................................................................... 80
(4) Moi Ci ......................................................................................... 80
(5) Ka Kon ....................................................................................... 80
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xix
(6) Ku Chong ................................................................................... 81
(7) Thaiko ......................................................................................... 81
(8) Chang Fu .................................................................................... 81
(9) Lo Thai Sim ................................................................................ 81
3.3.1.2 Istilah ................................................................................... 82
3.3.2 Sistem Pengetahuan ............................................................... 82
3.3.3 Sistem Peralatan dan Teknologi ............................................. 83
3.3.4 Sistem Mata Pencaharian Hidup ............................................. 84
(1) Berkebun .................................................................................... 84
(2) Pasar Terapung ........................................................................... 85
(3) Berdagang .................................................................................. 85
(4) Kerja Tambang ........................................................................... 86
3.3.5 Sistem Religi ........................................................................... 87
3.4 Rangkuman ............................................................................................. 87
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ..................................................................................... 89
4.2 Saran ............................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 95
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karya sastra sebagai produk budaya, merupakan institusi sosial. Sebagai
institusi sosial, karya sastra memiliki peran dan fungsi dalam rangka sosialisasi
nilai-nilai pendidikan, kritik sosial, dan penilaian terhadap kenyataan
masyarakatnya (Suhariyadi, 2014: 69). Selain berhubungan dengan masyarakat,
karya sastra juga dapat bersumber dari peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah juga
motivasi seorang pengarang untuk menciptakan karya sastra. Menurut
Kuntowijoyo (2006: 171), objek karya sastra adalah realitas, apa pun dimaksud
dengan realitas oleh pengarang.
Sebagai gambaran tentang bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat,
karya sastra juga dapat dikaji secara mendalam untuk menemukan apa yang
terjadi dalam masyarakat dan selanjutnya dituangkan dalam karya sastra. Jika
membaca cerita fiksi, kita akan bertemu dengan sejumlah tokoh, tempat, waktu,
dan latar belakang sosial budaya di mana cerita itu terjadi, dan lain-lain.
Kesemuanya tampak berjalan serempak dan saling mendukung. Misalnya,
bagaimana tokoh saling berhubungan, berbagai peristiwa saling terkait walaupun
pencitraannya berjauhan, bagaimana latar sosial budaya memfasilitasi dan
membentuk karakter tokoh dan lain-lain. Hal itu semuanya dapat berjalan dengan
baik, cerita dapat dipahami dengan baik, karena ada benang merah yang mengatur
dan menghubungkan semua elemen, yaitu struktur (Nurgiyantoro, 2015: 59).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2
Aspek pendukung karya sastra adalah unsur yang membangun karya sastra
dari luar yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara unsur tersebut yaitu
kondisi masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik pada saat karya
sastra diciptakan. Koentjaraningrat (1990: 203) membagi unsur-unsur kebudayaan
menjadi tujuh unsur, yaitu (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi
sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian
hidup, (6) sistem religi, dan (7) kesenian. Setiap kebudayaan mempunyai unsur
universal misalnya struktur sosial, sistem politik, ekonomi, teknologi, agama,
bahasa, dan sistem komunikasi. Semua unsur dan sistem kebudayaan tersebut
dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya dalam
masyarakat Dayak dan Tionghoa yang juga mengenal beberapa unsur budaya dan
adat istiadat.
Menurut Coomans (1987: 71), nenek moyang penduduk Kukar berasal
dari dataran Asia yang kini disebut dengan propinsi Yunan, China Selatan. Para
nenek moyang ini merupakan kelompok-kelompok kecil pengembara yang
berhasil sampai di Pulau Kalimantan. Namun, masing-masing menempuh rute dan
waktu yang berbeda. Suku Dayak ini dibedakan menjadi dua wilayah, pertama
wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah kedua
adalah Kalimantan Barat, Utara, dan Timur. Pembedaan ini dapat dilihat dari suku
Dayak yang mendiami Kalimantan bagian Utara, yang memiliki budaya dan
sistem imigrasi yang beda dengan mereka yang mendiami Kalimantan bagian
Selatan dan Tengah, imigrasi diperkirakan terjadi pada abad ke-13.
Nenek moyang Lansau juga datang lewat jalur yang sama, berabad-abad sebelumnya. Beda masa migrasi, menyebabkan yang satu dianggap asli,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3
sedangkan yang lainnya dicap sebagai “pendatang” di bumi Borneo yang sama, dari asal yang sama (Putra, 2014: 105).
Golongan Cina yang sudah beradaptasi dengan alam dan budaya di
Kalimantan yaitu golongan ketiga. Mereka sudah tidak tahu asal-usul nenek
moyang. Keluarga Mei dan Thaiko adalah golongan ketiga ini. Migrasi nenek
moyang Lansau dan Mei hanya selang beberapa abad. Akan tetapi, mengapa yang
satu disebut Dayak? Sedangkan yang satunya Tionghoa, bahkan kerap didengar
dengan sebutan Cina yang merupakan sebuah negara. (Putra, 2014: 116).
Ngayau adalah sebuah novel berdasar sejarah karya Masri Sareb Putra.
Novel ini diterbitkan pertama kali pada Maret 2014 oleh Entertainment Essence
Center. Melalui novel tersebut, Masri Sareb Putra menggambarkan bahwa pada
tahun 1967 terjadi sebuah peristiwa besar yang mengakibatkan perang antara
Dayak dan Tionghoa.
Ngayau bercerita tentang seorang pemuda Dayak bernama Lansau dan
gadis keturunan Tionghoa Siat Mei, yang gagal menikah. Pernikahan mereka
dibatalkan oleh A pa Mei dengan alasan bahwa Siat Mei dan Lansau berbeda.
Akan tetapi, Mei tidak mengerti dengan perbedaan yang dimaksud oleh A pa nya.
Ciri-ciri fisik mereka hampir sama. Soal bahasa, mereka sama-sama bisa
menuturkan bahasa Dayak, dialek Khek, dan bahasa Indonesia. Makanan dan
kebiasaan juga sama. Pada saat itu, Ben Teng mendapatkan kabar akan terjadinya
balas dendam karena seorang panglima Dayak ditemukan terbunuh mengenaskan
di sebuah hutan. Beredar kabar bahwa pelakunya warga Tionghoa. Maka balas
dendam menunggu waktu. Kisah Ben Teng tersebut pun didengar oleh A pa Mei.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4
Itulah alasan mengapa ia membatalkan pernikahan anak gadisnya dengan Lansau.
Saat tariu, ruh Panglima Burung merasuk ke dalam tubuh Lansau. Lansau
membawa terbang Mei dan ayahnya untuk menghindari amuk massa yang
dirasuki ruh-ruh leluhur. Mereka pun masuk di ruang penyekapan. Lansau pun
mengisahkan yang sebenarnya terjadi. Massa Dayak diprovokasi untuk menghalau
etnis Tionghoa di pedalaman. Lansau terpaksa menyelamatkan Mei dan
keluarganya seperti penculikan. A pa Mei yang mendengar isu orang Dayak akan
mengusir orang Tionghoa menjadi mafhum. Tujuannya membatalkan perkawinan
putrinya dengan Lansau didasarkan pertimbangan. Ada pihak yang khawatir jika
kedua suku bangsa bersatu maka akan menguasai pulau Borneo.
Karya ini diangkat sebagai objek material penelitian karena dua alasan.
Alasan pertama karena masalah sejarah dari dua etnis, Dayak dan Tionghoa yang
terkandung di dalamnya. Dalam Ngayau, dipaparkan tentang asal nenek moyang
suku Dayak dan Tionghoa yang sama-sama berasal dari daratan Yunan. Di
Singkawang, pendaratan pertama dari Cina secara besar-besaran pada abad ke-13.
Nenek moyang suku Dayak juga melewati jalur yang sama, berabad-abad
sebelumnya. Hanya beda masa migrasi, itulah yang menyebabkan yang satu dicap
pribumi, dan yang lainnya dicap sebagai pendatang.
Alasan kedua, karena suku Dayak Kalimantan yang tetap menjaga
kebudayaan dan tetap menjalankannya di zaman yang sudah modern. Begitu jelas
digambarkan oleh pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat Dayak.
Contohnya, seperti perayaan Nosu Minu Podi, yaitu merupakan suatu upacara
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Jubata (Tuhan) saat masa panen padi telah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5
selesai. Tujuannya adalah sebagai penghormatan kepada roh padi dan memohon
restu untuk keberhasilan di tahun berikutnya.
Novel Ngayau terdiri atas 21 sub bab. Akan tetapi, ceritanya ada yang
terputus. Demikianlah kata “Headhunter” berevolusi dari masa ke masa. Pada
zaman dahulu, dalam setting novel ini, berarti mencari kepala musuh; kemudian
berevolusi ke dunia olahraga menjadi mengumpulkan piala sebagai tanda
kemenangan, dan kini berarti mencari pekerja (karyawan) yang andal. Intinya
sama memburu, mengumpulkan, dan hasilnya adalah tanda kekuatan (Putra, 2014:
188).
Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas dua hal, yaitu struktur novel
Ngayau, serta unsur-unsur kebudayaan dalam novel Ngayau. Struktur novel
Ngayau yang akan dibahas mencakup tokoh, penokohan, dan latar dengan
pendekatan struktural. Kemudian, dilanjutkan dengan teori unsur-unsur
kebudayaan Koentjaraningrat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
1.2.1 Bagaimana struktur cerita dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra?
1.2.2 Bagaimana unsur-unsur kebudayaan Dayak dan Tionghoa dalam novel
Ngayau karya Masri Sareb Putra?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Mendeskripsikan struktur cerita dalam novel Ngayau karya Masri Sareb
Putra. Hal ini akan dibahas dalam Bab II.
1.3.2 Mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan Dayak dan Tionghoa dalam
novel Ngayau karya Masri Sareb Putra. Hal ini akan dibahas dalam Bab
III.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
pengembangan ilmu sastra Indonesia dan teori sastra, khususnya teori sosiologi
sastra.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan apresiasi sastra Indonesia,
khususnya novel berdasar sejarah Ngayau. Penelitian ini juga dapat menjadi
referensi studi sejarah suku Dayak dan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat. Selain
itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian
selanjutnya.
1.5 Tinjauan Pustaka
Peneliti menemukan jurnal yang membahas tentang budaya Ngayau dan
jurnal tentang Peristiwa Mangkok Merah pada tahun 1967 di Kalimantan Barat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7
Masri Sareb Putra merupakan penulis dari novel Ngayau. Dalam artikelnya
yang berjudul “Makna di Balik Teks Dayak Sebagai Etnis Headhunter” pada
tahun 2012 . Dalam pembahasannya, Masri membongkar mitos dengan mencari
hakikat dari sebuah teks atau realitas, dengan mengacu pada sejarah dan tradisi
pada waktu teks itu ditulis. Kemudian, mencari hakikat makna dari teks yang
ditulis para pelancong dan antropolog asing dari abad 18 hingga masa
kemerdekaan.
Dalam tulisannya yang berjudul “Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan
Barat pada tahun 1967”, Superman membahas bagaimana keterlibatan segelintir
masyarakat Cina dalam gerakan politik pada tahun 1963 di Kalimantan Barat yang
terhimpun dalam organisasi PGRS-Paraku yang pada awalnya merupakan gerakan
oposisi untuk melancarkan “Ganyang Malaysia”.
1.6 Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian karya sastra menurut
M.H Abrams.
Dalam empat klasifikasi yang dilakukan oleh Abrams adalah realitas,
pencipta, karya, dan pembaca (1997: 17). Mengenai kritik sastra, Abrams
menjelaskan bahwa kritik sastra memiliki bentuk, metode, orientasi atau dasar
pendekatan kepada karya sastra.
Menurut Taum (2017), dalam reposisi paradigma M.H Abrams, terdapat
enam pendekatan dalam kritik sastra. Abrams memberikan peluang bagi kritik
sastra untuk menggulati aspek-aspek di luar teks, meskipun hal ini dipandang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8
sebagai konteks pemahaman tekstual. Terdapat enam pendekatan kritik sastra
Abrams menurut Taum. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang
menitikberatkan pada karya sastra itu sendiri. Pendekatan mimetik adalah
pendekatan yang menitikberatkan semesta. Pendekatan pragmatik adalah
pendekatan yang menitikberatkan pembaca. Pendekatan ekspresif adalah
pendekatan yang menitikberatkan penulis. Pendekatan eklektik adalah pendekatan
yang menggabungkan secara selektif beberapa pendekatan mimetik. Terakhir,
pendekatan diskursif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada wacana sastra
sebagai sebuah praktik diskursif (Taum, 2017).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yang
dikemukakan oleh Abrams, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan mimetik
sastra. Kedua pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada
karya sastra itu sendiri dan unsur-unsur budaya yang terdapat dalam novel Ngayau
karya Masri Sareb Putra.
Dalam penelitian novel Ngayau, unsur intrinsik yang akan dibahas adalah
tokoh, penokohan, dan latar. Peneliti menganalisis kedua unsur tersebut karena
menunjukkan unsur-unsur kebudayaan Dayak dan Tionghoa. Keseluruhan
tersebut membangun novel Ngayau menjadi karya sastra yang menggambarkan
kehidupan nyata. Dalam penelitian ini juga digunakan teori sosiologi sastra, guna
untuk menganalisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian untuk
memahami lebih dalam lagi gejala sosial yang ada di luar sastra (Damono, 1979:
2-3).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9
1.6.1 Pendekatan Objektif dan Kajian Struktural
Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada karya
sastra itu sendiri (Taum, 1997: 17). Pendekatan ini memfokuskan bagaimana isi
dan pembangun dari sebuah karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif dalam
penelitian ini guna menganalisis struktur pembangun cerita yang mencakup tokoh,
penokohan, dan latar yang terdapat dalam novel Ngayau. Hudayat dalam
Suhariyadi (2014: 60), mengemukakan bahwa pendekatan objektif memusatkan
perhatian semata-mata pada unsur-unsur karya sastra. Pendekatan ini mengarah
pada analisis intrinsik.
Dalam menganalisis struktur pembangun karya sastra, penulis
menggunakan teori struktural. Struktur karya sastra dapat diartikan sebagai
susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi
komponennya secara bersama membentuk kebulatan yang indah. Analisis
struktural karya sastra dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan dengan
mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur
fiksi yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2002: 36-37).
Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni
membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra
dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom
dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal
yang ada di luar karya sastra (Satoto, 1993: 32). Pendekatan struktural mencoba
menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10
kesatuan struktural yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw,
1984: 135)
Peneliti memilih unsur tokoh, penokohan, dan latar karena unsur-unsur
tersebut merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam jalannya cerita. Unsur
tokoh dan penokohan mampu menjelaskan dari segi fisik, perwatakan, dan kondisi
sosial para tokoh dan mampu menjelaskan peran tokoh. Sedangkan, latar
dianalisis untuk mengetahui konteks, waktu, dan sosial-budaya dalam novel
Ngayau.
1.6.1.1 Tokoh
Tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif, atau
drama, oleh pembaca ditafsirkan kualitas moral dan kecenderungan tertentu
seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.
Tokoh menjadi unsur penggerak alur cerita.
1.6.1.2 Tokoh Berdasarkan Peranan
Aminuddin (2004: 79-80) menggolongkan tokoh berdasarkan peranan dan
keseringan pemunculannya, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan.
(1) Tokoh Utama
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu
cerita (Amminuddin, 2004: 79). Menurut Nurgiyantoro (2015: 268) dilihat dari
segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh tersebut tidak sama. Ada tokoh
tergolong penting dan ditampilkan terus menerus sehingga terasa mendominasi
sebagian besar cerita.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11
(2) Tokoh Tambahan
Menurut Aminuddin (2004: 79-80), tokoh yang memiliki peranan yang
tidak penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung
pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Pemunculan tokoh-
tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, dan
kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, baik secara
langsung mau pun tidak langsung (Nurgiyantoro, 2007: 177).
1.6.1.3 Penokohan
Penokohan adalah unsur penting dalam cerita fiksi. penokohan adalah
pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah
cerita. Unsur penokohan menunjuk pada teknik perwujudan dan pengembangan
tokoh dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2015: 248).
1.6.1.4 Latar
Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menunjuk pada
pengertian tempat, hubungan waktu sejarah, dan lingkungan sosial tempat
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams, 1999: 284). Stanton
dalam Nurgiyantoro (2015: 302), mengelompokkan latar bersama tokoh dan plot,
ke dalam fakta (cerita) sebab ketiga hal inilah yang akan dihadapi dan dapat
diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika membaca sebuah fiksi. Atau, ketiga
hal inilah yang secara konkret dan langsung membentuk cerita: tokoh cerita
adalah pelaku dan penderita kejadian-kejadian yang bersebab akibat, dan itu perlu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12
pijakan, di mana, kapan, dan pada kondisi sosial-budaya masyarakat yang
bagaimana.
Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat,
waktu, dan sosial-budaya.
(1) Latar Tempat
Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan
dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa
tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin nama lokasi
tertentu tanpa nama jelas. Latar tempat yang tanpa nama jelas biasanya hanya
berupa penyebutan jenis dan sifat umum tempat-tempat tertentu, misalnya desa,
sungai, jalan, hutan, kota kecamatan, dan sebagainya. Pelukisan tempat tertentu
dengan sifat khasnya secara rinci biasanya menjadi sifat kedaerahan, berupa
pengangkatan suasana daerah, atau warna lokal (local color).
Pengangkatan suasana kedaerahan, sesuatu yang mencerminkan unsur
local color, akan menyebabkan latar tempat menjadi unsur yang dominan dalam
karya yang bersangkutan. Namun, perlu dipertegas bahwa sifat ketipikalan daerah
tidak hanya ditentukan oleh rincinya deskripsi lokasi, melainkan terlebih harus
didukung oleh sifat kehidupan sosial-budaya masyarakat penghuninya
(Nurgiyantoro, 2015: 314-315).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13
(2) Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-
peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra fiksi. Masalah “kapan”
tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya
atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Masalah waktu dalam karya naratif,
Gennete dalam Nurgiyantoro (2015: 318), dapat bermakna ganda: di satu pihak
menunjuk pada waktu penceritaan, waktu penulisan cerita, dan di pihak lain
menunjuk pada waktu dan urutan waktu yang terjadi dan dikisahkan dalam cerita.
Pengangkatan unsur sejarah ke dalam cerita fiksi akan menyebabkan
waktu yang diceritakan menjadi bersifat khas, tipikal, dan dapat menjadi sangat
fungsional sehingga tidak dapat diganti dengan waktu yang lain tanpa
mempengaruhi perkembangan cerita lain (Nurgiyantoro, 2015: 321).
(3) Latar Sosial-Budaya
Latar sosial budaya menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan
perilaku kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya
fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam
lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat,
tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain-lain
yang tergolong latar spiritual seperti dikemukakan sebelumnya. Di samping itu,
latar sosial-budaya juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang
bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas (Nurgiyantoro, 2015: 322).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14
Ketika mengangkat latar tempat tertentu ke dalam cerita fiksi pengarang
perlu menguasai medan, keadaan itu juga terlebih berlaku untuk latar sosial-
budaya. Pengertian penguasaan medan lebih menunjuk pada penguasaan latar.
Jadi, ia mencakup unsur tempat, waktu, dan sosial-budaya sekaligus. Di antara
ketiganya tampaknya unsur sosial-budaya memiliki peranan yang cukup
menonjol. Latar sosial-budaya berperan menentukan apakah sebuah latar.
Khususnya latar tempat, menjadi khas, tipikal, dan fungsional, atau sebaliknya
bersifat netral. Dengan kata lain, untuk menjadi tipikal dan lebih fungsional,
deskripsi latar tempat harus sekaligus disertai deskripsi latar sosial-budaya,
tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di tempat yang bersangkutan
(Nurgiyantoro, 2015: 322-323).
1.6.2 Pendekatan Mimetik
Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengutamakan aspek
semesta (Taum, 1997: 17). Pendekatan mimetik dalam penelitian ini guna
menjelaskan tentang teori sosiologi sastra dan teori unsur-unsur kebudayaan
menurut Koentjaraningrat dalam menganalisis novel Ngayau dalam penelitian ini.
Dengan pendekatan mimetik, dapat ditemukan adanya unsur-unsur kebudayaan
Dayak dan Tionghoa dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra.
1.6.3 Sosiologi Sastra
Pendekatan sosiologi sastra yang banyak dilakukan saat ini menaruh
perhatian yang besar terhadap aspek dokumenter sosial. Landasannya adalah
gagasan bahwa karya sastra merupakan cermin zamannya. Pandangan ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15
beranggapan bahwa karya sastra merupakan cermin langsung dari pelbagai segi
struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-lain. Dalam
hal ini tugas ahli sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman tokoh-tokoh
khayali dan situasi-situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah yang
merupakan asal-usulnya. Tema dan gaya hidup yang ada dalam karya sastra yang
bersifat pribadi itu, harus diubah menjadi hal-hal yang sosial sifatnya (Saraswati,
2003: 4).
. Pendekatan sosiologi sastra dalam penelitian sastra bertolak dari pandangan
bahwa sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat (Semi, 1989: 46).
Pendekatan sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini oleh
beberapa ahli sosiologi sastra. Istilah itu pada dasarnya tidak berbeda
pengertiannya dengan sosiosastra, pendekatan sosiologis, atau pendekatan
sosiokultural terhadap sastra (Damono, 1979: 2). Manusia dalam kehidupannya,
tidak akan terlepas dari kebudayaan karena manusia adalah pencipta sekaligus
pengguna dari kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan
dan budaya tersebut akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau
melestarikan kebudayaan. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin jika tidak
berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan (Soemardjan, 1964: 155).
Ritzer (dalam Faruk, 1994: 2) menganggap sosiologi sastra sebagai sesuatu
ilmu pengetahuan yang multiparadigma. Maksudnya, di dalam ilmu tersebut
dijumpai beberapa paradigma yang saling bersaing satu sama lain dalam usaha
merebut hegemoni dalam lapangan sosiologi sastra secara keseluruhan. Ada tiga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16
paradigma yang Ritzer temukan ialah paradigma fakta-fakta sosial, paradigma
definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial.
1.6.4 Teori Unsur-Unsur Kebudayaan Menurut Koentjaraningrat
Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan
milik dari manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 153). Hal tersebut
berarti bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya
sedikit kegiatan manusia yang tanpa belajar, Hal itu disebut tindakan naluri,
refleks, dan sebagainya. Kemampuan manusia dapat mengembangkan konsep-
konsep yang ada dalam kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari
kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakukan yang
didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan
masyarakat (Koentjaraningrat, 1974: 79). Kebudayaan merupakan hasil buah
pikiran manusia atas apa yang didapatnya dari apa yang manusia ketahui, apa
yang dirasakan dan apa yang didapatkan dari alam semesta. Manusia selalu
bertindak atau berbuat berdasarkan pola pikirannya atas apa yang diketahui dan
dirasakan.
Ada juga nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan. Nilai budaya
adalah tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Nilai
budaya berfungsi juga sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi
sebagai konsep, suatu budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup
yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17
Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret, maka nilai-
nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam
jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan yang bersangkutan
(Koentjaranigrat, 2009: 153).
Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat 1996: 80), juga mengungkapkan
adanya unsur-unsur yang meliputi suatu kebudayaan. Unsur-unsur tersebut saling
berkaitan satu dengan yang lainnya dalam sistem kehidupan manusia. Ketika
hendak menganalisis membagi keseluruhan itu ke dalam unsur-unsur besar yang
disebut unsur kebudayaan universal atau cultural universals yang berarti pasti
dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini. Tujuh unsur-unsur
kebudayaan itu adalah: (1) Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Organisasi Sosial
dan Kemasyarakatan, (4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, (5) Sistem Mata
Pencaharian Hidup, (6) Sistem Religi, (7) Kesenian.
1.6.4.1 Bahasa
Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia
untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun
gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau
kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat
menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan
sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Fungsi
bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan
alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan, fungsi bahasa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18
secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari,
mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk
mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Koentjaraningrat, 2002).
1.6.4.2 Sistem Pengetahuan
Menurut Koentjaraningrat (1977: 273), sistem pengetahuan memiliki tujuh
objek. Pertama, alam sekitar manusia, contohnya pengetahuan tentang musim-
musim. Kedua, alam flora, terutama untuk masyarakat yang hidup dari bercocok
tanam dan bertani. Ketiga, alam fauna, terutama bagi masyarakat yang hidup dari
berburu. Keempat, bahan-bahan mentah yang dapat memudahkan manusia untuk
mempergunakan alat-alat hidupnya. Kelima, tubuh manusia, yaitu ilmu untuk
menyembuhkan penyakit secara tradisional. Keenam, sifat-sifat dan kelakuan
manusia, yaitu pengetahuan tentang sopan-santun, adat-istiadat, sistem norma-
norma, serta hukum adat. Ketujuh, ruang dan waktu, yaitu ilmu untuk
menghitung, mengukur, menimbang, atau menentukan tanggal.
Spradley (dalam Kalangie, 1994) menyebutkan, bahwa pengetahuan
budaya itu bukanlah sesuatu yang bisa kelihatan secara nyata, melainkan
tersembunyi dari pandangan, namun memainkan peranan yang sangat penting
bagi manusia dalam menentukan perilakunya. Pengetahuan budaya yang
diformulasikan dengan beragam ungkapan tradisional itu sekaligus juga
merupakan gambaran dari nilai-nilai budaya yang mereka hayati.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

19
Nilai budaya sebagaimana dikemukan oleh Koentjaraningrat (2002) adalah
konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu
masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam
hidup. Suatu sistem nilai budaya, yang sifatnya abstrak, biasanya berfungsi
sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.
1.6.4.3 Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi; kekerabatan,
organisasi politik, norma atau hukum, perkawinan, kenegaraan, kesatuan hidup,
dan perkumpulan. Sistem organisasi adalah bagian kebudayaan yang berisikan
semua yang telah dipelajari yang memungkinkan bagi manusia
mengkoordinasikan perilakunya secara efektif dengan tindakan-tindakan orang
lain (Syani, 1995). Yang termasuk organisasi sosial adalah sistem kekerabatan,
sistem komunitas, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik
(Koentjaraningrat, 1980: 207).
Kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial.
Kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur
sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial
yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan
perkawinan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20
1.6.4.4 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
Sistem peralatan hidup dan teknologi meliputi, alat-alat produksi, senjata,
wadah, makanan, dan jamu-jamuan, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan
perumahan, serta alat-alat transportasi (Koentjaraningrat, 1990: 343).
1.6.4.5 Sistem Mata Pencaharian Hidup
Sistem mata pencaharian hidup merupakan produk dari manusia sebagai
homo economicus yang menjadikan kehidupan manusia terus meningkat. Dalam
tingkat sebagai food gathering, kehidupan manusia sama dengan hewan. Akan
tetapi, dalam tingkat food producing terjadi kemajuan yang pesat. Setelah
bercocok tanam, kemudian beternak yang terus meningkat (rising demand) yang
kadang-kadang serakah. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi
meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan (Koentjaraningrat, 2002).
Sistem mata pencaharian hidup tradisional meliputi berburu dan meramu,
beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam
menetap dengan irigasi (Koentjaraningrat, 1980: 358).
1.6.4.6 Sistem Religi
Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi
keagamaan, dan upacara keagamaan. Definisi kepercayaan mengacu kepada
pendapat Fishbein dan Azjen (dalam Soekanto, 2007) yang menyebut pengertian
kepercayaan atau keyakinan dengan kata “belief”, yang memiliki pengertian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21
sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan tersebut merupakan
acuan bagi seseorang untuk menentukan persepsi pribadi maupun pengalaman
sosial.
1.6.4.7 Kesenian
Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari
ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun
telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan
berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian
yang kompleks. Kesenian yang meliputi; seni patung/pahat, seni rupa, seni gerak,
lukis, gambar, rias, vokal, musik/seni suara, bangunan, kesusastraan ,dan drama
(Koentjaraningrat, 2002). Sehingga dapat diperoleh pengertian mengenai
kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan
meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga
dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bersifat abstrak.
1.7 Metode Penelitian
Metode berasal dari kata methodos, bahasa Latin, yang berasal dari akar
kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah,
sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah (Ratna, 2006: 34). Penelitian adalah
usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan
menganalisis data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik,
dan dapat dipertanggungjawabkan (Wasito, 1992:6).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

22
Pada bagian ini akan dipaparkan jenis penelitian, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, dan teknik penyajian analisis data. Berikut akan
dipaparkan ketiga bagian tersebut.
1.7.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis kualitatif
yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain
secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moeloeng, 2007:6). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian
yang menggunakan kata-kata sebagai bahasa kajiannya dengan mendekripsikan
hasil analisis yang telah berhasil dilakukan dan dimulai dari dasar.
Penelitian ini menggunakan paradigma M.H Abrams menurut Taum.
Menurut Abrams, kritik sastra adalah studi yang berhubungan dengan
pendefinisian, penggolongan, penguraian (analisis), dan penilaian (evaluasi)
(Pradopo, 2002: 18).
Pendekatan kritik sastra menurut Abrams dibedakan menjadi enam yaitu:
pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik, pendekatan ekspresif, pendekatan
objektif, pendekatan eklektik, dan pendekatan diskursif. Dalam penelitian ini,
peneliti hanya memfokuskan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:
pendekatan objektif dan pendekatan mimetik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

23
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan
teknik simak dan teknik catat. Metode studi pustaka digunakan untuk
mendapatkan data yang ada, yaitu sebuah novel berjudul Ngayau, buku-buku
referensi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek tersebut. Sedangkan,
teknik simak digunakan untuk menyimak teks sastra yang telah dipilih sebagai
bahan penelitian. Teknik catat digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap
sesuai dan mendukung penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Teknik
catat merupakan lanjut dari teknik simak (Sudaryanto, 1993: 135).
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah
Judul buku : Ngayau
Pengarang : Masri Sareb Putra
Tahun Terbit : 2014 (Cetakan Kedua)
Penerbit : Entertainment Essence Center
Halaman : 373 halaman
1.7.3 Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis isi/konten (content analisys). Metode ini mengungkapkan karya sastra
sebagai bentuk komunikasi antar pembaca dan pengarang. Menurut Arikunto
(2006: 231), analisis konten yaitu mengungkap makna simbolik yang tersamar
dalam karya sasrta. Pada metode ini, peneliti sebagai pembaca mampu memahami
hal-hal yang disampaikan oleh pengarang sebagai objek penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

24
Data pada penelitian karya sastra berupa struktur pembangun cerita yang
dianalisis menggunakan teori kajian struktural. Dalam penelitian ini, penulis akan
mengkaji dua struktur pembangun cerita, yaitu: tokoh penokohan, dan latar.
Dalam membahas unsur-unsur budaya, peneliti akan menggunakan teori unsur-
unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat yang ada di dalam objek material.
1.7.4 Teknik Penyajian Analisis Data
Metode penyajian analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah
metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang hasil
analisis datanya berupa pemaknaan karya sastra yang disajikan secara deskriptif.
Metode kualitatif memanfaatkan cara penafsiran dengan menyajikannya dalam
bentuk deskripsi. Metode ini memberikan perhatian terhadap data ilmiah, data
dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Metode deskriptif adalah
prosedur pematahan/pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor-
faktor yang tampak sebagaimana adanya. Melalui metode ini, peneliti
menggambarkan fakta-fakta yang terkumpul harus diolah atau ditafsirkan (Ratna,
2004: 4647). Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan secara
deskriptif dengan hasil analisis berupa data kualitatif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

25
1.8 Sistematika Penyajian
Penelitian ini disajikan dalam empat bab. Keempat bab tersebut antara satu
dengan yang lainnya saling berkaitan. Pembagian tiap bab tersebut adalah sebagai
berikut:
Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian,
landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penyajian.
Bab II merupakan bab yang berisi analisis struktur cerita dalam novel
Ngayau, meliputi tokoh dan penokohan, serta latar.
Bab III merupakan bab yang berisi analisis unsur-unsur budaya Dayak dan
Tionghoa yang tergambar dalam novel Ngayau.
Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

26
BAB II
STRUKTUR CERITA DALAM NOVEL NGAYAU KARYA
MASRI SAREB PUTRA
2.1 Pengantar
Dalam Bab II akan dipaparkan mengenai struktur cerita yang terdiri dari
tokoh, penokohan, dan latar. Analisis struktural merupakan kajian untuk
mendeskripsikan unsur pembangun yang ada dalam karya sastra dan
menggambarkan hubungan antarunsur tersebut untuk memperoleh kesatuan
makna. Unsur tokoh, penokohan, serta latar saling terkait dan dipilih sebagai
unsur yang perlu dikaji dalam penelitian ini karena unsur-unsur tersebut
selanjutnya nantinya akan dikaitkan dengan analisis unsur-unsur budaya Dayak
dan Tionghoa yang akan dibahas dalam bab III.
Berikut akan dipaparkan hasil analisis kedua unsur pembentuk karya sastra
tersebut dalam novel Ngayau sebagai objek material penelitian ini.
2.2 Tokoh dan Penokohan
Dalam penelitian ini, hanya sebagian dari para tokoh yang akan dianalisis.
Tokoh-tokoh tersebut dipilih karena kaitannya dengan unsur-unsur budaya Dayak
dan Tionghoa. Dalam novel Ngayau terdapat sejumlah tokoh yang memiliki
pengaruh besar terhadap terjadinya sebuah peristiwa sehingga membentuk cerita
yang berkesinambungan. Berikut beberapa tokoh yang akan dianalisis: Lansau,
Siat Mei, A pa Mei, Ben Teng, A kong Mei, Ahong, Sinfu, Sin Sang, Kek Longa,
Domia, dan Domamakng Bunso. Sepuluh tokoh tersebut akan dianalisis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

27
berdasarkan peran dan pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara
keseluruhan yang akan dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan.
2.2.1 Tokoh Utama
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam karya
sastra. Dalam novel Ngayau, tokoh utama terdiri dari dua orang, yaitu Lansau dan
Siat Mei. Peran tokoh utama adalah penentu perkembangan jalannya cerita secara
keseluruhan. Mereka dikategorikan sebagai tokoh utama karena sering muncul
dalam cerita.
2.2.1.1 Lansau
Lansau merupakan salah satu tokoh utama dalam novel Ngayau. Hal
tersebut didasari kemunculannya yang cukup banyak dalam penceritaan.
Lansau adalah suami dari Siat Mei yang merupakan seorang pemuda
Dayak. Dalam Ngayau, pengarang tidak menyebutkan Lansau dari sub suku
Dayak mana pun. “Itu tentang masa lalu,” sembari menepuk bahu lelaki itu.
“Kamu ini chang fu aku!” (Putra, 2014: 153). Pernikahan mereka pernah
dibatalkan oleh a pa Mei saat terjadinya perang Dayak kontra Tionghoa karena
provokasi. Berikut ini adalah kutipannya.
Kisah Ben Teng dicerna a pa Mei dengan saksama. Itu yang membuat a pa
Mei tiba-tiba membatalkan perkawinan anak gadisnya dengan Lansau (Putra,
2014: 63).
Dalam situasi tegang saat tariu, di mana ruh leluhur mencari tubuh yang bisa
dirasuki, saat itu Lansau menyelamatkan Mei dan a pa-nya. Lansau pandai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

28
melucu dan mencairkan suasana. Ia memegang perut yang kena tonjok a pa Mei.
Mei berusaha membantu Lansau untuk bangkit berdiri. Ketika berdiri, Lansau
seperti tidak terkena sepukul pun. Melihat Mei dan a pa-nya seperti tak percaya.
Lansau berusaha mencairkan suasana. “Untung panglima burungku tidak apa-apa”
katanya (Putra, 2014: 80).
Secara fisik, tidak digambarkan bagaimana kondisi fisik Lansau. Akan
tetapi, pengarang menjelaskan bahwa ciri fisik orang Dayak dan Tionghoa hampir
sama. Ciri fisik keduanya yang notabene bermata sipit, kulit berwarna kuning
langsat, dan rambut lurus berwarna hitam. Ciri-ciri fisik, mereka hampir sama.
Soal bahasa, mereka sama-sama bisa menuturkan bahasa Dayak, dialek Khek, dan
bahasa Indonesia. Makanan dan kebiasaan juga sama. (Putra, 2014: 48).
“Lansau, kamulah titisanku dalam perang ini” kata Panglima Burung, seraya
menghentikan pengejaran dua sasaran tak bertanda itu setelah merasuk tubuh
Lansau.” (Putra, 2014: 75).
Dari kutipan tersebut, Lansau adalah titisan Panglima Burung karena saat
tariu, Panglima Burung memilih masuk ke tubuh Lansau.
Lansau membawa lari Mei dan a pa-nya secepat cahaya. Panglima Burung
yang dipanggil lewat tariu memilih masuk raga pemuda itu (Putra, 2014: 75).
Dalam Ngayau, Panglima Burung adalah sebuah gelar. Orang Dayak dalam
kesehariannya, tidak dapat lepas dari burung sebagai pemberi tanda. Memiliki
kekuatan magis, dan bertugas memata-matai kekuatan musuh, dan meluncur
secepat cahaya ke medan laga (Putra, 2014: 25). Saat tariu, Lansau yang
merupakan pemimpin manusia kepala merah membawa lari Mei dan A pa-nya ke
sebuah ruangan penyekapan. Di sana, Lansau pun mengisahkan apa yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29
sebenarnya terjadi. Massa Dayak diprovokasi untuk menghalau etnis Tionghoa di
pedalaman tanpa kecuali (Putra, 2014: 77). Lansau berusaha menyelamatkan Mei
beserta keluarganya dan terpaksa melakukannya seperti penculikan. Akhirnya,
Lansau menitipkan Mei dan a pa-nya di truk menuju kota (Putra, 2014: 86). Di
samping itu juga, Lansau berusaha mencari ibu Mei. Lansau merasa bertanggung
jawab untuk menemukan ibu Mei dalam keadaan hidup atau mati. Haru biru pun
menyelimuti saat mereka akan berpisah. Suasana tersebut terdapat dalam kutipan
berikut.
Tak terasa, sebutir air jatuh dari pelupuk matanya. Hanya setitik. Sebab
pantang bagi lelaki, apalagi ksatria untuk menangis! Anehnya, panglima
perang seperti Lansau pun bisa terharu (Putra, 2014: 86).
Saat tariu dan masih dirasuki ruh leluhur, Lansau membawa a pa Mei
mengungsi ke Singkawang (Putra, 2014: 101). A pa Mei ditinggalkan di sebuah
rumah adat yang terbuat dari bahan kayu besi bersama orang yang Lansau panggil
Pak Miguk. Belum sempat mencerna situasi, Lansau pamit kepada a pa Mei untuk
pergi berperang, yang dianggap Lansau sebagai tugasnya menyelamatkan
khalayak ramai.
Dalam novel Ngayau, tokoh Lansau adalah sahabat Ahong, pemimpin
pasukan seribu kuil yang merupakan abang dari Siat Mei. Ahong menyapa Lansau
dengan sebutan “thai sim”. Saat itu, Lansau hanya sebatas suka kepada Mei.
Persahabatan antara Lansau dan Ahong terdapat dalam kutipan percakapan
berikut.
Namun, raut muka kesedihan serta merta berubah menjadi keterkejutan. “Lo
thai sim! Kata thaiko. “Lansau, ka. . . kamu? Apa saya tak salah melihat?
“Tidak salah penglihatanmu, akulai ini!” kata Lansau. “Dan kau, ako Ahong,
kenapa di sini?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

30
Kedua sahabat itu berpelukan. Lansau dan Ahong. Ahong adalah nama asli
pemimpin pasukan seribu kuil. Oleh Mei, abang kandungnya, ia dipanggil
“thaiko”. Sementara Lansau sudah biasa menyapa sahabatnya dengan sebutan
kelakar “thai sim”, meski antara Lansau dan Mei baru sebatas suka sama suka
waktu Lansau meninggalkan kampung seberang sungai untuk sekolah ke kota
tiga tahun lalu. . . . (Putra, 2014: 130).
Dari pernikahannya dengan Siat Mei, Lansau dikaruniai seorang anak
perempuan yang tidak disebutkan namanya oleh pengarang. Saat itu, Lansau, Mei
beserta anaknya berziarah ke pemakaman a pa Mei. Hal tersebut dapat dilihat
dalam kutipan berikut.
“Kasih hormat, itu akong!” kata Mei pada seorang gadis, seusia seperti
dirinya juga ketika dulu dievakuasi, sembari memberi padanya hio yang
menyala (Putra, 2014: 149).
2.2.1.2 Siat Mei
Siat Mei merupakan salah satu tokoh utama selain Lansau. Kehadirannya
cukup dominan dalam cerita dalam novel Ngayau. Peristiwa perang yang
dialaminya bersama a me, a pa-nya, dan suaminya, Lansau yang menjadi patokan
penceritaan.
Siat Mei adalah seorang gadis Tionghoa yang sejak kecil sudah tinggal
dalam lingkungan orang Dayak. Ia dipanggil Moici (sapaan anak perempuan
dalam bahasa Hakka) oleh ayahnya. Mei merupakan anak seorang pedangang
kelontong. Ia merupakan istri Lansau yang merupakan seorang pemuda Dayak.
Pernikahan mereka pernah dibatalkan oleh a pa Mei. Siat Mei sudah berteman
dengan Lansau sedari SD hingga SMP.
Penokohan Siat Mei dapat dilihat dalam beberapa kutipan berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31
“Tiba-tiba Siat Mei merasa pusing. Dunianya serasa berhenti berputar.
Pemandangan jadi gelap. Ia tidak mengerti mengapa upacara perkawinannya
dengan Lansau harus dibatalkan. Kami kan sejak es de selalu berteman, a
pa.” kata Siat Mei, tidak mengerti. Ia masih tidak percaya yang dikatakan a
pa-nya. “Kenapa hubungan kami harus diputus?” (Putra, 2014: 47-48).
Dari segi fisik, kebiasaan, dan bahasa Siat Mei sama sekali tidak merasa
berbeda dengan Lansau karena sejak kecil Mei sudah tinggal dalam lingkungan
orang Dayak .
“Heran saja Siat Mei mendengar kata-kata a pa-nya. sama sekali ia tidak
merasa berbeda sedikitpun dengan Lansau, kecuali jenis kelamin. Ciri-ciri
fisik mereka hampir sama. Soal bahasa, mereka sama-sama bisa menuturkan
bahasa Dayak, dialek Khek, dan bahasa Indonesia. Makanan dan kebiasaan
juga sama.” (Putra, 2014: 48).
Siat Mei digelari Dara Juanti karena kecantikannya. Dara berarti dara atau
putri, jika pria maka bujang atau abang. Sedangkan Juanti berarti: mahkluk air
yang sangat jelita, atau indah sekali seperti anggrek.
Lansau perlahan membelai rambut Mei yang panjang terurai disisir angin
pantai Pasir Panjang. lalu menatap wajah wanita itu: masih seperti dulu.
Molek jelita sehingga digelari Dara Juanti” (Putra, 2014: 153)
Dalam masyarakat Kalimantan Barat, Dara Juanti merupakan cerita rakyat,
khususnya Kabupaten Sintang. Putri Dara Juanti yang terkenal dalam sejarah
kerajaan Sintang yang membawa perhubungan dengan tanah jawa. Dalam
sejarahnya, Dara Juanti berlayar ke ranah Jawa untuk membebaskan saudaranya
Demong Nutup (di Jawa dikenal dengan nama Adipati Sumintang) yang ditawan
oleh salah satu kerajaan di Jawa. Di pelabuhan Tuban, Dara Juanti dihadang oleh
prajurit kerajaan dan merupakan pertemuan pertama dengan seorang patih dari
Majapahit yaitu Patih Loh Gender. Dari pertemuan itu, keduanya semakin dekat.
Akhirnya Patih Loh Gender pergi ke Sintang untuk melamar Dara Juanti. Namun,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

32
Patih Loh Gender harus kembali ke Tanah Jawa karena harus memenuhi
persyaratan yang diminta Dara Juanti. Persyaratan tersebut di antaranya, keris
elok tujuh berkepala naga, empat puluh kepala, dan empat puluh dayang-dayang.
Pinangan sudah terpenuhi, selain itu Patih Loh Gender menyerahkan barang
pinangan lainnya seperti seperangkat alat musik, patung burung garuda terbuat
dari emas, dan sebongkah tanah majapahit. Pinangan berhasil, pernikahan pun
diselenggarakan.
Dalam catatan sejarah, pernikahan Putri Dara Juanti dengan Patih Loh Gender
diperkirakan pada tahun 1401 M, karena pada saat pernikahan usia Dara Juanti
berusia 27 tahun. Sedangkan Patih Loh Gender diperkirakan di atas 50 tahun.
Sebelumnya, Patih Loh Gender sudah memiliki istri dan memiliki tiga orang anak.
Dari pernikahannya dengan Lansau, Mei dikaruniai seorang anak perempuan
yang tidak disebutkan namanya oleh pengarang. Saat itu, Lansau, Mei beserta
anaknya berziarah ke pemakaman a pa Mei. Hal tersebut dapat dilihat dalam
kutipan berikut.
“Kasih hormat, itu akong!” kata Mei pada seorang gadis, seusia seperti
dirinya juga ketika dulu dievakuasi, sembari memberi padanya hio yang
menyala (Putra, 2014: 149).
2.2.2 Tokoh Tambahan
Tokoh-tokoh lain yang ada dalam novel Ngayau adalah a pa Mei, Ben
Teng, A kong Mei, Ahong, Sinfu, Sin Sang, Kek Longa, Domia, dan Domamakng
Bunso. Tokoh tambahan dalam novel ini kehadirannya diperlukan untuk
mendukung tokoh utama.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

33
2.2.2.1 A pa Mei
A pa Mei adalah ayah dari Siat Mei. Dalam novel Ngayau, pengarang
tidak menyebutkan siapa nama dari ayah Mei. Pengarang hanya menyebutkan
sapaan a pa. A pa adalah panggilan untuk ayah dalam bahasa Tionghoa, dialek
Hakka. Dari segi fisik, ayah Mei digambarkan dengan jelas sebagai seorang pria
keturunan Tionghoa yang berkulit kuning, berambut lurus hitam, gemuk, dan
bermata sipit.
“Batalkan segera! Kata seorang pria setengah baya, berkulit kuning rambut
lurus hitam, agak gendut, dan bermata sipit.” (Putra, 2014: 46).
Beberapa orang keturunan Tionghoa kesulitan melafalkan bunyi R, demikian
juga dengan a pa Mei. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut.
“Kita olang pendatang, halus pandai-pandai. Harus pandai belgaul. Kalau
jodo, kawin pun tadak masalah,” thaiko masih ingat kata-kata a pa-nya yang
tak lain juga adalah a pa Mei (Putra, 2014: 120).
Dari perwatakannya, Ayah Mei sangat menyayangi anak perempuan semata
wayangnya, Siat Mei yang terpaksa ia batalkan perkawinannya dengan Lansau
sehari menjelang acara.
“Mungkin, saat ini menyakitkan. Namun, suatu hari, kamu akan mengerti.
Maafkan a pa, kata pria itu. “Moici, a pa sayang kamu!” katanya sembari
memeluk, kemudian mencium anak gadisnya.” (Putra, 2014: 48).
Ayah Mei adalah seorang yang suka membaca dan jago silat sejak remaja.
Akan tetapi, dia mudah terhasut, mudah percaya dengan berita yang belum tentu
kebenarannya. Dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

34
Adakah sebuah ungkapan ntuk menggambarkan rasa takut dan ingin tahu,
campur baur jadi satu seperti saat ini dialami a pa Mei? Meski hanya
pedagang kelontong di desa, a pa Mei sebenarnya suka baca. Bacaan apa saja,
terutama membaca literatur-literatur ilmu sosial dan kebudayaan (Putra, 2014:
68).
A pa Mei sudah mencium gelagat adu domba sejak kabar ia terima dari
tauke-nya di Sanggau. “Kita olang selalu jadi kolban,” kata Ben Teng, sang
tauke. “Kelja susah payah, sudah makmul, e. . . . tahu-tahu diusil pelgi!
(Putra, 2014: 59).
Lansau yang tidak menduga, roboh seketika oleh pukulan aneh a pa Mei yang
sejak remaja sudah ikut bela diri. Dari mana lelaki gemuk, berkulit kuning,
bermata sipit itu mendapat jurus demikian aneh? Lansau tak mengerti (Putra,
2014: 72).
Dari segi sosial, Ayah Mei adalah seorang pedagang kelontong.
Kelontongnya dibakar massa saat tariu terjadi. Hal ini terlihat dalam kutipan
berikut..
“Inikah yang menyebabkan pedagang kelontong itu membatalkan perkawinan
anak gadisnya yang tinggal menghitung jam?” (Putra, 2014: 52).
Dan bunyi itu semakin dekat dengan bantaran sungai tempat tinggal Mei,
sekaligus toko kelontong milik keluarganya,” (Putra, 2014: 68).
A pa Mei adalah seorang ayah yang lemah lembut. Terlihat saat Ahong
mengingat kembali apa yang telah a pa-nya sampaikan kepadanya.
“Kita olang pendatang, halus pandai-pandai. Harus pandai belgaul. Kalau
jodo, kawin pun tadak masalah,” thaiko masih ingat kata-kata a pa-nya yang
tak lain juga adalah a pa Mei. Sayang sekali! Thaiko tidak mendengar bahwa
kata-kata yang sama disangkal sendiri oleh sang ayah. A pa mereka yang
lemah lembut, suatu malam tidak seperti biasanya. A pa memanggil Mei. Dan
dengan nada tinggi membentak anak gadisnya (Putra, 2014: 120).
2.2.2.3 Ben Teng
Ben Teng adalah teman a pa Mei yang merupakan orang kaya di Sanggau.
Ben Teng lahir dan dibesarkan di Borneo. Ia digambarkan sebagai orang yang
senang bersosialisasi dan memiliki banyak relasi saat isu perang akan dimulai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35
Wajib baginya untuk tidak membatasi komunikasi dan relasi. Dalam hal ini, Ben
Teng memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Sama seperti Siat Mei, Ben
Teng sama sekali tidak merasa berbeda dengan orang Dayak. Ben Teng adalah
penyuplai logistik saat PGRS/Paraku di wilayah perbatasan. Dari cara
berbicaranya, Ben Teng masih kental menggunakan dialek Hakka.
Ben Teng adalah tauke besar di Sanggau. Kekayaan yang dimilikinya tak
terhingga. Mungkin cukup untuk tujuh keturunan. Hampir semua pedagang
dari mulai pesisir hingga pedalaman dikuasainya. Ben Teng dan a pa Mei
lahir dan dibesarkan di bumi Borneo. “Kita melasa olang Cin dali seblang!”
kata Ben Teng suatu pagi, ketika bersama a pa Mei sedang kongkow-
kongkow. “Kita olang Cin wajib mengangkat delajar olang Dayak. Sebab
meleka sama sepelti kita, kita juga dali negeli yang sama! (Putra, 2014: 61).
Ben Teng juga melakukan kontak sosial ekonomi dengan rakyat dan tokoh
gerakan Kalimantan Utara. Ben Teng punya banyak informasi mengenai
kedua belah pihak. Dan selalu bisa memanfaatkan informasi untuk meraih
keuntungan (Putra, 2014: 61).
2.2.2.5 A kong Mei
A kong Mei adalah kakek dari Siat Mei. Ia senang mengoleksi buku-buku
yang dibelinya di pasar loak. Karena hobinya mengoleksi buku tersebut, A kong
merupakan pemilik kios penyewaan komik yang memiliki banyak peminat.
Akong Mei adalah agen cerita silat. Ia membuka kios penyewaan komik yang
laris luar biasa. Sembari mendatangkan serial cerita silat, si akong juga
mengoleksi buku-buku yang ia beli di pasar loak.” (Putra, 2014: 69).
2.2.2.4 Ahong
Ahong adalah abang dari Siat Mei. Ahong adalah pemimpin pasukan seribu
kuil dan bersahabat dengan Lansau, yang merupakan titisan Panglima Burung.
Mei memanggilnya dengan sapaan Thaiko, yang berarti abang. Sementara, Lansau
menyapanya thai sim, yang berarti abang ipar. Secara fisik, Lansau dan Ahong
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

36
disebut seperti pinang dibelah dua karena secara fisik mereka tidak jauh berbeda,
karena secara umum fisik orang Tionghoa dan orang Dayak berkulit kuning dan
bermata sipit.
Demikian juga Ahong yang sekilas bak pinang dibelah dua dengan Lansau.
Dalam situasi normal, tidak ada yang menyangka dia pemimpin kelompok
pendekar seribu kuil (Putra, 2014: 69).
Oleh Mei, abang kandungnya, ia dipanggil “thaiko”. Sementara, Lansau
sudah biasa menyapa sahabatnya dengan sebutan kelakar “thai sim”. Meski
antara Lansau dan Mei baru sebatas suka sama suka saat Lansau
meninggalkan kampung seberang sungai untuk sekolah ke kota tiga tahun
lalu. . . (Putra, 2014: 130).
Selama tiga tahun Ahong dikirim oleh orang tuanya melanjutkan studi di
sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa di Kota Singkawang. Di luar sekolah,
Ahong juga mengikuti kegiatan ekstra. Hal tersebut dilakukannya demi
memajukan kaumnya yang dianggap sebagai pendatang dan selalu dimarjinalkan
dalam berbagai bidang. Tak hanya itu, Ahong pun tergelitik dan merasa terpanggil
membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Beberapa hal lain yang
dipelajarinya yaitu belajar silat, belajar ilmu-ilmu profan, serta belajar bahasa dan
aksara Cina (Putra, 2014: 114). Dengan inisiatifnya sendiri, Ahong memimpin
perang gerilya yang diberi nama “pasukan seribu kuil. Tujuannya, membela dan
mempertahankan diri. Agar kaum Tionghoa yang sudah berabad-abad menetap di
Indonesia, terutama di bumi Borneo, tidak selamanya dianggap pendatang.
Ahong mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah atas di
Singkawang. Tentu ada maksud dan tujuan tertentu mengapa Ahong tetap
melanjutkan sekolah. Hal ini tentu berkaitan dengan identitasnya yang merupakan
bagian dari etnis Tionghoa yang dianggap pendatang di Bumi Borneo. Selain itu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

37
juga, tujuannya untuk membela diri serta menegakkan keadilan. Karena sudah
belajar dan mengamalkan ilmu bela diri dan ilmu profan, thaiko akhirnya menjadi
pemimpin pasukan seribu kuil saat perang gerilya.
2.2.2.6 Sinfu
Sinfu merupakan seorang pastor tentara dan menjadi sukarelawan saat
perang. Pengarang tidak menyebutkan siapa nama sebenarnya dan tidak
mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri Sinfu secara fisik. Sinfu bertemu Lansau dan
Ahong saat memapah para korban perang. Oleh penduduk setempat, ia disapa
menggunakan panggilan Tuan Serani. Dalam novel Ngayau, Sinfu digambarkan
sebagai tokoh tambahan yang mengetahui seluk-beluk terjadinya provokasi, dan
siapa saja pihak yang berkepentingan dibalik perang yang terjadi antara suku
Dayak dan Tionghoa. Sinfu yang menjelaskan kepada Lansau dan Ahong
mengapa provokasi dapat terjadi dan berhasil. Dapat dilihat dalam kutipan
berikut.
Dua panglima sembari memapah para korban, bertemu sukarelawan. Ia
adalah pastor tentara yang dipanggil sinfu atau “tuan serani” (Putra, 2014:
137-138).
Bukan hanya demontrasi untuk mengusir warga etnis Tionghoa, tetapi juga
pembunuhan,” jelas sukarelawan yang juga pastor tentara (Putra, 2014: 139).
Sinfu menjelaskan misteri perang gaib. “Ini operasi tingkat tinggi.
Pembersihan, sekaligus pengusiran warga Tionghoa dari pedalaman,” Katanya
(Putra, 2014: 138). Lansau dan Ahong terkesima mendengar uraian sinfu. Etnis
Dayak dihasut, dibakar emosinya. Dalam sebuah grand design itu tentara telah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

38
menyamar, memasuki perkampungan Dayak. Operasi intel dilakukan untuk
menghasut etnis Dayak agar memusuhi etnis Tionghoa.
Menurut analisis dan data intel, 90 persen etnis Tionghoa di Kalimantan Barat
distempel sebagai komunis. Maka, tentara yang menyamar, masuk ke kampung
dayak dan mendekati tokoh masyarakat setempat. Dalam sebuah silent operation,
tentara membunuh beberapa tokoh Dayak, tidak di kampung mereka. untuk
memancing kemarahan warga Dayak, disebarluaskan isu dan propaganda bahwa
tokoh Dayak dibunuh PGRS/Paraku. Sinfu juga menjelaskan bahwa perang antara
bangsa Lansau dan Ahong ini adalah “rekayasa luar biasa” (Putra, 2014: 139).
2.2.2.7 Sin Sang
Dalam bahasa Hakka, “sin sang” bukan saja untuk menyebut tuan, bapak,
dan guru: melainkan juga untuk orang yang terampil dan cakap di bidangnya. Sin
sang adalah guru silat Ahong yang memiliki ilmu-ilmu profan. Pengarang tidak
menyebutkan nama dan bagaimana kondisi fisiknya. Sin sang digambarkan
sebagai tokoh yang rendah hati dan penolong. Ia lah yang telah membantu anak
dan wanita saat di truk sebagai pengungsian saat kerusuhan.
Si penolong tepat waktu itu lalu membantu para pengungsi di truk itu turun.
Sin sang adalah guru thaiko. Selain sakti mandraguna, sang guru juga mahir
dalam ilmu persilatan, selain kaya akan ilmu-ilmu profan. Rendah hati, tidak
suka kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ilmu yang dimilikinya murni
digunakan untuk kebaikan dan menolong kaum lemah dan tertindas (Putra,
2014: 128).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

39
2.2.2.8 Kek Longa
Dalam novel Ngayau, “Kek Longa” atau Babae Longa merupakan
manusia yang sudah bosan hidup di bumi yang disebut babae. Kek Longa
merupakan ayah Domia. Ia diberi gelar “Kek Longa” karena tubuhnya tinggi dan
kekar. Pengarang menyebutkan bahwa Kek Longa merupakan seorang yang sakti.
Akan tetapi, karena faktor usia, Kek Longa sudah tidak mampu. Saat tariu, Babae
Longa lah yang masuk ke raga Lansau. Pengarang menjelaskan bahwa orang baik
dan orang sakti tidak dapat mati. Jika sudah bosan hidup di dunia, maka akan
berubah menjadi babae yang ruhnya dapat merasuk ke dalam benda atau makhluk
tertentu. Dalam situasi apa pun, babae pun siap melindungi. Penggambaran
tentang Kek Longa dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut.
Sementara ayahanda, Kek Longa makin tua. meski sakti mandraguna,
kecepatan dan kekuatan Kek Longa sudah tidak sanggup mengimbangi
Lawan di medan laga. Maka yang memimpin dan menjadi macatn di
kampung itu jatuh ke tangan Domamakng Bunso (Putra, 2014: 169).
Babae haruslah dipelihara, meski sudah tidak berwujud manusia. Babae
yang dipelihara menjadi puaka bersama, suatu waktu siap melindungi
anak, cucu, dan buyut kapan pun dan di mana pun diperlukan (Putra, 2014:
184).
Kek Longa digambarkan sebagai seorang suami yang setia. Dengan
pengetahuan musim yang dimilikinya, ia pergi berburu saat binatang keluar hutan
saat musim kemarau untuk mencari makan dan minum. Saat itu juga, Kek Longa
gelisah karena tidak berhasil menangkap buruan untuk istrinya yang sedang hamil
tua. Istrinya tersebut mengidam binatang buruan.
Kek Longa makin diliputi rasa gelisah karena istrinya di rumah sedang
hamil tua. Hasil buruannya ditunggu-tunggu, sebab sang istri mengidam
binatang buruan. Si pemburu akhirnya tidak kuat menahan rasa lelah. Ia
merebahkan diri di bawah sebatang pohon beringin yang rindang (Putra,
2014: `85).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40
Kala merasa bosan hidup, Kek Longa meminta warga menjalankan
wasiatnya agar mengantarnya ke sebuah tempat. Wasiat tersebut menjadikannya
berubah menjadi seekor burung yang menjadi simbol dalam suku Dayak
Kalimantan. Wasiat Kek Longa tersebut terdapat dalam kutipan berikut.
“Balut badanku dengan tikar!” katanya. “Lalu antar saya ke sebuah pulau
di ujung kampung. Pada hari keempat, jenguk tempat di mana saya semula
diletakkan.”
Warga menuruti wasiat Kek Longa. Mereka melakukan seperti yang
diminta: mengantar jasad manusia yang tak dapat mati itu ke sebuah pulau.
Pada hari keempat, jenguk tempat itu. Mereka tidak menemukan tikar
beserta isinya. Namun, warga melihat nun di dahan pohon ketapang yang
menjulang, ada seekor burung. Mereka menamainya “burung Enggang”.
Kek Longa bertransformasi jadi babae. Ruhnya dan kesaktiannya sewaktu-
waktu dapat dipanggil. Nama Kek Longa selalu muncul dalam buah-buah
mantra dan rapalan tariu (Putra, 2014: 174).
2.2.2.9 Domia
Dalam novel Ngayau, ciri fisik Domia digambarkan dengan jelas oleh
pengarang. Penggambaran ciri fisik Domi terdapat dalam kutipan berikut.
Oleh karena cantik dan menyukakan semua orang, bayi perempuan itu
dinamakan “Domia”.
“Kulitnya bersih. Hidungnya mancung. Alisnya tebal. Bulu matanya
lentik,” seru para wanita.
Karena amat cantuk, bayi perempuan itu dinamakan Domia. Dalam bahasa
Dayak, Domia berarti Dewi. Seperti ramalan banyak orang, Domia
tumbuh menjadi gadis jelita (Putra, 2014: 168-169).
Domia merupakan anak dari Kek Longa. Saat gawai notokng, Domia
menari dan bernyanyi. Ia menyambut tunangannya pulang berperang. Saat itu juga
Domia menyuguhkan tuak buatannya kepada Domamakng Bunso.
“Ini tuak dibuat dari tanganmu sendiri,” kata Domia pad tunangannya,
“Minunlah!” Domia menyuguhkan tuak itu. Tercetak di wajahnya rasa
bangga (Putra, 2014: 172).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

41
Sebelumnya, Raja Kerajaan Tayan ingin menjadikan Domia sebagai istri
yang ke-7. Akan tetapi, karena atok Domia, ia tetap berjodoh dengan Domamakng
Bunso. Raja rela melepas Domia untuk menikah dengan Domamakng Bunso.
Akan tetapi, Raja memberinya syarat. Jika nanti Domia melahirkan anak laki-laki,
Raja ingin memiliki anak tersebut. Domia pun melahirkan anak kembar diberi
nama Begumban Berderai Darat dan Bejamban Perangai Laut.
2.2.2.10 Domamakng Bunso
Domamakng Bunso merupakan suami dari Domia dan seorang ayah dari
anak kembar yang bernama Bagumban Berderai Darat dan Bejamban Perangai
Laut. Bagumban Berderai Darat diartikan sebagai Darat. Bejamban Perangai Laut
Sedangkan diartikan sebagai Laut. Nama tersebut diberi oleh D Domamakng
Bunso dengan penuh arti dan harapan. Melalui kedua nama anak kembar tersebut,
pengarang menggambarkan bahwa darat dan laut tidak dapat dipisahkan dan
harapannya agar semua suku bangsa tetap bersatu, meskipun memiliki perbedaan.
Penggambaran mengenai nama tersebut terdapat dalam kutipan berikut.
Supaya adil, namanya Bagumban Berderai Darat. Sedangkan yang satunya
lagi Bejamban Perangai Laut. Sebab hakikatnya darat dan laut tidak adalah
satu, tak terpisah satu sama lain. Laut ada karena darat. Sebaliknya, darat
ada karena laut. Simbol bahwa kita, meski dari suku berbeda, tetap satu
sampai kapan pun jua dan selalu rukun di bumi khatulistiwa,” terang
Domamakng Bunso (Putra, 2014: 223).
Dalam novel Ngayau, Domamakng Bunso digambarkan oleh tokoh Raja
sebagai seorang yang sakti. Dari segi fisik, pengarang menggambarkan bahwa
Domamakng Bunso merupakan seorang yang gagah. Tinggi badannya di atas
rata-rata serta kaki dan lengannya yang berotot. Akan tetapi, karena sifat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

42
bawaannya yang lembut dalam berkata-kata. dinilai tidak sedikitpun seperti
seorang ksatria. Penggambaran tersebut terdapat dalam kutipan-kutipan berikut.
Sementara kepada Domia, Raja bersabda, “Kamu beruntung mendapat
suami. Selain sakti mandraguna, juga sangat mencintaimu.” (Putra, 2014:
219).
Ditilik dari perawakan, Domamakng Bunso memang sosok yang gagah
perkasa. Postur tubuhnya melebihi rata-rata. Kaki dan lengannya berotot,
lagi pula bidang dadanya. Namun, dilihat dari perangainya yang lembut
serta tutur katanya yang halus, sama sekali Domamakng Bunso tidak
mengesankan seorang ksatria (Putra, 2014: 197).
2.3 Latar
Dalam novel Ngayau dianalisis juga mengenai latar. Latar merupakan
salah satu unsur sebagai pendukung dalam suatu penceritaan. Latar yang akan
dianalisis pada bagian ini meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar sosial-
budaya. Berikut analisis latar dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra.
2.3.1 Latar Waktu
Terdapat beberapa latar waktu yang dominan dan berkaitan dengan
peristiwa sejarah dan sekaligus melatari peristiwa sejarah dalam novel Ngayau,
yaitu pada saat Peristiwa Mangkok Merah yang terjadi pada tahun 1967. Perang
yang melibatkan etnis Tionghoa melawan suku Dayak di Kalimantan Barat karena
provokasi. Latar waktu juga terjadi pada tahun 1999 saat kerusuhan antar etnis di
Kabupaten Sambas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

43
2.3.1.1 Tahun 1967
Peristiwa Mangkuk Merah 1967 adalah peristiwa yang melatari novel
Ngayau. Peristiwa penyerangan yang disertai pembunuhan dan pengusiran yang
dilakukan oleh suku Dayak terhadap permukiman warga etnis Tionghoa di
pedalaman Kalimantan Barat pada akhir tahun 1967. Peristiwa yang terjadi antara
bulan September hingga Desember 1967 ini menjadi salah satu tragedi
kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Mangkuk Merah sendiri merupakan istilah
ritual dan adat suku Dayak sebagai sarana konsolidasi dan mobilisasi pasukan
lintas subsuku yang efektif dan efesien dan simbol dimulainya perang.
Peristiwa Mangkuk Merah 1967 yang sangat kental dengan nuansa politik
ini dipicu oleh serangkaian rekayasa pembunuhan sejumlah tokoh Dayak dan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuduh pelakunya adalah PGRS/Paraku dan
etnis Tionghoa merupakan penyokong mereka. Peristiwa ini mengakibatkan
setidaknya 3.000 korban tewas terbunuh di pedalaman dan sekitar 4.000-5.000
korban tewas di pengungsian di Pontianak dan Singkawang karena gizi buruk,
minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan
(Darmayana, 2013).
Sebelum pekik perang dilancarkan pada 17 Oktober 1967, di antara warga
Dayak sepakat tidak melakukan penyerangan atau kau Tionghoa sebagai
manusia, melainkan ditujukan hanya kepada harta benda milik mereka saja
(Putra, 2014: 141)
Dalam kutipan di atas, pengarang menggambarkan bahwa latar waktu saat
Perang Mangkok Merah terjadi pada tanggal 17 Oktober 1967.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

44
2.3.1.2 Tahun 1999
Tahun 1999 juga melatari cerita dalam novel Ngayau. Meskipun tidak
tergambarkan secara rinci tanggal dan bulan terjadinya suatu peristiwa pada tahun
1999. Latar waktu pada tahun 1999 terdapat dalam kutipan-kutipan berikut.
Sambas bukan hanya dihuni tiga suku: Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Juga
datang mengadu untung etnis dari sebuah pulau kecil dekat pusat kerajaan
Majapahit ke wilayah pantai utara Kalimantan Barat ini.
Keturunan Laut (Melayu) diganggu ruh Puyang Gana yang terevolusi ke
etnis pendatang. Tak terhindarkan lagi terjadi bentrok fisik antara Melayu
dan etnis pendatang (Putra, 2014: 308).
Tahun 1999 terjadi kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan
sekitarnya. Sebelumnya, kerusuhan sudah pernah terjadi di Sambas dan sudah
berlangsung sekitar tujuh kali sejak tahun 1970. Namun, pada 1999 merupakan
yang terbesar dari akumulasi kejengkelan dari Melayu dan suku Dayak terhadap
ulah pendatang dari Madura. Akan tetapi, ketika ada warga Dayak yang menjadi
korban provokasi, panglima-panglimanya tak tinggal diam. “Mangkok Merah”
pun diedarkan. Tariu kembali diserukan (Putra, 2014: 309).
Awal peristiwa dilatar belakangi kasus pencurian ayam oleh seorang warga
Madura yang ditangkap dan dianiaya oleh warga masyarakat suku Melayu.
Peristiwa berkembang dengan terjadinya kerusuhan, pembakaran, pengrusakan,
perkelahian, penganiayaan, dan pembunuhan antara warga suku Melayu dan
warga suku Dayak menghadapi warga suku Madura yang meluas sampai ke
daerah sekitarnya. Telah terjadi pengungsian warga suku Madura secara besar-
besaran. Kemudian, isu ini dieksploitir oleh kelompok-kelompok tertentu untuk
kepentingannya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45
Akibat dari pertikaian tersebut, orang-orang keturunan Madura yang sudah
bermukim di Sambas sejak awal 1900-an ikut menanggung dosa perusuh. Korban
akibat kerusuhan Sambas terdiri dari 1.189 tewas, 168 orang luka berat, 34 orang
luka ringan, 3.833 orang rumahnya dibakar dan dirusak, 12 mobil, dan 9 motor
dibakar dan dirusak, 8 masjid/madrasah dirusak, 1 gudang dirusak, dan 29.823
warga Madura mengungsi (Wikipedia, Kerusuhan Sambas).
2.3.2 Latar Tempat
Banyak tempat yang melatari peristiwa yang terjadi di dalam novel
Ngayau. Akan tetapi, hanya beberapa tempat yang dipilih dan dianalisis. Beberapa
tempat tersebut dianalisis untuk menggambarkan unsur budaya. Beberapa tempat
tersebut adalah: (1) Negeri Poromuan, (2) Rumah Mei, dan (3) Hutan.
(1) Negeri Poromuan
Negeri Poromuan adalah salah satu tempat yang terkenal kesaktiannya.
Poromuan dikenal karena penduduk laki-lakinya yang mahir dalam hal perang. Di
tempat ini, Panglima Burung mengintai tempat perkemahan musuh untuk
memantau target yang akan di-kayau. Di sana, satu kemah terdiri atas tujuh laki-
laki dewasa yang selalu siap untuk berperang. Akan tetapi, pengintaian tersebut
sudah dirasakan oleh kepala pasukan pengayau yang peka terhadap tanda dan
peristiwa alam. Poromuan digambarkan sebagai kampung yang sama dengan
kampung Dayak yang lainnya. Memiliki kekuatan magis yang terdapat dalam
benda, pohon, dan patung-patung. Perhatikan kutipan berikut.
Poromuan sama seperti kampung-kampung Dayak yang lain. Artefak, bentuk, dan gaya perkampungan yang sama. Sama-sama yakin bahwa alam raya punya kekuatan magis. Kekuatan magis juga terdapat dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

46
setiap benda, termasuk pohon dan patung-patung. Maka, setiap akan masuk kampung, selalu ada tanda. Ada gerbang, pagar, tangga naik/turun, dan ada pantak (Putra, 2014: 181).
Sekarang, Poromuan dikenal sebagai daerah Ributn, satu kabupaten
dengan Jangkang, yakni Kabupaten Sanggau. Dibatasi oleh dua kecamatan (Putra,
2014: 27). Poromuan juga dijuliki negeri seribu tengkorak karena Poromuan
punya ksatria-ksatria tangguh yang tidak mudah ditundukkan dalam pengayauan
biasanya mereka keluar sebagai pemenang. Mereka menyimpan tengkorak musuh
sedemikian rupa dan dipajang, mungkin fungsinya mirip dengan piala di dunia
sport dan olahraga sebagai tanda bukti kemenangan, sekaligus kekuatan (Putra,
2014: 203).
(2) Rumah Mei
Dari celah-celah dinding kulit kayu, Mei mengintip asal suara yang
memekkan itu. kakinya bergetar ketakutan. Bulu kuduknya berdiri.
Mei melihat kerumunan massa berikatkan kepala dengan daun sabang
merah, muka dicat hitam, dan hanya biji mata yang dibiarkan tetap asli
(Putra, 2014: 53)
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa rumah Mei yang juga merupakan
toko kelontong melatari cerita. Saat tariu, Mei hanya berani mengintip suara dari
celah dinding rumahnya. Mei takut keluar karena saat itu, para pengayau yang
sudah dirasuki kekuatan magis hanya mencari orang Tionghoa saja untuk
ditangkap. Sedangkan, orang Dayak dibiarkan saja. Pengarang juga
menggambarkan bahwa rumah Lansau tidak jauh dari rumah Mei. Hanya
dipisahkan oleh aliran sungai. Penggambaran rumah Lansau jelas digambarkan
oleh pengarang dalam kutipan berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

47
Berseberangan dengan rumah tinggal Mei yang dipisah oleh sealir sungai,
agak sedikit naik, adalah rumah Lansau. Modelnya masih tradisional,
berbentuk panggung, disangga tiang setinggi dua meter dari tanah. Dari
celah jendela dan tempat ketinggian, dari rumah adat itu, dapat dipantau
keadaan di bawah dan di sekitarnya.
Baik Lansau maupun Mei tidak pernah tahu bahwa pemisahan tempat
tinggal itu dilakukan kompeni agar mudah memilah dan mengawasi gerak-
gerik penduduk (Putra, 2014: 56).
(3) Hutan
Hutan merupakan tempat di mana Kek Longa berburu. Saat itu, musim
kemarau, waktu yang dinantikan untuk menunggu binatang keluar hutan mencari
makan dan minum untuk bertahan hidup. Saat itu juga, Kek Longa berburu untuk
istrinya yang sedang hamil dan mengidam binatang buruan. Segala peralatan
berburu telah disiapkannya, seperti sumpit yang disebut ngansu, dan senjata laras
panjang yang disebut nganapm. Latar tempat di hutan terdapat dalam kutipan
berikut.
Kek Longa semakin ke dalam masuk hutan. Namun, sampai hari di
ambang sore, ia tak menangkap hewan seekor pun. jelang matahari
tenggelam, Kek Longa merasa lelah. Hatinya dirundung rasa was-was,
sebab seharian berburu, tak seekor pun binatang berhasil ditangkapnya.
Kek Longa makin diliputi rasa gelisah karena di istrinya di rumah sedang
hamil tua. Hasil buruannya ditunggu-tunggu, sebab sang istri mengidam
binatang buruan (Putra, 2014: 157).
2.3.3 Latar Sosial-Budaya
Latar sosial budaya mencakup penggambaran keadaan masyarakat,
kelompok sosial, dan sikapnya, bagaimana adat dan kebiasaan sehari-hari, cara
hidup, bahasa, dan beberapa hal lain yang melatari peristiwa. Terdapat latar sosial
dalam novel Ngayau yang meliputi cara hidup, makanan, dan bahasa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

48
Dalam novel Ngayau, cara hidup adalah mengenai bagaimana suku Dayak
menjalankan kehidupan bersama-sama dalam sebuah betang, baik antarsubsuku
Dayak maupun dengan suku lain.
Sering disebut “rumah panjang”, atau “rumah adat” karena bentuknya
memang panjang mencapai lebih dari 100 meter. Tiap-tiap keluarga
disekat-sekat dan dapat dikenali dari lawakng (pintu) yang setiap pintunya
memiliki anak tangga masing-masing (Putra, 2014: 23-24)
Dari kutipan di atas, diketahui bahwa kehidupan masyarakat suku Dayak
berbentuk komunal. Satu desanya terdiri dari satu rumah betang dan yang tinggal
di dalam satu betang tersebut merupakan satu keluarga. Kalau pun terdapat
keluarga baru di lawakng maka keluarga tersebut dapat menyambung bilik-bilik
yang sudah ada, atau membuat sekat di balai-balai yang sejak awal dirancang
cukup luas.
Dalam novel Ngayau juga terdapat penggambaran latar sosial berupa
makanan khas Tionghoa yaitu kwee cap. Kwee cap adalah makanan khas dari
etnis Tionghoa di Kalimantan Barat. Namun juga disukai oleh etnis lain, terutama
Dayak. Terbuat dari tepung, berwarna putih sebesar jari, dengan bumbu dan aneka
bahan khas Tionghoa. Dari bahannya, kwee cap adalah potongan kwetiau atau mie
lebar yang terbuat dari tepung beras. Lalu disiram dengan kuah dari kaldu tulang
babi dan minyak babi. Penggambaran latar sosial berupa makanan, terdapat dalam
kutipan kalimat yang diucapkan oleh Ben Teng sambil menikmati semangkok
kwee cap.
“Kita olang kejepit” kata Ben Teng, sembari menyantap Kwee Cap. Itu
adalah sendok yang terakhir (Putra, 2014: 62).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

49
Dalam novel Ngayau, penggunaan kosa kata bahasa daerah digambarkan
oleh pengarang. Pemilihan kosa kata membuat latar sosial budaya cukup kental.
Bahasa dan dialek yang digunakan para tokoh dapat diketahui darimana dan dari
etnis apa tokoh berasal. Dari segi bahasa, para tokoh dalam novel Ngayau dapat
menunjukkan bahwa mereka berasal dari suku Dayak atau dari etnis Tionghoa.
Hal ini ditandai dengan digunakannya kosa kata-kosa kata dari sub suku Dayak
Kanayatn, sub suku Dayak Djongkang, dan etnis Tionghoa.
2.4 Rangkuman
Demikianlah analisis pendekatan objektif dalam novel Ngayau karya
Masri Sareb Putra. Melalui hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa novel
tersebut memiliki dua tokoh utama yaitu Lansau dan Siat Mei. Dalam Ngayau
juga terdapat sepuluh tokoh tambahan yang berperan sebagai pelengkap cerita
yaitu (1) Siat Mei, (2) A pa Mei, (3) Ben Teng, (4) A kong Mei, (5) Ahong, (6)
Sinfu, (7) Sin sang, (8) Kek Longa, (9) Domia, dan (10) Domamakng Bunso.
Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh tambahan yang hadir di sekitar kedua
tokoh utama.
Dari analisis latar, juga dapat disimpulkan bahwa latar tempat yang
menunjukkan unsur budaya dalam novel Ngayau yaitu (1) Negeri Poromuan, (2)
Rumah Mei, dan (3) Hutan. Latar waktu yang melatari cerita yaitu pada tahun
1967 saat perang antara suku Dayak dan etnis Tionghoa karena provokasi.
Kemudian, tahun 1999 di Sambas saat terjadi kerusuhan antar etnis pendatang,
yaitu Melayu dan Madura. Latar sosial budaya dalam novel Ngayau yang meliputi
cara hidup, makanan, dan bahasa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

50
Dalam pembahasan bab II mengenai pendekatan objektif, terlihat bahwa
unsur-unsur budaya Dayak dan Tionghoa tergambar dalam analisis struktural,
yaitu: tokoh, penokohan, dan latar. Analisis struktur cerita dalam Ngayau
dilakukan terlebih dahulu untuk memahami dan memberi gambaran mengenai
tokoh, penokohan, dan latar. Unsur-unsur budaya akan diklasifikasikan oleh
peneliti ke dalam tujuh unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Hal tersebut
akan dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

51
BAB III
UNSUR-UNSUR BUDAYA DAYAK DAN TIONGHOA DALAM NOVEL
NGAYAU KARYA MASRI SAREB PUTRA
3.1 Pengantar
Pada bab III ini, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai unsur budaya
Dayak dan Tionghoa yang terdapat dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra.
Melalui analisis struktural yang meliputi tokoh, penokohan, dan latar yang telah
dibahas dalam bab II, dapat diketahui bahwa novel Ngayau terdapat unsur-unsur
budaya Dayak dan Tionghoa. Menurut Koentjaraningrat (1980: 180), kebudayaan
adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
Kebudayaan memiliki tujuh unsur, unsur-unsur kebudayaan itu adalah: (1)
Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Organisasi Sosial, (4) Sistem Peralatan
Hidup dan Teknologi, (5) Sistem Mata Pencaharian Hidup, (6) Sistem Religi, dan
(7) Kesenian.
Berikut diuraikan pembahasan terkait hasil penelitian dalam novel Ngayau
karya Masri Sareb Putra yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan Dayak dan
Tionghoa.
3.2 Unsur-Unsur Budaya Dayak dalam novel Ngayau Karya Masri Sareb
Putra
Dalam novel Ngayau, ditemukan enam unsur-unsur kebudayaan Dayak
yang meliputi: (1) Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Sistem Peralatan Hidup
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

52
dan Teknologi, (4) Sistem Mata Pencaharian Hidup, (5) Sistem Religi, dan (6)
Kesenian.
3.2.1 Bahasa
Bahasa adalah alat atau perwujuduan budaya yang digunakan manusia
untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan,maupun
gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau
kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain (Koentjaraningrat, 2002).
Sebagai orang Dayak, Masri Sareb Putra menggunakan beberapa bahasa
Dayak dari beberapa sub suku yang ada di Kalimantan Barat. Beberapa bahasa
sub suku Dayak yang digunakan yaitu bahasa Dayak Kanayatn dan Bahasa Dayak
Djongkang. Selain itu, pengarang juga menggunakan bahasa Tionghoa, dialek
Hakka, dan Dialek Tio Ciu. Bahasa dalam novel Ngayau berupa bahasa bahasa
verbal dan bahasa non verbal. Bahasa verbal meliputi bahasa lisan dan tulisan
yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu penggunaan bahasa Dayak Kanayatn
dan Bahasa Dayak Djongkang (Djo). Bahasa nonverbal meliputi tanda dan
simbol, yaitu tanda dari suara gong, tanda dari suara burung , dan penggunaan
sandi.
Dalam novel Ngayau, terdapat penggunaan bahasa Dayak Kanayatn.
Bahasa Dayak Kanayatn adalah sebuah bahasa yang dituturkan di wilayah
Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Bahasa Dayak Kanayatn mempunyai
beberapa dialek, antara lain Ambawang, Kendayan, Ahe, dan Selako. Dalam
bahasa Dayak Kanayatn memakai dialek bahasa ahe/nana’ serta damea/jare.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53
“Pariksa samua!” kata seseorang. Ia merasa heran! Logat yang digunakan adalah “Ahe”, khas suku Dayak Kanayatn; tapi nada dan tekanannya persis seseorang yang tadi turun dari pohon kelapa. “Barek kamudak nian bajalatn!” kata suara mirip seseorang yang beberapa jam yang lalu tadi turun dari pohon kelapa.
Dalam bahasa Kanayatn, pariksa samua berarti periksa semua!. Barek
kamudak nian bajalatn adalah Dialek Kanayatn yang berarti: suruh mereka jalan!
Dalam novel Ngayau, terdapat kosa kata Jubata. Jubata adalah sebutan
Tuhan orang Dayak Kanayatn. Jubata inilah yang dikatakan menurunkan adat
kepada nenek moyang orang Dayak yang berlokasi di Bukit Bawakng. Di mana
sekarang lokasi tersebut sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bengkayang. Kata
Jubata ditemui dalam kutipan berikut.
Ada yang memanggil-manggil nama ayah dan suaminya. Dan tidak sedikit
yang menyerukan nama Jubata (Putra, 2014: 88).
Selain kosakata Jubata, juga terdapat Tariu adalah upacara memanggil roh
para leluhur yang dilakukan oleh seorang Panglima Suku Dayak untuk
mengetahui kapan saat yang tepat untuk memulai perang. Kosakata tariu
ditemukan dalam kutipan berikut.
“Mangkok merah” dan tariu satu paket dalam perang gaib itu. Oleh
karena itu, supaya tidak terjadi pertumpahan darah, lebih baik mencegah
sebelum keputusan dijatuhkan. Sebab, mengedarkan “mangkok merah”
tanpa alasan yang sesuai, akan menuai sanksi hukum adat” (Putra, 2014:
136-137).
Dalam novel Ngayau juga terdapat penggunaan Bahasa Dayak. Djongkang
Bahasa Dayak Djongkang adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh orang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

54
Dayak sub suku Jangkang yang terdapat di wilayah Jangkang, Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat. Bahasa Djongkang mempunyai dua dialek yaitu
dialek Jangkang Sejati dan dialek Pompakng. Berikut ini dikemukakan temuan
kutipan bahasa Dayak Djongkang. Bepacu adalah bagian dari acara perkawinan
dalam budaya Dayak, yaitu memberikan bekal, nasihat, serta petuah kepada kedua
mempelai bagaimana seharusnya menjalani kehidupan baru dalam berumah
tangga. Kata bepacu ditemukan dalam kutipan berikut.
Tuak ini yang nanti dibuka dan dibagi-bagi pada puncak pesta perkawinan,
yakni setelah acara bepacu.
“Membatalkan perkawinan yang tinggal menunggu jam?” Siat Mei
berusaha meluluhkan hati a pa-nya. (Putra, 2014: 50)
Dalam bahasa Dayak Djo berarti pemakaman umum tua yang sudah tidak
terpakai lagi.
Senantiasa meletakkan apa saja, makanan dan minuman, termasuk barang
berharga, pada pongaretn yang dianggap rumah tinggal para leluhur. (Putra,
2014: 155).
Selain penggunaan beberapa kosa kata, pengarang juga menggambarkan
bahasa Dayak Djongkang dalam percakapan sebagai berikut.
“Ah. . . mak mok nyen, tulah boh oh omo macatn!” (Jika nekad juga ngayau,
kamu akan tulah, macat)”
“Mae lokng koh tulah. Koto maeh eh!” (Mana saya mau tulah. Rasakan
seranganku!)
Macatn Gaikng makin kesetanan.
“Kih sani neh onya dek mora boranak seh?” (Mana ibu-ibu yang baru saja
melahirkan?” (Putra, 2014: 183).
Dalam novel Ngayau, terdapat juga penggunaan kata ngabas poya.
Pengarang menggambarkan bahwa manusia Dayak tidak dapat terlepas dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

55
hutan. Dilihat dari asal-usulnya katanya, ngabas poya berarti melihat atau
mengamati lahan atau tanah yang akan menjadi areal perladangan (Putra, 2014:
235). Penggunaan kosa kata ngabas poya ditemukan dalam kutipan berikut.
Diawali dengan ngabas poya yang akan dihitung menurut tarikh Masehi
jatuh pada akhir bulan Mei.
Menebas atau membersihkan lahan dilakukan pada bulan Juni. (Putra, 2014:
236).
Dalam novel Ngayau, terdapat penggunaan tanda. Seperti yang diketahui,
manusia Dayak tidak dapat lepas dari simbol. Boleh dikatakan, hampir tidak ada
hari orang Dayak tanpa simbol. Tak pelak lagi, orang Dayak adalah “homo
symbolicum”. (Putra, 2014: 182).
Terdapat tanda dari suara Gong, Masyarakat Dayak masih menggunakan
gong sebagai bentuk komunikasi non-verbal. Penggunaan gong sebagai alat
pemberitahuan dan informasi berkomunikasi kepada masyarakat yang digunakan
dengan cara dipukul, cara pemberitahuan tentang suatu kejadian tertentu
berbeda-beda cara pemukulannya seperti pada acara perkawinan maupun
upacara kematian. Dalam upacara perkawinan Dayak Ngaju yang berisi tindakan
simbolik dengan nilai dan norma. Hal ini sesuai dengan pesan yang disampaikan
yaitu tentang bentuk nilai-nilai budaya Dayak Ngaju dengan maksud agar kedua
pengantin dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga
mereka kelak.
Pada masyarakat Dayak Pesaguan, gong tidak sekadar alat musik atau
simbol dalam upacara seremonial. Gong juga untuk membayar hukuman
mengganti suara orang yang meninggal karena pembunuhan (Sukanda, 2012).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

56
Dalam novel Ngayau, bunyi gong pada malam itu, bertujuan memanggil warga
untuk bermusyawarah dan menyusun strategi untuk menghadapi pasukan
pengayau dari negeri Poromuan.
Dari gendang cepat lambatnya, serta caranya memukul, warga mafhum
makna bunyi gong. Ada bunyi gong yang minta pertolongan atau tanda
kritis. Ada bunyi gong ketika pesta pora. Ada bunyi gong yang menandakan
ada warga yang meninggal. Dan ada bunyi gong yang memanggil agar
warga datang ke pertemuan untuk musyawarah (Putra, 2014: 34).
Dalam Ngayau juga terdapat tanda dari suara burung. Pengarang
menggambarkan bahwa orang Dayak sangat percaya dan mahir dalam membaca
tanda-tanda burung. Jika di kanan jalan hendak pergi ngayau, maka akan
menang. Jika suara burung dari arah sebelah kiri, sebaliknya ngayau dibatalkan,
menunggu hari baik tiba. Setidaknya, di kalangan ibanik percaya dan
menganggap keramat burung-burung ini: Tujuh macam burung yang sangat
penting dalam kehidupan Ibanik, yaitu: Ketupung, Beragai, Bejampung,
Pangkas, Embuas, Papau, dan Nendak. Saat hendak bercocok tanam atau
berhuma, ngayau, berburu, atau pergi ke hutan harus mendengar petunjuk suara
burung (Putra, 2015:13).
Demikianlah pada hari yang ditetapkan.
Ketika pagi tiba. Bunyi burung terdengar datang dari sebelah kanan jalan
pergi ngayau, berangkatlah para pengayau ke negeri musuh dipimpin
panglimanya, Domamakng Bunso. (Putra, 2014: 170).
Burung Bogurak, bentuknya sebesar murai batu, berwarna hitam, bersuara
nyaring lantang. Jika di hutan, sering suaranya menakutkan karena memiliki
kekuatan magis. Orang Dayak tertentu menganggapnya burung keramat dan
hewan jadi-jadian. Dayak Djongkang percaya bahwa burung bogurak adalah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

57
manifestasi dari hantu somatianak, yaitu ruh orang yang meninggal karena
bersalin (Putra, 2014: 198).
Domamakng Bunso lalu mengambil sehelai daun yang diselip di telinganya.
Daun sabang merah. Dilemparnya ke arah suara orang nyorao tadi. Itu
adalah suara burung bogurak yang jika orang takut mendengarnya, dapat
berubah jadi hantu somantianak yang sangat menakutkan. (Putra, 2014:
198).
Terdapat juga tanda dari bambu. Suku Dayak menggunakan bambu untuk
beberapa keperluan. Salah satunya mengadakan ritual. Ada banyak hal yang
digunakan sebagai simbol yang memiliki makna tersendiri dan tak jarang
dianggap sebagai suatu tanda kehadiran penguasa alam atas.
Kerap ada pula tanda dari bambu muda yang diikatkan dengan janur kelapa
sebagai tanda ada orang sakit, berkabung, atau ada wanita yang baru saja
melahirkan. (Putra, 2014: 181).
Dalam novel Ngayau juga terdapat penggunaan sandi. Manfaat
penggunaan sandi saat tariu, manusia-manusia kepala merah hanya dapat
mengenal sasaran dan bukan sasaran. Sandi para pengayau dalam Ngayau saat
tariu berlangsung, yaitu 2-B, singkatan dari Bakar dan Bunuh .
Herman Josef van Hulten, saksi sejarah, mencatat demikian:
Perang itu tidak akan ditujukan kepada kaum Cina sebagai manusia,
melainkan ditujukan kepada semua milik mereka. Ini terbukti dari
perampokan atas harta benda dan milik mereka, toko, dan tanah. Mereka
harus memegang teguh disiplin yang diperintahkan dan harus bisa
menghindari dua hal yang didahului dengn huruf “b”, yakni: bakar dan
bunuh. Dua ketentuan itu saya dengar sendiri dari seorang panglima
(pimpinan dalam pertempuran) yang disampaikan dengan penuh
keyakinan kepada rekan-rekan seperjuangannya…. Peristiwa itu terjadi di
rumh seorang guru Toho, 18 km dari Menjalin, Hulten dalam Putra (2014:
141).
Pada akhirnya, warga Dayak benar-benar dipakai tangannya menghalau
etnis Tionghoa dari pedalaman ke kota. Pada akhirnya, warga Dayak yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

58
terpancing melanggar kesepakatan untuk tidak melakukan 2-B. Namun, lewat
pembacaan mantra dan tariu, manusia-manusia kepala merah hanya mengenal
sasaran dan bukan (Putra, 2014: 144).
3.2.2 Sistem Pengetahuan
Dalam Ngayau, terdapat tiga sistem pengetahuan yang dimiliki oleh
masyarakat Dayak yaitu: (1) pengetahuan tentang musim, (2) pengetahuan tentang
flora, (3) pengetahun tentang fauna, dan (4) adat istiadat.
3.2.2.1 Membaca Musim
Suatu hari, di bulan yang panas. Kemarau hampir mengeringkan sungai.
Saat yang tepat untuk berburu sebab binatang-binatang keluar hutan semua
untuk mencari makan dan minum. (Putra, 2014: 157).
Dari kutipan tersebut, orang Dayak memiliki pengetahuan tentang alam.
Mereka akan berburu pada musim kemarau. Seperti yang dilakukan Kek Longa. Ia
berburu untuk istrinya yang sedang hamil dan mengidam binatang buruan.
Biasanya, berburu dilakukan saat musim panen dan jika akan melaksanakan
tradisi atau pesta. Mereka tidak akan berburu jika persediaan makanan masih
banyak. Ada pun binatang buruan bisa berupa babi hutan, kijang, rusa, kancil,
ular, mau pun hewan lainnya yang biasa dikonsumsi masyarakat. Salah satu
bentuk kearifan lokal sub-sub suku Dayak di Kalimantan adalah bagaimana
mereka memprediksi datangnya musim kemarau.
Kebutuhan masyarakat Dayak akan padi di ladang telah menghasilkan
sistem pengetahuan yang dapat memahami gejala alam yang berpengaruh
terhadap sistem perladangan. Menurut Mudiyono (1995), pengetahuan tentang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

59
gejala alam yang berkaitan dengan perladangan orang Dayak di Kalimantan
adalah pengetahuan tentang bintang tujuh. Jika bintang tujuh sudah timbul pada
malam hari, udara akan menjadi dingin. Itulah pertanda bahwa sudah tiba
waktunya untuk membuka ladang. Jika bintang tujuh berada di timur, sedangkan
bintang satu lebih rendah dari bintang tujuh, hal itu menandakan bahwa orang
Dayak sudah bisa menanam padi. Akan tetapi, bila di langit tampak garis seperti
tembok dan awan yang menyerupai garis seperti sisik ikan, maka orang
mengerahui bahwa musim kemarau telah tiba. Sebaliknya, jika langit terlihat
memerah pada pagi hari dan awan menggumpal seperti gunung, itu adalah
pertanda bahwa musim hujan telah tiba. Gejala datangnya musim hujan dapat pula
diketahui apabila pohon buah-buah banyak yang berbunga.
3.2.2.2 Sistem Pengetahuan Alam Flora
(1) Daun Sabang Merah
Daun berwana hijau, kemerahan, lonjong, biasa dipakai dalam upacara-upacara
suku Dayak (Putra, 2014: 229).
Lansau tahu kebiasaan itu. maka selain mengikat kedua tangan Mei dan
ayahnya dengan sesobek kain, juga membungkam mulut mereka, pada daun
telinga kedua warga Tionghoa itu diselipnya sehelai daun: sabang merah.
(Putra, 2014: 65).
Dalam novel Ngayau, daun sabang merah adalah pertanda bagi makhluk
gaib bahwa yang bersangkutan bukan sasaran saat terjadinya perang. Tentu saja,
sebelum diselip pada daun telinga, dibacakan mantra terlebih dahulu, semacam
kata kunci, agar yang bersangkutan terbaca bukan musuh yang harus dienyahkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

60
Sabang merah sebagai tanda pengenal. Di antara pertanyaan yang
berkecamuk itu, a pa Mei merasa pada daun telinganya terselip sehelai daun:
sabang merah.
“Mungkin ini tanda pengenal itu!” batinnya. Pantas saja manusia kepala
merah tidak pernah salah sasaran!
A pa Mei merasa ini sebuah perang yang fair, sekaligus gaib. Ia ingat,
sehelai daun sabang merah tadi diselipkan oleh Lansau setelah membaca
rapalan, seperti sebuah mantra. (Putra, 2014: 93).
Dalam kehidupan sehari-hari, daun sabang merah biasanya digunakan
sebagai tanaman hias yang ditanam di pekarangan rumah. Selain itu juga, tanaman
ini ditanam di sekitar rumah bertujuan agar ketika dibutuhkan dapat langsung
diambil dan diolah. Daun sabang merah juga memiliki beberapa khasiat untuk
menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di tubuh. Beberapa khasiat tanaman
andong yaitu untuk menghentikan pendarahan, diare, dapat menyembuhkan
gigitan hewan berbisa, dan dapat menyembuhkan wasir.
3.2.2.3 Sistem Pengetahuan Adat-istiadat
Dalam novel Ngayau, hukum adat diciptakan berbedasarkan pengalaman
dari Bagumban Berderai Darat. Suatu hari, para peladang melihat tamu asing yaitu
Bagumban Berderai Darat (selanjutnya disingkat BDD) yang berjalan tetapi tidak
membawa api. Setelah ditawari sampai tiga kali, ia pun menginap di salah satu
rumah warga. Di sana, BDD sudah dihidangkan makanan oleh tuan rumah. Hal
tersebut terlihat dalam kutipan berikut.
Jelang malam, setiap rumah Dayak yang tempat tamu menginap, sesuai
adat, harus memberi makan kepada tamu tersebut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

61
Jika tidak diberi makan, dan tamu asing sampai kelaparan, maka si empunya
rumah akan dikenakan adat.
Dakwaan kena hukum adat adalah menelantarkan tamu, sebab tamu
dipercaya mendatangkan berkah. Bagi orang Dayak, tamu sepertinya halnya
rezeki yang datang nomplok, jangankan ditolak, diminta iya (2014: 246).
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa betapa orang Dayak menghormati
tamu asing yang datang dan dianggap sebagai rezeki yang diberikan oleh Tuhan.
Adat orang Dayak, terutama Dayak Djongkang, jika belum hendak makan atau
minum, maka cukup menyentuh dengan ujung jari saja, sambil mengucap
“polopas” (nyicipi) atau tabek asakng yang berarti menahan nafsu (Putra, 2014:
245). Jika tidak menyentuh, maka dipercaya dapat terkena marabahaya, seperti
kecelakaan, luka, dan sebagainya.
Hukum adat ini masih berlaku, terutama di Kecamatan Jangkang, tertuang
dalam hukum Adat Bab 6, pasal 2, ayat 4 tentang “Tidak memberi
makan/minum pada tamu yang diundang atau menginap (Putra, 2014: 245
Pengarang mengambarkan bahwa tidak sempat mencicipi masakan tersebut
dan memilih mandi terlebih dahulu. Ia pun tidak melakukan polopas. Di
pemandian, BDD merasa ada yang mengganggunya, sebuah tangan menariknya
ke suatu tempat. Ia tersadar saat sudah berada di puncak pohon ketapang.
Ternyata, yang menculiknya adalah ratu hutan, sejenis kera yang disebut mayas.
Mayas adalah salah satu spesies cerdas yang juga jarang kontak dengan manusia
secara langsung (Putra, 2014: 24). Sudah lama mayas tersebut menginginkan
pasangan. Ia pun mulai mencintai BDD dan ingin menjadi pasangannya. BDD
memilih berpura-pura tunduk pada kemauan si ratu mayas daripada celaka. Ia pun
ingin lepas dari penjara ratu mayas dengan cara bekerja dan memanjakan si ratu.
Dapat dilihat dalam kutipan berikut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

62
Sedikit demi sedikit dilobanginya bagian bawah bambu itu. agar air
sehabis diciduk dan bambu terisi penuh, begitu tiba di istana pucuk
ketapang, menjadi habis dan kosonglah air dalam wadah bambu itu. Maka
ratu mayas akan kembali lagi ke sungai untuk menimba air. Saat itu
kesempatan untuk meloloskan diri nanti (Putra, 2014: 251).
Saat ratu mayas menimba air, BDD turun ke tanah dengan seutas tali. Ia
pergi dari markas ratu mayas. Agar tidak ketahuan, BDD membuat jejak kakinya
di empat penjuru mata angin. BDD pun berhasil lolos. Berdasarkan
pengalamannya saat di tawan oleh ratu mayas, ia menyusun peraturan hukum adat
istiadat yang intinya: seseorang tidak boleh secara paksa dikawinkan dengan
pihak lain jika dari dalam dirinya tidak timbul rasa suka dan rasa cinta (Putra,
2014: 254). Dalam hukum adat dikerajaan BDD, ia mengharamkan satu gender
lebih dihormati dari gender lainnya. Keduanya harus saling melengkapi.
3.2.3 Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi
Sistem peralatan hidup dan teknologi meliputi alat-alat produksi, senjata,
wadah, makanan, dan jamu-jamuan, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung,
dan perumahan, serta alat-alat transportasi (Koentjaraningrat, 2014: 22). Dalam
novel Ngayau, ditemukan unsur-unsur kebudayaan berupa sistem peralatan dan
teknologi Dayak yang meliputi senjata, tempat berlindung, perumahan, alat
produksi, dan makanan.
3.2.3.1 Senjata
Dalam novel Ngayau, terdapat beberapa senjata yang digunakan oleh Kek
Longa yaitu berupa alat-alat yang biasa digunakan untuk berburu yaitu sumpit,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

63
tombak, tikak, pongamik, parang, bikas, dan belantik. Penggunaan senjata tersebut
ditemukan dalam kutipan-kutipan berikut.
Sebelum merebahkan diri, Kek Longa melepas semua senjata dan alat-alat
berburu, seperti: sumpit, tombak, tikak, pongamik, dan parang yang
disarungkan di pinggang (Putra, 2014: 158).
Rintangan yang keenam ialah belantik. Busur dari bambu sebesar ibu jari
orang dewasa itu siap menembusi paha jika terlepas. Untung Domamakng
Bunso segera mencegahnya bikas dan mengambilnya (Putra, 2014: 203).
3.2.3.2 Tempat Berlindung
Polaman merupakan pondok semipermanen, tempat menginap, disertai
bekal secukupnya (Putra, 2014: 196). Polaman terletak agak jauh dari
permukiman warga. Biasanya polaman didirikan di pinggir kebun atau ladang dan
digunakan pada saat musim me-nugal atau menanam padi. Pemilik ladang
bermalam di polaman karena ingin menyiapkan segala peralatan menanam padi,
benih-benih padi yang akan ditaburkan, makanan, minuman, dan segala keperluan
yang berkaitan dengan kegiatan menanam padi. Dalam novel Ngayau, yang
menggunakan polaman adalah Domamakng Bunso. Ia menginap di sana untuk
beristirahat karena sedang mengolah rimba untuk dijadikan ladang. Tempat
berlindung berupa polaman terdapat dalam kutipan berikut.
Dengan santun, Boraket menjelaskan adik bungsunya sedang tidak di
rumah, ada di polaman karena sedang membuka hutan rimba untuk ladang
baru.
Setelah mendapat petunjuk di mana polaman itu maka prajurit utusan pergi
menemui Domamakng Bunso. Setelah sampai di polaman bernama Tinyan,
prajurit pasukan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka
(Putra, 2014: 196).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

64
3.2.3.3 Perumahan
Betang merupakan perumahan yang berupa rumah adat suku Dayak
Kalimantan. Betang biasanya ditemuakan di daerah hulu sungai yang menjadi
pemukiman suku Dayak. Betang didirikan tidak hanya sebagai tempat tinggal.
Namun, rumah betang memiliki makna dan simbol. Rumah betang berbentuk
panggung dan panjang. Berbentuk sedemikian rupa, betang memiliki fungsi
tertentu. Bentuk rumah betang yang berbentuk memiliki beberapa fungsi, yaitu:
(1) untuk menghindari banjir karena banyak rumah betang yang dibangun
dipinggir sungai, (2) untuk melindungi penghuninya dari binatang buas, (3) untuk
melindungi penghuninya dari musuh (Get Borneo, 2015). Dalam novel Ngayau,
betang digambarkan sebagai sebuah tempat tinggal komunal. Kampung Jangkang
berencana mendirikan betang. Mendirikan betang pun tidak sembarangan, Macatn
Gaikng yang merupakan petinggi kampung ingin mengadakan boraupm dan
mencari waktu yang tepat. Pada saat boraupm tersebut, Macatn Gaikng juga ingin
menyampaikan hal lain yang berkaitan dengan budaya Dayak kepada warga. Hal
tersebut terdapat dalam kutipan berikut.
Kesempatan itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh petinggi kampung.
Bukan hanya sebatas menyusun taktik dan strategi perang, melainkan juga
ajang menjelaskan adat istiadat dan tradisi, memberikan motivasi,
sekaligus menggelorakan semangat perang kepada seluruh warga (Putra,
2014: 35).
Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah betang harus memenuhi
beberapa persyaratan. Hulunya harus searah dengan matahari terbenam. Hal ini
dianggap sebagai simbol dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari
matahari terbit dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Semua suku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

65
Dayak, terkecuali suku Dayak Punan yang hdiup mengembara, pada mulanya
berdiam dalam kebersamaan hidup secara komunal di rumah betang, yang lazim
disebut Lou, Lamin, Betang, dan Lewu Hante (Wikipedia, Rumah Betang). Dalam
novel Ngayau, ciri-cir, fungsi, dan hal-hal betang dijelaskan secara rinci oleh
pengarang dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Lazimnya, betang terdiri atas 50-100 lawakng. Tiap berang merupakan
sebuah kampung atau desa yang dikepalai seorang kepala atau pemimpin.
Setiap lawakng memiliki satu tangga yang fungsinya untuk naik dan turun.
Tinggi tangga disesuaikan dengan tinggi betang, antara 3-4 meter dari
permukaan tanah. Posisi tangga dapat dibalik untuk menghindari
masuknya orang yang berniat buruk atau binatang buas, selain berfungsi
untuk melindungi dari ancaman banjir atau genangan air.
Tiap lawakng memiliki balai-balai di muka dan dapur di belakang. Jika
ada tamu yang hendak menginap maka segala sesuatunya, mulai dari
akomodasi sampai keamanan, menjadi tanggung jawab keluarga tempat
tamu menginap. Jika terdapat keluarga baru di lawakng maka keluarga
tersebut dapat menyambung bilik-bilik yang sudah ada, atau membuat
sekat di balai-balai yang sejak awal dirancang cukup luas pada suku Dayak
tertentu, bahkan terdapat pintu darurat yang menhubungkan satu lawakng
dengan lawakng yang lain agar mudah berkomunikasi, atau memusatkan
kekuatan, apabila sewaktu-waktu ada bahaya mengancam.
Di belakang betang terdapat lumbung-lumbung padi. Lumbung padi juga
tinggi tiang-tiangnya. Banyak upacara suku Dayak diadakan di lumbung.
Orang Dayak yakin bahwa padi mempunyai semangat atau nyawa. Oleh
sebab itu, tempat penyimpanan padi haruslah ditata dan dipelihara
sedemikian rupa (Putra, 2014: 38).
3.2.3.4 Alat Produksi
Alat produksi adalah alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Mulai dari
alat sederhana seperti batu untuk menumbuk terigu, sampai yang agak kompleks
seperti alat untuk menenun kain (Koentjaraningrat, 1990: 345). Dengan kata lain,
alat produksi adalah benda yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Alat
produksi yang terdapat dalam novel Ngayau adalah bambu yang merupakan alat
untuk memasak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

66
Orang Dayak ke hutan untuk berburu, bekerja, atau ngayau biasanya tidak
membawa alat-alat memasak, kecuali api, garam, dan nasi. Mereka
menggunakan ruas-ruas bambu sebagai alat-alat memasak, setelah dipotong-
potong, dibersihkan, lalu dipanggang dengan nyala atau bara api sampai
matang. Muncul aroma khas, sangat harum dari bambu itu (Putra, 2014: 27).
Manusia Dayak ternyata tak kehabisan akal, selalu kreatif di hutan sekalipun,
sehingga bisa survive. Masakan dalam buluh bambu muda disebut pansoh
(Putra, 2014: 27).
3.2.3.5 Makanan
Dalam novel Ngayau, jelas digambarkan bahwa tuak merupakan minuman
tradisional suku Dayak. Biasanya tuak digunakan untuk menjamu tamu dan
minuman wajib saat prosesi perkawinan adat suku Dayak. Dalam Ngayau, cara
pembuatan tuak dijelaskan secara rinci oleh pengarang. Mulai dari apa saja bahan
yang akan digunakan hingga alat apa saja yang akan digunakan untuk membuat
dan menyimpan tuak.
Persiapan upacara perkawinan sudah dilakukan. Yakni upacara adat lengkap.
Untuk itu, ibu Siat Mei dan ibu Lansau sudah dari enam bulan lalu memasak
ketan di rumah masing-masing secara bergantian.
Beras ketan hitan dan putih dimasak dalam periuk yang berbeda. Lalu diambil
dengan sendok terbuat dari kayu, kemudian dihampar di sebuah tikar khusus
terbuat dari anyaman rotan yang disebut “kolayak”, dan setelah dingin nasi
ketan itu ditabur ragi (Putra, 2014: 48-49).
Sama seperti beberapa suku lainnya, suku Dayak juga memiliki minuman
tradisional yaitu tuak. Tuak adalah minuman hasil fermentasi dari beras ketan.
Minuman ini mengandung alkohol. Dalam suku Dayak, tuak menjadi simbol
kebersamaan, diartikan untuk mempererat persaudaraan. Biasanya, tuak selalu
disediakan saat upacara adat perkawinan. Seperti minuman alkohol pada
umumnya, tuak dapat menyebabkan mabuk jika diminum berlebihan. Akan tetapi,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

67
bagi orang Dayak, sedikit meminum tuak biasa mengurangi lelah, mengobati sakit
maag, dan mengobati malaria.
3.2.4. Sistem Mata Pencaharian Hidup
Suku Dayak memiliki mata pencaharian yang menjadi pokok penghidupan
masyarakat. Sumber daya alam Kalimantan diberdayakan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Dalam Ngayau, ditemukan dua macam sistem mata
pencaharian hidup suku Dayak yaitu berburu, kerja tambang, dan berladang.
(1) Berburu
Suatu hari, di bulan yang panas. Kemarau hampir mengeringkan sungai.
Saat yang tepat untuk berburu sebab binatang-binatang keluar hutan semua
untuk mencari makan dan minum .
Pergilah berburu ke hutan seorang pria gagah perkasa. Lelaki yang berburu itu
digelari “Kek Longa” oleh karena tubuhnya tinggi, lagi kekar. Dalam bahasa
Dayak, jika berburu menggunakan sumpit disebut ngansu, sedangkan
menggunakan senjata laras disebut ngimpak atau nganap (Putra, 2014: 157).
(2) Berladang
Semacam land clearing, kegiatan membersihkan lahan, atau tanaman yang
halus dan kecil-kecil dibersihkan menggunakan alat parang, sedangkan yang lebih
besar dari kepala menggunakan beliung. (Putra, 2014: 236). Dalam novel Ngayau,
pengarang secara rinci menjelaskan mengenai siklus masa perladangan dalam
suku Dayak, apa saja yang ditanam, dan tahap-tahap apa saja yang dilakukan.
Sistem perladangan dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut.
Menjadi kebiasaan sejak saat itu, umur seorang anak dihitung dari berapa
kali berladang/berhuma. Siklus masa perladangan adalah sekali setahun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

68
Diawali dengan ngabas poya yang jika dihitung menurut tarikh Masehi jatuh
pada akhir bulan Mei. Menebas atau membersihkan lahan dilakukan pada
bulan Juni.
Dibiarkan selama dua bulan menunggu kemarau yang mengeringkan semua
tebangan di lahan baru, lahan dibakar pada awal bulan Agustus bersamaan
waktunya dengan puncak musim kemarau.
Batas ladang dibuat sedemikian rupa, sehingga nanti jika lahan dibakar api
tidak memakan dan membumihanguskan lahan orang lain. Jika sampai
terjadi kebakaran maka si empunya asal mula api atau si empunya lahan
harus membayar adat kepada orang yang lahannya kena bakar.
Hukum adat ini untuk mencegah jangan sampai api membumihanguskan
semua flora dan fauna di suatu lahan yang akan mengakibatkan
terganggunya keseimbangan ekosistem.
Setelah lahan dibakar, antara 1-2 minggu di akhir Agustus dan jelang
September, biasanya musim hujan. Hujan yang mulai turun pada bulan yang
berujung “ber” akan membasahi lahan yang sudah dibakar. Lalu secara
alamiah membentuknya menjadi tanah bakar, atau meninggalkan sisa
pembakaran yang menyuburkan tanaman. Biasanya, waktu yang pas mulai
menanam (menugal) adalah pada minggu akhir bulan Agustus.
Padi serta tanaman ladang sudah mulai tumbuh subur setelah sebulan lebih
ditanami. Namun, bersamaan dengan itu, tumbuh juga rumput-rumput.
Masa merumput adalh Desember-Januari. Lalu, padi dan jagung berbuah
dan panen bulan Februari.
Seminggu sebelum panen, ketika padi-padi di ladang sedang menguning,
ketika itulah masa ngayau. Kepala-kepala hasil kayauan akan ditarikan pada
gawai “notokng”, bersamaan dengan puncak gawai yang jatuh pada akhir
April atau awal Mei. (Putra, 2014: 238)
Yang ditanam di ladang adalah tanaman palawija.
Areal bekas huma itu disebut juga jamih yang setelah tanaman utaama padi
dan jagung masih ada tanaman setelahnya, seperti: ubi kayu, keladi, jahe,
terong, bawang dayak, tebu, tebu telor, dan sebagainya. Tanaman-tanaman
itu dibudidayakan di bekas ladang sehabis panen padi.
Setelah sebuah lahan purnatanam dan mati maa lahan itu diganti tanaman
liar. Orang Dayak menamakannya “bawas”. Lahan yang sama baru boleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

69
dibuka kembali pada siklus 15 tahun kemudian setelah humus mulai tersedia
dan ekosistem di sekitarnya sudah seimbang kembali.
. . . . semua ladang penduduk wilayah kerajaan Bagumban Berderai Darat
tumbuh subur.
Penduduk menamakan panen itu “mengetam” . di masa lalu, dan kini pun masih
di pedalaman, memanen padi bukan menggunakan alat potong padi (ani ani) yang
memotong tangkai padi satu demi satu, melainkan menggunakan dua genggam
tangan (Putra, 2014: 238).
Setelah tiba waktunya panen orang Dayak memetik padi di ladang secara
alami, menggunakan tangan. Setangkai padi, segenggam tangan.
Mereka sangat terampil. Wadah yang lebih kecil dinamakan “torokot”,
diikat dipinggang setelah penuh dengan padi, dimuat dalam keranjang
bernama “toranyankng” (Putra, 2014: 239).
Tahap selanjutnya yaitu padi di letakkan di sebuah tempat penyimpanan.
Agar padat berisi, padi didorong masuk setiap keranjang dengan ujung
sebatang kayu tumpul agar tidak menyisakan rongga sedikit pun.
. . .
Pada tahun pertama pemerintahan Bagumban Berderai Darat, seluruh
wilayah kerajaan semua panen berhasil.
. . .
Padi dalam keranjang lalu dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu tempat
penyimpanan padi atau dalam bahasa Dayak Djangkang yang disebut “jurokng”.
Tingginya dari permukaan tanah 2-3 meter, tiang-tiang penyangganya bulat, di
tiap tiang dibuatkan lingkaran dari kayu untuk mencegah tikus atau binatang
lainnya masuk. Disediakan anak tangga untuk masuk lumbung yang dapat
dipindah ke suatu tempat setelah digunakan (Putra, 2014: 240).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

70
Padi hasil panen pada tahun sebelumnya dinamakan “podi toyatn”, atau padi
lama. Padi yang diolah menjadi beras, dan kemudian dikonsumsi sehari-hari
menjadi nasi, haruslah dari tumpukan atau persediaan padi yang
sebelumnya.
Ukuran kaya pada waktu itu adalah jika sebuah keluarga punya persediaan padi
tahun-tahun sebelumnya. Jadi, mirip dengan simpanan deposito pada masa kini.
(Putra, 2014: 240).
(3) Kerja Tambang
Dalam novel Ngayau, digambarkan oleh pengarang bahwa kerja tambang
merupakan salah satu mata pencaharian suku Dayak. Saat itu, banyak petambang
dari etnis Tionghoa sukses dan memiliki jaringan yang luas. Hal tersebut memicu
kompeni untuk memprovokasi. Kompeni takut jika suku Dayak dan etnis
Tionghoa menjadi penguasa di Borneo. Hal itulah yang menyebabkan perang
antara Dayak dan Tionghoa. Penggambaran kerja tambang terdapat dalam kutipan
berikut.
Di sebuah ladang tambang daerah Lara yang kemudian hari menjadi
wilayah Kabupaten Sambas. Kompeni melihat ancaman. Para pekerja
tambang imigran dari negeri Cina sukses dan berhasil menjalin relasi lebih
luas sampai ke luar wilayah nusantara ketika itu. Petambang Dayak dan
petambang imigran Cina sengaja dibentur-benturkan, sehingga terjadi
perang Dayak vs imigran Cina, wilayah yang sama dengan “Tragedi
Sambas” pada 1999 (Putra, 2014: 119)
3.2.5 Sistem Religi
Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi
keagamaan, dan upacara keagamaan. Dalam novel Ngayau, suku Dayak mengenal
kepercayaan animisme dan dinamisme.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

71
Seperti layaknya burung, Lansau membawa terbang Mei dan ayahnya. Lari
menghindar amuk massa yang juga dirasuki ruh-ruh leluhur. Ruh-ruh yang
dipanggil lewat tariu, merasuk ke dalam tubuh seperti manusia. Tapi
ukuran tubuh itu tanggung, seperti anak akil balig namun jumlahnya
sangat banyak. Kepala mereka semua berikatkan kain merah (Putra, 2014:
74)
Poromuan sama seperti kampung-kampung Dayak yang lain. Artefak,
bentuk, dan gaya perkampungan sama. Sama-sama yakin bahwa alam raya
punya kekuatan magis. Kekuatan magis juga terdapat dalam setiap benda,
termasuk pohon dan patung-patung. Maka setiap akan masuk kampung,
selalu ada tanda. Ada gerbang, pagar, tangga naik/turun, dan ada pantak
(Putra, 2014: 181).
Dari kutipan-kutipan di atas, tergambar bahwa masyarakat Dayak masih
menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Jelas digambarkan oleh
pengarang melalui tariu, yang dilakukan saat akan memulai perang dan meminta
agar ruh leluhur membantu suku Dayak dalam peperangan. Sistem kepercayaan
suku Dayak juga tetap percaya bahwa benda-benda memiliki nyawa dan memiliki
kekuatan magis. Contohnya suku Dayak menggunakan patung kayu atau disebut
hampatokng untuk kegiatan tolak bala. (Putra, 2014: 181). Pantak-pantak atau
patung dimaksudkan untuk menjaga kampung dari marabahaya. Akan tetapi, kini
ketika etnis Dayak adalah Katolik/Kristen, patung-patung pun digantikan salib
dengan tujuan yang sama.
3.2.6 Kesenian
Dalam novel Ngayau, terdapat beberapa perwujudan kesenian yang
meliputi seni rupa berupa benda lama yang masih digunakan, kesusasteraan
berupa mantra dan cerita rakyat, serta seni musik .
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

72
3.2.6.1 Benda-benda Lama yang Masih Digunakan
Dalam novel Ngayau, salah satu benda lama yang masih digunakan adalah
tajao yang merupakan tempayan berukuran besar, digunakan untuk menyimpan
benda-benda keramat. Biasa juga digunakan untuk menyimpan beras dan tuak.
Penggunaan tajao terdapat dalam kutipan berikut
“Mudah!” jawab Macatn Gaikng. “Dekat tajao” selalu tersimpan tengkorak
dan tulang musuh. Nah, kalian ambil salah satu tulang itu!” (Putra, 2014:
185).
3.2.6.2 Kesusasteraan
Dalam novel Ngayau, ditemukan beberapa mantra yang merupakan bagian
dari kesusasteraan, yaitu mantra saat tariu, mantra nosu minu, dan mantra sokutuk
sokutokng.
(1) Mantra saat Tariu
Tariu telah memprogram otak massa yang tadinya santun, tiba-tiba beringas.
Mantra seperti sebuah password yang membuat ruh-ruh leluhur merasuk ke dalam
tubuh massa manusia yang jumlahnya luar biasa banyak, entah dari mana, seperti
kerumunan semut merah.
“Babae Longa, Babae Ana, Babae bala nya muntuh mula. O bala macatn
sakti mandraguna! Lokei monik koto nulokng ome boporakng lawan musuh!
O Ponompa, o Jubata, kapikng soru ome! Tariuuuu. . . .!!” (Putra, 2014:
68).
Yang berarti
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73
“Babae Longa, Babae Ana, babae para leluhur. Hai macatn sakti mandraguna!
Bergegaslah datang menolong kami berperang melawan musuh. Hai Yang Maha
Kuasa, dengan seruan dan permintaan kami! Tariuuuu!”
(2) Mantra Nosu Minu (Menyerukan semangat/jiwa)
Dalam novel Ngayau, mantra Nosu Minu digunakan untuk menyerukan
semangat atau jiwa seseorang. Orang Dayak percaya bahwa jiwa atau semangat
orang sedang menderita suatu penyakit perlu dibacakan mantra nosu minu
supaya dapat kuat kembali. Hal ini dilakukan oleh Domia untuk kesembuhan
Bejamban Perangai Laut. Domia pun menggendong anaknya itu. Ia
membawanya ke kaki rumah pohon. Hanya sebagai syarat, sekaligus penguat
semangat, tabib wanita itu membaca mantra yang berikut ini. Berikut merupakan
bunyi mantra Nosu Minu.
Tomona kek okapm ponompa, potara
Tomona ari panca ina balai potara
Panca agong balai domokng
Pucok kayu langae buru
Pucok ongkah langae didah
Okapm basal eh mobak ponuru somak
Okapm basal eh manu ponuru oju
Minte monik bokah, monik sagala
Minte monik pongki, monik jowi
Manu: onak ucok KEEEEE, okapm!
Artinya:
Turun, ya (kek – sebutan hormat) Tuhan,
Pencipta, sang penjadi
Turun dari panca ini, tempat kediaman-Mu yang mahatinggi
Panca agung tempat semayam para malaikat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

74
Pucuk kayu, pucuk bambu (simbol ketinggian)
Pucuk tali, pucuk buru (buru: salah satu jenis bambu)
Namanu diseur, di pagi yang dini
Engkau didatangi, di malam yang larut
Kami mohon datanglah segra
Datanglah, hadirkan wajahmu
Temui: anak cucu, ya JUNJUNGAN kami,
Yang mahatinggi (Putra, 2014: 225-226).
(3) Mantra Sokutuk Sokutokng
Dalam novel Ngayau, mantra sokutuk sokutokng digunakan untuk
penangkal ramuan sirep, agar tidak terkena sihir yang dapat menyebabkan
seseorang tertidur. Siapa pun yang terkena mantra tersebut akan tertidur pulas.
Untuk menghindari hal tersebut, para awak kapal kerajaan Sintang pura-pura
tertidur dan sebelumnya sudah mengoles minyak sokutuk sokutokng di kening.
Bunyi mantranya terdapat dalam kutipan berikut.
Minyak sokutuk sokutokng, nasi dimakan dalapm periuk. Tik mada dioles
sokutuk sokutokng, kolak tiduk somalapm suntuk. Artinya: Minyak sokutuk
sokutokng, nasi dimakan dalam periuk. Jika tidak dioles sokutuk sokutokng,
maka akan tidur semalam suntuk (Putra, 2014: 322).
3.2.6.3 Cerita Rakyat
Dalam novel Ngayau, pengarang menyinggung sedikit tentang kisah Dara
Juanti. Juanti adalah cerita rakyat dari Kabupaten Sintang. Cerita rakyat ini adalah
tentang seorang gadis Dayak yang ditinggal oleh saudara laki-lakinya bernama
Demong Nutup atau Jubair II. Saudaranya tersebut merantau ke Pulau Jawa. Inilah
yang menyebabkan Dara Juanti yang memimpin kerajaan Sintang. Dara Juanti
pun ingin pergi berlayar ke Pulau Jawa untuk bertemu Jubair. Berita tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

75
didengar oleh Jubair. Di pelabuhan Tuban, Dara Juanti dihadang oleh prajurit
kerajaan dan merupakan pertemuan pertama dengan seorang patih dari Majapahit
yaitu Patih Loh Gender. Dari pertemuan itu, keduanya semakin dekat. Akhirnya
Patih Loh Gender pergi ke Sintang untuk melamar Dara Juanti. Namun, Patih Loh
Gender harus kembali ke Tanah Jawa karena harus memenuhi persyaratan yang
diminta Dara Juanti. Persyaratan tersebut di antaranya, keris elok tujuh berkepala
naga, empat puluh kepala, dan empat puluh dayang-dayang. Pinangan sudah
terpenuhi, selain itu Patih Loh Gender menyerahkan barang pinangan lainnya
seperti seperangkat alat musik, patung burung garuda terbuat dari emas, dan
sebongkah tanah majapahit. Pinangan berhasil, pernikahan pun diselenggarakan.
Lansau perlahan membelai rambut Mei yang panjang terurai disisir angin
pantai Pasir Panjang. Lalu menatap wajah wanita itu: masih seperti dulu.
Molek jelita, sehingga digelari “Dara Juanti”. (Putra, 2014: 153).
3.2.6.4 Kisah Asal Usul Padi versi suku Dayak
Dalam suku Dayak, terdapat beberapa versi kisah asal usul padi. Salah
satunya dalam novel Ngayau, terdapat sebuah kisah dari mana padi berasal yaitu
dari sepasang suami istri yaitu Sabung Mangulur dan Sabang Menjulur. Kisah
ini berkaitan dengan banyaknya upacara suku Dayak diadakan di lumbung.
Orang Dayak yakin bahwa padi mempunyai semangat atau nyawa. Oleh sebab
itu, agar nyawa padi tidak lari atau hilang, tempat penyimpanan padi haruslah
ditata dan dipelihara sedemikian rupa. Area penyimpanan padi dijaga tengkorak-
tengkorak para sakti mandraguna agar nyawa padi tidak lari dan tetap terpelihara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

76
sesuai petunjuk Sabung Mangulur dan Sabang Menjulur (Putra, 2014: 38). Kisah
asal usul padi terdapat dalam kutipan berikut.
Alkisah, benih padi dipercaya datang dari sepasang suami istri bernama
Saking mencintai anak-anaknya, suatu hari, mereka memberikan wasiat.
Sepasang suami istri ini masuk ke dalam lumbung lalu anak-anak menutup
dan mengunci lumbung itu dengan rapat. Setelah genap tujuh hari setelah
Sabung Mangulur dan Sabang Menjulur masuk ke dalam lumbung maka
anak-anak mereka datang menjenguk. Ketika membuka lumbung, mereka
melihat aneka benih bertumpukan di dalamnya. Berbagai macam bibit sayur
mayur dan palawija tergeletak di situ. Namun, yang terpenting dari
semuanya adalah yang terletak di gundukan paling tengah, yakni bulir-bulir
padi. Antara sedih dan girang, keenam saudara itu menyaksikan semua yang
telah terjadi. Sedih karena tidak lagi menemukan orang tua yang sangat
mereka cintai dan mencintai mereka. Girang karena sebagai silih kedua
orang tua yang telah tiada, mereka menemukan dalam lumbung bermacam-
macam benih, terutama padi, untuk mereka tanam pada masanya nanti akan
memberikan kehidupan dan penghidupan. (Putra, 2014: 38).
3.2.6.5 Seni Musik
Dalam novel Ngayau, terdapat kutipan yang mengingat suatu peristiwa
bagaimana lagu berjudul Pancong Buluh Mundak diciptakan, terdapat dalam
kutipan berikut.
Diliputi rasa haru serta tatap penuh cinta, Domamakng Bunso menerima
pemberian Domia. Ia menerima tuak dari tangan kekasihnya. Lalu
meminumnya.
“Cop, cop, cop, pong!”
Isap demi isap, teguk demi teguk dihirupnya. Tuak yang diisi dalam buluh
bambu itu pun tinggal separuh. Kini giliran Domamakng Bunso nyunsokng
tuak itu ke mulut tunangannya.
“Sekarang giliranmu!” kata Domamakng Bunso seraya meraih bahu
Domia.
Domia menunduk. Lalu menjulurkan mulut. Mendadak kelebat mandau
memutus buluh bambu berisi tuak itu.
“Tega ayahnda berlaku seperti ini!” kata Domamakng Bunso. Heran
campur marah ia menatap Kek Longa.
“Maafkan ayahnda,” jawab Kek Longa, sembari menunjuk ke bawah, ke
arah potongan bambu muda.
“Lihat!” kata Kek Longa, sembari menunjuk ke arah potongan bambu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77
Seekor kala putih putus dua bagian oleh mandau.
“Jika tidak saya pancung buluh berisi tuak itu,” lanjut Kek Longa, “kala
putih ini akan menggigit leher tunanganmu, dan tunanganmu akan mati!”
Domamakng Bunso dan Domia berpelukan. Hadirin yang menyaksikan
kejadian itu, terpana. Kagum kan kepandaian dan kedigdayaan Kek Longa.
Dalam novel Ngayau terdapat seni musik yaitu lagu rakyat (kondan)
Dayak Kualan berjudul Pancong Buluh Mundak. Bagian ulangan lagunya
berbunyi “Pancong buluh mudak, Ogot mosi ogot toga) artinya langsung putus
sekali tebas, belum habis belum selesai. Dari liriknya, lagu ini sering dikaitkan
dengan gurauan bagi peminum tuak mau pun arak dalam suku Dayak. Jika
minuman belum habis, maka acara minum pun belum selesai. Berikut adalah
cuplikan lirik dari lagu Pancong Buluh Mundak.
Mulailah mulai membuka pantun
Pancong buluh mundak
Ogotn mosi ogot toga
Pantun dibuka ongan suara
Pancong buluh mundak
Ogotn mosi ogot togo.
3.2.6.6 Seni Rupa
Dalam novel Ngayau, terdapat seni repa berupa pantak. Pantak biasanya
terdapat di gerbang saat memasuki perkampungan Dayak. Patung kayu atau
hampatokng digunakan untuk tolak bala. Pantak-pantak dimaksudkan untuk
menjaga kampung dari marabahaya. Kini, ketika 90% etnis Dayak adalah katolik
dan Kristen, pantak-pantak pun digantikan dengan salib dengan tujuan yang sama
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

78
(Putra, 2014: 181). Masyarakat Dayak tempo dulu memiliki kebiasaan dan tradisi
untuk mengenang tokoh yang sudah meninggal dengan membuat pantak. Pantak
adalah sejenis patung kayu yang wajahnya simbolik menyerupai dengan tokoh
masyarakat. Pantak aslinya terbuat dari kayu. Kayu yang akan dibuat pantak pun
tidak sembarangan. Dalam arti, saat merencanakan, memilih kayu, membuat,
hingga selesai proses itu menggunakan upacara adat Djuweng (dalam Wuryani,
2015). Gambaran pantak dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Poromuan sama seperti kampung-kampung Dayak yang lain. Artefak,
bentuk, dan gaya perkampungan sama. Sama-sama yakin bahwa alam raya
punya kekuatan magis. Kekuatan magis juga terdapat dalam setiap benda,
termasuk pohon dan patung-patung.
Maka setiap akan masuk kampung, selalu ada tanda. Ada gerbang, pagar,
tangga naik turun, dan ada pantak. (Putra, 2014: 181).
3.3 Unsur-unsur Budaya Tionghoa dalam novel Ngayau karya Masri
Sareb Putra
Menurut Koentjaraningrat (1980: 180), kebudayaan adalah keseluruhan
gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat
yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam novel Ngayau,
ditemukan empat unsur-unsur budaya Tionghoa yang meliputi: (1) Bahasa, (2)
Sistem pengetahuan, (3) Sistem peralatan dan Teknologi, dan (4) Sistem Religi.
3.3.1 Bahasa
Bahasa Hakka yang dituturkan di Provinsi Kalimantan Barat. Bahasa
Hakka yang dituturkan di Kalimantan Barat terdiri dari beberapa varian menurut
asal kelompoknya dari Tiongkok. Hakka di Kalimantan Barat merupakan bahasa
pergaulan, komunikasi warga Tionghoa di daerah tersebut. Di Singkawang,
sebanyak 62% warganya berbicara dalam bahasa Hakka.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

79
Seperti yang dikatakan Mary Somers, “orang Tionghoa di Kalimantan Barat
bukan “penyinggah” atau orang-orang yang hanya tinggal untuk sementara,
karena orang Tionghoa di Kalimantan Barat mempertahankan kebudayaan asli
Tionghoa mereka”. Selain itu, mereka juga masih tetap menggunakan bahasa
Tionghoa secara turun-temurun. Hal ini lah yang membuat keluarga Siat Mei
berbeda dengan etnis Tionghoa lainnya dalam segi penggunaan bahasa sehari-
hari.
Tabel 1
Daftar Bahasa Tionghoa
No Bahasa Tionghoa Tema
1 A kong Sapaan Kekerabatan
2 Lo pho
3 A moi
4 Moi ci
5 Ka Kon
6 Ku Chong
7 Thai Ko
8 Chang Fu
9 Lo Thai Sim
10 Cheu Fung Theu Istilah
11 Ceng Beng
3.3.1.1 Sapaan Kekerabatan
Beberapa sapaan khas Tionghoa yang digunakan pengarang untuk
menandakan bahwa tokoh merupakan keturunan etnis Tionghoa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

80
(1) A kong
Dalam dialek Hakka berarti kakek.
Akong Mei adalah agen cerita silat. Ia membuka kios penyewaan komik
yang laris luar biasa. Sembari mendatangkan serial cerita siat, si akong juga
mengoleksi buku-buku yang dibeli murah di pasar loak. (Putra, 2014: 69).
(2) Lo Pho
Dalam dialek Hakka berarti istri.
A pa Mei juga tiba-tiba teringat lo pho-nya.
“Mei, a me-mu! Di mana dia? Maafkan a pa yang tak berguna ini! kata
lelaki gemuk, berkulit kuning, bermata sipit itu. baru menyadari ada yang
kurang. (Putra, 2014: 78).
(3) A moi
Amoi adalah sapaan atau panggilan kesayangan seorang anak gadis etnis
Tionghoa di Kalimantan Barat. dalam hal ini, maksudnya adalah Mei.
Ia melihat sorot mata a pa-nya dan yakin tak ada segaris benci pun pada
tatap a pa-nya. sebaliknya, “A moi” sungguh mencintai pemuda itu!” pikir a
pa Mei. (Putra, 2014: 81).
(4) Moi Ci
Dalam dialek Hakka berarti anak perempuan.
“A pa kenapa? Tanya Mei. “Ini moi ci!”
“Kau bukan anak gadisku! Kau Domia! Kata ayah Mei. (Putra, 2014: 83).
(5) Ka Kon
Panggilan kesayangan mertua laki-laki dalam dialek Hakka.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

81
“Ya, ini saya ka kon!” sahut Lansau dengan nada santun. (Putra, 2014: 10
(6) Ku Chong
Dalam dialek Hakka, Ku Chong berarti paman.
“Ku Chong pasti lelah dan haus. Minumlah ini!” kata Pak Miguk menawar
dengan santun. “Saya penjaga rumah ini. Di sini ku chong pasti aman!”
(Putra, 2014: 102).
(7) Thaiko
Dalam dialek Hakka berarti abang.
“Thaiko!” seru Mei.
Mei seperti melihat kelebar seseorang. Namun, orang yang dipanggil
Thaiko,yang tiba-tiba muncul dari balik pohon kelapa, menghentikan truk
yang tengah berjalan. Melihat gelagat dan carana, Mei mafhum itu thaiko. Ia
hafal. “Tak salah lagi! Pendekar muda itu adalah abangnya. (Putra, 2014:
105).
(8) Chang Fu
Dalam bahasa Hakka berarti suami.
“Sudahlah,” katanya lembut. “Itu tentang masa lalu,” sembari menepuk
bahu lelaki itu. “Kamu chang fu aku!” (Putra, 2014: 153).
(9) Lo Thai Sim
Dalam bahasa Hakka berarti: abang ipar.
Namun, raut muka kesedihan serta merta berubah jadi keterkejutan.
“Lo thai sim! Kata thaiko. Lansau, ka. . .kamu? apa saya tak salah melihat?
(Putra, 2014: 130).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

82
3.3.1.2 Istilah
Dalam novel Ngayau, terdapat penggunaan istilah menggunakan bahasa
Tionghoa, yaitu Cheu Fung Theu yang berarti manusia kepala merah.
Penggunaan istilah tersebut terdapat dalam kutipan berikut.
Siapa saja yang melihat kepala merah akan lari terbirit-birit, sehingga dialek
Hakka setempat menyebutnya sebagai “Cheu fung theu,” atau lari terbirit-
birit karena amukan kepala merah. (Putra, 2014: 74).
“Kita tidak melasa olang Cin dali Seblang!” kata Ben Teng suatu pagi,
ketika bersama a pa Mei sedang kongkow-kongkow. “Kita olang Cin wajib
mengangkat delajat olang Dayak. Sebab meleka sama sepelti kita, hanya
miglasi lebih dulu. Nenek moyang olang Dayak dali Yunan, kita juga dali
negeli sama!”
Ayah Mei manggut-manggut.
“Cili-cili fisik dan makanan kita dengan olang Dayak juga sama! Kata Ben
Teng. “Leluhul kita dali Guang Dong.” (Putra, 2014: 60).
Dari catatan pembentukan “Kongsi Cina”, Kongsi Lan Fong di Mandor
didirikan oleh Lo Fong Fak yang berasal dari suku Hakka (Khek) yang bersama
rombongan datang dari provinsi Guang Dhong. Setelah mendarat di Pantai Laut
Cina Selatan, mereka menuju Mandor dan tiba pada 1772.
3.3.2 Sistem Pengetahuan
Dalam novel Ngayau, terdapat sistem pengetahuan etnis Tionghoa yang
ketujuh yaitu ruang dan waktu, yaitu ilmu untuk menghitung, mengukur,
menimbang, atau menentukan tanggal. Setiap tahunnya, tokoh Lansau selalu
menemani istrinya pergi ke pemakaman a pa Mei pada bulan Maret-April untuk
melaksanakan ceng beng.
Tiap tahun, antara bulan Maret-April ada ceng beng, dan Lansau selalu setia
menemani istrinya (Putra, 2018: 149).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

83
Ceng beng merupakan ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang
berziarah ke pemakaman sesuai dengan ajaran Khonghucu. Festival tradisional ini
jatuh pada hari ke 104 setelah titik balik Matahari pada musim dingin (atau hari
ke-15 dari hari persamaan panjang siang dan malam pada musim semi), pada
umumnya jatuh pada tanggal 5 April, dan setiap tahun kabisat, Qing Ming jatuh
pada tanggal 4 April. Secara astronomi, ini juga merupakan terminologi matahari,
yang dinamai Qingming. Nama yang menandakan waktu untuk orang pergi keluar
dan menikmati hijaunya musim semi, dan juga ditujukan kepada orang-orang
untuk berangkat ke kuburan.
Ceng beng masih dianut oleh Siat Mei sebagai bagian dari etnis Tionghoa.
Mei mengunjungi pemakaman ayahnya. Sebenarnya, tidak ada aturan yang
menyebutkan bahwa orang Tionghoa yang merayakan Ceng Beng harus beragama
Buddha atau Kong Hu Cu. Siapa pun boleh saja melakukan sembahyang kubur
karen tujuannya adalah untuk menghormati jasa-jasa orangtua atau leluhur. Selain
itu, saat Ceng Beng juga sebagai momen untuk berkumpul kembali bersama
keluarga dan sanak saudara yang jauh.
3.3.3 Sistem Peralatan dan Teknologi
Sistem peralatan dan teknologi meliputi, alat-alat produksi, senjata, wadah,
makanan, dan jamu-jamuan, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung, dan
perumahan, serta alat-alat transportasi (Koentjaraningrat, 1990: 343). Dalam novel
Ngayau, terdapat satu unsur dari sistem peralatan dan teknologi yaitu makanan
khas Tionghoa, yaitu Kwee Cap. Kwee Cap adalah Makanan khas Tionghoa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

84
Kalimantan Barat, namun juga disukai etnis lain, terutama Dayak. Terbuat dari
tepung, berwarna putih sebesar jari, dengan bumbu, dan aneka bahan khas
Tionghoa. Kwee cap adalah potongan kwetiau atau mie lebar yang terbuat dari
tepung beras. Lalu disiram dengan kuah dari kaldu tulang babi dan minyak babi.
Makanan khas Tionghoa berupa kwee cap terdapat dalam kutipan berikut.
“Kita olang kejepit” kata Ben Teng, sembari menyantap Kwee Cap. Itu
adalah sendok yang terakhir (Putra, 2014: 62).
3.3.4 Sistem Mata Pencaharian Hidup
Dalam novel Ngayau, digambarkan bahwa sistem mata pencaharian etnis
Tionghoa yaitu berkebun dan berdagang.
(1) Berkebun
Dalam novel Ngayau, saat perang usai warga Tionghoa diungsikan ke
beberapa tempat di Kalimantan Barat, yaitu Gudang Tama, Kaliasin, Lirang, dan
Kopisan. Sistem mata pencaharian terlihat dari penokohan a pa Mei. A pa Mei
adalah salah satu pengungsi dan menjadi penggangguran sebagai akibat dari
peristiwa Mangkok Merah. Ia mencoba memulai hidup dari berkebun. Sistem
mata pencaharian Tionghoa berkebun terdapat dalam kutipan berikut.
A pa Mei diungsikan di Lirang. Mulai meniti hidup dari bawah lagi, mula-
mula membangun gubuk di sebuah lahan tepi sawah. Sedikit demi sedikit
menanam sayur mayur. Lalu berkebun jeruk. Sementara a me Mei tidak
tahu ke mana rimbanya? (Putra, 2014: 145).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

85
(2) Pasar Terapung
Ketika Mei dan a pa-nya diculik Lansau, a me sedang ke pasar terapung.
Sore-sore penangkap ikan dan para petani baru tiba dengan aneka jualan yang
masih segar. Mereka berjualan di pasar terapung, di dalam perahu-perahu yang
berbaris tertambat. Pasar terapung dalam novel Ngayau terdapat dalam kutipan
berikut.
Perhatian Lansau tertuju pada Mei dan ayahnya yang tengah melayani
pembeli toko kelontong ketika itu. (Putra, 2014: 78).
(3) Berdagang
Mata pencaharian etnis Tionghoa bervariasi. Ada yang bertani, peternak,
bahkan tenaga pengajar. Akan tetapi, kebanyakan warga dari etnis Tionghoa
adalah pedagang, seperti Ayah Mei yang merupakan seorang pedagang kelontong.
Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. Kelontongnya dibakar massa saat tariu
terjadi.
“Inikah yang menyebabkan pedagang kelontong itu membatalkan perkawinan
anak gadisnya yang tinggal menghitung jam?” (Putra, 2014: 52).
Dan bunyi itu semakin dekat dengan bantaran sungai tempat tinggal Mei,
sekaligus toko kelontong milik keluarganya,” (Putra, 2014: 68).
Etnis Tionghoa memang punya kemampuan unik dalam bidang ekonomi.
Terdapat beberapa mitos dalam hal tersebut. Tersohornya kesuksesan orang besar
yang datang dari etnis Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari paham yang mereka
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

86
anut. Konghucu atau lebih dikenal dengan confucianism adalah sistem norma dan
filosofi yang dianut oleh kebanyakan etnis Tionghoa (Rengganis, 2014)..
Dalam sistem kepercayaan ini, diatur hierarki hubungan antar individu yang
biasa disebut Wu-Lun. Hal tersebutlah yang dianut oleh Ben Teng bahwa dalam
hal hubungan sosial tidak boleh memilah dan membatasi komunikasi dan relasi
hanya dengan satu suku atau satu golongan saja. Sebisa mungkin berelasi dengan
siapa pun. Dalam dunia dagang, semakin banyak relasi, semakin baik (Putra,
2014: 60-61).
(4) Kerja Tambang
Dalam novel Ngayau, digambarkan oleh pengarang bahwa kerja tambang
merupakan salah satu mata pencaharian etnis Tionghoa. Saat itu, banyak
petambang dari etnis Tionghoa sukses dan memiliki jaringan yang luas. Hal
tersebut memicu kompeni untuk memprovokasi. Kompeni takut jika suku Dayak
dan etnis Tionghoa menjadi penguasa di Borneo. Hal itulah yang menyebabkan
perang antara Dayak dan Tionghoa. Penggambaran kerja tambang terdapat dalam
kutipan berikut.
Di sebuah ladang tambang daerah Lara yang kemudian hari menjadi
wilayah Kabupaten Sambas. Kompeni melihat ancaman. Para pekerja
tambang imigran dari negeri Cina sukses dan berhasil menjalin relasi lebih
luas sampai ke luar wilayah nusantara ketika itu. Petambang Dayak dan
petambang imigran Cina sengaja dibentur-benturkan, sehingga terjadi
perang Dayak vs imigran Cina, wilayah yang sama dengan “Tragedi
Sambas” pada 1999 (Putra, 2014: 119)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87
3.3.5 Sistem Religi
Dalam novel Ngayau, tokoh Siat Mei merayakan ceng beng pada bulan
Maret-April setiap tahunnya untuk menghormati dan a pa dan a me serta
leluhurnya. Penghormatan leluhur yang dilakukan oleh Siat Mei adalah
kepercayaan tradisional dalam etnis Tionghoa. Ini dikarenakan pengaruh ajaran
Konfusianisme yang mengutamakan bakti kepada orang tua termasuk leluhur
(Wikipedia, Kepercayaan Tradisional Tionghoa). Ceng Beng dimengerti semua
oleh berbagai etnis Tionghoa Kalimantan Barat sebagai sembahyang kubur.
Pelaksaan ceng beng yang dilakukan oleh Siat Mei terdapat dalam kutipan
berikut.
Tempat kenangan ini, sekarang adalah pemakaman keluarga Tionghoa. Tiap
tahun, antara bulan Maret-April ada ceng beng, dan Lansau selalu setia
menemani istrinya. mungkin dengan cara begini, ia merasa sebagai silih atas
dosa masa lalu.
. . . .
Anak gadis itu mengangkat hio ke atas, lalu meletakannya ke bawah lagi.
Ibunya membantu menancapkan batang hio itu di tempat yang semestinya.
(Putra, 2014: 149).
3.4 Rangkuman
Dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra, peneliti menemukan enam
unsur-unsur budaya Dayak yaitu: (1) bahasa yang digunakan yaitu bahasa Dayak
Kanayatn dan Bahasa Dayak Djongkang (Djo). (2) Sistem pengetahuan yang
meliputi sistem pengetahuan musim, sistem pengetahuan flora, dan sistem
pengetahuan adat-istiadat. (3) Sistem peralatan hidup dan teknologi meliputi
senjata, tempat berlindung, perumahan, alat produksi, dan makanan. (4) Sistem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

88
mata pencaharian hidup yang meliputi berburu dan berladang. (5) Sistem religi
yang meliputi kepercayaan animisme dan dinamisme, dan (6) kesenian meliputi
benda lama yang masih digunakan, kesustraan berupa mantra-mantra, cerita
rakyat, dan seni musik. Sedangkan, unsur-unsur budaya Tionghoa terdapat empat
unsur yaitu: (1) bahasa yang digunakan meliputi bahasa Tio Ciu, dialek hakka. (2)
Sistem peralatan dan teknologi yang meliputi makanan khas Tionghoa di
Kalimantan Barat yaitu kwee cap. (3) Sistem mata pencaharian etnis Tionghoa
yang meliputi berkebun dan ada pasar terapung, berdagang, dan kerja tambang.
(4) Sistem religi Tionghoa yang meliputi konfusianisme.
Di bumi Borneo, imigran asal negeri Cina ibarat ikan bertemu air. Klop!
Dari isi budaya dan bahasa, tidak ada masalah dengan saudara tuanya yang
migrasi lebih awal. Mereka pun tidak merasa berbeda. Satu sama lain bertutur
dengan dua bahasa yang berbeda. Penduduk asli fasih bertutur dialek Khek
(Hakka) dan Tio Ciu. Sebaliknya. Etnis Tionghoa di Bumi Borneo pun sangat
fasih berbahasa Dayak. Sampai-sampai dalam kehidupan dan berkomunikasi
sehari-hari, tidak dapat dibedakan lagi, mana Dayak dan Tionghoa. Akan tetapi,
tetap saja ada semacam luka batin yang terbawa sejak lama, turun-temurun. Orang
bilang, waktu akan menyembuhkan luka. Nyatanya, tidak! Bukan kali ini saja
orang Dayak dibentur dengan orang Tionghoa (Putra, 2014: 118).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

89
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Penelitian ini menggunakan objek material novel Ngayau karya Masri
Sareb Putra. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu: (1)
Bagaimana unsur pembangun novel yang mencakup tokoh, penokohan, dan latar
dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra? Dan (2) Apa saja unsur-unsur
kebudayaan Dayak dan Tionghoa dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra?
Dalam menganalisis unsur-unsur kebudayaan, peneliti menggunakan teori unsur-
unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat.
Pada bab II, peneliti memaparkan hasil analisis struktur pembangun novel
yang terdiri dari tokoh, penokohan, dan latar. Penulis memilih unsur-unsur
tersebut karena struktur tersebutlah yang paling dominan dalam cerita dan dapat
menggambarkan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam novel Ngayau.
Dalam novel Ngayau karya Masri Sareb Putra terdapat dua tokoh utama yaitu
Lansau dan Siat Mei. Sedangkan terdapat tokoh tambahan yaitu (1) A pa Mei, (2)
Ben Teng, (3) A kong Mei, (4) Ahong, (5) Sinfu, (6) Sin Sang, (7) Kek Longa, (8)
Domia, dan (9) Domamakng Bunso. Tokoh-tokoh tersebut hadir di sekitar tokoh
utama.
Lansau yang merupakan tokoh utama adalah seorang pemuda Dayak, ia
menjadi pemimpin manusia kepala merah saat tariu dan sekaligus menjadi
penggerak dalam cerita novel Ngayau. Siat Mei yang merupakan gadis Tionghoa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

90
dan diperistri oleh Lansau juga termasuk tokoh utama karena kehadirannya cukup
dominan saat peristiwa perang yang dialaminya bersama Lansau. A pa Mei yang
merupakan ayah dari Siat Mei sebagai seorang pria keturunan Tionghoa yang
berdagang kelontong. Ben Teng adalah teman a pa Mei yang dibesarkan dan
dilahirkan di Borneo. Ahong adalah abang dari Siat Mei, sahabat Lansau yang
merupakan pemimpin pasukan seribu kuil. Sinfu yang merupakan pastor tentara
dan menjadi sukarelawan saat perang. Sin sang merupakan guru silat Ahong yang
memiliki ilmu-ilmu profan. Kek Longa, ayah dari Domia yang menjadi babae.
Domia adalah anak Kek Longa yang merupakan ibu dari bayi kembar bernama
Bagumban Perangai Darat dan Bejamban Perangai Laut. Domamakng Bunso,
suami Domia dan merupakan seorang yang gagah dan berjiwa ksatria.
Dalam menganalisis latar, hanya beberapa latar yang dipilih karena
berkaitan dengan unsur-unsur budaya. Peneliti membagi unsur latar menjadi tiga
bagian yaitu: latar tempat, latar waktu, dan latar sosial budaya. Latar tempat yang
meliputi negeri Poromuan, Rumah Mei, dan Hutan. Latar waktu dominan adalah
tahun 1967 saat perang akibat provokasi antara suku Dayak dan etnis Tionghoa,
dan pada tahun 1999 saat terjadi kerusuhan antar etnis di Sambas, dan latar sosial-
budaya yang meliputi cara hidup suku Dayak yang hidup secara berkomunal di
rumah betang, penggambaran makanan khas Tionghoa di Kalimantan Barat, kwee
cap, dan penggunaan bahasa yang dapat mengindikasikan dari mana seseorang
berasal.
Pada bab III, peneliti memaparkan hasil analisis unsur-unsur kebudayaan
Dayak dan Tionghoa yang terdapat dalam novel Ngayau. Pada penelitian ini,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

91
peneliti menemukan enam unsur-unsur budaya Dayak yaitu: (1) Penggunaan
kosakata bahasa Dayak Kanayatn yaitu jubata dan tariu dan penggunaan bahasa
Dayak Djongkang (Djo) yaitu bepacu, pongaretn dan ngabas poya, sebagai sarana
komunikasi, digunakan beberapa tanda karena orang Dayak tidak bisa terlepas
dari tanda yaitu tanda dari suara gong sebagai bentuk komunikasi non-verbal,
tanda dari suara burung sebagai petunjuk saat hendak pergi me-ngayau, tanda dari
bambu untuk keperluan ritual, dan penggunaan sandi saat tariu yaitu 2-B yang
berarti bunuh dan bakar. (2) Sistem pengetahuan yang meliputi membaca musim
sebagai pedoman berburu saat musim kemarau , sistem pengetahuan flora yaitu
daun sabang merah yang digunakan sebagai tanda pengenal saat tariu, dan sistem
pengetahuan adat yang meliputi asal-usul terciptanya hukum adat. (3) Unsur
sistem peralatan dan teknologi yang meliputi senjata untuk berburu yaitu sumpit,
tombak, bikas, belantik, polaman sebagai tempat berlindung saat musim menanam
padi tiba, perumahan suku Dayak berupa rumah adat betang yang terdapat di hulu
sungai, bambu sebagai alat memasak, dan makanan. (4) Sistem mata pencaharian
hidup yang meliputi berburu saat musim kemarau, berladang pada bulan Agustus
saat puncaknya musim kemarau, dan kerja tambang di daerah Lara bersama etnis
Tionhoa. (5) Sistem religi yang meliputi animisme, memanggil ruh leluhur saat
tariu agar membantu suku Dayak perang dan dinamisme, suku Dayak percaya
bahwa pantak yang merupakan patung sebagai benda bernyawa. (6) Kesenian
meliputi benda lama yang masih digunakan yaitu tajao untuk menyimpan tuak,
kesustraan berupa mantra-mantra yaitu mantra saat tariu untuk memanggil ruh
leluhur, mantra nosu minu untuk menyerukan semangat seorang yang sedang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

92
menderita suatu penyakit, mantra sokutuk sokutokng untuk penangkal ramuan
sirep agar seseorang yang terkena sihir tidak tertidur, dan cerita rakyat Dara Juanti
dan kisah asal usul padi versi Dayak yaitu dari sepasang suami istri bernama
Sabang Mangulur dan Sabang Menjulur, dan Seni musik yang berupa penggalan
lagu Pancong Buluh Mundak. Sedangkan, unsur-unsur budaya Tionghoa terdapat
empat unsur yaitu: Dalam beberapa bahasa meliputi bahasa Tio Ciu, dialek hakka,
terdapat penggunaan sapaan kekerabatan, dan penggunaan istilah Cheu Fung Theu
yang berarti Manusia Kepala Merah. (2) Sistem pengetahuan yang ketujuh, yaitu
ruang dan waktu. Mampu menentukan tanggal pelaksaan ceng beng. (3) Sistem
peralatan dan teknologi meliputi makanan khas etnis Tionghoa di Kalimantan
Barat yaitu kwee cap. (3) Sistem mata pencaharian etnis Tionghoa meliputi
berkebun, pasar terapung, berdagang, dan kerja tambang. (4) Sistem kepercayaan
Tionghoa yang meliputi konfusianisme.
Etnis Dayak dan Tionghoa sudah hidup bersama sejak puluhan abad.
Sudah berasimilasi dan berakulturasi. Tampak dalam adanya beberapa persamaan
dalam analisis unsur-unsur budaya Dayak dan Tionghoa yang terdapat dalam
novel Ngayau, yaitu sistem mata pencaharian hidup, Dayak dan Tionghoa bermata
pencaharian dalam bidang yang sama yaitu pertanian, suku Dayak berladang dan
etnis Tionghoa berkebun. Selain itu, terdapat juga persamaan bahwa suku Dayak
dan Tionghoa sama-sama bermata pencaharian sebagai petambang. Selain itu,
dalam penokohan Lansau dan Ahong, pengarang menggambarkan bahwa suku
Dayak dan etnis Tionghoa sama-sama bisa menggunakan bahasa Hakka. Ciri fisik
juga tidak jauh berbeda, sama-sama berkulit kuning dan berambut hitam lurus.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

93
Saat provokasi, etnis Dayak pun dihasut, agar etnis Dayak memusuhi etnis
Tionghoa. Karena banyak memiliki kesamaan, Dayak dan Tionghoa tidak mudah
diprovokasi. Sebelumnya, provokasi antara kedua etnis tersebut tidak mempan.
Dayak dan Tionghoa tetap hidup rukun dan damai. Dalam rekayasa tersebut,
tentara menyamar dan mulai memasuki kampung-kampung Dayak. Saat etnis
Dayak berhasil diprovokasi, maka perang pun terjadi. Menurut analisis dan data
intel, 90 persen etnis Tionghoa di Kalimantan Barat distempel sebagai komunis.
Maka tentara yang menyamar, masuk ke kampung-kampung Dayak dan
mendekati tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam sebuah silent operation,
tentara membunuh beberapa tokoh Dayak, tidak di kampung mereka. Untuk
memancing kemarahan warga Dayak, disebarluaskan isu dan propaganda bahwa
tokoh Dayak dibunuh PGRS/Paraku (Putra, 2014: 139).
Kerusuhan sosial 1967 di Kalimantan Barat yang dipermukaan melibatkan
Dayak vis a vis Tionghoa ini, berlangsung selama sekitar tiga bulan (Putra, 2014:
145). Dua etnis satu asal tersebut saling bunuh, seperti tidak pernah kenal
sebelumnya. Dalam kerusuhan tersebut, Tionghoa adalah korban. Akan tetapi, di
sisi lain orang Dayak juga merasa menjadi korban. Perang antar kedua etnis
tersebut. Akhirnya, dalam perang tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada
yang kalah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

94
4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran. Bagi peneliti
selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan acuan dalam melaksanakan
penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji novel ini dari teori dan
pendekatan yang berbeda yaitu dengan teori Antropologi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

95
DAFTAR PUSTAKA
Abrams, M.H. 1999. A Glosary of Literary Terms. Seventh Edition.
Massachusetts: Heinle&Heinle, Thompson Learning Inc.
Aminuddin, 2004. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi
Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Atar, Semi. 1989. Kritik Sastra. Bandung: Angkasa.
Bock, C. 1882. The Head Hunters of Borneo; a narrative of travel up the
Mahakam and down the Barito; also, Journeyings in Sumatra. London:
Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.
Coomans, Mikhael. 1987. Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan.
Jakarta: Gramedia.
Damono, Sapardi J. 1979. Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang. Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
, Sapardi Djoko. 1984. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas.
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Darmayana, Hiski. 2013. "Peristiwa Mangkok Merah, Ketika Imperialisme
'Mengawini' Rasialisme". http://www.berdikarionline.com/peristiwa-
mangkok-merah-ketika-imperialisme-mengawini-rasialisme/, diakses
19/07/2018 pukul 00.30.
Faruk. 1994. Pengantar Sosiologi Sastra (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Kalangie, N.S. 1994. Kebudayaan dan Kesehatan. Pengembangan Pelayanan
Kesehatan Primer Melalui Pendekatan Sosial-Budaya. Jakarta: Kesaint
Blank.
Krisna, Pramesti. 2016. Burung Enggang, Burung Khas Kalimantan.
https://undas.co/2016/01/burung-enggang-burung-khas-kalimantan/
diakses pada 21/07/2018 pukul 23: 32.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

96
Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan (Cetakan 1).
Jakarta: Gramedia.
. 1980. Pengantar Ilmu Antropologi (cetakan ke-2). Jakarta:
Aksara Baru.
. 1990. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Djambatan.
. 1996. Pengantar Ilmu Antropologi Jilid I. Jakarta: Grasindo.
. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi II. Jakarta. Rineka Cipta.
. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Lontaan, J. U. 1975. Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat.
Pontianak: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
Moleong, Lexy. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset.
Mudiyono. 1995. Kearifan Tradisional Masyarakat Dayak Dalam Pemeliharaan
Lingkungan Hidup di Daerah Kalimantan Barat. Pontianak: Fisip
Untan.
Nurgiyantoro, B. 2007. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
. 2015. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Pradopo, Rachmat D. 2002. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritis, dan
Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putra, M.S. 2014. Ngayau. Tangerang: Entertainment Essence Center.
. 2012. Makna di Balik Teks Dayak Sebagai Etnis Headhunter.
Gading Serpong: Universitas Multimedia Nusantara.
. 2015. Keling Kumang. Banten: Entertainment Essence Center.
Ratna, Nyoman Kutha.2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rengganis, Nendra. 2014. Rahasia Kenapa Orang Tionghoa Bisa Jadi Super Kaya.
https://www.hipwee.com/sukses/rahasia-kenapa-orang-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

97
tionghoa-bisa-lebih-kaya-dibanding-kamu/ diakses pada
21/07/2018 pukul 00:21.
. 2006. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Dari
Strukturalisme Hingga Poststrukturalisma Perspektif Wacana Naratif
(Cetakan Ke-2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
. 2011. Antropologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saraswati, Ekarini. 2003. Sosiologi Sastra: Sebuah Pemahaman Awal. Malang:
Bayu Media dan UMM.
Satoto, Soediro. 1993. Metode Penelitian Sastra. Surakarta: UNS Press.
Semi, Atar. 1989. Kritik Sastra. Bandung: Angkasa.
Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Soemardjan, Selo. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi.
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar
Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik). Yogyakarta: Duta
Wacana University Press.
Suhariyadi. 2014. Pengantar Ilmu Sastra. Lamongan: Pustaka Ilalang.
Sukanda, Al Yan. 2012. Gong Dalam Budaya Dayak Pesaguan.
http://kampungtumbangtiti.blogspot.com/ Ketapang: Yayasan Warisan
Ketapang diakses pada 21/07/2018 pukul 23:42.
Superman. 2017. Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Pada Tahun
1967. Pontianak: IKIP-PGRI Pontianak.
Supriyadi, Yohanes. 2008. Cina dalam Dayak. Potret Inkulturasinya di Kalangan
Dayak Mempawah-Kalimantan Barat.
http://yohanessupriyadi.blogspot.com/2008/08/cina-dalam-dayak-
potret-inkulturasinya.html diunduh 18/07/2018 pukul 13:09.
Syani, Abdul. 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Pustaka Jaya. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.
Taum, Y. Yapi. 1997. Pengantar Teori Sastra. Flores: Nusa Indah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

98
. Y. Yapi. 2017. “Kritik Sastra yang Memotivasi dan Menginspirasi”.
Disampaikan dalam Seminar Nasional Kritik Sastra yang
diselenggarakan oleh KEMENDIKBUD dan Dewan Kesenian Jakarta,
di Jakarta tanggal 15-16 Agustus 2017.
Teeuw, A. 1984. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Dunia
Pustaka Jaya.
. 1998. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia.
Waluyo, H. J. 2002. Apresiasi Puisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Wasito, Hermawan. 1992. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Wikipedia.“Kerusuhan Sambas”.https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Sambas
diakses pada21/07/2018 pukul 00.21
Wuryani, Emmy. 2015. Makna Pantak Bagi Suku Dayak Kanayatn, Desa Bagak
Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Salatiga:
Universitas Kristen Satya Wacana.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI