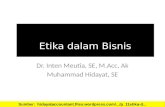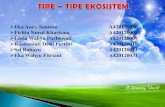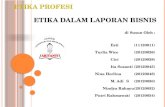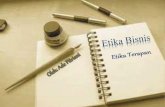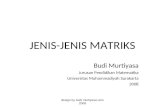Tugass Etika Tipe 1
description
Transcript of Tugass Etika Tipe 1

Type Soal: ……………………….
TUGAS II
ETIKA
Nama:
No. MHS:
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN
2014

BAB 1
1. Jelaskan kata “etika” dan “moral” mmenurut etimologinya ?
Etika secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos”, yang berarti
watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom), norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah
dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.
Secara etimologi, istilah “Moral” berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata
‘moral’ yaitu “mos” sedangkan bentuk jamaknya yaitu “mores” yang masing-masing
mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat.
2. Bandingkan penjelasan tentang “etika” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
(Poerwadinata) dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 1988 dan edisi-edisi
berikutnya.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 –
mengutip dari Bertens,2000), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang
asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens
2000), mempunyai arti :
1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Dari perbadingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus
Bahasa Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu etika sebagai ilmu.
Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti.

3. Apa yang dimaksud dengan “amoral” ?
Amoral adalah sebuah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang
karena kurangnya pengetahuan, memiliki kelainan atau belum cukup umur. Contohnya
adalah seperti ketika anda melihat orang gila di jalan yang berjalan tanpa mengenakan
busana apapun. Anda tidak mungkin bisa bilang itu bejat karena walaupun anda bilang
seperti itu mereka juga tidak akan mengerti. Hal ini juga sama seperti anak kecil yang
telanjang ketika ada tamu di rumah. Mereka tidak mengerti bahwa berlari tanpa busana
adalah hal yang tidak sopan.

BAB 2
10. Bagaimana kritik C. Giligan atas pandangan L. Kohlberg tentang perkembangan moral ?
Carol Gilligan percaya bahwa teori perkembangan moral Kohlberg tidak mencerminkan
secara memadai relasi dan keperdulian terhadap manusia lain. Perspektif keadilan
(justice prespective) ialah suatu perspektif moral yang berfokus pada hak-hak individu;
individu berdiri sendiri dan bebas mengambil keputusan moral. Teori Kohlberg ialah suatu
perspektif keadilan. Sebaliknya, perspektif kepedulian (care perspective) ialah suatu perspektif
moralyang memandang manusia dari sudut keterkaitannya dengan manusia lain dan
menekankankomunikasi interpersonal, relasi dengan manusia lain, dan kepedulian terhadap
orang lain.Teori Gilligan ialah suatu perspektif kepedulian. Menurut Gilligan, Kohlberg
kurangmemperhatikan perspektif kepedulian dalam perkembangan moral. Ia percaya bahwa hal
inimungkin terjadi karena Kohlberg seorang laki-laki, karena kebanyakan penelitiannya
adalahdengan laki-laki daripada dengan perempuan, dan karena ia menggunakan respons laki-
lakisebagai suatu model bagi teorinya.
11. Bagaimana pandangan antropologi budaya tentang shame culture dan guilt culture ?
Antropologi budaya membedakan dua macam kebudayaan: kebudayaan malu (shame
culture) dan kebudayaan kebersalahan (guilt culture). Kebudayaan malu seluruhnya ditandai oleh
rasa malu dan di situ tidak dikenal rasa besalah. Kebudayaan kebersalahan terdapat rasa
bersalah. Shame culture adalah kebudayaan di mana pengertian-penggertian seperti “hormat”,
“reputasi”, “nama baik”, “status”, dan “gengsi” sangat ditekankan.
Guilt culture adalah kebudayaan di mana pengertian-pengertian seperti “dosa” (sin),
“kebersalahan” (guilt), dan sebagainya sangat dipentingkan. Sekalipun suatu kesalahan tidak
akan pernah diketahui oleh orang lain, namun si pelaku merasa bersalah juga. Ia menyesal dan
merasa tidak tenang karena perbuatan itu sendiri, bukan karena dicela atau dikutuk orang lain.
Jadi bukan karena tanggapan pihak luar.

BAB 3
5. Apa yang dimaksud dengan kebebasan yuridis ?
Kebebasan ini berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan
yuridis merupakan salah satu aspek dari hak-hak manusia, sebagaimana tercantum pada
Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dideklarasikan oleh PBB
tahun 1948. Yang dimaksud, adalah semua syarat hidup di bidang ekonomi, sosial, politik yang
diperlukan untuk menjalankan kebebasan manusia secara konkret dan mewujudkan
kemungkinan-kemungkinan yang terpendam dalam setiap manusia. Kebebasan ini
mengandalkan peran negara, yang membuat undang-undang yang cocok untuk keadaan konkret.
6. Apa yang dimaksud dengan kebebasan psikologis ? Apa yang merupakan hakikat kebebasan
ini ?
Kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan serta mengarahkan hidupnya.
Kebebasan ini menyangkut kehendak, bahkan merupakan ciri khasnya. Nama lain untuk
kebebasan psikologis itu adalah ”kehendak bebas’ (free will). Kebebasan ini terkait erat dengan
kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki rasio, yang bisa berpikir sebelum
bertindak, berkelakuan dengan sadar dan pertimbangan. Kemungkinan untuk memilih antara
pelbagai alternatif merupakan aspek penting dari kebebasan psikologis.
7. Apa itu kebebasan moral ? Jelaskan perbedaan dengan kekebasan psikologis dan kebebasan
fisik ?
Kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan
psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Namun, kebebasan psikologis tidak berarti
otomatis menjamin adanya kebebasan moral.
Cara membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa
kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti suka
rela (voluntary) atau tidak terpaksa secara moral, walaupun ketika mengambil keputusan itu
seseorang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan (kebebasan psikologis).

*Cari perbedaan kebebasan moral dengan kebebasan fisik
Kebebasan Fisik
Yakni, ”bebas” diartikan dengan tidak adanya paksaan atau rintangan dari luar. Ini merupakan pengertian yang dangkal, karena bisa jadi secara fisik seseorang dipenjara, tetapi jiwanya bebas merdeka. Sebaliknya, ada orang yang secara fisik bebas, tetapi jiwanya tidak bebas, jiwanya diperbudak oleh hawa nafsunya, dan lain-lain.
Biarpun dengan kebebasan fisik belum terwujud kebebasan yang sebenarnya, namun kebebasan ini patut dinilai positif. Jika kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan harus ditolak sebagai penyalahgunaan kata “kebebasan”, maka kebebasan fisik bisa kita hargai tanpa ragu-ragu.
Kebebasan Moral
Sebetulnya masih terkait erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan dengannya. Kebebasan moral mengandaikan kebebasan psikologis, sehingga tanpa kebebasan psikologis tidak mungkin terdapat kebebasan moral. Namun, kebebasan psikologis tidak berarti otomatis menjamin adanya kebebasan moral.
Cara yang paling jelas untuk membedakan kebebasan psikologis dengan kebebasan moral adalah bahwa kebebasan psikologis berarti bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti suka rela (voluntary) atau tidak terpaksa secara moral, walaupun ketika mengambil keputusan itu seseorang melakukan secara sadar dan penuh pertimbangan (kebebasan psikologis).

BAB 4
5. Apa yang bisa dijawab kepada orang seperti sartre yang menganggap norma moral itu
subyektif ?
Nilai moral menyatakan suatu norma moral, sehingga dengan demikian dalam norma
moral pun juga terdapat unsur subyektif. Tanpa adanya subyek, norma moral menjadi tidak
bermakna. Pernyataan bahwa perilaku korupsi itu tidak baik tentu tidak bermakna apa-apa, jika
tidak ada aparat pemerintah atau birokrat yang menjadi subyeknya.Kita yakin bahwa norma
moral mewajibkan kita secara objektif. Kita sendiri tidak menciptakan norma itu. Norma tidak
tergantung pada selera subjektif kita.
Immanuel Kant adalah filsuf yang menyajikan suatu sistem etis berdasarkan semata-mata
pada nalar (reason). Sistem moral Kant didasarkan pada rasionalitas. Kant mencoba
menunjukkan bagaimana setiap makhluk rasional akan setuju pada hukum moral yang universal.
Menurut Immanuel Kant, ada tiga patokan untuk menentukan apakah perbuatan seseorang
dikategorikan sebagai tindakan bermoral atau tidak.
Tiga hal ini dalam pemikiran etika Kant masuk dalam syarat-syarat imperatif kategoris,
yaitu perintah mutlak yang wajib kita patuhi. Ketiga patokan tersebut adalah prinsip hukum
umum, prinsip hormat terhadap person, dan prinsip otonomi.Seturut dengan prinsip ketiga ini,
Kant membedakan antara legalitas dan moralitas. Legalitas adalah tindakan yang sesuai dengan
kewajiban/hukum.
Legalitas merupakan tindakan yang dilakukan bukan karena kecenderungan langsung,
melainkan demi kepentingan tertentu yang terpuji atau menguntungkan. Misalkan saja ada
seorang penjual yang tidak mau menipu pembelinya. Menurut Kant, tindakan penjual tersebut
belum tentu bermoral. Karena bisa jadi ia melakukan itu bukan karena tindakan itu baik, tetapi
agar pembelinya terus menjadi pelanggannya. Kalau demikian adanya, maka tindakan penjual
tersebut tidak masuk kategori bermoral, tetapi hanya legal saja.

Sedangkan moralitas adalah tindakan yang dilakukan demi untuk kewajiban. Tindakan
ini mengesampingkan unsur-unsur subjektif seperti kepentingan sendiri, melainkan berpedoman
pada kaidah objektif yang menuntut ketaatan kita begitu saja, yaitu hukum yang diberikan oleh
rasio dalam batin kita.
6. Bagaimana pandangan etika situasi dalam bentuk ekstrem ? Argumen-argumen mana bisa
dikemukakan melawan etika situasi itu ?
Jean Paul Sartre (1905-1980) sangat ekstrem dalam memandang persoalan kebebasan
manusia. Pemikiran Sartre berawal dari konsep ada manusia. Ada dibagi menjadi dua, ada
sebagai benda (l’etre-en-soi) dan ada sebagai kesadaran (l’etre-pour-soi). Ada sebagai benda
ialah ada yang menyangkut hal-hal yang bersifat jasmani, ada yang demikian ini merupakan
sekadar ada. Sedangkan ada sebagai kesadaran ialah ada yang menyangkut kesadaran.
Sartre memiliki ide radikal tentang kebebasan manusia. Radikalisasi pemikirannya
tereksploitasi lewat paham kebebasan mutlak. Kebebasan mencakup seluruh eksistensi manusia.
Kebebasan tidak mengenal batas selain oleh kebebasan itu sendiri. Kebebasan sendiri yang
menentukan batas-batasnya. Kebebasan identik dengan eksistensiku sebagai manusia.Pandangan
Sartre ini tidak proporsianal. Ia terlalu menekankan kebebasan individual. Sartre lupa bahwa
manusia secara individual ia juga sosial. Manusia tidak hanya berdiri sendiri tetapi serentak
mengada bersama orang lain. Oleh karena itu, kebebasan eksistensial sebagai kapasitas yang
dimiliki setiap orang untuk menentukan diri hanya dapat diwujudkan dan dihayati dalam
relasinya dengan orang lain.
Merleau Ponty menegaskan kebebasan manusia adalah sebuah keterjalinan yang erat dengan
lingkungan eksistensi yang tidak lain merupakan cara berada manusia dalam lingkungan tertentu.
Lebih lanjut dalam mengkritik pendapat Sartre tentang kebebasan mutlak ia mengatakan bahwa
harus diakui adanya sandiwara dalam kehidupan manusia. Manusia seringkali menilai sikap yang
sama terhadap dunia, karena kecenderungan dalam diri manusia yang takterelakan. Secara
teoritis, manusia memang bebas tetapi secara kongkrit banyak fakta yang membatasi kebebasan
manusia tersebut. Singkatnya tidak ada determinasi absolut dan kebebasan absolut.

Hal senada dikemukakan oleh Karl Jaspers. Menurut Jaspers, membayangkan suatu
kebebasan terlepas dari orang lain itu tidak mungkin. Kebebasan yang menjadi kondisi
eksistensial dari hakikatnya yang sejati harus dihayati bersama orang lain. Oleh karena itu,
Jaspers menolak kebebasan mutlak. Bagi dia, tidak ada kebebasan yang diisolasi, karena dimana
ada kebebasan di situ selalu ada pertentangan dan ketidakbebasan dan kalau ketidakbebasan
sepenuhnya diatasi dengan jalan meniadakan segala halangan, maka kebebasan itu sendiri akan
hilang.
Senada dengan Marleau dan Jaspers, A.H. Bakker berpendapat bahwa cita-cita tentang
kebebasan mutlak adalah suatu cita-cita yang membawa orang pada tindakan yang tidak
mempedulikan apa dan siapa. Orang akan mengikuti kemauannya sendiri tanpa mengikuti
nasihat, anjuran, dan hukum. Ini merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan. Cita-cita ini
bertolak belakang dengan realitas kongkrit dan berarti menghancurkan diri sendiri.
Albert Camus seorang Sastrawan Prancis sekaligus sahabat dekat Sartre mengajukan kritik
atas pandangan Sartre tentang kebebasan. Ia berpendapat bahwa dengan mencanangkan manusia
sebagai kebebasan dan dengan menganggap kebebasan itu absolut maka terselubunglah
kenyataan bahwa dalam banyak hal manusia tidak bebas. Kalau dikatakan bahwa manusia bebas
seratus persen maka orang tidak akan dikerahkan untuk mengusahakan pembebasan. Manusia
dilukiskan Sartre hidup dalam situasi firdaus yang jauh berbeda dengan kenyataan kongkrit,
dimana manusia sering terbelenggu oleh macam-macam ketidakbebasan
-