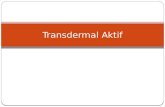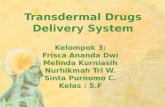Transdermal
-
Upload
frandes-reynaldo-sitio -
Category
Documents
-
view
520 -
download
125
description
Transcript of Transdermal

MAKALAH MATA KULIAH
SISTEM PENGHANTARAN OBAT
“Sediaan Transdermal”
Disusun oleh
Kelompok 1 Paralel
Frandes Reynaldo 0806398215
Nisrina Ramadhyanti 1106067141
Dinar Amalia 1106067242
Izmiaty Nurjanah 1106067425
Masuko Tri Sutandio 1106067570
Nurrahmah Nawwir A. 1106067633
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2014
i

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita hadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan rahmat-Nya, makalah untuk tugas Sistem Penghantaran Obat ini dapat
terselesaikan. Di dalam makalah ini dibahas mengenai sediaan obat transdermal
disertai dengan hal-hal yang berpengaruh pada pemberian obat dengan rute
tersebut.
Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang telah membantu dari
awal pembuatan makalah ini hingga selesai pembuatannya. Ucapan terima kasih
juga diberikan kepada Ibu Dr. Silvia Surini, M.Pharm.Sc dan Ibu Kurnia Sari
Setio Putri S.Farm., M.Farm. yang telah membimbing penulis dalam pembuatan
makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih mempunyai kekurangan.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.
Penyusun berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Depok, Mei 2014
Penulis
ii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDU………………………………. i
KATA PENGANTAR………………………………………………………….
ii
DAFTAR ISI……………………………………………… iii
BAB 1 : PEDAHULUAN
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………....1
1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………..1
1.3 Tujuan Penulisan………………………………………………………....1
1.4 Metode Penulisan………………………………………………………...2
1.5 Sistematika Penulisan……………………………………………………2
BAB II : ISI
2.1 Definisi Sistem Penghantaran Obat Transdermal………………………...
4
2.2 Struktur dan Fisiologi Kulit……………………………………………....
4
2.3 Transdermal Patch………………………………………………………..
7
2.4 Komponen Sediaan Patch........................................................................
10
2.5 Keuntungan patch transdermal………………………………………….
20
2.6 Kerugian Transdermal………………………………………………….. 21
2.7 Transdermal Terbantu (Active Methods for Enhancing Transdermal Drug
Delivery)…………………………………………………………….... 21
2.8. Evaluasi Sediaan Transdermal Patch…………………………………. 36
BAB III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan……………………………………………………………. 41
3.2 Saran…………………………………………………………………... 41
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... 42
iii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem penghantaran obat bermacam-macam, pengembangannya pun
semakin diperbaharui. Pemberian obat secara oral menimbulkan berbagai dilema
dimana obat yang menggunakan jalur ini harus melewati berbagai macam barrier
alami tubuh yang mempengaruhi bioavaibilitas obat dalam tubuh. Masalah-
masalah tersebut meliputi, waktu pengosongan lambung, efek perubahan pH,
deaktivasi enzim dalam lintasan gastrointenstinal, metabolisme lintas pertama di
hati.
1.2. Perumusan Masalah
Makalah sistem penghantaran obat secara transdermal ini disusun
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai :
1. Apa yang dimaksud dengan penghantaran obat secara transdermal?
2. Apa faktor-faktor yang memepengaruhi pemberian obat secara transdermal?
3. Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pemberian obat
secara transdermal?
Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kami menyusun
makalah ini sehingga dapat memberikan keterangan dan pengertian sistem
penghantaran obat secara transdermal.
1.3. Tujuan Penulisan
1. Memberikan penjelasan tentang system penghantaran obat secara transdermal.
2. Memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengarui pemberian
obat secara transdermal.
3. Memberikan penjelasan tentang solusi untuk mengefektifkan pemberian obat
secara transdermal.
1

1.4. Metode Penulisan
Makalah ini disusun dengan cara melakukan studi literatur dari buku
referensi dan mencari sumber lain yang terkait dari media elektronik (internet).
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 : PEDAHULUAN
1.6 Latar Belakang
1.7 Rumusan Masalah
1.8 Tujuan Penulisan
1.9 Metode Penulisan
1.10Sistematika Penulisan
BAB II : ISI
2.3 Definisi Sistem Penghantaran Obat Transdermal
2.4 Struktur dan Fisiologi Kulit
2.4.1 Mekanisme Penetrasi Obat Transdermal
2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Bioavabilitas Sistem Pemberian
Obat Transdermal
2.3 Transdermal Patch
2.8 Komponen Sediaan Patch
2.9 Keuntungan patch transdermal
2.10 Kerugian Transdermal
2.11 Transdermal Terbantu (Active Methods for Enhancing
Transdermal Drug Delivery)
2.11.1 Sonophoresis/ Phonophoresis
2.11.2 Iontoforesis
2.7.3 Elektroporasi
2.8. Evaluasi Sediaan Transdermal Patch
2.8.1 Ketebalan
2.8.2 Keseragaman Bobot
2.8.3 Kandungan Obat
2.8.4 Keseragaman Kandungan
2.8.5 Ketahanan Lipatan (Folding Endurance)
2

2.8.6 Persentase Kelembaban yang Hilang
2.8.7 Permeabilitas Uap Air (Water Vapour Permeability)
2.8.8 Gaya Tarik (Tensile Strength)
2.8.9 Uji Iritasi pada Kulit
2.8.10 Uji Pelepasan Obat In Vitro
BAB III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
3

BAB II
ISI
2.1. Definisi Sistem Penghantaran Obat Transdermal
Sistem penghantaran obat transdermal adalah sistem yang memfasilitasi
obat atau zat aktif masuk ke sirkulasi sistemik melalui kulit dengan dosis terapetik
dan memberikan efek sistemik. Bukti penyerapan obat secara perkutan dapat
dilihat melalui pengukuran konsentrasi obat atau zat aktif dalam darah, deteksi
obat yang diekskresi dan/ atau metabolit obat dalam urin, dan respon klinis pasien
terhadap terapi.
Obat dianggap yang ideal untuk penghantaran melalui transdermal adalah
obat-obat yang dapat bermigrasi melalui kulit ke pembuluh darah tanpa terjadi
penumpukan dalam lapisan dermal. Hal inilah yang menjadi perbedaan obat
sediaan transdermal dengan sediaan topikal. Pada sediaan topikal obat hanya
disebar dan meresap pada kulit bukan pada organ target yang diinginkan.
2.2. Struktur dan Fisiologi Kulit
Gambar 1. Penampang Melintang Kulit
Kulit terdiri atas tiga lapisan, Dari paling luar ke dalam berturut-turut
adalah epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis yang merupakan lapisan
terluar kulit berperan sangat penting bagi proses lewatnya obat melalui kulit.
Lapisan ini tebal, sel-selnya tersusun rapat dan tidak memiliki pembuluh darah.
Lapisan paling luarnya mengalami keratinisasi yang memungkinkan tertahannya
air (mencegah hidrasi) dari dalam sel tubuh dan mencegah masuknya zat-zat asing
dengan mudah ke dalam tubuh. Namun hal ini juga yang menjadi pembelajaran
bagi obat-obat yang diinginkan diadministrasikan melalui kulit.
4

Gambar 2. Penampang Membujur Kulit dan Posisi Patch
2.2.1. Mekanisme Penetrasi Obat Transdermal
Gambar 3. Penghantaran Obat Transdermal
Suatu film pada stratum korneum terbentuk dari sebum dan keringat, tapi
karena komposisinya yang bervariasi dan kontinuitasnya yang minim, ini tidak
menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi penetrasi obat, begitu juga dengan
adanya folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar minyak (sebasea) yang
merupakan sebagian kecil dari permukaan kulit.
Penyerapan obat secara perkutan pada umumnya terjadi dengan penetrasi
langsung obat melalui stratum korneum (tebal 10-15 µm) yang merupakan
jaringan tak hidup. Stratum korneum terdiri dari sekitar 40% protein (terutama
keratin) dan 40% air, dan lipid terutama trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol,
dan fosfolipid. Komponen lipid dianggap sebagai penentu dalam langkah
penyerapan. Ketika molekul obat mencapai lapisan vaskular dermis, molekul obat
5

akan diabsorbsi ke dalam sirkulasi sistemik. Stratum korneum akan menjadi
jaringan kreatin dan bertindak sebagai membran semipermeabel, dan molekul obat
berpentrasi secara difusi pasif. Hal inilah yang menjadi penghalang pada obat
yang diadministrasikan secara transdermal.
Laju pergerakan obat di lapisan stratum korneum tergantung pada
konsentrasi obat dalam pembawa, kelarutan obat dalam air, dan koefisien partisi
minyak-air antara pembawa dan stratum korneum. Zat yang memiliki karakteristik
larut air dan larut minyak merupakan kandidat yang baik untuk difusi menembus
stratum korneum, epidermis, dan dermis. Karena obat yang larut lemak akan
mampu menembus lapisan bilayer sel sementara yang larut air akan dengan
mudah menembus kulit.
Lapisan dermis mengandung sistem kapiler yang mengangkut darah ke
seluruh tubuh. Jika obat mampu menembus stratum korneum, maka obat tersebut
dapat memasuki aliran darah. Proses aliran obat ini tejadi secara difusi pasif, yang
berjalan lambat, hanya untuk menransfer obat-obatan normal.
Gambar 4. Cara Penetrasi Obat di Stratum Korneum
(1. Paraseluler, 2. Intraseluler)
2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Bioavabilitas Sistem Pemberian Obat
Transdermal
- Faktor Fisiologi
1. Stratum korneum: lag time dan zat aktif terikat stratum korneum
2. Segi anatomi
3. Umur
4. Kondisi kulit & penyakit
5. Metabolisme kulit
6. Desquamasi
6

7. Iritasi & penyakit kulit
- Faktor Formulasi
1. Sifat fisikokimia pembawa
2. Konsentrasi obat
3. Luas area aplikasi
4. Massa molekul obat
5. Hidrasi kulit
6. Tebal aplikasi transdermal
7. Lamanya pelekatan sistem transedermal
2.3. Transdermal Patch
Sistem penghantaran obat bermacam-macam, pengembangannya pun
semakin diperbaharui. Pemberian obat secara oral menimbulkan berbagai dilema
dimana obat yang menggunakan jalur ini harus melewati berbagai macam barrier
alami tubuh yang mempengaruhi bioavaibilitas obat dalam tubuh. Masalah-
masalah tersebut meliputi, waktu pengosongan lambung, efek perubahan Ph,
deaktivasi enzim dalam lintasan gastrointenstinal, metabolisme lintas pertama di
hati.
Selain itu pemberian oral untuk obat yang harus dimakan secara teratir
dalam jangka panjang pun menurunkan kepatuhan pasien, serta penggunaannya
sulit dihentikan ketika reaksi obat yang tidak diinginkan muncul.
Oleh karena itu seiring perkembangan teknologi dikembangkanlah sistem
penghantaran obat yang lebih praktis dan efisien dalam terapinya. Seperti
penghantaran secara transdermal.
Menurut Ansel yang dimaksud dengan Transdermal Pacthes (TDDSs)
adalah sediaan yang di desain untuk menghantarkan substansi obat dari
permukaan kulit menembus lapisan-lapisan kulit ke sirkulasi sitemik.
Transdermal patch adalah suatu patch obat yang dapat ditempelkan dan
ditempatkan pada kulit untuk memberikan dosis tertentu obat melalui kulit dan
masuk ke aliran darah. Sistem ini memanfaatkan membran khusus yang didesain
agar dapat mengontrol pelepasan obat yang terkandung dalam resevoir patch yang
dapat melewati kulit dan masuk ke aliran darah.
7

Gambar 5. Gambaran Umum transdermal patch dan cara pemakaiannya
Berdasarkan pembuatannya Transdermal Patch dibagi menjadi dua macam
yaitu:
1. Monolitik
Sistem ini menggabungkan matriks obat antara layer depan dan
belakang. Obat terdispersi di matriks polimer dimana obat dilepaskan dengan
absorpsi perkutan. Dalam penyiapannya obat dan polimer dilarutkan atau
dicampur bersama dan dikeringkan.
2. Sistem Membran Terkontrol
Sistem ini didesain memiliki resevoir atau kantung obat. Biasanya
sediaan dalam bentuk cairan atau gel yang dapat mengontrol laju pelepasan
obat. Contoh obat dengan sistem ini adalah Transderm Nitro (Summit) dan
Transderm-Scop (Baxter). Keuntungan dari sistem ini dibandingkan dengan
sistem monolitik adalah konstannya pelepasan obat selama larutan obat dalam
resevoir masih jenuh.
Gambar 6. Transdermal Patch Sistem Membran Terkontrol (Nitro-Transderm /Summit)
Prinsip pelepasan obat dengan cara transdermal patch ini adalah dengan
difusi dengan mengandalkan gradien konsentrasi dimana konsentrasi obat tinggi
ke konsentrasi nol dari kulit.
8

Gambar 7. Pelepasan Obat dengan sistem transdermal patch di dalam tubuh
Selanjutnya obat akan masuk ke dalam sirkulasi darah melalui beberapa mekanisme, yaitu:
1. Absorpsi Trans-epidermal
Merupakan jalur masuk utama, karena luas permukaan epidermis yang
sangat luas. Penetrasi melalui jalur ini sangat ditentukan oleh stratum
korneum pada epidermis. Jalur difusi melintasi stratum korneum dapat dibagi
menjadi dua jalur, yaitu jalur transseluler dan jalur interseluler.
9
OBAT LEPAS

Gambar 8. Jalur permeasi obat melalui kulit manusia: jalur transseluler
dan intraseluler
2. Absorpsi Trans-appendageal
Merupakan jalur masuknya obat melalui folikel rambut dan kelenjar
keringat. Hal ini dapat terjadi karena adanya pori-pori di antaranya, sehingga
obat dapat berpenetrasi ke dalam kulit hingga mencapai pembuluh darah.
Gambar 9. Folikel Rambut2.4. Komponen Sediaan Patch
Pada kebanyakan desain patch transdermal, obat diletakkan dalam sebuah
reservoar yang ditutup pada satu sisi dengan penutup impermeabel dan satu sisi
lainnya bersifat adesif pada kulit. Pada beberapa desain lain, obat dilarutkan di
dalam reservoar cair atau reservoar berbasis gel sehingga formulasi bisa
disederhanakan dan memungkinkan penggunaan enhancer kimia seperti etanol.
Desain-desain ini memiliki ciri khas yang terdiri dari empat lapisan :
a. membran penutup yang impermeabel
b. reservoar obat
10

c. membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penentu laju
pelepasan obat
d. lapisan adesif. Biasanya bahan yang dipakai adalah silikon,
poliisobutilen, dan akrilat. Akrilat dikenal yang paling sedikit memberikan
iritasi di kulit. Akrilat juga bisa digunakan sebagai matriks pada patch
yang dikontrol oleh matriks..
3. Gambar 10. skema patch dengan empat lapisan.
Desain lain, obat dimasukkan ke dalam matriks polimer padat, sehingga
manufaktur bisa disederhanakan. Sistem matriks memiliki tiga lapisan dengan
mengeliminasi lapisan semi-permeabel atau hanya dua lapisan dengan
memasukkan obat langsung pada komponen adesif.
Gambar 11. skema patch yang pelepasannya dikontrol matriks.
11

Formulasi patch yaitu:
1. Karakteristik dari zat aktif pada sediaan patch diantaranya :
– Harus memiliki sifat kelarutan yang baik dalam air dan minyak
– Ukuran molekul kurang dari ± 100 daltons.
– Obat harus memiliki titik leleh yang rendah
– Molekul obat memiliki koefisien partisi yang seimbang untuk
berpenetrasi melalui stratum korneum.
2. Lapisan Adhesif
Lapisan adhesif adalah material utama yang bertanggungjawab
untuk menciptakan ikatan antara kulit dengan patch. Lapisan adhesif
ini umumnya terdapat dalam bentuk larutan organik, larutan emulsi,
atau dalam bentuk padatan. Larutan organik dan emulsi umumnya
dikombinasi dengan eksipien lain sebelum dikeringkan untuk
menciptakan matriks adhesif.
Terdapat 3 tipe dasar polimer adhesif yang umum digunakan,
dalam sediaan transdermal, yaitu acrylic copolymer, polimer silicon,
dan rubber (karet alam). Setiap lapisan adhesif memiliki afinitas yang
berbeda pada masing-masing obat. Perbedaan lapisan adhesif ini juga
dapat mempengaruhi penghanaran obat melalui kulit. Adapun kriteria
dari lapisan adhesif secara umum adalah :
a. Menjaga patch tetap kontak dengan kulit.
b. Harus sensitif terhadap tekanan.
c. Tidak boleh mengiritasi kulit
d. Harus kompatibel dengan zat lainnya yang terdapat dalam
sistem
e. Harus mudah dilepaskan setelah digunakan
f. Umumnya, dipakai poliisobutilen dan poliakrilat.
3. Backing Films/ Backing Layers
Fungsinya melindungi sistem sediaan dari lingkungan luar dan
mencegah lepasnya zat aktif dari sistem ke lingkungan luar (baik
selama masa penyimpanan maupun sewaktu digunakan). Umumnya,
digunakan tipis polipropilen, polietilen, dan polyolefin.
12

Karakteristik dari backing film diantaranya :
a. Memiliki ikatan yang permanen dengan matriks
b. Tidak reaktif
c. Tidak mengiritasi
d. Nyaman dan dapat diterima secara estetika (tidak terlalu tebal
dan kaku)
4. Realease Liners
- Lapisan penutup yang harus dibuka sebelum sediaan transdermal
digunakan.
- Berguna untuk mencegah hilangnya zat aktif selama penyimpanan
dan untuk mencegah adanya kontaminasi.
- Umumnya terbuat dari silikon, polyester, dan Teflon.
Pada sistem reservoir, zat aktif tersimpan dalam reservoir compartment
yang mengandung obat dalam bentuk larutan atau suspensi yang terpisah dari
release liner karena terseling oleh membrane dan adhesif. Membran memiliki
peranan penting dalam pelepasan dan penghantaran obat. Keuntungan utama dari
bentuk desain ini adalah diperolehnya laju pelepasan orde-nol.
Pada desain Matriks transdermal memiliki karakteristik dimana tidak
terdapat membrane layer yang berfungsi untuk mengontrol laju pelepasan obat.
Penampilan dari system ini mirip dengan system reservoir, tapi pelepasannya
memiliki sistem dimana laju dari penghantaran transdermal dikontrol oleh kulit.
Desain ini paling simple diantara yang lain.
Polimer yang digunakan pada Reservoir dan Matriks harus stabil dan
mampu memberikan pelepasan yg efektif. Polimer yang umum digunakan
diantaranya;
a) Polimer alam: derivat selulosa, zein, gelatin, shellac, wax, gum, chitosan
b) Elastomer sintetik: polibutadien, poliisobutilen, karet silikon, akrilonitril,
neopren
Polimer sintetik: polivinil alkohol, polivinil klorida, polietilen,
polipropilen, poliakrilat,
Enhancer sendiri memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan permeabilitas
kulit dengan merusak/merubah keadaan fisikokimia alami stratum korneum secara
13

reversible untuk mengurangi resistensi difusi. Kriteria peningkat penetrasi yang
baik:
1. Tidak memiliki efek farmakologi
2. Bekerja cepat dan memiliki aksi reversible
3. Stabil secara fisika dan kimia, serta kompatibel dengan komponen lain
pada sistem penghantaran obat
4. Tidak berbau dan tidak berwarna
5. Tidak toksik, tidak membuat alergi, dan tidak mengiritasi kulit
Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan penetrasi terbagi
2, yaitu:
A. Meningkatkan Penetrasi dengan Modifikasi Stratum Korneum
untuk meningkatkan penetrasi obat melalui kulit, dapat dilakukan
dengan memodifikasi struktur dari stratum korneum. Contoh: air,
alkohol, surfaktan, minyak esensial dan terpen, DMSO (Dimethyl
Sulfoxide)
a) Hidrasi
Dengan menambahkan konsentrasi air ke dalam stratum
korneum, dapat meningkatkan hidrasi yang nantinya
mengembangkan dan membuka struktur dari stratum korenum,
lalu penetrasi obat akan meningkat. Peningkatan hidrasi dapat
juga dengan penambahan: paraffin, minyak, emulsi w/o yang
dapat mencegah keluarnya air yang ada di stratum korenum
b) Mengganggu struktur dari lipid
membentuk pori yang nantinya akan meningkatkan penetrasi.
Contoh: Azone, DMSO, alkohol, asam lemak, dan terpen
B. Peningkatan Penetrasi dengan Optimasi Obat dan Karakteristik
Pembawa
a) Prodrug dan Pasangan Ion
Prodrug digunakan untuk meningkatkan penetrasi obat yang
memiliki koefisien partisi yang buruk. Prodrug dapat
meningkatkan koefisien partisi, kelarutan dan transport obat ke
stratum korneum. Pasangan ion digunakan untuk meningkatkan
14

penetrasi obat melalui kulit. Molekul obat yang bermuatan
dibentuk pasangan ion lipofilik untuk meningkatkan penetrasi
obat melalui stratum korneum.
b) Potensi Kimia dari obat dalam pembawa
Laju penetrasi maksimum pada kulit terjadi ketika aktivitas
termodinamik tertinggi yang biasa disebut larutan supersaturasi.
Larutan saturasi dapat terjadi karena adanya penguapan dari
pelarut atau pencampuran dengan kosolven
c) Sistem Eutetik
Titik lebur obat menginduksi kelarutan dan penetrasi kulit.
Sesuai teori, semakin rendah titik lebur semakin baik kelarutan
suatu material pada pelarut termasuk lipid pada kulit. Titik lebur
dari obat ditekan agar sama atau dibawah suhu kulit untuk
meningkatkan kelarutan obat.
Tabel 1: Daftar enhancers yang dapat digunakan
Chemical Class Compounds
Solvent Water
Alcohols Propilenglikol, etanol
Azone dan derivates Azone®(1-dodecylazacycloheptan-2-
one)
Terpenes Menthol, Limonene
Fatty acids Oleic acid, Undecanoic acid
Pyrrolidones and derivates N-methyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidone
Sulfoxides and similar chemicals Dimethyl sulfoxide, Dodecyl methyl
sulfoxide
Surfactants Sodium lauryl sulfate, Cetyltrimethyl
amonium
bromide, Sorbitan monolaurate,
Polisorbate 80,
Dodecyl dimethyl ammoniopropane
sulfate
Ureas Urea
15

1. Urea
Urea meningkatkan permeasi transdermal dengan membantu proses
hidrasi pada stratum korneum dan juga dengan membentuk saluran difusi
hidrofilik pada barrier.
2. Surfaktan
Banyak surfaktan yang mampu berinteraksi dengan stratum korneum
untuk meningkatkan absorpsi obat dari sediaan ketika ditempelkan pada kulit.
Surfaktan bereaksi dengan kulit dengan mendepositokan pada stratum korneum ,
dimana dapat mengacaukan strukturdari stratum korneum. Surfaktan dapat
melarutkan atau menghapus lipid atau konstituen larut air dari dalam atau pada
permukaan stratum korneum dan dengan demikian dapat diangkut ke dalam dan
melalui stratum korneum .
Umumnya , surfaktan anionik lebih efisien daripada surfaktan kationik dan
nonionik dalam meningkatkan penetrasi molekul. Ada beberapa surfaktan anionik
yang dapat bereaksi dengan keratin dan lipid, sedangkan surfaktan kationik yang
dapat bereaksi dengan fibril keratin dari sel-sel cornified dan mengakibatkan
matriks sel - lipid yang terganggu .
Dengan menginduksi fluidisasi lipid pada stratum korneum , surfaktan nonionik
dapat meningkatkan penyerapan . Pengukuran penetrasi kulit sangat berharga
dalam menentukan efek ini dan mengamati pengaruh kimia surfaktan dan
konsentrasi . Dengan demikian, kapasitas stratum korneum untuk
mempertahankan jumlah yang signifikan dari membran terikat air menurun
dengan adanya natrium dodecanoate dan sodium dodesil sulfat. Efek ini mungkin
mudah reversibel pada penghapusan agen . Penyelidikan ini memberikan ide
tentang surfaktan anionik yang mengubah permeabilitas kulit melalui filamen
heliks dari stratum korneum yang dapat mengakibatkan uncoiling dan
perpanjangan filamen keratin membentuk keratin dan ini akan menyebabkan
perluasan membran yang dapat meningkatkan permeabilitas . Temuan terbaru
menunjukkan bahwa penurunan sifat penghalang kulit tidak mungkin hasil dari
perubahan konformasi protein saja . Melalui hasil scanning kalorimetri diferensial
16

ditemukan bahwa sodium lauryl sulfate ( SLS ) terganggu baik lipid dan
komponen protein. Gangguan penghalang kulit tergantung pada aktivitas
monomer dan konsentrasi misel kritis ( CMC ) terjadi karena jumlah surfaktan
yang menembus ke dalam kulit dan di atas CMC, surfaktan ditambahkan ada
sebagai misel dalam larutan misel dan terlalu besar untuk menembus kulit .
Tingkat gangguan penghalang dan peningkatan penetrasi surfaktan ini juga sangat
tergantung pada struktur surfaktan , terutama pada panjang rantai alkil.
1. Dengan mengikat protein permukaan kulit
2. Dengan denaturasi protein permukaan kulit
3. Dengan pelarut atau mengacaukan lipid interseluler kulit
4. Dengan menembus melalui penghalang epidermal lipid
5. Dengan berinteraksi dengan sel hidup
a) Interaksi dengan Protein Kulit
Surfaktan berdifusi melalui daerah lipid. Setelah mengikat protein,
surfaktan menyebabkan denaturasi protein dan menyebabkan
pembengkakan stratum korneum. Melarutkan cairan lipid dan memisahkan
kalsium atau ion multivalent lain untuk mengurangi adhesi korneosit.
b) Interaksi dengan Interselular Lipid Kulit
Penghalang lipid pelindung kulit terdiri dari lapisan lipid yang sangat
terorganisir, terletak di antara sel-sel dari stratum korneum. Surfaktan
masuk ke dalam lapisan lipid untuk mengacaukan dan mengubah fungsi
barrier kulit.
Jenis-jenis surfaktan terbagi menjadi:
1) Surfaktan Anionik
Surfaktan anionik berinteraksi kuat dengan keratin dan lipid. Sodium
Lauryl Sulfate dapat berpenetrasi dan berinteraksi dengan kulit,
menghasilkan perubahan besar sifat barrier. Mekanisme tambahan
untuk meningkatan penetrasi oleh SLS melibatkan interaksi hidrofobik
dari rantai alkil SLS dengan struktur kulit. Proses ini dapat
memisahkan matriks protein, mengurai filamen, dan membuka tempat
mengikat air lebih banyak, sehingga meningkatkan tingkat hidrasi
17

kulit. Surfaktan anionik berpenetrasi buruk melalui stratum korneum
pada waktu yang singkat tetapi permeasi meningkat dengan
meningkatnya waktu aplikasi. Alkil sulfat dapat menembus dan
menghancurkan kekuatan stratum korneum beberapa jam setelah
aplikasi. Surfaktan anionik menyebabkan kerusakan yang lebih besar
dari surfaktan non ionik.
2) Surfaktan Kationik
Surfaktan Kationik berinteraksi dengan protein kulit melalui interaksi
polar dan ikatan hidrofobik. Interaksi hidrofobik antara rantai
surfaktan dan protein menghasilkan pembengkakan stratum corneum.
Molekul kationik lebih merusak jaringan kulit sehingga menyebabkan
perubahan yang lebih besar dari surfaktan anionik.
3) Surfaktan Nonionik
Pertama surfaktan dapat menembus ke daerah interselular stratum
korneum, meningkatkan fluiditas dan melarutkan komponen
lipid. Kedua, penetrasi surfaktan ke dalam matriks interselular diikuti
oleh interaksi dan mengikat filamen keratin dapat mengakibatkan
gangguan dalam korneosit tersebut.
4) Surfaktan Zwitterionik
Lima surfaktan zwitterionik dapat mempengaruhi fungsi barrier kulit
tikus tidak berbulu. Peningkatan kelarutan lipid stratum korneum
merupakan mekanisme penting dari peningkatan penetrasi. Surfaktan
pada penelitian adalah dodecylbetaine, hexadecylbetaine,
hexadecylsulfobetaine, N, oksida amina N-dimetil-N-dodesil, bromida
dodecyltrimethylammonium. (Ridout et.al.)
3. Asam Lemak dan Ester
Yang paling populer adalah asam oleat. Contoh asam lemak antara lain
adalah asam laurat, asam miristat dan asam kaprat. Asam laurat meningkatkan
penghantaran antiestrogen yang sangat lipofilik. Asam oleat sangat meningkatkan
fluks obat-obatan seperti meningkatkan fluks asam salisilat 28 kali lipat dan fluks
5 - flurouracil 56 kali lipat di membran kulit manusia. Peningkat penetrasi
18

dipengaruhi dengan domain lipid dari stratum korneum dan dimodifikasi seperti
yang diharapkan untuk asam lemak rantai panjang dengan cis - konfigurasi.
4. Pirolidon
Pirolidon telah disukai sebagai peningkat permeasi untuk banyak molekul
termasuk hidrofilik (misalnya manitol dan 5-flurouracil) dan lipofilik (misalnya
progesteron dan hidrokortison). Dalam formulasi patch transdermal; N-metil-2-
pyrolidone digunakan sebagai penambah penetrasi untuk kaptopril. Pirolidon
bekerja di stratum korneum dan bertindak dengan mengubah sifat melarutkan
dari membran. Pirolidon membentuk reservoir dalam membran kulit. Jadi efek
dari reservoir akan menambah potensi untuk obat keluar kedalam stratum
corneum secara sustained release dalam jangka waktu yang panjang
5. Sulfoksida dan Senyawa Lain yang Mirip
Peningkat penetrasi saat ini yang paling banyak disukai adalah Dimetil
Sulfoksida (DMSO) . Pemeriannya tidak berwarna , tidak berbau dan memiliki
sifat hydroscopic . DMSO digunakan secara topikal dalam pengobatan
peradangan sistemik . DMSO bekerja sebagai peningka tdan mempercepat
penetrasi dan sebagai pemercepat yang sangat baik tetapi dapat menimbulkan
masalah. Tumpahan bahan ke kulit dapat terasa di mulut dalam hitungan detik.
Pada dasarnya efek peningkat konsentrasi tergantung dan jika konsolven
mengandung >60 % DMSO maka ada kebutuhan peningkatan optimal dalam
keberhasilan. Namun, pada konsentrasi yang relatif tinggi , dapat menyebabkan
eritema dan wheal dari stratum corneum. Zat kimia yang mirip juga sebagai
pemercepat yang telah diselidiki karena DMSO menunjukkan masalah dalam
menggunakan sebagai penambah penetrasi. Dimethyl acetamide (DMAC) dan
dimetil formamida (DMF) adalah pelarut aprotik yang sama kuat.
6. Alkohol, Gliserida, dan glikol
Sebagai sebuah penetration enhancer untuk transdermal, etanol merupakan
penetration enhancer yang paling disukai. Etanol meningkatkan permeasi
ketoprofen dari formulasi gel-spray. Etanol juga digunakan untuk meningkatkan
penetrasi dari metil paraben sebagai pembawa untuk mentol. Kombinasi etanol
dengan Triklorofenol (TCP) dan air digunakan sebagai 2 sistem kosolven untuk
zalcitabine, didanosine, dan zidovudine, tegafur, alclofenac, dan ibuprofen. Rantai
19

pendek gliserida juga efisien sebagai permeation enhancer (ex. TCP). Sebuah
larutan jenuh dari terpen pada propilen glikol (PG)-sistem kosolven air
meningkatkan fluks dari 5-fluorourasil (5-FU), fluks maksimum diperoleh dari
sebuah formulasi yang terdiri dari 80% PG dan terpen karena aktivitas terpen
tergantung pada jumlah PG dan terpen juga dapat meningkatkan partisi dan
permeasi obat. PG, kombinasi dengan azone, dapat menigkatkan fluks dari
metotreksat, piroksisam, siklosporin A, dan 5-FU. Fluks dari estradiol 19 kali
lebih tinggi ketiga menggunakan PG pada konjungsi dengan 5% asam oleat
7. Azon (1-dodeklazikloheptan-2-one atau Laurokapram)
Merupakan molekul pertama/ agen yang secara spesifik didesain sebagai
penetration enhancer kulit. Azon merupakan material lipofilik yang tinggi dan
dapat larut serta kompatibel dengan semua pelarut organik termasuk alkohol dan
propilen glikol. Azon meningkatkan penghantaran pada kulit dari banyak variasi
obat termasuk steroid, antibiotik, dan agen-agen antivirus. Azon secara umum
paling efektif pada konsentrasi yang rendah. Biasanya, azon dikembangkan antara
0,1-5% tetapi lebih sering antara 1-3%.
8. Terpen (Mentol, Limonene), Minyak Esensial, Terpenoid
Terpen telah digunakan untuk banyak tujuan terapi, seperti antispasmodik,
karminatif, pewangi, dan lain-lain, tetapi potensinya juga masih dipertimbangkan
sebagai enhancer absorpsi perkutan. Dengan membentuk sebuah campuran
eutektik dengan obat, L-Mentol telah terbukti meningkatkan absorpsi kulit dari
testosteron dengan cara menurunkan titik leburnya secara drastis dari 153,7
menjadi 39,9°C, sesuai dengan yang diamati oleh studi Differential Scanning
Calorimetry (DSC). Minyak Eukaliptus ditemukan sebagai enhancer yang paling
efektif, menyebabkan peningkatan 60x lipat, sementara minyak pepermin dan
terpentin menunjukkan masing-masing 48 dan 28x lipat. Modus aksi peningkat ini
mungkin terlihat karena proses gabungan partisi dan difusi.
2.5. Keuntungan patch transdermal
Penghantaran transdermal memiliki bermacam keuntungan dibandingkan
pemberian per oral karena penghantaran transdermal secara signifikan tidak
terpengaruh oleh efek lintas pertama hati. Karena zat aktif dihantarkan lewat kulit,
pasien yang mengalami gangguan pencernaan atau tak sadarkan diri bisa dengan
20

mudah menerima pengobatan. Obat yang sifatnya mengiritasi saluran cerna juga
lebih mudah diberikan ke pasien lewat jalur ini. Kemungkinan kerusakan oleh
suasana asam dan enzim di saluran cerna juga bisa dihindari lewat jalur ini.
Penghantaran transdermal juga memiliki keuntungan dibandingkan dengan
injeksi hipodermik yang menyakitkan, menghasilkan sampah medis, dan ada
risiko penularan penyakit akibat pemakaian berulang jarum suntik yang sering
terjadi di negara berkembang. Lagipula penghantaran transdermal sifatnya non-
invasif serta bisa digunakan sendiri oleh pasien. Obatnya bisa dilepaskan konstan
untuk waktu lama (hingga satu minggu). Pasien umumnya mudah menerima
penghantaran transdermal dan harganya terjangkau.
2.6. Kerugian transdermal
Barangkali tantangan terberat untuk penghantaran transdermal adalah
hanya sedikit obat yang bisa diberikan lewat jalur ini yaitu obat dengan bobot
molekul rendah (beberapa ratus dalton) dan lipofilik. Di samping itu, ada
kemungkinan terjadi eritema, iritasi lokal, edema lokal, maupun gatal pada kulit
yang ditempelkan patch. Risiko-risiko ini bisa ditekan dengan merotasi lokasi
penempelan patch.
Pasien harus diberikan instruksi yang jelas pada pemakaian patch agar
lapisan-lapisan patch tidak rusak. Bila terjadi kerusakan pada lapisan reservoar,
jumlah obat yang masuk ke pasien berkurang. Sedangkan bila terjadi kerusakan
pada lapisan rate-controlling membrane, bisa terjadi toksisitas pada pasien.
2.7. Transdermal Terbantu (Active Methods for Enhancing Transdermal
Drug Delivery)
Cara konvensional pemberian obat melalui kulit (transdermal) adalah
dengan pembawa seperti salep, krim, gel, dan teknologi patch pasif. Cara terbaru
untuk meningkatkan penetrasi obat secara pasif telah dikembangkan seperti
dengan menggunakan peningkat penetrasi, sistem jenuh, prodrug atau pendekatan
metabolik, dan liposom. Namun, jumlah obat yang dihantarkan dengan
menggunakan metode ini masih terbatas dan hanya untuk jenis obat tertentu saja
karena sifar penghalang kulit yang tidak berubah secara mendasar.
Salah satu cara untuk meningkatkan penetrasi obat melalui pemberian
secara transdermal adalah dengan menggunakan metode transdermal terbantu.
21

Metode ini melibatkan penggunaan energi eksteral untuk bertindak sebagai motor
penggerak dan atau tindakan untuk mengurangi sifat penghalang subkutan dengan
tujuan untuk meningkatkan permeasi molekul obat ke dalam kulit. Selain itu,
molekul besar seperti peptida atau protein dapat terdegradasi oleh enzim
pencernaan jika diberikan secara oral. Untuk menghindari hal tersebut, pemberian
senyawa obat dengan berat molekul yang besar dapat diformulasikan melalui
metode transdermal terbantu. Metode transdermal terbantu dapat dilakukan
melalui bantuan energi listrik yaitu Elektroporasi dan Iontofofesis, dan dengan
bantuan gelombang ultrasonik yaitu Sonoforesis.
2.7.1. Sonophoresis/ Phonophoresis
1. Definisi
Sonoforesis adalah sebuah proses yang secara eksponensial
meningkatkan penetrasi senyawa topikal semisolid (pengiriman
transdermal) ke dalam epidermis, dermis dan appendageal. Sonophoresis
terjadi karena gelombang ultrasonic menstimulasi getaran mikro dalam
epidermis kulit dan meningkatkan energi kinetik keseluruhan molekul
yang membentuk agen topikal. Sonoforesis banyak digunakan di rumah
sakit untuk penghantaran obat melalui kulit. Apoteker mencampur obat
dan membentuknya menjadi sediaan topikal semisolid (gel, krim, salep),
lalu mentransfer energi ultrasonik dari transduser ke kulit. USG mungkin
meningkatkan transportasi obat oleh kavitasi, acoustic streaming, dan efek
termal.
Gelombang ultrasonic yang digunakan terbagi 2, yaitu
a. LFS (Low Frequency Sonophoresis)
Memiliki frekuensi 10-200 kHz. Saat ini masih dilakukan penelitian
lebih lanjut mengenai penggunaan LFS ini. LFS membentuk kavitasi
hanya pada permukaan kulit tidak membentuk kavitasi didalam kulit.
LFS ini biasanya digunakan untuk senyawa yang memiliki berat
molekul besar
b. HFS (High Frequency Sonophoresis)
22

Memiliki frekuensi 0,7-16 MHz. Menurut penelitian, HFS lebih sering
digunakan dibandingkan HFS karena lebih aman. Frekuensi yang
biasanya digunakan yaitu 1-3 MHz. HFS sendiri lebih baik digunakan
untuk molekul yang memiliki senyawa dengan berat molekul yang
kecil.
2. Mekanisme pelepasan Sonoforesis
Sonoforesis memiliki 3 mekanisme dalam pelepasannya, yaitu:
a. Efek termal
Ketika ultrasonik melewati medium, energi sebagian diserap. Dalam
tubuh manusia,, energi ultrasonik yang diserap oleh jaringan
menyebabkan kenaikan suhu lokal yang tergantung pada frekuensi
ultrasonik, intensitas, luas permukaan alat penghantar ultrasonik,
durasi eksposur, dan tingkat pemindahan panas ke aliran darah (atau
konduksi). Kenaikan suhu yang dihasilkan dari kulit memungkinkan
peningkatan permeabilitas akibat terjadi peningkatan difusivitas kulit.
Suhu kulit meningkat sebesar 20˚ C dengan ultrasonik frekuensi
rendah (20 kHz), dan pengiriman manitol ditingkatkan 35 kali lipat.
Namun, penghantaran manitol hanya 25% ketika kulit dipanaskan
sampai tingkat yang sama tanpa bantuan ultrasonik. Parameter
keamanan paparan ultrasonik adalah time to threshold (TT). TT
mengindikasikan berapa lama jaringan aman apabila terpapar
ultrasonik.
b. Kavitasi
Kavitasi merupakan pembentukan rongga berisi udara (gas) pada
medium selama pemaparan ultrasonik. Kavitasi akan menyebabkan
pertumbuhan gelembung yang cepat dan gelembung akan pecah.
Kavitasi juga dapat berupa pergerakan gelembung yang lambat.
Pecahnya gelembung akan menimbulkan getaran yang dapat
menimbulkan perubahan struktur jaringan di sekitarnya. Kavitasi
menyebabkan adanya kerusakan lemak pada stratum korneum yang
menjadikan peningkatan jumlah air yang berpenetrasi melalui daerah
23

dengan lemak yang rusak. Kavitasi penting ketika digunakan
ultrasonik berfrekuensi rendah, paparan pada cairan yang mengandung
gas, atau pada rongga yang mengandung gas.
Gambar 12: Mekanisme Kavitasi
Gambar 13: Efek kavitasi pada subkutan
c. Efek acoustic streaming
Acoustic streaming merupakan perkembangan dari aliran listrik satu
arah dalam suatu cairan yang disebabkan oleh gelombang ultrasonik.
Penyebab utama acoustic streaming adalah pemantulan gelombang
ultrasonik dan distorsi lainnya yang terjadi selama pemaparan. Osilasi
24

dari gelembung yang terbentuk juga menyebabkan acoustic streaming.
Acoustic streaming penting apabila medium memiliki impedansi yang
berbeda dengan jaringan sekitar.
3. Aplikasi Sonoforesis
Penggunaan alat ultrasonik sebagai peningkat penetrasi dapat
memberikan rasa tidak nyaman terhadap pasien. Oleh karena itu,
penggunaan ultrasonik dalam beberapa obat dilakukan sebagai
pretreatment sebelum pemberian obat. Beberapa penelitian in vivo
menunjukkan perbedaan pretreatment kulit dengan pemaparan ultrasonik
berfrekuensi rendah dapat meningkatkan permeabilitas kulit dan
membantu penetrasi obat. Pretreatment dilakukan dengan memaparkan
ultrasonik berfrekuensi rendah terhadap kulit (20 kHz, 7 W/cm2).
Pemaparan menggunakan ultrasonik pada kulit mencit akan meningkatkan
konduktivitas kulit sekitar 60 kali. Kemudian insulin diberikan pada kulit
yang sebelumnya telah diberi pretreatment ultrasonik. Cara ini akan
menurunkan kadar glukosa darah sebanyak 80% dalam waktu 2 jam.
Sementara pada kulit yang sebelumnya tidak diberi pretreatment, tidak
terjadi penurunan kadar glukosa darah (dalam 2 jam). Berikut ini
merupakan beberapa penelitian mengenai sonoforesis sebagai
pretreatment untuk meningkatkan penetrasi obat
Tabel 2: Hasil penelitian penggunaan sonoforesis pada kardiotonik, vasodilator,
dan hormon
25

Penggunan enhancer berupa ultrasonik harus memperhatikan
keselamatan dan kenyamanan pasien. Pasien harus menggunakan sebuah
alat yang mudah dipakai. Untuk memberikan kenyamanan pada pasien
26

diciptakan sebuah alat yang dinamakan flextensional tranducer yang
menggunakan cymbal ultrasonik berfrekuensi rendah. Desain dari
transducer cymbal adalah pennggabungan dua kap logam yang
dihubungkan pada keramik timah-zincornat-titanat
Gambar 14: Sontra’s SonoPrep Skin Permeation Device
Gambar 15: Ultrasonic Transducer
4. Keuntungan dan Kerugian Sonoforesis
Tabel 3: Keuntungan dan Kerugian Sonophoresis
27

Keuntungan Kerugian
- Meningkatkan penetrasi obat
- Memungkinkan kontrol yang
ketat dari laju penetrasi
transdermal
- Mengurangi frekuensi dosis
pemberian dan meningkatkan
kepatuhan pasien
- Meningkatkan kontrol
pelepasan konsentrasi obat
dengan indeks terapi sempit
- Mengurangi fluktuasi kadar
plasma obat
- Menghindari metabolisme
lintas pertama di hati dan
menghindari iritasi lambung
(obat tertentu)
- Mudah dalam penghentiannya
apabila terjadi toksisitas
- Membutuhkan waktu yang
cukup lama dalam pemberian
obat melalui sonophoresis
- Stratum korneum harus dalam
kondisi baik agar penetrasi
obat dapat efektif
- Timbul iritasi dan kulit yang
terbakar
Tabel 3: Keuntungan dan Kerugian Sonoforesis
2.7.2. Iontophoresis
1. Pendahuluan
Stratum korneum merupakan barrier utama absorpsi obat melalui kulit
dalam sistem transdermal dan menghambat permeasi beberapa senyawa obat
hidrofilik, obat berbobot molekul besar, dan bermuatan, seperti misalnya peptida.
Maka diperlukan suatu teknologi yang dapat mengatasi berbagai permasalahan ini
agar penghantaran obat secara transdermal dapat efektif, yakni dengan
memfasilitasi penghantaran, salah satunya dengan bantuan arus listrik.
Iontoforesis didefinisikan secara sederhana sebagai teknik untuk meningkatkan
penetrasi obat ke kulit dengan menggunakan arus listrik langsung. Adanya energi
listrik membantu perpindahan ion melewati kulit menggunakan prinsip “like
28

charges repel each other and opposite charges attract”, yakni muatan yang sama
saling tolak-menolak dan muatan yang berlawanan saling tarik-menarik.
Ketika obat bermuatan negatif (anion) akan dihantarkan melewati barrier
epitel, maka diletakkan dibawah elektroda penghantar bermuatan negatif (katode)
sehingga akan terjadi tolak menolak untuk ditarik menuju elektroda bermuatan
positif yang diletakkan ditempat lain tertentu pada tubuh. Sistem tersebut dikenal
dengan katodal iontoforesis. Sementara, dalam sistem anodal iontoforesis, ion
bermuatan positif (kation) diletakkan dibawah anoda (elektroda bermuatan
positif). Hanya satu elektroda saja yang dapat diisi dengan zat aktif yang terlarut
dalam pelarut yang sesuai. Maka elektroda yang berisi obat disebut sebagai
elektroda aktif (active electrode) dan elektroda sisanya disebut sebagai elektroda
kembali (return electrode/indifferent electrode) yang berisi ion buffer untuk
mengurangi lonjakan pH selama proses berlangsung.
2. Mekanisme
Elektromigrasi/ Elektrorepulsi: Perpindahan ion karena adanya
arus listrik yang menyebabkan interaksi medan listrik ion sehingga
memberikan gaya repulsi (tolak menolak) yang mendorong ion
melalui kulit. Elektromigrasi ini merupakan mekanisme yang
paling dominan
Elektroosmosis: Elektroosmosis menghasilkan gerakan massal
pelarut yang membawa ion. Kulit bermuatan negatif pada pH di
atas 4, maka gugusan bermuatan positif seperti ion Ag+ akan lebih
mudah menembus, karena berusaha untuk menetralkan muatan ke
dalam kulit. Maka transfer ion akan berasal dari anoda menuju ke
katoda. Untuk mengkompensasi hilangnya kation (Ag+) dari
elektroda dalam proses ini, counter ion, anion (Cl-) bergerak dari
sebrang arah, dari katoda ke anoda
Permeabilisasi ke kulit dengan arus listrik: Adanya arus listrik
merubah susunan molekular komponenkulit. Perubahan ini dapat
menghasilkan perubahan permeabilitas kulit
3. Faktor yang mempengaruhi Penghantaran
a. Faktor Formulasi
29

- kosentrasi obat : Tergantung dari obat yang digunakan, the steady-
state flux (perpindahan ion) menunjukkan peningkatan konsentrasi
larutan dalam kompartemen donor, misal penghantaran elektroda.
Peningkatan ambilan oleh kulit selama dan setelah iontoforesis,
dengan meningkatkan konsentrasi obat. Faktor penentu yang perlu
dipertimbangkan yakni kekuatan dari arus yang digunakan
- pH larutan : pH adalah faktor penting dalam penghantaran obat
menggunakan iontoforesis. pH yang tepat ini bergantung dari obat
yang akan digunakan, yakni pada pH berapa obat tersebut akan
membentuk ion.
- Buffer : : Adanya buffer akan menurunkan kompetisi ion yang
dapat mencegah perubahan pH
b. Sifat Fisikokimia
- Ukuran molekul obat: koefisien permeabilitas dari larutan muatan
positif, negatif, dan larutan tak bermuatan melewati membrane
tergantung pula dari ukuran molekul. Apabila ukuran molekul
besar, maka koefisien permeabilitas rendah. Sebaliknya, bila
ukuran molekul kecil maka koefisien permeabilitas besar sehingga
obat dapat dengan mudah melewati kulit.
- Muatan: Muatan obat sangat mempengaruhi tempat di bagian
elektroda mana ia akan dihantarkan. Obat yang bermuatan positif
akan diletakkan pada elektroda yang bermuatan positif (Anoda)
dan begitu pula sebaliknya.
- Kelarutan : Kelarutan obat harus baik, sehingga dapat dihantarkan
dengan baik
c. Kondisi Administrasi
- Densitas Arus: adalah jumlah arus yang dihantarkan per unit luas
permukaan. Kriteria yang harus dipertimbangkan adalah
menentukan densitas arus yang tepat untuk iontoforesis. Arus harus
cukup mampu untuk menyedikan laju pelepasan obat yang
30

diinginkan. Namun, tidak boleh memberikan efek yang berbahaya
bagi kulit. (densitas arus: <0,5 mA/cm2)
- Intensitas arus: Arus amper rendah bekerja lebih baik dibanding
amper tinggi, intensitas yang direkomendasikan yakni 3-5 mA.
- Durasi iontoforesis: Durasi berlangsung Antara 10-20 menit,
namun bisa jadi lebih dari 20 menit. Dilakukan pengecekan setiap
3-5 menit untuk mengecek tanda-tanda adanya luka bakar
- Arus Konstan : Aplikasi arus konstan atau kontinu dalam jangka
waktu yang lama dapat menyebabkan polarisasi kulit yang akan
menurunkan efisiensi penhantaran iontoforesis. Polarisasi ini dapat
diatasi dengan menggunakan pulsed DC atau aliran langsung
berdenyut atau aliran langsung yang diberikan secara periodic
- Jenis Elektroda : Elektroda platina atau elektroda inert lainnya
seperti nikel atau stainless steel diketahui dapat menyebabkan
perubahan pH dan gelembung gas karena dekomposisi air sehingga
menyebabkan produksi ion H+ dan OH-. Namun Penggunaan
elektroda Ag/AgCl ini tidak menyebabkan penyimpangan pH.
d. Faktor Biologi
Faktor anatomi pasien sangat mempengaruhi derajat penetrasi yang
bervariasi dari pasien ke pasien termasuk ketebalankulit tempat
aplikasi, adanya jatingan adipose.Adanya inflamasi yang parah pada
kulit juga dapat berpengaruh.
4. Kelebihan dan Kekurangan
- Kelebihan
• Menghindari risiko dan ketidaknyamanan Terapi parenteral.
• pemutusan pemberian obat mudah dalam kasus toksisitas.
• Menawarkan kontrol yang lebih baik atas jumlah obat disampaikan karena
jumlah obat disampaikan tergantung pada saat ini diterapkan, durasi
arus diterapkan, dan daerah kulit yang terpapar.
31

• Mencegah variasi dalam penyerapa seperti yang terlihat dengan pemberian
oral.
• Mencegah first pass metabolism
• Menghindari degradasi sediaan pada saluran pencernaan
• Simple administrasi non invasif dan meningkatkan bioavailabilitas.
- Kekurangan
• Administrasi obat berlangsung lama 15-20 menit atau lebih
• Tidak untuk obat dengan molekul besar
• Rasa geli, iritasi kecil, dan rasa terbakar dapat terjadi
• Ada batas untuk jumlah obat, yang dapat disampaikan biasanya 5 sampai
10mg/hr
• Perlu alat khusus
2.7.3. Elektroporasi
Pada tahun 2008, Prauznitz dan Langer mempublikasikan sebuah paper
yang didalamnya mereka mengajukan 3 generasi dari penghantaran obat
transdermal (TDDS). Tiga generasi tersebut adalah :
• Generasi 1 TDDS :
Meliputi patch konvensional seperti patch klonidin atau estrogen
• Generasi 2 :
Meliputi patch yang ditambahkan dengan komponen lain yang dapat
meningkatkan efektivitas penghantaran obat
• Generasi 3 dari TDDS:
Memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan jangkauan molekul
sehingga dapat ditransportasikan melalui kulit.
Sistem penghantaran transdermal generasi 3 ini bertujuan untuk
mengacaukan lapisan lipid bilayer stratum korneum sehingga memungkinkan obat
dengan ukuran molekul besar dapat menembus lapisan kulit dan berpenetrasi
32

dalam kulit dan masuk ke sirkulasi. Yang termasuk dalam sistem penghantaran
obat transdermal generasi ketiga :
1. Iontoforesis
2. Elektroporasi
3. Ablasi termal
4. PassPort System
5. Penggunaan ultrasound sebagai peningkat absorbs perkutan
6. Microneedles
Elektroporasi merupakan metode untuk meningkatkan penetrasi obat
melintasi hambatan biologis (skin penetration enhacer). Elektroporasi
mengaplikasi rangsangan tegangan tinggi untuk menginduksi pengacauan
membran lipid bilayer pada stratum korneum sehingga meningkatkan
permeabilitas dan obat mudah terdifusi. Tegangan tinggi (≥ 100 V) dan jangka
waktu pendek (milidetik) adalah yang paling sering digunakan.
1. Definisi elektroporasi
Elektroporasi merupakan sistem yang dapat mengacaukan susunan
membran lipid bilayer secara reversibel menggunakan getaran-getaran listrik
bertegangan tinggi. Sistem ini diaplikasikan pada kulit dan telah menunjukkan
peningkatan penghantaran obat transdermal melalui berbagai mekanisme.
Elektroforesis dapat digunakan secara tunggal maupun secara kombinasi dengan
metode peningkat penetrasi molekul lainnya, dapat juga dilakukan bersama
dengan peningkatan luas permukaan obat sehingga obat tersebut dapat
dihantarkan secara transdermal. Tegangan tinggi (≥ 100 V) dan jangka waktu
pendek (milidetik) adalah yang paling sering digunakan.
2. Karakteristik Elektroporasi
Ada tiga karakteristik diharapkan dapat terdapat pada sediaan
elektroposari transdermal:
1. Peningkatan dramatis dalam transmembran transport selama terjadi
rangsangan listrik
33

2. Dapat mengembalikan sifat dasar lipid bilayer secara reversibel baik
parsial reversibel maupun full reversibel dalam waktu beberapa menit
hingga beberapa jam.
3. Sesuai untuk mengubah struktural membrane barrier.
3. Mekanisme dalam meningkatkan penetrasi molekul obat
Mekanisme penetrasi obat adalah melalui pembentukan pori-pori sementara
yang disebabkan oleh adanya listrik tegangan tinggi (50-1000 volt). Pori yang
terbentuk ini memungkinkan masuknya makromolekul lebih mudah. Mekanisme
kerja elektroporasi yaitu dengan menciptakan pori-pori aqueous pada stratum
corneum, namun mekanisme ini masih kontroversial. Mekanisme ini tidak dapat
diidentifikasi menggunakan pengamatan mikroskop, karena ukuran porinya yang
sangat kecil (sekitar 10 nm) dan distribusi pori yang kecil (hanya <0,1% dari total
luas kulit yang diaplikasikan elektroporasi) dan waktu munculnya yang hanya
sebentar (mili-detik hingga detik).
Gambar 16: Mekanisme kerja sistem elektroporasi
4. Keunggulan elektroporasi
Sistem penghantaran secara elektroporasi tidak bersifat infasif karena dapat
mengembalikan sifat dasar lipid bilayer secara reversibel baik parsial reversibel
maupun full reversibel dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam. Sistem
ini dapat menghantarkan molekul sintetik dan makromolekul kecil (<10 kDa)
misalnya peptide (<6 kDa), oligonukleotida (<5 kDa) dan beberapa molekul yang
lebih besar diantaranya : heparin (12 kDa), insulin, vaksin, dan DNA. Getaran
elektroforesis dari 10-100 volt yang diaplikasikan selama mikrodetik sampai
milidetik diketahui aman dan tidak tercipta rasa sakit karena getaran listrik ini
dapat dihantarkan tanpa menimbulkan rasa sakit dengan menggunakan elektroda
34

yang berdekatan untuk membatasi medan listrik dengan saraf bebas pada apisan
stratum korneum.
Pengukuran listrik menunjukkan bahwa resistensi kulit selama elektroporasi
dapat menurun tiga lipat dalam mikrodetik, menunjukkan pemulihan parsial
dalam milidetik, dan menunjukkan pemulihan tambahan dalam beberapa detik
hingga beberapa menit. Hal ini menunjukkan bahwa penghantaran obat dengan
mekanisme elektroforesis memiliki onset yang sangat cepat dan reversibel.
Elektroporasi menggunakan elektroda berupa logam stainless steel untuk
menghantarkan arus listrik.
Pengamatan melalui mikroskop juga menunjukkan hasil bahwa situs
transportasi transdermal selama elektroporasi tersebar secara heterogen, di mana
molekul menyeberangi kulit pada daerah tertentu yang memiliki permeabilitas
tinggi.
5. Contoh Penerapan
Contoh penerapan adalah penghantaran insulin, heparin, molekul-molekul
peptida dan oligonukleotida. Elektroporasi juga digunakan sebagai
elektrokemoterapi. Elektroforesis memfasilitasi tegangan listrik tinggi yang
memungkinkan masuknya obat-obat untuk menembus sel tumor.
Elektroemoterapi ini menunjukkan hasil yang lebih efektif apabila dibandingkan
dengan kemoterapi tunggal pada kulit. Selama 20 tahun, metode elektroforesis
untuk penghantaran obat secara transdermal banyak digunakan dalam dunia
kedokteran. Selain itu, elektroporosi juga digunakan dalam dunia kosmetik yang
dapat mempermudah memasukkan bahan-bahan yang baik bagi kecantikan wajah.
Gambar17 : Electrochemotheraphy
35

i. Contoh sediaan :
Metode elektroporasi sebagai peningkat penghataran obat masih dalam tahap
eksperimen dan pengembangan. Contoh sediaan elektroporasis adalah NeoPulse®
yang dikembangkan oleh perusahaan OncoSec Medical yang merupakan sediaan
untuk pengobatan kanker sel skuamosa, melanoma, dan sarkoma. Merupakan
sediaan yang berisi bleomysin, anti-kanker, yang poten dalam dosis kecil namun
juga sangat toksik. Penggunaan tradisional belomysin yaitu secara infus intravena,
namun dengan penggunaan aplikasi elektroporasi, hanya diperlukan 1/20 dosis
infus intravena.
ii. Parameter yang mengendalikan elektroporasi
1. Elektrokimia
• Bentuk gelombang dari getaran yang dihasilkan
• Tegangan, waktu, jumlah dan laju getaran yang dihasilkan
• Desain elektroda yang digunakan
2. Sifat fisikokimia obat
• Muatan
• Lipofilisitas
• Berat molekul
• Formulasi reservoir
• Modifying agent
36

Tabel 4: Perbedaan Sonoforesis, Iontoforesis, dan Elektroforesis
2.8. Evaluasi Sediaan Transdermal Patch
Evaluasi yang dilakukan terhadap sediaan transdermal patch meliputi
ketebalan, keseragaman bobot, kandungan obat, keseragaman kandungan,
ketahanan lipatan (folding endurance), persentase kelembapan yang hilang,
permeabilitas uap air (Water Vapour Permeability), gaya tarik (tensile strength),
uji iritasi pada kulit, dan uji pelepasan obat in vitro.
2.8.1. Ketebalan
Ketebalan patch diukur pada tiga bagian patch yang berbeda menggunakan
mikrometer digital.
2.8.2. Keseragaman Bobot
37

Keseragaman bobot diukur dengan cara menimbang 10 patch secara acak.
Kemudian dihitung bobot rata-ratanya dan simpangan deviasinya.
2.8.3. Kandungan Obat
Patch pada area tertentu dipotong lalu dilarutkan dalam pelarut yang sesuai
dengan zat aktif dalam volume tertentu. Setelah larut kemudian disaring dan
dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Filtrat yang diperoleh,
diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang
gelombang maksimum tertentu sesuai dengan monografi zat aktif. Nilai serapan
tersebut dibandingkan dengan nilai serapan standar melalui persamaan regresi
linier, sehingga diperoleh kadar zat aktif dalam sediaan. Kandungan obat diambil
dari rata-rata 3 sampel yang berbeda.
2.8.4. Keseragaman Kandungan
10 patch dipilih dan masing-masing patch diuji kandungan obatnya. Jika 9
dari 10 patch memiliki kandungan antara 85%-115% dari nilai yang ditentukan
dan 1 patch mengandung tidak kurang dari 75% dan tidak lebih dari 125% dari
nilai tertentu, maka patch transdermal lulus uji keseragaman kandungan. Tetapi
jika 3 patch memiliki kandungan dalam kisaran 75%-125%, tambah 20 patch
untuk diuji kandungan obatnya. Jika 20 patch memiliki rentang dari 85%-115%,
patch transdermal lulus uji.
2.8.5. Ketahanan Lipatan (Folding Endurance)
Ketahanan lipatan patch diukur dengan cara melipat patch secara berulang-
ulang pada bagian yang sama hingga rusak. Jumlah lipatan yang dapat dilakukan
pada film pada bagian yang sam tanpa menimbulkan kerusakan dihitung sebagai
nilai ketahanan lipatan (folding endurance).
2.8.6. Persentase Kelembaban yang Hilang
Evaluasi ini dilakukan dengan cara patch ditimbang secara akurat kemudian
disimpan dalam desikator yang berisi kalsium klorida anhidrat. Setelah tiga hari,
patch dikeluarkan dan ditimbang. Persentase kelembaban yang hilang dihitung
melalui rumus:
38

% kelembaban yang hilang =
2.8.7. Permeabilitas Uap Air (Water Vapour Permeability)
Permeabilitas uap air dapat ditentukan dengan oven sirkulasi udara alami.
WVP dapat ditentukan dengan rumus berikut:
Water Vapour Permeability = Weight / Area
Dimana, WVP dinyatakan dalam g/m2 per 24 jam, W adalah jumlah uap
yang berpermeasi melalui patch dinyatakan dalam g/24 jam, A adalah luas
permukaan sampel paparan dinyatakan dalam m2.
Gambar 18: Alat Pengukur Water Vapour Permeability
2.8.8. Gaya Tarik (Tensile Strength)
Gaya tarik patch dapat diukur salah satunya menggunakan Universal
strength testing Machine. Sensitifitas mesin ini sebesar 1 g. Alat ini terdiri dari
dua pegangan. Pegangan bagian bawah tidak dapat digerakkan sedangkan
pegangan bagian atas dapat digerakkan. Patch berukuran 4 x 1 cm2 diletakkan
diantara dua pegangan tersebut dan diberikan gaya hingga patch tersebut rusak.
Gaya tarik dari sediaan langsung terbaca melalui alat ini dalam satuan kg. Gaya
tarik yang ditunjukkan didapatkan dari perhitungan:
Gaya tarik =
39

Gambar 19: Universal strength testing Machine
2.8.9. Uji Iritasi pada Kulit
Uji iritasi kulit dilakukan menggunakan kelinci sehat dengan berat rata-rata
sekitar 1,5-2,25 kg. Permukaan dorsal (50cm2) kelinci dibersihkan, dan bulunya
dihilangkan dengan cara dicukur. Kemudian kulit dibersihkan dengan cairan
pembersih. Patch yang diuji diletakkan diatas kulit selama 24 jam kemudian
dilepas dan diamati apakah terjadi iritasi pada kulit hewan coba.
2.8.10. Uji Pelepasan Obat In Vitro
Contoh obat pada uji pelepasan obat in vitro adalah Ketotifen Fumarat
sebagai obat terapi asma dan kondisi alergi lainnya. Permeasi obat melalui kulit
dilakukan menggunakan metode Sel Difusi Franz termodifikasi dengan kapasitas
kompartemen reseptor sebesar 20 ml. Membran cellophane sintetis dipasang
diantara kompartemen donor dan reseptor dari sel difusi. Patch dipotong menjadi
ukuran 1cm2 dan diletakkan pada membran cellophane sintetis. Kompartemen
reseptor diisi dengan dapar fosfat pH 7,4. Larutan dapar pada kompartemen
reseptor secara konstan diaduk menggunakan pengaduk magnetik pada kecepatan
50 rpm, pada suhu 37˚C ±0,5˚C. Sebanyak 1 ml sampel (larutan pada
kompartemen reseptor) dikeluarkan dan diuji kadar zat aktifnya menggunakan
spektrofotometer pada saat jam ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24.
Jumlah sampel sebanyak 1 ml yang diambil dari kompartemen reseptor selalu
diganti dengan larutan dapar fosfat dalam jumlah yang sama setiap kali diambil
untuk diuji kadar zat aktifnya. Jumlah kumulatif obat yang berpermeasi per satuan
luas (cm) patch diplot per satuan waktu.
40

Gambar 20: Perbandingan Pelepasan Ketotifen Fumarat Secara In Vitro
Hasil penelitian menunjukkan obat dilepas dengan pelepasan terkontrol.
Tingkat pelepasan obat meningkat ketika konsentrasi polimer hidrofilik
meningkat. Persentase kumulatif pelepasan obat untuk F1 ditemukan menjadi
95,521 ± 0.982 % pada 8 jam dan untuk F2 ditemukan 67,078 ± 1,875 % pada 24
jam. Pada formulasi F7, HPMC E5 dan Etil Selulosa dengan perbandingan 5:5
dianggap sebagai formulasi terbaik, karena hal itu menunjukkan pelepasan obat in
vitro yang maksimal yaitu, 86,812 ± 0,262 % pada 24 jam.
41

BAB III
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Sistem penghantaran obat transdermal adalah sistem yang memfasilitasi
obat atau zat aktif masuk ke sirkulasi sistemik melalui kulit dengan dosis terapetik
dan memberikan efek sistemik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghanataran
obat secara transdermal ada beberapa faktor, antara lain faktor fisiologi dan faktor
formulasi. Cara yang dapat digunakan untuk mempermudah penghantaran obat
secara transdermal adalah dengan deitambahkan peningkat penetrasi. Ada
beberapa cara yang memperbaiki penghantaran transdermal yang dijelaskan, yaitu
dengan menggunakan ultrasonik yakni sonoforesis, sedangkan dengan
menggunakan arus listrik yaitu iontoforesis dan elektroporesis,
1.2. Saran
Penulis mengharapkan kepada para pembaca agar lebih mengerti mengenai
sistem penghantaran obat secara transdermal, kelebihan dan kekurangannya,
bagaiamana mengatasi kekurangannya, serta mengetahui bagaimana cara
meningkatkan penetrasi obat melalui kulit.
42

DAFTAR PUSTAKA
B. Brown Marc, et al. Transdermal Drug Delivery System: Skin Perturbation Devices. United Kingdom: MedPharm Ltd.
Dhiman Sonia, et al. September, 2011. Transdermal Patches: A Recent Approch to New Drug Delivery System. Rajpura, India: Chitkara College of Pharmacy, Chandigarh-Patiala National Higway
Dhote, Vinod, et al. 2011. Review Iontophoresis: A Potential Emergence of a
Transdermal Drug Delivery System. Sci Pharm. 2012; 80: 1–28
Galkwad, Archana K. 2013. Transdermal drug dlivery system: Formulation
aspects and evaluation. India: Knowledgebase Publishers
Kesarwani, arti, et al. 2013. Theoretical Aspect Of Transdermal Drug Delivery
System. Bulletin of Pharmaceutical Research 2013;3(2):78-89
M.R Prausnitz, Peter M. Elias, et al. 2012. Skin Barrier and Transdermal Drug Delivery.
M. R Prausnitz. 1999. A Practical Assessment of Transdermal Drug Delivery by
Skin Electroporation. Atlanta, USA: School of Chemical Engineering and
Institute for Bioengineering and Bioscience, Georgia Institute of
Technology
Mani, Tamiz et.al. 2010. Design and Evaluation of Transdermal Drug Delivery of
Ketotifen Fumarate. India: Int J Pharm Biomed Res 1(2), 42-47
Panzade, Phrabakar, et al. 2012. Review Iontophoresis: A Functional Approach
for Enhancement of Transdermal Drug Delivery. Asian Journal of
Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2(11) 2012, 01-08.
Patel, Dipen et.al. 2012. Transdermal Drug Delivery System: A Review. India:
The Pharma Innovation
Sharma, Anshu et.al. 2007. Development and Evaluation of Carvedilol
Transdermal Patch. India: Acta Pharm 57, 151-159
Shinde, Anilkumar J. 2010. Physical Penetration Enhancement By Iontophoresis:
A Review. International Journal of Current Pharmaceutical Research Vol 2,
Issue 1
43

Wilson, Ellen Jett. 2011. Three Generations: The Past, Present, and Future of
Transdermal Drug Delivery Systems. Baltimore: College of Southern
Maryland.
http://www.electrotherapy.org/modality/iontophoresis
http://legacy.uspharmacist.com/index.asp?show=article&page=8_1061.htm.
http://www.pharmatutor.org/articles/detail-information-on-transdermal-patches
http://www.pharmainfo.net/reviews/transdermal-drug-delivery-technology-revisited-recent-advances
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700785/
44