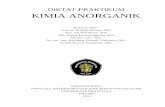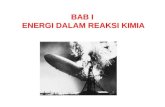tgas kimia anorganik
-
Upload
fitry-wahyuni -
Category
Documents
-
view
164 -
download
0
description
Transcript of tgas kimia anorganik

Tugas kimia anorganik ii
Unsur aluminium(Al), Timbal(Sn),
dan Timbal(Pb)
Oleh :
DIAN AGUS SETYAWATI
A1C111051
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2013

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala atas rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berisi penjelasan tentang
logam Alumunium (Al), Timah (Sn), dan Timbal (Pb) . Makalah ini disusun untuk memenuhi
tugas mata kuliah Kimia Anorganik II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program
Studi Kimia Universitas Jambi.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan makalah ini dengan
baik. Apabila dalam makalah ini masih terdapat banyak kesalahan, hal itu karena
keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam menghasilkan makalah
pada masa yang akan datang. Penulis berharap makalah sederhana ini dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.
Jambi, Maret 2013
Penulis

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1........................................................................................................Latar Belakang Masalah
.......................................................................................................................... 1
1.2.............................................................................................................Rumusan Masalah
.......................................................................................................................... 1
1.3..............................................................................................................Tujuan Penulisan
.......................................................................................................................... 2
BAB II. PEMBAHASAN
2.1. Logam Timbal (Pb).............................................................................................3
Pengertian...................................................................................................... 3
Sumber dan Pembuatan..................................................................................3
Sifat - Sifat......................................................................................................6
Persenyawaan Timbal.....................................................................................8
Manfaat..........................................................................................................11
2.2. Logam Timah(Sn)...............................................................................................13
Pengertian......................................................................................................13
Sumber dan Pembuatan................................................................................ 13
Sifat - Sifat................................................................................................... 15
Isotop Timah.................................................................................................18
Manfaat.........................................................................................................19
Persenyawaan...............................................................................................20
2.3. Logam Aluminium (Al).....................................................................................22
Pengertian.....................................................................................................22
Sejarah..........................................................................................................23
Sumber dan Pembuatan................................................................................23
Sifat - Sifat....................................................................................................25
Manfaat.........................................................................................................29
Persenyawaan...............................................................................................30

BAB III. PENUTUP
3.1. Kesimpulan....................................................................................................... 33
3.2 Saran.................................................................................................................. 34
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan logam berat yang
terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui
proses alami. Apabila timbal terhirup atau tertelan oleh manusia dan di dalam tubuh, ia akan
beredar mengikuti aliran darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan disimpan di
dalam tulang dan gigi.
Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim terdapat dalam
kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral lain terutama seng dan tembaga.
Timah merupakan logam putih keperakan, logam yang mudah ditempa dan bersifat
flesibel, memiliki struktur kristalin, akan tetapi bersifat mudah patah jika didinginkan. Timah
tidak ditemukan dalam unsur bebasnya dibumi akan tetapi diperoleh dari senyawaannya.
Timah merupakan unsur ke-49 yang paling banyak terdapat di kerak bumi.
Aluminium (dalam bentuk bauksit) adalah suatu mineral yang berasal dari magma
asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Proses
pengendapan residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral bahan
galian di tempat. Aluminium merupakan suatu metal reaktif, dan tidak terjadi secara alami.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Apa itu logam timbal, timah, dan alumunium ?
Apa sumber penghasil logam timbal, timah, dan aluminium ?
Bagaimana proses pembuatan logam – logam tersebut ?
Bagaimana sifat fisik dan sifat kimia logam tersebut ?
Bagaimana persenyawaan logam tersebut ?
Apa manfaat dari logam – logam tersebut ?

1.3 TUJUAN PENULISAN
Mengetahui apa itu logam timbal, timah, dan alumunium
Mengetahui apa sumber penghasil logam timbal, timah, dan aluminium
Mengetahui bagaimana proses pembuatan logam – logam tersebut
Mengetahui bagaimana sifat fisik dan sifat kimia logam tersebut
Mengetahui bagaimana persenyawaan logam tersebut
Mengetahui apa manfaat dari logam – logam tersebut

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 LOGAM TIMBAL (Pb)
I. PENGERTIAN TIMBAL
Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan logam berat
yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil
melalui proses alami. Apabila timbal terhirup atau tertelan oleh manusia dan di dalam tubuh,
ia akan beredar mengikuti aliran darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan
disimpan di dalam tulang dan gigi.
Manusia menyerap timbal melalui udara, debu, air dan makanan. Salah satu penyebab
kehadiran timbal adalah pencemaran udara. Yaitu akibat kegiatan transportasi darat yang
menghasilkan bahan pencemar seperti gas CO3, NOx, hidrokarbon, SO2,dan tetraethyl lead,
yang merupakan bahan logam timah hitam (timbal) yang ditambahkan ke dalam bahan bakar
berkualitas rendah untuk menurunkan nilai oktan.
Timbal di udara terutama berasal dari penggunaan bahan bakar bertimbal yang dalam
pembakarannya melepaskan timbal oksida berbentuk debu/partikulat yang dapat terhirup oleh
manusia. Mobil berbahan bakar yang mengandung timbal melepaskan 95 persen timbal.
Sedangkan dalam air minum, timbal dapat berasal dari kontaminasi pipa, solder dan kran air.
Kandungan timbal dalam air sebesar 15mg/l. Dalam makanan, timbal berasal dari
kontaminasi kaleng makanan dan minuman dan solder yang bertimbal. Kandungan timbal
yang tinggi ditemukan dalam sayuran terutama sayuran hijau.
II. SUMBER DAN PEMBUATAN TIMBAL
Timbal tidak ditemukan bebas dialam akan tetapi biasanya ditemukan sebagai biji
mineral bersama dengan logam lain misalnya seng, perak, dan tembaga. Sumber mineral
timbal yang utama adalah “Galena (PbS)” yang mengandung 86,6% Pb, “Cerussite (PbCO3)”,
dan “Anglesite (PbSO4). Kandungan timbal dikerak bumi adalah 14 ppm, sedanngkan
dilautan adalah:
1. Permukaan samudra atlantik : 0,00003 ppm
2. Bagian dalam samudra atlantik : 0,000004 ppm
3. Permukaan Samudra pasifik : 0,00001 ppm
4. Bagian dalam samudra pasifik : 0,000001 ppm

Cara Memproduksi Timbal
Pada umumnya biji timbal mengandung 10% Pb dan biji yang memiliki kandungan
timbal minimum 3% bisa dipakai sebagai bahan baku untuk memproduksi timbal. Biji timbal
pertama kali dihancurkan dan kemudian dipekatkan hingga konsentrasinya mencapai 70%
dengan menggunakan proses “froth flotation” yaitu proses pemisahan dalam industri untuk
memisahkan material yang bersifat hidrofobik dengan hidrofilik.
Kandungan sulfide dalam biji timbal dihilangkan dengan cara memanggang biji
timbal sehingga akan terbentuk timbal oksida (hasil utama) dan campuran antara sulfat dan
silikat timbal dan logam-logam lain yang ada dalam biji timbal. Pemanggangan ini dilakukan
dengan menggunakan aliran udara panas.
Timbal oksida yang terbentuk direduksi dengan menggunakan alat yang dinamakan
“blast furnace” dimana pada proses ini hampir semua timbal oksida akan direduksi menjadi
logam timbal. Hasil timbal dari proses ini belum murni dan masih mengandung kontaminan
seperti Zn, Cd, Ag, Cu, dan Bi. Timbal oksida yang tidak murni ini kemudian dicairkan
dalam “furnace reverberatory” dan di treatment menggunakan udara, uap, dan belerang
dimana kontaminan akan teroksidasi kecuali perak, emas, dan bismuth. Kontaminan ini akan
terapung pada bagian atas sehingga dapat dipisahkan. Logam silver dan emas dipisahkan
dengan menggunakan proses Parkes, dan bismuthnya dihilangkan dengan menggunakan
logam kalsium dan magnesium. Hasil logam yang dihasilkan dari keseluruhan proses ini
adalah logam timbal. Logam timbal yang sangat murni diperoleh dengan cara elektrolisis
meggunakan elektrolit silica flourida.
Ekstraksi Timbal
Pada proses ekstraksi, bijih galena dipekatkan dengan teknik flotasi buih kemudian
ditambahkan sejumlah kwarsa SiO2, dilanjutkan dengan proses pemanggangan terhadap
campuran ini.
Persamaan reaksi pada proses ini :
2PbS(s)+ 3O2(g) 2PbO(s)+ 2SO2(s)
Proses reduksi dilaksanakan dengan batu bara (C) dan air kapur:

PbO(s)+ C(s) Pb (l) + CO(g)
PbO(s)+ CO(g) Pb(l) + CO2(g)
Proses pemanggangan dengan temperature tinggi akan mengubah galena menjadi PbSO4,
sehingga diperlukan penambahan kwarsa (SiO2) untuk mengubah sulfat menjadi silikat.
PbO4(g) + SiO3(g) PbSiO3(s)+ SO3(g)
Silikat dalam proses reduksi akan diubah oleh air kapur, CaO menjadi PbO (tereduksi oleh
batubara) dan kalsium silikat sebagai kerak atau ampas.
PbSiO3(s)+ CaO(s) PbO + CaSiO3(s)
Alternatif lain pada proses reduksi yaitu pemakaian reduktor bijih bakar dari galena segar
sebagai penganti batubara:
PbS(s) + 2PbO(s) Pb(s)+ SO2(g)
Pemurnian logam timbel
Tahap I :melelehkan dibawah titik leleh tembaga sehingga tembaga pengotor
mengkristal dan dapat dipisahkan
Tahap II : meniupkan udara diatas permukaan lelehan timbel, pengotor arsen dan
antimon akan berubah menjadi arsenat dan antimonat. Atau oksidanya
termasuk bismuth sebagai buih atas permukaan dapat diambil keluar.
Tahap III : menambahkan 1-2% seng agar perak atau emas pengotor akan lebih
mudah larut dalam lelehan seng. Campuran didinginkan secara perlahan
dengan suhu 4200C – 4800C. logam perak dan emas akan terbawa dalam
seng yang telah mengkristal sehinga dapat dipisahkan dari lelehan timbal.,
kelebihan sen dapat pula dipisahkan dengan teknik penyulingan vakum
(tekanan rendah)
Tahap IV :melakukan teknik elektrolisis metode Betts, menggunakan elektrolit larutan
timbal heksafluoro silikat (PbSiF6) dan asamnya (H2SiF6). Lembaran-

lembaran tebal timbal dipasang sebagai katoda dan plat-plat timbel belum
murni dipasangkan sebagai anoda. Anoda timbel akan mengalami oksidasi
menjadi larutan Pb2+ yang kemudian akan tereduksi menjadi logam Pb.
Timbel (II) relatif lebih stabil dan lebih banyak ditemui daripada timbel (IV). Timbel (II)
bukan reduktor yang baik bila dibandingkan dengan timah (II) dan timbal (IV) merupakan
oksidator yang baik bila dibandingkan timah (IV).
III.SIFAT - SIFAT TIMBAL (Pb)
Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim terdapat
dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral lain terutama seng dan
tembaga.
Sifat-sifat khusus logam timbal, yaitu :
a) Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan
menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat di bentuk dengan
mudah
b) Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat
sehingga logam Pb dapat digunakan sebagai bahan coating
c) Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logamlogam
biasa kecuali emas dan merkuri
d) Merupakan penghantar listrik yang tidak baik.
Timbal (Plumbum) beracun baik dalam bentuk logam maupun garamnya. Garamnya
yang beracun adalah timbal karbonat (timbal putih), timbal tetraoksida (timbal merah), timbal
monoksida, timbal sulfide, timbale asetat (merupakan penyebab keracunan yang paling sering
terjadi). Nilai ambang toksisitas timbal (total limit values atau TLV) adalah 0,2 miligram/m3.
1. Sifat-sifat Fisika

1. Si
fat
-
sifat Kimia
Ciri-ciri Fisik
Keadaan benda Padat
Massa jenis (sekitar suhu kamar) 11.34 g/cm³
Massa jenis cair pada titik lebur 10.66 g/cm³
Titik lebur 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F)
Titik didih 2022 K (1749 °C, 3180 °F)
Titik leleh 327oC
Kalor peleburan 4.77 kJ/mol
Kalor penguapan 179.5 kJ/mol
Kapasitas kalor (25 °C) 26.650 J/(mol·K)
Massa jenis (sekitar suhu kamar) 11.34 g/cm³
Massa jenis cair pada titik lebur 10.66 g/cm³
Titik lebur 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F)
Konduktivitas termal (300 K) 35.3 W/(m·K)
Skala kekerasan Mohs 1.5
Ciri-Ciri Kimia
Nomor atom 82
Nomor massa 207,2
Konfigurasi electron [54Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Tingkat oksidasi +2(lebih stabil) dan +4
Struktur kristal cubic face centered
Bilangan oksidasi 4, 2 (Amphoteric oxide)
Elektronegativitas 2.33 (skala Pauling)
Energi ionisasi (detil) ke-1: 715.6 kJ/mol
ke-2: 1450.5 kJ/mol
ke-3: 3081.5 kJ/mol
Jari-jari atom 180 pm
Jari-jari atom (terhitung) 154 pm
Jari-jari kovalen 147 pm
Jari-jari Van der Waals 202 pm
Struktur kristal cubic face centered

Isotop
Timbal alami adalah campuran 4 isotop: 204Pb (1.48%), 206Pb (23.6%), 207Pb (22.6%)
dan 208Pb (52.3%). Isotop-isotop timbal merupakan produk akhir dari tiga seri unsur
radioaktif alami: 206Pb untuk seri uranium, 207Pb untuk seri aktinium, dan 208Pb untuk seri
torium. Dua puluh tujuh isotop timbal lainnya merupakan radioaktif.
Pengenalan timbal dengan warna endapan
Karakteristik adanya timbel (II) dalam larutan membentuk endapan putih, bila
direaksikan dengan ion sulfat SO42-. Membentuk endapan kuning direaksikan dengan ion
kromat, CrO42-. Membentuk endapat hitam bila direaksikan dengan ion sulfide.
IV. PERSENYAWAAN TIMBAL

Senyawaan timbal yang umum adalah PbN6 timbal azida, timbal bromat
Pb(BrO3)2.2H2O, timbal klorida PbCl2, timbal(II)oksida PbO, Pb(NO3)2, Pb3O4, Pb(C2H5)4,
dan Pb(CH3)4.
Tetra Etil Lead (TEL)
Tetra etil lead disingkat sebagai TEL adalah senyawa organometalik yang memiliki rumus
Pb(CH3CH2). Senyawa ini disintesis dengan mereaksikan antara alloy NaPb dengan etil
klorida dengan reaksi sebagai berikut:
4NaPb + 4 CH3CH2Cl (CH3CH2)4Pb + 4 NaCl + 3 Pb
TEL yang dihasilkan berupa cairan kental tidak berwarna, tidak larut dalam air akan tetapi
larut dalam benzena, petroleum eter, toluena, dan gasoline. TEL dipakai sebagai zat
“antiknocking” pada bahan bakar. TEL jika terbakar tidak hanya menghasilkan CO2 akan
tetapi juga Pb.
(CH3CH2)4Pb + 13O2 8CO2 + 10H2O + Pb
Pb akan terakumulasi dalam mesin sehingga dapat merusak mesin. Oleh sebab itu
ditambahkan 1,2-dibromoetana dan 1,2-dikloroetana bersamaan dengan TEL sehingga akan
dapat dihasilkan PbBr2 dan PbCl2 yang dapat dibuang dari mesin. Karena efek racun terhadap
manusia maka TEL sekarang tidak boleh dipergunakan.
Timbal(II) Klorida PbCl2
PbCl2 merupakan salah satu reagen berbasis timbal yang sangat penting disebabkan dari
senyawa ini dapat dibuat berbagai macam senyawa timbal. Banyak digunakan sebagai bahan
untuk mensintesis timbal titanat dan barium-timbaltitanat, untuk produksi kaca yang
menstransimisikan inframerah, dipakai untuk memproduksi kaca ornament, untuk bahan cat
dan sebagainya. PbCl2 dibuat dari beberapa metode yaitu dengan proses pengendapan
senyawa Pb2+ dengan garam klorida, atau dengan mereaksikan PbO2 dengan HCl.
PbO2(s)+ 4HCl PbCl2(s)+ Cl2 + 2H2O
Atau dibuat dari logam Pb yang direaksikan dengan gas Cl2

Pb + Cl2 PbCl2
Timbal membentuk berbagai macam kompleks dengan klorida. PbCl2 jika dilarutkan dalam
HCl berlebih akan membentuk kompleks PbCl42-. PbCl2 larut juga dalam air panas.
Pb2+ + Cl- PbCl+
PbCl+ + Cl- PbCl2
PbCl2 + Cl- PbCl3-
PbCl3- + Cl- PbCl42-
PbO2
Nama kimianya adalah Plumbi oksida atau Timbal(IV) oksida merupakan oksida timbal
dengan biloks 4. PbO ada dialam sebagai mineral plattnerite. PbO2 bersifat amfoter dimana
dapat larut dalam asam maupun basa. Jika dilarutkan dalam basa kuat akan terbentuk ion
plumbat dengan rumus Pb(OH)62-. Dalam kondisi asam maka biasanya tereduksi menjadi ion
Pb2+. Ion Pb4+ tidak pernah diketemukan dalam larutan. Penggunaan PbO2 yang utama adalah
sebagai katoda dalam accu.
Pb3O4
Dikenal dengan nama timbal tetroksida, minium, atau triplumbi tetroksida. Berupa zat padat
berwarna merah atau oranye. Rumus umumnya adalah Pb3O4 atau 2PbO.PbO2. Memiliki titik
leleh 500oC dimana pada suhu ini Pb3O4 terdekomposisi menjadi PbO dan oksigen. Pb3O4 ini
banyak dipergunakan oleh industri penghasil baterai, kaca timbal, dan cat anti korosi.
Senyawa timbal ini tidak larut dalam air akan tetapi larut dalam HCl, asam asetat glacial, dan
campuran antara asam nitrat dan hydrogen peroksida. Pb3O4 dibuat dari proses kalsinasi dari
PbO2 dengan kehadiran oksigen pada suhu 450-4800C.
Pb3O4 diperoleh dari oksidasi PbO dalam udara terbuka dengan pemanasan pada temperatur
sekitar 4000C-5000C
6PbO(s)+ O2(s) 2Pb3O4(s)

Kuning merah
Timbal(II) Nitrat
Memiliki rumus kimia Pb(NO3)2. Timbal(II) nitrat umumnya merupakan kristal yang tidak
berwarna atau berbentuk bubuk putih, dibandingkan dengan garam timbal yang lain maka
gram timbal ini sangat mudah larut dalam air. Timbal(II) nitrat sangat bersifat racun terhadap
manusia dan merupakan oksidator.
V. MANFAAT TIMBAL
1. Timbal digunakan dalam accu dimana accu ini banyak dipakai dalam bidang automotif.
2. Timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik terutama untuk
warna kuning dan merah.
3. Timbal dipakai dalam industri plastic PVC untuk menutup kawat listrik.
4. Timbal dipakai sebagai proyektil untuk alat tembak dan dipakai pada peralatan pancing
untuk pemberat disebakan timbal memiliki densitas yang tinggi, harganya murah dan
mudah untuk digunakan.
5. Lembaran timbal dipakai sebagai bahan pelapis dinding dalam studio musik.
6. Timbal dipakai untuk pelindung alat-alat kedokteran, laboratorium yang menggunakan
radiasi misalnya sinar X.
7. Timbal cair dipergunakan sebagai agen pendingin dalam peralatan reactor yang
menggunakan timbal sebagai pendingan.
8. Kaca timbal mengandung 12-28% Pb dimana dengan adanya Pb ini akan mengubah
karakteristik optis dari kaca dan mereduksi transmisi radiasi.
9. Timbal banyak dipakai untuk elektroda pada peralatan elektrolisis.
10. Timbal digunakan untuk solder untuk industri elektronik.
11. Timbal dipakai dalam berbagai kabel listrik bertegangan tinggi untuk mencegah difusi air
dalam kabel.
12. Timbal ditambahkan dalam peralatan yang terbuat dari kuningan agar tidak licin dan
biasanya digunakan dalam peralatan permesinan.
13. Timbal dipakai dalam raket untuk memperberat massa raket.
14. Timbal karena sifatnya tahan korosi maka dipakai dalam bidang kontruksi.
15. Dalam bentuk senyawaan maka tetra-etil-lead dipakai sebagai anti-knock pada bahan
bakar.

16. Semikonduktor berbahan dasar timbal banyak seperti Timbal telurida, timbal selenida,
dan timbal antimonida dipakai dalam peralatan sel surya dan dipakai dalam peralatan
detector inframerah.
17. Timbal biasanya dipakai untuk menyeimbangkan roda mobil tapi sekarang dilarang
karena pertimbangan lingkungan.
18. Sebagai bingkai kaca-kaca berwarna sebagai lukisan kaca jendela, campuran bahan atap,
dan pipa saluran air.
19. Campuran dengan timah sebagai bahan solder untuk perekat/pematri barang-barang
elektronik.
20. Sebagai pelindung bahan radioaktif
21. Senyawa timbel banyak digunakan sebagai pigment (perwarna), misalnya PbCrO4- kuning
pewarna cat jalan atau bahan plastik, PbMoO4- merah orange, PbO-kuning kenari,
2PbCO3.Pb(OH)2- putih.
22. Dalam industri keramik, PbSi2O5 (PbO.2SiO2) dipakai untuk pelapis glatsir. Pewarna
PbO-merah-orange-kuning (bergantung model pembuatannya) dan senyawa tribasa
timbel sulfat (2PbO.PbSO4.H2O) dipakai untuk memperoleh gelas dengan kerapatan
tinggi, penghantar panas rendah, indeks bias tinggi dan stabilitas tinggi.
23. Pb3O4 dipakai sebagai “cat dasar” terhadap baja, besi dan kayu untuk menghambat
terjadinya korosi dan dipakai untuk pewarnaan pada bahan karet serta plastik.
24. Sebagai pelat-pelat katida PbO2 (berwarna merah cokelat) pada aki dan anode berbentuk
bunga karang (busa) yang terbuat dari logam Pb (dipadu dengan antimon, Sb) dan
elektrolit H2SO4.
25. Tetraetiltimbel (TEL), (C2H5)4, Pb dipakai sebagai bahan antiketuk (antiknocking) dalam
bahan bakar bensin. TEL dapat mengakibatkan polusi udara, senyawa ini sangat beracun
jika masuk dalam tubuh manusia, melekat pada katoda sehingga diperoleh Pb dengan
kemurnian 99,9%.
2.2 LOGAM TIMAH (Sn)
I. PENGERTIAN
Timah dalam bahasa Inggris disebut sebagai Tin dengan symbol kimia Sn. Kata “Tin”
diambila dari nama Dewa bangsa Etruscan “Tinia”. Nama latin dari timah adalah “Stannum”
dimana kata ini berhubungan dengan kata “stagnum” yang dalam bahasa inggris bersinonim

dengan kata “dripping” yang artinya menjadi cair / basah.
Timah merupakan logam putih keperakan, logam yang mudah ditempa dan bersifat
flesibel, memiliki struktur kristalin, akan tetapi bersifat mudah patah jika didinginkan.
II. SUMBER DAN CARA PENGOLAHAN TIMAH
Timah tidak ditemukan dalam unsur bebasnya dibumi akan tetapi diperoleh dari
senyawaannya. Timah merupakan unsur ke-49 yang paling banyak terdapat di kerak bumi
dimana timah memiliki kandungan 2 ppm jika dibandingkan dengan seng 75 ppm, tembaga
50 ppm, dan 14 ppm untuk timbal. Hampir 80% produksi timah diperoleh dari
alluvial/alluvium atau istilahnya deposit sekunder. Diperkirakan untuk mendapatkan 1 Kg
Cassiterite maka sekitar 7 samapi 8 ton biji timah/alluvial harus ditambang disebabkan
konsentrasi cassiterite sangat rendah.
Di bumi timah tersebar tidak merata akan tetapi terdapat dalam satu daerah geografi
dimana sumber penting terdapat di Asia tenggara termasuk china, Myanmar, Thailand,
Malaysia, dan Indonesia.
Cassiterite
Cassiterite adalah mineral timah oksida dengan rumus SnO2. Berbentuk kristal dengan
banyak permukaan mengkilap. Cassiterite adalah sumber mineral untuk menghasilkan
logam timah yang utama dan biasanya terdapat dialam di alluvial atau aluvium.
Stannite
Stannite adalah mineral sulfida dari tembaga, besi dan timah. Rumus kimianya adalah
Cu2FeSnS4 dan merupakan salah satu mineral yang dipakai untuk memproduksi timah.
Stannite mengandung sekitar 28% timah, 13% besi, 30% tembaga, dan 30% belerang.
Stannite berwarna biru hingga abu-abu.
Cylindrite
Cylindrite merupakan mineral sulfonat yang mengandung timah, timbal, antimon, dan
besi. Rumus mineral ini adalah Pb2Sn4FeSb2S14. Cylindrite membentuk kristal
pinakoidal triklinik dimana biasanya berbentuk silinder atau tube dimana bentuk
nyatanya adalah gulungan dari lembaran kristal ini. Warna cylindrite adalah abu-abu
metalik dengan spesifik gravity 5,4.
Cara Memproduksi Timah
1) Ekstraksi Timah

Prinsip pengolahan menjadi logamnya yaitu proses reduksi dari bijih oksida tersebut (SnO2).
pada zaman kuno , reduksi bijih SnO2 dilakukan dengan batubara panas (glowing).
SnO2(s) +2C(s) → Sn(l) +CO2(g)
Pada tahap awal biji timah harus dipekatkan dan ini dilakukan dalam wadah dengan proses
flotasi-buih; dalam proses ini serbuk bijih timah dibuat suspensi dengan air kemudian ke dalamnya
disemprotkan udara melalui saluran yang berlubang-lubang dan berputar akan terjadi gelembung-
gelembung udara yang naik kepermukaan. Penambahan zat aditif tertentu seperti minyak pinus dan
natrium etil santat, akan membentuk buih/busa yang menyelimuti bijih timah sehingga terbawa keatas
bersama dengan gelembung udara untuk kemudian dikumpulkan dengan penumpahan keluar;
sedangkan bijih pengotor tidak dipengaruhi zat aditif tersebut melainkan jatuh ke bagian dasar bak.
Bijih timah yang sudah pekat kemudian dipanggang, karena bijih timah sudah dalam bentuk
oksidanya, maka proses pemanggangan ini bertujuan untuk mengoksidasi logam pengotor dan
menghilangkan belerang dan arsen sebagai oksidanya yang mudah menguap.
Proses selanjutnya yaitu reduksi dengan karbon. Lelehan timah yang belum murni dari hasil
reduksi dengan karbon dipisahkan dari logam-logam lain yang tidak meleleh, diaduk secara kuat dan
kemudian kontak dengan oksigen atmosfer agar terjadi oksidasi pengotor-pengotor yang terlarut dapat
dilakukan dengan menggunakan uap air panas. Oksida-oksida pengotor ini pada pengadukan biasanya
membentuk film yang mengambang diatas permukaan sehingga dapat dipisahkan dari logam
timahnya.
Cara Lain untuk Memproduksi Timah
Berbagai macam metode dipakai untuk membuat timah dari biji timah tergantung dari jenis
biji dan kandungan impuritas dari biji timah. Bijih timah yang biasa digunakan untuk produksi adalah
dengan kandungan 0,8-1% (persen berat) timah atau sedikitnya 0,015% untuk biji timah berupa
bongkahan-bongkahan kecil. Biji timah dihancurkan dan kemudian dipisahkan dari material-material
yang tidak diperlukan, adakalanya biji yang telah dihancurkan dilewatkan dalam “floating tank” dan
titambahkan zat kimia tertentu sehingga biji timahnya bisa terapung sehingga bisa dipisahkan dengan
mudah.
Biji timah kemudian dikeringkan dan dilewatkan dalam alat pemisah magnetik sehingga kita
dapat memisahkan biji timah dari impuritas yang berupa logam besi. Biji timah yang keluar dari
proses ini memiliki konsentrasi timah antara 70-77% dan hampir semuanya berupa mineral
Cassiterite.

Cassiterite selanjutnya diletakkan dalam furnace bersama dengan karbon dalam bentuk coal
atau minyak bumi. Adakalanya juga ditambahkan limestone dan pasir untuk menghilangkan
impuritasnya kemudian material dipanaskan pada suhu 1400 C. Karbon bereaksi dengan CO2 yang
ada didalam furnace membentuk CO, CO ini kemudian bereaksi dengan cassiterite membentuk timah
dan karbondioksida. Logam timah yang dihasilkan dipisahkan melalui bagian bawah furnace untuk
diproses lebih lanjut. Untuk memperoleh timah dengan kemurnian yang tinggi maka dapat dilakukan
dengan menggunakan proses elektrolisis. Dengan cara ini kemurnian timah yang diperoleh bisa
mencapai 99,8%.
III. SIFAT FISIS DAN KIMIA
1. Sifat fisika
TABEL 2.1 Ciri-ciri
fisik Timah
Berdasarkan
tabel, titik leleh timah
(232OC) lebih rendah
dibandingkan dengan timbal dikarenakan timah membentuk struktur koordinasi 12 yang terdistorsi,
bukan murni. Ada 3 macam bentuk timah yang dikenal yaitu timah abu-abu, timah putih-lunak, dan
timah rapuh masing-masing berurutan mempunyai massa jenis 5,75:7,28 dan 6,97 gram/cm3. Timah
putih paling stabil pada temperatur kamar, dan pada temperatur bawah 13,2OC berubah secara
Ciri-ciri Fisik
Keadaan benda Padat
Titik lebur 505.08 K (449.47 °F)
Titik didih 2875 K (4716 °F)
Titik leleh 232 oC
Volume molar 16.29 ×10-6 m3/mol
Kalor penguapan 295.8 kJ/mol
Kalor peleburan 7.029 kJ/mol
Kalor jenis 27,112 J/molK
Tekanan uap 5.78 E-21 Pa at 505 K
Kecepatan suara 2500 m/s pada 293.15 K
Densitas 7,365 g/cm3 (Sn putih); 5,769 g/cm3 (Sn abu-abu)

perlahan menjadi serbuk abu-abu amorf. Jika dipanaskan lagi hingga diatas 161OC, timah akan
berubah menjadi timah rapuh.
Unsur ini memiliki 2 bentuk alotropik pada tekanan normal, yaitu timah alfa dan beta. Timah
alfa biasa disebut timah abu-abu dan stabil dibawah suhu 13,2 C dengan struktur ikatan kovalen
seperti diamond. Sedangkan timah beta berwarna putih dan bersifat logam, stabil pada suhu tinggi,
dan bersifat sebagai konduktor.
1. Sifat Kimia
TABEL 2.2 Ciri-
ciri kimia Timah
Timah
tidak
mudah
dioksidasi
dan tahan
Ciri-Ciri Kimia
Nomor atom 50
Nomor massa 118,71
Elektronegatifitas 1,96 (skala pauli)
Energi ionisasi 1 708,6 kJ/mol
Energi ionisasi 2 1411,8 kJ/mol
Energi ionisasi 3 2943,0 kJ/mol
Elektronegatifitas 1,96 (skala pauli)
Jari-jari atom 145 (145) pm
Jari-jari kovalen 141 pm
Jari-jari van der Waals 217 pm
Konfigurasi elektron [Kr]4d10 5s2 5p2
Elektron per tingkat energi 2, 8, 18, 18, 4
Bilangan oksidasi (Oksida) 4, 2
Struktur KristalTetragonal (Sn putih); kubik diamond
(Sn abu-abu)
Konduktifitas termal 66,8 W/mK

terhadap korosi disebabkan terbentuknya lapisan oksida timah yang menghambat
proses oksidasi lebih jauh. Timah tahan terhadap korosi air distilasi dan air laut, akan
tetapi dapat diserang oleh asam kuat, basa, dan garam asam. Proses oksidasi
dipercepat dengan meningkatnya kandungan oksigen dalam larutan.
Jika timah dipanaskan dengan adanya udara maka akan terbentuk SnO2.
Timah ada dalam dua alotrop yaitu timah alfa dan beta. Timah alfa biasa disebut timah
abu-abu dan stabil dibawah suhu 13,2 C dengan struktur ikatan kovalen seperti
diamond. Sedangkan timah beta berwarna putih dan bersifat logam, stabil pada suhu
tinggi, dan bersifat sebagai konduktor.
Timah larut dalam HCl, HNO3, H2SO4, dan beberapa pelarut organic seperti asam
asetat asam oksalat dan asam sitrat. Timah juga larut dalam basa kuat seperti NaOH
dan KOH.
Timah umumnya memiliki bilangan oksidasi +2 dan +4. Timah(II) cenderung
memiliki sifat logam dan mudah diperoleh dari pelarutan Sn dalam HCl pekat panas.
Timah bereaksi dengan klorin secara langsung membentuk Sn(IV) klorida.
Hidrida timah yang stabil hanya SnH4.
IV. ISOTOP TIMAH
Timah adalah unsur dengan jumlah isotop stabil yang terbanyak dimana jangkauan isotop ini
mulai dari 112 hingga 126. Dari isotop-isotop tersebut yang paling banyak jumlahnya adalah
isotop 120Sn dimana komposisinya mencapai 1/3 dari jumlah isotop Sn yang ada, 116Sn, dan 118Sn.
Isotop yang paling sedikit jumlahnya adalah 115Sn. Beberapa isotop bersifat radioaktif dan beberapa
yang lain bersifat metastabil (dengan lambang m). Berkut beberapa isotop Sn dan kelimpahannya di
alam. Timah memiliki nomor atom 50 dan nomor massa rata-rata adalah 118,71. Dengan nomor atom
tersebut maka timah memiliki konfigurasi elektron [Kr] 5s2 4d10 5p2. Dalam sistem tabel periodik
timah berada pada golongan utama IVA (atau golongan 14 untuk sistem periodik modern) dan periode
5 bersama dengan C, Si, Ge, dan Pb. Timah menunjukkan kesamaan sifat kimia dengan Ge dan Pb
seperti pembentukan keadaan oksidasi +2 dan +4.

V. MANFAAT UNSUR TIMAH
Data pada tahun 2006 menunjukkan bahwa logam timah banyak dipergunakan untuk
solder(52%), industri plating (16%), untuk bahan dasar kimia (13%), kuningan & perunggu
(5,5%), industri gelas (2%), dan berbagai macam aplikasi lain (11%).
Logam Timah dan Paduannya
Logam timah banyak manfaatnya baik digunakan secara tunggal maupun sebagai
paduan logam (alloy) dengan logam yang lain terutama dengan logam tembaga. Logam timah
juga sering dipakai sebagai container dalam berbagai macam industri. Contoh-contoh paduan
antara tembaga dan timah adalah:
Pewter, merupakan paduan antara 85-99% timah dan sisanya tembaga, antimony,
bismuth, dan timbale. Banyak dipakai untuk vas, peralatan ornament rumah, atau
peralatan rumah tangga.

Bronze adalah paduan logam timah dengan tembaga dengan kandungan timah sekitar
12%.
Fosfor Bronze adalah paduan bronze yang ditambahkan unsur fosfor.
Plating
Logam timah banyak dipergunakan untuk melapisi logam lain seperti seng, timbale dan baja
dengan tujuan agar tahan terhadap korosi. Aplikasi ini banyak dipergunakan untuk melapisi
kaleng kemasan makanan dan pelapisan pipa yang terbuat dari logam.
Superkonduktor
Timah memiliki sifat konduktor dibawah suhu 3,72 K. Superkonduktor dari timah merupakan
superkonduktor pertama yang banyak diteliti oleh para ilmuwan contoh superkonduktor
timah yang banyak dipakai adalah Nb3Sn.
Solder
Solder sudah banyak dipakai sejak dahulu kala. Timah dipakai dalam bentuk solder
merupakan campuran antara 5-70% timah dengan timbale akan tetapi campuran 63% timah
dan 37% timbale merupakan komposisi yang umum untuk solder. Solder banyak digunakan
untuk menyambung pipa atau alat elektronik
VI. Pembuatan Senyawaan Kimia Untuk Berbagai Keperluan
Logam timah juga dipakai untuk membuat berbagai maca senyawaan kimia. Salah
satu senyawa kimia yang sangat penting adalah SnO2 dimana dipakai untuk resistor dan
dielektrik, dan digunakan untuk membuat berbagai macam garam timah. Senyawa SnF2
merupakan aditif yang banyak ditambahkan pada pasta gigi. Senyaan timah, tembaga,
barium, kalsium dipakai untuk pembuatan kapasitor.
Senyawaan Organotin
Senyawa organotin adalah senyawa yang dibangun dari timah dan substituen
hidrokarbon sehingga terdapat ikatan C-Sn. Contoh beberapa senyawa organotin ini adalah:
Tetrabutiltimah, dipakai sebagai material dasar untuk sintesis senyawaan di- dan
tributil.
Dialkil atau monoalkil-timah, dipakai sebagai stabilisator panas dalam pembuatan
PVC.

Tributil-Timah oksida, dipakai untuk pengawetan kayu.
Trifenil-Timah asetat, merupakan kristal putih yang dipakai untuk insektisida dan
fungisida.
Trifenil-timah klorida dipakai sebagai biosida
Trimetil-timah klorida, dipakai sebagai biosida dan sintesis senyawa organic.
Trifenil-timah hidroksida, untuk fungisida dan engontrol serangga.
Senyawa organotin dibuat dari reagen Grignard dengan timahtetraklorida. Metode yang lain
adalah dengan menggunakan reaksi Wurtz seperti senyawaan alkil natrium dengan tmah
halide ataupun dengan menggunakan reaksi pertukaran antara timah halide dengan
senyawaan organo-aluminium.
Timah Oksida
Merupakan senyawa anorganik dengan rumus kimia SnO2. Oksida timah ini merupakan
oksida timah yang paling penting dalam pebuatan logam timah. SnO2 memiliki struktur
kristal rutile dimana setiap 1 atom Sn berkoordinasi dengan 6 atom oksigen. SnO 2 tidak larut
dalam air akan tetapi larut dalam asam dan basa kuat. SnO2 larut dalam asam halida
membentuk heksahalostanat seperti:
SnO2 + 6HI H2SnI6 + 2 H2O
Atau jika dilarutkan dalam asam maka:
SnO2 + 6 H2SO4 Sn(SO4)2 + 2 H2O
SnO2 larut dalam basa membentuk stanat dengan rumus umum Na2SnO3. SnO2 digunakan
bersama dengan vanadium oksida sebagai katalis untuk oksidasi senyawa aromatic, dipakai
sebagai pelapis, ataupun sebagai bahan pembuatan organotin.
Timah(II) Klorida
SnCl2 berupa padatan kristal berwarna putih, dapat membentuk dihidrat yang stabil. SnCl2
dipakai sebagai reduktor dalam larutan asam, dan juga dalam cairan electroplating. SnCl2
dibuat dengan cara reaksi gas HCl kering dengan logam Sn.
Sn + 2HCl SnCl2 + H2
SnCl2 memiliki satu pasangan electron bebas. Dalam bentuk fasa gas maka molekul SnCl2
berbentuk bengkok, sedangkan pada bentuk padatan SnCl2 membentuk rantai yang saling

terhubung dengan jembatan klorida. Selain dipakai sebagai reduktor SnCl2 juga dipakai
sebagai katalis, reagen analisis untuk raksa, dan juga dipakai sebagai aditif makanan untuk
mempertahankan warna dan sebagai antioksidan.
Timah(IV) Klorida
Disebut juga stani klorida atau timah tetraklorida merupakan senyawaan kimia dengan rumus
SnCl4. Pada suhu kamar SnCl4 ini merupakan cairan yang tidak berwarna dan akan
membentuk kabut jika terjadi kontak dengan udara. SnCl4 dipergunakan sebagai senjata kimia
dalam perang dunia ke-1, dipakai untuk memperkuat gelas, dan sebagai bahan dasar
pembuatan organotin.
Timah Sulfida
Senyawaan timah dengan belerang terdapat sebagai SnS yaitu timah(II)sulfide dan ada
dialam sebagai mineral herzenbergite. Pebuatan SnS adalah dibuat dengan mereaksikan
belerang, SnCl2 dan H2S. Sn + S SnS
SnCl2 + H2S SnS + 2HCl
Sedangkan timah(IV) sulfide memiliki rumus SnS2 dan terdapat dialam sebagai mineral
berndtite. Senyawa ini mengendap sebagai padatan berwarna coklat dengan penambahan H2S
pada larutan senyawa timah(IV) dan banyak dipakai sebagai ornament dekoratif karena
warnanya mirip emas.
Timah Hidrida
Hidrida dari timah disebut sebagai stannan dan rumus formulanya adalah SnH4. Hidrida
timah ini dapat dibuat dengan cara mereaksikan antara SnCl4 dengan LiAlH4. Stannan
terdekomposisi secara lambat menghasilkan loga timah dan gas hydrogen. Hidrida timah ini
sangat analog dengan gas metana CH4.
Stanat
Dalam ilmu kimia stanat berkoporasi dengan senyawaan:
Ortostanat yang memiliki rumus kimia SnO44- contoh senyawaannya adalah K4SnO4 atau
Mg2SnO4.
Metastanat yaitu MSnO3 atau M2SnO3 yaitu campuran oksida atau polimerik anoin.
Perlu dicatat bahwa asam stanit yang merupakan precursor stanat sebenarnya tidak terdapat
dialam dan ini sebenarnya merupakan hidrat dari SnO2. Istilah stanat juga dipakai untuk

sufiks penamaan senyawa misalnya SnCl62- hesaklorostanat.
2.3 LOGAM ALUMINIUM (Al)
I. PENGERTIAN
Aluminium (dalam bentuk bauksit) adalah suatu mineral yang berasal dari magma
asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Proses
pengendapan residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral bahan
galian di tempat.
Aluminium merupakan suatu metal reaktif, dan tidak terjadi secara alami. Oleh karena
itu, aluminium tak dikenal sebagai unsur terpisah sampai tahun 1820-an, walaupun
keberadaan nya telah diramalkan oleh beberapa ilmuwan yang telah belajar aluminum
campuran. Aluminium pertama kali diproduksi dengan bebas oleh ahli kimia dan ahli ilmu
fisika yang berasal dari Denmark, Hans Oersted Kristen, dan ahli kimia Jerman, Frederich
Wohler, pada pertengahan tahun1820-an. Nama aluminum diperoleh dari bahasa latin:
alumen, yang berarti tawas tawas ( suatu aluminium sulfate mineral).
II. SEJARAH
Pada tahun 1761 de Morveau mengajukan nama alumine untuk basa alum dan
Lavoisier, pada tahun 1787, menebak bahwa ini adalah oksida logam yang belum ditemukan.
Wohler yang biasanya disebut sebagai ilmuwan yang berhasil mengisolasi logam ini pada
1827, walau aluminium tidak murni telah berhasil dipersiapkan oleh Oersted dua tahun
sebelumnya. Pada 1807, Davy memberikan proposal untuk menamakan logam ini aluminum
(walau belum ditemukan saat itu), walau pada akhirnya setuju untuk menggantinya dengan
aluminium. Nama yang terakhir ini sama dengan nama banyak unsur lainnya yang berakhir
dengan “ium”.
Aluminium juga merupakan pengejaan yang dipakai di Amerika sampai tahun 1925
ketika American Chemical Society memutuskan untuk menggantikannya dengan aluminum.
Untuk selanjutnya pengejaan yang terakhir yang digunakan di publikasi-publikasi mereka.
III.SUMBER DAN PENGOLAHAN ALUMINIUM

Metoda untuk mengambil logam aluminium adalah dengan cara mengelektrolisis
alumina yang terlarut dalam cryolite. Metoda ini ditemukan oleh Hall di AS pada tahun 1886
dan pada saat yang bersamaan oleh Heroult di Perancis. Cryolite, bijih alami yang ditemukan
di Greenland sekarang ini tidak lagi digunakan untuk memproduksi aluminium secara
komersil. Penggantinya adalah cariran buatan yang merupakan campuran natrium, aluminium
dan kalsium fluorida.
Aluminium terdapat melimpah dalam kulit bumi, yaitu sekitar 7,6 %. Dengan
kelimpahan sebesar itu, aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan
silikon, serta merupakan unsur logam yang paling melimpah. Namun, Aluminium tetap
merupakan logam yang mahal karena pengolahannya sukar. Mineral aluminium yang bernilai
ekonomis adalah bauksit yang merupakan satu-satunya sumber aluminium. Kriloit digunakan
pada peleburan aluminium, sedang tanah liat banyak digunakan untuk membuat batu bata,
keramik. Di Indonesia, bauksit banyak ditemukan di pulau Bintan dan di tayan (Kalimantan
Barat).
Pengolahan Alumininum
Aluminium dibuat menurut proses Hall-heroult yang ditemukan oleh Charles M. Hall di
Amerika Serikat dan Paul Heroult tahun 1886. Pengolahan aluminium dan bauksit meliputi 2
tahap :
1. Pemurnian bauksit untuk meperoleh alumina murni.
2. Peleburan / reduksi alumina dangan elektrolisis
Pemurnian bauksit melalui cara :
a. Ba direaksikan dengana NaOH(q) . Aluminium oksida akan larut membentuk
NaCl(OH)4.
b. Larutan disaring lalu filtrat yang mengandung NaAl(OH)4 diasamkan dengan
mengalirkan gas CO2, Al mengendap sebagai Al(OH)3.
c. Al(OH)3 disaring lalu dikeringkan dan dipanaskan sehingga diperoleh Al2O3 tak
berair.
d. Bijih –bijih Aluminium yang utama antara lain:
- bauksit

- mika
- tanah liat
Peleburan Alumina
Peleburan ini menggunakan sel elektrolisis yang terdiri atas wadah dari besi berlapis
grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode (-) sedang anode (+) adalah grafit. Campuran
Al2O3 dengan kriolit dan AlF3 dipanaskan hingga mencair dan pada suhu 9500C kemudian
dielektrolisis . Al yang terbentuk berupa zat cair dan terkumpul di dasar wadah lalu
dikeluarkan secara periodik ke dalam cetakan untuk mendapat aluminium batangan (ingot).
Anode grafit terus menerus dihabiskan karena bereaksi dengan O2 sehingga harus diganti dari
waktu ke waktu. Untuk mendapat 1 Kg Al dihabiskan 0,44 anode grafit.
2Al2O3 +3C 4Al + 3CO2
Beberapa nijih Al yang utama :
1. Bauksit (Al2O3. 2H2O)
2. Mika (K-Mg-Al-Slilkat)
3. Tanah liat (Al2Si2O7.2H2O)
Aluminium ada di alam dalam bentuk silikat maupun oksida, yaitu antara lain :
- sebagai silikat misal feldspar, tanah liat, mika
- sebagai oksida anhidrat misal kurondum (untuk amril)
- sebagai hidrat misal bauksit
- sebagai florida misal kriolit.
IV. SIFAT-SIFAT
Aluminium murni, logam putih keperak-perakan memiliki karakteristik yang diinginkan pada
logam. Ia ringan, tidak magnetik dan tidak mudah terpercik, merupakan logam kedua
termudah dalam soal pembentukan, dan keenam dalam soal ductility.
Sifat Fisik Aluminium

Nama, Simbol, dan Nomor Aluminium, Al, 13
Wujud Padat
Massa jenis 2,70 gram/cm3
Massa jenis pada wujud cair 2,375 gram/cm3
Titik lebur 933,47 K, 660,32 oC, 1220,58 oF
Titik didih 2740 K, 2467 oC, 4472,6 oF
Kalor jenis (25 oC) 24,2 J/mol K
Resistansi listrik (20 oC) 28.2 nΩ m
Konduktivitas termal (300 K) 237 W/m K
Pemuaian termal (25 oC) 23.1 µm/m K
Modulus Young 70 Gpa
Modulus geser 26 Gpa
Poisson ratio 0,35
Kekerasan skala Mohs 2,75
Kekerasan skala Vickers 167 Mpa
Kekerasan skala Brinnel 245 Mpa
Radius Atom 1.43 Å
Volume Atom 10 cm3/mol
Massa Atom 26.9815
Radius Kovalensi 1.18 Å
Struktur Kristal Fcc
Konduktivitas Listrik 37.7 x 106 ohm-1cm-1
Formasi Entalpi 10.7 kJ/mol

Konduktivitas Panas 237 Wm-1K-1
Potensial Ionisasi 5.986 V
Kapasitas Panas 0.9 Jg-1K-1
Entalpi Penguapan 290.8 kJ/mol
Sifat Kimia Aluminium
Aluminium merupakan logam yang aktif karena mudah teroksidasi menjadi ion +3.
Logam ini sebagai agen pereduksi yang baik. Sifat sebagai agen pereduksi ini menjadikan
aluminium sering digunakan dalam produksi logam-logam tertentu untuk mendapatkan
logam bebas. Reaksi seperti yang diuraikan ini disebut dengan reaksi thermit.
Al(s)+ Fe2O3(s) Al2O3(l)+ Fe(l) ΔH°= -852 kJmol-1
Aluminium apabila beraksi dalam suasana asam menghasilkan H2
2Al(s)+ 6H+(aq) 2Al3+(aq) + 3H2(g)
Aluminium juga dapat bereaksi dalam suasana basa.
2Al(s)+ 2OH-(aq) + 6H2O 2[Al(OH)4]-(aq) + 3H2(g)
Serbuk aluminium mudah teroksidasi oleh udara atau oksidan lainnya menghasilkan panas
yang tinggi. Dengan sifat ini aluminium sering digunakan pada bahan bakar roket dan proses
peledakan.
2Al(s)+ 3/2 O2(g) Al2O3(s) ∆H = -1.676 kJ
Ciri-ciri Kimia Aluminium

Aluminium oksida
dapat bereaksi dalam suasana asam dan basa (amfoter), tetapi tidak dalam suasana netral.
Al2O3(s)+ 5H+(aq) 2A13+(aq) + 3H2O
A12O3(s)+ 2OH-(aq) 2[A1(OH)4]-(aq)
Aluminium oksida adalah insulator (penghambat) panas dan listrik yang baik. Umumnya
Al2O3 terdapat dalam bentuk kristalin yang disebut corundum atau α-aluminum oksida. Al2O3
dipakai sebagai bahan abrasif dan sebagai komponen dalam alat pemotong, karena sifat
kekerasannya.
Ciri-Ciri Kimia
Nomor atom 13
Oksida (utama) 1,96 (skala pauli)
Sifat oksida Amfoter
Hidroksida Al(OH)3
Kekuatan basa Basa Lemah
Senyawa dengan Klorida AlCl3
Senyawa dengan hidrogen AlH3
Ikatan Ion
Reaksi dengan air menghasilkan bau dan gas H2
Golongan, periode,blok 13, 3, p
Bilangan oksidasi 3, 2 [1], 1 [2] (oksida amfoter)
Elektronegativitas 1,61 (Skala Pauling)
Energi ionisasi (lebih lanjut) 1st: 577,5 kJ·mol−1
2nd: 1816,7 kJ·mol−1
3rd: 2744,8 kJ·mol−1
Jari-jari atom 125 pm
Jari-jari atom (perhitungan) 118 pm
Jari-jari kovalen 118 pm
Struktur kristalkubus berpusat muka 0,40494
nm

Aluminium oksida berperan penting dalam ketahanan logam aluminium terhadap perkaratan
dengan udara. Logam aluminium sebenarnya amat mudah bereaksi dengan oksigen di udara.
Aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida, yang terbentuk sebagai
lapisan tipis yang dengan cepat menutupi permukaan aluminium. Lapisan ini melindungi
logam aluminium dari oksidasi lebih lanjut. Ketebalan lapisan ini dapat ditingkatkan melalui
proses anodisasi. Beberapa alloy (paduan logam), seperti perunggu aluminium,
memanfaatkan sifat ini dengan menambahkan aluminium pada alloy untuk meningkatkan
ketahanan terhadap korosi.
Al2O3 yang dihasilkan melalui anodisasi bersifat amorf, namun beberapa proses oksidasi
seperti plasma electrolytic oxydation menghasilkan sebagian besar Al2O3 dalam bentuk
kristalin, yang meningkatkan kekerasannya.
Oksida aluminium dapat diperoleh dari pemanasan hidroksida dibawah 600°C larut dalam
asam maupun basa, dengan kata lain bersifat amfoter.
V. KEGUNAAN
Beberapa penggunaan aluminium antara lain:
1. Sektor industri otomotif, untuk membuat bak truk dan komponen kendaraan bermotor.
2. untuk membuat badan pesawat terbang.
3. Sektor pembangunan perumahan;untuk kusen pintu dan jendela.
4. Sektor industri makanan ,untuk kemasan berbagai jenis produk.
5. Sektor lain, misal untuk kabel listrik, perabotan rumah tangga dan barang kerajinan.
6. Membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi (III) oksida,
digunakan untuk mengelas baja ditempat, misalnya untuk menyambung rel kereta api.
Beberapa senyawa Aluminium juga banyak penggunaannya, antara lain:
1. Tawas (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O)
Tawas mempunyai rumus kimia KSO4.Al2.(SO4)3.24H2O. Tawas digunakan untuk
menjernihkan air pada pengolahan air minum.
2. Alumina (Al2O3)
Alumin dibedakan atas alfa-allumina dan gamma-allumina. Gamma-alumina
diperoleh dari pemanasan Al(OH)3 di bawah 4500C. Gamma-alumina digunakan

untuk pembuatan aluminium, untuk pasta gigi, dan industri keramik serta industri
gelas. Alfa-allumina diperoleh dari pemanasan Al(OH)3 pada suhu diatas 10000C.
Alfa-allumina terdapat sebagai korundum di alam yang digunakan untuk amplas atau
grinda. Batu mulia, seperti rubi, safir, ametis, dan topaz merupakan alfa-allumina
yang mengandung senyawa unsur logam transisi yang memberi warna pada batu
tersebut. Warna-warna rubi antara lain:
♣ Rubi berwarna merah karena mengandung senyawa kromium (III)
♣ Safir berwarna biru karena mengandung senyawa besi(II), besi(III) dan
titan(IV)
♣ Ametis berwarna violet karena mengandung senyawa kromium (III) dan titan
(IV)
♣ Topaz berwarna kuning karena mengandung besi (III)
VI. SENYAWA
Senyawa yang memiliki kegunaan besar adalah aluminium oksida, sulfat, dan larutan sulfat
dalam kalium. Oksida aluminium, alumina muncul secara alami sebagai ruby, safir,
corundum dan emery dan digunakan dalam pembuatan kaca dan tungku pemanas.
Senyawa organo-aluminum
Senyawa-senyawa organoaluminum digunakan dalam jumlah besar untuk polimerisasi olefin,
dan di industri dihasilkan dari logam aluminum, hidrogen, dan olefin seperti reaksi berikut:
Senyawa ini berupa dimer kecuali yang mengandung gugus hidrokarbon yang meruah.
Misalnya, trimetilaluminum, Al2(CH3)6, adalah dimer dengan gugus metil menjembatani atom
aluminum dengan ikatan tuna elektron (Gambar 5.2). Senyawa organoaluminum sangat
reaktif dan terbakar secara spontan di udara. Senyawa-senyawa ini bereaksi dengan hebat
dengan air dan membentuk hidrokarbon jenuh, dengan aluminium berubah menjadi
aluminium hidroksida sesuai reaksi berikut:

Oleh karena itu, senyawa-senyawa ini harus ditangani di laboratorium dalam atmosfer yang
inert sempurna.
Katalis Ziegler-Natta, yang terdiri atas senyawa organoaluminium dan senyawa logam
transisi membuat fenomena dalam katalisis polimerisasi, katalis ini dikembangkan tahun
1950-an, dan dianugerahi Nobel tahun 1963.
Senyawa alkil logam transisi terbentuk bila senyawa organoaluminum bereaksi dengan
senyawa logam transisi. Senyawa alkil logam transisi yang terbentuk dapat diisolasi bila ligan
penstabil terkordinasi dengan atom logam pusat.
Gallium, Ga, di antara logam yang ada galium memiliki perbedaan titik leleh dan titik didih
terbesar. Karena galium meleleh sedikit di atas suhu kamar, rentang suhu keberadaan cairan
galium sangat lebar dan galium digunakan dalam termometer suhu tinggi. Dalam tahun-tahun
terakhir ini, galium digunakan untuk produksi senyawa semikonduktor galium arsenida,
GaAs dan galium fosfida, GaP.
Indium adalah logam lunak dan juga memiliki titik leleh rendah. Indium digunakan sebagai
bahan baku pembuatan senyawa semikonduktor InP, InAs, dsb. Indium memiliki dua
keadaan stabil, In (I) atau In (III), dan senyawa In (II) dianggap senyawa valensi campuran
indium monovalen dan trivalen.
Talium juga memiliki dua valensi Tl(I) dan Tl(III), dan Tl(II) adalah juga senyawa valensi
campuran Tl monovalen dan trivalen. Karena unsur ini sangat beracun logam dan senyawa ini
harus ditangani dengan sangat hati-hati. Karena senyawa ini adalah reduktor lemah
dibandingkan Na(C5H5), talium siklopentadiena, Tl(C5H5), kadang digunakan untuk preparasi
senyawa siklopentadienil, dan merupakan reagen yang bermanfaat dalam kimia organologam.

BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
1. Timbal atau dikenal sebagai logam Pb dalam susunan unsur merupakan logam berat yang
terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil

melalui proses alami. Timbal tidak ditemukan bebas dialam akan tetapi biasanya
ditemukan sebagai biji mineral bersama dengan logam lain misalnya seng, perak, dan
tembaga.
2. Timbal alami adalah campuran 4 isotop: 204Pb (1.48%), 206Pb (23.6%), 207Pb (22.6%)
dan 208Pb (52.3%). Isotop-isotop timbal merupakan produk akhir dari tiga seri unsur
radioaktif alami: 206Pb untuk seri uranium, 207Pb untuk seri aktinium, dan 208Pb untuk seri
torium. Dua puluh tujuh isotop timbal lainnya merupakan radioaktif.
3. Karakteristik adanya timbel (II) dalam larutan membentuk endapan putih, bila
direaksikan dengan ion sulfat SO42-. Membentuk endapan kuning direaksikan dengan ion
kromat, CrO42-. Membentuk endapat hitam bila direaksikan dengan ion sulfide.
4. Timah merupakan logam putih keperakan, logam yang mudah ditempa dan bersifat
flesibel, memiliki struktur kristalin, akan tetapi bersifat mudah patah jika didinginkan.
5. Aluminium (dalam bentuk bauksit) adalah suatu mineral yang berasal dari magma asam
yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Proses pengendapan
residual sendiri merupakan suatu proses pengkonsentrasian mineral bahan galian di
tempat. Aluminium merupakan suatu metal reaktif, dan tidak terjadi secara alami.
6. Aluminium terdapat melimpah dalam kulit bumi, yaitu sekitar 7,6 %. Dengan kelimpahan
sebesar itu, aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon,
serta merupakan unsur logam yang paling melimpah.
3.2 SARAN
Dengan keterbatasan dan kekurangan dari makalah, penulis banyak berharap
para pembaca yang budiman sudi memberikan saran yang membangun kepada
penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan –
kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya
juga para pembaca yang budiman pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.Aluminium. Diunduh pada 16 Maret 2013
http://masteropik.blogspot.com/2010/05/logam-aluminium.html
Anonim. Logam.Diunduh pada 17 Maret 2013

http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-anorganik-universitas/kimia-logam-
golongan-utama/logam-golongan-13-dan-14/
Anonim.Aluminium.Diakses pada 17 Maret 2013
http://ashar-redland.blogspot.com/2011/07/makalah-logam-aluminium.html
Anonim.Timah.Diakses pada 17 Maret 2013
http://www.chem-is-try.org/tabel_periodik/timah/
Christoph Schmitz, Josef Domagala, Petra Haag.2006. Handbook of aluminium recycling:
fundamentals, mechanical preparation, metallurgical processing, plant design.
Vulkan-Verlag GmbH.
Polmear, I. J. 1995. Light Alloys: Metallurgy of the Light Metals. Arnold.
__________. 2006. Light alloys from traditional alloys to nanocrystals. Oxford:
Elsevier/Butterworth-Heinemann