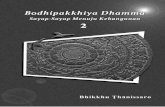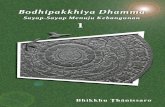TEKNIK PENANGKARAN DAN KUALITAS SUARA CUCAK … · DAFTAR GAMBAR. 1 Struktur organisasi pengelolaan...
Transcript of TEKNIK PENANGKARAN DAN KUALITAS SUARA CUCAK … · DAFTAR GAMBAR. 1 Struktur organisasi pengelolaan...
TEKNIK PENANGKARAN DAN KUALITAS SUARA CUCAK
RAWA (Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) DI MEGA BIRD
AND ORCHID FARM, BOGOR
DINI AYU LESTARI
DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Teknik
Penangkaran dan Kualitas Suara Cucak Rawa (Pycnonotus zeylanicus Gmelin,
1789) di Mega Bird and Orchid Farm, Bogor adalah benar karya saya dengan
arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada
perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya
yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam
teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.
Bogor, Juli 2014
Dini Ayu Lestari
NIM E34100036
ABSTRAK
DINI AYU LESTARI. Teknik Penangkaran dan Kualitas Suara Cucak Rawa
(Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) di Mega Bird and Orchid Farm, Bogor.
Dibimbing oleh BURHANUDDIN MAS’UD dan JARWADI BUDI HERNOWO.
Upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi
cucak rawa (Pcynonotus zeylanicus) di alam melalui penangkaran. Identifikasi
teknik penangkaran, ukuran keberhasilan, teknik pelatihan suara dan sebaran
kualitas suara perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan penangkaran cucak
rawa. Penelitian dilakukan di Mega Bird and Orchid Farm, Bogor pada Maret
sampai April 2014. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitaif. Jenis
kandang cucak rawa terdiri dari kandang pembesaran, kandang reproduksi, dan
inkubator. Pakan yang diberikan pada cucak rawa pisang kepok, pepaya, pur, dan
jangkrik. Jenis penyakit yang pernah di derita cucak rawa yakni diare, feses
berwarna putih, feses berwarna hijau, flu, dan kaki seperti lumpuh. Persentase dan
kriteria keberhasilan penangkaran cucak rawa meliputi daya tetas telur sedang
(68.69%), tingkat perkembangbiakan tinggi (77.38%), dan angka kematian rendah
(10.34%). Teknik pelatihan suara yang dilakukan oleh pengelola yakni dengan
mendekatkan kandang cucak rawa yang ingin dilatih dengan kandang cucak rawa
pelatihnya. Sebaran kualitas suara cucak rawa bervariasi.
Kata kunci: cucak rawa, penangkaran
ABSTRACT
DINI AYU LESTARI. Captive Breeding Technique and Song Quality of Straw
Headed Bulbul (Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) in Mega Bird and Orchid
Farm, Bogor. Supervised by BURHANUDDIN MAS’UD and JARWADI BUDI
HERNOWO.
The effort which can be established to save straw headed bulbul
(Pcynonotus zeylanicus) that has decreased population is ex-situ conservation.
Captivation technique, success indicator, voice training techniques performed by
manager and distribution sound quality of straw headed bulbul varies need to be
identified in order to find out the success rate in captivating straw headed bulbul.
This research was conducted in Mega Bird and Orchid Farm, Bogor from March
to April 2014. Descriptive and quantitative data analysis was applied in this
research. The cage consist of growing cage, reproduction cage, and incubator.
Foods given to the bird were banana, papaya, voer and cricket. The types of
diseases recorded were diarrhea, white-colored feces, green-colored feces, flu, and
paralyzed feet. The criteria and success rate in captivating were consist of
medium-scaled egg hatching rate (68.69%), high breed rate (77.38%), and low
mortality rate (10.34%). Song training techniques performed was close the straw
headed bulbul cage that want to be trained with a cage of straw headed bulbul
coach. Distribution sound quality of straw headed bulbul was varies.
Keywords: captivity, straw headed bulbul
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kehutanan
pada
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
DINI AYU LESTARI
DEPARTEMEN SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014
TEKNIK PENANGKARAN DAN KUALITAS SUARA CUCAK
RAWA (Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) DI MEGA BIRD
AND ORCHID FARM, BOGOR
Judul Skripsi : Teknik Penangkaran dan Kualitas Suara Cucak Rawa
(Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) di Mega Bird and Orchid
Farm, Bogor
Nama : Dini Ayu Lestari
NIM : E34100036
Disetujui oleh
Dr Ir Burhanuddin Masy’ud, MS
Pembimbing I
Dr Ir Jarwadi Budi Hernowo, MScF
Pembimbing II
Diketahui oleh
Prof Dr Ir H Sambas Basuni, MS
Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas
segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Departemen Konservasi Sumberdaya
Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB. Tema yang dipilih dalam
penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2014 ini ialah penangkaran,
dengan judul Teknik Penangkaran dan Kualitas Suara Cucak Rawa (Pycnonotus
zeylanicus Gmelin, 1789) di Mega Bird and Orchid Farm, Bogor.
Karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik karena tidak luput dari
dukungan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Penghargaan dan terimakasih diberikan kepada Bapak Dr Ir Burhanuddin Mas’ud,
MS dan Dr Ir Jarwadi Budi Hernowo, MScF sebagai dosen pembimbing yang
dengan sepenuh hati mendukung dan senantiasa memberikan kritik dan saran.
Diucapkan juga terimakasih kepada Bapak Prasetyo Hardiono, Ibu Tri
Ruspiyani, Lucky Indah Setyani, Anniza Dian Pertiwi dan keluarga besar yang
selalu bermurah hati untuk mendoakan penulis selama menempuh pendidikan dan
mencari ilmu pengetahuan. Penghargaan penulis juga sampaikan kepada seluruh
staf pengelola penangkaran Mega Bird and Orchid Farm yang telah membantu
selama pengumpulan data karya ilmiah ini. Ungkapan terimakasih juga
disampaikan kepada Nurul Rahayu, SSi, sahabatku 274, ami, dayang, estu, qiqin,
dan penghuni asrama putri darmaga (APD), teman-teman KSHE 47 dan pihak-
pihak lain yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan karya ilmiah ini secara
tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Bogor, Juli 2014
Dini Ayu Lestari
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR vii
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Tujuan Penelitian 2
Manfaat Penelitian 2
METODE 2
Waktu dan Tempat 2
Bahan dan Alat 2
Jenis dan Metode Pengumpulan Data 2
Prosedur Analisis Data 4
HASIL DAN PEMBAHASAN 5
Teknik Penangkaran 5
Teknik Pelatihan Suara dan Sebaran Kualitas Suara 20
SIMPULAN DAN SARAN 22
Simpulan 22
Saran 23
DAFTAR PUSTAKA 23
DAFTAR TABEL
1 Jenis data dan metode pengumpulan data 3 2 Analisis kuantitatif pakan 4 3 Analisis faktor keberhasilan penangkaran 5 4 Populasi cucak rawa April 2014 berdasarkan jenis kelamin dan kelas
umur 6 5 Jenis, ukuran, konstruksi, dan fasilitas kandang di MBOF 7 6 Fasilitas kandang cucak rawa di penangkaran MBOF 9 7 Jenis pakan dan minum cucak rawa di MBOF 12 8 Rata-rata jumlah konsumsi dan tingkat palatabilitas 13 9 Kandungan gizi pakan cucak rawa 13 10 Konsumsi pakan cucak rawa di MBOF 14 11 Riwayat penyakit yang pernah diderita cucak rawa di MBOF 15
12 Faktor pembeda cucak rawa jantan dan betina 16 13 Penentuan jenis kelamin cucak rawa di MBOF 16 14 Perbandingan pertumbuhan anakan cucak rawa di MBOF 19 15 Persentase tingkat keberhasilan penangkaran cucak rawa di MBOF
periode tahun 2013 sampai 2014 19 16 Klasifikasi harga jual cucak rawa di MBOF 20 17 Karakteristik pola suara cucak rawa di penangkaran MBOF 21 18 Wave form suara cucak rawa di penangkaran MBOF 22
DAFTAR GAMBAR
1 Struktur organisasi pengelolaan MBOF 6 2 Suhu dan kelembaban di dalam kandang reproduksi 11
3 Topografi sayap burung 15 4 Pasangan cucak rawa, A) jantan, B) betina 16 5 Sketsa pasangan cucak rawa. A) jantan, B) betina 17 6 Piyik cucak rawa umur lima hari 18
7 Anakan cucak rawa umur dua minggu 18
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Burung cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus Gmelin, 1789) tergolong dalam
famili Pycnonotidae yang sering disebut merbah atau cucak-cucakan. Menurut
Iswantoro (2008) dan Turut (1999) famili ini tergolong dalam burung pengicau
yang memiliki suara merdu, sehingga burung ini sangat digemari dan dicari para
penggemar burung.
Holmes (1995) dalam BirdLife International (2001) melaporkan bahwa
penyebab utama penurunan populasi cucak rawa karena perburuan liar, sehingga
cucak rawa telah menjadi satwa peliharaan di Indonesia. Iswantoro (2008)
menambahkan bahwa populasi cucak rawa menurun karena rusaknya ekosistem
hutan dan habitat alaminya. Dampaknya adalah burung ini menjadi langka di alam
dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepunahan jika tidak ada upaya
pelestarian yang tepat dan berkelanjutan.
Collar et al. (1994) dalam MacKinnon et al. (2010) menggolongkan cucak
rawa dalam status rentan. International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) versi 3.1 tahun 2014 menyatakan cucak rawa dalam
status rentan (vulnerable). Convention on International Trade in Endangered
Species of wild fauna and flora (CITES) pada tahun 1998 menyatakan cucak rawa
termasuk dalam kategori Appendix II yaitu jenis burung yang perlu diatur dan
dibatasi perdagangannya, serta perdagangannya hanya diperbolehkan dari hasil
penangkaran (breeding) (Iswantoro 2008). Menurut Sukmantoro et al. (2006)
peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menetapkan cucak rawa
sebagai satwa yang dilindungi. Gunarso et al. (2009) menambahkan bahwa
spesies ini tidak dilindungi di Indonesia, namun diperlukan upaya konservasi dan
pelarangan perburuan cucak rawa di habitat alaminya.
Upaya konservasi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan populasi
cucak rawa di luar habitat alaminya salah satunya melalui konservasi ek-situ.
Tujuan upaya konservasi ek-situ melalui penangkaran adalah meningkatkan
populasi cucak rawa dengan tetap menjaga kemurnian genetiknya (Mas’ud 2002).
Menurut Setio dan Takandjandji (2007) kegiatan penangkaran tidak hanya untuk
kegiatan konservasi jenis dan peningkatan populasi, tetapi juga dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan wisata.
Kegiatan penangkaran dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 tahun
1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwaliar yang
merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jenis flora-fauna liar dengan tujuan
agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat (Setio dan Takandjandji 2007).
Penangkaran yang berhasil mengembangbiakan cucak rawa salah satunya
adalah penangkaran Mega Bird and Orchid Farm (MBOF), Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan pemikiran tersebut penelitian mengenai teknik penangkaran cucak
rawa di MBOF penting dilakukan untuk mengidentifikasi teknik penangkaran dan
ukuran keberhasilan penangkaran. Identifikasi teknik pelatihan suara dan sebaran
2
kualitas suara cucak rawa di MBOF dinilai penting untuk dilakukan karena
tingginya permintaan cucak rawa di MBOF.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi teknik penangkaran, ukuran
keberhasilan penangkaran, teknik pelatihan suara dan sebaran kualitas suara cucak
rawa di MBOF.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi dalam upaya
pengembangan penangkaran cucak rawa, khususnya di penangkaran MBOF,
Bogor, Jawa Barat.
METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2014.
Penelitian ini dilaksanakan di penangkaran Mega Bird and Orchid Farm (MBOF)
yang berlokasi di Desa Cijujung Tengah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah cucak rawa yang
terdapat di MBOF. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis,
kamera, panduan wawancara, termometer dry-wet, timbangan pegas, timbangan
manual, penggaris, jangka sorong, recorder dan microphone, program analisis
suara burung yakni Gold Wave versi 5.6 dan Raven Pro versi 1.4.
Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan
metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pengukuran, teknik
wawancara terpadu serta penulusuran dokumen/ studi literatur (Tabel 1).
3
Teknik penangkaran
Pengelolaan penangkaran dilakukan dengan pengamatan langsung di
lapangan dan wawancara pengelola. Data yang diambil untuk mengetahui faktor-
faktor pengaruh keberhasilan penangkaran cucak rawa adalah :
1. Teknik adapatasi satwa meliputi : proses perlakuan satwa dan lama waktu
adaptasi.
2. Sistem perkandangan meliputi : jenis kandang, ukuran dan konstruksi
kandang, peralatan dan perlengkapan kandang, perawatan dan sanitasi
kandang serta suhu dan kelembaban di dalam kandang.
3. Manajemen pakan meliputi : jenis pakan, jumlah pakan, sumber pakan,
waktu pemberian pakan, cara pemberian pakan, dan frekuensi pemberian
pakan, jumlah konsumsi, tingkat palatabilitas, konsumsi protein dan
konsumsi energi.
4. Manajemen kesehatan dan perawatan meliputi : jenis penyakit yang pernah,
sedang, dan sering diderita serta pengobantannya, serta perawatan pasca
susut bulu (moulting).
5. Manajemen reproduksi meliputi : sumber dan jumlah bibit, penentuan jenis
kelamin, pemilihan bibit/induk dan penjodohan, seks ratio, pengaturan
peneluran atau penetasan, pengasuhan atau pembesaran piyik dan anakan.
6. Ukuran keberhasilan penangkaran meliputi persentse daya tetas telur,
tingkat perkembangbiakan, dan persentase angka kematian.
7. Pemanfaatan atau pengelolaan hasil meliputi harga jual, cara penanganan
satwa yang akan dijual, dan proses pengiriman.
Teknik pelatihan suara dan sebaran kualitas suara
Data sebaran kualitas suara dikelompokkan kedalam beberapa kategori
suara, yakni suara cucak rawa master (pelatih), alam, dan cucak rawa yang telah
Tabel 1 Jenis data dan metode pengumpulan data
No Data yang diambil
Jenis data Metode pengumpulan data
Primer Sekunder
Pengamatan
dan
pengukuran
Wawancara Literatur
i Teknik penangkaran
Teknik adaptasi v v v
Sistem perkandangan v v v
Manajemen pakan v v v v
Manjemen kesehatan v v v
Manajemen reproduksi v v v
Ukuran keberhasilan v v v
Pemanfaatan hasil v v v
ii Identifikasi pola suara v v v
iii Data pendukung
Sejarah, Asal bibit v v
Organisasi
penangkaran v v
Populasi v v
4
dilatih berkicau di penangkaran (berhasil dan belum berhasil dilatih). Perekaman
suara dilakukan pada pagi hari yakni pukul 07.00-09.00 WIB. Hal ini dikarenakan
menurut Lundberg dan Atallo (1992) dalam Rusfidra (2004) bahwa puncak
aktivitas berkicau pada burung pada umumnya terjadi pagi hari dan cenderung
akan menurun pada siang dan sore hari. Suara cucak rawa direkam dengan
menggunakan recorder dan microphone kemudian dilakukan proses editing
menggunakan program gold wave 5.6 dan program raven pro versi 1.4 untuk
mengidentifikasi pola suara. Perekaman pola suara diulang sebanyak 3 kali pada
5 sampel burung, yaitu 1 ekor cucak rawa master (pelatih), 2 ekor cucak rawa
berasal dari alam, dan 1 ekor cucak rawa yang telah berhasil dilatih berkicau, dan
1 ekor cucak rawa yang belum berhasil dilatih berkicau. Parameter pola suara
yang diamati mengacu penelitian Rusfidra (2004) adalah :
1. Jumlah syllable, yaitu ukuran elemen yang muncul sebagai alur (trace)
yang terpisah antara satu suara dengan suara lainnya
2. Frekuensi (Hz), merupakan jumlah getearan per detik dari suatu
syllable
3. Durasi suara (detik), adalah lama tempuh suara pada saat individu
burung mempoduksi suara
4. Tempo (syllable/detik) yaitu pengulangan beberapa syllable yang sama
per detik
5. Amplitudo (kuat suara) : simpangan terjauh dari syllable.
Prosedur Analisis Data
Data hasil wawancara mengenai data pendukung dan teknik penangkaran
dianalisis secara deskriptif. Data mengenai teknik penangkaran dianalisis secara
deskriptif meliputi teknik adaptasi, aspek kandang, pakan, kesehatan, reproduksi,
dan pemanfaatan hasil serta identifikasi pola suara. Analisis data mengenai pakan
juga dilakukan secara kuantitatif (Tabel 2).
Tabel 2 Analisis kuantitatif pakan
Jumlah
Konsumsi
Tingkat Paltabilitas Kebutuhan Pakan*
JK = B-b
Keterangan:
JK = jumlah
konsumsi
B = berat pakan
sebelum
diberikan
B = berat pakan
sisa
%P=
Keterangan:
% P = tingkat
palatabilitas
G0 = berat pakan
semula
G1 = pakan sisa
Kebutuhan protein (%) :
Kebutuhan kalori (kkal)
*Kandungan gizi pada pakan diperoleh berdasarkan studi pustaka
5
Data mengenai ukuran keberhasilan penangkaran juga dianalisis secara
kuantitatif menggunakan analisis faktor keberhasilan yang mengacu pada
Suprijatna et al. (2008) (Tabel 3).
Data hasil rekaman suara kicauan menggunakan recorder dianalisis dengan
program gold wave versi 5.6 untuk proses editing dan program raven pro versi 1.4
untuk mengidentifikasi pola suara cucak rawa. Suara hasil rekaman
divisualisasikan dalam bentuk wave form untuk menggambarkan pola kicauan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik Penangkaran
Sejarah penangkaran, sumber bibit, organisasi penangkaran
Cucak rawa mulai ditangkarkan di penangkaran MBOF pada tahun 1997.
Pemilik penangkaran MBOF pada awalnya membuat penangkaran burung hanya
untuk dijadikan hiburan dan hobi, namun karena kecintaannya pada burung-
burung berkicau (termasuk cucak rawa) pemilik penangkaran menangkarkan
burung-burung tersebut. Tingginya permintaan (demand) cucak rawa di pasaran
juga melatarbelakangi dibentuknya penangkaran.
Jumlah cucak rawa yang ditangkarkan pada awalnya berjumlah dua pasang.
Cucak rawa tersebut diperoleh dari membeli kepada penangkar burung berkicau
dan penangkap burung di alam yang berada di daerah Medan. Cucak rawa tersebut
dipelihara dan dijadikan sebagai indukan. Jumlah cucak rawa saat ini mencapai 70
ekor. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola MBOF dapat mengembangbiakan
cucak rawa dengan baik. Mas’ud (2002) menjelaskan bahwa suatu penangkaran
dinilai berhasil jika dapat mengembangbiakan satwa yang ditangkarkan.
Manajemen pengelolaan penangkaran MBOF dibagi kedalam beberapa spesifikasi
pekerjaan yang berbeda-beda (Gambar 1).
Tabel 3 Analisis faktor keberhasilan penangkaran
Persentase daya tetas
telur
Persentase angka
kematian
Persentase tingkat
perkembangbiakan
Keterangan:
a = Σ telur yang
berhasil menetas
b = Σ total telur yang
dihasilkan
Keterangan:
M = Σ anak yang mati
Mt = Σ total anak
Keterangan:
I = Σ induk yang bertelur
It = Σ total induk
Keterangan kriteria faktor keberhasilan penangkaran :
0 – 30% = rendah
31 – 70% = sedang
71 – 100% = tinggi
6
Populasi cucak rawa di penangkaran
Populasi cucak rawa di MBOF pada tahun 2013 berjumlah 73 ekor,
sedangkan sampai bulan April 2014 jumlah populasi cucak rawa di MBOF
sebanyak 84 ekor, namun setelah dikurangi dengan cucak rawa yang telah
diperdagangkan populasinya menjadi 70 ekor (Tabel 4).
Proses adaptasi
Pengelola MBOF tidak menyediakan kandang khusus sebagai kandang
karantina untuk burung cucak rawa yang baru didatangkan. Cucak rawa yang baru
didatangkan langsung dimasukkan ke dalam kandang reproduksi, kemudian
langsung disatukan dengan cucak rawa lainnya yang sedang dalam masa
penjodohan. Tujuannya adalah untuk menjodohkan cucak rawa bukan untuk
mengkarantina. Perlakuan yang diberikan pengelola pada cucak rawa yang baru
didatangkan sama seperti perlakuan pada cucak rawa lainnya.
Tabel 4 Populasi cucak rawa April 2014 berdasarkan jenis kelamin dan umur
Kelas umur Jenis kelamin Jumlah
(ekor) Keterangan
0 bulan - 2 Piyik*
0 s/d <1 bulan - 3 Piyik*, 3 sudah dijual
1 s/d <2 bulan - 15 Anakan*, 9 sudah dijual
2 s/d <5 bulan - 2 Anakan*
5 s/d <12 bulan - 0 Remaja*
1 s/d <2 tahun 1 jantan, 2 betina 3 Dewasa* (awal mampu
reproduksi dan bersuara)
2 s/d <3 tahun 4 jantan, 5 betina 9 Indukan*, 1 pasang sudah
dijual
≥3 tahun 25 jantan, 25
betina 50 Indukan
Total 29 jantan, 31
betina 84
Populasi yang ada di
MBOF 70 ekor Keterangan: *(Sudrajad 1999)
Gambar 1 Struktur organisasi pengelolaan MBOF
Direktur
Manager
Asisten manager
Penjaga
kebun
Perawat
burung
Penjaga
keamanan Pembantu rumah
Tangga Petugas
memperbaiki
kandang
7
Sistem perkandangan
Mas’ud (2002) mendefinisikan kandang sebagai habitat buatan yang dibuat
menyerupai kondisi alaminya, sehingga cucak rawa dapat beraktivitas seperti di
habitat alaminya. Menurut Setio dan Takandjandji (2007) kondisi menyerupai
habitat alami cucak rawa didapatkan dengan cara penanaman pohon-pohon
pelindung di dalam kandang, tidak ada pengaruh binatang lainnya, tersedia air
untuk minum dan mandi burung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat
kandang adalah ukuran dan konstruksi kandang, sarana pendukung di dalam
kandang, dan kondisi lingkungan kandang (Mas’ud 2002).
Jenis, ukuran, konstruksi, dan fasilitas kandang
Jenis kandang cucak rawa yang terdapat pada penangkaran MBOF terdiri
dari tiga bagian kandang yaitu kandang pembesaran, kandang reproduksi, dan
kandang inkubator yang memiliki ukuran, konstruksi, dan fasilitas yang berbeda-
beda (Tabel 5).
Kandang pembesaran atau sangkar berfungsi sebagai tempat pemeliharaan
anakan sampai dewasa (1 bulan sampai < 2 tahun). Menurut Soemarjoto (2003)
ukuran kandang sangkar cucak rawa ideal yakni ± (50 x 50 x 60) cm dengan
Tabel 5 Jenis, ukuran, konstruksi, dan fasilitas kandang di MBOF
Jenis
kandang
Konstruksi
kandang
Ukuran
kandang
(p x l x t)
Fasilitas
kandang Keterangan
Kandang
pembesaran
Triplek,
kayu, dan
besi
40 cm x
40 cm x
60 cm
Tempat pakan,
minum, dan
bertengger
berupa kayu
Kandang
reproduksi
Dinding dari
batako, atap
berupa kawat
ram dan
asbes
3 m x 3
m x 1,5
m
Tempat pakan,
minum dan
mandi, tempat
bertengger
berupa kayu dan
pohon palem,
sarang
Inkubator
Alas triplek,
dinding kayu,
sirkulasi
udara/jendela
berupa kawat
ram
110 cm x
45 cm x
47 cm
Sarang, lampu 5
watt,
termometer,
pengatur
kelembaban
berupa bak air
dan kain, tempat
sirkulasi udara,
pot penyangga
8
bentuk persegi empat yang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum serta
tempat bertengger. Fasilitas kandang pembesaran cucak rawa di MBOF
diantaranya tempat pakan, minum, dan tempat bertengger/tenggeran, hal ini sesuai
dengan pendapat Soemarjoto (2003) (Tabel 6). Tempat pakan dan minum pada
kandang pembesaran terbuat dari plastik agar tidak mudah pecah jika terjatuh.
Sudrajad (1999) menjelaskan tempat pakan dan minum cucak rawa terbuat dari
bahan yang tidak bocor dan tidak mudah pecah, seperti terbuat dari plastik, bambu,
almunium. Menurut Turut (1999) bahwa tenggeran cucak rawa sebaiknya berupa
cabang atau ranting kayu dengan diameter kurang lebih 2 cm. Berdasarkan hal-hal
tersebut maka kandang pembesaran cucak rawa di MBOF dapat dikatakan sesuai
untuk memenuhi kebutuhan hidup cucak rawa. Cucak rawa yang berada pada
kandang pembesaran dimandikan pada tempat mandi khusus (kandang
pemandian) oleh pengelola setiap pagi hari.
Kandang reproduksi berfungsi sebagai tempat perkawinan indukan dan
reproduksi. Kandang reproduksi cucak rawa terletak dibagian dalam dan lebih
tertutup jika dibandingkan kandang lainnya. Hal tersebut dikarenakan agar proses
reproduksi tidak terganggu oleh aktivitas manusia, gangguan burung lain dan
kebisingan. Mas’ud (2002) menjelaskan bahwa cucak rawa yang mengerami
telurnya harus dihindarkan dari berbagai gangguan karena dapat menyebabkan
telur tidak menetas karena induk tidak ingin mengeraminya lagi. Menurut Mas’ud
(2002) ukuran minimal kandang reproduksi cucak rawa yakni ± (2 x 1,5 x 2,5)
meter. Atap kandang reproduksi di MBOF tidak semuanya tertutupi asbes,
terdapat sisi atap yang hanya menggunakan kawat ram agar sirkulasi udara
optimal dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam kandang. Asbes digunakan
sebagai atap karena untuk melindungi cucak rawa ketika hujan dan panas. Lantai
kandang reproduksi cucak rawa berupa tanah untuk mempermudah proses
dekomposisi/penguraian feses. Mas’ud (2002) dan Soemarjoto (2003)
menjelaskan bahwa kandang reproduksi yang ideal mempunyai ventilasi yang
baik dengan menggunakan atap kawat ram dan asbes pada sisi lainnya sebagai
tempat berlindung, serta lantainya berupa tanah agar kotoran mudah terurai.
Kandang reproduksi terdapat dua buah pintu yakni pintu besar pada bagian bawah
dan pintu kecil pada bagian tengah. Pintu besar berfungsi untuk mempermudah
penangkar dalam membersihkan kandang dan mengganti air minum yang
sekaligus air mandi, sedangkan pintu kecil digunakan untuk memberikan pakan
setiap harinya.
Kandang reproduksi cucak rawa dilengkapi dnegan fasilitas diantaranya
tempat pakan, minum yang sekaligus menjadi tempat mandi, tempat
bertengger/tenggeran, tempat bersarang dan pohon palem agar sesuai di habitat
alaminya dan membuat sejuk kandang (Tabel 6). Soemarjoto (2003) menjelaskan
bahwa kandang reproduksi dilengkapi dengan tempat pakan, minum, mandi,
tempat bertengger, pohon, dan sarang. Sarang cucak rawa di MBOF terbuat dari
sabut kelapa berdiameter 10 cm dengan kedalaman 2-2,5 cm dan beratapkan fiber.
Sarang tersebut berada pada ketinggian sekitar 1,5 meter dari tanah. Menurut
Mas’ud (2002) cucak rawa menyusun sarang yang berbentuk cawan, dengan
diameter 10 cm dan kedalaman 2.5 cm, dengan ketinggian 1.5-4.5 meter dari
permukaan tanah. Sudrajad (1999) menjelaskan bahwa bahan penyusun sarang
cucak rawa diantaranya jerami, sabut kelapa, dan rumput kering. Berdasarkan hal-
9
hal tersebut maka kandang reproduksi cucak rawa di MBOF dapat dikatakan
sesuai untuk memenuhi kebutuhan reproduksi cucak rawa.
Kandang inkubator terletak di dalam kantor MBOF berfungsi untuk
memelihara piyik-piyik (usia 0 bulan dan belum tumbuh bulu serta berwarna
merah) dan anakan cucak rawa (usia <1 bulan). Kandang ini hanya memiliki satu
pintu besar dengan tiga buah tempat sirkulasi udara/jendela disamping dan
diatasnya. Suprijatna dkk (2008) menjelaskan bahwa inkubator yang baik harus
dapat mengatur sirkulasi udara dengan lancar. Kandang inkubator MBOF
memiliki sirkulasi udara yang baik, bak penampung air sebagai pengatur
kelembaban, sarang yang disangga dengan pot bunga, lampu, dan tempat pakan
dan minum yang diletakkan diluar kandang (Tabel 6).
Tabel 6 Fasilitas kandang cucak rawa di penangkaran MBOF
Jenis
kandang
Gambar fasilitas kandang Keterangan gambar
Kandang
pembesaran
A) tempat pakan
B) tempat minum
C) tempat bertengger (ranting)
Kandang
reproduksi
D) tempat bertengger (kayu)
E) tempat minum sekaligus
mandi
F) tempat bersarang (jerami)
G) pohon palem
H) tempat pakan
Kandang
inkubator
I) tempat pakan
J) tempat minum dan pipet
K) pengatur kelembaban
L) lampu
M) ventilasi (kawat ram)
N) sarang yang disangga pot
10
Sarang pada kandang inkubator disangga dengan pot agar terhindar dari
semut. Menurut Sudrajad (1999) diperlukan penanganan khusus pada kandang
inkubator agar piyk dan anakan cucak rawa terhindar dari semut. Lampu lima watt
yang terdapat pada kandang inkubator digunakan untuk mengahangatkan tubuh
piyik-piyik dan anakan cuak rawa. Suhu kandang inkubator berkisar 25-26oC.
Pengatur kelembaban yang terdapat pada kandang inkubator terdiri dari wadah
plastik yang berisi kain basah dan sedikit air. Ventilasi (jendela) terbuat dari
kawat ram. Berdasarkn hal-hal tersebut maka kandang inkubator cucak rawa di
MBOF dapat dikatakan sesuai untuk memenuhi kebutuhan piyik dan anakan
cucak rawa.
Pemeliharaan kandang
Kegiatan pemeliharaan kandang penting untuk dilakukan karena berkaitan
dengan prinsip kesejahteraan satwa yakni satwa bebas dari sakit atau penyakit.
Kegiatan pemeliharaan kandang bertujuan untuk menghindari timbulnya penyakit
akibat dari kandang kotor (Setio dan Takandjanji 2007). Kegiatan pemeliharaan
kandang di MBOF meliputi kegiatan pemeliharaan di luar kandang dan di dalam
kandang. Kegiatan pemeliharaan di luar kandang meliputi pembersihan sampah
dan daun-daun kering yang ada di luar kandang yang dilakukan setiap hari yakni
pagi hari, merapikan tanaman dan menanam tanaman untuk memperindah
penangkaran yang dilakukan secara insidental.
Kegiatan pemeliharaan di dalam kandang meliputi pembersihan dan
penjemuran sarang pada kandang inkubator, pembersihan tempat pakan dan
tempat minum, pembersihan kandang dari feses burung, sisa-sisa makanan, serta
penggantian dan perbaikan kawat ram yang telah rusak. Kegiatan-kegiatan
pemeliharaan di dalam kandang dilakukan secara rutin setiap satu kali sehari
yakni pagi hari, namun untuk kegiatan perbaikan kawat ram yang telah rusak
dilakukan secara insidental.
Kegiatan pemeliharaan kandang cucak rawa yang dilakukan oleh
pengelola dapat dikatakan baik karena persentase angka kematian cucak rawa
rendah dan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola MBOF sesuai
dengan acuan Sudrajad (1999). Menurut Sudrajad (1999) upaya pemeliharaan
kandang meliputi perbaikan kawat ram/dinding kandang yang rusak, pembersihan
kandang dan fasilitasnya secara rutin. Alat-alat yang digunakan untuk merawat
dan membersihkan kandang adalah sapu lidi, pengki, gunting rumput, karung,
gerobak sampah, sikat, lap, dan selang air.
Suhu dan kelembaban kandang
Hasil pengamatan suhu di dalam kandang reproduksi cucak rawa di MBOF
adalah berkisar antara 26.5-31oC dengan kelembaban 85-92% (Gambar 2).
Mas’ud (2002) menjelaskan bahwa cucak rawa dapat hidup di daerah dataran
rendah (0-200 mdpl) sampai ketinggian sekitar 1050 mdpl. Menurut Handoko
(1995) hubungan suhu rata-rata harian dengan berbagai ketingian tempat di
Indonesia antara lain pada ketinggian 0-500 mdpl suhu rata-rata harian mencapai
24.5-27oC, sedangkan pada ketinggian 1000-1500 mdpl suhu rata-rata harian
mencapai 20-21.5oC. Suhu rata-rata kandang reproduksi cucak rawa di MBOF
yakni 28.35oC, hal ini berbeda denga suhu rata-rata harian cucak rawa di alam
sebesar 24.5-27oC pada ketinggian 0-500 mdpl.
11
Menurut William (1999) burung termasuk kedalam hewan berdarah panas
(homeotherm) yang suhu didalam tubuhnya tinggi yakni 40-44 oC. William (1999)
menjelaskan bahwa suhu 32.2 oC dapat mempengaruhi ovum dan sperma serta
menurunkan daya tetas telur, oleh karena itu suhu kandang cucak rawa di MBOF
dapat ditoleransi oleh cucak rawa untuk proses reproduksinya. Menurut William
(1999) fluktuasi kelembaban yang ekstrim (seperti di daerah sub tropis) akan
mempengaruhi reproduksi. Fluktuasi suhu dan kelembaban di kandang reproduksi
cucak rawa dapat ditoleransi untuk proses reproduksinya.
Manajemen pakan
Pemberian pakan dan minum
Jenis pakan dan minum cucak rawa di MBOF diklasifikasikan berdasarkan
kelas umurnya (Tabel 7). Menurut Turut (1999) cucak rawa di alam memakan
jenis buah-buahan yang terdapat di hutan, seperti pisang, pepaya, ceri, dan jambu.
Pemberian pakan berupa pisang kepok dan pepaya (pakan utama) yang dilakukan
oleh pengelola sesuai dengan kehidupan cucak rawa di alam. Pakan hewani cucak
rawa di alam berasal dari siput sungai, kumbang kecil, lebah penggerek, telur
semut merah, rayap, belalang, dan cacing tanah (Mas’ud 2002). Pemberian pakan
berupa jangkrik (pakan tambahan) yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan
kehidupan cucak rawa di alam yang membutuhkan protein hewani. Sumber pakan
cucak rawa di MBOF berasal dari supplyer khusus yang dipesan oleh pengelola.
Cara pemberian buah (pepaya/pisang) dibelah menyerupai bentuk persegi panjang,
dan dicuci terlebih dahulu, kemudian bagian atas buahnya di sayat dengan pisau
agar mempermudah cucak rawa untuk memakannya.
Gambar 2 Suhu dan kelembaban di dalam kandang reproduksi
12
Jangkrik diberikan dengan cara menghilangkan kaki belakangnya terlebih
dahulu. Cara tersebut dilakukan karena kaki belakangnya bergerigi tajam sehingga
dapat merusak pita suara cucak rawa (Sudrajad 1999). Cara pemberian pakan pada
piyik dan anakan cucak rawa yaitu dengan cara disuapi secara perlahan dengan
kayu sedangkan pemberian air minumnya dengan menggunakan pipet kecil
kemudian disuapi secara perlahan.
Jumlah konsumsi dan palatabilitas
Jumlah konsumsi adalah jumlah pakan yang dikonsumsi cucak rawa.
Tingkat palatabilitas adalah tingkat kesukaan satwa terhadap suatu jenis pakan.
Rata-rata jumlah konsumsi terbesar cucak rawa pada kandang pembesaran dan
kandang reproduksi adalah pepaya, yakni masing-masing berjumlah 44 g dan 29.5
g (Tabel 8). Hal ini menunjukkan pakan palatabel cucak rawa pada kedua kandang
tersebut adalah pepaya, yakni sebesar 33.3% dan 54.63%. Walaupun jangkrik
memiliki rata-rata palatabilitas tertinggi pada kedua kandang, namun tidak dapat
dibandingkan karena jangkrik merupakan pakan tambahan.
Jumlah konsumi pakan tertinggi cucak rawa di kandang pembesaran dan
kandang reproduksi yakni pepaya karena pada saat penelitian suhu rata-rata harian
mencapai 28.35 oC, sehingga cucak rawa membutuhkan air dari sumber pakannya.
Kadar air dalam pepaya lebih tinggi dibandingkan jenis pakan lainnya. Cucak
rawa di kedua kandang tersebut tidak menyukai pur karena pur memiliki serat
kasar yang tinggi sehingga sulit dicerna. Serat kasar pada suatu pakan
menunjukkan kesukaran pakan tersebut untuk dicerna (Tillman et al. 1989).
Tabel 7 Jenis pakan dan minum cucak rawa di MBOF
Klasifikasi
cucak rawa
Usia Jenis pakan Frekuensi
pemberian
pakan
Jenis
minum
Piyik 0 bulan & masih
merah
Campuran
minyak ikan,
scott’s emulsion,
pur yang
dicairkan
4 kali sehari
(pagi, siang,
sore,
malam)
Air
mineral
aqua Anakan < 1 bulan
Remaja 5 sampai < 12
bulan
Pakan utama :
pepaya/pisang,
pakan
tambahan :
jangkrik, pakan
buatan : pur
1 kali sehari
(pagi)
Air
tanah
Dewasa 1 tahun sampai
< 3 tahun
Indukan ≥ 3 tahun
13
Analisis Kandungan Gizi
Jenis-jenis pakan cucak rawa di MBOF memiliki kandungan gizi yang
berbeda-beda. Kandungan gizi terbesar pada pepaya yakni kadar air, sedangkan
kandungan gizi pada pisang kepok, jangkrik, dan pur adalah energi (Tabel 9). Air
tergolong ke dalam gizi yang sangat penting untuk satwa kerena kandungan air
dalam tubuh makhluk hidup sebesar 70% (Kateran 2010). Fungsi air diantaranya
memperlancar proses metabolisme dan fisiologi tubuh (Tilmen et al. 1789).
Menurut Kateran (2010) energi merupakan gizi yang bermanfaat untuk
menunjang aktivitas.
Pemberian pakan cucak rawa yang dilakukan oleh pengelola MBOF
bervariasi (berupa pepaya, pisang, jangkrik, dan pur) dapat dikatakan baik, karena
memiliki berbagai macam kandungan gizi yang beranekaragam jumlahnya,
Tabel 8 Rata-rata jumlah konsumsi dan tingkat palatabilitas
Jenis
pakan
Kandang pembesaran/ekor Kandang reproduksi/ekor
Rata-rata
Σ
konsumsi/hari/ekor
Rata-rata
palatabilitas
Rata-rata
Σ
konsumsi/hari/ekor
Rata-rata
palatabilitas
Pepaya 44 g 33.33 % 29.5 g 54.63 %
Pisang
kepok
17.5 g 30.97 % 26.25 g 52.5 %
Jangkrik 8 g 100 % 5 g 62.5 %
Pur 1 g 3.70 % 6.75 g 44.26 %
Tabel 9 Kandungan gizi pakan cucak rawa
Nilai gizi
Pepaya(a) Pisang
Kepok(b)
Jangkrik(c) Pur(d)
Kadar abu (%) 0.5 2.65 - 5.90
Kadar protein (%) 0.5(a1) 4.30 13.70 21.05
Serat kasar (%) 0.7 1.33 2.90 4.19
Kadar lemak (%) 0.1(a1) 0.19 5.30 7.21
Energi (kkal) 39.4 3969.30 117 4753.03
Kadar air (%) 86.6 66.48 76 8.82
Vitamin A (IU) 365(a2) 439(b1) - -
Vitamin B (mg) 0.04(a2) 0.14(b1) - -
Vitamin C (mg) 78(a2) 2(b1) - -
Ca (%) 10,.47 0.03 - 1.08
P (%) 3.39 0.09 - 0.75 Sumber : (a) Villegas (1997) dalam Suketi dkk (2010); (a1) Desai & Wagh (1995) dalam Suketi dkk
(2010); (a2) Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1979) dalam Baga (1999); (b) Aji (1996)
dalam Yunanti (2012); (b1) Depkes RI (1990) dalam Putri (2012); (c) Koswara (2010) dalam
Yunanti (2012); (d)Yunanti (2012)
14
sehingga kebutuhan gizi cucak rawa terpenuhi dan dapat meminimalisir tingkat
stres burung dari kebosanan terhadap pakan.
Konsumsi pakan
Konsumsi pakan yang perlu diketahui adalah konsumsi protein kasar (%)
dan konsumsi energi (kkal) karena protein dan energi sangat mempengaruhi
proses pertumbuhan dan reproduksi (Tabel 10). Mas’ud (2002) melaporkan bahwa
pakan untuk cucak rawa dewasa yang tidak reproduksi diperlukan karbohidrat
yang tinggi untuk menunjang aktivitasnya dan karena pertumbuhannya sudah
maksimal.
Cucak rawa anakan dan piyikan memerlukan asupan protein yang banyak
didalam pakan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Kandungan
protein yang tinggi pada bahan pakan juga diperlukan oleh cucak rawa yang
sedang atau akan bertelur. Protein dibutuhkan satwa untuk meningkatkan
produktivitas telur dan meningkatkan daya tetas telur (Kateran 2010). Daya tetas
telur di MBOF dikategorikan sedang, sehingga dapat dikatakan konsumsi protein
cucak rawa (4.79%) di MBOF cukup tercukupi. Menurut Yunanti (2012)
konsumsi energi Jalak Bali di MBOF sebesar 1909.1 kkal, sehingga dapat
dikatakan konsumsi energi cucak rawa di MBOF lebih tinggi dari konsumsi Jalak
Bali.
Manajemen kesehatan dan perawatan
Jenis penyakit dan penanganannya
Jenis penyakit yang pernah diderita cucak rawa di penangkaran MBOF
adalah diare, feses berwarna putih, feses berwarna hijau, flu, dan seperti lumpuh
(Tabel 11). Semua jenis penyakit yang pernah diderita oleh cucak rawa di
penangkaran MBOF hanya diobati dengan satu macam obat, yakni tonic treasur.
Cara pemberian obat pada anakan/piyik cucak rawa yakni dengan dihaluskan
terlebih dahulu kemudian dicampurkan kedalam minum, sedangkan pada indukan
cucakrawa obat langsung dimasukkan ke dalam paruh cucak rawa setelah
dihancurkan terlebih dahulu. Suplemen makanan yang diberikan pada piyik dan
anakan cucak rawa, yakni scott’s emulsion dan minyak ikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan piyik dan anakan cucak rawa. Induk cucak rawa
diberikan vitamin yakni canary post agar menghasilkan telur yang berkualitas
baik.
Tabel 10 Konsumsi pakan cucak rawa di MBOF
Jenis pakan Protein kasar (%) Energi (kkal)
Pepaya 0.22 17.49
Pisang kepok 1.68 1558.15
Jangkrik 1.02 8.74
Pur 1.86 420.78
Jumlah 4.79 2005.19
15
Bentuk perawatan cucak rawa lainnya di MBOF adalah dengan cara
memandikannya atau menyediakan tempat untuk mandi. Sudrajad (1999)
menjelaskan bahwa cucak rawa pada habitat alaminya di alam memiliki
kegemaran untuk mandi, oleh sebab itu pengelola penangkaran harus
memandikannya. Pengelola MBOF memandikan cucak rawa yakni pukul 08.00,
hal ini sesuai dengan pendapat Sudrajad (1999) bahwa waktu yang tepat
memandikan cucak rawa pagi hari, yakni pukul 08.00-10.00.
Perawatan pasca susut bulu
Susut bulu (moulting) pada cucak rawa di MBOF bukan merupakan
penyakit, namun peristiwa alami yang terjadi untuk regenerasi bulu sayap kanan
atau kirinya. Menurut Karso (1996) moulting pada cucak rawa terjadi pasca
perkawinan. Menurut Jarulis et al. (2013) moulting family pycnonotidae terjadi
pada bulu sayap primer (Gambar 3).
Cucak rawa yang mengalami susut bulu (moulting) tidak diberikan
perlakuan khusus oleh pengelola. Hal ini dikarenakan bahwa bulu yang susut
hanya 1-2 buah, tidak seperti burung lainnya yang mengalami penyusutan bulu
dalam jumlah yang besar selama kurun waktu 3-4 bulan.
Tabel 11 Riwayat penyakit yang pernah diderita cucak rawa di MBOF
Jenis
penyakit Gejala Keterangan
Diare Feses cair, tidak kompak Piyik dan anakan
Feses berwarna
putih
Feses cair, encer, berlendir, dan
berwarna putih
Piyik,
anakan, indukan
Feses berwarna
hijau
Feses cair, encer, dan berwarna
hijau
Piyik, anakan,
indukan
Flu Paruh dan hidungnya berair,
terdengar suara seperi bersin-bersin
Piyik, anakan,
indukan
Seperti lumpuh Lemas, tidak dapat berdiri tegak Piyik dan anakan
Gambar 3 Topografi sayap burung
(Sumber: Ginn dan Melville (1983) dalam Jarulis et al. (2013))
16
Manajemen Reproduksi
Penentuan jenis kelamin
Pengetahuan mengenai cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina
cucak rawa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan
perkembangbiakannya. Apabila pengelola salah dalam menentukan jenis kelamin
cucak rawa yang akan dijodohkan maka proses reproduksi tidak akan berhasil.
Menurut Sudrajad (1999) dan Mas’ud (2002) bahwa burung cucak rawa jantan
dan betina dapat dibedakan melalui beberapa cara yakni suara, bentuk kepala,
ekor, dan dada (Tabel 12 ).
Pengelola MBOF dapat membedakan burung cucak rawa jantan atau
betina pada umur satu tahun dengan melihat suara, tingkah laku, dan bentuk
morfologi (Tabel 13). Bentuk morfologi yang membedakan cucak rawa jantan dan
betina adalah bulu dada (Gambar 4 dan 5).
Tabel 13 Faktor pembeda cucak rawa jantan dan betina
Faktor pembeda Jantan Betina
Suara Sangat keras dan nyaring Tidak keras dan cukup
nyaring
Bentuk kepala
Agak bulat dan setelah
dewasa tidak terdapat
belahan bulu pada
kepalanya
Agak pipih dan setelah
dewasa tidak terdapat
belahan bulu pada kepalanya
Ekor Lebih panjang Lebih pendek
Bulu dada Warna hitam yang tidak
jelas pada bulu dadanya
Warna hitam dan putih yang
jelas
Gambar 4 Pasangan cucak rawa, A) jantan, B) betina
Tabel 12 Penentuan jenis kelamin cucak rawa di MBOF
Faktor pembeda Jantan Betina
Suara Sangat keras dan nyaring Tidak keras dan cukup
nyaring
Perilaku Lebih aktif Pendiam
Bulu dada Warna hitam keabu-abuan Warna hitam legam
Bulu dada
berwarna
hitam keabu-
abuan
Bulu dada
berwarna
hitam keabu-
abuan
Bulu dada
berwarna
hitam legam
Bulu dada
berwarna
hitam legam
17
Pemilihan induk
Pengelola MBOF memilih cucak rawa yang sehat dan tidak cacat sebagai
indukan. Sudrajad (1999) mendefinisikan cucak rawa sehat jika badannya besar,
bulu tubuhnya bagus, dan nafsu makan tinggi. Karso (1996) menambahkan bahwa
cucak rawa sehat dicirikan dengan tidak sedang sakit. Suara tidak menjadi syarat
utama dalam pemilihan induk, hanya sebagian kecil saja induk cucak rawa yang
bersuara roppel (bagus) dipilih sebagai indukan. Perbandingan seks rasio cucak
rawa jantan dan betina di MBOF adalah 1:1 artinya jantan dan betina selalu
dipasangkan dalam satu kandang. Total jumlah induk cucak rawa di MBOF
adalah 28 pasang dengan komposisi 28 ekor cucak rawa dari alam dan 28 ekor
cucak rawa dari penangkaran.
Penjodohan
Mas’ud (2002) menjelaskan terdapat dua tipe penjodohan cucak rawa
yakni menjodohkan secara berkelompok di dalam kandang besar dan
menjodohkan di dalam kandang soliter. Proses pembentukan pasangan yang
dilakukan oleh pengelola adalah dengan cara menjodohkan beberapa pasang
cucak rawa di dalam satu kandang, kemudian diamati perlilakunya. Apabila
terlihat ada pasangan cucak rawa yang saling tertarik (diketahui apabila dua ekor
cucak rawa saling mendekat dan bermain bersama), maka pasangan tersebut
dipisahkan dan dimasukkann kedalam kandang reproduksi. Sudrajad (1999)
melaporkan bahwa ciri cucak rawa yang telah mendapatkan pasangan adalah
terlihat saling berdekatan, terlihat tenang, terbang berkejaran serta terkadang
terdengar kicauan dari jantan dan betina secara bergantian, namun apabila
pasangan tidak cocok ditandai dengan adanya perkelahian diantara kedua
pasangan. Proses penjodohan berlangsung selama 2-3 bulan. Pengelola MBOF
melakukan kegiatan penjodohan pada cucak rawa ketika berusia 2-3 tahun.
Peneluran, pengeraman, dan penetasan telur
Peneluran, pengeraman, dan penetasan telur dilakukan di dalam kandang
reproduksi. Sudrajad (1999); Mas’ud (2002) melaporkan bahwa pengeraman telur
cucak rawa secara alami yakni 14 hari yang dilakukan oleh jantan dan betina
secara bergantian. Mas’ud (2002) menjelaskan bahwa proporsi mengeraman induk
betina lebih banyak dibandingkan induk jantan. Telur yang dihasilkan oleh cucak
rawa di MBOF sebanyak 2 butir dengan pengeraman selama 14 hari. Piyik cucak
Bulu dada
berwarna
hitam keabu-
abuan
Bulu dada
berwarna
hitam keabu-
abuan
Bulu dada
berwarna
hitam legam
Bulu dada
berwarna
hitam legam
Gambar 5 Sketsa pasangan cucak rawa. A) jantan, B) betina
18
rawa yang baru menetas dibiarkan berada di dalam kandang reproduksi bersama
induknya selama 5-7 hari pasca penetasan, setelah itu dipindahkan ke dalam
kandang inkubator untuk mendapatkan perawatan oleh pengelola MBOF. Waktu
yang dibutuhkan cucak rawa untuk dapat kembali bertelur adalah 14 hari pasca
pengangkatan piyik. Cucak rawa di MBOF mampu bereproduksi sebanyak 8 kali
dalam satu tahun. Tingkat reproduksi cucak rawa di MBOF dapat dikatakan tinggi
karena menurut Mas’ud (2002) cucak rawa di penangkaran dapat berkembangbiak
sebanyak 7 kali dalam satu tahun.
Pembesaran piyik dan anakan cucak rawa
Piyik cucak rawa (Gambar 6) yang telah menetas dalam kandang
reproduksi dibiarkan bersama induknya, namun setelah 5-7 hari piyik tersebut
dipindahkan ke kandang inkubator. Hal ini dilakukan oleh pengelola agar
meminimalisir tingkat kematian, kesehatan piyik dan pertumbuhannya terkontrol,
serta induk cucak rawa dapat melakukan reproduksi kembali. Pembesaran piyik
cucak rawa seperti ini disebut hand rearing yakni pembesaran piyik cucak rawa
dengan memisahkan atau mengambil piyik dari induknya untuk selanjutnya
dipelihara dan dibesarkan oleh penangkar secara intensif hingga burung dapat
mandiri. Pembesaran piyik pasca telur menetas dapat dilakukan dengan dua cara
yakni secara alami oleh induknya dan dirawat oleh pengelola, namun perawatan
piyik oleh pengelola lebih baik karena dapat meminimalisir kematian (Sudrajad
1999).
Anakan cucak rawa (Gambar 7) yang mencapai umur <1 bulan akan
dibesarkan dan dirawat di kandang inkubator. Saat anakan cucak rawa berumur 1
bulan akan dipindahkan ke kandang pemeliharaan agar dapat mandiri dan
memacu pertumbuhan badannya.
Pertumbuhan piyik cucak rawa
Hasil observasi pertumbuhan piyik selama dua minggu diperoleh bahwa
terdapat perbedaan pertumbuhan antara generasi F1a (kedua induk berasal dari
alam) dengan F1b (induk berasal dari alam dan penangkaran) (Tabel 14).
Observasi dilakukan hanya dua minggu, karena piyik yang berumur lebih dari dua
minggu dijual oleh pengelola.
Gambar 6 Piyik cucak rawa umur
lima hari
Gambar 7 Anakan cucak rawa umur
dua minggu
19
Generasi F1b memiliki ukuran morfometrik relatif lebih panjang
dibandingkan F1a karena cucak rawa asal penangkaran memiliki performa tubuh
yang lebih baik dibandingkan cucak rawa berasal dari alam. Hal ini dikarenakan
pengelola MBOF melakukan pengaturan pakan dengan baik pada setiap kelas
umur cucak rawa, sehingga cucak rawa indukan memiliki sifat-sifat morfologi
kuantitatif yang lebih baik.
Warwick et al. (1995) menjelaskan bahwa sifat-sifat morfologi kuantitatif
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang berperan
mempengaruhi sifat-sifat morfologi kuantitatif diantaranya pengaturan pakan oleh
pengelola.
Ukuran keberhasilan penangkaran cucak rawa
Peresentase tingkat keberhasilan penangkaran cucak rawa di MBOF pada
tahun 2013 dan 2014 memiliki perbedaan (Tabel 15).
Hasil perhitungan rata-rata daya tetas telur cucak rawa di MBOF sebesar
68.69% yang termasuk kedalam kategori sedang. Faktor yang mempengaruhi daya
tetas telur yakni kandungan gizi dalam pakan cucak rawa. Sudrajad (1999)
menjelaskan bahwa induk yang tercukupi gizinya akan menghasilkan telur yang
berkualitas dan berdaya tetas tinggi. Rata-rata tingkat perkembangbiakan cucak
rawa yakni 77.38% dengan kategori tinggi karena kegiatan penjodohan di MBOF
berhasil, sehingga jumlah induk cucak rawa bertambah setiap tahunnya.
Tabel 15 Persentase tingkat keberhasilan penangkaran cucak rawa periode tahun
2013 dan 2014
Tahun
Persentase (%)
Daya tetas telur Tingkat
perkembangbiakan Angka kematian
2013 58.06 71.43 10.96
2014 79.31 83.33 9.72
Rata-rata 68.69 77.38 10.34
Kriteria Sedang Tinggi Rendah
Tabel 14 Perbandingan pertumbuhan anakan cucak rawa di MBOF
Rataan Pengukuran
Morfometrik (mm)
Generasi F1a Generasi F1b
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 1 Minggu 2
Panjang tubuh total 67 115 67.7 125.7
Panjang sayap 37.4 73 38.5 81.3
Panjang ekor 0.3 30 4.3 37.6
Panjang kepala 27 31.7 27.2 36.8
Panjang paruh 15.1 16.7 15.1 17.4
Tinggi paruh 13.5 14.7 13.1 13.8
Pajang kaki 20.8 21.7 20.8 22.9
20
Tingkat kematian tinggi terjadi pada piyik cucak rawa karena kondisi
tubuhnya masih lemah. Rata-rata angka kematian cucak rawa di MBOF adalah
10.96% yang termasuk kedalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan pemantauan
piyik di kandang inkubator dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya
kelaparan pada piyik. Berdasarkan hal tersebut maka sistem pembesaran piyik
secara hand rearing berhasil karena dapat meminimalisir tingkat kematian pada
piyik cucak rawa.
Pemanfaatan atau pengelolaan hasil
Sudrajad (1999) melaporkan bahwa permintaan cucak rawa di pasar
burung tinggi. Harga jual cucak rawa yang ditawarkan oleh pengelola MBOF
sudah termasuk kandang pemeliharaan, namun belum termasuk biaya pengiriman
untuk pembeli diluar Pulau Jawa (Tabel 16).
Harga yang ditawarkan oleh pengelola MBOF sudah termasuk kandang
pemeliharaan, namun belum termasuk biaya pengiriman untuk pembeli di luar
Pulau Jawa. Pembeli cucak rawa di MBOF beragam, diantaranya berasal dari
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pulau Jawa, dan luar Pulau Jawa.
Burung yang akan di jual di luar Pulau Jawa dimasukkan ke dalam boks atau
kotak yang terbuat dari triplek. Jika pembeli bersal dari Pulau Jawa burung hanya
dimasukkan ke dalam kandang pemeliharaan/sangkar dengan ditutupi koran.
Pembeli yang berasal dari Pulau Jawa biasanya langsung mengambil burung yang
akan dibelinya, sedangkan pembeli yang berasal dari luar Pulau Jawa pengelola
menggunakan jasa pengiriman atau kargo.
Teknik Pelatihan Suara dan Sebaran Kualitas Suara
Teknik pelatihan suara yang dilakukan oleh pengelola yakni dengan
mendekatkan kandang cucak rawa yang ingin dilatih dengan kandang cucak rawa
pelatih (master). Cucak rawa di MBOF sering berkicau pada pagi hari. Sebaran
kualitas suara cucak rawa di MBOF bervariasi. Sebaran kualitas suara cucak rawa
dikelompokkan menjadi empat kriteria yakni suara cucak rawa pelatih (cucak
rawa yang bersuara bagus atau roppel), suara cucak rawa berasal dari alam (cucak
rawa berasal dari alam tanpa ada pelatihan suara), suara cucak rawa yang berhasil
dilatih (cucak rawa hasil penangkaran yang intensitas pelatihannya lebih tinggi),
dan suara cucak rawa yang belum berhasil dilatih (cucak rawa hasil penangkaran
yang intensitas pelatihannya rendah). Cucak rawa pelatih memiliki tempo yang
cepat dan amplitudo yang tinggi dibandingkan burung lainnya (Tabel 17).
Tabel 16 Klasifikasi harga jual cucak rawa di MBOF
Klasifikasi burung Umur Suara Harga (Rp)
Anakan 2 minggu-
1 bulan
Belum
berkicau
5 000 000 – 8 000 000
Dewasa reproduktif ≥ 3 tahun Belum bagus 15 000 000
Dewasa ≥ 2 tahun Roppel (suara
bagus)
50 000 000 – 80 000 000
21
Cucak rawa di MBOF memiliki dua tipe suara yakni kwo-kikoek-kuekik-
kikeik (suara cucak rawa pelatih) dan kuik-kuik-kukak-kuik (suara cucak rawa
berasal dari alam). Grant dan Grant (1997) mejelaskan bahwa sifat nyanyian
merupakan sifat yang diwariskan melalui proses imprinting. Menurut Cardoso dan
Sabbatini (2004) dalam Rusfidra (2007) proses imprinting merupakan interaksi
antara naluri dan pengalaman berlatih (learning).
Menurut Mas’ud (2002) kriteria kualitas suara kicauan yang baik
ditentukan oleh keras lunaknya suara, besar kecilnya volume suara, dan kerapatan
suara. Keras lunaknya suara diinterpretasikan dengan amplitudo (Rusdin 2007).
Cucak rawa yang berhasil dilatih memiliki aplitudo tertinggi ke dua setelah cucak
rawa master. Hal ini menunjukkan bahwa cucak rawa yang dilatih akan
mempunyai karakteristik suara seperti cucak rawa master. Besarnya amplitudo
dipengaruhi oleh stamina atau tenaga dari setiap individu burung Rusdin (2007).
Besar kecilnya volume suara diukur melalui frekuensi yang dihasilkan.
Menurut Purnamasari (2006) frekuensi dapat menggambarkan volume suara yang
dihasilkan. Semua cucak rawa di MBOF memiliki frekuensi yang sama (0-2250
Hz) hal ini menunjukkan bahwa volume kicauan cucak rawa terdengar nyaring.
Besar kecilnya frekuensi yang dihasilkan dipengaruhi oleh kemampuan individu
burung dalam mengolah udara pada saat respirasi (inspirasi dan ekspirasi) (Rusdin
2007).
Kerapatan suara digambarkan dengan tempo yang cepat artinya tidak ada
jeda atau interval antar elemen suara. Kerapatan suara dikenal dengan istilah
roppel yakni tidak ada jeda pada suara depan, tengah, dan akhir, sehingga
terdengar suara yang berulang-ulang (Mas’ud 2002). Turut (1999) menambahkan
bahwa suara roppel yakni tidak ada jarak antar elemen suara dan terdengar
nyaring.
Cucak rawa pelatih yang bersuara roppel memiliki bentuk wave form yang
hampir sama dengan suara cucak rawa yang telah berhasil dilatih (Tabel 18).
entuk wave form cucak rawa pelatih tebal dan rapat atau tidak ada interval antar
elemen suara yang menunjukkan tempo cepat dan amplitudo tinggi, sedangkan
cucak rawa yang telah berhasil dilatih memiliki pola tebal dan terdapat interval
antar elemen suara. Hal ini menunjukkan bahwa cucak rawa yang dilatih dengan
intensitas pelatihan lebih tinggi akan mempunyai karakteristik suara seperti cucak
rawa master (kualitas suaranya bagus atau roppel). Cucak rawa yang berasal dari
Tabel 17 Karakteristik pola suara cucak rawa di penangkaran MBOF
Jenis cucak
rawa
Jumlah
syllable
Frekuensi
(Hz)
Durasi
suara
(detik)
Tempo Amplitudo
Pelatih
(master) 9 0-22050 6.55
1.37 81.75
Alam 9 0-22050 8.96 1.00 64.56
Pelatihan:
berhasil 23 0-22050 38.81 0.59 80.42
Pelatihan:
belum
berhasil
10 0-22050 16.15
0.61
69.15
22
alam dan cucak rawa yang belum berhasil dilatih memiliki tampilan wave form
yang hampir sama yakni bentuk wave form tipis yang menandakan bahwa
amplitudonya rendah. Cucak rawa yang belum berhasil dilatih belum dapat
dibedakan suara depan, tengah, dan belakang. Hal ini menunjukkan bahwa cucak
rawa yang belum berhasil dilatih memiliki kualitas suara yang rendah, oleh karena
itu perlu mendapatkan pelatihan yang lebih intensif.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa teknik penangkaran cucak
rawa di MBOF yang terdiri dari sistem perkandangan, manajemen pakan,
manajemen kesehatan dan perawatan, manajemen reproduksi, dan pemanfaatan
sudah baik. Hal ini dikarenakan ukuran kandang, fasilitas kandang, dan
Tabel 18 Wave form suara cucak rawa di penangkaran MBOF
Jenis cucak
rawa
Gambar wave form
Pelatih
(master)
Syllable 1 Syllable 2
Dep
an
Akh
ir
Ten
gah
Alam
Syllable 1 Syllable 2 Syllable 3
Dep
an
Ten
gah
Akhir
Pelatihan:
berhasil
Syllable 3 Syllable 1 Syllable 2
Dep
an
Ten
gah
h Ak
hir
Pelatihan:
belum
berhasil
Syllable 1 Syllable 2 Syllable 3
23
manajemen yang telah dilakukan pengelola sesuai untuk memenuhi kehidupan
cucak rawa sehingga cucak rawa dapat berkembangbiak. Penangkaran cucak rawa
di MBOF dapat dikategorikan cukup berhasil karena persentase daya tetas telur
sedang (68.69%), persentase tingkat perkembangbiakan tinggi (77.38%), dan
persentase angka kematian rendah (10.34%). Teknik pelatihan suara yang
dilakukan oleh pengelola yakni dengan mendekatkan kandang cucak rawa yang
ingin dilatih dengan kandang cucak rawa pelatihnya. Sebaran kualitas suara cucak
rawa di MBOF bervariasi yakni cucak rawa berkualitas rendah (suara cucak rawa
yang belum berhasil dilatih sehingga suara depan, tengah, dan akhir belum dapat
dibedakan) hingga cucak rawa berkualitas bagus atau (roppel yakni tidak ada
interval antar elemen suara, tempo cepat, dan amplitudo tinggi).
Saran
Saran yang dapat diberikan yakni pengeloala MBOF perlu menyediakan
kandang karantina untuk cucak rawa yang baru didatangkan. Diperlukan
penelitian lanjutan mengenai analisis inbreeding (perkawinan antar kerabat dekat)
untuk meminimalisir resiko inbreeding, sehingga ukuran keberhasilan
penangkaran tidak mengalami penurunan.
DAFTAR PUSTAKA
[IUCN] International Union for Conservation of Nature. 2014 Daftar Populasi
Satwa yang Termasuk kedalam Red List of IUCN. [Internet]. [diunduh 2014
Jun 10]. Tersedia pada: http : www.iucnredlist.org.
Baga KM. 1999. Budidaya Pepaya. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
BirdLife International. 2001. Threatened birds of Asia : the BirdLife international
Red Data Book. Cambridge (US): BirdLife International,
Grant PR, Grant. 1997. Genetics and the origin of bird species. Proc. Natl. Acad.
Sci. [Internet]. [diunduh 2014 Mei 1]; 94: 7768–7775. Tersedia pada:
http://www.pnas.org/content/94/15/7768.full.pdf.
Gunarso P, Setyawati T, Sunderland T, Shackleton C. 2009. Pengelolaan
Sumberdaya Hutan di era Desentralisasi Pelajaran yang Dipetik dari Hutan
Penelitian Malinau, Kalimantan Timur, Indonesia [Laporan Teknis]. Bogor
(ID): Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International
Tropical Timber Organization (ITTO).
Handoko. 1995. Klimatologi Dasar: Landasan Pemahaman Fisika Atmosfer dan
Unsur-unsur Iklim. Bogor (ID): Pustaka Jaya.
Iswantoro. 2008. Konservasi dan peluang bisnis dalam penangkarkan burung
cucakrawa. J Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. [Internet]. [diunduh 2013 Jul 31];
9(2): 57-70. Tersedia pada: http://digilib.uin-
suka.ac.id/8236/1/ISWANTORO%20KONSERVASI%20DAN%20PELUA
NG%20BISNIS%20DALAM%20PENANGKARAN%20BURUNG%20CU
CAKRAWA.pdf.
24
Jarulis. Meidian A, Kamilah SN, Alrahmado. 2013. Breeding dan Moulting
Burung-burung di Hutan Terfragmen Taman Wisata Alam Seblat, Bengkulu
dan Semirata FMIPA Universitas Lampung; 2013; Lampung, Indonesia.
Lampung (ID): Universitas Lampung. Hlm 15-28.
Karso SP. 1996. Penangkaran burung cucak rowo. Yogyakarta (ID): Kanisius.
Kateran PP. 2010. Kebutuhan gizi ternak unggas di Indonesia. Wartazoa. 20(4):
172-180.
MacKinnon J, Phillipps K, Balen BV. 2010. Seri Panduan Lapang Burung-
Burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Bogor (ID): Pusat
Penelitian dan Pengembangan LIPI.
Mas’ud B. 2002. Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis Menangkarkan Cucak
Rawa. Jakarta (ID): AgroMedia Pustaka.
Noor RR. 2008. Genetika Ternak. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
Purnamasari DK. 2006. Pemberian ekstrak daun saga, sambiloto, pare hutan dan
efeknya terhadap suara burung perkutut (Geopelia striata) [tesis]. Bogor
(ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Puti AR. 2012. Pengaruh kadar air terhadap tekstur dan warna keripik pisang
kepok (Musa paradidiaca formatypica) [skripsi]. Makassar (ID): Jurusan
Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.
Rusdin M. 2007. Analisis fenotipe, genotipe dan suara ayam pelung di kabupaten
cianjur [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Rusfidra. 2004. Karakterisasi sifat-sifat fenotipik sebagai strategi awal konservasi
ayam kokok balenggek di Sumatera Barat [tesis]. Bogor (ID): Sekolah
Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Rusfidra. 2007. Kajian Bioakustik Pada Ayam Kokok Balenggek “Ayam Lokal
Penyanyi” Sumatera Barat dan Seminar Nasional Teknologi Peternakan
dan Veteriner; 2007. Padang, Indonesia, Padang (ID): Universitas Andalas.
hlm.608-614.
Setio P, Takandjandji M. 2007. Konservasi Ek-Situ Burung Endemik Langka
Melalui Penangkaran dan Prosiding Ekspose Hasil-hasil Penelitian;
Padang, 20 September 2006. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan dan Konservasi Alam. hlm 47–61.
Soemarjoto R. 2003. Mengatasai Permasalahan Burung Berkicau. Jakarta (ID):
Penebar Swadaya.
Sudrajad. 1999. Cucakrawa. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
Suketi K, Poerwanto R, Sujiprihati S, Sobir, Widodo WD. 2010. Studi karakter
mutu buah pepaya IPB. J. Hort Indoneisa. 1(1): 17-26.
Sukmantoro W, Irham M, Novarino W, Hasudungan F, Kemp M, Muchtar M.
2006. Daftar Burung Indonesia No. 2. Bogor (ID): Indonesian
Ornithologists’ Union.
Suprijatna E, Atmomarsono U, Kartasudjana R. 2008. Ilmu Dasar Ternak Unggas.
Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
Thohari M. 1987. Gejala inbreeding dalam penangkaran satwa liar. J Media
Konservasi. [Internet]. [diunduh 2013 Sep 2]; 1(4): 1 – 10. Tersedia pada:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30029.
25
Tillman DA, Hartadi D, Reksohadiprodjo S, Prawirokusumo S, Lebdosoekojo.
1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Yogyakarta (ID): Gajah Mada
University Press.
Turut R. 1999. Sukses Melatih Cucak Rawa. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
Warwick EJ, Astuti JM, Hardjosubroto W. 1984. Pemuliaan Ternak. Yogyakarta
(ID): Gajah Mada University Press.
Widodo W. 1995. Nutrisi dan Pakan Unggas Kontekstual. Yogyakarta (ID):
Gajah Mada University Press.
Yunanti BD. 2012. Teknik penangkaran dan analisis koefisien inbreeding pada
Jalak Bali (Leucopsar rothschildi Stresemann, 1912) di Mega Bird And
Orchid Farm Bogor, Jawa Barat [skripsi]. Bogor (ID): Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor.
26
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Indramayu, Jawa Barat pada 20 Januari 1992. Penulis
merupakan putri kedua dari Bapak Prasetyo Hardiono dan Ibu Tri Ruspiyani.
Pendidikan formal penulis yang telah ditempuh yaitu pendidikan sekolah dasar di SD
Negeri Kedokan Agung III pada periode tahun 1998–2004, kemudian penulis
melanjutkan ke pendidikan SMP Negeri 01 Karang Ampel periode tahun 2004–2007,
dan melanjutkan ke pendidikan SMA Negeri 7 Cirebon periode tahun 2007–2010.
Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB)
melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan masuk dalam mayor departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan.
Penulis aktif ke dalam unit kegiatan mahasiswa IPB Koran Kampus pada
tahun 2010-2013. Selama kuliah di Fakultas Kehutanan IPB, penulis aktif mengikti
kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata (HIMAKOVA) dan menjadi anggota Kelompok Pemerhati Tumbuhan
(KPF).
Pada tahun 2009, penulis mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan
(P2EH) di Taman Wisata Alam Pangandaran. Pada tahun 2011, penulis mengikuti
Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) dan
melakukan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Gunung
Halimun Salak, Sukabumi.
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan
judul Teknik Penangkaran dan Kualitas Suara Cucak Rawa (Pycnonotus zeylanicus
Gmelin, 1789) di Mega Bird and Orchid Farm, Bogor dibimbing oleh Dr Ir
Burhanuddin Masy’ud, MS dan Dr Ir Jarwadi Budi Hernowo, MScF.