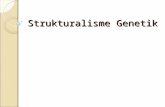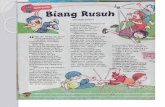Strukturalisme Dan Pascastrukturalisme
-
Upload
alfian-rokhmansyah -
Category
Documents
-
view
484 -
download
29
Transcript of Strukturalisme Dan Pascastrukturalisme

STRUKTURALISME DAN PASCASTRUKTURALISME:SEBUAH PERJALANAN TEORI SASTRA
OlehAlfian Rokhmansyah, S.S.
Abstrak
Dalam kurun waktu satu abad, perkembangan teori sastra tampaknya sangat pesat. Ketika pertama kali muncul, teori sastra hanya berkutat pada struktur karya sastra yang sering disebut teori strukturalisme. Teori strukturalisme merupakan teori yang telah ada sejak jaman Aristoteles, tetapi secara terus-menerus diperbaharui sampai awal abad ke-20. Pergerakan kaum-kaum yang menolak tradisi strukturalis merupakan penyebab utama perkembangan teori sastra. Perkembangan teori sastra diawali dengan teori strukturalisme yang melihat karya sastra adalah struktur yang otonom. Dalam perkembangan selanjutnya, teori strukturalisme mulai ditinggalkan dan dan digantikan teori pascastrukturalis yang menolak serta ingin melepaskan diri dari belenggu struktural. Teori pascastrukturalisme berupaya untuk memberikan teori sastra yang tidak hanya berkutat pada struktur karya sastra, tetapi juga pada struktur ekstrinsik dan hubungan sastra dengan lingkungan. Beberapa teori strukturalisme adalah formalisme Rusia, New Criticism, strukturalisme dinamik, strukturalisme genetik, naratologi, dan semiotika. Sedangkan teori pascastrukturalisme adalah postmodernisme, postkolonialisme, dekonstruksi, resepsi sastra, intertekstual, feminisme sastra, dan teori-teori naratologi pascastrukturalis. Teori strukturalisme dan pascastrukturalisme dapat digunakan untuk menganalisis sastra klasik maupun modern. Hal ini karena teori-teori sastra dapat digunakan untuk memahami objek yang berbeda. Selain itu, perkembangan teori sastra juga disebabkan oleh kebutuhan teori-teori dari disiplin ilmu lain yang dapat mendukung studi sastra. Hal ini yang menyebabkan munculnya teori interdisipliner dalam sastra.
Kata kunci : teori sastra, strukturalisme, pascastrukturalisme
PENGANTAR
Dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan, istilah teori memang sudah tidak asing.
Teori dapat dianggap sebagai suatu bumbu, sedangkan ilmu pengetahuan adalah
masakan. Secara umum, yang dimaksudkan dengan teori adalah suatu sistem ilmiah
atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-
gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu
objek ilmu pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara
logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek atau gejala yang
diamati tersebut.
1

Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, kriteria yang dapat diacu dan dijadikan
titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Sedangkan studi terhadap karya konkret disebut
kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiganya berkaitan erat sekali. Tidak mungkin kita
menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, kritik sastra tanpa teori sastra
dan sejarah sastra (Wellek dan Warren 1989: 38–39).
Pada awal kemunculannya, teori sastra berkutat pada struktur karya sastra, yang
sering disebut dengan periode strukturalisme. Teori-teori strukturalisme merupakan
teori yang secara genesis telah ada sejak zaman Aristoteles, tetapi secara terus-menerus
diperbaharui sepanjang sejarahnya hingga awal abad ke-20 (Ratna 2009: 5).
Perkembangan teori strukturalisme sejak zaman Formalisme Rusia hingga
pascastrukturalisme mengalami banyak perubahan yang dilakukan para pembawa
teorinya. Hal ini menunjukkan bahwa teori sastra mengalami perkembangan yang besar.
Sebenarnya semua teori sastra sejak zaman Aristoteles telah menekankan pentingnya
pemahaman struktur dalam analisis sebuah karya sastra. Akan tetapi istilah kritik
strukturalisme secara khusus mengacu kepada praktik kritik sastra yang mendasarkan
model analisisnya pada teori linguistik modern.
Teori-teori strukturalisme maupun pascastrukturalisme dapat digunakan untuk
menganalisis sastra lama dan sastra modern. Hal ini karena teori sastra dapat
dimodifikasi sebagai upaya memahami objek-objek yang berbeda. Menurut Ratna
(2009: 15–16) pesatnya perkembangan teori sastra hingga saat ini dipicu oleh beberapa
sebab, antara lain (1) medium sastra adalah bahasa yang mempunyai problematika yang
luas; (2) sastra memasukkan berbagai dimensi kebudayaan yang mengandung
permasalahan yang beragam; (3) teori-teori utama dalam bidang sastra telah
berkembang sejak zama Aristoteles yang telah dimatangkan dalam berbagai displin
ilmu; (4) kesulitan dalam memahami gejala sastra memicu para ilmuwan untuk
menemukan teori baru; dan (5) ragam sastra berkembang secara dinamis sehingga
memerlukan cara peahaman yang berbeda.
IKHTISAR TEORI SASTRA MODERN
Teori-Teori Strukturalisme
Perkembangan teori sastra dimulai sejak awal abad ke-20. Perkembangan teori
sastra ini sejalan dengan berkembangnya genre sastra. Hal ini menunjukkan bahwa
2

dengan berkembangnya suatu genre sastra akan memengaruhi berkembang dan
munculnya teori sastra baru agar lebih relevan. Pada masa awal ini strukturalisme
berhasil menjadi daya pikat dalam penelitian terhadap karya sastra masa itu.
Sebelum muncul teori-teori strukturalisme muncul teori yang berkembang di Rusia,
yaitu teori formalisme yang dibawa oleh kelompok Formalisme Rusia. Teori
formalisme muncul sebagai akibat penolakan pada paradigma positivme abad ke-19
yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dan sebagai reaksi terhadap studi
biografi. Pada umumnya Formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan
berkembangnya teori-teori strukturalisme.
Tokoh utama formalis adalah Roman Jakobson yang kemudian membantu
mendirikan Kalangan Linguistik Praha pada tahun 1926. Kaum formalis mulai
memproduksi teori sastra yang bersangkutan dengan kecakapan teknis penulis dan
keterampilan kerja tangan (Selden 1993: 2). Tujuan utama formalisme adalah studi
ilmiah mengenai sastra. Mereka percaya bahwa studi mereka akan meningkatkan
kemampuan pembaca untuk membaca teks sastra dengan caya yang tepat. Persepsi
lewat bentuk artistik memperbaiki kesadaran dunia dan membangkitkan banyak hal
(Nuryatin 2005: 3).
Setelah banyak tokoh yang menolak teori formalis, muncul teori baru karena
ketidakpuasan terhadap formalisme, yaitu teori strukturalisme. Meskipun strukturalisme
masih berhubungan dengan formalisme Rusia, strukturalisme pada umumnya dianggap
sebagai perkembangan dari formalisme. Sebelum perkembangan strukturalisme, di
Amerika Serikat berkembang sebuah teori dan model aliran sastra baru, yaitu New
Criticism. Istilah new criticism pertama kali dikemukakan oleh John Crowe Ransom
dalam bukunya The New Criticism (1940) dan ditopang oleh I.A. Richard dan T.S.
Eliot. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kritik sastra sebelumnya yang terlalu
fokus pada aspek-aspek kehidupan dan psikologi pengarang serta sejarah sastra. Para
new criticism menuduh ilmu dan teknologi menghilangkan nilai perikemanusiaan dari
masyarakat dan menjadikannya berat sebelah. Manurut mereka, ilmu tidak memadai
dalam mencerminkan kehidupan manusia. Sastra dan terutama puisi merupakan suatu
jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan lewat pengalaman. Tugas kritik sastra adalah
memperlihatkan dan memelihara pengetahuan yang khas, unik dan lengkap seperti yang
ditawarkan kepada kita oleh sastra agung (Van Luxemburg dkk, 1988: 52-54).
3

Strukturalisme sebenarnya merupakan paham filsafat yang memandang dunia
sebagai realitas berstruktur. Hal ini yang diterapkan dalam sastra sehingga menganggap
karya sastra adalah suatu struktur yang otonom. Dalam teori-teori strukturalisme
terdapat sebuah konsep antarhubungan yang menyatakan bahwa karya sastra adalah
sebuah struktur yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan antara bagian yang satu
dengan bagian yang lainnya. Unsur-unsur itu hanya memperoleh artinya di dalam relasi,
baik relasi asosiasi ataupun relasi oposisi. Relasi-relasi yang dipelajari dapat berkaitan
dengan mikroteks (kata, kalimat), keseluruhan yang lebih luas (bait, bab), maupun
intertekstual (karya-karya lain dalam periode tertentu).
Strukturalisme sastra mengupayakan adanya suatu dasar yang ilmiah bagi teori
sastra, sebagaimana dituntut oleh disiplin-disiplin ilmiah lainnya. Untuk itu objek
penelitiannya, yakni karya sastra diidentifikasi sebagai suatu benda seni yang indah
karena penggunaan bahasanya yang khusus. Objek studi teori strukturalisme itu
ditempatkan dalam suatu sistem atau susunan relasi yang memudahkan pengaturannya.
Dengan sistem ini kita menghimpun dan menemukan hubungan-hubungan yang ada
dalam realitas yang diamati.
Dalam perkembangan selanjutnya muncul beberapa kelompok teori strukturalisme,
seperti teori-teori strukturalisme dinamik, strukturalisme genetik, strukturalisme
naratologi, dan semiotik. Teori-teori tersebut mempunyai ciri khas masing-masing yang
dipergunakan dalam penelitian sastra. Strukturalisme dinamik (Ratna 2009: 93), yang
pertama kali dikemukakan oleh Mukarovsky dan Felik Vodicka, didasarkan atas
kelemahan-kelemahan strukturalisme sebagaimana yang dianggap sebagai
perkembangan dari formalisme. Strukturalisme dinamik bertujuan untuk
menyempurnakan strukturalisme yang hanya memprioritaskan unsur-unsur intrinsik
karya sastra.
Strukturalisme genetik senada dengan strukturalisme dinamik yang dikembangkan
atas dasar penolakan terhadap analisis strukturalisme murni, yaitu analisis pada unsur
intrinsik. Sktrukturalisme dinamik dan strukturalisme genetik menolak fungsi bahasa
sastra sebagai bahasa yang khas. Tetapi dalam lingkup komunikasi sastra,
strukturalisme dinamik hanya terbatas pada peranan penulis dan pembaca sastra,
sedangkan strukturalisme genetik dapat melangkah lebih jauh ke struktur sosial. Tokoh
utama dalam strukturalisme genetik adalah Lucien Goldmann. Strukturalisme genetik
4

memiliki implikasi yang lebih dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu
kemanusiaan pada umumnya. Sebuah struktur, bagi Goldmann, harus disempurnakan
agar memiliki makna, di mana setiap gejala memiliki arti apabila dikaitkan dengan
struktur yang lebih luas, demikian seterusnya hingga setiap unsur menopang totalitasnya
(Ratna 2009: 121–122).
Dalam perkembangan strukturalisme, terdapat kelompok strukturalisme naratologi.
Naratologi juga disebut teori wacan (teks) naratif. Baik naratologi maupun teori wacana
(teks) naratif diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan.
Naratologi berkembang atas dasar analogi linguistik, seperti model sintaksis,
sebagaimana hubungan antara subjek, predikat, dan objek penderita (Ratna 2009: 128).
Awal perkembangan teori narasi terdapat beberapa tokoh pelopornya, seperti: Poetica
Aristoteles (cerita dan teks), Henry James (tokoh dan cerita), Forster (tokoh bundar dan
datar), Percy Lubbock (teknik naratif), Vladimir Propp (peran dan fungsi), Claude Levi-
Strauss (struktur mitos), Tzvetan Todorov (historie dan discours), Claude Bremond
(struktur dan fungsi), Mieke Bal (fabula, story, text), Greimas (tata bahasa naratif dan
struktur aktan), dan Shlomith Rimmon-Kenan (story, text, narration). Pada umumnya
periode strukturalis terlibat ke dalam dikotomi fabula dan sjuzhet (cerita dan plot).
Teori dalam periode struktural terdapat istilah teori semiotik. Strukturalisme dan
semiotik umumnya dipandang termasuk dalam suatu bukan teoritis yang sama.
Sebetulnya apa yang dinamakan semiotik sastra bukan merupakan suatu aliran ilmu
sastra. Berbagai aliran seperti strukturalisma dan ilmu sastra linguistik dapat dinamakan
semiotik (Van Luxemburg dkk, 1984: 44–46). Hal ini berbeda dengan pendapat Culler
(dalam Ratna 2009: 97) yang menyebutkan bahwa strukturalisme dan semiotika adalah
dua teori yang hampir sama, strukturalisme memusatkan pada karya sedangkan
semiotika pada tanda. Sedangkan Selden (1993: 55) mengungkapkan bahwa
strukturalisme dan semiotika adalah dua bidang ilmu yang sama sehingga keduannya
dapat dioperasikan secara bersama-sama. Analisis semiotika merupakan tindak lanjut
dari analisis strukturalisme.
Teori-Teori Pascastrukturalisme
Pada akhir tahun 1960-an lahir paham baru yang dianggap sebagai penyempurna
dan tindak lanjut dari paham sebelumnya, yaitu pascastrukturalisme. Pikiran
5

pascastrukturalis telah menemukan kodrat pemaknaan yang tidak stabil secara esensial.
Dibalik munculnya paham pascastrukturalisme adalah karena kelemahan strukturalisme,
seperti (1) model analisis strukturalisme dianggap kaku karena hanya didasarkan pada
struktur dan sistem tertentu, (2) strukturalisme lebih memberikan perhatian pada karya
sastra sebagai suatu sistem yang otonom sehingga melupakan pengarang dan
pembacanya, dan (3) hasil analisis seolah-olah hanya untuk kepentingan karya sastra itu
dan melupakan kepentingan masyarakat. Kelahiran pascastrukturalisme dimaksudkan
untuk mengantisipasi berbagai distorsi sistem semantis sehingga karya sastra dapat
berfungs dalam masyarakat.
Pada masa pascastrukturalis muncul beberapa teori yang banyak berkembang
hingga saat ini, seperti teori postmodernisme, postkolonialisme, resepsi sastra,
intertekstual, feminisme sastra, dekonstruksi, dan naratologi pascastrukturalis.
Munculnya pascastrukturalis secara otomatis akan melupakan struktur dan akan
mendekonstruksi karya sastra sehingga pascastrukturalis juga sering disebut dengan
istilah dekonstruksi. Dekontruksi merupakan ragam teori sastra yang tidak begitu
menghiraukan struktur karya sastra. Menurut Ratna (2009: 222) dekonstruksi, yang
dipelopori oleh Jaques Derrida, menolak adanya logosentrisme dan fonosentrisme yang
secara keseluruhan melahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lain yang bersifat
hierarkis dikotomis.
Abrams mengungkapkan bahwa dekonstruksi pada hakikatnya merupakan cara
membaca teks yang menumbangkan anggapan bahwa sebuah teks itu memiliki
landasan, dalam sistem bahasa yang berlaku untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan
makna yang telah menentu. Teori ini menolak anggapan bahwa bahasa telah memiliki
makna yang pasti, tertentu, dan konstan sebagaimana halnya pandangan strukturalisme
klasik (dalam Nurgiyantoro 1998: 59).
Menurut Endraswara (2008b: 167–168) pascastrkturalis dapat dikatakan sebagai
periode postmodernis. Hal ini disebabkan karena postmodernis merupakan lawan dari
modernisme yang masih memanfaatkan teori-teori struktural dalam analisis karya sastra.
Paham modernisme yang dibawa kaum modernis akan berhenti pada kajian struktural
sastra. Ciri utama postmodernis adalah penolakan terhadap adanya satu pusat,
kemutlakan, narasi-narasi besar, metanarasi, gerak sejarah yang monolinier.
6

Postmodernis mensubversi uniformitas, homogenitas, dan totalitas dengan memberikan
intensitas pada perbedaan-perbedaan, relativitas, dan pluralisme.
Naratologi yang berkembang pada masa pascastrukturalis pada umumnya
mendekonstruksi dikotomi parole dan langue, fabula, dan sjuzhet dengan ciri-ciri naratif
nonliterer, interdisipliner, termasuk feminis dan psikoanalisis. Para pelopornya, di
antaranya: Gerard Gennet (urutan, durasi, frekuensi, modus, dan suara), Gerald Prince
(struktur narratee), Seymoeur Chatman (struktur naratif), Jonathan Culler (kompetensi
sastra), Roland Barthes (kernels dan satellits), Mikhail Bakhtin (wacana polifonik),
Hayden White (wacana sejarah), Marry Louise Pratt (tindak kata), Umberto Eco
(wacana dan kebohongan), Michel Foucault (wacana dan kekuasaan), Jean-Francois
Lyotard (metanarasi), dan Jean Baudrillad (hiperealitas, pastiche). (Ratna 2009: 242)
Dalam periode pascastrukturalis, teori resepsi dan interteks berkembang dengan
pesat. Resepsi memberikan perhatian pada pembaca, sedangkan interteks pada
hubungan antara karya yang satu dengan yang lain. Dalam arti luas, resepsi sastra
merupakan pengolahan teks yaitu cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra
sehingga dapat memberika respon terhadap karya sastra itu. Dalam dunia kesusastraan,
teori resepsi yang banyak digunakan adalah teori resepsi Hans Robert Jauss (horizon
harapan) dan Wolfgang Iser (pembaca implisit). Namun pada perkembangannya banyak
tokoh yang memunculkan teori resepsi sastra, seperti Jonathan Culler dengan teori
konvensi pembaca.
Teori interteks tidak akan lepas dari teori Riffaterre mengenai konsep hipogram.
Menurut Riffaterre (dalam Endraswara 2008b: 132) hipogram adalah modal utama
dalam sastra yang akan melahirkan karya sastra berikutnya. Jadi dapat diartikan bahwa
hipogram merupakan karya sastra yang akan menjadi latar belakang munculnya karya
sastra berikutnya yang dinamakan karya transformasi. Prinsip dasar intertekstualitas
adalah karya sastra hanya dapat dipahami maknanya secara utuh dalam kaitannya
dengan teks lain yang menjadi hipogram.
Dalam perkembangan selanjutnya, teori-teori pascastrukturalis juga mendapat
kontribusi dari teori kontemporer pada tahun 1960-an, yaitu teori feminis yang
dipelopori oleh Virginia Woolf (Ratna 2009: 183). Konsep feminisme adalah
membalikkan paradigma bahwa perempuan berada di bawah dominasi laki-laki,
perempuan adalah pelengkap, dan perempuan sebagai makhluk kedua. Sejalan dengan
7

konsep itu, studi feminisme dalam sastra adalah studi literer perempuan, pengarang
perempuan, pembaca perempuan, tokoh perempuan, dan sebagainya.
Teori pascastrukturalis yang dapat dikatakan masih baru adalah teori-teori
postkolonialisme. Teori postkolonial dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang
mencoba mengungkapkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme (Ratna
2008: 120). Analisis menggunakan teori postkolonial dapat digunakan untuk menelusuri
aspek-aspek tersembunyi atau dengan sengaja disembunyikan sehingga dapat diketahui
bagaimana kekuasaan itu bekerja, selain itu untuk membongkar disiplin, lembaga, dan
ideologi yang mendasarinya. Dalam hubungan inilah, bahasa, sastra, dan kebudayaan
dapat memainkan peranan sebab dalam ketiga gejala tersebut mengandung wacana
sebagaimana diintensikan oleh kelompok kolonialis (2008: 104). Teori postkolonial
awalnya dikhususkan bagi penelitian negara-negara yang secara langsung pernah
menjadi koloni. Tetapi pada perkembangannya, postkolonialisme dianggap telah
berpengaruh secara global.
Teori-Teori Interdisipliner
Perkembangan teori-teori interdisipliner muncul akibat adanya kebutuhan para
peneliti sastra terhadap teori-teori disiplin ilmu lain yang dapat dimanfaat dalam studi
sastra. Sebenarnya teori interdispliner ini sudah dibicarakan sejak zaman strukturalis
yaitu oleh Wellek dan Warren dalam buku Teori Kesusastraan. Dalam buku tersebut
Wellek dan Warren memberikan hubungan antara karya sastra dengan bidang lain, yaitu
sastra dan pemikiran, sastra dan ilmu jiwa, sastra dan masyarakat, sastra dan biografi.
Hubungan antara sastra dengan ilmu jiwa dan masyarakat banyak berkembang hingga
saat ini. Teori-teori interdisipliner dalam sastra yang banyak ditemukan adalah teori-
teori dalam bidang psikologi sastra, sosiologi sastra, dan antropologi sastra. Dalam
praktiknya, penelitian interdisipliner ini menggunakan teori-teori strukturalisme dan
pascastrukturalisme di samping teori-teori disiplin ilmu lain.
Bidang psikologi sastra adalah bidang interdisipliner ilmu sastra dengan ilmu-ilmu
psikologi. Tokoh psikologi yang banyak dimanfaatkan teorinya dalam studi sastra
adalah Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya. Selain itu juga banyak digunakan
teori psikologi lain seperti Carl Gustav Jung (psikologi kepribadian), Hurlock (psikologi
perkembangan), dan beberapa tokoh lainnya. Dalam penerapannya dalam studi sastra,
8

psikologi dapat digunakan untuk menganalisis psikologi pengarang, psikologi tokoh,
dan pesikologi pembaca.
Bidang sosiologi sastra merupakan bidang interdisipliner ilmu sastra dengan teori-
teori ilmu sosial. Teori-teori ilmu sosial yang banyak dimanfaatkan dalam studi sastra
adalah teori hegemoni yang dibawa Antonio Gramsci, teori strukturalisme genetik oleh
Lucian Goldmann, teori-teori Marxis oleh Karl Marx, teori ideologi, teori trilogi
pengarang-karya-pembaca, dan teori dialogis (Ratna 2009: 339).
Bidang antopologi sastra merupakan bidang interdisipliner antara sastra dengan
ilmu antropologi, khususnya bidang kajian antropologi budaya. Dalam bidang ini
banyak berkembang studi-studi yang memanfaatkan teori-teori naratologi strukturalis
maupun pascastrukturalis. Umumnya teori-teori antropologi sastra digunakan untuk
menganalisis folklor, baik folklor lisan maupun folklor yang telah dibukukan. Dalam
perkembangannya antropologi sastra juga berkembang ke dalam kajian etnografi dan
kebudayaan yang ada dalam sastra. Hal ini menunjukkan bahwa antropologi sastra
memiliki relevansi dengan sastra yang bercorak lokal. Menurut Ratna (2009: 353)
antropologi sastra cenderung memusatkan perhatiannya pada masyarakat kuno. Karya
sastra dengan masalah mitos, bahasa dengan kata-kata arkhais banyak digunakan
sebagai objek kajian antropologi sastra.
PENUTUP
Dalam kurun waktu satu abad, perkembangan teori sastra dapat dikatakan sangat
pesat. Hal ini juga dipengaruhi adanya kontribusi teori-teori dari disiplin ilmu lain.
Pergerakan-pergerakan kaum-kaum yang menolak tradisi strukturalis merupakan akibat
utama berkembangnya teori-teori sastra.
Perbedaan pendapat tentang teori sastra tidak pernah akan ada akhirnya, dan
memang seharusnya tidak perlu diakhiri. Dengan munculnya teori-teori
pascastrukturalis tidak berarti bahwa teori strukturalis tidak relevan lagi dan harus
ditinggalkan. Banyak penelitian sastra yang menggabungkan dua teori yang berbeda
masa ini sehingga dapat menciptakan karya penelitian yang lebih mendalam. Teori-teori
sastra yang ada sekarang dapat mengalami perkembangan apabila para peneliti sastra
membutkan teori-teori sastra yang lebih relevan untuk karya sastra di masa mendatang.
9

DAFTAR PUSTAKA
Damono, Sapardi Djoko. 1973. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: P3B Dekdikbud.
Endraswara, Suwardi. 2008a. Metodologi Penelitian Psikologi Sastra. Yogyakarta: Media Pressindo.
_________. 2008b. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Media Pressindo.
Faruk. 1999. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurgiyantoro, Burhan. 1998. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: UGM Press.
Nuryatin, Agus. 2005. Formalisme Rusia: Mengolah Fakta dalam Fiksi. Semarang: Rumah Indonesia.
_________. 2006. “Teori Sastra I”. Modul. FBS, Unnes.
Ratna, Nyoma Kutha. 2008. Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_________. 2009. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Selden, Raman. 1993. Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini. Diterjemahkan oleh Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: UGM Press.
Sugihastuti. 2005. Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Teeuw, A. 1988. Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Dunia Pustaka.
Todorov, Tzvetan. 1985. Tata Sastra. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. Teori Kesusastraan. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Jakarta: Gramedia.
10