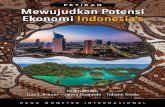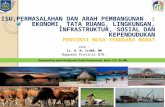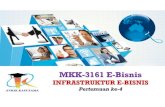Sosial Dan Infrastruktur Di Negara Berkembang
-
Upload
rieesqy-kiekik -
Category
Documents
-
view
139 -
download
1
Transcript of Sosial Dan Infrastruktur Di Negara Berkembang
Gelombang globalisasi yang terjadi saat ini memungkinkan negara berkembang untuk melakukan terobosanterobosan kreatif dan melakukan perubahan dalam negeri mengingat pesaingan antar negara yang ketat hanya akan dimenangkan oleh mereka yang memiliki keunggulan. Salah satu yang membedakan mengapa negara maju unggul karena pada umumnya negara maju memiliki daya saing yang tinggi dibanding negara berkembang. Berdasarkan data Global Competitiveness Report (GCR) tahun 2010 2011, daya saing Indonesia berada di urutan ke-44 dari 144 negara, mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya di mana Indonesia hanya berada di posisi 54. Daya saing ini menjadi semakin unggul jika didukung oleh sarana sarana lain seperti sarana infrastruktur yang memadai. Ada tujuh kelompok yang dikategorikan sebagai komponen dari Infrastruktur menurut Grigg & Fontane dalam Infrastructure System Management & Optimization yaitu Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan), Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan), Komunikasi, Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air : sungai, saluran terbuka, pipa), Pengelolaan limbah, Bangunan; serta Distribusi dan produksi energi. Infrastruktur tersebut merupakan modal dasar dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi faktor penting menghadapi persaingan global. Tingginya tingkat daya saing dan kualitas serta kuantitas infrastruktur yang memadai akan membuat negara menjadi kuat dan maju. Sebagai negara berkembang yang akan segera bergabung dengan kelompok negara-negara maju, Indonesia sudah saatnya memiliki rencana jangka panjang dalam program pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Apabila kondisi tersebut didukung oleh stabilitas yang semakin baik dan meningkat dari sektor ekonomi, politik, hukum dan sektor-sektor lainnya maka tidak lama lagi Indonesia telah siap untuk dijadikan bagian dari negara BRIC (Brazil, Russia, India dan China) + I (Indonesia) sebagai negara dengan potensi pertumbuhan terkuat di dunia. Saat ini, sepertinya peningkatan daya saing Indonesia belum diimbangi dengan perbaikan dari sisi infrastruktur. Infrastruktur Indonesia pada tahun 2010 berada di urutan 82, kondisi jalan berada di posisi 84, dan ketersediaan pasokan listrik di posisi 97. Sementara, jika dibandingkan dengan infrastruktur negara tetangga, Malaysia menempati urutan 23, dan Thailand di posisi 29. Dari segi sarana jalan raya, pada tahun 2008 kondisi jalan yang layak pakai hanya berkisar 9.500 km, jalan rusak berat 2.500 km dan rusak ringan 3.800 km. Maka tidak mengherankan kalau kalangan pengusaha mengeluhkan kondisi ini. Buruknya infrastruktur jalan mengakibatkan kenaikan biaya logistik. Bahkan kalangan pengusaha harus menanggung biaya logistik berkisar 20%-25% sedangkan di Malaysia hanya mengeluarkan biaya logistik sebesar 10% dari seluruh ongkos produksi. Bagi Indonesia, investasi infrastruktur menjadi pilihan utama untuk dapat bersaing di kancah global. Investasi dibidang ini akan mampu menarik investor asing dan menambah lapangan pekerjaan, sehingga mampu mengikis jumlah pengangguran.
Sebagaimana diketahui, pembangunan infrastruktur memiliki korelasi kuat dalam menambah jumlah lapangan kerja. Menurut data BPS, pada bulan Februari 2010, dari total angkatan kerja sebesar 116,00 juta orang, sekitar 92,60 persennya adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada Februari 2010 bertambah sebanyak 2,53 juta orang (2,42 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2009 dan bertambah sebanyak 2,92 juta orang (2,80 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2009). Data BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada Februari 2010 sebesar 8,59 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 666 ribu orang (7,20 persen) dibandingkan keadaan Februari 2009 yang besarnya 9,26 juta orang. Menurut Bappenas,
kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBN, dengan total anggaran Rp 50 triliun, akan mampu menciptakan sekitar 1,4 juta pekerja selama satu tahun. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa jika sejak awal pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan baik dan terencana maka tingkat pengangguran akan lebih rendah daripada kondisi saat ini. Perbedaan daya saing dan infrastruktur antarnegara ini berimplikasi pada optimalisasi dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai oleh negara tersebut.Belajar dari sejarah krisis Amerika tahun 1930, diketahui bahwa pembangunan infrastruktur merupakan resep utama untuk meredam pelambatan ekonomi. Pada saat Amerika dilanda krisis ekonomi pada tahun 1930-an, salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, yang melibatkan banyak tenaga kerja. Proyek raksasa yang dibiayai pemerintah tersebut berhasil menggerakkan ekonomi Amerika yang lumpuh karena berbagai perusahaan konstruksi terlibat dan ratusan ribu pekerja menjadi bagian dari proyek tersebut. Pembangunan Infrastruktur selain menyerap banyak tenaga kerja, juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan Jepang yang ekonominya sudah maju sampai saat ini masih terus membangun jalan dan jembatan di tempat-tempat terpencil. Pemerintah sebagai regulator utama dalam pembangunan sebaiknya memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas perlahan sudah dilakukan. Pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp 26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010. Kebijakan ini perlu kita dukung karena ini adalah kenaikan tertinggi, jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Anggaran belanja modal yang meningkat ini diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Mengingat bahwa salah satu masalah utama dalam pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan. Saat ini pemerintah menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak mungkinnya pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat apalagi sampai menjangkau daerah terpencil. Jika mengacu pada data Bappenas, untuk mewujudkan pembangunan infrastuktur selama tahun 2010-2014, Indonesia membutuhkan dana Rp l.429 triliun. Dari total kebutuhan anggaran itu, pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 31% atau Rp 451 triliun. Sisanya Rp 978 triliun masih belum jelas, darimana sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diusahakan. Untuk memenuhi anggaran tersebut harus ada terobosan alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang bisa dilakukan pemerintah. Alternatif pembiayaan tersebut berasal dari dana pinjaman luar negeri atau dari dalam negeri. Belajar dari pengalaman Jepang, saat ini Jepang memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia. Namun, dengan kondisi tersebut, Jepang relatif masih mampu menjaga stabilitas karena semua utang didanai dari sumber dalam negeri, misalnya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Sumber dana dalam negeri ini diharapkan terus berkembang jumlahnya sehingga dana ini perlu mendapat prioritas dari pemerintah, baik berupa obligasi maupun sukuk (obligasi syariah). Meski potensinya cukup positif, kebijakan untuk memanfaatkan pasar obligasi dan sukuk secara rutin perlu kontrol karena fluktuasi yang demikian besar pada kedua pasar tersebut. Hal ini penting sebagai
mekanisme check and balance keuangan negara dan juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar persepsi masyarakat tidak keliru dengan adanya penerbitan SUN. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pemerintah dibenarkan untuk menerbitkan SUN secara terus menerus? Tentunya selama tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan dari investasi yang dibiayai oleh obligasi tersebut lebih dari biaya bunganya dan belum mencapai titik optimal maka penjualan obligasi masih dapat dibenarkan. Sebaliknya jika tingkat pengembalian investasi lebih rendah dari biaya bunga obligasi maka penjualan obligasi wajib dihentikan. SUN mampu memberikan nilai tambah untuk pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika dilakukan dengan governance yang tepat. Maka dari itu, pemerintah diupayakan mampu menciptakan hutang baru dalam negeri melalui SUN yang bersifat jangka panjang (10-20 tahun) untuk membiayai infrastruktur. Apalagi sampai saat ini pemerintah lebih memiliki kepastian dalam pemasukan negara, khususnya dari pajak yang mencapai hampir 800 trilyun pada tahun ini sehingga ada jaminan yang jelas. Alternatif lainnya, pemerintah juga harus progresif dalam membangun kerjasama dan kemitraan dengan publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya pemerintah mutlak memerlukan hadirnya pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara serius untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja secara masif. Karena itu sangat diperlukan jenis proyek infrastruktur yang dikerjakan dalam jangka panjang, memberikan dampak ekonomi jangka panjang sebagai public infrastructure utilities, dan pemerintah menjadi pengendalinya. Kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pembangunan proyek infrastruktur merupakan altematif strategi pembiayaan yang tepat. Kemitraan pemerintah dengan swasta didefinisikan sebagai suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsep yang perlu dikembangkan untuk jangka panjang adalah konsep Users pays sebagaimana diterapkan pada jalan tol di Indonesia. Sebagai contoh, dalam pembangunan jalan tol prinsipnya harus memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Sebagai regulator pemerintah memberikan jaminan kepada pihak swasta melalui kepastian hukum dalam bisnis jalan tol, iklim investasi yang kondusif, diberikan konsesi yang layak untuk dapat mengembalikan dana investasi dan keuntungan yang wajar. Model seperti ini dapat dilakukan untuk pengembangan infrastruktur lain diberbagai wilayah di Indonesia. Sekali lagi, perbaikan infrastruktur penting karena pengaruhnya terhadap perekonomian cukup besar, meski bersifat jangka panjang. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi alat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Maka dari itu pemerintah harus lebih fokus dalam membangun Infrastruktur di berbagai wilayah dan kreatif dalam pembiayaan karena diyakini langkah-langkah ini akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di era global dan memunculkan efek multiplier lainnya seperti penurunan angka pengangguran, percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi sosial ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita sangat butuh pemimpin yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan yang terencana dan terintegrasi secara jangka panjang hingga 20-30 tahun kedepan. Pemimpin yang memiliki integritas dan cermat dalam mengambil keputusan untuk kebaikan negeri ini. Pemimpin visioner yang siap untuk segera bergerak menanam pohon-pohon kebaikan yang buahnya suatu saat akan dinikmati oleh generasi yang akan datang
Terdapat 33 negara yang masuk kategori Negara Maju. Sebanyak 26 negara berada di kawasan Eropa (Prancis, Jerman, Belanda, Inggris,dst.) dan 6 diantaranya masuk bagian Eropa Timur dan Tengah (Bulgaria, Hongaria, Polandia, Slovenia, Republik Slovak dan Czechnya). Dua negara, Estonia dan Ukraina, merupakan negara yang baru merdeka dari bekas Uni Sovyet. Mayoritas negara-negara ini memiliki sejarah demokrasi yang kukuh dan sistem ekonomi terbuka. Kondisi ekonominya sangat baik dan stabil. Rata-rata GDP mencapai $18.700 dengan inflasi yang relatif rendah (3,1%). Tingkat tabungan dan investasi tinggi, sedangkan utang luar negerinya sangat rendah. Sebagian besar Negara Maju adalah negara kecil dengan penduduk kurang dari 25 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Tingkat kematian bayi di negara-negara ini sangat rendah, hanya 8 orang per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan usia harapan hidup mencapai 79 tahun dengan ketergantungan anak hanya 20%. Sebagian besar penduduknya (98%) dapat membaca dan melanjutkan pendidikan tinggi. Satu faktor utama yang menyebabkan majunya pembangunan sosial di negara-negara ini adalah adanya jaminan sosial universal yang melindungi setiap penduduknya dari resiko kehilangan pendapatan, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, masa tua, hamil, dan pengangguran. Sebesar 46% dari GNP-nya dikeluarkan untuk mebiayai berbagai pelayanan sosial dan kesehatan (OECD, 1996). Negara-negara yang masuk kategori Negara Berkembang Menengah menyebar diseluruh wilayah geografis: Asia (36 negara), Amerika Latin (22), Afrika (10), dan Oceania (1). Sebagian besar negaranegara ini telah memiliki apa yang disebut social ingredients yang diperlukan untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi maju, seperti stabilitas politik, dinamika ekonomi, akses ke sumber daya alam (khususnya enegi), kualitas kesehatan, pendidikan dan sistem jaminan sosial. GNP per kapita di Negara Berkembang Menengah juga relatif tinggi, sekitar US$4910 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun dan laju inflasi 7% per tahun. Tingkat pengangguran relatif rendah, sekitar 13,1% dari jumlah angkatan kerja. Namun demikian, beberapa negara masih memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti pemerintahan korup, jumlah dan pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya pengangguran dan meluasnya kemiskinan. Negara yang termasuk kategori Negara Berkembang Terbelakang berjumlah 38. Sebagian besar berada di Afrika (29 negara), 7 negara di Asia,1 negara di Amerika, dan 1 negara di Pasifik Selatan. Terbelakangnya pembangunan sosial di negara ini terlihat dari rendahnya kualitas hidup, seperti rendahnya usia harapan hidup (51 tahun), tingginya kematian bayi (110/1000) dan anak (177/1000). Tingginya kematian bayi dan anak merupakan yang tertinggi di dunia yang diakibatkan oleh infeksi dan penyakit menular. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang Terbelakang sangat tinggi, terutama disebabkan oleh rendahnya penggunaan alat KB dan tingginya migrasi internal. Yang penting dicatat, migrasi penduduk di negara-negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh motive ekonomi, melainkan juga oleh perang, konflik sipil dan ketidakstabilan politik. Konsekuensi sosial dari tingginya migrasi ini adalah (a) penelantaran anak, lanjut usia, dan kelompok tidak produktif di daerah pedesaan, (b) melemahnya, atau bahkan hilangnya, nilai-nilai tradisional dan keeratan keluarga, (c) memudarnya budaya dan praktek pertanian, (d) meluasnya kemiskinan, kekurangan gizi, dan kematian dini bagi orang yang tidak dapat bertahan hidup di kota besar yang padat polusi dan penduduk. Hingga hari ini, belum ada satu negarapun yang mampu mengatasi problema migrasi ini dengan efektif. Rata-rata GDP di negara-negara berkembang terbelakang ini sekitar US$950. Pertumbuhan ekonominya juga sangat rendah, hanya sekitar 3% dengan inflasi tinggi, mencapai 37%. Sarana komunikasi dan transportasi sangat terbatas, serta daya saing di pasar internasional juga sangat terbatas. Tabungan pemerintah dan sektor swasta sangat rendah, sementara utang luar negerinya sangat tinggi. Pemerintahan di sebagian besar negara ini sangat sentralistik. Roda ekonomi sangat tergantung pada gabungan antara pinjaman luar negeri, bantuan negara donor, dan investasi swasta dari luar negeri. Tingkat pengangguran di Negara Berkembang Terbelakang juga sangat tinggi. Meski secara resmi tercatat 20%, kenyataannya bisa lebih dari itu. Pengangguran terutama dialami oleh wanita, laki-laki berusia lebih ari 45 tahun, para penyandang cacat dan buta hurup.
Pengeluaran negara untuk program sosial sangat minimal. Sebagian besar negara bahkan tidak menyediakan asuransi dan jaminan sosial untuk pengangguran, sakit, hamil, kematian, dan cacat. Ironisnya, pengeluaran negara untuk Hankam di negara-negara ini mencapai 4,6% dari GNPnya yang berarti 50% lebih tinggi dari pada di Negara Berkembang Menengah.