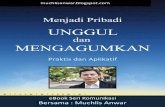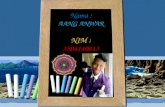Seful anwar
Transcript of Seful anwar
1. A. Hubungan antara Manusia dengan Bahasa Bahasa digunakan oleh manusia sebagai media untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan pada orang lain. Bahasa dengan manusia, pada gilirannya, menjadi hal yang menyatu karena bahasa adalah media paling representatif dalam mengemas ide untuk disampaikan pada orang lain. Koentjaraningrat dalam Pengangtar Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 80-81 meletakan bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan lainnya, yaitu sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Sementara itu, E. Cassier (1985), menyebutkan bahwa manusia adalah animal symbolicum, yaitu binatang yang menggunakan dan memproduksi simbol-simbol bahasa. Artinya, keistimewaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya (binatang) adalah paa kemampuan manusia dalam menggunakan dan memproduksi bahasa sebagai simbol, sedangkan binatang tidak bisa. B. Hipotesis Monogenesis dan Hipotesis Poligenesis 1. Hipotesis Monogenesis Menyebutkan bahwa bahasa itu berasal dari satu gen (induk), yaitu Tuhan, yang telah memberikan, memperkenalkan, dan mengajarkan bahasa pada manusia pertama: Nabi Adam a.s. 2. 2. Hipotesis Poligenesis (poli: banyak dan geneis: kelahiran) Hipotesis ini kebalikan dari hipotesis monogenesis, yaitu menganggap bahwa bahasa manusia lahir tidak dalam satu intuk Tuhan, tetapi bahasa manusia lahir secara beragam berdasarkan pada proses evolusi manusia di bumi yang beragam. C. Pengertian Bahasa, Fungsi Bahasa dan Ragam Bahasa 1. Pengertian Bahasa Secara umum, dapat dipahami, bahasa adalah media komunikasi untuk menyampaikan ide-gagasan, dan setiap manusia menggunakan bahasa ketika dirinya ingin mengungkapkan isi perasaan dan pikirannya pada orang lain. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana (1952), dikatakan bahasa adalah kedirian manusia, karena dengan manusia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, maka bahasa selalu merepresentasikan pribadi orang. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi untuk komunikasi antaranggota masyarakat yang bersifat konvensi (Keraf, 1997: 1; Widjono, 2007: 14; Chaer, 1998: 1; dan Ullmann, 2009: 20). 2. Fungsi Bahasa 3. a. Bahasa untuk menyatakan ekpresi diri Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Misalnya, saat sedang sedih manusia biasanya menangis dan akan menceritakan kesedihannya pada orang lain sebagai cara untuk membebaskan dirinya dari masalah tersebut. b. Bahasa sebagai alat komunikasi Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat intra-personal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antarmanusia. Hubungan timbal balik antarindividu dalam penyampaian pikiran dan perasaan yang dimediasi lewat bahasa inilah yang disebut dengan komunikasi. c. Bahasa untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial Manusia adalah mahluk sosial-masyarakat (kolektif) yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat inilah, manusia selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakatnya. Dalam pembentukan eksistensi itulah, maka manusia akan melakukan integrasi (pembauran) dan adapatasi (penyesuaian diri) dalam masyarakat, dan selalu, dalam proses integrasi dan adaptasi ini manusia selalu menggunakan bahasa sebagai perantaranya. 4. d. Bahasa untuk mengadakan kontrol sosial Yaitu bahasa akan dimobilisasi oleh seseorang sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Hampir setiap hari kegiatan kontrol sosial akan terjadi dalam masyarakat, misalnya, orangtua yang menasihati anak-anaknya, kepala desa yang memberikan penerangan dan penyuluhan pada warganya, kegiatan rapat-rapat di desa, dan sebagainya. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif, maka seseorang bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai dengan yang diharapkannya. 3. Ragam Bahasa Ragam bahasa berarti variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraanya (Alwi, dkk., 2003: 920). Dalam hal ini, ragam bahsa itu bersifat kompleks, bisa dibedakan dari berbagai aspek. Namun, pada pembahasan ini, dengan melihat fungsi utama bahasa sebagai media komunikasi, maka pembahasan ragam bahasa difokuskan pada proses komunikasinya yang melibatkan penutur, bahasa, dan komunikannya. Penuturnya: keragaman pembicara (penutur) dalam bahasa terjadi karena menurut patokan daerah, pendidikan, dan sikap penuturnya (Alwi, dkk., 2003: 3-5). 5. Berdasarkan situasi pembicaraannya, ragam bahasa disesuaikan dengan situasi dan keadaan saat pembicaraan (komunikasi) terjadi. Oleh karena bahasa Indonesia bersifat egaliter (terbuka), biasanya penggunaan bahasanya tergantung pada konteks atau situasinya. Bahasa: ragam bahasa berdasarkan pada bahasa sebagai sarananya terbagai atas ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah variasi bahasa yang simbol-simbolnya dihasilkan oleh alat ucap manusia (ujaran), sedangkan ragam tulisan adalah ragam bahasa yang simbol-simbolnya berupa kode-kode bahasa yang tercetak dalam tulisan. D. Pengertian Bahasa Indonesia Adalah sistem tanda yang konvensinya didasarkan pada masyraakat Indonesia, yang digunakan juga sebagai alat komunikasi oleh masyrakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Amin Singgih mendefinisikan bahasa Indonesia ialah bahasa yang dibuat, dimufakati, dan diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indoneisa (Rahayu, 2007: 8). E. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Berdasarkan konteks historisnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu rumpun bahsa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca, artinya bahasa perantara orang (masyarakat) yang latar budayanya berbeda, di Nusantara sejak abad-abad awal penaggalan modern, yang dalam temuan berbagai prasastinya yang paling tua, yang menggunakan bahasa 6. Melayu adalah paa abad ke-7 lewat prasasti itu antara lain, Prasasti Karang Birahi, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Kedukan Bukit yang masing-masing bertahun 686, 686, dan 688 Masehi Berdasarkan prasasti ini, bahasa Melayu bahasa Melayu dalam bentuk tulis pada abad ke-7 ini sudah ada. Namun, pastilah dapat dipastikan bahwa bahasa lisan Melayu tentu sudah lama ada. Adapun momentum kelahiran bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia ditengarai oleh Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menyatakan: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lewat sumpah pemuda ini, bahasa Melayu sebagai rumpun bahasa Indonesia telah resmi diangkat sebagai bahsa persatuan, yaitu bahasa yang secara politis dan kebudayaan akan digunakan sebagai bahasa pemersatu dan pergaulan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya, pada tahun 1945 dalam Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, pasal 36). Hal ini berarti, selain kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, UUD 1945 ini menegaskan tentang bahasa Indenesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam segala aktivitas kenegaraan atau peristiwa yang resmi, baik secara lisan dan tulisan. F. Definisi Huruf dan Tanda Baca Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakaan anggota abjad atau satuan terkecil dari penulisan lambang-lambang bunyi yang 7. membedakan arti. Membedakan arti karena perubahan huruf dalam sebuah kata menyebabkan perubahan artinya. G. Perbedaan antara Bahasa Lisan dan Bahasa Tulis Bahasa manusia, pada awalnya, adalah bahasa lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang berupa lambang-lambang bunyi. Akan tetapi, seiring perkembangan kebudayaan, manusia mulai menyadari kelemahan bahasa lisan, salah satunya, bahasa lisan bersifat temporal dan situasional. Artinya, komunikasi yang terjadi dengan bahasa lisan hanya bisa dilakukan secara situasional, dan bila komunikasi telah selesai, maka informasi yang disampaikan lenyap. Kelemahan bahasa lisan yang bersifat temporal ini membuat manusia berpikir: bagaimana caranya mendokumentasikan pikiran-pikiran manusia dengan bahasa yang tetap, bisa terus dipelajari dan dibaca oleh generasi yang akan datang. Hal inilah yang menjadi salah satu hal yang melatari munculnya bahasa tulis, yaitu bahasa yang merupakan pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk simbol-simbol tertulis (Keraf, 1997: 12). Sebagai bentuk pencerminan, maka bahasa tulis sering disebut bahasa sekunder, sedangkan bahasa lisan adalah bahasa primer, yaitu bahasa yang pertama kali digunakan manusia untuk berkomunikasi, sekaligus menjadi bahasa yang menjadi objek kajian linguistik, yaitu ilmu yang mengkaji bahasa. Bahasa tulis bisa melenyapkan dimensi ruang dan waktu dalam berkomunikasi karena dengan tulisan, komunikasi tidak harus melibatkan 8. hubungan penulis dan pembaca secara langsung dalam satu konteks. Akan tetapi, tulisan bisa dibaca oleh siapapun dan kapanpun. H. Aspek-aspek yang Membangun Ragam Bahasa Tulis dan Ragam Bahasa Lisan Dua aspek yang selalu ada dalam bahasa tulis, yang merupakan bentuk inskripsi (pendokumentasian) bahasa lisan, adalah unsur segmental, yang berupa simbol-simbol hruf yang membentuk kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana, dan unsur suprasegmental yang berupa tanda-tanda baca (pungtuasi) yang mengikuti unsur segmental. Oleh karena itu, ketepatan komunikasi dalam bahasa tulis ditentukan oleh ketepatan dalam menggunakan huruf dan tanda bacanya. I. Pengertian Klausa dan Kalimat Klausa merupakan tataran dalam sintaksis yang berada di antara frasa dan kalimat. Frasa merupakan gabungan atau kelompok kata yang bersifat nonpredikatif, sedangkan klausa merupakan gabungan atau kelompok kata yang belum memiliki intonasi aau tanda baca tertentu dan bersifat predikatif (Alwi, dkk., 2003: 39). Artinya, di dalam konstruksi klausa itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, dan yang lainnya berfungsi sebagai subejk. Selain fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa, fungsi subjek boleh dikatakan bersifat wajib (Chaer, 1994: 231). 9. Sementara itu, batasan kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan maupun tulis, yang mempunyai dua ciri pokok, yaitu: 1. Kalimat harus lengkap aspek ketatabahasaan atau unsur gramatikalnya, minimal terdiri atas subjek dan predikat. 2. Kalimat selalu mengungkapkan pikiran dan informasi secara utuh dan lengkap. J. Paragraf 1. Pengertian Paragraf Menurut Widjono Hs. (2007: 173-174), paragraf mempunyai beberapa pengertian: (1) paragraf adalah karangan panjang sudah ada; (2) paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri beberapa kalimat yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu; (3) paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya; (4) paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Namun, sekalipun tidak sempurna, paragraf yang terdiri satu kalimat dapat digunakan. 2. Ciri-ciri Paragraf 10. a. Kalimat pertama bertakuk ke dalam atau untuk karangan berbentuk lurus tidak bertakuk (block style) ditandai dengan jarak spasi merenggang. b. Paragraf menggunakan pikiran utama (gagasan utama) yang dinyatakan dalam kalimat topik. c. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam topik. d. Paragraf menggunakan pikiran penjelas (gagasan penjelas) yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 3. Syarat Paragraf yang Baik a. Kelengkapan Syarat utama sebuah paragraf adalah adanya pikiran utama yang dijabarkan dalam kalimat utama, dan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. b. Kesatuan Pikiran Paragraf ynag gagal adalah paragraf yang hubungan antara pikiran utama dan pikiran penjelasnya tidak sinkron, atau mungkin dalam kalimat-kalimat penjelas, sebagai representasi pikiran penjelas, masih dijumpai ketidaksatuannya dengan pikiran utama. 11. c. Kepaduan Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat- kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf akan menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Hubungan tersebut akan menghasilkan paragraf menjadi satu padu, utuh, dan kompak (Widjono Hs., 2007: 182).