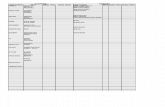REFERAT3
-
Upload
istiiryan1 -
Category
Documents
-
view
92 -
download
2
description
Transcript of REFERAT3
REFERAT
MASSA / BENJOLAN INTRAABDOMEN
Nama Pembimbing : dr. Djaja Sutisna , Sp.B
Disusun Oleh :
Isti Iryan Prianti
RSUD SUBANG
UNIVERSITAS YARSI FAKULTAS KEDOKTERAN
2014
BAB I
PENDAHULUAN
Abdomen adalah suatu regio yang sangat penting di dalam tubuh kita,
akan terdapat banyak organ-organ yang sangat penting di dalamnya, seperti
hati, limpa, kantong empedu dan lain-lain. Begitu banyaknya organ yang
termasuk dalam rongga abdomen. Terdapat pula banyak macam kelainan
yang dapat terjadi. Dengan ini penulis akan mencoba membahas dan
memaparkan bagian diagnosis dari beberapa kelainan yang terdapat dalam
abdomen, utamanya massa ataupun benjolan. Demikian juga mengetahui
perjalanan kelenjar limpa maka dapat mengetahui neoplasma ventriculi dapat
menjalar ke phylorus, gaster sinister dan lain–lain.
Seperti kita ketahui perut (abdomen), terdiri dari bagian dinding dan
bagian dalam, lazim disebut bagian parietal dan bagian visceral. Bagian
dinding terdiri dari cutis, subcutis, fascia super fisial, otak, lemak, pembuluh
darah superfisial, fascis super fisial, otot, lemak, pembuluh darah superfisial,
fascia profunda tulang dan peritoneum pariental. Bagian dalam akan dijumpai
organ–organ seperti, hepar, lien, duodenum, colon, appendix vermiformis,
caecum, pembuluh darah arteri vena atau pembuluh limph. Termasuk
pembuluh darah yang penting adalah aorta abdominalis dengan cabang–
cabangnya.
Aliran darah ini penting karena pada bagian dalam ini terdapat usus,
sehingga perlu peredaran darah yang kayak agar bila terjadi perlukaan,
maka tidak akan terjadi pembusukan jaringan dengan cepat.
Pembentukan massa atau benjolan pada bagian mana saja dalam tubuh
merupakan proses abnormal yang terjadi pada tubuh. Benjolan didefiniskan
sebagai tonjolan lembut atau tonjolan pada kulit. Seringkali yang harus
dipikirkan bahwa benjolan atau massa merupakan gejala klasik dari adanya
suatu tumor ataupun gangguan kesehatan lainnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
I. ANATOMI
Abdomen merupakan rongga terbesar dalam tubuh. Bentuknya lonjong dan
meluas dari atas dari drafragma sampai pelvis di bawah. Rongga abdomen
dilukiskan menjadi dua bagian, abdomen yang sebenarnya yaitu rongga sebelah
atas dan yang lebih besar dari pelvis yaitu rongga sebelah bawah dan lebih kecil.
Batas-batas rongga abdomen adalah di bagian atas diafragma, di bagian bawah
pintu masuk panggul dari panggul besar, di depan dan di kedua sisi otot-otot
abdominal, tulang-tulang illiaka dan iga-iga sebelah bawah, di bagian belakang
tulang punggung dan otot psoas dan quadratus lumborum. Bagian dari rongga
abdomen dan pelvis beserta daerah-daerah.
Abdomen merupakan bagian tubuh yang terletak di antara thorax dan pelvis.
Abdomen dibatasi:
- Superior: diaphragma
- Inferior: apertura pelvis superior
- Anterior: atas : bagian bawah cavum thoracis
bawah: m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis,
m. obliquus internus abdominis, dan m. transversus
abdominis beserta fascianya
- Posterior: bagian garis tengah dibentuk kelima vertebrae lumbales dan
discus intervertebralisnya
- Lateral: costae, os coxae, m. psoas major, m. quadratus lumborum, dan
aponeurosis origo m. transversus abdominis
Dinding abdomen dibagi menjadi dinding anterior dan posterior.
DINDING ABDOMEN ANTERIOR
Terdiri dari:
A. Kulit
Bagian tengah kulit mendapat vascularisasi dari arteri epigastrica superior
(cab. arteri thoracica interna) dan arteri epigastrica inferior (cab. arteri
iliaca externa). Sedangkan bagian pinggang divascularisasi cabang-cabang
arteri intercostalis, arteri lumbalis, dan arteri circumflexa ilium profundus.
Persarafan bagian kulit berasal dari Rr. anteriores 6 nervi thoracici bagian
bawah (5 nervi intercostales bagian bawah dan nervus subcostalis) dan
nervus lumbalis 1 (nervus iliohypogastricus dan nervus ilioinguinalis).
Pada saat inspeksi dan palpasi permukaan kulit, didapatkan bangunan
antara lain:
1. Angulus infrasternalis
Merupakan sudut yang dibentuk arcus costae dan processus
xiphoideus
2. Umbilicus
Derivat funiculus umbilicalis, terletak setinggi VL3 – VL5
3. Linea alba
Terdapat pada garis median yang dibentuk oleh lamina anterior et
posterior vagina musculi recti abdominis
4. Linea transversa
Gambaran inscriptions tendineae musculi recti abdominis di kanan kiri
linea alba
5. Linea semilunaris Spigelli
Garis lengkung dari pertemuan antara aponeurosis m. obliquus
internus abdominis dan m. transversus abdominis
6. Ligamentum inguinale
Merupakan penebalan aponeurosis m. obliquus externus abdominis
yang memanjang dari SIAS hingga tuberculum pubicum
7. Linea nigra
Gambaran linier dari pigmen kecoklatan pada linea mediana di bawah
umbilicus yang timbul selama kehamilan dan seterusnya tetap ada
8. Striae gravidarum
Gambaran linier berwarna kemerahan pada abdomen bagian bawah
yang disebabkan robeknya jaringan ikat intradermal karena
pengembangan kulit pada kehamilan, ascites, dll
9. Linea albicantes
Bekas striae gravidarum yang setelah partus berubah menjadi
gambaran linier berwarna putih dan berkilat
10. Caput medusa
Merupakan gambaran pembesaran vena-vena superficialis abdomen di
sekitar umbilicus akibat penghambatan sistem porta
Regiones pada kulit dinding anterior abdomen
Terdapat beberapa garis bantu horizontal dan vertikal untuk menentukan
regiones antara lain:
1. Linea xiphisternalis
Garis horizontal yang melalui articulatio xiphisternalis. Terletak antara
V.Th 9 dan V.Th 10 tetapi bervariasi tergantung sikap tubuh dan
respirasi.
2. Linea transpyloricae
Garis horizontal yang melalui titik tengah garis vertikal dari margo
superior symphisis pubis hingga margo superior manubrium sterni.
Terletak setinggi VL1.
3. Linea subcostalis
Garis horizontal yang melalui titik terbawah arcus costae. Terletak
setinggi processus spinosus VL2 saat posisi berdiri dan setinggi
processus spinosus VL3 saat berbaring.
4. Linea supracristalis
Garis horizontal yang melalui titik tertinggi crista iliaca dexter et
sinister. Terletak setinggi proc. spinosus VL4.
5. Linea intertubercularis
Garis horizontal yang melalui terbuculum crista iliaca. Terletak
setinggi proc. spinosus VL5.
6. Linea interspinosa
Garis horizontal yang melalui SIAS dexter et sinister.
7. Linea mediana
Garis vertikal yang berjalan di tengah dan membagi tubuh menjadi 2
bagian yang simetris.
8. Linea medioclavicularis
Garis vertikal yang menghubungkan titik tengah clavicula dengan titik
tengah dari garis antara SIAS dan symphisis pubis.
Dengan adanya garis-garis bantu, abdomen dibagi menjadi 9 regiones
yaitu:
1. Regio epigastrica
2. Regio hypochondriaca dextra
3. Regio hypochondriaca sinistra
4. Regio umbilicalis
5. Regio lumbalis dextra
6. Regio lumbalis sinistra
7. Regio hypogastrica
8. Regio inguinalis dextra
9. Regio inguinalis sinistra
B. Fascia Superficialis
Fascia superficialis abdominis dibagi menjadi fascia campher dan fascia
scarpa. Di atas umbilicus kedua fascia ini akan bersatu dan meluas ke
dinding anterior thorax menjadi fascia pectoralis superficialis, sedangkan
ke arah posterior menjadi fascia superficialis dorsi. Di bawah umbilicus,
kedua fascia ini dipisahkan menjadi:
1. Fascia Campher (lamina superficialis, berupa lemak):
Ke arah tungkai menjadi tela subcutanea femoris
Ke arah scrotum menjadi fascia superficialis penis
Ke arah perineum menjadi fascia perinealis superficialis
2. Fascia Scarpa (lamina profunda, berupa membranosa)
Ke arah tungkai menjadi fascia lata
Ke arah scrotum menjadi tunica dartos
Ke arah penis membentuk lig. fundiforme penis dan menjadi fascia
profunda penis
Ke arah perineum menjadi fascia perinealis profunda
Bangunan-bangunan pada fascia superficialis abdominis:
1. Pembuluh darah:
a. a. epigastrica superficialis (cabang a. femoralis)
b. a. circumflexa externa
c. a. pudenda externa
d. r. cutaneus a. epigastrica superior
e. r. cutaneus a. epigastrica inferior
f. r. cutaneus a. intercostalis
g. Vv. superficialis abdominis dibentuk oleh:
- v. thoraco epigastrica
- v. epigastrica superior
- ujung v. paraumbilicalis
- ujung v. epigastrica inferior
- v. circumflexa ilium superficialis
- v. pudenda externa
- v. dorsalis penis
2. Saraf:
a. Rr. cutanei Nn. intercostales 7-11
b. r. cutaneus n. subcostalis
c. r. cutaneus n. iliohypogastricus
d. r. cutaneus n. ilioinguinalis
3. Vasa lymphatica:
a. Di atas umbilicus, vasa efferent akan menuju: nl. axillaris, nl.
deltoideopectoralis, dan nl. mammaria interna
b. Di bawah umbilicus, vasa efferent akan menuju: nl. inguinalis dan
nl. iliaca interna
C. Fascia Profunda
Fascia profunda hanya berupa lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi
musculus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia Scarpa.
D. Musculi dan Aponeurosis
Bagian anterior: m. rectus abdominis
Bagian lateral (dari luar ke dalam): m. obliquus externus, m. obliquus
internus, dan m. transversus abdominis.
1. M. obliquus externus abdominis
Origo: dataran luar costae V-XII
Insertio: crista iliaca, linea alba
Saraf yang menembus musculus ini: Rr. cutanei n. intercostalis 7-12
dan r. cutaneus lateralis n. iliohypogastricus
Bangunan-bangunan:
a. Ligamentum inguinale Pouparti
Merupakan penebalan aponeurosis m. obliquus externus abdominis
yang membentang dari SIAS hingga tuberculum pubicum
b. Ligamentum lacunare Gimbernati
Merupakan perluasan dari lig. inguinale pars medialis ke arah
medial dan melekat ke pecten ossis pubis.
c. Ligamentum reflexum Callosi
d. Trigonum lumbale Petiti
Merupakan bangunan segitiga pada regio lumbal bawah dekat
crista iliaca.
Batas-batas:
Tepi medial : tepi lateral m. latissimus dorsi
Tepi lateral : tepi medial m. obliquus externus abdominis
Tepi bawah : crista iliaca
Dasar : m. obliquus internus abdominis
e. Annulus inguinalis superficialis
Merupakan celah triangulair pada aponeurosis m. obliquus
externus abdominis di atas tuberculum pubicum. Annulus
inguinalis superficialis terdiri dari dua crura yaitu crus lateralis
yang melekat pada tuberculum pubicum dan crus medialis yang
melekat pada symphisis pubis.
Bangunan yang keluar dari annulus ini:
Pada laki-laki : funiculus spermaticus
Pada perempuan : ligamentum teres uteri bersama a/v ligamenti
teres uteri, n. ilioinguinalis
f. Funiculus spermaticus
Berjalan pada canalis inguinalis, lalu keluar dari annulus inguinalis
superficialis untuk masuk ke dalam scrotum. Bungkus funiculus
spermaticus setelah keluar dari annulus inguinalis superficialis dari
luar ke dalam) adalah fascia spermatica externa, fascia spermatica
media, dan fascia spermatica interna.
Isi:
- a. testicularis cabang aorta abdominalis
- v. testicularis (dexter menuju vena cava inferior, sinister
menuju v. renalis sinistra)
- plexus testicularis
- vasa lymphatica
- a/v deferentialis
- ductus deferentis
2. M. obliquus internus abdominis
Origo: fascia lumbodorsalis, crista iliaca, ligamentum inguinale
Insertio: costae IX-XII, linea alba
Saraf yang menembus m. obliquus internus abdominis:
o r. cutaneus lateralis n. iliohypogastricus
o r. cutaneus lateralis n. subcostalis
o r. cutaneus anterior n. iliohypogastricus
o n. ilioinguinalis
Bangunan-bangunan:
a. Fascia spermatica media
Bungkus kedua dari funiculus spermaticus yang dibentuk lanjutan
tepi inferior m. obliquus internus abdominis
b. Falx inguinalis
Aponeurosis m. obliquus internus abdominis dan m. transversus
abdominis yang menuju crista pubica
3. M. transversus abdominis
Origo: fascia lumbodorsalis, dataran dalam costae VII-XII, crista
iliaca, ligamentum inguinale
Insertio: linea alba, tuberculum pubicum
Saraf dan pembuluh darah yang menembus m. transversus abdominis:
o Nn. intercostales 7-11
o n. subcostalis
o n. iliohypogastricus
o n. ilioinguinalis
o a. intercostalis posterior 10-11
o a. subcostalis
o a. musculophrenica
o r. ascenden a. circumflexa ilium profunda
Bangunan-bangunan:
a. Ligamentum interfoveolare
Perluasan serabut otot dan tendo m. transversus abdominis
b. Falx inguinalis
4. M. rectus abdominis
Origo: anterior symphisis pubis dan crista iliaca
Insertio: cartilagines costales V-VII dan processus xiphoideus
Musculus ini dibagi menjadi segmen-segmen yang jelas oleh 3
intersectiones tendineae, pertama terletak setinggi proc. xiphoideus,
kedua terletak setinggi umbilicus, dan satunya terletak di antara
keduanya. Musculus rectus abdominis dibungkus oleh vagina musculi
recti yang dibentuk oleh aponeurosis dari m. obliquus externus
abdominis, m. obliquus internus abdominis, dan m. transversus
abdominis.
Isi vagina musculi recti:
a. m. rectus abdominis
b. m. pyramidalis (di bagian bawah vagina musculi recti)
c. ujung terminal Nn. intercostales 6-12
d. a/v epigastrica superior
e. a/v epigastrica inferior
E. Fascia Extraperitonealis
Merupakan jaringan ikat areolair yang terletak di antara fascia yang
melapisi bagian dalam dinding cavum abdominis dengan peritoneum.
Bangunan-bangunan pada jaringan extraperitoneal adalah:
1. Organ:
- Tractus digestivus: ventriculus, intestinum, hepar, pancreas, dan
lien
- Tractus urinarius: ren, ureter, vesica urinaria, dan urethra pars
prostatica
- Tractus genitalis: ovarium, tubae uterine, uterus (pada wanita)
ductus ejaculatorius, vesicular seminalis,
glandula prostata (pada pria)
2. Vasa darah:
- Aorta abdominalis dan cabang-cabangnya
- Vena cava inferior & vena yang bermuara padanya
- Vena porta & vena yang bermuara padanya
3. Vasa lymphatica: vasa lymphatica dan lymphonodi dari viscera
abdominis
4. Saraf:
- Simpatis : Nn. splanchnici beserta ganglionnya
- Parasimpatis: n. vagus dan n. erigentes
5. Bangunan sisa foetus:
- Lig. teres hepatis sisa v. umbilicalis
- Lig. vesico umbilicale mediale sisa dari urachus (saluran
penghubung vesica urinaria dan allantois saat embrional)
- Lig. vesico umbilicale laterale sisa a. umbilicalis dextra et
sinistra
F. Peritoneum parietale
Peritoneum adalah membran serosa tipis dan licin yang melapisi bagian
dalam dinding cavum abdominis dan membungkus sebagian atau seluruh
viscera abdomen. Peritoneum dibagi menjadi 2 yaitu peritoneum parietale
(melapisi bagian dalam dinding cavum abdominis) dan peritoneum
viscerale (membungkus sebagian/seluruh organ viscera abdominis).
Berhubungan dengan fungsi peritoneum viscerale:
Hanya melapisi sebagian organ-organ yang berada di dekat dinding
cavum abdominis. Organ-organ ini disebut organ retroperitoneal.
Melapisi hamper seluruh bagian organ-organ yang letaknya mengarah
ke dalam cavum abdominis. Organ-organ ini disebut organ
intraperitoneal.
Kedua lapisan peritoneum tersebut akan membentuk suatu rongga yang
disebut cavum peritonei. Dalam keadaan normal, cavum ini hanya berisi
sedikit cairan serosa untuk membasahi permukaannya. Keadaan patologis
cavum peritonei:
- Berisi udara : pneumoperitoneum
- Berisi darah : hemoperitoneum
- Berisi exudat serous : ascites
Akibat adanya perputaran usus saat embrional, pada saat dewasa, cavum
peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang terdiri dari dua ruangan
yang saling berhubungan sehingga dikenal adanya cavum peritonei mayor
dan minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui lubang yang disebut
foramen epiploicum Winslowi. Cavum peritonei minor terletak di
belakang omentum sehingga sering disebut bursa omentalis.
Fungsi peritoneum antara lain:
1. Mengurangi/mencegah terjadinya gesekan antar bangunan viscera
abdominis
2. Pertahanan terhadap infeksi
3. Menyimpan lemak
4. Sebagai alat penggantung
5. Mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan intraperitoneal
Radang pada peritoneum: peritonitis
NEUROVASCULARISASI
1. Vascularisasi
a. Peritoneum parietale sesuai vascularisasi dinding abdomen
b. Peritoneum viscerale sesuai vascularisasi alat-alat yang
dibungkusnya
2. Innervasi
a. Peritoneum parietale cabang-cabang: n. intercostalis 7-12,
plexus lumbalis, dan n. phrenicus
b. Peritoneum viscerale serabut-serabut otonom sesuai innervasi
alat-alat yang dibungkusnya
DUPLICATOR PERITONEI
1. Alat penggantung peritonei
Merupakan duplicator peritonei yang membentang dari peritoneum
parietale ke peritoneum viscerale dari organ yang digantungnya.
Contoh:
- Colon mesocolon
- Intestinum tenue mesenterium
- Appendix vermiformis mesenteriolum
2. Omentum
Merupakan duplicator peritonei yang membentang dari
ventriculus/gaster ke organ-organ sekitarnya. Terdapat 2 macam
omenta:
a. Omentum minus terdiri dari:
- Ligamentum hepatoduodenale
- Ligamentum gastrohepaticum
b. Omentum majus
Merupakan bagian peritoneum yang dibentuk oleh duplicator
mesogastrium dorsale yang menutupi organ-organ perut di sebelah
ventral. Fungsi:
- Proteksi terhadap invasi bakteri ke peritoneum
- Tempat timbunan lemak
- Menghambat masuknya duodenum ke lumen ventriculus
- Mengisi ruangan yang terbentuk sementara
3. Ligamentum peritonei
Merupakan duplicator peritonei yang terbentuk akibat perjalanan
peritoneum yang melapisi lebih dari 1 organ viscera abdominis. Pada
saat embrional, ligamenta ini berasal dari mesogastrium ventrale dan
dorsale.
o Yang berasal dari mesogastrium ventrale:
a. Ligamentum coronaria hepatis
b. Ligamentum triangulare hepatis
c. Ligamentum falciforme hepatis
d. Omentum minus
e. Tunica serosa hepar, vesica fellea, dan pancreas
o Yang berasal dari mesogastrium dorsale:
a. Ligamentum phrenico lienale
b. Ligamentum gastro lienale
c. Mesenterium
d. Mesenteriolum
e. Mesocolon transversum
f. Mesocolon sigmoideum
g. Omentum majus
h. Tunica serosa lien
DINDING POSTERIOR ABDOMEN
Tersusun atas:
A. Kulit
Kulit pada daerah ini sangat tebal.
B. Fascia superficialis dorsi
Pada fascia ini terdapat:
1. Pembuluh darah cutan: cabang Aa. Lumbales dan vena cutanea yang
bermuara ke Vv. lumbales
2. Saraf-saraf cutan: cabang dari Rr. primarii posteriors Nn. spinales Th
7-12
3. Vasa lymphatica: ke nl. inguinalis superficialis
C. Musculus
Musculi pada dinding posterior abdomen terbagi menjadi 4 lapisan dengan
susunan luar ke dalam yaitu:
1. Lapisan pertama: M. latissimus dorsi
Origo: proc. spinosus V.Th 7-12, vertebrae lumbales et sacrales
fascia lumbodorsalis
costae X-XII
Insertio: dasar sulcus intertubercularis humeri, ventral crista tuberculi
minoris humeri
Innervasi: n. thoracodorsalis
Bangunan penting berkaitan dengan musculus ini yaitu:
a. Trigonum auscultasi batas:
Craniomedial: tepi lateral m. trapezius
Lateral : margo vertebralis scapula
Inferior : tepi atas m. latissimus dorsi
Dasar : m. rhomboideus major
b. Trigonum lumbale Petiti
2. Lapisan kedua:
a. M. obliquus externus abdominis
b. M. erector spinae
c. M. longisimus dorsi
d. M. serratus posterior inferior
Origo: lig. sacroiliaca posterior, proc. transversus V.Th 8-12, VL1-
2
Insertio: margo inferior costae 9-12
Innervasi: cabang-cabang Nn. intercostales 9-12
3. Lapisan ketiga:
a. M. multifudus
b. M. interspinales
c. M. obliquus internus abdominis
4. Lapisan keempat:
a. M. quadratus lumborum
Origo: crista iliaca, proc. transversus vertebrae lumbales bawah
Insertio: proc. transversus vertebrae lumbales atas, margo
inferomedial costa XII
Innervasi: r. muscularis n. subcostalis dan r. muscularis plexus
lumbalis (L1-4)
b. M. iliopsoas yang terdiri dari:
M. psoas major
Origo: proc. transversus vertebrae lumbales, arcus tendineus
Insertio: trochanter minor femur
Innervasi: plexus lumbalis
M. psoas minor
Origo: margo lateralis V.Th 12 dan VL1
Insertio: linea pectinea
Innervasi: plexus lumbalis
M. iliacus
Origo: fossa iliaca
Insertio: trochanter minor femur
Innervasi: n. femoralis
c. M. transversus abdominis
D. Jaringan extraperitoneal
E. Peritoneum parietale
SYSTEMA DIGESTIVA ACESSORIA
Systema digestiva acessoria terdiri dari 4 organ yaitu hepar, vesica fellea,
pancreas, dan lien.
A. HEPAR
Hepar (liver/hati) merupakan kelenjar terbesar dari tubuh manusia dengan
berat sekitar 1,5 kg pada orang dewasa. Fungsi hepar antara lain:
1. Sebagai organ hematopoiesis pada fetus
2. Berperan dalam metabolism karbohidrat, lemak, dan protein
3. Menyimpan glikogen dan mensekresi empedu (bile)
Letak: regio hypochondriaca dextra, epigastrium, dan kadang sampai regio
hypochondriaca sinistra. Diaphragma memisahkan hepar dari pleura, pulmo,
pericardium, dan cor.
BAGIAN-BAGIAN HEPAR:
1. Facies hepatis
a. Facies diaphragmatica merupakan permukaan yang halus dan
berbentuk seperti kubah karena sesuai dengan facies inferior
diaphragmatica. Facies ini dibagi 2 yaitu:
- Facies superior oleh ligamentum falciforme terbagi menjadi
facies lobi dexter dan facies lobi sinister. Pada facies ini terdapat
lekukan akibat hubungan dengan jantung yang disebut impressio
cardiaca hepatis.
- Facies posterior terdapat pars affixa hepatis / area nuda / bare
area yaitu bagian hepar yang tidak tertutup peritoneum dan
melekat langsung pada diaphragma.
b. Facies visceralis ditutupi oleh peritoneum, kecuali pada fossa
vesica fellea dan porta hepatis. Facies ini berbatasan dengan pars
abdominalis oesophagus, gaster, duodenum, flexura coli dextra, ren
dextra dan glandula suprarenalis dextra, serta vesica fellea.
Pada facies visceralis dijumpai:
- Fossa sagitalis dextra
Merupakan fossa yang tidak berbatas nyata yang membatasi lobus
hepatis dexter dengan lobus caudatus dan lobus quadratus. Pada
fossa ini terdapat fossa vesica fellea dan sulcus vena cava inferior
(dilewati vena cava inferior).
- Fossa sagitalis sinistra
Merupakan celah yang membatasi lobus hepatis dexter et sinister.
Padanya terdapat fissura sagitalis sinistra, yang terdiri dari:
1) Fissura ligamenti teretis hepatis dilalui oleh ligamentum
teres hepatis (obliterasi dari vena umbilicalis yang bermuara ke
vena portae hepatis).
2) Fissura ligamenti venosi Arantii dilalui oleh ligamentum
venosum Arantii (obliterasi dari ductus venosus Arantii yang
menghubungkan vena umbilicalis dan vena cava inferior).
- Portae hepatis (fissura transversa)
Memisahkan lobus quadratus dan lobus caudatus. Portae hepatis
dilalui oleh: ductus hepaticus dexter et sinister, ramus dexter et
sinister arteria hepatica, vena portae hepatis, plexus hepaticus, dan
nodi lymphatici hepatici. Bangunan-bangunan yang melalui porta
hepatis tersebut, di luar akan berjalan dalam ligamentum
hepatoduodenale (antara portae hepatis dan duodenum).
- Facies lobi quadrati
- Facies lobi caudati
2. Margines hepatis
a. Margo anterior
Margo ini tajam dan terdapat incisura umbilicalis (tempat
menyeberangnya ligamentum falciforme hepatis).
b. Margo inferior (postero inferior)
Memisahkan facies diaphragmatica (posterior) dan facies visceralis.
Pada tepi ujung kiri terdapat ligamentum triangulare sinister dan
appendix fibrosa hepatis*. Pada tepi ujung kanan terdapat ligamentum
triangulare dexter.
*appendix fibrosa hepatis adalah sisi lobus hepatis sinister yang berisi
fossa abberantia, sisa ductus biliverus yang atrofi. Jika jaringan ini
persisten maka akan membentuk beavertail liver.
c. Margo postero superior
Memisahkan facies posterior dengan facies superior anterior facies
diaphragmatica. Margo ini tidak jelas dan tumpul.
3. Lobi hepatis
a. Lobus Hepatis Dexter
Merupakan lobus terbesar yang terletak di regio hypochondriaca
dextra dan dipisahkan dari lobus sinister oleh:
- Ligamentum falciforme hepatis (pada facies diaphragmatica)
- Fossa sagitalis sinistra (pada facies visceralis)
Pada facies visceralis terdapat fossa vesica fellea, portae hepatis, dan
sulcus vena cava. Selain itu juga terdapat beberapa pendesakan organ
lain (impressiones) yaitu:
- Impressio colica : ditempati flexura colica dextra
- Impressio renalis : ditempati ren dexter
- Impressio suprarenalis : ditempati glandula suprarenalis dextra
- Impressio duodenalis : ditempati pars descendens duodenum
b. Lobus Quadratus, terletak di antara fossa vesicae felleae dan fissura
ligamenti teres hepatis. Secara fungsional, lobus ini berhubungan
dengan lobus hepatis sinister. Lobus ini berbentuk empat persegi
dengan batas-batasnya:
- Ventral : margo inferior hepar
- Dorsal : portae hepatis
- Dexter : fossa vesica fellea
- Sinister : fissura ligamenti teretis hepatis
c. Lobus Caudatus
Lobus ini setinggi vertebra thoracalis X-XI dan memiliki 2 penonjolan
yaitu processus papilaris dan processus caudatus (memisahkan portae
hepatis dengan vena cava inferior, menghubungkan lobus caudatus
dan lobus hepatis dexter). Batas-batas:
- Inferior : vena portae hepatis
- Dexter : sulcus vena cava
- Sisnister : fissura ligamenti venosi
d. Lobus Hepatis Sinister
Terletak di regio epigastrica dan hypochondriaca sinstra. Pada lobus
ini ada 2 bangunan penting yaitu:
- Impressio gastrica : akibat desakan facies ventralis gaster
- Impressio oesophagea
- Tuber omentale : penonjolan di bagian dexter, di depan
omentum minus, bersentuhan dengan curvatura ventriculi minor.
STRUKTUR HEPAR
Secara umum, hepar tersusun oleh:
1. Lobuli hepar
Lobuli hepar dipisahkan satu sama lain oleh jaringan fibrosa yang
dinamakan septum interlobularis. Terdapat bangunan intralobular yang
merupakan lanjutan dari bangunan interlobular pada canalis portae antara
lain:
- Vena centralis pada masing-masing lobulus bermuara ke venae
hepaticae
- Sinusoid membawa darah ke vena centralis
- Arteri intralobularis cabang a. interlobularis
- Canaliculi billiveri mencurahkan bilus ke ductus biliverus
Lig. hepatoduodenale
INTRAHEPATALCanaliculi biliveri ductus biliverus ductus hepaticus dexter et sinister
Vesica fellea
Ductus choledochus
Ductus pancreaticus Wirsungi
Papilla duodeni mayor
- Spatium (perivascularisasi) Disse mencurahkan lymphe ke vasa
lymphatica interlobularis
2. Trigonum portae (canalis portae)
Bangunan interlobulair yang terdapat pada setiap sudut dari lobulus hepar.
Bangunan yang mengisinya:
- Arteri interlobularis dari a. hepatis dextra et sinistra
- Vena Interlobularis bermuara ke vena portae
- Ductus biliverus mencurahkan bilus ke ductus hepaticus
- Vasa lymphatic
SALURAN EMPEDU
Empedu disekresi oleh sel-sel hepar dan akan disimpan serta dipekatkan di
vesica fellea. Empedu akan disekresikan ke duodenum dan mengemulsikan
lemak yang masuk duodenum. Ductus biliaris hepatis terdiri dari: ductus
hepaticus dexter et sinister, ductus hepaticus communis, ductus choledochus,
vesica fellea, dan ductus cysticus
Ductus hepaticus communis Ductus
cysticus
NEUROVASCULARISASI
1. Vascularisasi
a. Arteriosa
V. cava inferior
V. hepatica
V. sublobularisV. centralis( di tengah2 lobulus)
Sinusoid (intra lobularis)
V. Interlobularis
Masuk porta hepatis
V. portae hepatis
Systema portae hepatis
Truncus coeliacus a. hepatica communis a. hepatica propria a.
hepatica dextra et sinistra (masuk porta hepatis) a. interlobaris
(dalam canalis portae) a. intralobaris (dalam lobulus hepar)
b. Venosa
Vena portae hepatis
Vena ini mengalirkan darah dari sebagian tractus gastrointestinalis
mulai dari sepertiga bagian bawah oesophagus sampai setengah bagian
atas canalis analis. Vena portae hepatis juga mengalirkan darah dari
lien, pancreas, dan vesica fellea. Vena-vena yang bermuara ke vena
portae hepatis: v. lienalis, v. mesenterica superior, v. gastrica sinistra,
v. gastrica dextra, v. cystica.
Anastomosis Portal Sistemik
Selain rute venosa (hubungan langsung) di atas, terdapat hubungan
yang lebih kecil di antara sistem portal dan sistem sistemik. Hubungan
ini menjadi penting bila rute venosa terhambat. Hubungan-hubungan
tersebut antara lain:
- Pada sepertiga bawah oesophagus, rami oesophagei sinistra
(cabang portal) beranastomosis dengan venae oesophageales.
- Pada pertengahan atas canalis analis, vena rectalis superior
(cabang portal) beranastomosis dengan vena rectalis media dan
vena rectalis inferior (cabang sistemik)
Cysterna chyli
Ductus thoracicus
Lnn. Gastrica sin/Lnn colica
VL. Porta Hepatis
Limphonodi hepatici
Spatium disse Vasa lymphaticainterlobularis
Lnn. Mediastinum posterior
Lnn. Di sekitar V. cava inferior
Lnn. phrenici
Vv. Hepatici
- Venae paraumbilicales menghubungkan r. Sinister venae portae
hepatis dengan venae superficialis dinding anterior abdomen
(cabang sistemik)
- Vena-vena colon ascendens, colon descendens, duodenum,
pancreas, dan hepar (cabang portal) beranastomosis dengan vena
renalis, vena lumbalis, dan vena phrenicae (cabang sistemik)
2. Innervasi
Plexus hepaticus cabang plexus coeliacus mengandung serabut saraf:
- Preganglioner parasimpatis n. Vagus
- Simpatis preganglioner: n. splanchinus mayor; postganglioner: Ggl.
Coeliacum
SYSTEMA LYMPHATICA
PATOLOGI
1. Hepatomegali
Hepar
Merupakan pembesaran hepar yang dapat diukur dengan satuan pengukuran
BLANKHART.
a = garis vertikal ditarik dari proc. Xyphoideus ke umbilicus
b = garis diagonal dari arcus costa di linea midclavicularis ke umbilicus
a = b = 1 blankhart, bila ada pembesaran (a, b)
2. Cirrhosis hepatis
Pada penyakit ini, terjadi destruksi sel parenkim hepar dan digantikan
oleh jaringan fibrosa. Penyebabnya antara lain hepatitis dan chronic
alcohol abuse.
3. Hipertensi portal
Merupakan peningkatan tekanan vena porta akibat resistensi / tahanan
dari aliran di vena porta. Keadaan klinis ini menyebabkan pembebanan
berlebih pada sistem portal. Tekanan normal sekitar 6-10 mmHg.
B. VESICA FELLEA
Vesica fellea (gallbladder/kandung empedu) adalah kantong berbentuk buah
pir yang terletak di facies visceralis hepar di antara lobus dexter hepatis dan
lobus quadratus hepar. Panjangnya sekitar 7-10 cm dan dapat menampung
empedu 30-50 mL. vesica fellea berfungsi menyimpan empedu dan
memekatkan empedu dengan cara menyerap cairan. Pengeluaran empedu
dikontrol oleh kolesistokinin yang dihasilkan oleh tunica mucosa duodenum.
BAGIAN-BAGIAN
1. Fundus : berbentuk bulat dan menonjol di bawah
margo inferior hepar. Proyeksi fundus ke dinding
anterior abdomen adalah setinggi ujung cartilago
costae IX dextra.
2. Corpus : berhubungan dengan facies visceralis hepar
dan arahnya ke atas, belakang, dan kiri.
3. Infundibulum
4. Collum : bagian yang sempit dan melanjutkan diri sebagai ductus cysticus,
yang berbelok ke dalam omentum minus dan bergabung dengan ductus
hepaticus communis membentuk ductus choledochus. Infundibulum dan
collum kadangkala membentuk ampulla.
SALURAN KELUAR
Saluran vesica fellea disebut ductus cysticus yang terdiri dari:
a. Pars valvularis tunica mucosa membentuk lipatan-lipatan yang berjalan
spiral yang disebut valvula spiralis Heisteri, berfungsi untuk
mempertahankan lumen terbuka agar aliran empedu tidak terganggu.
b. Pars glebra mempunyai tunica mucosa yang licin
Pars glebra ductus systicus bergabung dengan ductus hepaticus communis
menjadi ductus choledochus. Ductus choledochus berjalan dalam
ligamentum hepatoduodenale dan bersama dengan ductus pancreaticus
Wirsungi akan bermuara pada papilla duodeni major.
Pada muara tersebut terdapat musculus sphincter Oddi yang berfungsi
mengatur pemasukan empedu dan enzim pancreas ke duodenum.
M. sphinter Oddi dibentuk oleh:
- M. sphincter ductus choledoci tunica muscularis muara ductus
choledochus
- M. sphincter ductus pancreatici tunisa muscularis muara ductus
pancreaticus
- M. sphincter ampullae tunica muscularis ampulla vateri
NEUROVASCULARISASI
1. Vascularisasi
a. cystica cabang a. hepatica dextra
v. cystica, bermuara ke vena portae hepatis
2. Innervasi
Plexus cysticus, cabang dari plexus hepaticus yang mengandung serabut
simpatis maupun parasimpatis (nervus vagus).
SYSTEMA LYMPHATICA
Pembuluh lymphe vesica fellea nl. cysticus nl. hepatici dan nl. gastrica
sinistra
PATOLOGI
1. Cholesistitis: radang vesica fellea
2. Cholelithiasis: batu empedu
3. Cholangitis: radang ductus cysticus
C. PANCREAS
Pancreas merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin adalah
menghasilkan enzim yang terlibat dalam pencernaan seperti tripsinogen
(memecah protein), amilase (memecah karbohidrat), dan lipase (memecah
lemak). Bagian endokrin kelenjar adalah pulau Langerhans yang berfungsi
memproduksi hormon insulin dan glukagon.
Letak: regio epigastrica dan hypochondriaca sinistra, memanjang seperti
pistol dan membentang dari lengkung duodenum hingga lien menyilang
transversal dinding posterior abdomen.
BAGIAN-BAGIAN
Retroperitoneal caput, collum, corpus
Intraperitoneal cauda
a. Caput pancreatis
Terletak pada lengkung duodenum. Pada bagian ini terdapat:
1. Processus uncinatus (Pancreas Winslowi) penonjolan di sebelah
caudal dan sinistra di belakang a/v mesenterica superior
2. Incisura pancreatis alur untuk lewatnya a/v mesenterica superior
- Facies anterior bersentuhan dengan mesocolon transversum
- Facies posterior bersentuhan dengan vena cava inferior, ductus
choledochus, v. renalis, crus dexter phren, dan aorta
b. Collum pancreatis
- Merupakan bagian pancreas yang mengecil dan menghubungkan caput
dan corpus pancreatis
- Terletak di depan pangkal vena portae hepatis dan tempat
dipercabangkannya a. mesenterica superior dari aorta
c. Corpus pancreatis
Pada perbatasan dengan collum pancreatis terdapat penonjolan yang
disebut tuber omentale. Sebelah posterior corpus terdapat ren sinister dan
glandula suprarenalis sinister.
d. Cauda pancreatis
Terletak dalam ligamentum phrenicolienale dan mengadakan hubungan
dengan hilum lienalis, bersentuhan dengan flexura coli sinistra.
STRUKTUR
Sebagai kelenjar endokrin, massa kelenjarnya disebut sel-sel pulau
Langerhans yang tersebar dalam massa pancreas. Sebagai kelenjar eksokrin
terdiri atas acinus-acinus (acini). Acini terdiri atas sejumlah slauran-saluran
kelenjar yaitu: ductus intercalatus ductus intralobularis ductus
pancreaticus
Ductus pancreaticus terbagi menjadi:
1. Ductus pancreaticus Wirsungi mulai dari cauda pancreatis dan berjalan
di sepanjang kelenjar. Ductus ini akan beranastomose dengan ductus
choledocus membentuk ampulla hepatopancreatica Vateri yang bermuara
ke papilla duodeni major.
Nucleus dorsalis N. X Pancreas
N. Vagus
(serabut pre ganglioner)
Gglterminale
Ganglion coeliacum
n. Splanchnicus major
(Pre ggl) (post ggl)NILCLMS Segmen Th V- IX
Pancreas
2. Ductus pancreaticus Accessorius (Santorini), mengalirkan getah pancreas
dari bagian atas caput dan kemudian bermuara ke papilla duodeni minor
yang terletak di atas papilla duodeni major.
NEUROVASCULARISASI
1. Vascularisasi
Arteriosa
- a. pancreaticoduodenalis superior cab. a. gastroduodenalis
- a. pancreaticoduodenalis inferior cab. a. mesenterica superior
- Rr. Pancreatici a. lienalis
Venosa
- Sesuai dengan arterinya, mengalirkan darah venosa ke sistem portae
2. Innervasi
a. Parasimpatis
b. Simpatis
SYSTEMA
LYMPHATICA
Pembuluh lymphe dari pancreas nl. pancreaticoduodenalis nl.
mesentericus superior dan nl. coeliacus
PATOLOGI
1. Pancreatitis
Merupakan radang pada pancreas yang dapat disebabkanbatu empedu
menyumbat ampulla Vateri dan menyebabkan refluks empedu ke ductus
pancreaticus.
2. Ruptur pancreas
Menyebabkan robekan pada ductus sehingga getah pancreas masuk ke
dalam kelenjar dan mencerna kelenjar itu sendiri sehingga timbul nyeri
hebat.
D. LIEN
Lien (spleen/limpa) merupakan organ limfoid terbesar dalam tubuh manusia.
Lien tberbentuk ovoid dan terletak di regio hypochondriaca sinistra setinggi
costae IX-XI sinistra, posterior terhadap gaster/lambung, dan anterior
terhadap bagian atas ren sinister. Fungsi lien yaitu organ hematopoiesis pada
fetus, membuat limfosit, destruksi eritrosit yang sudah tua, dan reservoir
darah.
BAGIAN-BAGIAN
1. Facies facies diaphragmatica, facies visceralis (facies gastrica, facies
renalis, dan facies colica yang ditempati flexura coli sinistra)
2. Margines margo superior et inferior
3. Extremitas extremitas anterior et posterior
Hilus lienalis (tempat masuk keluarnya pembuluh darah dan saraf) dilalui
oleh: a/v lienalis, plexus nervosus, plexus lymphaticus, dan cauda pancreatis.
Bagian hilus tidak ditutupi oleh peritoneum.
Lien merupakan organ intraperitoneal, terhubung dengan:
- Curvatura mayor gaster oleh ligamentum gastrolienale
- Ren sinistra oleh ligamentum lienorenale
Kedua ligamentum ini merupakan bagian dari omentum majus.
NEUROVASCULARISASI
1. Vascularisasi
Arteriosa
Truncus coeliacus a. lienalis r. lienalis (masuk hilus) a. centralis
a. penicilus kapiler
Venosa
v. lienalis (keluar dari hilum lienalis) bersatu dengan v. mesenterica
superior bermuara v. portae hepatis
2. Innervasi
a. Simpatis
SBN I = Afferens ganglion spinale
Efferens NILCLMS segmen thoracalis V – IX
Saraf preganglioner = n. Splanchnicus major
SBN II= ganglion coeliacum
b. Parasimpatis
SBN I = Afferens ganglion nodusum
Efferens nucleus dorsalis Nn. Vagi
SBN II= Efferens ganglion terminale
SYSTEMA LYMPHATICA
Pembuluh lymphe keluar hilus lienalis kelenjar lymphe sepanjang a.
lienalis nl. pancreaticolienalis
PATOLOGI
Splenomegali (pembesaran lien) satuan ukuran:
SCHUFFNER, diukur dengan cara:
1. Tarik garis singgung a dengan arcus costarum sinistra
2. Dari umbilicus, tarik garis b yang tegak lurus garis a,
lalu bagi menjadi 4 bagian
3. Garis b diteruskan ke bawah sampai SIAS sinistra, lalu
dibagi menjadi 4 bagian
Tumor abdomen adalah suatu massa yang padat dengan ketebalan yang
berbeda-beda, yang disebabkan oleh sel tubuh yang yang mengalami transformasi
dan tumbuh secara autonom lepas dari kendali pertumbuhan sel normal, sehingga
sel tersebut berbeda dari sel normal dalam bentuk dan strukturnya. Kelainan ini
dapat meluas ke retroperitonium, dapat terjadi obstruksi ureter atau vena kava
inferior. Massa jaringan fibrosis mengelilingi dan menentukan struktur yang
dibungkusnya tetapi tidak menginvasinya.
Yang termasuk tumor intra abdomen antara lain, Tumor hepar, Tumor
limpa / lien, Tumor lambung / usus halus, Tumor colon, Tumor ginjal
(hipernefroma), Tumor pankreas. Pada anak-anak dapat terjadi Tumor wilms
(ginjal). Yang akan dibahaskan di sini adalah yang terutama tumor di saluran
cerna intestinal.
ETIOLOGI TUMOR INTRAABDOMEN
Penyebab neoplasi umumnya bersifat multifaktorial. Beberapa faktor yang
dianggap sebagai penyebab neoplasi antara lain meliputi bahan kimiawi, fisik,
virus, parasit, inflamasi kronik, genetik, hormon, gaya hidup, serta penurunan
imunitaws. Penyebab terjadinya tumor karena terjadinya pembelahan sel yang
abnormal. Perbedaan sifat sel tumor tergantung dari besarnya penyimpangan
dalam bentuk dan fungsi autonominya dalam pertumbuhan, kemampuannya
mengadakan infiltrasi dan menyebabkan metastasis.
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tumor
antara lain:
1. Karsinogen
a. Kimiawi
Bahan kimia dapat berpengrauh langsung (karsinogen) atau memerlukan
aktivasi terlebih dahulu (ko-karsinogen) untuk menimbulkan neoplasi. Bahan
kimia ini dapat merupakan bahan alami atau bahan sintetik/semisintetik.
Benzopire suatu pencemar lingkungan yang terdapat di mana saja, berasal
dari pembakaran tak sempurna pada mesin mobil dan atau mesin lain (jelaga
dan ter) dan terkenal sebagai suatu karsinogen bagi hewan maupun manusia.
Berbagai karsinogen lain antara lain nikel arsen, aflatoksin, vinilklorida.
Salah satu jenis benzo (a) piren, yakni, hidrokarbon aromatik polisiklik
(PAH), yang banyak ditemukan di dalam makanana yang dibakar
menggunakan arang menimbulkan kerusakan DNA sehingga menyebabkan
neoplasia usus, payudara atau prostat.
b. Fisik
Radiasi gelombang radioaktif seirng menyebabkan keganasan. Sumber
radiasi lain adalah pajanan ultraviolet yang diperkirakan bertambah besar
dengan hilangnya lapisan ozon pada muka bumi bagian selatan. Iritasi kronis
pada mukosa yang disebabkan oleh bahan korosif atau penyakit tertentu juga
bisa menyebabkan terjadinya neoplasia.
c. Viral
Dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenis asam ribonukleatnya; virus DNA
serta RNA. Virus DNA yang sering dihubungkan dengan kanker antara
human papiloma virus (HPV), Epstein-Barr virus (EPV), hepatiti B virus
(HBV), dan hepatitis C virus (HCV). Virus RNA yang karsonogenik adalah
human T-cell leukemia virus I (HTLV-I) .
2. Hormon
Hormon dapat merupakan promoter kegananasan.
3. Faktor gaya hidup
Kelebihan nutrisi khususnya lemak dan kebiasaan makan- makanan yang
kurang berserat. Asupan kalori berlebihan, terutama yang berasal dari lemak
binatang, dan kebiasaan makan makanan kurang serat meningkatkan risiko
berbagai keganasan, seperti karsinoma payudara dan karsinoma kolon.
4. Parasit
Parasit schistosoma hematobin yang mengakibatkan karsinoma planoseluler.
5. Genetik, infeksi, trauma, hipersensivitas terhadap obat.
A. KLASIFIKASI
Dewasa :
- Tumor hepar
- Tumor limpa / lien
- Tumor lambung / usus halus
- Tumor colon
- Tumor ginjal (hipernefroma)
- Tumor pankreas
Anak-anak :
- Tumor wilms (ginjal)
B. GEJALA KLINIS
Kanker dini sering kali tidak memberikan keluhan spesifik atau menunjukan
tanda selama beberapa tahun. Umumnya penderita merasa sehat, tidak nyeri dan
tidak terganggu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Pemeriksaan darah atau
pemeriksaan penunjang umumnya juga tidak menunjukkan kelainan.
Oleh karena itu, American Cancer Society telah mengeluarkan peringatan
tentang tanda dan gejala yang mungkin disebabkan kanker. Tanda ini disebut “7-
danfer warning signals CAUTION”. Yayasan Kanker Indonesia menggunakan
akronim WASPADA sebagai tanda bahaya keganasan yang perlu dicuraigai.
C = Change in bowel or bladder habit
A = a sore that does not heal
U = unusual bleding or discharge
T = thickening in breast or elsewhere
I = indigestion or difficult
Tumor abdomen merupakan salah satu tumor yang sangat sulit untuk
dideteksi. Berbeda dengan jenis tumor lainnya yang mudah diraba ketika
mulai mendesak jaringan di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena sifat
rongga tumor abdomen yang longgar dan sangat fleksibel. Tumor abdomen
bila telah terdeteksi harus mendapat penanganan khusus. Bahkan, bila perlu
dilakukan pemantauan disertai dukungan pemeriksaan secara intensif. Bila
demikian, pengangkatan dapat dilakukan sedini mungkin.
Biasanya adanya tumor dalam abdomen dapat diketahui setelah perut
tampak membuncit dan mengeras. Jika positif, harus dilakukan pemeriksaan
fisik dengan hati-hati dan lembut untuk menghindari trauma berlebihan yang
dapat mempermudah terjadinya tumor pecah ataupun metastasis. Dengan
demikian mudah ditentukan pula apakah letak tumornya intraperitoneal atau
retroperitoneal. Tumor yang terlalu besar sulit menentukan letak tumor
secara pasti. Demikian pula bila tumor yang berasal dari rongga pelvis yang
telah mendesak ke rongga abdomen.
Berbagai pemeriksaan penunjang perlu pula dilakukan, seperti
pemeriksaan darah tepi, laju endap darah untuk menentukan tumor ganas atau
tidak. Kemudian mengecek apakah tumor telah mengganggu sistem
hematopoiesis, seperti pendarahan intra tumor atau metastasis ke sumsum
tulang dan melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan lainnya.
Tanda dan Gejala :
- Hiperplasia.
- Konsistensi tumor umumnya padat atau keras.
- Tumor epitel biasanya mengandung sedikit jaringan ikat, dan apabila tumor
berasal dari masenkim yang banyak mengandung jaringan ikat elastis kenyal
atau lunak.
- Kadang tampak Hipervaskulari di sekitar tumor.
- Bisa terjadi pengerutan dan mengalami retraksi.
- Edema sekitar tumor disebabkan infiltrasi ke pembuluh limfa.
- Konstipasi.
- Nyeri.
- Anoreksia, mual, lesu.
- Penurunan berat badan.
- Pendarahan.
.
C. PEMERIKSAAN KLINIS
Pemeriksaan klinik di sini adalah pemeriksaan rutin yang biasa
dilakukan dengan cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, yaitu:
- Inspeksi
- Palpasi
- Perkusi
- Auskultasi
Pemeriksaan ini sangat penting, karena dari hasil pemeriksaan klinik yang
dilakukan secara teliti, menyeluruh, dan sebaik-baiknya dapat ditegakkan
diagnosis klinik yang baik pula. Pemeriksaan klinik yang dilakukan harus secara
holistik, meliputi bio-psiko-sosio-kulturo-spiritual.
Anamnesis seorang pasien, dapat bermacam-macam mulai dari tidak ada
keluhan sampai banyak sekali keluhan, bisa ringan sampai dengan berat. Semakin
lanjut stadium tumor, maka akan semakin banyak timbul keluhan gejala akibat
tumor ganas itu sendiri atau akibat penyulit yang ditimbulkannya.
Apabila ditemukan tumor ganas di dalam atau di permukaan tubuh yang
jumlahnya banyak (multiple), maka perlu ditanyakan tumor mana yang timbul
lebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memperkirakan asal dari tumor tersebut.
Pemeriksaan fisik ini sangat penting sebagai data dasar keadaan umum pasien dan
keadaan awal tumor ganas tersebut saat didiagnosa. Selain pemeriksaan umum,
pemeriksaan khusus terhadap tumor ganas tersebut perlu dideskripsikan secara
teliti dan rinci. Untuk tumor ganas yang letaknya berada di atau dekat dengan
permukaan tubuh, jika perlu dapat digambar topografinya pada organ tubuh
supaya mudah mendeskripsikannya. Selain itu juga perlu dicatat :
1. Ukuran tumor ganas, dalam 2 atau 3 dimensi,
2. Konsistensinya
3. Ada perlekatan atau tidak dengan organ di bawahnya atau kulit di
atasnya.
D. PEMERIKSAAN RADIOLOGI
Endoskopi (sebuah penelitian dimana sebuah pipa elastis digunakan
untuk melihat bagian dalam pada saluran pencernaan) adalah prosedur
diagnosa terbaik. Hal yang memudahkan seorang dokter untuk melihat
langsung dalam perut, untuk memeriksa helicobacter pylori, dan untuk
mengambil contoh jaringan untuk diteliti di bawah sebuah mikroskop
(biopsi). Sinar X barium jarang digunakan karena hal tersebut jarang
mengungkapkan kanker tahap awal dan tidak dianjurkan untuk biopsi. Jika
kanker ditemukan, orang biasanya menggunakan computer tomography (CT)
scan pada dada dan perut untuk memastikan penyebarannya yang mana
tumor tersebut telah menyebar ke organ-organ lainnya. Jika CT scan tidak
bisa menunjukkan penyebaran tumor. Dokter biasanya melakukan endoskopi
ultrasonic (yang memperlihatkan lapisan saluran pencernaan lebih jelas
karena pemeriksaan diletakkan pada ujung endoskopi) untuk memastikan
kedalaman tumor tersebut dan pengaruh pada sekitar getah bening.
Pemeriksaan imaging yang diperlukan untuk membantu menegakkan
diagnosis tumor ganas (radiodiagnosis) banyak jenisnya mulai dari yang
konvensional sampai dengan yang canggih, dan untuk efisiensi harus dipilih
sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pada tumor ganas yang letaknya
profunda dari bagian tubuh atau organ, pemeriksaan imaging diperlukan
untuk tuntunan (guiding) pengambilan sample patologi anatomi, baik itu
dengan cara fine needle aspiration biopsi (FNAB) atau biopsy lainnya. Selain
untuk membantu menegakkan diagnosis, pemeriksaan imaging juga berperan
dalam menentukan staging dari tumor ganas. Beberapa pemeriksaan imaging
tersebut antara lain:
- Radiografi polos atau radiografi tanpa kontras, contoh: X-foto tengkorak,
leher, toraks, abdomen, tulang, mammografi, dll.
- Radiografi dengan kontras, contoh: Foto Upper Gr, bronkografi, Colon in
loop, kistografi, dll.
- USG (Ultrasonografi), yaitu pemeriksaan dengan menggunakan gelombang
suara. Contoh: USG abdomen, USG urologi, mammosografi, dll.
- CT-scan (Computerized Tomography Scanning), contoh: Scan kepala,
thoraks, abdomen, whole body scan, dll.
- MRI (Magnetic Resonance Imaging). Merupakan alat scanning yang masih
tergolong baru dan pada umumnya hanya berada di rumah sakit besar.
Hasilnya dikatakan lebih baik dari CT.
- Scinfigrafi atau sidikan Radioisotop. Alat ini merupakan salah satu alat
scanning dengan menggunakan isotop radioaktif, seperti: Iodium,
Technetium, dll. Contoh: scinfigrafitiroid, tulang, otak, dll.
- RIA (Radio Immuno Assay), untuk mengetahui petanda tumor (tumor
marker).
E. GAMBARAN RADIOLOGI
1. Tumor Hepar
Ada 2 macam gambaran hepatoma yaitu bentuk nodular yang gambaran
nodul tumor jelas misalnya tumor yang tidak berbatas rata, atau bentuk
difuse. Hepatoma bentuk difuse ditandai dengan edchopattern yang sangat
kasat dan mengelompok dengan batas tidak teratur dan bagian sentralnya
lebih ecvhogenik. Pembuluh darah disekitarnya sering distorted. Seringkali
para ultrasonografer yang tidak berpengalaman membuat diagnosa sirosis
padahal diagnosa yang betul adalah sirosis dan hepatoma diffuse. Gambaran
hepatoma diffuse harus dibedakan dari gambaran focal fatty liver dimana ada
gambaran echopattern yang kasar tetapi fokal.
Gambar 2.1 - Hepatoma Difuse dan Hepatoma Noduler
Hepatoma yang berukuran 3 cm atau kurang disebut : Hepatoma dini
(early). Bila ukuran lebih dari 3 cm disebut : Hepatoma lanjut (advanced).
Hepatoma dini sering kali bersifat hypoechoic sedang hepatoma lanjut
biasanya hyperechoic atau multiple echo yang menunjukkan nekrosis atau
fibrosis dalam tumor. Kadang – kadang hepatoma dini berbentuk seperti mata
sapi (bull’s eye).
Gambar 2.2 - Gambaran USG Hepatoma Lanjut berupa hyperechoic
2. Tumor Limpa
Pada tumor primer pada limpa ditemukan gambaran bulging atau
penggelembungan tepi limpa dengan struktur eko parenkim yang tidak
homogen.
Gambar 2.3 - Spiral CT scan dipotong 7 mm, dengan limpa sangat membesar
(di sebelah kanan pemirsa), menunjukkan massa tumor kurang radiodense
dengan limpa agak padat normal berdekatan.
3. Tumor Lambung atau Usus halus
Bila ada tumor lambung, maka dengan sendirinya kontras tidak dapat
mengisinya, sehingga pada pengisian lambung, tempat tersebut merupakan
tempat yang luput dari pengisian kontras (luput isi atau filling defect).
Stadium Awal Kanker Lambung
Lesi-lesi yang Nampak di mukosa dan submukosa diklasifikasikan
menjadi 3 tipe:
a. Lesi tipe I yaitu adanya elevasi dan penonjolan keluar lumen lebih dari 5 mm.
b. Lesi tipe II yaitu adanya lesi superficial yang adanya elevasi (IIa), datar (IIb),
atau tertekan (IIc).
c. Lesi tipe III stadium kanker awal adalah gambaran dangkal, ulkus ireguler
dikelilingi nodul-nodul, kumpulan lipatan-lipatan mukosa.
Kanker Lambung Stadium Lanjut
Kanker lambung kadang-kadang Nampak dalam foto polos abdomen
sebagai gambaran abnormalitas pada kontur gaster atau adanya gambaran
massa soft tissue yang masuk ke dalam kontur gaster. Jarang ditemukan
musin yang diproduksi kanker yang akan memberikan gambaran area
kalsifikasi. Pada studi barium, karsinoma gaster tampak gambaran polypoid,
ulcerative atau lesi infiltrate.
Gambar 2.4 - Polypoid Carcinoma lambung. Radiografi dengan
kontras Foto Upper GI menunjukkan kelainan yang mengisi lobulated
(panah) di antrum lambung.
Gambar 2.5 - Tumor jinak stroma gastrointestinal dalam Duodenum
4. Tumor K olon
- Adanya penonjolan ke dalam lumen berupa polip bertangkai (pedunculated)
atau tak bertangkai (sesile).
- Terjadi kerancuan dinding kolon bersifat simetris (napskin ring) atau asimetris
(apple core).
- Kekakuan dinding colon bersifat segmental (lumen colon dapat atau tidak
menyempit)
Gambar 2.6 – Pedunculated polip pada kolon descenden
Gambar 2.7 - Gambaran “apple core” pada colon sigmoid
Gambar 2.8 – Kanker caecum. Massa polipoid mendesak lipatan iliocaecal
sehingga menyebabkan obstruksi.
Gambar 2.9 - Polypoid carcinoma. Massa berlobus besar di rectosigmoid
junction.
5. Tumor Ginjal
- pemeriksaan dengan IVP terlihat gambaran sistem kalixes yang tidak teratur
(tumor willms).
- bayangan masa dapat tidak homogen, tidak ada kalsifikasi, mengandung
banyak jaringan lunak (hipernefroma).
- massa di daerah ginjal, batas tidak jelas, menutupi bayangan musculus psoas
bagian atas (sarcoma ginjal).
Gambar 2.10 - CT scan bayi dengan massa ginjal yang besar (panah).
Jaringan ginjal normal adalah ditunjukkan di sebelah kanan tumor Wilms
(panah kepala, struktur berwarna putih).
6. Tumor U reter
Terdapat gambaran filling defect pada daerah yang terdapat polip dengan
atau tanpa dilatasi proksimalnya.
Gambar 2.11 Gambaran filling defect (panah) di ureter adalah karakteristik
dari polip fibroepithelial.
7. Tumor B uli-buli
Penampakan carsinoma vesika urinaria dapat berupa defek pengisian
pada vesika urinaria yang terisi kontras atau pola mukosa yang tidak teratur
pada film kandung kemih pascamiksi. Jika urogram intravena menunjukkan
adanya obstruksi ureter, hal tersebut lebih menekankan pada keterlibatan otot
– otot di dekat orifisium ureter dibandingkan obstruksi akibat massa
neoplasma yang menekan ureter. CT atau MRI bermanfaat dalam penilaian
praoperatif terhadap penyebab intramural dan ekstramural, invasi lokal,
pembesaran kelenjar limfe, dan deposit sekunder pada hati atau paru.
Gambar 2.12 - Transisi Cell Carcinoma. Radiografi dari urogram ekskretoris
menunjukkan massa lobulated (panah) yang menyebabkan kelainan di dasar
kandung kemih
.
8. Tumor P ankreas
CT Scan dari multisection aksial pada pasien dengan kanker pankreas
menunjukkan penipisan massa rendah di kepala pankreas, berdekatan dengan
vena mesenterika superior.
Gambar 2.13 – CT Scan Tumor Pankreas (kiri)
Gambar 2.14 - Endoskopi Tumor pancreas (kanan)
NEOPLASMA DI USUS HALUS
Neoplasma usus kecil primer sangat jarang. Kolon terkena 40 kali lebih besar
dari usus kecil. Gejala sering kali tidak jelas; nyeri epigastrik, mual, muntah,
kolik, diare, perdarahan (biasanya samar). Alasan yang paling sering untuk
operasi adalah obstruksi, perdarahan dan nyeri. Tumor jinaj menyebabkan
intususepsi pada orang dewasa; tumor ganas secara langsung mengobstruksi atau
membengkokkan usus. Diagnosis sulit untuk ditentukan, endoskopi bermanfaat
untuk deodenum, sisa usus membutuhkan enteroklisis (intubasi usus kecil dengan
radigraf barium).
Neoplasma usus kecil sangat jarang meskipun panjang usus kecil adalah 80%
dari panjang saluran gastrointestinal. Hanya 5% dari neoplasma dan 1% dari
keganasan di saluran gastrointestinal terkena usus kecil.
Neoplasma jinak
Berasal dari epitel atau jaringan penyambung. Paling sering adenoma,
leiomioma atau lipoma. Sering tidak menimbulkan gejala, kecuali
menyebabkan obstruksi melalu intususepsi, juga dapat berdarah (sepertiga
perdarahan samar). Pembedahan diindikasikan jika diagnosis dibuat atau
diduga. Yang paling sering digunakan adalah reseksi segmental sederhana.
Adenoma
Adenoma mengisi kira-kira 15% dari semua tumor jinak usus halus dan
mempunya tiga tipe yang utama; Adenoma sejati, adenoma villosa atau
adenoma kelenjar brunner (proliferasi glandular deodenum hiperplastik
tanpa potensi keganasan); 20% dalam deodenum mayoritas asimptomati.
Adenoma billosa mempunya potensial keganasan 35%-55%. Lesi-lesi ini
sering asimptomatik dan ditemukan secara tidak sengaja pada
pemeriksaan autopsi. Manifestasi klinis yang paling sering ditemukan
adalah perdarahan dan obstruksi. Terapi yang dianjurkan adalah reseksi
segmental.
Leiomioma
Jinak, tunggal, lesi otot polos. Merupakan neoplasma jinak yang
simptomatik. Akhir-akhir ini ahli patologis menggunakan istilah tumor
stroma bagi menggantikan istilah leiomioma. Insiden terjadinya tumor
adalah sama pada pria dan wanita, paling sering didiagnosa pada dekade
kelima kehidupan. Tumor dapat tumbuh secara intramural dan menyebabkan
obstruksi. Namun tidak jarang juga tumor ini secara intramural dan
ekstramural, kadang-kadang mencapai ukuran yang cukup besar dan akhirnya
tumbuh melampaui suplai darah pada tumor dan mengakibatkan perdarahan,
yang merupakan indikasi yang paling umum untuk operasi pada pasien
dengan tumor stroma jinak. Reseksi usus dilakukan bagi mengurangkan dan
menghentikan perdarahan, namun resiko untuk terjadinya rekurensi masih
ada.
Sindroma Peutz-Jeghers
Pigmentasi melanotik mukokutan (sirkumoral, bukal, telapak tangan,
telapak kaki, perianal) dan polip gastrointestinal. Diturunkan secara dominan
sederhana. Polipnya multiple pada jejunum, iluem dan rektum, dan
merupakan hamartoma. Dapat menyebabkan nyeri kolik dari intususepsi
intermitten. Reseksi kuratif biasanya tidak dimungkinkan. Pembedahan
diindikasikan utnuk obstruksi atau perdarahan.
Neoplasma Persentase
Leiomioma 17
Lipoma 16
Adenoma 14
Polip
-Poliposis, Peutz-Jeghenz
14
3
Hemangioma 10
Fibroma 10
Tumor neurogenik 5
Fibromioma 5
Miksoma 2
Limfangioma 2
Fibroadenoma 1
Jenis dan frekuensi relatif dari neoplasma jinak usus halus
Neoplasma ganas
Adenokarsinoma (paling umum), karsinoid, sarkoma, limfoma. Pasien mengalami
diare dengan mukus/tenesmu, obstruksi dan perdarahan kronis. Biasanya timbul
secara tersembunyi. Terapi adalah reseksi luas, mencakup nodus. Lesi deodenum
membutuhkan pankretikoduodenektomi. Reseksi paliatif untuk mengurangi
gejala.obstruksi. Kelangsungan hidup keseluruhan buruk (rata-rata kelangsungan
hidup 5 tahun adalah 20%). Karsinoma periampular mungkin mempunyai
kelangsungan hidup 5 tahun sampai 40%.
Adenokarsinoma
Sekitar 50% dari keganasan usus kecil. Kebanyakan dalam deodenum dan
jejunum proksimal; 50% karsinoma deodenum melibatkan mapula dan
berkaitan dengan ikterus intermitten. Lesi jejunum berkaitan dengan
obstruksi.
Sarkoma
Merupakan 20% dari keganasan usus kecil; leiomiosarkoma paling umum.
Dapat berdarah atau mengobstruksi.
Limfoma
Merupakan 10-15% dari keganasan usus kecil. Paling umum dalam ileum.
Mungkin merupakan penyakit usus kecil primer atau bagian dari penyakit
sistemik.
Karsinoid
Timbul dari sel enterokromafin (Kulchitdky). Terjadi sama seringnya dengan
adenokarsinoma usus kecil. Potensial keganasan bervariasi. Mensekresi
serotonin dan substansi P. Sindrom karsinoid (warna merah pada wajah,
bronkospasme, diare, kolaps vasomotor, hepatomegali, penyakit katup
jantung kanan) terjadi dalam < 50%. Beberapa orang percaya bahawa
metastasis hepatik harus ada sebelum terjadinya sindrom. Paling sering,
karsinoid timbuk dalm apendik (46%), ileum (24%) dan rektum (17%).
Tumor apendiks 3% bermetastasis bila dibandingkan dengan karsinoid ileum
(angka metastatik 35%). Dari tumor yang berdiameter <1 cm (75% dari
karsinoid gastrointestinal), hanya 2% yang bermetastasi. Penampilan mayou
adalah kuning atau coklat, bulat, nodul keras yang ditutupi oleh mukosa
normal. Gejalanya adalah sindrom karsinoid (jarang) atau nyeri abdomen,
obstruksi, diare dan turunnya berat badan.
Diagnosis serial usus kecil, arteriogram mesenterik, CT scan bermanfaat.
Urin untuk 5-HIAA dengan/tanpa perangsangan pentagastrin digunakan untuk
diagnosis sindrom.
Sindroma karsinoid ganas jarang terjadi, hanya dalam 6-9% pasien karsinoid.
Paling sering dengan penyakit usus kecil dan metastatik hepatk. Mengalami
hepatomegali, diare, warna merah pada wajah, penyakit kanutng jantung kanan
dan asma. Gejala diakibatkan oleh serotonin, substansi P, kemungkina bradikinin
dan prostaglandin E dan F.
Terapi karsinoid primer <1 cm diterapi dengan reseksi usus kecil segmental.
Lesi yang lebih besar atau lesi dengan keterlibatan dari nodus, membutuhkan
eksisi luas usus dengan inklusi dan mesenterium. Karsinoid apendiseal <2 cm
membutuhkan hanya apendiktomi sederhana; >/= 2cm harus menjalani
hemikolektomi. Sindrom karsinoid dapat diterapi dengan reseksi kuratif atau
paliatif, atau dengan somastatin kerja lama.
Prognosis keseluruhan 54%, 75% untuk penyakit lokal, 59% untuk
penyebaran regional, dan 19% untuk penyebaran distal. Karena sifatnya yang
indulen, membesar, maka digunakan reseksi paliatif.
III. DEFEK PADA DINDING ABDOMEN
Omfalokel dan Gastroskisis
Definisi
Omfalokel (disebut juga Exomfalos) merupakan defek dinding abdomen pada
garis tengah dengan berbagai derajat ukuran, disertai hernia visera yang ditutupi
oleh membran yang di terdiri atas peritoneum di lapisan dalam dan amnion di
lapisan luar serta Wharton’s Jelly di antara lapisan tersebut. Pembuluh darah
berada di dalam membran, bukan pada dinding tubuh. Isi dari hernia antara lain
berbagai jenis dan dan jumlah usus, sering sebagian dari hati dan kadang-kadang
organ lainnya. Sedangkan tali pusat terdapat pada puncak kantong ini. Defek ini
mungkin terletak di pusat atas, tengah atau bawah abdomen dan ukuran serta
lokasi memiliki implikasi yang penting dalam penanganannya.
Gastroskisis adalah defek pada dinding abdomen yang biasanya tepat di
sebeah kanan dari masuknya korda umbilikus ke dalam tubuh. Ada juga yang
terletak di sebelah kiri, namun kasusnya jarang. Sejumlah usus dan kadang-kadang
bagian dari organ abdomen lain ikut mengalami herniasi keluar dinding abdomen
dengan tanpa adanya membran yang menutupi ataupun kantung.
Gambar 1. Bayi dengan omfalokel.
gastroskisis.
Ada perbedaan insidens defek dinding abdomen dan proporsi relatif
gastroskisis dan omfalokel; meskipun demikian, perkiraan kasar di seluruh dunia,
insidens gastroskisis berkisar antara 0,4─3 per 10.000 kelahiran dan tampaknya
akan meningkat terus, sementara itu insidens omfalokel berkisar antara 1,5─3 per
10.000 kelahiran dan tampaknya stabil. Etiologi defek dinding abdomen tidak
diketahui dan kebanyakan sporadik, tetapi terdapat kasus gastroskisis dan
omfalokel familial yang jarang (mungkin ditentukan juga secara genetik).
Terdapat faktor resiko maternal khusus untuk defek dinding abdomen yang
berlainan. Gastroskisis memiliki asosiasi yang kuat dengan usia maternal muda,
dengan kebanyakan ibu berada pada usia 20 tahun atau lebih muda. Sebagai
tambahan lagi, gastroskisis dihubungkan dengan pajanan maternal terhadap asap
rokok, narkoba, obat-obatan vasoaktif (pseudoefedrine) dan toksin lingkungan.
Hubungan tersebut tampaknya konsisten dengan teori insufisiensi vaskular
dinding abdomen pada gastroskisis. Sebaliknya, omfalokel berhubungan dengan
peningkatan usia maternal, dengan kebanyakan berada pada usia 30 tahun atau
lebih.
Setelah kejadian omfalokel pada kelahiran anak pertama, risiko untuk
terjadinya omfalokel pada kelahiran selanjutnya sangat bergantung penyebab dari
omfalokel tersebut. Jika omfalokel tidak berhubungan dengan suatu sindom,
seperti Beckwith-Wiedermannan, dan tidak berhubungan dnegan adanya kelainan
kromosomal, tingkat rekurensinya sangat rendah, sekitar 1% atau kurang.
Bagaimanapun, dengan kemungkinan yang lebih sedikit, dapat muncul
predisposisi genetik, dan tingkat kekambuhannya dapat mencapai 50%.
Sementara sekitar 75% kejadian gastroskisis terjadi pada kelahiran anak pertama,
dan sangat jarang berulang pada kelahiran berikutnya. Insiden pada anak laki-laki
sedikit lebih sering dibanding anak perempuan.
Patologi Omfalokel dan Gastroschisis
Dinding abdomen dibentuk oleh pelipatan ke dalam dari kranial, kaudal dan
dua lipatan embrionik lateral. Sejalan dengan pembentukan dinding abdomen,
pertumbuhan traktus intestinalis menyebabkan migrasi keluar kavum abdomen
melalui cincin umbilikus dan ke arah korda umbilikus selama minggu ke-6 gestasi.
Pada minggu ke-10 dan ke-12, dinding abdomen dibentuk dan usus kembali ke
kavum abdomen pada pola stereotipikal yang menghasilkan rotasi normal dan
fiksasi lateral.
Gambar 3. Sonogram pada usia gestasi 10 minggu: menunjukan herniasi fisiologis (tanda panah). UC-korda umbilikalis
Gastroskisis diperkirakan sebagai hasil dari iskemik terhadap perkembangan
dinding abdomen. Daerah paraumbilikal kanan merupakan daerah dengan resiko
tinggi karena disuplai oleh vena umbilikal kanan dan arteri omfalomesenterika
kanan hingga mengalami involusi. Jika perkembagan dan involusi ini terganggu
pada derajat dan waktu tertentu, kemudian defek dinding tubuh akan
menghasilkan iskemia dinding abdomen. Hipotesis lain menyatakan bahwa
gastroskisis terjadi karena defek dari ruptur awal hernia korda umbilikalis.
Pada omfalokel, isi abdomen tidak kembali ke dalam rongga abdomen tetapi
tetap berada di luar abdomen namun berada di dalam korda umbililukus. Berbagai
variasi dan jumlah dari midgust dan organ intra abdomen mengalami herniasi
keluar pada defek tersebut tergantung dari ukuran dan lokasi relatif dinding
abdomen. Defisit pelipatan kranial terutama menghasilkan omfalokel epigastrik
yang mungkin berhubungan dengan kelainan pelipatan kranial tambahan seperti
hernia diafragma anterior, celah sternal, defek perikardial dan defek karidak.
Ketika bagian-baian tersebut terjadi bersamaan, disebut sebagai Pentalogy of
Cantrell (gambar 4). Ketika pelipatan ke dalam melibatkan pelipatan kaudal,
omfalokel mungkin berhubungan dengan Extrophy cloacal atau bladder (gambar
5).
Gambar 4. Pentalogy ofCantrell.
Gambar 5. Exstrophy Cloacal.
Diagnosis
Diagnosis Prenatal
Defek dinding abdomen sering terdiagnosis selama pemeriksaan prenatal
dengan ultrasonografi (USG), yang merupakan suatu skreening rutin atupun
kerena adanya indikasi obsetrik seperti evaluasi peningkatan serum alfa
fetoprotein (AFP) maternal.
AFP analog dengan fetal albumin dan serum AFP maternal merefleksikan nilai
AFP cairan amnion. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi abnormalitas
kromosomal fetus dan defek tabung neural, tetapi AFP juga biasanya meningkat
pada defek dinding abdomen. Keparahan peningkatan nilai AFP bervariasi antara
gastroskisis dan omfalokel. Pada gastroskisis, nilai serum AFP maternal biasanya
abnormal, dengan rata-rata peningkatan >9X dari nilai rata-rata. Sebaliknya, pada
omfalokel, AFP biasanya meningkat rata-rata 4X dari nilai normal. Pola yang
berbeda ini menyebabkan sensitivitas nilai serum AFP maternal yang rendah
untuk omfalokel dibandingkan gastroskisis. Seperti kebanyakan tes skrining,
sensitivitas tergantung pada nilai batas yang dipilih. Contohnya, jika nilai
abnormal didefinisikan sebagai lebih dari 3X nilai normal, maka 96% gastroskisis
akan terdeteksi tetapi hanya 65% pada omfalokel.
USG fetus sering dapat mengindikasikan adanya omfalokel pada trimester
kedua atau awal trimester ketiga. Kebanyakan omfalokel sekarang dapat
didiagnosis sebelum kelahiran. Hal ini sangat membantu dalam mempersiapkan perawatan bagi neonatal.
Pemeriksaan USG abdomen pada diagnosis omfalokel ditunjukkan dengan
adanya kantong hernia dan letak korda umbilikalis pada apex dari kantong
hernia.Adanya gambaran kantong tersebut mengkonfirmasi diagnosis omphalokel
dan menyingkirkan gastroskisis. Bagaimanapun, kantong hernia tersebut tidak
selalu dapat dilihat. Keadaan yang lebih jarang, yaitu terjadinya ruptur kantong
hernia.
Gambar 6. minggu.
Organ visera yang terdapat pada kantong hernia dapat berupa usus, hati, dan
lambung. Ukuran defek dinding abdomen dapat bervariasi dari sederhana yang
hanya mengandung usus sampai defek besar (giant omphalocele) yang
mengandung organ hati. Ukuran defek berkorelasi dengan tindakan reduksi dan
perbaikan pada operasi. Pada kehamilan dengan omfalokel yang terdeteksi awal
dengan USG, diperlukan pemeriksaan lanjutan khususnya pada usia 20-24 minggu
dengan CT-Scan untuk mendeteksi anomalikongenital lain.
Gambar 7. Potongan tranversal pada usia gestasi 22 minggu: menunjukan omfalokel (OM). Gambaran ekogenik mengarah kepada
eviserasi hepar.
Diagnosis prenatal dengan USG pada gastroskisis menunjukan insersi korda
umbilikalis yang normal dan adanya hernia yang ‘free-floating’ tanpa ada kantong
yang membungkus. Bagian usus yang berada di luar rongga abdomen
mengakibatkan bagian usus menjadi tebal, edem, dan terlihat sebagai gambaran
hiperekogenik ‘cauliflower-shaped’ atau gambaran hiperekogenik dengan sudut
pinggir kasar. Kelainan ini dapat didiagnosis pada awal minggu ke-12 kehamilan,
namun juga terdapat laporan diagnosis pada awal trimester pertama yang mana hal
ini lebih jarang.
Bagaimanapun, keakuratan pemeriksaan USG prenatal untuk mendiagnosis
kelainan dinding abdomen sangat dipengaruhi oleh waktu, tujuan awal dari
pemeriksaan, posisi janin, serta pengalaman dan keahlian pemeriksa. USG
memiliki spesifitas yang tinggi, lebih dari 95% namun sensitivitasnya hanya
60─75% untuk mengidentifikasi omfalokel dan gastroskisis. Kesalahan diagnosis
dapat terjadi karena:(a) Kekeliruan dengan adanya defek dinding abdomen lain
yang jarang. (b) Ruptur kantong omfalokel sehingga mengakibatkan adanya
diagnosis gastroskisis.
Gambar 8. Gambaran gastroskisis pada USG abdomen.
Diagnosis Postnatal
Diagnosis omfalokel cukup dengan melihat defek di daerah umbilikus dengan
bagian yang tertutup selaput tipis transparan. Di bagian dalam dapat terlihat usus-
usus, sebagian hepar, mungkin lambung dan lien bergantung pada luas defek.3
Pada omfalokel, pada bayi baru lahir, tampak kantong yang berisi usus dengan
atau tanpa hati di garis tengah. Pada gastrosisis, usus berada diluar rongga perut
tanpa kantong. Defek dinding abdomen terbuka tanpa tertutup peritoneum.
Umbilikus tampak normal. Usus-usus terlihat tebal dan pendek.
Anomali Yang Berhubungan
Seperti semua bayi yang memiliki defek lahir, anak-anak yang memiliki
defek dinding abdomen akan memiliki peningkatan resiko untuk terjadinya
anomali tambahan, tetapi resiko relatif dan pola anomali yang berhubungan
merupakan perbedaan mayor antara gastroskisis dan omfalokel. Perbedaan
tersebut sangat penting dalam manajemen klinis dan prognosis jangka panjang.
Pada gastroskisis, insidens anomali yang berhubungan berkisar anatara 10─20%
dan kebanaykan anomali yang signifikan ditemukan berada pada traktus
gastrointestinal. Sekitar 105 bayi yang dengan gastroskisis memiliki stenosis atau
atresia sebagai hasil dari insufisiensi vaskular di usus pada waktu perkembangan
gastroskisis atau lebih umumnya, dari volvuls atau kompresi vaskular mesenterika
oleh penyempitan cincin dinding abdomen. Lesi lain yang sering berhubungan
termasuk undescensus testes, divertikulum Meckel’s dan duplikasi intestinal.
Anomali serius laninnya di luar abdomen atau traktus gastrointestinal seperti
abnormalitas kromososm jarang ditemukan. Hal yang berbeda terlihat pada pasien
omfalokel, di mana memiliki insidens yang lebih tinggi untuk terjadinya anomali
yang berhubungan ( hingga 50─70%). Abnormalitas kromosom, seperti trisomi
13, 14, 15, 18 dan 21 terdapat pada hingga 30% kasus. Defek kardiak juga sering
terjadi, berkisar 30%-50% kasus. Multipel anomali sering terjadi dan mungkin
terbagi dalam beberapa pola sindrom. Satu pola yang penting yaitu, Beckwith-
Weidenmann syndrome yang ditandai makroglosia, organomegali, hipoglikemia
awal (dari hiperplasia pankreas dan insulin berlebihan) dan peningkatan resiko
tumor Wilms, hepatoblastoma dan neuroblastoma, yang berkembang belakangan
pada usia anak-anak. Ukuran defek dinding abdomen pada omfalokel tidak secara
langsung berhubungan dengan adanya anomali lain, seperti yang didemontrasikan
oleh temuan bahwa defek kecil yang terdapat pada USG prenatal memiliki resiko
yang lebih tinggi untuk terdapatnya abnormalitas kromosomal dan defek kardiak.
Manajemen
Manajemen Prenatal
Janin dengan defek dinding abdomen merupakan kehamilan resiko tinggi
pada banyak tingkatan. Untuk kasus gastroskisis dan omfalokel, terdapat
peningkatan resiko retardasi pertumbuhan intrauterin/Intrauterine growth
retardation (IUGR), kematian janin dan kelahiran prematur, sehingga pengkajian
obstetrik dengan serial USG dan tes lainnya menjadi indikasi. Pada kedua kasus
tersebut, ada beberapa kontroversi mengenai waktu dan jenis kelahiran. Pada
gastroskisis, diagnosis IUGR dapat menjadi masalah karena sulitnya menilai torso,
namun hal itu mungkin hanya mempengaruhi 30─70% janin. Penyebab kegagalan
pertumbuhan janin pada gastroskisis belum diketahui tetapi diperkirakan oleh
karena peningkatan kehilangan protein dari visera yang terpapar, walaupun tidak
adekuatnya suplai nutrien janin merupakan hipotesis alternatif. Usus yang terpapar
mudah untuk mengalami perlukaan. Perlukaan
bervariasi dalam derajatnya dari volvulus dan hilangnya keseluruhan midgut
hingga ke atresia intestinal lokal dan stenosis serta inflamasi yang menyebar atau
serositis yang dapat membuat lingkaran usus tidak dapat dipisahkan satu sama
lain. Infalamasi tersebut berkembang setelah minggu ke-30 kehamilan dan
diperkirakan karena terpaparnya usus dengan cairan amnion atau oleh karena
obstruksi limfatik intestinal. Derajat inflamasi sulit untuk dinilai pada USG dan
setelah kelahiran, sehingga hal tersebut sulit untuk dikorelasikan dengan hasil
klinis. Karena perlukaan usus merupakan prediktor utama morbiditas dan
mortalitas postnatal, maka pemahaman dan tes prediktif diperlukan untuk dapat
melakukan intervensi. Oligohidramion juga sering ditemukan pada gastroskisis,
sekitar hingga 25% kasus. Penyebabnya belum diketahui dan biasanya memiliki
derajat sedang dan berhubungan dengan IUGR, distress janin dan asfiksia lahir.
Manajemen Postnatal
Manajemen awal bayi yang baru lahir dengan defek dinding abdomen
diawali dengan resusitasi ABC dan setelah dinilai dan distabilisasi, perhatian
diarahkan ke defek dinding abdomennya. Masalah yang penting yaitu kehilangan
panas, sehingga perawatan harus dilakukan seperti menjaga suhu lingkungan
hangat selagi melakukan proteksi terhadap visera yang terpapar. Kelahiran
prematur umumnya berhubungan dengan kondisi tersebut di atas. Menilai dan
menjaga nilai glukosa serum merupakan bagian dari resusitasi tetapi khususnya
penting pada bayi dengan defek dinding abdomen karena hubungannya dengan
prematuritas, IUGR dan pada omfalokel serta kemungkinan terjadinya sindrom
Beckwith-Wiedeman. Prematuritas berhubungan dengan hipoplasia paru atau
defek jantung signifikan yang terlihat pada omfalokel mungkin memerlukan
intubasi awal dan ventilasi mekanik. Dekompresi lambung penting untuk
mencegah distensi traktus gastrointestinal dan kemungkinan aspirasi. Akses
vaskular diperoleh untuk memberikan cairan intravena dan antibiotilk spektrum
luas untuk profilaksis. Bayi dengan gastroskisis memiliki kehilangan cairan yang
cukup tinggi dari penguapan dan ruang ketiga dan mungkin membutuhkan
pemberian cairan dua kali volume untuk menjaga volume intravascular tetap
adekuat. Kateter urin berguna untuk memonitor keluaran urin secara ketat dan
sebagai panduan resusitasi. Arteri dan vena umbilicus mungkin dilakukan kanulasi
jika diperlukan selama resusitasi, namun pada omfalokel penempatan mungkin
sulit karena insersi abnormal pembuluh darah. Bahkan jika kanulasi berhasil,
mungkin perlu dilepaskan selama pembetulan defek.
Setelah resusitasi berhasil dilakukan, defek dinding abdomen dapat dinilai
dan diobati. Proses ini melibatkan pertimbangan yang berbeda pada gastroskisis
dan omfalokel. Pada gastroskisis dilihat keadaan visera yang terpapar dan
dihindari agar jangan sampai terjadi puntiran pedikulus vascular mesenterika. Jika
terjadi gangguan vascular karena pembukaan dinding abdomen terlalu kecil, defek
sesegera mungkin dilakukan pembesaran melalui operasi. Usus yang terpapar
harus diproteksi dan kehilangan panas dan cairan harus diminimalisasi. Metode
paling mudah yaitu menempatkan visera yang terpapar dan setengah bagian
bawah tubuh bayi pada kantong plastic usus transparan. Cara ini cepat, tidak
membutukan keterampilan khusus atau pengalaman khusus dan dapat
memudahkan penilaian perfusi usus. Cara lain, hanya usus yang ditutupi dengan
plastic bening, namun membutuhkan teknik yang lebih sulit. Cara terakhir, bahan
kain yang lembab ditutupi pada usus dengan dilapisi plastic bening tetapi
membutuhkan penilaian tentang bagaimana ketat atau kuatnya untuk menutupi
dan agar tampak dilihat. Bahan kain lembab sendiri seharusnya dihindari karena
meningkatkan kehilangan panas melalui penguapan. Setelah usus tadi ditutupi,
seluruh masa distabilisasi dengan menempatkan bayi dengan posisi miring kanan
untuk mencegah bengkoknya pedikulus mesenterika. Pada omfalokel
penangannya berbeda. Defek diinspeksi agar menjamin membrane yang menutupi
nya tetap intak dan kain basah yang tidak menempel diletakkan dan distabilisasi
untuk mencegah trauma terhadap kantong. Jika kantong omfalokel ruptur, usus
yang terpapar harus ditangani seperti halnya gastroskisis.
Manajemen Operasi
Pada gastroskisis dan omfalokel, tujuan utama adalah untuk mereduksi
visera yang mengalami hernia masuk kembali ke dalam abdomen dan untuk
menutup fasia dan kulit untuk menciptakan dinding abdomen yang solid dengan
umbilicus yang relatif normal untuk meminimalkan resiko bayi. Untuk mencapai
tujuan tersebut, banyak teknik yang dapat digunakan. Pengobatan sangat
bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis defek, ukuran bayi dan masalah yang
berhubungan. Karena terdapat sedikit bukti untuk mengganggap suatu metode
lebih bagus dari yang lain, terdapat variasi dalam pendekatan operasi.
Pada gastroskisis, hilangnya panas dan cairan yang terus menerus dan
perubahan metabolik membuat penutupan menjadi prioritas tinggi. Selama
resusitasi awal pada saat lahir atau sesegera mungkin setelahnya, a prefabricated,
spring-loaded Silastic silo ditempatkan pada defek untuk menutupi usus yang
terpapar tadi. Praktek ini, akan meminimalisasikan kehilangan melalui penguapan,
mencegah trauma tambahan dan juga dapat menilai perfusi usus secara terus
menerus. Alat ini dapat ditempatkan dalam ruang bersalin atau disamping tempat
tidur tanpa anestesi. Jika defek dinding abdomen terlalu kecil untuk
mengakomodasi alat, defek dapat dbesarkan dengan anestesi lokal dan sedasi. Jika
alat tidak dapat ditempatkan di samping tempat tidur, sesegera mungkin setelah
resusitasi awal dan stabilisasi, bayi dilakukan operasi untuk penutupan primer atau
pemasangan silo. Penutupan di kamar bersalin merupakan konsep yang menarik
yang meminimalisasi waktu dan trauma perioperatif tetapi hanya mungkin dengan
kelahiran yang terencana dari defek yang diketahui sebelumnya dan membutuhkan
komitmen berbagai pihak. Perbaikan primer segera tanpa anestesi pernah
dilaporkan untuk kasus tertentu dan mungkin menjadi contoh dramatik operasi
dengan trauma dan invasif minimal.
Setelah pemasangan spring-loaded silo, bayi dievaluasi lebih lanjut dan
dirawat di ICU. Dengan diuresis spontan, dekompresi traktus gastrointestinal dari
atas dan bawah dan resolusi edema dinding usus, maka volume usus yang terpapar
yang berada di dalam bag menjadi turun dalam periode waktu yang singkat.
Ketika bayi berada dalam kondisi stabil dan reduksi spontan usus ke dalam
abdomen telah mencapai keadaan puncak, bayi dibawa ke kamar operasi untuk
dilakukan percobaan penutupan primer tunda. Reduksi serial alat pada tempat
tidur pernah disarankan, tetapi resiko salah pemasangan alat membuat rencana ini
kurang menarik. Di kamar operasi, jika usus dapat direduksi ke dalam abdomen
dan defek menutup primer (atau melalui perbaikan primer tunda), maka operasi
dilakukan. Keputusan apakah bayi dapat mentoleransi reduksi dan perbaikan dapat
menjadi susah dan dapat ditambahkan dengan mengukur tekanan intragastik
selama penutupan berlangsung. Tekanan <20 mmHg dapat memprediksikan
kesuksesan penutupan tanpa komplikasi tekanan intra-abdomen yang berlebihan.
Metode lain dilaporkan untuk membantu dalam keputusan untuk menutup atau
tidak adalah mengukur perubahan tekana vena sentral, tekanan ventilator dan
karbondioaksida. Jika bayi dalam keadaan stabil ketika fascia ditutup, umbilicus
dapat direkontruksi pada tingkat krista iliaka posterior selama penutupan kulit.
Pembuatan umbilicus dapat selalu ditunda untuk waktu berikutnya. Jika perbaikan
tidak mungkin, formal silastic silo dijahitkan ke fasia dan reduksi serial dilakukan
post-operasi. Bayi dengan gastroskisis dan atresia intestinal memiliki tantangan
yang cukup serius, jika usus berada dalam kondidi bagus dan abdomen dapat
ditutup dengan mudah, perbaikan primer kombinasi dari kedua defek menjadi
mungkin dilakukan. Oleh karena itu, jika atresia terjadi, prioritas pertama adalah
menutup abdomen dengan primer atau primer tunda atau perbaikan silo bertahap.
Bayi dijaga dengan dekompresi gaster dan nutrisi parenteral selama beberapa
minggu hingga laparotomy dan perbaikan atresia intestinal. Tahap perbaikan ini
akan menyebabkan inflamasi menghilang dan isi hernia kembali ke abdomen
sebelum pembukaan usus dan pembuatan anastomosis.
Pada omfalokel, strategi yang digunakan berbeda. Pertama, menutup
kantong yang intak, kemudian tidak perlu terburu-buru untuk melakukan operasi
penutupan. Sepanjang visera tertutupi membrane, evaluasi yang lengkap untuk
defek yang berhubungan dapat dilakukan dan masalah lain teratasi. Ketika bayi
stabil dan jika defek relative kecil, perbaikan primer dapat dilakukan dengan insisi
membrane omfalokel, mengurangi hernia visera dan menutup fasia dan kulit.
Membrane yang melapisi liver mungkin terluka saat insisi, karena itu dapat
dibiarkan saja. Ketika penutupan primer tidak mungkin dilakukan, ada banyak
pilihan, namun yang dapat dilakukan adalah mengobati kantong omfalokel dengan
sulfadiazine silver topical dan membiarkan agar terjadi epitelisasi
hingga beberapa minggu atau bulan. Makanan enteral biasanya dapat ditolerasi
setelah bayi sembuh dari berbagai masalah sistemtik. Setelah masalah lain yang
berhubungan sudah diatasi, keluarga dapat diajarkan untuk untuk melakukan
perawatan luka dan bayi diijikan untuk rawat jalan.
Gambar 9. Epitelisasi setelah pemberian silver sulfadiazin.
Ketika epitelisasi kantong sudah terjadi atau sudah cukup kuat untuk
mendapatlan tekanan luar, kompresi dilakukan dengan plester elastik dan secara
serial dilakukan hingga isi abdomen mereduksi. Ketika isi abdomen tereduksi,
membran mengalami epitelisasi dan bayi berada dalam keadaan baik, perbaikan
hernia ventral dilakukan. Proses ini dapat dicapai dalam waktu 6─12 bulan,
namun terdapat sedikit resiko dalam menunggu dalam menunggu selama masa
tadi. Defek fasia menyisakan ukuran yang sama ketika bayi tumbuh. Hal ini
membuat penutupan relative sedikit terlambat dari omfalokel yang berukuran
besar. Strategi ini awalnya diadopsi hanya untuk pasien yang memiliki omfalokel
berukuran besar atau berhubungan dengan masalah yang serius tetapi berjalan
dengan baik pada kasus sulit yang sebelumnya tidak dapat ditutup. Teknik ini juga
dapat mencegah kompromis paru, pecahnya luka, infeksi dan tertundanya
pemberian makanan enteral yang terganggu dengan sejumlah operasi besar pada
bayi yang baru lahir. Hal ini juga berguna khususnya untuk memperoleh
penutupan fasia pada regio epigastrium omfalokel besar. Banyak strategi
alternative untuk penutupan omfalokel, termasuk hanya penutupan kulit, reduksi
silastic silo dan perbaikan, reduksi di dalam membrane omfalokel, inverse amnion
dan penambalan fasia.
Gambar 10. Delapan bulan setelah implantasi : epitelisasi hampir komplit, tetapi hernia ventral yang besar masih berkembang
Prognosis
Prognosis pasien dengan gastrosksis tergantung pada kondisi usus, sementara
pasien dengan omfalokel tergantung pada anomaly lain yang berhubungan dan
kondisi medis. Secara keseluruhan, pasien dengan gastroskusis memiliki prognosis
baik. Harapan hidup sedikitnya 90─95%, dengan kebanyakan pasien yang
meninggal terjadi pada yang memiliki usus katastropik, sepsis dan komplikasi
jangka panjang sindrom usus pendek. Pasien dengan atresia dan
sindrom usus pendek mungkin akhirnya membaik walaupun perawatan selama di
rumah sakit cukup lama dan panjang. Bahkan bayi dengan traktus intestinal intak
mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit selama beberapa minggu hingga
bulan karena toleransi yang rendah pada pemberian makanan enterik. Sebuah
bentuk enterokolitis nekrosis dapat bermanifestasi sebagai pneumatosis intestinal
pada pemeriksaan radiologi abdomen, yang merupakan bentuk unik dari perlukaan
intestinal yang terjadi selama periode post-operasi setelah perbaikan
gastroskusis.pemberian makanan sering berkomplikasi sebagai refluks
gastroesofagus yang dapat memebrat. Fungsi gastrointestinal jangka panjang
biasanya bagus, walaupun terdapat resiko obstruksi adesif 5─10%.2
Prognosis bayi dengan omfalokel lebih sulit untuk digeneralisasikan, tetapi
kebanyakan mortalitas dan morbiditas berhubungan dengan anomaly daripada
defek dinding abdomennya.itu sendiri. Survavie rate pada bayi omfalokel
dipengaruhi oleh beberapa hal dibawah ini.· Prematuritas
Neonatus yang lahir pada usia gestasi <36 minggu memiliki survival rate yang
rendah, 57%. Survival rate akan meningkat dengan peningkatan usia gestasi
>36 minggu mencapai 87%
· Ukuran omfalokel
Pada omfalokel yang mengandung organ hati, umumnya merupakan suatu
giant omphalocele. Kebanyakan akan mengalami gangguan pada
perkembangan paru, bayi ini akan mengalami kesulitan bernapas. Bayi ini
memiliki survival rate 50%.
· Adanya anomali pada organ lain
Neonatus dengan defek tambahan memiliki survival rate yang rendah. Dapat
dilihat pada tabel berikut:
Defek Insiden Survival rate
Jantung 34% 63%
Malformasi anus 15% 69%
Anomali kromosom 30% 1%
· Hernia Umbilikalis
Definisi
Hernia umbilikalis merupakan defek dinding abdomen persis dipusat
umbilikus, berupa herniasi utuh yang hanya tertutup peritoneum dan kulit yang
terdapat waktu lahir. Omentum dan usus dapat mesuk ke dalam kantong hernia,
khususnya bila bayi menangis.
Kulit kantong hernia tidak pernah ruptur dan sangat jarang terjadi inkarserasi.
Umumnya hernia umbilikalis dapat menutup spontan tanpa pembedahan setelah
bayi berumur 2─3 tahun. Hernia yang tetap ada sampai umur 5 tahun umumnya
memerlukan tindakan bedah, meskipun jarang ditemukan terjadinya komplikasi
pada hernia umbilikalis.
Gambar 11. Hernia Umbilikalis
Hernia umbilikalis pada bayi dan anak terjadi karena defek fasia di daerah
umbilikus dan manifestasinya terjadi setelah lahir. Waktu lahir pada fasia terdapat
celah yang hanya dilalui tali pusat. Setelah pengikatan, puntung tali pusat sembuh
dengan granulasi dan epitelisasi terjadi dari pinggir kulit sekitarnya.Waktu lahir
banyak bayi dengan hernia umbilikalis karena defek yang tidak menutup
sempurna dan linea alba tetap terpisah. Pada bayi prematur defek ini lebih sering
ditemukan. Defek ini cukup besar untuk dilalui peritoneum; bila tekanan
intraabdomen meninggi, peritoneum dan kulit akan menonjol dan berdekatan.
Penampang defek kurang 1 cm, 95% dapat sembuh spontan, bila defek lebih 1,5
cm jarang menutup spontan. Defek kurang 1 cm waktu lahir dapat
menutupspontan pada umur 1─2 tahun. Pada kebanyakan kasus, cincin hernia
mengecil setelah umur beberapa tahun, hernia hilang spontan dan jarang sekali
residif. Penutupan defek terjadi perlahan-lahan kira-kira 18% setiap bulan. Bila
defek lebih besar, penutupan lebih lama dan beberapa hernia tidak hilang spontan.
Hernia yang besar sekali menimbulkan gangguan pada anak dan ibu sehingga
perlu operasi lebih cepat.
Epidemiologi
Hernia ini terdapat pada kira-kira 20% bayi dan angka ini berbeda lebih tinggi
lagi pada bayi prematur.Tidak ada perbedaan angka kejadian pada bayi laki-laki
dan perempuan. Di amerika, insiden hernia umbilikalis 8 kali lebih sering pada
bayi kulit hitam dibanding bayi kulit putih.
Gejala Klinis
Hernia umbilikalis merupakan penonjolan yang mengandung isi rongga perut
yang masuk melalui cincin umbilikus akibat peninggian tekanan intraabdomen,
biasanya ketika bayi menangis.Hernia umumnya tidak menimbulkan nyeri dan
sangat jarang terjadi inkaserasi. Diagnosis tidak sukar yaitu dengan adanya defek
pada umbilikus. Diagnosis banding bila ada defek supraumbilikus dekat dengan
defek umbilikus dengan penonjolan lernak preperitonial yang dirasakan tidak
enak.
Tatalaksana
Strepping dengan plester di atas hernia dengan ataupun tanpa uang logam
yang dipertahankan selama 10─20 hari dan di ulang sampai 6─1 tahun, hal ini
dapat mempercepat penyembuhan namun masih kontroversi
Indikasi dilakukan tindakan bedah:
1. Bila diameter cincin hernia < 1 cm pada umur 1 tahun, hernia mungkin sekali
akan menutup spontan. Sebaiknya ditunggu sampai pasien berumur 3 tahun.
2. Bila diameter cincin hernia > 1 cm pada umur 1 tahun, kemungkinan menutup
spontan kurang, tetapi tidak ada salahnya bila ditunggu hingga umur 3 tahun
3. Bila diameter cincin hernia 2 cm atau lebih, penutupan spontan hampir pasti tidak akan terjadi,
pembedahan dapat dilakukan pada setiap saat dalam tahun ke-2 atau ke-3
Tindakan bedah dalam praktek
1. Bila diameter cincin hernia 1 cm atau kurang pada waktu pemeriksaan, hernia menutup spontan
dapat diharapkan dan pembedahan mungkin tidak di perlukan.
2. Bila diameter cincin hernia 2 cm atau lebih pada waktu pemeriksaan, kecil kemungkinan hernia
menutup secara spontan, pembedahan dapat dilakukan setiap saat setelah pasien berumur 3─6 bulan;
dengan catatan pembedahan (prosedur mayo) dilakukan secara baik sehingga kekhawatiran residif
tidak terjadi.
Komplikasi
Hernia umbilikalis jarang mengalami inkarserasi. Kalau terjadi, kerusakan usus lebih cepat
dibanding pada hernia inguinal karena cincin umbilikus kurang elastis dibanding hernia inguinal.
Reposisi spontan seperti hernia inguinal tidak dianjurkan. Pada beberapa kasus yang mengalami
inkarserasi, dalam kantong terdapat usus tidak mengalami nekrosis, hanya ada satu kasus dengan
nekrosis omentum.
IV. ABSES
Abses adalah suatu penimbunan nanah, biasanya terjadi akibat suatu infeksi bakteri. Jika bakteri
menyusup ke dalam jaringan yang sehat, maka akan terjadi infeksi. Sebagian sel mati dan hancur,
meninggalkan rongga yang berisi jaringan dan sel-sel yang terinfeksi. Sel-sel darah putih yang
merupakan pertahanan tubuh dalam melawan infeksi, bergerak ke dalam rongga tersebut dan setelah
menelan bakteri, sel darah putih akan mati. Sel darah putih yang mati inilah yang membentuk nanah,
yang mengisi rongga tersebut.
Akibat penimbunan nanah ini, maka jaringan di sekitarnya akan terdorong. Jaringan pada akhirnya
tumbuh di sekeliling abses dan menjadi dinding pembatas abses. Hal ini merupakan mekanisme tubuh
untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Jika suatu abses pecah di dalam, maka infeksi bisa
menyebar di dalam tubuh maupun di bawah permukaan kulit, tergantung kepada lokasi abses.
Penyebab
Suatu infeksi bakteri bisa menyebabkan abses melalui beberapa cara: bakteri masuk ke bawah kulit
akibat luka yang berasal dari tusukan jarum yang tidak steril,bakteri menyebar dari suatu infeksi di
bagian tubuh yang lain,bakteri yang dalam keadaan normal hidup di dalam tubuh manusia dan tidak
menimbulkan gangguan, kadang bisa menyebabkan terbentuknya abses.
Peluang terbentuknya suatu abses akan meningkat jika: terdapat kotoran atau benda asing di
daerah tempat terjadinya infeksi, daerah yang terinfeksi mendapatkan aliran darah yang kurang, terdapat
gangguan sistem kekebalan.
Gejala
Gejala dari abses tergantung kepada lokasi dan pengaruhnya terhadap
fungsi suatu organ atau saraf. Gejalanya bisa berupa nyeri, nyeri tekan, teraba hangat, pembengkakan,
kemerahan, dan demam.
Suatu abses yang terbentuk tepat di bawah kulit biasanya tampak sebagai suatu benjolan. Jika abses
akan pecah, maka daerah pusat benjolan akan lebih putih karena kulit diatasnya menipis. Sedangkan,
suatu abses di dalam tubuh, sebelum menimbulkan gejala seringkali terlebih dahulu tumbuh menjadi
lebih besar. Abses dalam lebih mungkin menyebarkan infeksi ke seluruh tubuh.
Diagnosis
Abses di kulit atau dibawah kulit sangat mudah dikenali, sedangkan abses dalam seringkali sulit
ditemukan. Pada penderita abses, biasanya pemeriksaan darah menunjukkan peningkatan jumlah sel
darah putih. Untuk menentukan ukuran dan lokasi abses dalam, bisa dilakukan pemeriksaan rontgen,
USG, CT scan atau MRI.
Pengobatan
Suatu abses seringkali membaik tanpa pengobatan, abses pecah dengan sendirinya dan
mengeluarkan isinya. Kadang abses menghilang secara perlahan karena tubuh menghancurkan infeksi
yang terjadi dan menyerap sisa-sisa infeksi. Abses tidak pecah dan bisa meninggalkan benjolan yang
keras.
Untuk meringankan nyeri dan mempercepat penyembuhan, suatu abses bisa ditusuk dan dikeluarkan
isinya. Suatu abses tidak memiliki aliran darah, sehingga pemberian antibiotik biasanya sia-sia.
Antibiotik bisa diberikan setelah suatu abses mengering dan hal ini dilakukan untuk mencegah
kekambuhan. Antibiotik juga diberikan jika abses menyebarkan infeksi ke bagian tubuh lainnya
Abses bisa terbentuk di seluruh bagian tubuh, termasuk otak, paru-paru, payudara, serta organ-organ
di abdomen khususnya hati. Berikut ini akan diuraikan lebih jauh mengenai abses pada organ-organ
tersebut.
V. TUMOR JARINGAN LUNAK
Gejala dan tanda tumor jaringan lunak tidak spesifik, tergantung pada lokasi di mana
tumor berada, umumnya gejalanya berupa adanya suatu benjolan dibawah kulit yang tidak
terasa sakit. Hanya sedikit penderita yang mengeluh sakit, yang biasanya terjadi akibat
pendarahan atau nekrosis dalam tumor, dan bisa juga karena adanya penekanan pada saraf-
saraf tepi. Tumor jinak jaringan lunak biasanya tumbuh lambat, tidak cepat membesar, bila
diraba terasa lunak dan bila tumor digerakan relatif masih mudah digerakan dari jaringan di
sekitarnya dan tidak pernah menyebar ke tempat jauh. Umumnya pertumbuhan kanker
jaringan lunak relatif cepat membesar, berkembang menjadi benjolan yang keras, dan bila
digerakkan agak sukar dan dapat menyebar ke tempat jauh ke paru-paru, liver maupun tulang.
Kalau ukuran kanker sudah begitu besar, dapat menyebabkan borok dan perdarahan pada
kulit diatasnya.
Jenis – jenis tumor jaringan lunak
Jaringan Asal Benigna Intermediet Maligna
Adiposa Lipoma Berdiferensiasi baik Liposarkoma berdiferensiasi
Angiolipoma Liposarkoma miksoma
Miolipoma Round cell liposarcoma
Lipoma Kondroid
Fibrosit/miofibrosit Fascitis nodular Fibromatosis superficial Fibrosarkoma dewasa
Fascitis proliferative (Palmar / Plantar) Miksofibrosarkoma
Myositis Osificans Fibromatosis tipe Sarcoma fibromiksoma daerah
Fibroma sarung tendo desmoids Rendah
Lipofibromatosis Fibrosarkoma epiteloid
Sklerosans
Biasa disebut Sel raksasa sarung Tumor fibriohistiositik Histiositoma fibrosa maligna
Tumor tendo pleksiform Pleomorfik
Fibrohistiositik Tumor sel raksasa tipe Tumor sel raksasa Histiositoma fibrosa maligna
difus jaringan lunak sel raksasa
Histiositoma fibrosa Histiositoma fibrosa maligna
benigna profunda Inflamatorik
Otot polos Angioleimioma Leiomiosarkoma
Leiomioma profunda
Leiomioma genital
Perivaskuler Tumor glomus Tumor glomus maligna
(Perisit) Mioperisitoma
Otot rangka Rabdomioma Rabdomiosarkoma embrional
Tipe dewasa Rabdomiosarkoma alveolar
Tipe fetus Rabdomiosarkoma pleomorfik
Tipe genital
Vaskular Hemangioma Hemangioendotelioma Hemangioendotelioma
Hemangioma epiteloid kaposiformis Epiteloid
Angiomatosis Hemangioendotelioma Angiosarkoma jaringan lunak
Limfangioma retiformis
Angioendotelioma
retiformis
Angioendotelioma
intralimfatik papilaris
Kondro-osseus Kondroma jaringan Kondrosarkoma mesenkimal
lunak Osteosarkoma ekstraskeletal
Tumor yang Miksoma intramuscular Histiositoma fibrosa Sarcoma synovial
berasal dari Miksoma juksta- angiomatoid Sarcoma bagian lunak alveolar
jaringan yang artikular Tumor fibromiksoma PNET/Tumor Ewing
diferensiasinya Angiomiksoma oksifikans ekstraskeletal Mesenkimoma
tidak jelas profunda Tumor campuran maligna
Hialinisasi pleomorfik Mioepiteloma
Timoma Parakordoma
hamartomatosa ektonik
Tumor Jaringan Lunak Jinak
Pada umumnya tumor jaringan lunak jinak tumbuh lambat dan terbatas, dapat
melakukan invasi local namun angka kekambuhannya rendah, dan merupakan kelompok
tumor yang sangat heterogen (terdiri dari 200 jenis). Walaupun bermacam-macam, tumor
jaringan lunak dapat dikelompokan sesuai dengan diferensiasi pada saat sel tumornya
telah dewasa, yaitu tumor lemak, vascular, fibrosa, dan saraf.
Tumor lemak jinak. Tumor lemak jinak mempunyai banyak varian, yaitu
lipoma subkutan superficial, lipoma intramuscular, lipoma sel spindle, angiolipoma,
lipoblastoma, lipomatosis difus, dan hibernoma. Lipoma merupakan tumor jaringan
lunak terbanyak, tumbuh lambat, dan relative jarang menimbulkan keluhan. Sebagian
besar lipoma tidak memerlukan terapi.
1. Lipoma
Definisi
Lipoma adalah tumor lemak yang pertumbuhannya lambat dan berada di antara kulit dan
lapisan otot. Seringkali lipoma mudah diidentifikasi karena tumor ini langsung bergerak
jika ditekan dengan jari. Lipoma dapat terjadi pada segala usia dan tumor ini dapat
bertahan dikulit selama bertahun-tahun.
Etiologi
Penyebab pasti dari lipoma belum diketahui sampai saat ini.
Gejala
Predileksi
Lipoma terletak di bawah kulit dan tidak menonjol Lipoma sering terjadi dileher,
punggung, lengan dan paha.‡
Gejala dan tanda pada lipoma
- Lipoma berukuran kecil dengan diameter kurang dari 2 inci (5 cm), tetapi lipoma
dapat tumbuh menjadi besar dengan diameter mencapai lebih dari 4 inci (10 cm).
- Lipoma jika disentuh terasa kenyal dan mudah bergerak (mobile), jika sedikit ditekan
dengan jari.
- Lipoma dapat menyebabkan nyeri jika tumor lemak ini tumbuh dan ditekan di dekat
saraf atau jika mengandung banyak pembuluh darah.
Penatalaksanaan
Pada dasarnya lipoma tidak perlu dilakukan tindakan apapun, kecuali berkembang
menjadi nyeri dan mengganggu pergerakan. Biasanya seseorang menjalani operasi bedah
untuk alasan kosmetik. Operasi yang dijalani merupakan operasi kecil, yaitu dengan cara
menyayat kulit diatasnya dan mengeluarkan lipoma yang ada. Namun hasil luka operasi
yang ada akan sesuai dengan panjangnya sayatan. Untuk mendapatkan hasil operasi yang
lebih minimal, dapat dilakukan liposuction. Sekarang ini dikembangkan tehnik dengan
menggunakan gelombang ultrasound untuk menghansurkan lemak yang ada. Yang perlu
diingat adalah jika lipoma yang ada tidak terangkat seluruhnya, maka masih ada
kemungkinan untuk berkembang lagi dikemudian hari.
2. Liposarkoma
Liposarkoma menempati sekitar 21,4% dari seluruh sarkoma jaringan lunak. Umumnya
terjadi pada orang dewasa, khususnya terbanyak pada usia 40 – 60 tahun. Di setiap lokasi
berjaringan lemak dapat timbul liposarkoma, lokasi predileksi adalah retroperitoneal,
ekstermitas bawah, torso. Durasi penyakit sangat bervariasi. Bahaya utama terletak pada
pertumbuhan invasif lokal dan rekurensi berulang – ulang.
Patologi
Tumor sering kali lobular, konsistensi lunak, liposarkoma yang timbul di
retroperitoneum tidak berbatas tegas dengan jaringan lemak normla, penampang irisan
tumor berwarna kuning keputihan. Dibawah mikroskop dapat dibagi menjadi 5 jenis
yaitu miksoid berdiferensisasi baik, miksoid berdiferensiasi buruk, pleomorfik, sel bulat,
dan lipomatoid. Liposarkoma diferensiasi baik sangat mirip dengan lipoma, sering
memiliki cukup banyak jaringan lipoid yang cukup matur, di dalam liposarkoma
diferensiasi buruk terdapat lipoblas, ukuran sel bervariasi, dan terdapat berbagai bentuk
dismorfisme.
Manifestasi klinis
Sarkoma jenis ini tumbuh relatif lambat. Umumnya berupa massa berlokasi dalam,
berbatas tegas dan tidak nyeri. Dengan berkembangnya penyakit, dapat timbul nyeri,
gejala desakan terkait dan gangguan fungsi. Liposarkoma di retroperitoneal lebih sulit
dideteksi secara klinis, pasien sering datang dengan komplikasi seperti hernia inguinalis,
udema tungkai bawah atau tanda desakan organ dalam. Pada stadium lanjut dapat disertai
penurunan berat badan, dll.
Terapi
Terutama dengan operasi, harus dengan eksisi luas. Disamping itu, anggapan luas bahwa
liposarkoma relatif peka terhadap radiasi, maka terhadap kasus tidak mudah dieksisi
tuntas karena lokasi yang unik, harus diraditerapi agresif
Tumor vascular jinak. Tumor ini merupakan tumor jaringan lunak terbanyak,
yang terdiri dari berbagai tipe, yaitu hemangioma, hemangioma kavernosa, hemangioma
arteriovenosa hemangioma epiteloid (penyakit Kimura), granuloma piogenik,
limfangioma, dan tumor glomus.
Hemangioma
Hemangioma merupakan neoplasma jinak yang sering ditemukan pada bayi baru lahir.
Dikatakan bahwa 10% dari bayi yang baru lahir dapat mempunyai hemangioma dimana
angka kejadian tertinggi terjadi pada ras kulit putih dan terendah pada ras asia.
Hemangioma lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki
dengan perbandingan 5:1. Angka kejadian hemangioma meningkat menjadi 20-30% pada
bayi -bayi. Pada dasarnya hemangioma dibagi menjadi dua yaitu hemangioma kapiler
dan hemangioma kavernosum. Hemangioma kapiler (hemangioma superfisial) terjadi
pada bagian atas, sedangkan hemangioma kavernosum terjadi pada kulit yang lebih
dalam, biasanya pada bagian dermis dan subkutis. Pada beberapa kasus kedua jenis
hemangioma ini dapat terjadi bersamaan atau disebut dengan hemangioma campuran.
Hemangioma kapiler/ strawberry hemangioma
Hemangioma kapiler terdapat pada waktu lahir atau beberapa hari sesudah lahir. Lebih
sering terjadi pada bayi prematur dan akan menghilang dalam beberapa hari atau
beberapa minggu. Tampak sebagai bercak merah yang makin lama makin membesar,
warnanya menjadi merah menyala, tegang dan berbentuk lobular, berbatas tegas dan
keras pada perabaan. Involusi spontan ditandai oleh memucatnya warna di daerah sentral
lesi menjadi kurang tegang dan lebih mendatar.
Granuloma piogenik, lesi ini terjadi akibat proliferasi kapiler yang sering terjadi sesudah
trauma, jadi bukan oleh karena proses peradangan, walaupun sering disertai infeksi
sekunder. Lesi biasanyasoliter, dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak dan
tersering pada bagiandistal tubuh yang sering mengalami trauma. Mula-mula berbentuk
papula eritematosadengan pembesaran yang cepat. Beberapa lesi dapat mencapai ukuran
1 cm dan dapat bertangkai, mudah berdarah.
Hemangioma kavernosum, lesi ini tidak berbatas tegas, dapat berupa makula
eritematosa atau nodus yang berwarna merah sampai ungu. Bila ditekan akan mengempis
dan cepat mengembung lagi apabila dilepas. Lesi terdiri dari elemen yang matang.
Bentuk kavernosum jarang mengadakan involusi spontan.
Hemangioma campuran, Jenis ini terdiri atas campuran antara jenis kapiler dan
jenis kavernosum. Gambaran klinisnya juga terdiri atas gambaran kedua jenis
tersebut. Sebagian besar ditemukan pada ekstremitas inferior, biasanya unilateral, soliter,
dapat terjadi sejak lahir atau masa anak-a n a k . L e s i b e r u p a t u m o r y a n g l u n a k ,
b e r w a r n a m e r a h k e b i r u a n ya n g k e m u d i a n p a d a p e r k e m b a n g a n n ya
d a p a tm e m b e r ig a m b a r a n k e r a t o t i k d a nv e r u k o s a .L o k a s i
h e m a n g i o m a c a m p u r a n p a d a l a p i s a n k u l i t s u p e r f i s i a l . Gambaran klinis
umum ialah adanya bercak merah yang timbul sejak lahir atau beberapa saat setelah
lahir, pertumbuhannya relatif cepat dalam beberapa minggu atau beberapa bulan,
warnanya merah terang bila jenis strawberry atau biru bila jenis kavernosa. Bila besar
maksimum sudah tercapai, biasanya pada umur 9
– 12 tahun, warnanya menajdi merah gelap.
Penatalaksanaan
Operasi
Indikasi :
1. Ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan terlalu cepat, misalnya dalam beberapa
minggu lesi menajdi 3 -4 kali lebih besar
2. Hemangioma raksasa dengan trombositopenia
3. Tidak ada regresi spontan, penurunan tersebut tidak terjadi setelah 6 -7 tahun.
Lesi terletak pada wajah, leher, tangan atau vulva yang tumbuh cepat, mungkin
memerlukan eksisi untuk mengendalikannya.
Tumor fibrosa jinak. Fibroma berasal dari proliferasi fibroblast bersama
matriksnya. Kelompok ini paling banyak variasinya, antara lain tumor fibrosa
proliferative jinak, tumor fibrosa proliferative pada bayi dan anak, fibromatosis, tumor
desmoid ekstra-abdominal, dan lain-lain. Pada kelompok tumor fibrosa ini, sebagian
besarnya (kecuali tumor desmoids ekstraabdominal) merupakan proses reaktif terutama
akibat inflamasi. Tumor desmoids terjadi pada usia dewasa muda sampai umur 40 tahun,
banyak terjadi pada pria dan lokasi tersering adalah daerah proksimal seperti bahu,
gluteus, posterior femur, poplitea, lengan atas, dan lengan bawah, umumnya lesi tunggal.
Fibrosarkoma
Fibrosarkoma paling sering ditemukan diantara berbagai sarkoma jaringan lunak. Tapi
belakangan ini dengan perbaikan dan peningkatan teknik diagnosis, sebagian tumor yang
terbentuk dari serat kolagen yang di produksi sel spindel didiagnosis sebagai
histiotistoma fibrosa maligna, neurilemoma maligna, dll, sehingga proporsi fibrosarkoma
dalam sarkoma jaringan lunak menurun.
Patologi
Fibroadenoma adalah tumor ganas yang berasal dari sel fibroblas. Konsistensinya
lembut, permukaan irisann umumnya berwarna abu-abu putih atau warna daging ikan,
dapat terjadi nekrosis, hemoragi dan transformasi. Dapat timbul “kapsul semu”, namun
bila tumor tumbuh relatif besar, batasnya sering tidak jelas, bentuknya dapat tidak
beraturan berekspansi menonjol ke jaringan sekitarnya. Di bawah mikroskopik : struktur
jaringan sangat dismorfik, bukan hanya terdeapat sangat banyak gambaran mitosis, tapi
dapat timbul sel datia tumor berbentuk sangat aneh. Pola ekspansi utamanya adalah
pertumbuhan invasif lokal, dan bukan metastasis jauh, eksisi bedah sulit tuntas. Oleh
karena itu faktor utama itu, faktor utama pengancam pasien fibrosarkoma bukanlah
metastasis, melainkan rekurensi refrakter. Jika timbul diseminasi hematogen, terutama
metastasis ke paru. Pada sedikit kasus dapat juga timbul metastasis kelenjar limfe
regional.
Manifestasi klinik
Usia predileksi fibrosarkoma adalah 30-55 tahun, wanita agak lebih banyak dari pria,
dapat rimbul disetiap lokasi tubuh, namun paling sering timbul di ekstermitas. Gejala
utamanya berupa tumor, tidak nyeri. Perjalanan penyakit lambat, bervariasi dari beberapa
minggu hingga 20 tahun, bila menekan saraf dapat timbul nyeri. Permukaan tumor yang
berlingkup luas, bervolume besar dapat mengalami udem, venodilatasi, ulserasi dan
perdarahan.
Diagnosis
Gejala dan tanda fisik dapat menunjukkan kemungkinan fibrosarkoma, tapi diagnosis
pasti harus mengandalkan diagnosis patologi. Sebelum terapi dilakukan perhatikan
hubungan antara tumor dengan jaringan lapisan dalam, untuk menetapkan batas eksisi.
Bila perlu harus dikerjakan pemeriksaan khusus lain, misal angiografi, dll.
Pemeriksaan pencitraan
Pada fluoroskopi sinar X fibrosarkoma tampak sebagai massa bulat, densitasnya lebih
tinggi dari jaringan lunak sekitar, bila timbul destruksi tulang, retraksi periosteum,
penipisan korteks tulang dan morfologi irreguler, maka pertanda tumor sudah mengenai
tulang, CT, MRI, angiografi arteri pemasok tumor dan lainnya juga membantu dalam
memahami luas invasinya.
Pemeriksaan biopsi
Secara prinsip sebelum terapi setiap sarkoma jaringan lunak, harus terlebih dahulu
diperoleh diagnosis patologi, untuk memastikan jenis tumornya, sebagai dasar handal
untuk memilih metode terapi yang tepat. Harus dengan prosedur bertahap melakukan
pulsan pungsi-biopsi jarum-biopsi insisi-biopsi eksisi.
Diagnosis banding
Fibrosarkoma kadangkala mudah tertukar dengan neurofibroma dan tumor jinak lainnya,
tapi yang terkakhir umumnya memiliki riwayat penyakit lebih panjang, pertumbuhan
lambat, mobilitas tinggi, jarang adhesi dengan jaringan sekitarnya, dapat didiagnosis
jelas secara klinis.
Terapi
Dewasa ini, terapi operasi merupakan piliha pertama terhadap tumor tersebut. Begitu
terbukti dari biopsi, harus dieksisi in too berikut jaringan normal sekitar yang luas. Untuk
daerah kepala, leher, dan khusus lainnya, tidak mudah melakukan eksisi luas, maka
dilakukan eksisi luas terhadap tumor, secara agresif dikombinasi dengan radioterapi dan
kemoterapi. Pada lesi yang masif, atau karena keterbatasan anatomis yang tidak
dimungkinkan eksisi langsung maka dapat dipertimbangkan kemoterapi infus panas
intra-arteri, sampai tumor mengecil berulah dieksisi dan tambah radioterapi pasca
operasi.
Fibroma desmoplastika
Fibroma desmoplastik adalah tumor dengan progresivitas lambat dengan sel yang
berdiferensiasi baik yang memproduksi kolagen.
Tempat yang paling sering terkena adalah mandibula, femur dan pelvis Epidemiologi
dapat ditemukan baik pada wanita maupun pria.
Gejala klinis biasanya ditemukan sebagai efusi yang terletak dekat dengan sendi. Hanya
12% kasus yang disetai dengan fraktur.
Pemeriksaan radiologi menunjukkan osteolitik meluas , lesi sklerotik meduler dengan
batas tegas.biasanya ditemukan tumor berbentuk oval dalam metaphysis sejajar dengan
sumbupanjang tulang. Terdapat penipisan pada korteks, dan trabekula
memberikantampilan yang berlobul seperti ´sabun berbuih
Tumor saraf perifer jinak. Biasanya tumor ini berasal dari selubung saraf tepi.
Kelompok tumor ini antara lain adalah neurolemoma, neurofibroma soliter,
neurofibromatosis. Neurofibromatosis tipe I (von Recklinghausen disease) merupakan
kelainan genetic (autosomal dominan) dengan insidensi 1 dari 3000 kelahiran. Penyakit
mulai timbul pada tahun pertama berupa timbulnya bercak café’ au lait (coklat
kehitaman) sejalan dengan pertumbuhan, tumor akan tumbuh membesar dan dan menjadi
multiple.
Tumor Jaringan Lunak Ganas . Tumor jaringan lunak ganas terdiri dari tumor
adipose ganas, tumor fibroblastic ganas, tumor fibrohistiotik ganas, tumor otot rangka
ganas, tumor vascular ganas, dan tumor kondro-osseus ganas. Secara umum,
penatalaksanaan tumor jaringan lunak ganas sama dengan tumor tulang ganas.
Kemoterapi dan atau radioterapi adjuvant akan sangat membantu pembedahan dan
ditambah dengan upaya rekonstruksi akan meningkatkan harapan hidup penderita.
Diagnosis
Metode diagnosis yang paling umum selain pemeriksaan klinis adalah pemeriksaan
biopsi, bisa dapat dengan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) atau biopsi dari jaringan
tumor langsung berupa biopsi insisi yaitu biopsi dengan mengambil jaringan tumor
sebagian sebagai contoh bila ukuran tumornya besar. Bila ukuran tumor kecil, dapat
dilakukan biopsi dengan pengangkatan seluruh tumor. Jaringan hasil biopsi diperiksa
oleh ahli patologi anatomi dan dapat diketahui apakah tumor jaringan lunak itu jinak atau
ganas. Bila jinak maka cukup hanya benjolannya saja yang diangkat, tetapi bila ganas
setalah dilakukan pengangkatan benjolan dilanjutkan dengan penggunaan radioterapi dan
kemoterapi. Bila ganas, dapat juga dilihat dan ditentukan jenis subtipe histologis tumor
tersebut, yang sangat berguna untuk menentukan tindakan selanjutnya.
Pemeriksaan Penunjang
Foto Rontgen, biasanya tampak massa isodens, berlatar belakang bayangan otot.
Beberapa lesi menunjukkan gambaran yang spesifik seperti aebolit di dalam
hemangioma, massa kartilago pada osteokondromatosis synovial, kalsifikasi perifer
pada miositis osifikans. Foto rontgen juga bisa menunjukkan reaksi tulang akibat
invasi tumor jaringan lunak seperti destruksi, reaksi periosteal atau remodeling tulang.
USG, mempunyai dua peran yaitu dapat membedakan tumor kistik atau padat, dan
mengukur besarnya tumor. Pada sarcoma jaringan lunak akan didapatkan gambaran
massa hiperechoic, kecuali pada liposarkoma. USG Doppler berwarna sangat berguna
untuk melihat vaskularisasi massa jaringan lunak.
CT Scan, memiliki keunggulan dalam mendeteksi kalsifikasi dan osifikasi, melihat
metastasis di tempat lain (misalnya paru-paru), dan mengarahkan FNAB (biopsy
tertutup) tumor jaringan lunak.
MRI, merupakan modalitas diagnostic terbaik untuk mendeteksi, karakterisasi, dan
menentukan stadium tumor jaringan lunak, MRI mampu membedakan jaringan tumor
dengan otot di sekitarnya dan dapat menilai terkena tidaknya komponen neurovascular
yang penting dalam limb salvage surgery. MRI juga bisa digunakan untuk mengarah
biopsy, merencanakan teknik operasi, mengevaluasi respons kemoterapi, penentuan
ulang stadium, dan evaluasi jangka panjang terjadinya kekambuhan local.
Terapi
Secara umum, pengobatan untuk jaringan lunak tumor tergantung pada tahap dari
tumor. Tahap tumor yang didasarkan pada ukuran dan tingkatan dari tumor. Pengobatan
pilihan untuk jaringan lunak tumors termasuk operasi, terapi radiasi, dan kemoterapi.
1. Terapi Pembedahan (Surgical Therapy)
Bedah adalah yang paling umum untuk perawatan jaringan lunak tumor. Jika
memungkinkan, dokter akan menghapus kanker dan margin yang aman dari jaringan
sehat di sekitarnya. Penting untuk mendapatkan margin bebas tumor untuk
mengurangi kemungkinan kambuh lokal dan memberikan yang terbaik bagi
pembasmian dari tumor. Tergantung pada ukuran dan lokasi dari tumor, mungkin,
jarang sekali, diperlukan untuk menghapus semua atau bagian dari lengan atau kaki.
2. Terapi radiasi
Terapi radiasi dapat digunakan untuk operasi baik sebelum atau setelah shrink Tumor
operasi apapun untuk membunuh sel kanker yang mungkin tertinggal. Dalam
beberapa kasus, dapat digunakan untuk merawat tumor yang tidak dapat dilakukan
pembedahan. Dalam beberapa studi, terapi radiasi telah ditemukan untuk memperbaiki
tingkat lokal, tetapi belum ada yang berpengaruh pada keseluruhan hidup.
3. Kemoterapi
Kemoterapi dapat digunakan dengan terapi radiasi, baik sebelum atau sesudah operasi
untuk mencoba bersembunyi di setiap tumor atau membunuh sel kanker yang tersisa.
Penggunaan kemoterapi untuk mencegah penyebaran jaringan lunak tumors belum
membuktikan untuk lebih efektif. Jika kanker telah menyebar ke area lain dari tubuh,
kemoterapi dapat digunakan untuk Shrink Tumors dan mengurangi rasa sakit dan
menyebabkan kegelisahan mereka, tetapi tidak mungkin untuk membasmi penyakit.
BAB III
KESIMPULAN
Tumor merupakan sekelompok sel-sel abnormal yang terbentuk hasil
proses pembelahan sel yang berlebihan dan tak terkoordinasi. Tumor abdomen
merupakan sepertiga dari seluruh tumor ganas. Berbeda dengan jenis tumor
lainnya yang mudah diraba ketika mulai mendesak jaringan disekitarnya. "Itu
karena sifat rongga tumor abdomen yang longgar dan sangat fleksibel”.
Tumor abdomen merupakan suatu benjolan atau pembengkakan abnormal
dalam abdomen, yang meliputi organ-organ hepar, limpa, lambung dan usus
halus, kolon, ginjal, ureter, buli-buli, pancreas. Ada beberapa faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya tumor antara lain karsinogen, hormon, faktor gaya
hidup, parasit, genetik, infeksi, trauma, hipersensivitas terhadap obat.
Berbagai pemeriksaan penunjang perlu pula dilakukan untuk menegakkan
diagnosa. Seperti pemeriksaan darah tepi, laju endap darah. Selain itu, perlu juga
pemeriksaan foto polos abdomen, ultrasonografi dan atau CT-scan dilakukan
sesuai sarana dan prasarana.
Yang termasuk tumor abdomen antara lain, Tumor hepar, Tumor limpa /
lien, Tumor lambung / usus halus, Tumor colon, Tumor ginjal (hipernefroma),
Tumor pankreas. Pada anak-anak dapat terjadi Tumor wilms (ginjal).
DAFTAR PUSTAKA
1. Doherty GM. Small Intestines. In : Current Diagnosis & Treatment
Surgery 13th edition. 2010. US : McGraw-Hill Companies,p544-55.
2. Hunter JG. Neoplasms in Small Intestine. In : Schwart’s Principles of
Surgery 8th edition. 2007. US : McGraw-Hill Companies.
3. http://www.artikelkeperawatan.info/materi-kuliah-batu-empedu-171.html
4. Heuman DM. Abdominal Neoplasms. 2011. Diunduh dari :
http://emedicine.medscape. com/article/175667-overview.
5. Silbernagl S, Lang F. Intra Abdominal Masses. 2000. In : Color Atlas of
Pathophysiology. New York : Thieme,p:164-7.
6. Sjamsuhidayat R, de Jong W. Kelainan di Usus Halus. Dalam : Buku Ajar
Ilmu Bedah. Edisi 1. 1997. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 767-
73.
7. Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Gastrointestinal
Tumours. In : Sabiston Textbook of Surgery 17th edition. 2004.
Pennsylvania : Elsevier.
8. Klingensmith ME, Chen LE, Glasgow SC, Goers TA, Spencer J. Small
Intestine Surgery. In : Washington Manual of Surgery 5th edition. 2008.
Washington : Lippincott Williams & Wilkins.