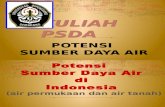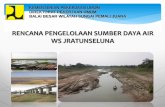psda
description
Transcript of psda

Bab I
Pendahuluan
Latar Belakang
Air merupakan sumber daya yang sampai saat ini belum dapat digantikan dalam
memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga keberadaan dan
kualitasnya haruslah di jadikan prioritas utama dalam pelestarian fungsinya dalam
memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran
penting bagi berbagai sektor kehidupan. Air merupakan sumber daya yang bersifat multi
sektoral. Semakin maju tingkat penghidupan masyarakat dan semakin canggih teknologi
yang digunakan, serta semakin banyak bermunculan industry yang membutuhkan air,
sedangkan jumlah air semakin lama relative berkurang.
Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara
berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air
yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Gejala degradasi fungsi
lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau
yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk dan lainnya.
Pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan adalah tujuan penting yang tengah
diterapkan pada tingkat nasional dan internasional untuk mencoba menangani masalah
kekurangan air, ketidakadilan dalam pembagian air, pencemaran air, dan banyak masalah
terkait sumberdaya air lainnya.
1

Bab II
Pengelolaan Sumber Daya Air secara Umum
A. Definisi Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air rusak.
Pengertian lain Pengelolaan sumberdaya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara
struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan
buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.
(Kodoatie Robert J dkk, 2002).
Pengelolaan di sini memiliki arti seluas-luasnya. Hal ini menekankan bahwa kita
tidak boleh hanya memusatkan pada pengembangan sumberdaya air namun kita juga
harus mengelola pengembangan sumberdaya air yang dapat memastikan kegunaan
jangka panjang yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. (Biltonen, 2002)
B. Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air
Alokasi air.
Mengalokasikan air bagi pengguna air dan kegunaan air dalam skala besar,
memelihara tingkat minimal untuk penggunaan secara sosial dan lingkungan
sekaligus memelihara kesetaraan dan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat.
Pengendalian pencemaran.
Menangani pencemaran dengan menggunakan sistem prinsip pencemar-bayar dan
insentif yang sesuai untuk mengurangi masalah pencemaran paling penting dan
meminimalisir dampak lingkungan dan sosial.
Pemantauan sumberdaya air, penggunaan air dan pencemaran.
Menerapkan sistem pengawasan yang efektif yang menyediakan informasi
pengelolaan yang penting dan mengidentifikasi dan merespon atas pelanggaran
terhadap hukum, peraturan dan izin.
Pengelolaan informasi.
2

Menyediakan data penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang jelas
dan transparan demi pembangunan dan pengelolaan berkelanjutan atas sumberdaya
air.
Pengelolaan ekonomi dan keuangan.
Menerapkan instrumen ekonomi dan keuangan demi investasi, pemulihan dana dan
perubahan perilaku untuk mendukung kesetaraan akses dan manfaat berkelanjutan
bagi masyarakat dari penggunaan air.
C. Permasalahan yang timbul dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin menghadapi berbagai
permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan
pertumbuhan social-ekonomi. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan
eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya
dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan
pasokan air.
Permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri
atas 3 aspek yaitu :
Too much atau terlalu banyak air (banjir)
Too little atau terlalu sedikit (Kekurangan air), dan
Too Dirty atau terlalu kotor (Pencemaran air).
Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan social-ekonomi
mengakibatkan kebutuhan air meningkat.
Degradasi Sumber Daya Air
Penggunaan air yang berlebihan dan kurang efisien.
Penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk
pemukiman dan industry.
Pencemaran air permukaan dan air tanah.
Erosi tanah sebagai akibat penggundulan hutan.
Secara umum masalah pengelolaan sumberdaya air dapat dilihat dari kelemahan
mempertahankan sasaran manfaat pengelolaan sumberdaya air dalam hal pengendalian
banjir dan penyediaan air baku bagi kegiatan domestik, municipal, dan industri.
3

D. Upaya-upaya dalam Penanganan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air
Untuk mengatasi bahaya banjir dan kerugian yang diakibatkan bahwasannya dapat
dilakukan upaya structural meliputi normalisasi sungai, pembuatan tanggul, sudetan,
waduk pengendali banjir, daerah retensi banjir dan perbaikan lahan , sedangkan upaya
non structural adalah zonasi banjir, pengaturan pada daratan banjir, peramalan banjir
dan peringatan dini, dan pemasangan peil banjir.
Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengelolaan
sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya pemukiman padat di
sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena
banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai sehingga mengakibatkan
berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat curah
hujan yang tinggi di daerah hulu.
Pada sisi lain penyediaan air baku yang dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga,
perkotaan dan industri sering mendapatkan gangguan secara kuantitas – dalam arti
terjadinya penurunan debit air baku akibat terjadinya pembukaan lahan-lahan baru bagi
pemukiman baru di daerah hulu yang berakibat pada pengurangan luas catchment area
sebagai sumber penyedia air baku. Disamping itu, secara kualitas penyediaan air baku
sering tidak memenuhi standar karena adanya pencemaran air sungai oleh limbah rumah
tangga, perkotaan, dan industri.
E. Bentuk – Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Pencemaran
Pengelolaan sumberdaya air memerlukan dua unsur yang saling terkait, yaitu
pemeliharaan dan pengembangan kuantitas air yang mencukupi dengan kualitas yang
memadai berkualitas. Karena itu, pengelolaan sumberdaya air tidak dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa memerhatikan kualitas air. Hal ini dapat
dilaksanakan dengan mengelola di titik sumber pencemaran dan di bukan titik
pencemaran.
Perlindungan Air Tanah
Kerangka pengendalian pencemaran air tanah membutuhkan tindakan-tindakan
seperti:
4

o Mengidentifikasikan ancaman terhadap air tanah dari titik sumbernya atau dari
sumber sebarannya, dan dengan berdasarkan bahan pencemar baik yang dapat
terurai maupun yang tidak dapat terurai dalam wilayah sungai;
o Mengelompokkan air tanah berdasarkan kerentanannya dan mendefinisikan zona
perlindungan sumber air tanah; dan
o Membuat kebijakan dan strategi pengendalian kegiatan pencemaran untuk
mengurangi atau menghapus risiko pencemaran.
Cara Untuk Melakukan Penghematan Air Tanah
Penghematan penggunaan air tanah merupakan bagian dari upaya konservasi
air tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan
fungsi air tanah.
Penghematan penggunaan air tanah dilakukan agar air tanah tersedia secara
terus menerus dan berkesinambungan/berkelanjutan (Peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 58 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah)
Penghematan penggunaan air tanah dilakukan dengan cara :
1. Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien;
Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien dilakukan dengan cara :
Menggunakan air tanah sesuai kebutuhan;
Pemakaian air tanah untuk keperluan irigasi diupayakan secara optimal sesuai
waktu dan jenis tanaman;
Membuat bak penampungan air tanah sebelum didistribusikan;
Memanfaatkan air tanah dengan gaya gravitasi;
Menghindari pemborosan penggunaan air tanah;
Mengurangi penggunaan air tanah dengan sistem tekanan;
Menggunakan meter air untuk memantau pengambilan air tanah;
Melakukan perawatan instalasi air tanah secara berkala serta mengganti
peralatan yang tidak bekerja dengan baik.
2. Mengurangi penggunaan air tanah;
5

Mengurangi penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan
cara:
Air tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
Menutup kran dengan segera setelah air tidak digunakan;
Membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai
kebutuhan;
Menggunakan kembali air tanah;
3 . Menggunakan kembali air tanah
Menggunakan kembali air tanah dapat dilakukan dengan cara:
Menggunakan air tanah yang telah dipakai dan masih layak untuk menyiram
tanaman, dan mencuci awal barang-barang tertentu, dan dilakukan pembilasan;
Menggunakan air tanah yang telah dipakai untuk penggelontoran (flushing).
4. Mendaur ulang air tanah;
Mendaur ulang air tanah sebagaimana dapat dilakukan dengan cara:
Membangun instalasi pengolah air yang telah dipakai hingga mencapai
kualitas aman untuk kemudian air dapat diresapkan kembali ke dalam tanah atau
air tanah digunakan kembali sesuai tingkat untuk kebutuhan lainnya;
Membuat bak penampungan air yang telah dipakai dan masih mempunyai
kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali ;
Membuat sumur resapan air hujan ke dalam tanah.
5. Mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
Mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara:
Menggunakan sistem penampungan air;
Menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan air tanah berdasarkan
kapasitas penampungan air;
Membuat bangunan untuk mencegah meluapnya air artesis ke saluran umum.
6. Menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
6

Menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir sebagaimana dimaksud
dapat dilakukan dengan cara:
Mengutamakan penggunaan air permukaan;
Memanfaatkan air hujan;
Menggunakan air dari perusahaan daerah air minum bagi daerah yang
terjangkau layanan;
Memperketat pemberian izin penggalian atau pengeboran guna mendapatkan
air tanah;
Meningkatkan kesadaran para pemegang izin untuk memasang meter air.
7. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air tanah.
Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air tanah dapat
dilakukan dengan cara:
Menggunakan shower untuk mandi;
Menggunakan penggelontor otomatis;
Menggunakan keran hemat air;
Menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.
F. Pemanfaatan Sumber Daya Air
1. Irigasi
Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian.
Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan
manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat
dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air
tersebut ke lahan pertanian.
7

2. Air Baku
Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah
air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air
hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
3. PLTA
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan
energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik
yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Bentuk utama dari
pembangkit listrik jenis ini adalah Generator yang dihubungkan ke turbin yang
digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik
tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan
juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain
seperti tenaga ombak.
8

4. Rekreasi
Air dapat merupakan sarana rekreasi, misalnya : sungai, danau, laut, pantai, dan
lain-lain. Salah satu tindakan pemanfaatan sungai yang dianggap dapat menambah
pemasukan negara adalah menjadikannya sebagai objek wisata.
9

Bab II
Daerah Aliran Sungai
A. Definisi Daerah Aliran Sungai
River Basin atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Daerah Aliran Sungai
( DAS) adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas topografi secara
alami sedemikian rupa sehingga setiap air hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan
mengalir melalui titik tertentu (titik pengukuran di sungai) dalam DAS tersebut.
Daerah aliran sungai (DAS) juga bisa diartikan sebagai daerah yang dibatasi
punggung-punggung (igir-igir) gunung, air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan
ditampung oleh punggung gunung tersebut dan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke
sungai utama (Asdak, 1995: 4).
Pengertian DAS tersebut menggambarkan bahwa DAS adalah suatu wilayah yang
mengalirkan air yang jatuh di atasnya beserta sedimen dan bahan terlarut melalui titik
yang sama sepanjang suatu aliran atau sungai. Dengan demikian DAS atau watershed
dapat terbagi menjadi beberapa sub DAS dan sub-sub DAS, sehingga luas DAS pun
akan bervariasi dari beberapa puluh meter persegi sampai ratusan ribu hektar tergantung
titik pengukuran ditempatkan.
10
Ilustrasi Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai terbagi menjadi tiga daerah yaitu bagian hulu, bagian tengah,
dan bagian hilir.
1. DAS Bagian Hulu (Upperland), daerah ini memiliki ciri ciri :
Merupakan daerah konservasi.
Mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi.
Merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (> 15%).
Bukan merupakan daerah banjir.
Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase.
Jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan.
Laju erosi lebih cepat daripada pengendapan.
Pola penggerusan tubuh sungai berbentuk huruf “V”.
2. DAS Bagian Tengah (Middle Land)
DAS bagian tengah merupakan daerah peralihan antara bagian hulu dengan
bagian hilir dan mulai terjadi pengendapan. Ekosistem tengah sebagai daerah
distributor dan pengatur air, dicirikan dengan daerah yang relatif datar. Daerah
aliran sungai bagian tengah menjadi daerah transisi dari kedua karakteristik
biogeofisik DAS yang berbeda antara hulu dengan hilir.
3. DAS Bagian Hilir (Lowerland), dicirikan dengan:
Merupakan daerah pemanfaatan atau pemakai air.
Merupakan zone sedimentasi
Kerapatan drainase kecil.
Merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat
kecil (kurang dari 8%).
Pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan).
Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi.
Jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang
didominasi hutan bakau/gambut.
11

Pola penggerusan tubuh sungai berbentuk huruf “U”
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu akan berpengaruh sampai pada hilir.
Oleh karenanya DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi
perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, jadi apabila terjadi pengelolan yang tidak benar
terhadap bagian hulu maka dampak yang ditimbulkan akan dirasakan juga pada bagian hilir.
Misalnya, erosi yang terjadi tidak hanya berdampak bagi daerah dimana erosi tersebut
berlangsung yang berupa terjadinya penurunan kualitas lahan, tetapi dampak erosi juga akan
dirasakan dibagian hilir, dampak yang dapat dirasakan oleh bagian hilir adalah dalam bentuk
penurunan kapasitas tampung waduk ataupun sungai yang dapat menimbulkan resiko banjir
sehingga akan menurunkan luas lahan irigasi (Asdak, 1995:12).
Jika digambarkan maka, Daerah Aliran Sungai memiliki komponen komponen yang khas
sebagai berikut :
Anak sungai (Tributaries) merupakan sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih
besar.
Sebuah DAS ( Watershed) adalah daerah dataran tinggi di sekitar aliran sungai.
Tempat pertemuan ( Confluence) yaitu tempat di mana sungai bergabung sungai lain.
Sumber ( source ) adalah awal sungai.
Mulut (mouth ) yaitu Dimana sungai bertemu dengan danau, laut atau samudra.
B. Fungsi Daerah Aliran Sungai
12

Beberapa proses alami dalam DAS dapat memberikan dampak menguntungkan
kepada sebagian kawasan DAS, tetapi pada saat yang sama dapat merugikan bagian
yang lain. Bencana alam banjir dan kekeringan silih berganti yang terjadi di suatu
wilayah atau daerah merupakan dampak negatif kegiatan manusia pada suatu DAS,
dapat dikatakan bahwa kegiatan manusia telah menyebarkan DAS gagal dalam
menjalankan fungsinya sebagai penampung air hujan, penyimpan, dan pendistribusian
air ke saluran-saluran atau sungai. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang
tergenang (danau, waduk, rawa) dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan
mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu
terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah
aliran sungai (DAS). Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah
adalah wujud dan tempatnya.
Fungsi suatu DAS merupakan fungsi gabungan yang dilakukan oleh seluruh faktor
yang ada pada DAS tersebut, yaitu vegetasi, bentuk wilayah (topografi), tanah, dan
manusia. Apabila salah satu faktor tersebut mengalami perubahan, maka hal tersebut
akan mempengaruhi juga ekosistem DAS tersebut dan akan menyebabkan gangguan
terhadap bekerjanya fungsi DAS. Apabila fungsi suatu DAS telah terganggu, maka
sistem hidrologisnya akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan
penyimpanan airnya menjadi sangat berkurang atau sistem penyalurannya menjadi
sangat boros. Kejadian itu akan menyebabkan melimpahnya air pada musim penghujan
dan sangat minimum pada musim pada musim kemarau, sehingga fluktuasi debit sungai
antara musim hujan dan musim kemarau berbeda tajam.
C. Dampak Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Sumberdaya alam utama yang terdapat dalam suatu DAS yang harus diperhatikan
dalam pengelolaan DAS adalah sumberdaya hayati, tanah dan air. Sumberdaya tersebut
peka terhadap berbagai macam kerusakan (degradasi) seperti kehilangan
keanekaragaman hayati (biodiversity), kehilangan tanah (erosi), kehilangan unsur hara
dari daerah perakaran (kemerosotan kesuburan tanah atau pemiskinan tanah), akumulasi
13

garam (salinisasi), penggenangan (water logging), dan akumulasi limbah industri atau
limbah kota (pencemaran) (Rauschkolb, 1971; ElSwaify, et. al. 1993).
Apabila ada kegiatan di suatu DAS maka kegiatan tersebut dapat mempengaruhi
aliran air di bagian hilir baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penebangan hutan
secara sembarangan di bagian hulu suatu DAS dapat mengganggu distribusi aliran
sungai di bagian hilir. Pada musim hujan air sungai akan terlalu banyak bahkan sering
menimbulkan banjir tetapi pada musim kemarau jumlah air sungai akan sangat sedikit
atau bahkan kering. Disamping itu kualitas air sungai pun menurun, karena sedimen
yang terangkut akibat meningkatnya erosi cukup banyak. Perubahan penggunaan lahan
atau penerapan agroteknologi yang tidak cocok pun dapat mempengaruhi kualitas dan
kuantitas air yang mengalir ke bagian hilir.
Salah satu jenis kerusakan DAS yang memerlukan penanganan khusus adalah
erosi. Dampak negatif erosi terjadi pada dua tempat yaitu pada tanah tempat erosi
terjadi, dan pada tempat sedimen diendapkan. Kerusakan utama yang dialami pada
tanah tempat erosi terjadi adalah kemunduran kualitas sifat-sifat biologi, kimia, dan
fisik tanah yang berupa :
kehilangan keanekaragaman hayati, unsur hara dan bahan organik yang terbawa
oleh erosi
tersingkapnya lapisan tanah yang miskin hara dan sifat-sifat fisik yang
menghambat pertumbuhan tanaman
menurunnya kapasitas infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air
meningkatnya kepadatan tanah dan ketahanan penetrasi serta berkurangnya
kemantapan struktur tanah.
Penurunan infiltrasi akibat kerusakan DAS mengakibatkan meningkatnya aliran
permukaan (run off) dan menurunnya pengisian air bawah tanah (groundwateri)
mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai pada musim hujan secara drastis dan
menurunnya debit aliran pada musim kemarau. Pada keadaan kerusakan yang ekstrim
akan terjadi banjir besar di musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini
14

mengindikasikan bahwa terjadi kehilanghan air dalam jumlah besar di musim hujan
yaitu mengalirnya air ke laut dan hilangnya mata air di kaki bukit akibat menurunnya
permukaan air bawah tanah. Dengan perkataan lain, pengelolaan DAS yang tidak
memadai akan mengakibatkan rusaknya sumberdaya air.
D. Cara cara pengelolaan DAS
Untuk menjaga produktivitas lahan, maka penggunaan lahan harus sesuai dengan
kemampuan lahan serta penggunaan agroteknologi harus disertai dengan penerapan
teknik konservasi tanah dan air yang memadai. Tipe teknik konservasi tanah dan air
yang banyak diterapkan di seluruh dunia termasuk dalam pengelolaan DAS di Indonesia
dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok utama yaitu agronomi, vegetatif,
struktur, dan manajemen (WASWC, 1998).
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok agronomi
antara lain penanaman tanaman campuran (tumpang sari), penananam berurutan
(rotasi),
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok vegetatif
antara lain penanaman tanaman pohon atau tanaman tahunan (seperti kopi, teh, tebu,
pisang), penanaman tanaman tahunan di batas lahan (tanaman pagar),
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok struktur
antara lain saluran penangkap aliran permukaan, saluran pembuangan air, saluran teras,
parit penahan air (rorak), sengkedan, guludan, teras guludan, teras bangku, dam penahan
air.
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok
manajemen antara lain perubahan pengunaan lahan menjadi lebih sesuai, pemilihan
usaha pertanian yang lebih cocok, pemilihan peralatan dan masukan komersial yang
lebih tepat, penataan pertanian.
15

Bab III
Kesimpulan
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber
daya air, dan pengendalian daya air rusak.
Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air
Alokasi air.
Pengendalian pencemaran.
Pemantauan sumberdaya air, penggunaan air dan pencemaran.
Pengelolaan informasi.
Pengelolaan ekonomi dan keuangan.
Permasalahan yang timbul dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air yaitu :
Too much atau terlalu banyak air (banjir)
Too little atau terlalu sedikit (Kekurangan air), dan
Too Dirty atau terlalu kotor (Pencemaran air).
Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan social-ekonomi
mengakibatkan kebutuhan air meningkat.
Degradasi Sumber Daya Air
Penggunaan air yang berlebihan dan kurang efisien.
Penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk
pemukiman dan industry.
Pencemaran air permukaan dan air tanah.
Erosi tanah sebagai akibat penggundulan hutan.
Upaya-upaya dalam Penanganan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air
Upaya structural meliputi normalisasi sungai, pembuatan tanggul, sudetan, waduk
pengendali banjir, daerah retensi banjir dan perbaikan lahan , sedangkan upaya non
structural adalah zonasi banjir, pengaturan pada daratan banjir, peramalan banjir dan
peringatan dini, dan pemasangan peil banjir.
16

Bentuk – Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Pencemaran
Perlindungan Air Tanah
Pemanfaatan Sumber Daya Air
Irigasi
Air Baku
PLTA
Rekreasi
Dll
Daerah Aliran Sungai ( DAS) adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas
topografi secara alami sedemikian rupa sehingga setiap air hujan yang jatuh dalam DAS
tersebut akan mengalir melalui titik tertentu (titik pengukuran di sungai) dalam DAS
tersebut.
Daerah aliran sungai terbagi menjadi tiga daerah yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan
bagian hilir.
Fungsi suatu DAS merupakan fungsi gabungan yang dilakukan oleh seluruh faktor yang ada
pada DAS tersebut, yaitu vegetasi, bentuk wilayah (topografi), tanah, dan manusia.
Dampak Kerusakan Daerah Aliran Sungai yakni kerusakan (degradasi) seperti kehilangan
keanekaragaman hayati (biodiversity), kehilangan tanah (erosi), kehilangan unsur hara dari
daerah perakaran (kemerosotan kesuburan tanah atau pemiskinan tanah), akumulasi garam
(salinisasi), penggenangan (water logging), dan akumulasi limbah industri atau limbah kota
(pencemaran) (Rauschkolb, 1971; ElSwaify, et. al. 1993).
Cara cara pengelolaan DAS
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok agronomi
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok vegetative
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok struktur
Teknik konservasi tanah dan air yang dikelompokkan ke dalam kelompok manajemen
Daftar Pustaka
17

Alaerts, G. dan Santika, S.S. 1987. Metode Penelitian Air, Usaha Nasional,
Surabaya
Asdak, C., 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. UGM–
Press,Yogyakarta
Minullah, E. 2003. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Kodoatie, J.R. dan Sugiyanto, 2002. Banjir, Beberpa Masalah dan Metode
Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rauschkolb, R.S. 1971. Land Degradation. FAO Soil Bull, No. 13
Sihite, J. and Sinukaban. 2004. Economic Valuation of Land Use Cange in Besai Sub
Watershed Tulang Bawang Lampung. Proceed of International Seminar on “Toward
Harmonization between Development and Environmental Conservation in Biological
Production” 3 – 5 Dec 2004. Cilegon, Indonesia.
WASWC (World Association of soil dan eater Conservation). 1998. Wocat (World
Overview of Conervation Approachs and Technologies). A Frame Work for the
Evaluation of Soil and water Conservation. Lang Druck AG, Bern Switzerland.
http://dony.blog.uns.ac.id/2010/06/02/daerah-aliran-sungai-das/
http://www.docstoc.com/docs/39974016/PENGELOLAAN-SUMBER-DAYA-AIR /
18